Sampai di mana ya, tadi khayalan Alen tentang sapu terbang di balik jendela mobil? Alen benar-benar lupa alur cerita si sapu sesaat setelah suara Alice menginterupsi. Sekarang Alice sudah meninggalkan mobil. Tampak menawan ketika berjalan menghampiri kru majalah yang tengah membereskan properti.
Tanpa sadar Alen menempelkan tangannya di kaca mobil, membayangkam dirinya menjadi Alice yang cakap dalam segala hal. Cantik, pintar matematika, menguasai beberapa bahasa asing, dan tentunya sudah bisa menghasilkan uang.
Bayangan Alen tak berlangsung lama. Gadis itu menjauh dari kaca mobil seraya mengerjap. Seorang pemuda berasal dari kerumunan kru fotografi tiba-tiba menghampirinya. Wajahnya putih pucat seperti tanpa darah. Untungnya pemuda itu memiliki dua bola mata cokelat bening yang membuat Alen yakin kalau pemuda itu bukanlah mayat hidup apalagi hantu.
Pemuda itu berhenti tepat di hadapan Alen. Ia mengetuk kaca mobil. Alen menurunkan kaca, sedikit mundur dari tempatnya duduk.
"Ya?" Ujar Alen setelah kaca mobil ia turunkan setengah.
"Ya?" Pemuda itu mengulang ucapan Alen dengan wajah tak percaya. Detik berikutnya ia mengangkat ponselnya, menunjukkan sebuah chat room pada Alen. "Kenapa tidak membalas pesan saya?"
Mata Alen menyipit memperhatikan chat room di ponsel pemuda di depannya. Chat room itu berisi pesan singkat yang beberapa jam lalu Alen terima di kamar.
"Itu..."
"Apa?" Pemuda itu memotong dengan galak. "Sepertinya masalah mengkhayalmu semakin parah."
"Dari mana kamu tahu—"
"Saya tahu segala hal tentang kamu." Pemuda itu lagi-lagi memotong.
"Keluarlah sebentar." Ucapnya setelah jeda beberapa detik. "Saya akan jelaskan."
Alen mengerutkan alis. "Menjelaskan apa?"
"Hal-hal yang tidak kamu mengerti."
"Misalnya?"
"Misalnya siapa saya."
Kalau mengikuti kewarasannya Alen rasa ia harus tetap tinggal di mobil. Tapi dibanding kewarasan, Alen lebih suka menuntaskan penasaran. Gadis itu membuka pintu mobil. Ia berpesan pada supir agar menunggu sampai ia kembali.
"Kamu tidak akan macam-macam, kan?" Alen menyeletuk sambil turun dari mobil. Tiba-tiba ia merasa konyol.
Kalaupun laki-laki itu ada niat mencelakai Alen, ia pasti tidak akan mengaku, kan?
"Memangnya saya terlihat seperti kriminal?"
#
"Galen?" Dengan kening berkerut Alen mengulang apa yang baru saja diucapkan pemuda di depannya. Pemuda itu mengangguk.
Sekuat tenaga Alen berusaha mengingat-ingat sesuatu tentang Galen, barangkali ada secuil informasi yang terselip di otaknya tentang pemuda berkulit pucat ini. Tapi semakin Alen berusaha, semakin ia merasa prefontalnya kehilangan detil-detil informasi.
"Kita bertemu di depan sekolah." Galen memberi petunjuk yang tak cukup.
"Sepertinya kamu salah memberi buku. Saya minta buku catatan, tapi yang kamu pinjamkan malah sketsa." Sambung Galen santai.
"Saya mencari waktu agar bisa mengembalikan sketsamu. Baru bisa sekarang."
Bertemu di depan sekolah? Tapi kapan? Catatan? Sketsa? Pulpen? Yang mana? Kapan Alen pernah meminjamkan barang-barangnya pada orang asing? Alen mengerjap-ngerjapkan mata.
"Terima kasih sudah meminjamkannya untuk saya."Galen merogoh tas yang tersampir di bahunya, lalu menyodorkan buku sketsa dan sebuah pulpen.
Alen tidak langsung menerima buku dan pulpen itu. Lama ia menatap lekat benda-benda di tangan Galen. Matanya membulat sewaktu ingatan abu muncul di benaknya. Ketika Alen mengambil alih buku dan pulpen dari tangan Galen, otaknya bekerja secara ajaib. Gadis itu sekoyong-koyong ingat dengan jelas pertemuannya dengan Galen di depan sekolah.
#
Bus yang Alen tumpangi melaju dengan lambat. Gadis itu menembuskan pandangan ke luar jendela, memperhatikan deretan gedung di luar sana. Suana hati Alen seperti hari-hari sebelumnya. Kacau. Terbersit di otak Alen untuk membolos saja hari ini. Siapa tahu gurunya akan menelpon Renata dan mengabari kalau untuk kali pertama Alen absen dari sekolah. Tapi mengingat eksistensi Alen di sekolah, gadis itu ragu gurunya akan merasa kehilangan. Bolos sekali tidak akan membuat guru-guru di sekolah bertanya kemana Alen, apalagi sampai menghubungi Renata.
Padahal, Alen ingin tahu kalau salah satu gurunya menghubungi Renata, respon seperti apa yang akan Renata berikan. Apa ibunya itu akan marah atau khawatir? Alen menebak-nebak sendiri. Kalau Alen seperti Alice yang mewakili sekolah di olimpiade matematika nasional, baru gurunya akan merasa kehilangan. Renata juga akan marah sekaligus khawatir.
Nah. Mulai lagi. Alen harus berhenti membanding-banding dirinya dengan Alice. Alen bisa kehilangan kepercayaan dirinya lebih dari yang ia rasakan saat ini kalau terus menerus berpikir Alice jauh lebih baik darinya. Bagaimana pun, ia dan Alice mewarisi darah yang sama dari ibu dan ayahnya. Setidaknya, Alen punya satu atau dua bakat yang membuatnya satu standar dengan Alice, kan?
Alen memandang cross bag di pangkuannya, sedetik kemudian tersenyum. Hampir saja Alen lupa kalau ia juga punya kelebihan yang tidak dimiliki Alice. Dikeluarkannya buku sketsa dari cross bag yang sejak tadi ia peluk, lalu ia buka satu per satu halaman yang mulai penuh dengan karya tangannya. Kebanyakan adalah gambar pemandangan halaman sekolah, ruang kelas, dan laboraturium sekolah.
Bus berhenti ketika Alen selesai membuka-buka sketsanya sampai halaman terakhir. Gerbang sekolahnya tampak riuh dengan siswa yang lalu lalang. Alen menjejalkan sketsannya, lalu turun dari bus. Belum sampai lima langkah sejak turun, tiba-tiba seseorang meraih tangannya, menghentikan langkahnya.
“Pinjam pulpen.”
Alen mematung sejenak. Ia memperhatikan pemuda yang menadahkan tangan padanya. Mata Alen bergerak cepat mebidik emblem nama di dada kiri pemuda itu. Galen.
“Saya Galen. Hari ini ada ulangan bahasa Indonesia. Saya lupa bawa pulpen. Saya juga nggak bawa uang buat beli pulpen.” Galen menyerocos ringan.
Alen nyaris tak menangkap apa yang dikatakan pemuda di depannya. Ia masih mematung, merasa aneh, tiba-tiba ditodong pemuda asing di depan sekolah.
“Saya dari SMA sebrang. Kita bertetangga. Kalau sudah jam pulang, kamu tunggu di sini. Nanti saya kembalikan.” Galen mendesak.
Dengan desakan yang seperti mantra hipnotis itu, secara tak sadar, Alen merogoh tasnya, mengeluarkan kotak pensil dan memberikan pulpen pada pemuda bernama Galen.
“Boleh pinjam buku catatan juga?”
“Untuk apa?”
“Pinjam saja.”
Alen tak habis pikir ia menurut dan mengeluarkan buku-buku dari tasnya. Alen memilah mana yang sebaiknya ia pinjamkan. Semua bukunya dipakai hari ini.
“Yang ini saja.” Galen menyambar salah satu buku yang sedang Alen pegang. Gadis itu memekik. Buku sketsanya dirampas dengan cepat.
“Jangan yang itu!”
Tapi sepertinya Galen tak mendengarkan. Pemuda itu berbalik dengan cepat, menyebrang jalan seperti kilat. Ia berlari ke SMA di sebrang, kemudian menghilang di tengah kerumunan siswa yang bergerombol masuk.
Alen memandangi sosok asing Galen yang berbaur dengan siswa lain. Gadis itu berdiri kikuk seperti baru saja kecurian di depan banyak orang. Kenapa siswa sekolah lain harus meminjam pulpennya? Alen benar-benar tak habis pikir. Kalau saat itu bel sekolah tidak berbunyi, Alen pasti sudah berlari menyusul pemuda aneh bernama Galen itu, lalu mengambil lagi pulpen serta buku sketsanya.
Mengingat kejadian itu secara runut membuat Alen meringis. Seperti baru saja pulih dari hilang ingatan, benar-benar aneh rasanya.
“Bukan saya yang salah. Kamu yang seenaknya meyambar buku sketsa saya.” Alen menukas sembari membolak-balik buku sketsa di tangannya. Kenapa Alen bisa lupa soal pulpen dan sketsanya? Biasanya saat barang-barangnya dipinjam, Alen selalu ingat dan cenderung ingin barang-barang itu kembali padanya secepat mungkin.
Mungkin karena akhir-akhir ini Alen banyak pikiran.
“Waktu itu saya buru-buru.” Galen memasang wajah menyesal. “Untung saya menemukan kamu. Kalau tidak, sepertinya saya akan merasa saya sudah mencuri barang anak gadis.” Senyuman merekah di wajah Galen. Pemuda itu menggeleng-geleng tak jelas.
“Omong-omong gambarmu bagus. Kamu ikut kelas seni?” Tangan Galen menggapai cangkir kopi di meja, menyeruput isinya sambil terus memandang Alen.
Alen menggeleng. Gadis itu dengan mantap membidik Galen. Ada yang aneh dengan pemuda itu. Caranya bicara seolah-olah ia sudah mengenal Alen sangat lama. Ia mengajak Alen mengobrol di kafetaria dekat lokasi pemotretan dan mentraktir Alen secangkir capucino. Oh, oh! Bahkan sewaktu di depan mobil tadi, Galen mengatakan ia tahu segala hal tentang Alen, ia juga mengungkit soal mengkhayal.
“Kenapa waktu itu kamu pinjam pulpen saya?”
Alen tak bisa tidak menghiraukan kejanggalan yang mengusik otaknya. Ia perlu tahu siapa Galen yang sebenarnya, bukan cuma ingat bahwa Galen adalah siswa SMA tetangga yang meminjam pulpen serta buku sketsanya kapan hari. Alen juga merasa perlu menanyakan hal-hal penting seperti bagaimana Galen bisa mengatakan ia tahu segala hal tentang Alen dengan yakin.
“Ingin saja.”
Jawaban itu jauh dari kata memuaskan. Kalau sesuatu terasa tidak masuk akal baginya, Alen akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ia jawab sendiri untuk membuat hal itu masuk akal. Kali ini Alen tak perlu menjawabnya seorang diri. Ia punya objek membingungkan yang memiliki kemampuan berbahasa verbal untuk menjawab.
Alen memutar otak, mencari pertanyaan lain untuk ia ajukan. Jujur saja, Alen perlu waktu lama untuk memilah hamburan-hamburan pertanyaan di otaknya. Alen tidak boleh bertanya secara serampangan. Ia harus bertanya secara bertahap dimulai dari pertanyaan sederhana. Sambil memikirkan urutan pertanyaan yang harus ia tanyakan pada Galen, Alen menyesap capucino pesanannya. Baru setelah merasa mantap, Alen bertanya.
“Kalau nomor saya? Kamu tahu dari mana?”
Ini pertanyaan dengan level kepentingan medium. Kalau Galen mengatakan sesuatu yang tak memuaskan apalagi sesuatu yang tak masuk akal seperti ‘Ada deh’ Alen akan berhenti bertanya. Ia tidak perlu berurusan dengan pemuda yang tidak jelas apa maunya.
“Dari instagram.”
Jawaban Galen di luar dugaan.
Perlahan-laan kejanggalan yang mengganggu Alen memudar. Alen memang membuat akun instagramnya menjadi akun bisnis untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada perusahaan yang tertarik dengan gambar yang ia unggah di instagram, lalu mengajak Alen berkolaborasi membuat desain untuk sampul buku, atau apalah yang berhubungan dengan gambar—walaupun hampir tak mungkin— jadi Alen menyematkan nomor ponselnya di akun itu. Masuk akal Galen mendapatkan nomornya dari instagram.
Sekarang pertanyaannya, dari mana Galen tahu instagram Alen. Ia yakin tidak sempat menyebutkan namanya sewaktu bertemu Galen di depan sekolah. Lagi pula nama akun instagramnya menggunakan nama lain yang jauh dari nama Alena Marissa.
“Sekarang ingin tanya apalagi? Bagaimana saya tahu akun instagrammu”
Alen mengangkat kedua Alisnya. Apa mungkin kepalanya transparan?
“Saya melihat-lihat isi sketsa kamu dan menemukan gambar yang sama di instargram. Waktu saya lihat, saya yakin akun instagram itu milikmu. Ada nomor ponselnya pula.” Galen menyerocos lagi.
Penjelasan Galen membuat Alen mengangguk-angguk paham. Masih ada satu pertanyaan lagi.
“Lalu bagaimana kamu tahu…” Alen menjilat bibirnya yang mendadak terasa kering. Sebelum ini, Alen tak pernah membicarakan soal kebiasaannya berkhayal pada orang lain. Bahkan pada keluarganya, Alen enggan bercerita.
Alasannya sederhana. Alen tidak mau dianggap gila meski dilihat dari sisi manapun, ada kemungkinan besar yang menunjukkan bahwa Alen memang gila.
“Bagaimana kamu tahu saya suka mengkhayal?”
Oke. Tidak masalah. Alen tidak menanyakan ini untuk mengumbar penyakit anehnya pada orang asing. Ia hanya butuh penjelasan supaya percaya ia tidak berurusan dengan orang aneh yang tak jelas.
Galen tidak langsung menjawab. Pemuda itu memainkan cangkirnya yang sudah kosong di atas pisin. Alen hampir habis sabar memperhatikan pemuda itu memutar-mutar cangkir dan menghasilkan bunyi gesek serta denting tak beraturan.
“Sebenarnya Alen, saya memperhatikan kamu sejak tahun pertama SMA. Mungkin benar, kita bersekolah di sekolah berbeda, tapi bukan masalah. Saya selalu bisa mendapatkan informasi tentang kamu. Banyak teman-temanmu yang bilang kalau kamu sering bicara di kamar mandi sekolah, katanya kadang kamu terlambat masuk karena terlalu asik bicara.”
Seluruh tubuh Alen menegang. Gadis itu meremas permukaan roknya sampai buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang biasa tampak lembut sekarang begitu keras. Ini bukan jawaban yang ingin Alen dengar. Bukan pula jawaban yang bisa membuat Alen merasa keanehan yang menyelimutinya masuk akal.
“Seperti yang sudah saya bilang, saya tahu segala hal tentang kamu.”


 Uswatunn
Uswatunn


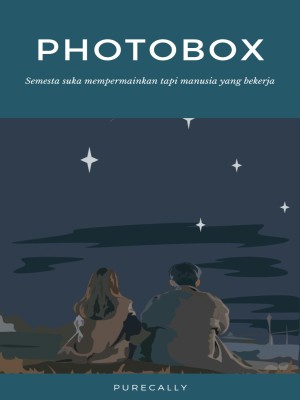




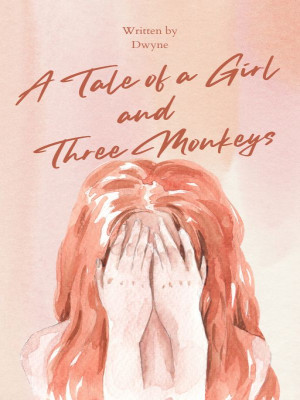


bagus
Comment on chapter Yang tidak diketahui