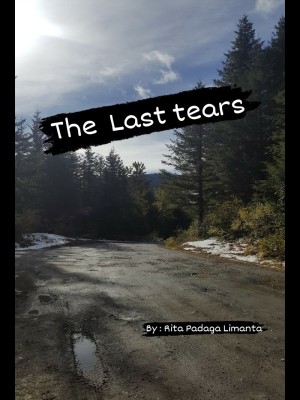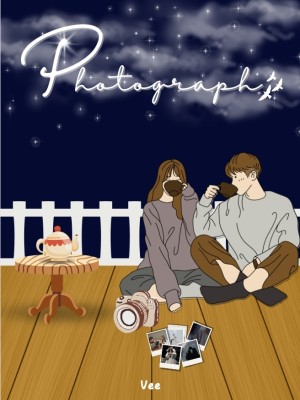Lima butir
kelereng besi itu saling bersinggungan satu sama lain. Mengayun teratur
membentuk garus linier di atas meja kerja Darren.
Darren terpaku
mengamati garis linier dari butiran keleng besi yang mengayun. Mendengarkan
dentingnya, seakan terhipnotis. Meski yang ia amati dengan seksama itu adalah
kekekalan momentum, percayalah, yang ada di pikirannya lebih dari sekadar hukum
Newton. Ia tak sekadar memikirkan gaya eksternal yang bergerak linier pada
benda seperti kelereng itu. Ia memikirkan kehidupan. Memikirkan dirinya. Teka-teki
alam bawah sadarnya.
Evolusi Darwin
mengatakan bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini berasal dari satu
spesies yang sama. Artinya, manusia, hewan, dan tumbuhan, berasal dari satu
spesies yang berevolusi sesuai hukum dan seleksi alam yang berlaku. Sedangkan
manusia termasuk kingdom animalia,
spesies paling pintar yang kemudian disebut homo
sapiens. Manusia berevolusi begitu sempurna melebihi kelompok animal
lainnya. Membentuk peradaban yang semakin maju dari waktu ke waktu. Tapi,
mengapa Darren merasa dirinya tak ikut berevolusi seperti para leluhurnya?
Ia adalah
manusia dengan ciri-ciri fisik yang amat sempurna. Tinggi tubuh 182 cm. Kaki
panjang dengan ruas-ruas otot yang membentuk proporsi ideal. Rambut hitam
mengkilap. Kulit kuning langsat seperti gadis keraton dengan sedikit gelap di
beberapa bagian akibat kemalasannya memakai sunblock.
Hidung mancung. Mata hitam bulat dengan lengkungan bulu mata yang panjang. Alis
tebal simetris yang merupakan warisan paling sempurna dari kakek buyutnya.
Sepertiga wajah bawahnya dipenuhi pangkal rambut janggut yang baru ia cukur.
Sedikit turun, ada tonjolan seperti kelereng di leher yang bergerak pelan saat
ia menelan ludah.
Kesempurnaan semu
tampak mengisi sosok lelaki bernama Darren yang sedang duduk manis di kursi
kerjanya. Tak hanya wajahnya yang menunjukkan keberhasilan evolusi manusia.
Tetapi juga otak briliannya. Ia telah menjadi doktor di usianya yang ke dua
puluh enam, tepatnya empat tahun lalu. Dan kini ia sedang memulai langkah
barunya dari seorang peneliti di labolaratorium psikologi pusat menjadi
pengajar profesional dan terlibat dalam birokrasi kampus swasta elite.
Semua
tentangnya tampak sempurna. Tanpa orang lain tahu, dalam tubuhnya bersarang
sebuah lubang yang selama ini ia artikan sebagai ‘kegagalan evolusi’.
Pintu ruang
berderit, seseorang masuk ke ruang kerja Darren.
“Bagaimana?
Kamu suka ruang kerja barumu?”
Pertanyaan itu
terlontar dari perempuan berusia lima puluhan yang tak lain adalah Profesor
Diana Marini, dekan Fakultas Psikologi kampus swasta elite tempat Darren
memulai karier barunya sebagai pengajar. Wanita dengan rambut diikat rapi dan
setelan jas abu-abu itu berjalan semampai menuju meja Darren. Menguarkan wibawa
sebagai sosok yang mengajari Darren kehidupan. Ia mendekat lengkap dengan
senyum hangatnya yang mekar anggun seperti bunga dahlia.
Darren beranjak
dari kursinya. Menyambut kedatangan Profesor Diana dengan raut wajahnya yang
tampak datar.
“Terima kasih
sudah menerima saya di sini, Profesor,” ucap Darren seketika Profesor Diana
sampai di hadapannya.
Dengan senyum
yang sama, Profesor Diana menjawab, “Aku yang harusnya berterima kasih karena
kamu bersedia mengajar di kampus ini.”
Darren berusaha
melekukkan senyum di bibirnya. Tampak kaku dan canggung.
“Tidak usah
dipaksa, Darren. Tidak perlu mencoba memanipulasi respon kesadaranmu.” Profesor
Diana berujar.
“Di hadapan
profesor saya tidak perlu melakukannya. Tapi orang lain perlu validasi,” kata
Darren.
“Kamu bisa
belajar sedikit demi sedikit, Darren. Di kampus ini kamu akan bertemu dan
berinteraksi dengan banyak orang. Stimulus sosial pastinya akan membawa sedikit
demi sedikit perubahan yang lebih baik.” Lalu Profesor Diana memutar tubuhnya.
Menatap jauh ke luar jendela ruangan Darren. “Kamu hanya perlu terbiasa dengan
dunia luar, Darren. Kamu bisa mulai mempelajari hal-hal baru di sekelilingmu.
Lalu menemukan jawaban untuk menutup ‘lubang’ yang berusaha kamu sembunyikan
selama ini. Bekerja di labolatorium tertutup menguntungkan secara kasat mata
karena membawa sensor yang sangat aman untuk alam bawah sadarmu. Tapi
bersembunyi tidak akan membawa dampak baik. Kamu perlu membuka diri untuk
melihat dunia yang lebih luas. Dimulai dari kampus ini.”
Penjelasan
panjang Profesor Diana membuat Darren tak bisa menampik kebenarannya. Benar
bahwa ia selama ini memilih hidup dalam persembunyian. Sebagai usaha menutupi
‘lubang’ besar dalam tubuhnya dari orang lain. Tetapi waktu terus merangkak
maju dan lubang itu masih hinggap di tubuh Darren. Tidak ada alasan lain untuk
Darren menolak tawaran Profesor Diana. Ia harus membuka diri dan berbaur dengan
dunia luar.
“Bagaimana
kalau ternyata ‘lubang’ itu adalah kegagalan evolusi, Prof?” Darren bertanya setelah
beberapa saat merenung.
“Kamu tahu
lebih dari siapa pun, Darren, tidak ada yang salah dari proses evolusi. Hanya
kamu satu-satunya orang dengan ‘lubang’ itu di keluargamu. Bukan karena
evolusi, bukan faktor genetik.” Profesor Diana menjelakan dengan pandangannya
yang belum beralih dari jendela ruang Darren. “Lihat anjing itu, Darren,”
lanjutnya bicara sambil menunjuk anak anjing yang sedang bermain dengan
beberapa mahasiswa di taman kampus, “seminggu yang lalu anjing itu menangis.
Ibunya baru saja meninggal karena radang usus. Dan anak anjing itu ada di
sampingnya, menyaksikan kematian ibunya.”
Pandangan
Darren ikut menuju anak anjing di taman yang sedang bermain dengan mahasiswa.
Ia mendengarkan penjelasan Profesor Diana dengan seksama.
“Bahkan anak
anjing pun bisa menangis karena merasakan emosi. Menurutmu, apa anak anjing itu
memiliki emosi karena mempelajari emosi seperti yang selama ini kamu lakukan?”
lanjut Profesor Diana bertanya. Lantas ia menatap Darren yang terdiam tanpa
kata. Senyumnya yang anggun pun kembali mengembang. “Tidak, Darren. Anjing itu
tidak mempelajarinya. Ia hanya melepaskannya. Hanya dengan melepaskan ia bisa
merasakan emosi. Di tempat ini kamu bisa belajar melepaskan sekat yang kamu
sendiri buat di masa kecilmu. Sekat yang mengurung emosimu di tempat yang tidak
bisa dijangkau alam bawah sadarmu. Tidak harus seketika, pastinya, tapi
perlahan-lahan sampai kamu tahu cara melepaskannya.”
Mendengarkan
semua penjelasan Profesor Diana, Darren menganggukkan kepala. Di saat
keluarganya sendiri terpecah belah, hanya Profesor Diana yang bersedia merawat
Darren semasa kecilnya. Mereka memang tak memiliki ikatan darah. Tapi Profesor
Diana hadir melebihi sosok orang tua bagi Darren.
“Baik, Prof.
Terima kasih sudah memberi saya kesempatan.”
Profesor Diana
menepuk pelan pundak Darren. “Sudah lama kita nggak makan malam bersama
Angeline. Nanti malam kamu bisa meluangkan waktu buat makan malam?”
“Angeline mau
pulang, Prof?”
Sekilas Profesor
Diana melirik arloji di tangan kirinya. “Sebentar lagi tiba.”
Sekali lagi
Darren menganggukkan kepala. “Baik, Prof.”
“Sementara
jadwal mengajarmu belum diputuskan, kamu bisa mengisi waktu buat mengenali
seluk beluk tempat ini. Labolatorium psikologi
ada di sebelah gedung opera, barang kali kamu ingin ke sana.”
Setelah menyelesaikan
kalimatnya, Profesor Diana berjalan anggun meninggalkan ruangan Darren. Di saat
itu juga Darren kembali melihat anjing diluar jendela. Berdiri tanpa kata,
tanpa ekspresi, menatap anak anjing jenis pudel yang melompat-lompat di atas
rerumputan taman bersama tiga mahasiswa perempuan.
Anjing pun bisa
menangis.
Pandangannya tampak kosong. Sesuatu menariknya menuju ruang hampa nan
sunyi. Ruang yang bersemayam di kesadarannya. Tempat paling damai yang
menyerupai mimpi kanak-kanak. Tidak ada kebisingan. Tidak ada tempaan yang
menyakitkan. Tidak ada bukti-bukti eksistensi dari emosi yang menjadikan
segalanya menjadi rumit. Ruang paling masyhur yang membuatnya lelap. Ruang
tempat sesuatu dari luar tubuhnya bersemayam.
Sekelebat wajah muncul di kesadarannya. Darren mengeluarkan sesuatu
dari saku celana. Sebuah jam saku berwarna perak yang terikat dengan sesuatu
berwarna emas. Liontin berbentuk hati. Darren membuka kedua sisinya. Melihat
wajah sukaria seorang gadis kecil yang menatapnya penuh ceria. Wajah manis
dengan senyum yang begitu terang.
Dalam ruang hampa Darren yang begitu gelap nan sunyi, hanya wajah
gadis itu yang memberikan sedikit penerangan. Wajah dari seorang yang tak ia
ketahui siapa. Yang telah bersemayam di kesadarannya cukup lama. Mengiringi
keberadaan lubang hitam yang ada dalam dirinya. Menjadi satu-satunya yang putih
di antara semua yang gelap. Darren merasa terikat dengannya. Sangat melekat.
Kertap pintu menyadarkan Darren dari lamunan. Seorang pria muda
yang ia prediksi adalah mahasiswa tingkat akhir berdiri di ambang pintu.
Membawa selembar kertas berukuran A3 yang digulung seperti peta.
“Permisi, Doktor. Profesor Diana meminta saya memberi denah lokasi
kepada Anda.”
*
Sesuai anjuran Profesor
Diana, Darren mengisi hari pertamanya di kampus dengan berjalan-jalan
mengelilingi lokasi. Berkenalan dengan suasana baru yang jauh berbeda dari
suasana labolatorium tempat ia selalu menghabiskan waktu.
Udara yang
segar mengisi paru-parunya dengan kejernihan alami, bukan dari penjernih udara
elektronik di ruang kerjanya. Tanaman hijau yang tumbuh subur di seluruh area
kampus seakan menjadi penyaring dari polusi. Suhu udara di tempat ini beberapa
derajat lebih dingin dari suhu udara ibukota. Terasa sejuk dan menenangkan,
seakan Darren tengah bercengkeram dengan aromaterapi dari bunga-bunga yang
merebakkan bebauan segar.
Ia berusaha mengenali
lebih dekat tempat ia akan menghabiskan banyak waktunya sebagai pengajar. Mempelajari
setiap struktur bangunan yang memiliki sejarah cukup panjang sebelum reformasi.
Mengamati para mahasiswa yang tampak produktif belajar di atas rerumputan taman
bersama anjing kecil yang berguling-guling.
Di samping
sebuah bangunan dekat taman langkah Darren berhenti. Pemandangan menarik dari
dinding kaca ruang penarikan uang itu seketika membuatnya mendekat.
Missing Person!
Tulisan itu
menarik. Darren membaca tajuk dari poster orang hilang itu. Bola matanya
menajam. Membaca kata demi kata yang mengantarnya pada sebuah foto anak
laki-laki berusia sepuluh tahun.
Dilihat dari
kertasnya yang masih baru, sepertinya poster ini belum lama ditempel. Artinya,
seseorang kembali mencari anak yang hilang dua puluh tahun silam. Yang berarti
juga, orang itu belum menyerah dan masih berharap akan menemukan anak yang
hilang selama dua dekade. Ada harapan sekaligus rasa putus asa yang tersirat di
dalam poster pencarian orang hilang itu. Darren membacanya dengan menyibak
semua kesemuan yang menyertai. Membaca sesuatu yang lebih besar dari rangkaian
kata-kata.
Menarik.
Pencarian penuh
rasa putus asa. Darren terpaku pada kenyataan bahwa ada seseorang yang masih
memiliki harapan setelah dua dekade berlalu dan menyebarkan poster orang hilang
dengan informasi penuh keragu-raguan dan ketidakpastian.
Anehnya, foto
anak kecil di poster itu terasa familiar di mata Darren. Seakan-akan ia pernah
melihatnya. Dan semakin ia amati foto anak kecil itu, ia merasa menyatu
dengannya.
Kening Darren
mengernyit. Sekelebat ingatan masa kecil menariknya ke sebuah momen. Wajah
laki-laki dalam poster itu. Wajah yang rupanya sangat ia kenali. Tak hanya
mengenali, ia bahkan merasa bocah lelaki itu adalah bagian dari dirinya. Bagian
dari lubang yang bersemayam dalam tubuhnya.
Teringat
sesuatu, Darren merogoh saku celana hitamnya. Menarik keluar jam saku klasik
yang selalu ia bawa ke mana pun ia pergi. Jam saku perak yang telah ia ikat
dengan sebuah liontin emas berbentuk hati. Kedua benda itu telah ia perlakukan
seperti jimat selama ini. Ia bawa ke mana pun ia pergi. Dan kalau hilang ia
cari melebihi anggota keluarganya sendiri.
Ia mencocokkan
liontin emas dalam genggamannya dengan liontin hati yang anak lelaki dalam
poster itu pakai. Tampak identik. Darren segera menyakui kembali jam sakunya.
Melihat nomor telepon yang tertulis di poster. Merekamnya baik-baik dalam
ingatan. Lalu membaca detil alamat Kedai Bunga Peony yang menjadi jaminan
pencarian orang hilang itu.
Saat menghapal
alamat Kedai Bunga Peony, Darren menyadari sesuatu. Astaga. Alamat itu tidak
jauh. Ia hanya perlu keluar gerbang kampus dan berjalan seratus meter untuk
sampai di Kedai Bunga Peony. Benar. Sedekat itu.
*


 elyarafanani
elyarafanani