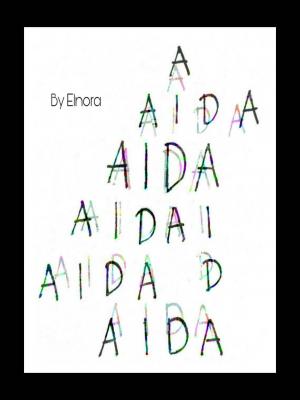Pagi ini, aku berangkat lebih pagi, disebabkan tidak ingin bertemu Gian ketika dia datang untuk menjemput. Tapi karena kami satu kelas, mau tidak mau aku tetap bertemu dengannya.
“Kenapa tiba-tiba minta putus?” tanyanya langsung ketika menghampiriku setelah bel istirahat baru berbunyi.
“Nggak ada apa-apa,” jawabku. “Aku cuma bosen sama kamu.”
Gian tanpa aba-aba langsung menarik tanganku. Dia berjalan menggandengku ke kursi panjang yang ada di bawah pohon samping lapangan outdoor.
“Bohong.”
“Aku nggak bohong.”
“Lalu kenapa? Apa alasannya?”
“Kubilang aku lagi bosen, Gi.”
“Bosen sama hubungan kita?” tanyanya. “Apa yang bikin kamu bosen?”
“Aku nggak mau ngomong sama kamu,” kataku sambil memalingkan wajah.
“Bener karena bosen? Bukan karena ibuku?”
“Eh?”
Aku terkejut begitu dengar pertanyaan Gian.
“Aku udah tau.”
“Tau apa?”
“Ibuku sama Papamu. Aku tau,” jawab Gian.
Aku diam karena tidak tahu harus bicara apa.
“Kamu kenapa nggak pernah cerita ke aku?”
Pertanyaan Gian barusan cuma bisa kujawab menggunakan gelengan pelan.
“Kamu juga tau, kan, perbuatan mereka?” tanya Gian. “Makanya, kamu tiba-tiba minta putus semalem?”
“Kamu tau dari siapa? Mbak Yanti yang cerita?”
“Bukan,” jawab Gian.
“Terus, dari siapa?”
“Ibu pulang ke rumah semalem. Dia cerita semuanya ke nenek buat minta solusi,” jawabnya. “Aku nggak sengaja denger.”
“Oh.”
“Alasanmu minta putus sebenernya karena itu, kan?”
“Iya, maaf.”
“Habis ini, jangan ngomong putus lagi.”
Tidak kujawab. Kusenderkan kepalaku di bahu Gian, berharap agar mendapatkan ketenangan, berharap agar berbagai pikiran yang hinggap dalam kepalaku bisa sirna seketika.
“Gian.”
“Hm?”
“Kita harus apa?” kutanya.
“Apanya?”
“Kalau sudah begini, kita harus apa, Gian?”
“Aku juga nggak tau.”
“Boleh, nggak, ya, kalau bayi itu digugurin aja?”
“Bayi yang ada di perut ibuku?”
“Iya,” jawabku. “Tapi, bayi itu nggak salah.”
“Iya, bayi itu nggak berdosa, jangan digugurin.”
“Terus, kita harus apa?” tanyaku. “Kalau bukan putus, kita harus apa?”
“Dengerin aku.”
Aku kemudian mengangkat kepala, memandang lurus ke Gian. Dia lalu memberiku sebuah kartu nama milik seseorang yang tidak kukenal. Kuperhatikan kartu nama itu dengan pandangan bingung.
“Aku dapet tawaran kuliah musik di Inggris dari orang itu.”
“Kamu kenal orang ini dari mana?”
“Semalem, habis kompetisinya selesai.”
“Terus, kamu mau nerima tawaran dari beliau?” kutanya serius.
“Masih kupikir-pikir dulu.”
“Ini tawaran bagus, Gian.”
“Iya, aku juga mikir begitu,” kata Gian.
“Kenapa nggak langsung di-iya-in aja?” tanyaku.
“Aku butuh kamu selama di sana.”
“Kenapa aku?”
“Kamu sendiri, kan, kemarin yang pengen kita kuliah satu kampus?” tanya Gian dengan raut wajah tegas sekaligus tampak serius. “Aku juga nggak mau jauh dari kamu lagi.”
“Tapi, Inggris terlalu jauh buatku.”
“Haira, kita bisa mulai awal hidup yang baru,” katanya. “Di sana, kita nggak perlu ketemu ibuku atau Papamu, jadi mau, ya, ikut aku ke sana?”
“Biar kupikir-pikir dulu.”
“Kenapa harus dipikirin dulu?”
“Kasih aku waktu, Gi,” kataku.
“Berapa lama?”
“Biar kupikirin dulu matang-matang. Nanti, kalau udah ketemu jawabannya, aku kasih tau ke kamu.”
“Oke, aku tunggu.”
“Iya.”
Tidak berapa lama kemudian, bel masuk berbunyi. Kami bangkit dari kursi, lalu jalan bersisian sambil pegangan tangan. Masih tersisa tiga mata pelajaran untuk hari ini. Tapi, pikiranku masih susah untuk bisa fokus karena sedang memikirkan banyak hal.
Setelah bel pulang berbunyi, Gian minta aku untuk ikut dengannya saja.
Kuiyakan saja permintaannya, karena sebenarnya aku juga ingin duduk satu motor dengannya lagi.
Selama perjalanan, kami saling diam.
Sepertinya, baik aku maupun Gian sedang sibuk dengan pikiran masing-masing.
Selama dibonceng oleh Gian, kedua mataku terus terpejam seperti orang sedang meditasi.
Semuanya terlalu tiba-tiba bagiku, terlalu rumit dan harus kutata satu demi satu terlebih dahulu sebelum memutuskan. Rasanya berat sekali, betul-betul melelahkan.
*****
Rumah dalam keadaan sepi ketika aku baru masuk.
Tidak lama kemudian kudengar suara orang ribut-ribut. Ternyata suara itu berasal dari Mbak Yanti dan Papa di lantai dua.
“Kamu pokoknya harus tanggung jawab!” Mbak Yanti membentak.
“Belum tentu itu anak saya.”
“Jelas-jelas ini anakmu! Setelah cerai, satu-satunya laki-laki yang pernah tidur sama aku ya cuma kamu, Mas!”
“Kamu pikir saya percaya?”
“Oke. Kalau kamu masih tetep nggak mau tanggung jawab, aku telepon istri kamu sekarang juga.”
“Jangan berani-berani kamu!” bentak Papa.
Aku terus mengintip pertengkaran mereka dari balik tembok. Tidak ada niat untuk mendekat, apalagi melerai. Itu urusan mereka sebagai orang dewasa, biarlah mereka selesaikan dengan cara mereka sendiri.
“Makanya, tanggung jawab sebagai laki-laki!” kata Mbak Yanti. “Mana janjimu mau nikahin aku, Mas?!” tanya Mbak Yanti.
“Saya memang mau nikahin kamu, tapi itu dulu.”
“Kenapa sekarang kamu berubah?”
“Kamu nggak mikirin perasaan Haira sama anakmu?”
“Aku tau Rara sama Gian lagi pacaran. Tapi, mereka masih muda, belum tentu mereka akan menikah nanti.”
“Tapi, bagi saya kebahagiaan Haira lebih penting!”
“Apa istrimu bakal kasih restu ke mereka berdua?”
“Kenapa kamu nanya begitu?”
“Jangan naif, Mas! Aku tau betul sifat istrimu itu kayak apa ke orang-orang yang nggak setara sama keluarga kalian.”
“Meski dia nggak kasih restu, saya tetep kepala keluarga di sini.”
“Masih nggak tau malu kamu nyebut dirimu sebagai kepala keluarga setelah perbuatan yang kita lakukan?”
“Apa maksudmu?”
“Kepala keluarga macam apa yang mengkhianati keluarganya sendiri?”
“Jaga mulutmu!”
“Apa yang kubilang ini bener, kan, Mas?” kata Mbak Yanti menantang. “Jangan berlagak jadi Papa yang baik buat Rara! Kamu itu Papa yang buruk buat anak sebaik Rara! Mana mau dia punya Papa tukang selingkuh kayak kamu!”
“Mulai hari ini, saya pecat kamu!” kata Papa. “Keluar dari rumah ini sekarang juga!”
“Kamu buang aku, Mas? Setelah aku hamil anak kamu?”
“Saya nggak pernah punya anak dari kamu. Sekarang pergi!”
“Aku nggak akan pergi sebelum kamu tanggung jawab. Kalau kamu nggak mau, aku bisa telepon istri kamu sekarang juga. Aku bakal bongkar semua perbuatan kamu di belakang dia.”
“Lebih baik kamu gugurkan anak itu.”
“Apa? Gugurin?”
“Iya, gugurkan anak itu sekarang juga.”
Tangan Mbak Yanti terangkat untuk menampar pipi Papa.
“Gila kamu!”
“Berani kamu tampar saya?”
“Aku minta kamu buat tanggung jawab, bukan malah nyuruh gugurin anak ini!”
“Cuma itu satu-satunya solusi. Semuanya nggak akan jadi rumit begini kalau anak itu nggak ada!”
“Tega kamu bilang begitu sama anakmu sendiri?”
“Katamu tadi, saya Papa yang buruk untuk Rara.”
Mbak Yanti diam. Papa kembali angkat bicara:
“Saya juga Papa yang buruk untuk anak itu, jadi daripada dia punya Papa seperti saya, lebih baik gugurkan dia sekarang.”
“Dasar laki-laki sampah!”
Mbak Yanti tampak semakin murka.
“Berani kamu bilang begitu?”
Mereka terlihat semakin bersitegang.
“Kamu perempuan nggak tau diri!” kata Papa.
“Apa katamu?”
Mbak Yanti kemudian mengeluarkan ponselnya. Dia mengutak-atik benda itu sebentar sebelum menempelkannya di samping telinga.
“Mohon maaf mengganggu, Nyonya, tapi saya punya sesuatu penting yang harus saya beritahukan pada Nyonya sekarang juga,” kata Mbak Yanti yang sepertinya dia sedang menelepon Mama.
“Ngapain kamu sekarang?!”
Papa berusaha merebut ponsel itu.
“Biarin aku bicara sama istrimu!”
Mbak Yanti yang masih diliputi amarah berusaha sekuat tenaga agar ponselnya tidak sampai direbut oleh Papa.
“Lepasin, Mas!” teriak Mbak Yanti yang sepertinya mulai kewalahan.
Peristiwa yang selanjutnya terjadi membuatku terkejut bukan main.
Papa berhasil merebut ponsel milik Mbak Yanti. Tapi hal itu justru membuatnya terjatuh dari lantai dua. Dia jatuh berguling di tangga sampai berakhir dengan posisi terkapar mengenaskan di lantai satu. Bau anyir seketika tercium akibat darah yang menggenang di sekitar kepala Papa. Mbak Yanti sontak teriak histeris dari tempatnya berdiri.
Aku juga melihat, menyaksikan sendiri bagaimana Papa jatuh hingga terkapar, tubuhku seketika bergetar hebat. Aku teriak sekencang-kencangnya. Segera kuhampiri tubuh Papa, yang sayangnya sudah tak bernyawa.


 nakum18
nakum18