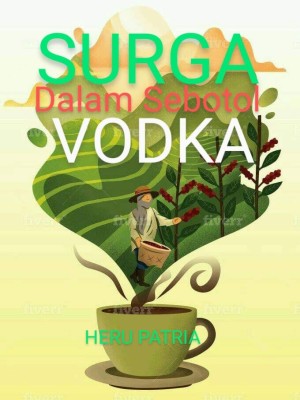"Kamu nggak ada kerja hari ini, Nam?" Suara Bu Fitri membuatku menoleh sebentar, lalu menyimpan pensil yang dari tadi aku gunakan untuk menggambar.
Aku menggeleng cepat sebagai jawaban. "Hari ini aku janji mau jemput adikku, Bu."
Bu Fitri duduk di depanku. "Hari ini kok tumben Bastari nggak ada, Nam?"
"Bastari tadi langsung dijemput paksa Mas Niko, Bu."
Mendengar kalimatku barusan Bu Fitri tertawa geli. Aku selalu bingung dengan pilihan kataku yang terkadang membuat lawan bicaraku justru tertawa, seperti saat ini. Aku hanya tersenyum menanggapi tawa Bu Fitri.
"Kamu nih, Nam, ada-ada saja. Mas Niko kan kakaknya Bastari, mana ada pemaksaan, itu memang sudah kewajibannya sebagai kakak, kan?"
Aku memamerkan deretan gigiku. "Maksudnya Nami, Mas Niko kan nggak perlu jemput Bastari segala, Bu ... lagian Bastari sudah gede juga, biasanya juga dia naik angkot bareng Nami," ucapku, teringat bagaimana Bastari berteriak kepada Mas Niko saat kakaknya itu mengancam tidak akan membiarkan Bastari keluyuran setelah jam pulang, termasuk untuk ekstrakurikuler sekalipun, kalau saat itu Bastari menolak ajakannya.
Ponselku berbunyi tanda pesan masuk. Aku melirik kearah layar ponsel yang menyala, di sana ada nama Babas.
"Mungkin kali ini ada urusan keluarga yang mendesak, Nam. Makannya Mas Niko sampai jemput, kan ...."
"Iya, Bu, mungkin," sahutku.
Bu Fitri mengeluarkan plastik dari dalam tas yang ia bawa. "Ini ada sedikit kue yang ibu buat sendiri, baru belajar, mungkin rasanya nggak akan seenak kue yang dijual di toko rotinya Bastari. Tapi, ibu harap kamu mau menerimanya, ya, Nami?" Bu Fitri memberikan plastik itu kepadaku.
Aku menerimanya, sembari berujar ucapan terima kasih atas pemberian Bu Fitri. "Ibu, apa boleh aku tunggu di sini sampai adikku mengabari untuk menjemputnya?" tanyaku. Jujur saja sebenarnya keberadaanku di perpustakaan membuat Bu Fitri jadi terlambat pulang.
Aku melihat air wajah Bu Fitri yang berubah, dia melihat sambil lalu ke arah jam tangannya. "Maafkan Ibu ya, Nami ... Ibu hari ini harus pulang cepat," jawabnya.
"Ah, begitu .... Iya, Bu, nggak apa-apa, kok. Nami bisa tunggu di taman depan saja." Aku segera membereskan peralatan menggambar milikku ke dalam tas.
"Sekali lagi Ibu minta maaf, ya, Sayang," ucap Bu Fitri dengan ekspresi menyesal yang kentara di wajahnya.
Aku mengukir senyum simpul, lalu berkata, "Nggak usah minta maaf, Ibu ... nggak apa-apa, Ibu nggak salah, kok."
Aku beranjak dari tempat duduk dan segera berdiri di sebelah Bu Fitri. "Ayo, Bu. Kita jalan sama-sama sampai depan," tambahku, segera dijawab lewat anggukan oleh Bu Fitri.
Bu Fitri pamit undur diri saat tiba di taman depan. Dia segera menuju tempat parkir yang berada tidak jauh dari taman. Tidak lama, sepeda motor yang dikendarai oleh Bu Fitri datang. Bunyi klakson panjang terdengar nyaring, dan membuatku melambaikan tangan kearahnya.
"Hati-hati, Bu!" Aku berseru.
Aku duduk di salah satu kursi yang ada di taman depan. Aku kembali ingat pesan Bastari yang belum sempat aku buka, baca dan balas.
Babas: [Nami ... tolong aku, please! Mas Niko gila, Nam!]
Babas: [Kamu tahu kan, perkara Mas Niko yang nggak mau nikah dan dia sampai ngaku di hadapan ortu kalau dia homo?]
[Aku sudah pernah cerita, kan, Nam?]
Aku menggelengkan kepalaku ke kiri dan kanan, sembari mengurut dadaku pelan seiring dengan embusan napas yang keluar. "Ampun banget deh nih, kakak-adik! Nggak ngerti lagi aku!"
Kembali aku membaca kelanjutan pesan yang dikirim oleh Bastari kepadaku.
Babas: [Gara-gara dia yang nggak mau nikah, akhirnya ortu aku nyuruh aku ikut acara pertemuan sama keluarga besar Pak Subroto, Nami ...!]
Babas: [Nami! Kamu tega banget nggak balas pesan aku, Nam! Dasar tega, sahabat macam apa kamu, Nam? 😭]
[Balas pesanku, Napa, dah!]
Tawaku pecah membaca isi chat terakhirnya. Segera aku membalas pesan Bastari.
Anda: [Maksudnya, kamu mau dinikahi sama om-om yang usianya 11-12 sama Papi kamu, gitu, Bas?]
[Atau gimana, sih? Aku nggak ngerti 😩]
Belum dibaca. Tumben Bastari cuekin chat aku?
"Anjing! Bangsat!" Tiba-tiba saja kalimat umpatan itu terdengar dan sukses membuat aku menengok ke sumber suara.
Kedua mataku terbuka lebar saat mendapati beberapa laki-laki berlarian sambil membawa tongkat baseball berlari mondar-mandir di depan gerbang sekolah.
"Hei, hei! Ada apa ini? Ngapain kalian di depan gerbang sekolah ini, hah?" Kali ini giliran suara Pak Tono, satpam sekolah yang terdengar. Takut-takut aku berjalan menuju arah gerbang. Aku melewati pos satpam terlebih dahulu, sebelum sampai di gerbang sekolah.
"Anjing! Si setan itu hilang!" Salah seorang dari gerombolan siswa laki-laki itu berkata, setelah pandangannya beredar ke dalam sekolah dan memastikan bahwa yang dicarinya tidak ada, dia memberikan kode lewat lembaian tangannya dan seketika gerombolan itu bubar mengikuti laki-laki itu.
"Ada apa, Pak?" tanyaku tiba-tiba penasaran.
"Nggak tahu, Dik. Tapi sepertinya mereka cari seseorang dari sekolah kita, hanya saja Bapak nggak tahu siapa yang mereka cari." Pak Tono menjelaskan.
"Daripada mereka ribut di sini, lebih baik Bapak usir, kan, Dik?" tambahnya.
Aku setuju jadi aku hanya mengangguk.
"Dik Namina belum pulang?"
Aku menggeleng pelan. "Belum, Pak. Kebetulan sebentar lagi Nami baru pulang, sekalian jemput adik."
"Oooh, begitu ...."
Aku mengangguk sebagai jawaban. "Masih banyak yang belum pulang di dalam, Pak?" Kali ini giliran aku yang bertanya.
"Iya betul, Dik. Masih banyak. Biasalah, Dik, siswa yang sedang ada kegiatan ekstrakurikuler."
Sekali lagi aku hanya dapat mengangguk sebagai jawaban.
"Kalau begitu, Bapak ke dalam dulu ya, Dik," pamit Pak Tono yang segera menuju pos jaganya. Mungkin dia harus memberikan laporan terkait dengan gerombolan barusan.
Ponsel miliku berbunyi nyaring, panggilan masuk dari adikku. Segera aku mengangkatnya. Adikku meminta jemput.
Aku berjalan menuju tempat pemberhentian angkutan umum sambil mengirim pesan kepada adikku.
Anda: [Tunggu sebentar ya, Kakak sedang menunggu angkot.]
"Aduh!" Kakiku terantuk sesuatu yang membuat tubuhku limbung ke depan. Aku terkejut saat melihat seseorang tengah berbaring di sana dan menghalangi laju kakiku. Rasa kaget itu tidak hilang sampai di situ, saat tiba-tiba tubuh yang membelakangiku itu berbalik dan menampakkan sosok Gi yang penuh luka lebam di wajahnya.
"Astaganaga!" pekikku dan segera beranjak dari tempatku terjatuh.
"Hei, kamu!"
Aku pura-pura tidak mengenali dirinya, dan memilih membuka kembali ponselku.
"Hei, cewek cengeng yang tadi pagi!" Kalimat itu entah kenapa berhasil membuat atensiku penuh kepadanya.
"Apa kamu bilang?"
Bukannya menjawab pertanyaan dariku, Gi justru tersenyum tidak ramah, cenderung meremehkan. "Kalau kamu menolongku, aku janji akan membalasnya nanti," ucapnya.
"Kalau aku nggak mau? Kamu mau apa?" balasku gusar.
Sekali lagi senyum itu bertengger pada wajahnya yang babak belur. "Aku bisa minta Papaku untuk mengeluarkan kamu dari sekolah. Kamu mau?"
Jujur saja aku tidak menyukai gaya dia yang sok berkuasa barusan. Padahal jelas-jelas dia sedang butuh bantuan tapi malah menyebalkan. Entah kenapa, situasi ini mirip seperti dongeng yang dulu sempat aku baca di buku, tentang 'Singa dan Tikus' dan pada akhirnya membuat tikus membantu singa yang sedang terjebak di jaring pemburu.
Sial, aku kalah!
Aku mendengus sebelum akhirnya berkata, "Jadi kamu mau minta tolong apa?"
"Kamu bisa mengendarai motor?" Gi beranjak, tubuhnya yang jangkung itu perlahan-lahan duduk di salah satu bangku.
"Bisa," jawabku singkat dan jelas.
"Motor cowok bisa?" tanyanya sekali lagi.
"Nggak, aku cuma bisa bawa motor metik," ungkapku jujur. Teringat cerita Bastari tadi pagi aku semakin malas berbicara dengan Gi, orang yang menurutku tidak bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai siswa.
"Nggak guna!"
Baru saja aku mendengar laki-laki yang dibenci seantero sekolah itu mengumpat padaku.
"Maksud kamu apa?" Nada suaraku tidak dapat dikontrol.
"Kalau begitu aku nebeng motormu." Dengan seenak jidat dia berkata.
"Aku nggak punya motor."
Sebelah alis tebal miliknya terangkat, dari air wajahnya terlihat jelas kalau dia tidak percaya dengan kata-kata yang aku ucapkan. Terserah.
"Kamu pulang naik angkutan umum?" Kali ini dia bertanya lagi tanpa mengabaikan betapa kesalnya diriku. Aku hanya bisa mengangguk sebagai jawaban.
"Ya iya, lah ... masa ya iya, dong!" Tambahku kesal. Dia beranjak dari tempat duduk dan berjalan sambil tertatih kearahku.
"Bawa aku .... A--aku ...." Laki-laki itu belum selesai berkata, dan dengan tanpa rasa bersalah dia justru pingsan.
"Apa-apaan ini?" Aku memekik saat tubuh jangkung itu menimpaku.
🌱


 tyanti
tyanti