Aku menyetir secepat yang kubisa. Aku melanggar semua
tanda Stop dan semua lampu merah dan seharusnya seluruh mobil polisi sudah
antre megejarku. Untungnya tidak. Aku masuk ke apartemen Anna dengan kunciku
sendiri dan langsung melihatnya. Ia sedang duduk menangis di sofa. Dan pria itu
ada di sana. Ia duduk di sebelahnya sambil memegang sekotak tisiu. Harusnya aku
tahu bahwa jika aku datang dengan helikopter sekalipun, ia tetap akan tiba di
sisi Anna lebih cepat karena ia tinggal di komplek apartemen yang sama. Aku
menjatuhkan diriku di sofa di samping Anna dan menariknya ke dalam pelukanku.
Justin berdiri, meletakkan kotak tisiu itu di meja dan berjalan menjauh. Ia duduk
di kursi meja makan sambil mengutak-atik ponselnya. Anna membenamkan wajahnya
pada dadaku dan menangis lebih keras.
“Shh.. Aku ada di sini,” bisikku. Walaupun mungkin
kalimat itu membuatnya lebih sedih karena walaupun aku ada di sini, kakaknya
tidak ada di sini dan tidak akan pernah bisa ada di sini lagi. “Anna, ceritakan
lagi padaku apa yang terjadi,” kataku. Tadi ia sudah bercerita di telpon di
sela sela tangisannya bahwa ia baru ditelpon papanya yang mengabarkan bahwa kakaknya, Amos, baru saja
tabrakan
“Dia sudah tidak ada. Dia sudah pergi. Aku tidak akan
pernah bisa melihatnya lagi,” katanya sambil terisak-isak. Aku tidak tahu harus
berkata apa. Apa yang dapat kau katakan pada seseorang yang baru kehilangan
seorang kakak? Apakah ada kata-kata yang punya kekuatan meringankan luka hati
seperti itu?
Tiba-tiba Justin berdiri dan berjalan ke arah kami.
“Sudah dapat,” katanya.
“Dapat apa?” tanyaku.
“Tiket,” katanya. “Jika ia terbang malam ini, masih
keburu mengejar pemakaman,” tambahnya. Rupanya sewaktu aku sibuk memikirkan apa
yang harus kukatakan untuk menenangkan Anna, Justin bukan cuma hanya main-main
dengan ponselnya.
“Jam berapa flight nya?” tanyaku.
“Setelah tengah malam,” katanya. Ia lalu memandang jam
tangannya. “Aku juga sudah memesan makanan. Harusnya sebentar lagi datang.
Bisakah kau temani dia di sini? Aku perlu beres-beres. Lima menit,” katanya.
“Ya, tentu,” kataku. Karena di mana lagi aku harus
berada? Tentu saja aku akan berada di sisi Anna tanpa perlu disuruh olehnya.
“Kau perlu beres-beres apa?” tanyaku.
“Baju. Aku akan pulang dengannya. Mana mungkin aku
dapat membiarkannya pulang seorang diri dalam kondisi seperti ini?” katanya. Ia
tidak menunggu jawabanku. Ia membuka pintu dan keluar.
“Kau mau aku temani pulang?” tanyaku. Aku setengah
berharap ia akan bilang iya, tapi di saat yang sama, jika ia bilang iya, aku
tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan semua kelas-kelas yang kuajar.
Semester musim semi baru berjalan separuh jadi akan susah bagiku untuk pergi.
“Tidak usah. Kau harus mengajar,” katanya seolah
membaca pikiranku.
“Anna, aku... turut berduka,” kataku. Ia mengangguk.
“Sebaiknya aku beres-beres,” katanya sambil berdiri dan
berjalan ke kamarnya. Aku mengikutinya. Ia hanya perlu waktu lima menit untuk
memasukkan sedikit barang ke dalam tas sport kecil. Yah, tentunya dia tidak
harus membawa banyak barang karena dia toh akan pulang dan bukannya pergi ke
tempat lain. Sesaat kemudian pintu depan di ketuk. Pastinya itu si pengantar
makanan yang dipesan Justin. Aku membuka pintu dan ternyata Justin juga sudah
kembali. Ia mengambil bungkusan makanan dari si pengantar dan memerikan tip
sebesar $20. Si pengantar makanan tersenyum lebar. Justin masuk dan meletakkan
tasnya di samping pintu. Aku melihat passport dan dua boarding pass yang baru
dicetaknya di kantung tepi tas. Boarding pass kelas bisnis. Ia meletakkan
bungkusan makanan di atas meja makan dan mulai mengambil piring dan alat makan
dari lemari Anna. Ia bergerak dengan
efisien seperti layaknya seseorang yang sering berada di tempat ini. Rupanya
aku bukan satu-satunya orang yang sering datang ke sini.
“Aku.. aku akan memanggil Anna,” kataku. Ia menangguk.
Makan malam itu begitu canggung. Kami berdua seperti
berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian Anna. Kami berdua menyendokkan
makanan ke piringnya. Kami berdua bertanya apakah dia perlu lebih. Kami berdua
bertanya apakah benar dia sudah kenyang. Dan tiba-tiba aku sadar sesuatu yang
harusnya sudah lama kusadari. Kami berdua mencintai gadis yang sama. Dan ada
satu hal lagi yang amat menggangguku. Pria yang satu ini bisa dengan enak saja
datang lalu menyewa sebuah studio di komplek apartemen Anna. Pastinya dia
mengunjungi Anna sesering yang ia bisa, mungkin dia datang setiap kali aku
tidak ada di sini. Dan sekarang ini, di saat Anna mengalami kesusahan, dengan
berbekal dua tiket business class di tangannya, dia langsung siap siaga
mengantar Anna pulang. Bagaimana caraku bersaing dengan orang seperti ini?


 arleen315
arleen315




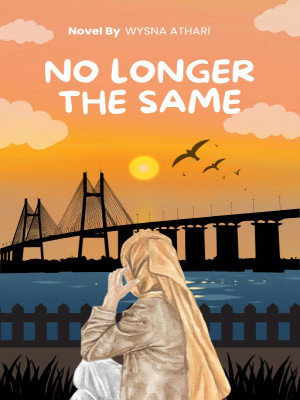





One of my favorite authors / writers
Comment on chapter opening page