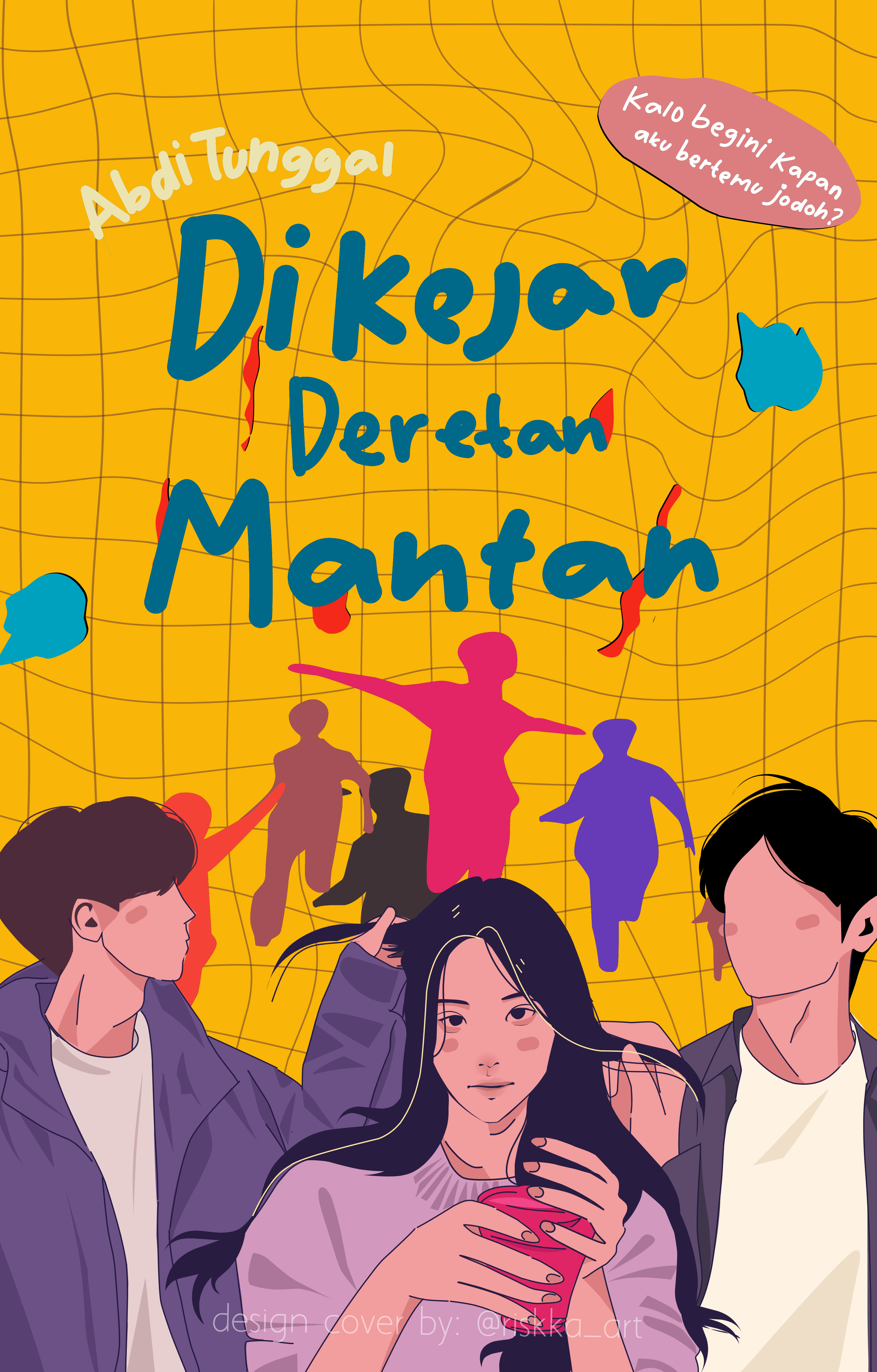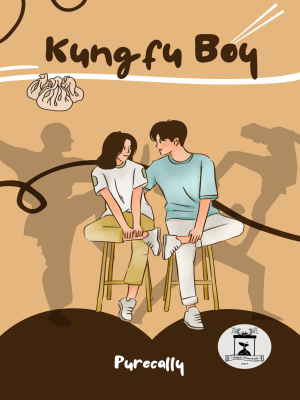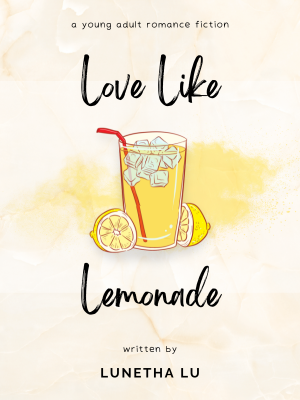Lisa membanting dirinya ke sofa sembari menghela napas gusar. Setelah panjang lebar bicara dengan Bu Ramona, mereka mencapai kesepakatan jika Lisa tidak perlu mengembalikan uang muka bayaran yang sudah diberikan Herman. Tetapi, sebagai gantinya ia akan bantu-bantu di restoran Jepang milik sepupu Ramona. Besok dia sudah bisa masuk kerja. Ya, tak masalah, lah.
Pintu depan kemudian terbuka, menampakkan ibunya yang kemungkinan baru pulang dari membeli lauk-pauk untuk makan malam. Hari ini Lisa memang berpesan pada ibunya untuk tidak masak, walau ibunya sudah pulang dari sore karena kebagian shift pagi. Kemarin malam Lisa tak sengaja mendengar keluhan sakit dari ibunya. Saat Lisa bertanya lebih lanjut mengenai apa yang dirasa, ibunya itu hanya diam dan mengalihkan pembicaraan.
“Oh, Lisa. Baru sampai?” tanya ibunya, melewati Lisa untuk terus berjalan menuju dapur. “Mandi dulu, Sayang. Habis itu kita makan sate!” lanjut sang ibu, yang langsung dibalas teriakan ‘oke’ dari Lisa.
Lima belas menit kemudian, Lisa yang telah mandi dan berganti baju keluar kamar. Setibanya di ruang tamu, dirinya terkejut mendapati ibunya yang tengah bersandar di sofa seraya terpejam. Wajah ibunya juga tampak pucat.
“Mama, nggak apa-apa?” panggil Lisa sembari mendudukan diri di sebelah ibunya, lalu memijit-mijit lengan sang ibu.
Perlahan, mata ibunya terbuka. Senyum lemah terbit di wajahnya. “Mama nggak apa-apa. Cuma capek aja, terus ketiduran tunggu kamu mandi.” Wanita itu mencoba untuk menegakkan tubuh. Lisa dengan sigap membantu. “Yuk, makan. Nasinya sudah dingin, nih.”
“Ma.” Lisa menyentuh tangan ibunya yang tengah menyendokkan nasi untuknya. “Mama sudah cek gula atau tensi darah? Nanti sehabis makan kita ke klinik, ya. Lisa khawatir.”
Senyum kembali terbit di wajah ibunya. “Mama nggak apa-apa, Lisa. Cuma capek aja. Habis makan nanti tolong pijat punggung, leher, dan kepala mama, ya.”
Ada jeda sebentar sebelum Lisa menghela napas. “Ya, tapi Mama janji kalau ada apa-apa, kita bisa langsung ke klinik.”
“Janji.”
Keesokan paginya, Lisa bangun dengan malas. Semalam Rika membuat gaduh ruangan obrolan Whatsapp kelas perkara tugas yang diberikan guru seni budaya minggu kemarin. Sang guru mengharuskan siswa-siswi membawa alat musik untuk mengambil nilai praktik. Lisa niatnya menggunakan suling recorder yang dibelinya saat kelas lima SD. Akan tetapi, si Rika yang rese mendadak mencetuskan ide random: dia sesumbar bahwa dia akan memimjamkan gitar kakaknya dan berniat memamerkan kebolehan Lisa dalam bermain gitar.
Lisa awalnya tidak setuju dengan ide konyol itu. Namun, berkat desakan dari teman-teman sekelas beserta bujuk rayu manis Rika, Lisa pun setuju—meski terpaksa.
Sebelum pergi sekolah, Lisa sempat mengecek keadaan ibunya. Ia sedikit bernapas lega lantaran kondisi ibunya membaik setelah dipijat dan istirahat.
“Ma, nanti Lisa pulang telat lagi, ya,” katanya sambil mencium tangan sang ibu, lalu menyengir melihat pelototan ibunya. “Biasa. Ada tugas kelompok.”
Ibunya mengangguk dan mengelus kepala Lisa. “Belajar yang benar. Kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon mama atau Tirta.”
“Siap.”
-oOo-
Lisa tidak tahu, rasanya ingin sekali dia memusuhi Rika, tapi ia sadar kalau mereka bertengkar yang ada malah banyak ruginya. Rika itu sering mentraktir, meminjamkan buku, dan bahkan menalanginya uang kas kelas. Lagi pula, Rika mana tahu masalah yang menjadi latar keenggannya memainkan gitar lagi. Dari awal yang bermasalah kan dirinya. Buktinya, ayahnya pergi dari rumah.
“Nih, sebelum kelas mulai, bisa dong lo main.” Tanpa tedeng aling-aling Rika menyodorkan gitar akustik milik kakaknya pada Lisa. Seketika itu juga anak-anak sekelas mengerubungi Lisa seperti semut.
“Lisa, kenapa lo nggak bilang kalau lo jago main gitar?”
Perut Lisa melilit setelah mendengar celetukan dari ketua kelas barusan. Ia meringis. “Gue nggak jago, kok. Rika salah paham.”
Rika menggebuk bahunya dan berteriak dramatis. “Salah paham dari mana?! Gue lupa kemarin nggak sempat rekam video. Sekarang gue bakal rekam, kok. Jadi tenang aja.”
Lisa berdecak malas.
“Ayo, dong, Lisa. Main lagunya. Kita penasaran, nih. Kata Rika lo jago banget!”
“Iya, Lisa! Kita pengin dengar.”
“Lisa, ayo buruan.”
Lisa mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Paksaan dari teman-temannya makin menggila. Karena pusing serta malas mendebat mereka satu per satu, akhirnya Lisa mengambil gitar yang disodorkan Rika. “Janji dulu sama gue, pulang nanti lo kudu traktir gue gado-gado,” todongnya pada Rika.
Rika mengacungkan jempol dan tersenyum lebar. Saking lebanya, Lisa takut mulut temannya itu sobek.
“Mau main lagu apa?” tanya Rika dengan badan bergidik penuh antisipasi.
Sebelah alis Lisa terangkat sembari memainkan capo di tangannya. Ia berpikir keras. Yang terekam di kepalanya hanyalah lagu-lagu jadul. Ia juga jarang mendengarkan lagu kekinian.
Ah, ia ingat salah satu lagu yang jadi favoritnya Mas Andri. Lisa pernah sekali melihat video tutorial akustik lagu itu bersama Mas Andri sewaktu lelaki itu coba-coba belajar bagaimana caranya bermain gitar. Sayang, masa belajar Mas Andri hanya bertahan selama dua minggu. Katanya sih bosan, tapi Lisa tahu alasan sebenarnya lantaran dia kurang sabar dan salah memilih lagu. Sebagai pemula, Mas Andri seharusnya memilih lagu belajar dengan tempo lambat. Menurutnya lagu yang dipilihnya bertempo lumayan cepat. Mungkin mencapai seratus empat puluhan lebih ketuk per menit.
Ayahnya pernah bilang, semua orang bisa bermain musik, yang terpenting adalah sabar dan konsistensi. Eh. Kenapa dia jadi ingat orang itu? Bikin emosi, huh!
“Jadi, mau mainin lagu apa, Lis?” tanya Rika sekali lagi.
Lisa mengangkat bahu. “Coba tebak sendiri,” tandasnya sembari memasang capo di fret kedua. Kemudian ia menggenjreng acak kunci G, D, dan C. Ia sengaja melakukan itu guna menyamakan nada dan mencari ritme yang pas. Tak lama jemari tangan kirinya bermanuver ke fret ketujuh, lalu mulai memetik senar paling bawah. Melodi familier terdengar.
“Jet Lag! Ini intronya Jet Lag!”
Cengiran lebar terpasang di wajah Lisa. Ia pun melanjutkan ke verse 1 lagu.
Si ketua kelas yang hapal betul dengan lagu itu ikut bernyanyi, lantas disusul yang lain. Suasana kelas memanas ketika permainan Lisa masuk ke chorus pertama.
“Heart, heart, heart is so jet-lagged!” Mereka menyanyi kompak.
Lisa merasakan adrenalin mengalir deras dari sekujur tubuh, berlomba-lomba menuju ujung-ujung jari. Ia menggigit bibir. Rasanya seperti ada yang menggelitik perutnya, lalu meledak, menimbulkan friksi amat menyenangkan di dada. Lisa terengah sewaktu lagu memasuki akhir lagu.
Senyuman tak lepas di bibir setelah dirinya berhasil menyelesaikan Jet Lag.
Gemuruh tepuk tangan membahana ke seantero kelas. Di depan pintu ternyata ada beberapa anak kelas lain yang menonton. Guru seni budaya mereka pun rupanya sudah masuk kelas. “Lisa, jadi kamu sudah siap ambil nilai praktik musik, dong?” goda si guru.
Lisa meringis malu. Ia dengan cepat mengembalikan gitar milik kakak Rika ke dalam tas khususnya.
“Lisa.” Cewek yang duduk di depan Lisa menoleh ke belakang. “Gue jadi penasaran, selain gitar lo bisa main alat musik apa lagi?”
Lisa terdiam, sementara temannya yang tadi bertanya memutar tubuhnya menghadap papan tulis lagi karena teguran dari guru.
Alat musik lain?
Memori yang tersegel rapat di kepala Lisa seakan-akan berjejalan keluar, melayang, dan berebut untuk dimainkan kembali.
Sebelum tragedi kepergian ayahnya, Lisa mengenal lelaki itu sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Walaupun perbedaan usia dengan ibunya terpaut cukup jauh, sepuluh tahun, tapi itu sama sekali tak masalah. Ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap, pemasukan utama keluarga berasal dari gajinya sebagai guru musik lepas yang mengajar sesuai panggilan. Meski begitu, dulu, Lisa tak pernah merasa kekurangan.
Selain menjadi tenaga pengajar, terkadang ayahnya mendapatkan undangan manggung sebagai musisi kafe maupun pernikahan. Lelaki itu menguasai gitar elektrik maupun akustik, piano dan kibor, serta sedikit bass. Ayahnya juga terbiasa memainkan berbagai genre seperti pop, rock, jazz, hingga dangdut sehingga range lagu yang bisa dimainkannya bisa dibilang tak terbatas. Pada saat mengisi acara di kafe dan pernikahan Lisa akan selalu menemani, melihatnya dari kejauhan dengan mata berbinar, dan berharap suatu hari nanti ia juga akan seperti ayahnya yang menerima tepuk tangan meriah sehabis pertunjukan.
Di waktu senggang ayahnya pun sering mengajak Lisa mengunjungi toko alat musik milik temannya untuk mencoba berbagai instrumen di sana. Lisa jadi teringat, kala umurnya baru menginjak enam tahun lebih dua bulan, ia pernah memainkan Minuet in G Major menggunakan piano lama teman ayahnya itu tanpa membaca partitur. Ia melakukannya hanya berdasarkan ingatan di mana ayahnya pernah memainkan lagu itu beberapa minggu lalu di acara ulang tahun anak orang kaya.
Waktu itu ayahnya tertawa sembari menciumi sekujur wajahnya dan memuji bangga, “Anak ayah memang berbakat! Padahal Lisa belum bisa baca partitur, ya, kan?”
Lisa tertawa sinis. Kalau ditanya apakah ia masih ingat caranya bermain piano; jawabannya tidak sama sekali. Semua ilmu musik yang dia miliki lenyap entah ke mana.
“Lisa!” panggilan guru di depan mengagetkan Lisa.
“Ya, Bu?” balas Lisa grogi.
“Giliran kamu maju. Ibu sudah panggil kamu berkali-kali, tapi kamu malah ketawa aja.”
Lisa yang malu segera menyikut Rika karena tak memberitahunya hal tersebut. Huh, mengkhayal yang tidak perlu memang sering membuatnya hilang kesadaran sesaat.
Rika menyengir sembari menunjukkan pianikanya. Cewek itu juga tengah sibuk menghapal not lagu.
“Kamu mau main apa, Lisa? Main gitar kayak tadi?” tanya gurunya lagi.
Gelengan Lisa berikan. Ia dengan sedikit tidak percaya diri maju bersama suling recordernya. Rika dan teman-temannya yang melihat langsung mendesah kecewa. Padahal mereka ingin melihat lagi kebolehan Lisa menggenjreng gitar.
-oOo-
Lisa merasa nyawanya seperti menghilang setengah. Seluruh tenaganya tersedot habis di sekolah dan tempat kerjanya yang baru. Dengan gontai ia merebahkan diri di sofa ruang tengah. Ia melihat sekilas pada pesan yang dikirim ibunya sejam yang lalu. Ibunya berkata ia sedang berada di rumah tetangga untuk mebantu persiapan hajatan akikah yang bakal dilangsungkan besok pagi. Karena keesokan hari ibunya tidak mungkin datang ke pesta itu, jadinya sekarang saja sekalian menolong si pemilik acara.
“Paket!”
Lisa mengumpat karena sesi istirahatnya terganggu. Ia bangkit dari sofa dengan malas. Sambil menyeret langkah, ia berlalu menuju pintu. “Ya, kenapa, Bang?”
“Paket untuk Ibu Nina,” jawab si tukang paket sambil menunjukkan kardus yang dilapisi plastik hitam.
Sebelah alis Lisa terangkat. Tumben sekali ibunya memesan barang online. “Ya, betul, ini rumah Bu Nina. Saya anaknya,” tukasnya sembari mengambil paket yang dimaksud.
“Di foto dulu ya, Mbak.”
Setelah si tukang paket menyelesaikan tugasnya, Lisa bergegas masuk. Dahinya berkerut bingung lantaran ia sepertinya mengenali alamat si pengirim paket.
DAMSELS AND HONEY
Lisa nyaris membanting paket itu.
Besok, dia akan mengirim balik paket itu, kalau perlu sekalian dilempar ke mukanya Zidan. Biar dia tahu rasa. Masa bodoh jika awalnya paket ini ditujukan kepada ibunya, dia bisa beralibi kalau ia tak pernah menerima atau paket ini tak pernah sampai ke rumah mereka. Masalah selesai.


 anisha_dayu
anisha_dayu