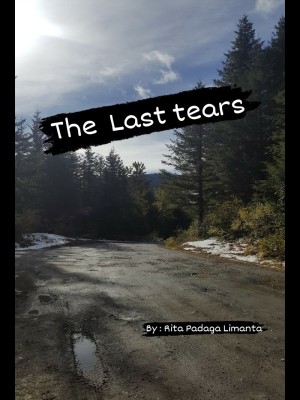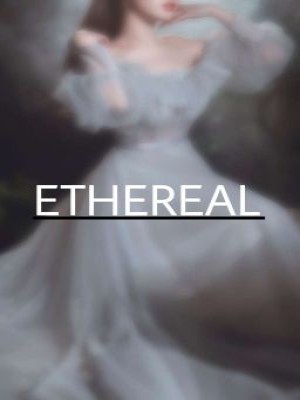Lisa pikir, hal yang pertama kali ia lihat setelah sadar adalah sosok dokter ganteng seperti di film-film, tapi nyatanya cuma langit-langit kamarnya yang dipenuhi noda bocor. Jadi, dia tidak dirawat di rumah sakit, nih? Padahal tadi ia sempat mengira kalau dirinya dirawat supaya ia punya alasan untuk tidak masuk sekolah. Secara, dia baru saja terjatuh dari lantai dua.
Gadis itu kemudian mengecek seluruh tubuhnya untuk mencari luka yang ia dapatkan. Untungnya, cuma ada satu memar biru sedang di siku, selebihnya ia sehat walafiat. Setelah anggota tubuh, pengecekan dilanjutkan ke bagian kepala—
“Aduh!” ringisnya saat tangannya sengaja menekan perban di pelipis kanan. Oh, mungkin ketika jatuh dari tangga tadi kepalanya terbentur lantai. Semoga saja lukanya ini tidak parah.
Akan tetapi, detik berikutnya ia tiba-tiba tertawa miris. Oke, kalaupun parah, ia berharap dirinya terkena amnesia supaya ia bisa melupakan kenangan buruk di masa lalu; mirip yang sering terjadi di sinetron-sinetron itu.
Karena bosan dan haus, Lisa memutuskan untuk keluar kamar. Pelan-pelan ia turun dari tempat tidur lalu berjalan menuju pintu. Di tengah perjalanan langkahnya mendadak terhenti saat suara nyanyian yang diiringi petikan gitar terdengar dari luar.
Ia terpaku. Suara itu ... ia kenal betul dengan pemilik suara itu!
Darahnya seketika mendidih. Ia membuka pintu kamar dengan beringas. Dunianya serasa runtuh ketika lelaki yang telah lama menghilang dari hidupnya menunjukkan batang hidungnya lagi. Lelaki itu tampak tak berubah. Senyum dan wajahnya masih sama seperti yang terakhir kali ia lihat tujuh tahun lalu.
“Hei, anak papa sudah bangun? Kemari, dong, papa kangen nih sama Lisa,” kata laki-laki itu sambil menepuk-nepuk sisi kosong di sebelahnya.
Lisa menggeram. “Pergi dari sini!”
Lelaki itu tersentak mendengar hardikan Lisa. Senyumnya mendadak hilang, tergantikan dengan raut muram. “Lisa,” panggilnya seraya beranjak mendekati sang anak.
“Jangan dekat-dekat!” Sambil tergopoh-gopoh Lisa menghindari lelaki itu lalu berlari menuju pintu depan. “Cepat pergi!” teriaknya seraya membuka pintu lebar-lebar.
“Lisa, kamu benci sama papa, Nak?” tanya si lelaki sambil berusaha meraih lengan Lisa. Namun sayang, Lisa langsung menepisnya kasar.
“Kenapa nanya? Nggak merasa sudah berbuat jahat? Sudah lupa, beegitu?”
“Lisa.”
“Diam! Sekarang lebih baik Papa pergi dari sini.” Lisa sudah bersiap untuk berteriak dan meminta tolong kepada tetangga jika dalam hitungan kelima lelaki itu tak keluar juga. Namun, mendadak gadis itu mengerang hebat sambil memegangi kepala.
Melihat anaknya nyaris roboh, lelaki itu buru-buru menangkapnya. “Elisa, kamu nggak apa-apa, Nak?”
“Jangan sentuh Lisa! Lisa nggak mau dipegang sama pembohong,” bentaknya sambil menyentak tangan sang ayah.
“Elisa, papa mohon, maafkan papa.”
Dengusan jijik Lisa terlontar. “Maaf? Papa nggak tahu kan selama ini mama sendirian banting tulang untuk membesarkan Lisa? Papa nggak tahu kan selama ini kita menderita? Tebak ini semua salah siapa? Salah Papa!”
“Ya, papa tahu papa emang salah. Tapi, waktu itu papa punya alasan kenapa papa harus meninggalkan kalian. Sekarang papa sudah pulang dan papa janji nggak akan ninggalin kamu dan mama lagi.”
“Bohong!” Lisa menjerit histeris. Air mata yang sedari tadi berusaha ia tahan pun tumpah ruah. “Papa ingat sudah berapa lama papa pergi? Lisa sama mama sudah bisa bertahan tanpa Papa, jangan buat luka yang sudah sembuh terbuka lagi.” Gadis itu perlahan merosot jatuh. Sakit yang datang bertubi-tubi di kepala dan juga hatinya benar-benar membuatnya tak berdaya.
Tak tega, sang ayah refleks memberikannya sebuah dekapan. Kali ini tak ada penolakan. Dengan tubuh lunglai Lisa membiarkan tubuhnya direngkuh erat. “Maafkan semua kesalahan papa, Nak. Papa janji papa akan menebus semuanya dosa papa pada kalian.”
Lisa tergugu. Di dalam pelukan hangat sang ayah, bahu sempitnya berguncang hebat. Segala umpatan dan cacian yang ingin ia muntahkan untuk lelaki itu mendadak tertahan di ujung lidah.
“Sudah dong, Lisa jangan nangis lagi. Papa jadi ikut sedih kalau lihat Lisa nangis,” ucapnya sambil mengelus-elus lembut kepala Lisa dan sesekali memainkan jepit rambut berbentuk tanda kunci trebel yang tersemat di rambutnya. Jepit rambut itu adalah hadiah ulang tahun Lisa yang kelima darinya.
Seperti sihir, usapan sayang di kepalanya mampu membuat tangisnya perlahan reda. Sang ayah tersenyum kecil dan mulai menyanyikan sebuah lagu. Ia kenal betul lagu itu. Lagu itu sering sang ayah nyanyikan sebagai pengantar tidur sewaktu ia kecil dulu.
Keheningan terjadi selama beberapa saat setelah sang ayah berhasil menyanyikan lagu itu secara utuh.
“Papa betulan nggak akan pergi lagi, kan? Papa nggak bakal ninggalin Lisa dan mama lagi, kan?” tanyanya sambil memegangi kaus sang ayah erat-erat. Sejujurnya, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, cintanya pada sang ayah masih lebih besar ketimbang rasa benci.
Ayahnya menggeleng pelan sambil menepuk-nepuk pelan bahunya. “Ya, papa bakal ada terus di sini sama Lisa dan mama.”
Napas Lisa tercekat ketika sebuah kecupan di kening ia dapatkan. “Janji?” tanyanya sambil mengusap jejak air mata di pipi.
“Janji.”
Lisa merasa ini adalah hal yang terindah di dalam hidupnya. Mengobrol dan dipeluk oleh sang ayah akan terasa lebih berharga dibandingkan ponsel layar sentuh paling mahal sedunia. Jika waktu berhenti saat itu juga, Lisa tidak akan menyesal karena ia akhirnya bisa merasakan lagi hal-hal yang sudah tak bisa ia rasakan selama tujuh tahun belakangan.
“Pa, Lisa ngantuk,” ucap Lisa sambil berusaha menahan kuap.
“Kalau ngantuk, ya, tidur.”
“Nggak mau. Nanti kalau Lisa tidur, Papa pergi lagi.”
Ayahnya tertawa kecil. “Nggak akan, kok,” ucapnya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur lagi.
Lisa mencoba untuk tetap terjaga meskipun matanya terasa berat. Sayang, nyanyian sang ayah selalu mampu membuatnya menyerah. Di antara ambang batas kesadaran, ia masih mampu mendengar nyanyian merdu sang ayah bercampur dengan suara berat yang memanggil-manggil namanya.
Dahi Lisa mengerut dalam. Suara itu terdengar sangat familiar.
“Lisa, bangun, dong!”
Tidak. Ia tidak mau bangun. Ayahnya pasti akan menghilang lagi kalau ia membuka mata. Biarkan ia menikmati belaian lembut dan nyanyian ayahnya. Biarkan dia begini selamanya.
“Lisa! Kamu kenapa nangis, sih?”
Lisa spontan terbangun akibat rasa sakit di pipinya. Dengan panik ia menatap sekitar; langit-langit kamar yang tinggi, gorden tebal, tiang infusan dan ... dan ... Mas Andri.
Mas Andri?
Kenapa Mas Andri yang ada di sisinya? Di mana ayahnya? Kenapa lelaki itu tidak ada? Seharusnya lelaki itu ada di sini menemaninya karena tadi dia sudah berjanji.
“Hei, jangan bikin takut orang, deh!”
Lisa menatap wajah Mas Andri kalut. “Mas Andri, papa ke mana?” racaunya sambil berusaha untuk bangkit dari rebah. Beruntung, Mas Andri buru-buru mencegah sebelum gadis itu benar-benar turun dan terjatuh dari tempat tidur.
“Eh, bandel amat, sih, kamu. Kamu mau apa memangnya?”
“Aku mau cari papa soalnya tadi dia ada di sini!”
Mas Andri berdecak jengkel. “Papa yang mana, sih? Dari tadi cuma ada saya di sini jaga kamu.”
Wajah Lisa mendadak pias. Jadi, semua itu cuma mimpi? “Se-sekarang kita ada di mana, Mas?” tanyanya dengan suara bergetar.
“Kita lagi di rumah sakit. Memangnya kamu nggak ingat kalau kamu habis jatuh dari tangga, hah? Thanks, God, pestanya sudah mau selesai. Kalau nggak, pasti gagal acara orang. Lagian, tadi kamu mimpi apaan sih sambil nangis kejer begitu? Saya jadi takut tahu,” cerocos seniornya itu tanpa jeda.
Lisa buru-buru menyeka jejak air mata di wajahnya. “Aku nggak mimpi apa-apa, Mas, tenang aja.”
“Jangan bohong, deh.” Mas Andri melotot galak.
“Beneraaan.”
“Oke, lah. Karena kamu sudah bangun, saya kabarin mama kamu dulu.”
“Hah, mama di sini?”
“Iya, lah! Si bos sendiri yang tadi jemput mama kamu,” kata Mas Andri tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya.
“Terus sekarang mama di mana?” tanyanya sambil memandang sekeliling.
“Mamamu lagi tebus obat,” jawab lelaki itu sambil menyimpan kembali ponselnya. “Oh, ya, kamu nggak ngerasa pusing, mual, atau apa, kan?”
Lisa terdiam sambil mencoba merasakan gejala-gejala yang diucapkan Mas Andri, lalu menggeleng pelan.
“Oke, jadi saya nggak usah panggil dokter. Nanti aja kali ya pas mama kamu balik. Ya sudah, saya mau ke toilet dulu,” ucap Mas Andri yang hendak pergi. Namun, baru saja tangannya menyentuh gorden pemisah ruang pemeriksaan, ia tiba-tiba berbalik. “Awas, jangan ke mana-mana. Nanti kalau kenapa-kenapa, saya yang bakal susah.”
“Iyaaa,” balas gadis itu sambil mendengkus pelan. Huh, memangnya dia bocah?
Sepeninggal Mas Andri, Lisa mendadak merasa bosan karena tak ada pemandangan asyik yang bisa dilihat. Omong-omong, karena tadi dia tak sempat mengecek kondisi tubuh, dia jadi penasaran luka apa yang didapatnya setelah jatuh dari tangga tadi.
Setelah beberapa saat mengecek, untungnya ia tak menemukan luka apapun. Kaki maupun tangannya juga tak ada yang terkilir. Ya, paling cuama memar biru yang bakal hilang dua hari kemudian. Akan tetapi, begitu ia memeriksa kepalanya, ia merasakan permukaan kasar perban bagian pelipis kanannya. Ia tersentak. Kejadian seperti ini mirip dengan mimpinya tadi. Mendadak rasa marah, kesal, dan benci menyeruak. Ingin sekali ia berteriak untuk melegakan dadanya yang sesak, tapi dia lagi di rumah sakit. Bisa-bisa dimarahi suster nanti.
“Kenapa Tante dateng ke sini?”
Lisa terperanjat saat suara bariton lelaki terdengar dari sebelah. Nada bicaranya dingin dan galak sekali. Ia jadi membayangkan muka si pemilik suara itu. Pasti wujudnya tak jauh dari cowok badboy berkepribadian dingin, persis seperti karakter novel yang sering dibaca Rika, teman semejanya.
“Tante khawatir sama kamu, Dan.”
Kali ini yang terdengar adalah suara lembut wanita. Lisa bisa menebak kalau si pemilik suara ini adalah wanita dewasa anggun yang sering nongkrong cantik di kafe-kafe kekinian.
“Oh, bagus, deh. Ternyata Tante masih ada rasa khawatir. Gue kira Tante sudah nggak punya hati.”
Kasar banget! Lisa menggerutu. Cowok itu mengobrol dengan tantenya, lho. Kurang ajar betul.
“Kamu kenapa bisa kecelakaan begini, Dan? Makanya, hati-hati kalau bawa motor.”
“Tenang aja, pernikahan Tante sama papa nggak bakal batal cuma gara-gara Zidan kecelakaan. Bahkan kalau Zidan mati pun pernikahannya pasti bakal jalan terus.”
Dahi Lisa mengerut dalam. Oke, percakapan mereka benar-benar sudah di luar jalur.
“Astaga, Zidan! Jangan ngomong begitu.”
“Kenapa? Nggak suka? Kalau Tante nggak suka dengernya, pergi aja sana. Zidan juga nggak butuh dikasihani sama perempuan pelakor macam Tante.”
Setelah medengar kalimat terakhir dari cowok bernama Zidan itu, Lisa langsung menggulingkan tubuhnya ke arah lain dan pura-pura tidur. Bisa gawat kalau dirinya ketahuan menguping.
Eh, tapi ... tunggu sebentar. Kalau dipikir-pikir ini bukan murni kesalahannya, dong! Secara, sekat yang membatasi mereka cuma selembar gorden, jadi wajar saja kalau percakapan mereka terdengar olehnya.
Lisa pun kembali menelentangkan tubuhnya lalu menghela napas panjang. Well, semua orang ternyata punya masalah masing-masing dengan orang tua mereka. Ah, ia jadi merasa simpati dengan cowok di sebelah. Dirinya mungkin tidak tahu masalah apa yang terjadi di antara cowok itu dan ayahnya, tapi ia bisa sedikit mengerti apa yang si cowok rasakan.
Ah, tidak. Tidak. Orang itu sudah bukan lagi menjadi bagian dari hidupnya. Dia harus melupakan sosok lelaki itu. Anggap saja dia sudah mati.
Beberapa detik berikutnya, keheningan menyelimuti. Sepertinya si 'calon' ibu tiri sudah pergi karena sudah tak terdengar lagi percakapan dari mereka. Karena bingung dengan suasana yang tiba-tiba senyap, Lisa pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar UGD sebentar. Masa bodoh kalau nanti Mas Andri memergoki lalu memarahinya. Toh, kondisinya sehat walafiat.
Baru saja kakinya turun dari tempat tidur, suara isakan tiba-tiba terdengar dari sebelah. Lisa refleks menoleh dan—entah disengaja atau tidak—gorden yang membatasi mereka sedikit tersingkap karena pergerakan brankar yang ditiduri cowok itu.
Dari tempatnya duduk, Lisa melihat cowok itu mencoba sekuat tenaga menahan tangis, meski sejujurnya hal itu sia-sia belaka. Entah dorongan dari mana Lisa akhirnya beranjak dari brankarnya lalu mendekat. Sebelah tangannya terjulur untuk menyingkap gorden pembatas. Di saat yang sama, si cowok yang menyadari keberadaan Lisa menoleh.
“So-sorry.” Lisa tergagap. Ia pun spontan berlari keluar untuk menghindari tatapan nyalang yang dihadiahkan pemuda itu kepadanya. Sayangnya, baru saja dirinya sampai di depan pintu, seorang pemuda jangkungtiba-tiba saja menghadang langkahnya.
Lisa mematung di tempat. “Kak Tirta?”


 anisha_dayu
anisha_dayu