Keesokan hari dan seterusnya, setiap pagi aku mulai kebiasaan baru, tetap berangkat keluar rumah, mandi dengan air dingin, memberi makan ayam, dan menebeng motor Nurdin.
Namun, kali ini tujuannya bukan lagi perempatan dekat Berdikari, melainkan halte bus angkutan umum.
Aku sedikit rindu dengan toko yang harus selalu rapi itu, pagi, siang, sore, dan beberapa malamku dahulu tak lepas dari sana.
Aku pergi ke mana saja yang aku bisa, mengunjungi rumah teman-teman SMP dahulu, mengantar Ibu membeli bibit, membantu Nurdin di tempat kerjanya, mungkin lebih tepatnya merepotkan, aku belum pernah punya pengalaman memotong dan menguliti hewan, apalagi menggilingnya.
Hal lain yang membuatku tidak mau melakukannya lagi adalah bau apek dari daging hewan potong yang macet di baju bahkan setelah dicuci berkali-kali.
Sejak saat itu aku mulai menjauhkan diri dari maniak daging kambing, ada rasa pusing dan perut yang seperti di-unyel-unyel ketika mencium baunya.
Sebelum sibuk berangkat mencari kesibukan, aku mengantar Laila ke rumah sakit tempatnya bekerja. Hanya mengantar, ia tak mau aku ikut dia bekerja.
Pernah sekali aku membantunya, bukannya terima kasih ia malah mengomeliku habis-habisan.
Seisi kantor jadi tahu cerita tentang Nurdin yang naksir berat padanya karena mulutku, tak sengaja aku menodongnya dengan ejekan Bebeb Nurdin karena ia tak mau memberitahuku cara membaca resep tulisan dokter.
Aku juga kerap menawarkan diri untuk mengantar pesanan jahitan yang sudah jadi ke pelanggan Bu Widi.
Warung dan rumah itu kini tak sama lagi semenjak Zahwa pergi. Taman dan pekarangannya memang hijau, tapi aku tidak melihat ada satu bunga pun yang mekar.
Di lain kesempatan aku suka membantu Ibu dan Paman di ladang jika sedang ada pekerjaan.
Apa pun kulakukan agar aku terus sibuk dan tidak merasa sendirian. Menganggur adalah sumbu yang mengerikan bagi orang yang tengah patah hati.
Ia bisa merangsang pikiran dan perasaan buruk untuk datang, dan aku tak mau itu terjadi.
Kini aku juga sedang menjalani kesibukan baruku setiap jumat dan sabtu, yaitu menjaga toko baju milik kerabatnya Pak Leo yang tinggal di Primavera, sebuah perumahan kelas atas di kawasan kota kabupaten.
Mengapa hanya jumat dan sabtu? Karena karyawannya yang telah bekerja di situ bertahun-tahun sedang punya anak balita yang tidak bisa ditinggal, daripada resign, ia lebih memilih untuk membagi hari denganku.
Mulai kuceritakan pada Ibu tentang ke mana sebenarnya aku pergi akhir-akhir ini.
Ibu tidak pernah menaruh curiga padaku, aku tak pernah macam-macam.
Kata orang, sebagai bujang hidupku lempeng-lempeng saja, tapi siapa peduli, yang lempeng begini saja masalah tidak ada selesainya, apalagi yang nyeleweng dan aneh-aneh.
“Lain kali, kalau kamu mau berkunjung ke rumah Pak Bah lagi, bawalah sesuatu agar tanganmu tak kosong melompong.”
“Bawa apa Bu?” Terus terang, bukannya aku tidak mau, hanya saja bingung dengan benda macam apa yang bisa kubawa karena Pak Bah adalah orang yang berkecukupan.
“Sayur atau buah dari ladang, mungkin.”
“Bu, Pak Bah itu sepuh yang tinggal sendiri. Beliau sungkan untuk masak atau sekadar menghangatkan air di kompor dapur.”
“Oh, kalau begitu, bawa saja masakan Ibu.”
Aku menimbang-nimbang sejenak. “Bisa, tapi ia bukan orang asli Jawa, bisa jadi selera lidahnya berbeda. Pak Bah suka memanggilku dengan sebutan kau, rasanya agak sedikit asing di telingaku.”
Sebuah rasa syukur yang melimpah karena pegunungan ini tak pernah libur dengan air meskipun kemarau tengah menyiksa daratan di kota-kota sana.
Sungai kecil belakang rumah masih tetap mengalir meski tak sederas bulan-bulan di musim hujan.
Di tanganku sudah ada dua rantang makanan yang harus kuantar. Satu ke rumah Bu Widi dan satunya akan kubawa ke rumah Pak Bah.
Bu Widi tengah memotong kain panjang berwarna candramawa. Sepertinya ia tengah sibuk.
Dilan sepertinya sedang tidak ada di rumah, kuperhatikan motor Zahwa tak ada, mungkin sedang dibawa oleh Dilan.
Yang menyambutku di ambang pintu adalah Pak Akbar. “Waalaikumsalam, Nadif.”
Aku berusaha bersikap sesopan mungkin padanya. Aku hendak bertanya mengapa Pak Akbar tidak berangkat kerja.
Tapi sebelum itu terjadi, ia sudah lebih dahulu menjelaskan.
“Beruntung sekali kami punya tetangga sepertimu, Dif. Aku sedang kurang sehat, Dilan sibuk dengan pekerjaan barunya, dan bisa kamu lihat sendiri, Ibu banyak pesanan. Punjungan yang seperti ini menyenangkan sekali,” ucapnya sambil tertawa dan mengelus kumisnya yang lebat.
“Ah, tidak begitu. Kami juga beruntung punya tetangga seperti keluarga ini, Pak.” Dan aku dipersilakan masuk.
Dengan langkahnya yang pelan, Bu Widi menghampiriku dan mengucapkan terima kasih atas kirimannya. “Salam buat ibumu ya,” tambahnya.
Sebelum aku meninggalkan rumah itu, Bu Widi juga berpesan, “Semalam Zahwa menelepon ke rumah, katanya ibu suruh bilang padamu terima kasih atas suratnya. Zahwa sudah baca dan menyukainya.”
Demi mendengar hal itu, perasaanku mengembang bukan main, hampir saja jantung naik ke kerongkongan.
Ini berita paling segar yang aku terima setelah berminggu-minggu. Hawa sejuk kembali masuk dalam sukmaku dan menyapa sel-selnya yang sempat kering.
“Zahwa juga memintamu agar jangan berganti nomor hp dulu, ia akan menghubungimu setelah punya simcard sendiri yang resmi di Jepang. Anak itu memang neko-neko sekali,” kata Bu Widi sambil tersenyum.
Senyumku pun sama mengembangnya, atau mungkin lebih lebar. Senyum itu bertahan di wajahku setelah 10 meter kakiku meninggalkan halaman rumah keluarga Zahwa.


 littlemagic
littlemagic










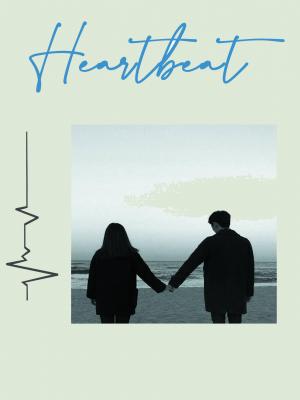

I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog