Kutanya pada diriku sendiri, esok Zahwa akan pergi.
“Apa aku rela?” Jika tidak, apa alasannya?
Namun jika benar aku rela, maka perasaan sesak ini namanya apa?
Harusnya pepatah lama itu benar, kita harus ikut senang melihat orang lain senang. Tapi pada kasus ini, aku tidak melihat Zahwa senang sedikit pun.
Derai air mata keluar dari sumbernya tidak sedikit, entah apa yang ada di pikirannya waktu itu.
Apa dia keberatan meninggalkanku? Tapi seharusnya tidak! Meskipun, dari hati yang terdalam, aku sungguh tak mau ditinggalkan olehnya.
Semalaman penuh aku tidak tidur, angin kemarau bertiup kencang saat rembulan tengah bersinar cerah cemerlang, sepertinya Agustus ingin menunjukkan jati diri yang sesungguhnya pada penduduk bumi.
Kuputuskan untuk mengambil selembar kertas dengan bolpoin tinta biru yang ada pada sling bag hitam andalanku.
“Silakan, untuk kau menghadap langit,
Menabur bintang di angkasa,
Menyemai harapan tinggi-tinggi,
Jika suatu saat kau tiba pada masa di mana lehermu lelah mendongak, jantungmu lemah berdegup, kakimu butuh singgah untuk memperingan langkah. . .
Kemari, temui aku,
Di tempat apa pun di mana kita bisa bertemu,
Kita akan bicara,
Tentang apa saja,
Mungkin tentang anak kucing, atau tentang martabak manis, atau bisa saja tentang buku sobek di perpustakaan.”
Paginya, selembar kertas itu aku selipkan diam-diam di sela-sela koper milik Zahwa yang kujaga baik-baik.
Dan kini, di sinilah aku. Menyapa pagi dengan sebenar-benarnya kenyataan.
Aku mencoba memakai baju terbaik, bukan jaket adidas yang jarang kucuci.
Memakai jam tangan, sepatu santai, dan juga wewangian. Tentu tidak otomatis mengubahku menjadi ganteng, mukaku tetap sama saja.
Tapi setidaknya aku terlihat rapi.
Sempat berpikir ingin membawa tisu, tidak ada jaminan untukku tidak menangis nantinya.
Tapi urung, segera kuingat pesan Ibu semenjak aku kecil, bahwa laki-laki tidak boleh menangis.
Walau aku tahu, itu bohong sekali. Menangis adalah hak segala bangsa.


 littlemagic
littlemagic








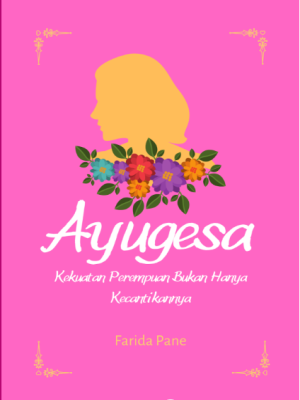



I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog