Aku bermimpi mengendarai selembar daun dan berusaha terbang mengimbangi cahaya. Aku tidak sendirian, entah bersama siapa. Cahaya itu melesat sangat jauh dan mengalun dengan tenangnya.
Saat itu aku yakin tengah di udara tapi kulihat beberapa ekor Arwana berenang di atas kepalaku dengan bebasnya. Entah benar berenang atau mungkin terbang.
Aku kembali bangun kesiangan. Ini hari kesekian di mana kokok ayam dan alarm Ibu tak ampuh membangunkanku.
Nurdin sudah berangkat saat aku tengah bersiap-siap, tak ingin membuatnya menunggu, kupersilakan ia berangkat duluan. Aku bisa berangkat dengan meminjam motor milik Laila.
Tak seperti biasanya, sampai jam sembilan toko masih sepi. Hanya ada beberapa pembeli yang sanggup diatasi oleh Yayuk sendiri.
Sementara aku hanya bengong dan menyeruput secangkir kopi yang kemanisan. Kopi ini Laras yang buatkan, dia tetanggaku juga, rumahnya berjarak tiga gang dari jembatan.
Ini hari pertamanya bekerja, dan kopi buatannya bukan dalam rangka perpeloncoan karyawan baru atau semacamnya, memang dia sendiri yang ingin.
Dalam keheningan, ponselku bergetar dan muncul sebuah pesan.
“Bang, doakan Zahwa ya. Hari ini pengumunan seleksi masuk PTN yang kemarin aku daftar.”
Aku terlonjak bukan main, belum ada sejarahnya Zahwa berbicara lewat telepon ataupun SMS padaku.
Bagai dikunjungi komet yang hanya hadir 70 tahun sekali, momen ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Aku berniat membalas, “Abang selalu mendo’akanmu tanpa kamu minta, Wa.” Namun urung, terlalu alay.
Aku hapus kembali. Kuganti dengan, “Siap, sudah aku do’akan. Tapi sebenarnya aku mendo’akanmu tidak kali ini saja. Sudah sejak dulu di setiap sholatku. Abang berharap Zahwa selalu sehat, lengkap, bahagia dan senantiasa tercukupi. Abang juga...” Yang ini juga urung aku kirim, terlalu panjang.
Setelah berkali-kali mengetik dan menghapus akhirnya kukirim pesan, “Semoga sukses, Wa. Abang berharap yang terbaik.”
“Alamak, kenapa lama sekali tidak terkirim,” ucapku pada diri sendiri.
Bukannya balasan dari Zahwa, pesan yang masuk malah dari operator yang memberitahu jika pulsaku tidak cukup untuk mengirim pesan. Aku menepuk jidat, lupa kapan terakhir kali membeli pulsa.
Tidak menunggu lama, aku langsung lari ke konter HP sebelah, minta cepat-cepat dikirim pulsa oleh operatornya. Tak seperti biasanya, aku jadi lebih sering mengecek ponsel karena kejadian ini.
Namun, sesering apa pun aku cek, ketika Zahwa belum membalas, ya tetap saja tidak ada pesan masuk. Aku merasa bodoh dengan hal ini.
Toko yang tak seramai biasanya membuatku jadi tidak ada kerjaan dan mengalihkan kesibukanku pada benda kecil sumber overthinking, yaitu handphone.
Pesanku sudah terkirim, tapi kenapa belum dibalas? Apa ada yang salah dari tulisanku? Atau Zahwa memang sedang tidak memegang ponsel?
Tapi bukankah ponsel selalu ada di genggamannya setiap saat, tidak mungkin ia tidak kenapa-kenapa tapi tidak membalas pesanku.
Astaghfirullah apa pesanku menyinggung perasaannya? Aku buka room chat-ku dengan Zahwa berkali-kali.
Kuterawang, tidak ada yang salah dari ucapanku. Zahwa juga bukan tipe orang yang mudah tersinggung. Atau pesanku terlalu singkat jadi dianggap jutek?
Ah tapi apa betul. Zahwa tidak akan mengira aku jutek, tapi bisa saja.
Aku terus menduga-duga alasan mengapa balasan Zahwa tidak juga muncul. Pikiranku sampai pada dugaan jangan-jangan Zahwa sedang sibuk membalas pesan laki-laki lain?
Aku memukul kepalaku sendiri, aku tidak boleh berpikiran begitu. Lagi pula, bukankah tidak apa-apa jika Zahwa sedang berbalas pesan dengan seseorang?
Ah! Aku menyerah dengan pikiran sendiri. Kuletakkan ponsel dan kuajak orang di sekitar bicara, agar aku lupa tentang perkara pesan singkat ini.
Tidak berselang lama, setelah melayani dua pembeli, ponselku bergetar dan layarnya menyala. Satu pesan masuk. Tentu saja dari Zahwa.
Segera kusambar ponsel kentang yang tak luput dari pandanganku. Alangkah bahagianya aku mendapat balasan ini.
“Amiin, terima kasih bang.” Katanya di ujung ponsel.
Ingin aku berjingkrak-jingkrak mendapati pesan yang ramah itu. Zahwa tidak marah dan menganggapku jutek.
Dari mana aku tahu? Dari huruf i yang dobel di kata amin.
Mungkin terdengar tidak logis, tapi banyak juga orang sepertiku. Teliti sekali memperhatikan kata per kata hingga ke huruf-hurufnya.
Berasumsi ini itu padahal belum tentu benar.
Tidak berselang satu menit aku sudah membalas pesannya, tapi hal yang sama terjadi kembali. Balasannya tak kunjung aku dapatkan.
Supaya pikiranku tidak terfokus pada ponsel, aku meminta diri melayani pelanggan di bagian depan dan Yayuk merapikan beberapa kertas dan rentalan di belakang.
Bertemu banyak orang membuatku sedikit lupa dengan kesibukan pikiranku sejenak. Semakin siang, toko semakin ramai.
Bermacam-macam pembeli aku temui, ada yang datang beramai-ramai dari desa, memakai pakaian terbaik yang mereka miliki, kemudian bibirnya berdecak diikuti kepalanya yang bergeleng-geleng melihat harga penghapus yang berjajar terpampang di etalase.
“Mahal sekali harga penghapus ini, bisa untuk beli beras satu kilo,” bisiknya pada orang di sebelah, sepertinya mereka masih saudara.
“Coba ditawar, kalo tidak boleh, suruh genduk-mu menghapus pakai karet saja.”
Aku hendak tertawa, tapi segera kudatangi mereka dan bertanya seperti pelayan toko pada umumnya. “Cari apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu?”


 littlemagic
littlemagic



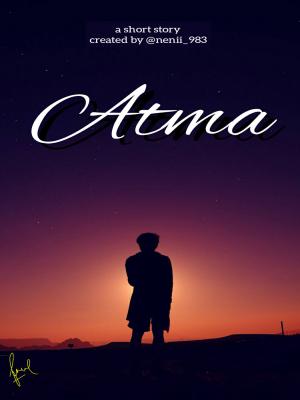








I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog