“Bang Nadif,” panggilnya dari ruang tamu.
Aku sengaja lewat pintu belakang karena kukira di ruang tamu ada teman Laila yang sedang mampir.
“Ternyata Zahwa, kukira tamu penting,” Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal, “Sudah lama?”
“Lumayan. Bang Nadif lama sekali pulangnya. Bukankah biasanya jam lima sudah di rumah? Tapi ini sudah hampir magrib.” Sejak Zahwa ujian SMA, ia jadi jarang datang ke rumah.
Biasanya seminggu sekali kemari, entah disuruh mengantar masakan atau sekadar main-main saja. Setahuku ia sibuk belajar untuk bisa masuk ke universitas impiannya yang ada di Jakarta.
Aku pun sibuk bekerja, kadang juga lembur hingga malam. Tak jarang Zahwa berkunjung dan aku tidak di rumah. Momen bertemu Zahwa seperti ini sangat aku nantikan.
“Aku diajak Nurdin mampir ke warung ronde, di sana agak antre jadi pulangnya terlambat. Aku tak tau kau Zahwa mampir ke rumah. Ada keperluan apa?”
“Aku sedang tanya-tanya ke Mba Lail tentang materi untuk persiapan test TPA-ku besok. Aku lolos seleksi berkas, Bang.”
Meskipun sedikit kecewa karena ia datang bukan untuk menemuiku, namun mendengar berita baik yang membuatnya senang aku jadi ikut senang, “Wah selamat ya, sudah lolos berkas, masih ada tesnya lagi?”
“Masih, Bang. Ada tes tertulis dan wawancara. Doakan Zahwa ya, Bang.”
“Pasti, selalu, Wa.”
Kutinggalkan Zahwa yang masih asyik mengobrol di ruang tamu dengan Laila. Aku harus bersih-bersih diri sebelum hari semakin larut dan udara semakin dingin.
Aku suka dimarahi Ibu jika mandi terlalu malam, katanya tidak baik buat kesehatan, bisa rematik.
Entah benar atau tidak tapi aku turuti saja, lagi pula mandi malam memang tidak enak, bisa beku tulang-tulangku karena dingin.
Untuk bulan-bulan kemarau ini suhu di kawasan Nara bisa mencapai tujuh derajat celsius di pagi dan dini hari.
Selesai aku mandi, Zahwa pamit pulang. Kuberikan wedang ronde yang tadi kubeli untuk Ibu. Kata Ibu tidak apa, mumpung Zahwa sedang kemari.
Setelah aku amati, ada yang berbeda darinya, ia kini berdandan. Bibirnya merah muda dan bulu matanya lebih lentik dari biasanya.
Sejujurnya aku lebih suka dia yang polos saja, tapi apa pun yang ia kenakan terasa nyaman untuk penglihatanku.
“Tadi dia menanyakan aku atau tidak, Lil?” tanyaku pada Laila.
“PD sekali, pasti tidak lah,” jawabnya sewot.
Kurang yakin, aku beralih bertanya ibu, “Zahwa tidak menanyakan aku, Bu?”
Ibu sedang mengulek bumbu dapur tidak memperhatikan. Bunyi gemeletuk dari ulekan sengaja betul Ibu gunakan supaya tidak hirau dengan pertanyaanku.
“Bu…”
“Zahwa tadi menanyakanmu, tapi kamunya lama sekali tidak pulang-pulang. Begitu pulang malah kamu tinggal mandi.”
“Aku tidak enak menemuinya dengan badan bau keringat, aku selesai malah dia yang pulang.” Aku mengeluh dan sedikit ingin menyalahkan Nurdin, tapi tidak bisa karena aku juga mengiyakan ajakannya tadi. “Zahwa bertanya apa?”
“Waktu sama ibu, Zahwa bertanya apakah kamu jadi ambil kuliah atau tidak, masih ingin atau tidak. Begitu-begitu, tapi ya ibu jawab ibu tidak tahu.”
“Kenapa Ibu jawab tidak tahu, Bu. Ibu harusnya bisa jawab lain seperti, Nadif ada kemauan tapi masih cari-cari rezeki dulu. Atau jawaban yang mirip-mirip tapi lebih panjang. Atau lagi, Ibu bisa tambahi seperti Nadif sedang kerja untuk mengumpulkan uang. Kenapa Ibu malah jawabnya tidak tahu.”
“Ibu jawab tidak tahu, karena waktu itu ibu tidak tahu. Daripada ibu mengarang, nanti malah terdengar aneh.”
Aku mengeluh mengusap wajah sendiri.
Diam-diam aku mendekatkan posisi dudukku ke samping Ibu, “Bu sejak kapan Zahwa berdandan?”
“Mana ibu tahu, Nang. Ibu bukan orang yang suka memperhatikan orang lain secara berlebihan.”
“Tapi aku baru melihatnya, kira-kira apa penyebabnya, Bu?”
“Ibu tidak tahu, Nang.”
“Ibu, kenapa Ibu jadi serba tidak tahu begitu..”
“Nang, ibu sedang mengulek kunyit, kalau kamu tanya terus bisa-bisa ulekan ibu nyasar ke kamu.”
Aku menyingkir dari sebelah Ibu. Berpindah ke depan tv, di sana Laila sedang mencorat-coret buku panjang yang entah apa isinya.
Aku tak terlalu paham pekerjaan perawat, meskipun Laila senang sekali sambat padaku tentang pekerjaannya yang melelahkan itu, aku tetap saja tidak relate dengannya.
“Lil, kapan pertama kali kamu dandan?”
Laila merasa aneh dengan pertanyaanku, “Mungkin SMA.”
Aku mengangguk, jawabannya sangat awam, tidak mengindentifikasikan atau menandakan apa pun.
“Kau mau membahas si Zahwa yang tadi pakai lipstik dan maskara?”
“Apa itu maskara?”
Laila menghembuskan napas, begitu saja tidak tahu. “Alat yang dipakai buat melentikkan bulu mata.”
Aku tetap tidak paham.
“Sudah, kamu tidak usah repot berpikir yang tidak-tidak. Zahwa dandan begitu bukan buat kamu. Ia kan sebentar lagi jadi mahasiswi, ia harus mulai belajar merias diri. Lagi pula dia akan pergi jauh, ketemu orang baru, teman baru, atau pacar baru. Haha.” Laila mulai meledekku.
Kata-kata Laila terdengar logis, walaupun aku punya pembelaan, jika Zahwa belajar dandan untuk kuliahnya nanti, kenapa ia dandannya sekarang? Kenapa saat ke rumahku? Kenapa kemarin-kemarin tidak?
Tapi segera aku tutup pertanyaanku sendiri, benar kata Laila, aku tidak perlu repot berpikir yang tidak-tidak.


 littlemagic
littlemagic


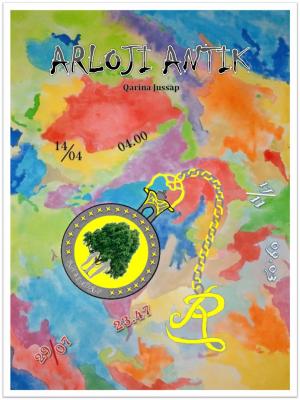









I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog