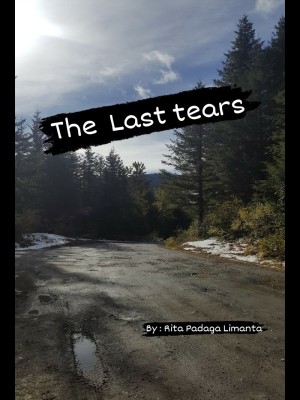Bohlam lampu usang yang berada di atas raga Varen berkedip kedua kalinya; mengalihkan atensinya meski sejenak. Jam dinding kuno yang tergantung di dinding telah menunjukkan pukul sembilan malam. Di sana, Varen masih menyesap kopi panas yang iseng dia pesan kala terduduk di sebuah cafe—tempat yang ia asal pilih untuk bertemu empat mata dengan wanodya nan terus mengaku bahwa sibuk sepanjang waktu.
Sesosok gadis muncul dari balik mobil, berlari dengan langkah mungil bersama lengan yang menenteng tas mahalnya. Ia tampak sangat mencolok meski langit sudah menggelap dan tersinar samar oleh rembulan.
Gadis yang sama membuka pintu cafe dengan feminim, mengerising tipis tatkala langsung menemukan Varen yang menatapnya tajam. Tanpa berlama-lama, ia mengegah elok ke meja persegi bernomor 03. Meja Varen.
Sepanjang langkahnya, Varen terus menentangnya dengan tatapan menusuk. Namun berhubung Iris sudah gila, ia terus mengembangkan kerising. Terduduk di meja yang sama dengan seringai yang kian melebar.
“Gilaaa ... gue berhasil bikin tiga orang sekaligus—yang lagi jadi buah bibir sekolah hubungin gue dengan mudahnya. Nggak sia-sia emang,” celetuknya menyombongkan diri. Berlagak terkejut.
Varen tersenyum sekejap, tetapi bibirnya mengucapkan dengan santai, “Lo tuh ibarat upil tahu, nggak?”
Ain Iris membelalang bersamaan dengan mulutnya yang terbuka lebar. Tangan kanannya memegang erat dadanya, terlonjak akibat makian itu yang jadi sapaan Varen pertama kalinya.
“Lo sampah!”
“Bentar, deh! Lo bisa jelasin makna 'upil' tadi?”
Varen tersenyum miring, memulai aksinya. “Tapi lo jangan berharap banyak sama apa yang bakal gue bilang nanti. Gue Varen, cowok gila bukan cowok savage.”
“Terserah!” ketusnya, mendesak untuk mengetahui makna upil tadi.
“Lo tuh ibarat seonggok upil. Iya gue tahu, awalnya lo dicari-cari. Butuh sedikit tenaga untuk dapetin lo. Tapi, lo dicari untuk dibuang.”
“Maksud lo?!” pekik Iris tak terima.
“Gue tahu, pada akhirnya lo bakal terbuang dan segala effort lo itu jadi percuma.” Varen terus melebarkan senyumnya. Kian lebar senyum itu, napas Iris semakin tak beraturan. Dadanya bergemuruh akibat ingin menampar laki-laki gila tersebut.
“Apa yang lo tahu tentang gue?!” Iris sedikit menaikkan tubuhnya dari kursi. Ingin rasanya telempap kanan itu menampar pipi Varen sekuat tenaga. Kalau saja wajah Varen tidak sesempurna itu, sudah dipastikan ia benar-benar melakukannya.
“Lo Iris Notabayu. Anak XI IPS 03. Punya banyak rencana buat hancurin Lana, atau Irena. Right?”
“Kok lo—“
“I'm a nut boy. Remember?” Iris mendengkus kasar, kembali menghempaskan tubuhnya ke kursi. "Kalau spekulasi gila gue bener, berarti lo sama gilanya dong?"
"Tapi gue gak gila!"
“Dan lo akui fakta tadi?” Varen tertawa renyah. Justru tanpa sadar Iris mengakuinya seorang diri.
“Bacot. Ngaku aja, info yang lo tahu gak cuma itu, ‘kan? Lo mesti dapetin semua info dari Septhian gila itu! Kalian berdua cocok jadi sobat sakit jiwa!” maki Iris naik pitam.
“Ckck, heran gue. Kenapa di dunia ini kalau orang kelewat pinter justru dibilang gila?”
“Berisik! Udah buruan lo bilang buat apa lo tahan gue di sini!”
Varen menyandarkan keseluruhan punggungnya pada kursi setinggi punggung atletiknya itu, menyeringai kembali. “Gue cuma heran, sih, kenapa cewek kayak lo habisin banyak waktu buat hancurin hidup orang bukannya menata masa depan.”
“Bukan urusan lo.”
“Urusan gue, dong! Lana kan calon istri gue.”
“Dalem mimpi lo! Gue emang benci Lana, tapi Lana gak sebodoh itu buat buang Candra dan pilih lo yang gak jelas.”
“Yang penting gue jenis good boy yang gak sentimental dan gak punya penyakit psikologis. Apalagi suka ngadu domba, ups!” tekan Varen, terlebih pada kata 'ngadu domba'nya barusan.
Iris menggeram kesal. Mencengkeram erat tali tasnya yang mungkin akan putus jika jemari itu terus mencekiknya.
“LO MAU APA, HAH?!” Iris menghantam meja yang berdiri di tengah keduanya dengan rampus. Berhasil mendorong keseluruhan orang untuk menoleh ke arahnya, ke arah meja keduanya.
“Gue sih simple aja. Cuma pengen denger pengakuan langsung dari bibir menor lo itu.”
Iris menggasak meja itu kedua kalinya. Ia bersilih menghela napas dalam-dalam lantas mengembuskannya kasar. Berupaya sabar.
“Iya! Gue author dari konten Breakbreak News. Gue juga yang utus beberapa Seksi Jurnalistik buat sorotin Lana setiap waktu dan ... woah.” Iris tergelak sesaat, “Gue gak nyangka lo demen sama Lana yang, pftt ... kampungan.”
“Cuma tentang Lana? Yang lain?”
“Lo kira berita di TV semuanya bener?”
“Bagus, deh. Setidaknya secara tidak langsung lo ngakuin itu.” Varen mengerising lebar, beralih menunduk dan memandang ponselnya; otomatis menciptakan kerutan pada kening sang gadis.
“Ngapain lo?!” Iris mendelik sangsi.
“Ini, ada yang kangen sama lo.” Varen menaikkan lengannya, memperlihatkan layar ponselnya tepat di depan netra Iris yang segera terbuka lebar. Gadis itu sengap.
'Sekakmat!’ seru Septhian dari sambungan telepon via suara bertepatan dengan tersimpulnya kerising dari bibir Varen. Kendati tampak terkejut setengah mati, Iris hanya tergelak seolah itu bukan hal yang dapat mengancam segala siasatnya.
“Okee! Gue akui lo pinter, Ren. Tapi sayang, cuma lo sama Septhian saksinya.” Iris tersenyum miring, “Apa mereka—seluruh murid— bakal percaya sama kalian? Banding gue detektif sekolah? Imposible,” kekehnya.
Septhian meresponsnya dengan kekeh sarkasme, menertawakan kepercayaan diri dara itu. Iris membangun suasana seakan dia-lah yang menang, padahal ia tertangkap basah telah menipu banyak orang.
‘Gue tau lo bakal bilang ini, makannya buat jaga-jaga gue rekam ucapan lo.’
Iris menggeram singkat, mengentakkan tungkainya atas permukaan lantai. Arkian, tanpa berniat berlama-lama di sana, Iris menyambar tas tangan hitamnya seraya berdiri—menghadap Varen sepenuhnya. “Lihat aja, Ren. Kalau lo berhasil buat rencana gue hancur berantakan, gue bakal buat lo nyesel!”
Iris berbalik meninggalkan café sederhana itu dengan gusar dan terus menggeram, mencuri banyak perhatian para pelanggan; menyisakan kasak-kusuk meski hanya sebentar. Banyak yang beranggapan bahwa yang barusan adalah masalah putus cinta, jadi mereka abai saja.
‘Lo keren banget, sih, gue akui. Ternyata ini pesona loo? Aliiig. Gue terpukau.'
“Dih, akhirnya lo terpesona juga, kan?!” sungut Varen, tetapi Septhian hanya terkekeh. “Oh, ya ... gimana kalau kita bikin kesepakatan aja sama Iris? Memanfaatkan suasana?”
Gumaman panjang terdengar dari sambungan telepon. Septhian tengah berpikir sejenak. ‘Terserah lo. Apa pun itu bakal gue dukung selama lo gak kelewat bates. Gue cuma bisa ngomong 'hati-hati' ke lo.’
“Hah? Hari ini gue naik taksi. Lo kalau mau ngomong 'hati-hati' ke pak sopirnya aja. Eh, tapi kalau lo sibuk, gue bakal sampein salam ke pak taksi nanti.”
‘Bukan itu, Kudaniil!’
“So?”
‘Pacar Iris tuh ketua geng brutal di Glare High School. Bukan geng motor, tapi preman bergengsi. Yaa ... gue jarang sih papasan sama dia. Setiap hari kalo gak di kantin, dia mesti ada di belakang sekolah. Penindas,' terang Septhian dengan lancar jaya.
“Serius?” Varen tergelak samar, “Manusia jenis itu ternyata ada di dunia, ya? Gue kira di novel-novel fiksi aja,” imbuhnya.
‘Gue minta lo hati-hati, bukan komentar!’
“Hm, gue paham! Eh, anyway, siapa?”
‘Namanya? Elard. Elard Arkana.’


 aneylarevaa_
aneylarevaa_