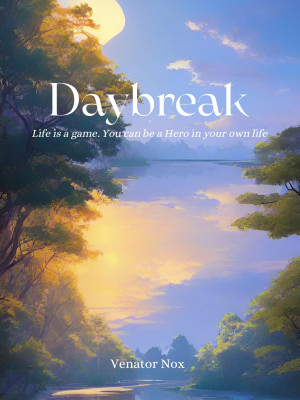Sabtu, 12 Desember, 17.52 WITA
Aku menemukan diriku berdiri di bawah kenaungan pohon akasia yang memayungi halaman rumah Ghea. Salah satu daunnya yang lebar dan telah menguning tertiup angin, jatuh, lalu tersangkut di rambutku. Aku mengambil waktu untuk menyingkirkannya. Sengaja berlama-lama. Bahkan diriku setengah berharap agar tidak ada orang di rumah. Agar tidak ada yang membukakan pintu.
Harapanku tidak terwujud. Karena setelah berjalan lambat-lambat melintasi halaman, menginjak dedaunan kering di atas halaman berkerikil yang bersih, lalu berdiri di pintu beberapa menit demi menyiapkan diri, pintu terbuka tanpa sempat kuketuk. Neneknya Ghea yang sudah berusia lebih dari tujuh puluh tahun itu berdiri di depanku, menatap lamat-lamat dengan matanya yang telah mengabur, menelitiku.
“Rara?” tanyanya setelah beberapa saat.
Aku tersenyum kecut. “Nana,” koreksiku.
“Oh!” Cepat-cepat, dia meraih tanganku dan menarikku masuk. “Masuk! Masuk!”
Ghea punya sofa besar, empuk dan lembut berwarna hijau lumut di ruang tamu rumahnya yang luas. Di situlah aku mendudukkan diri, atau lebih tepatnya menenggelamkan diri, karena begitu duduk, sofa itu rasanya menyembunyikan tubuhku. Ada meja kaca segiempat di tengah-tengah sofa berbentuk L, di bawahnya adalah karpet bulu lembut yang seakan memijat kaki. Ada kipas angin besar terpasang di langit-langit, tetapi sebenarnya ruangan itu sendiri dingin secara alami berkat lantai kayu ulin yang kuat, dinding-dinding kayu, serta bubungan tinggi yang beratap sirap.
Dulu, aku selalu mendambakan rumah seperti milik Ghea.
Dulu, aku selalu senang berada di rumah Ghea.
Sekarang ... semua yang ada di rumah ini rasanya menyesakkan.
“Mau minum apa?” Pertanyaan itu menyentakku sedikit.
Buru-buru, aku menggeleng. “Enggak usah, Nek. Saya bawa air putih.”
Tetapi ia tidak mendengarkan dan berjalan lambat-lambat ke dapur. “Nggak pa-pa. Kamu pasti haus.”
Tidak lama, aku dapat mendengar gemerincing sendok dan gelas dari arah sana. Dulu, aku tidak begitu sungkan untuk duduk di sini dan mendengarkan suara sejenis itu. Tahu, bahwa itu Ghea yang sedang membuat es jeruk dalam sebuah teko besar untuk kami semua. Atau Nenek yang menyusun kue sarang semut buatannya di atas piring. Kesukaan kami. Akan terdengar percakapan hangat di antara mereka, ditingkahi keberisikan Ulfi yang tengah menonton video mukbang atau ASMR dalam volume keras, Kama yang berusaha mengeraskan volume televisi, dan Laura yang sibuk menerima telepon. Kadang, akan ada perdebatan di sana-sini, mengatasi suara-suara yang telah bising tadi.
Aku memejamkan mata, menyesap dalam-dalam keberisikan yang kurindukan itu. Seperti sihir, ketika mataku terbuka, seluruh suara satu persatu menghilang. Hingga yang tersisa hanyalah senyap. Dan aku. Sendirian.
Nenek Ghea kembali beberapa menit setelahnya, menyajikanku segelas sirup berwarna merah dan sepiring kue sarang semut. Beliau duduk di sampingku, berjarak satu orang di antara kami. Berjarak Ghea. Ghealah yang terbiasa duduk di sana, di tempat itu, di antara aku dan Nenek.
“Gimana ... keadaan Nenek?” tanyaku setelah beberapa saat.
“Baik,” Nenek tersenyum. “Kemaren sempat tensi sampai 200, tapi hari ini sudah turun jadi 180.”
Aku mengangguk, balas tersenyum. Yang kutahu, Ghea begitu menyayangi Neneknya. Dia begitu menjaganya, melarangnya makan ini itu yang bisa membuat darah tinggi. Dan segera setelah melihat neneknya di rumah sakit, hal pertama yang gadis itu lakukan adalah ... menyuruh wanita ini pulang.
Dia ingin neneknya beristirahat. Dia tidak ingin neneknya darah tinggi karena memikirkannya. Dia bilang, hanya kecelakaan kecil, tidak ada yang serius, ia akan segera pulang, dan kita semua selamat. Aku membantu Ghea berbohong dengan baiknya.
“Bagaimana kabar Ghea?” tanya Nenek.
Sedikit gelagapan atas pertanyaan yang menyentak lamunan, aku menggigit bibir pelan. “Dia akan ... pulang. Sebentar lagi.”
Lama, Nenek menatapku, seakan meneliti. Selama itu, keheningan menyergap kami. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selain meremas tanganku sendiri. Aku orang yang kikuk, aku tahu itu. Tapi orang kikuk yang bertandang dan mencoba menghibur orang lain, tetapi gagal dengan menyedihkan benar-benar terdengar tidak tahu diri.
Di saat aku mulai berpikir adalah kesalahan datang kemari, Nenek kembali buka suara. Apa yang dia katakan membuatku mengangkat kepala yang tertunduk, lalu balas menatapnya.
“Kamu tahu. Bagaimana Ghea kehilangan kedua orangtua?”
Tidak ada kata yang tepat rasanya, untuk mengartikan perasaanku mendengar pertanyaan itu. Kami semua tahu penyebab kepergian kedua orangtua Ghea. Tetapi tidak pernah ada yang benar-benar mengetahui ceritanya. Katanya kecelakaan pesawat. Persisnya? Tidak ada yang tahu. Bahkan Ghea sendiri selalu menghindari topik itu.
“Kecelakaan pesawat,” Nenek melanjutkan tanpa menunggu jawabanku. “Ghea masih bayi... baru bisa berjalan, belum mahir berlari. Mamanya adalah anak perempuan Nenek satu-satunya. Si Bungsu, Si Kesayangan. Anak yang sangat penurut. Papanya orang baik, perhatian, pekerja keras. Lalu suatu hari, mereka memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, seperti biasa setiap dua bulan sekali, membeli pakaian untuk dijual lagi di toko. Biasanya hanya papanya Ghea, tapi waktu itu, tiba-tiba saja, Amira ingin ikut.”
Terdengar detak jam dinding sementara Nenek menghela napas. Gelas berisi sirupku mulai berembun. Ah, ternyata isinya air es.
“Hari itu Nenek marah. Menuduh ia meninggalkan Ghea yang masih kecil untuk jalan-jalan sama suaminya.”
Aku mendengarkan, sementara kulihat tangan wanita di depanku sedikit gemetaran.
“Dan itu adalah penyesalan terbesar Nenek.”
Tatapannya kembali padaku kemudian, membuatku mengerti kesedihan yang pernah menenggelamkannya. Kesedihan yang masih menenggelamkannya. Hingga detik ini.
“Tidak ada apapun di dunia yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seorang anak. Rasanya kehilangan anak ... yang sudah dikandung sembilan bulan,dilahirkan sampai menahan sakit dua hari dua malam, dibesarkan dengan banyak pengorbanan. Kehilangan anak ... rasanya seperti kehilangan separuh nyawa. Luka itu tidak ada habisnya.”
Kepahitan di setiap penggal kalimat, dapat kurasakan juga di ujung lidahku, membuatku sulit unuk menelan. Membuat tanganku menggapai, menyentuh tangan Nenek, meremasnya pelan.
Airmata mulai jatuh, menyapa pipinya.
“Sekarang, separuh nyawa itu tertitip pada Ghea. Ghea yang Nenek besarkan sejak dia lahir juga. Sejak dia merangkak sampai saat ini. Kalau Ghea juga direnggut ... Nenek sudah nggak punya apa-apa. Nenek nggak punya alasan untuk hidup.”
Sekarang aku memeluk Nenek. Karena aku tidak ingin mendengar kelanjutannya. Karena aku takut jika diucapkan, skenario-skenario buruk yang berputar di kepala kita dapat menjadi kenyataan. Dan aku tidak menginginkannya. Tidak lagi.
“Ghea ... baik-baik aja,” bisikku, merapalkan doa itu. “Ghea selamat. Dia akan pulang sebentar lagi. Ghea pasti baik-baik aja. Karena ...,” pelukan itu kulonggarkan pelan, kutatap Nenek. “Karena ... Nenek juga adalah alasannya untuk hidup...”
Dalam beberapa kesempatan, kadang aku mengasihani Ghea. Dia tidak lagi punya orangtua. Dia tidak punya siapapun lagi selain Neneknya. Neneknya yang sudah renta. Neneknya yang terus berjuang hidup lebih lama agar dapat terus merawatnya. Aku punya orangtua utuh, punya saudara perempuan, yang ... mungkin, jika kami berhenti saling bersikap menyebalkan, dapat menjadi sandaran satu sama lain.
Dalam kesempatan lainnya, aku kadang iri. Ghea begitu menyayangi neneknya, begitu juga sebaliknya. Kapan ... aku bisa menyayangi seseorang setulus itu? Tanpa pamrih? Tanpa berharap aku diperlakukan sama, atau lebih baik dari saudari kembarku?
Aku selalu merasa tidak adil karena diperlakukan sebagai bayangan.
Dan kini, pikiranku sendiri menamparku.
Aku diperlakukan seperti bayangan karena ... Aku. AKU sendiri yang memperlakukan diriku sebagai bayangan Laura. Aku membanding-bandingkan diriku sendiri. Aku menginginkan mandi cahaya yang dia dapatkan.
Terlupa bahwa ... aku lebih nyaman di sini. Di kegelapan ini.
Keluargaku tengah kalut sekarang. Dan aku baru menyadarinya, setelah sibuk menjadi bayangan. Seandainya aku menyadari ini lebih cepat, seandainya hatiku tidak merasa jengkel, seandainya birthday wish terkutuk itu tidak pernah ada ... akankah ada yang berubah?
***
Minggu, 13 Desember. 09.02 WITA
Ketika aku kembali ke rumah sakit, lorong tempat Ghea dirawat dipenuhi anak-anak dari kelas kami. Mereka datang menjenguk, membawa bunga dan keranjang-keranjang buah. Kata perawat yang memeriksaku, tidak ada luka serius, jadi aku diperbolehkan pulang sejak pagi Sabtu. Ghea berbeda. Ghea membutuhkan perawatan setidaknya hingga beberapa hari ke depan.
Tetapi hal yang membuat degup jantungku yang gila akhirnya mereda, adalah ketika aku melewati gerombolan teman sekelas, menengok ke dalam dan ... menemukan Ghea, duduk di atas tempat tidurnya. Dia masih tampak bernapas. Dia bahkan mampu tersenyum tipis menanggapi ucapan salah seorang teman. Detik itu pula, salah satu ketakutanku rasanya dicabut.
Kantung di bawah mataku yang baru saja ditegur Aya mengonfirmasi rasa itu. Ketakutanku. Aku tidak bisa lelap barang sedetik. Tiap kali kupejamkan mata, bayangan kepergian Ulfi yang disusul kepergian teman-temanku lainnya membuatku dihantui mimpi buruk. Kecuali, aku tidak sedang tidur. Kecuali, ini bukan mimpi.
Ini kenyataan.
“Nana, kamu nggak papa?” Seseorang menepuk pundakku.
Aku menoleh, menemukan Asta, teman sekelas Kama, Laura danUlfi. Di belakangnya, aku melihat teman-teman sekelas mereka yang lain, menyesaki lorong karena hanya sedikit yang diperbolehkan masuk ke ruangan.
“Hai. Aku nggak papa,” balasku disertai senyum yang tidak mencapai mata.
“Kamu pucet banget. Yakin nggak papa?”
Maksudku, kalau kamu baru saja terlibat dalam sebuah kecelakaan yang merenggut satu nyawa sahabatmu dan menempatkan yang lain dalam keadaan kritis, apakah wajar aku baik-baik saja? Apakah wajar aku bisa tidur dengan tenang tanpa seolah-olah kehilangan satu apapun? Sementara kamu, aku, secara tidak langsung menanggung rasa bersalah yang berusaha menelanmu bulat-bulat. Tidak.
Lebih wajar rasanya jika aku ingin mati saja.
Tetapi demi kesopanan, aku tersenyum tipis. “Nggak papa, cuma pusing dikit, tapi nggak pa-pa, kok.”
Asta menepuk-nepuk pundakku pelan. “Kalau sakit, bilang ya, istirahat. Omong-omong, kami mau pulang dulu, soalnya mau ke tempat lain.”
“Udah jenguk Kama?”
“Udah,” balasnya. Lalu terhenti. Ia bertanya balik. “Kamu udah?”
Aku menggeleng. Aku tidak seberani itu. Aku ... takut. Sangat takut. Papa bilang dia belum siuman. Papa bilang keadaannya parah.
Dan aku takut Ulfi tidak pergi sendirian.
Seakan membenarkan ketakutanku, Asta berbisik. “Dia kritis.”
“No ... she’s strong,” bisikku sebagai jawaban.
“Hm?”
Kerutan terlihat di kening Asta. Aku tahu ia tidak mendengar dengan jelas gumamanku. Jadi, aku menegakkan kepala dan mengucapkannya dengan lebih keras, dengan lebih tegas. Dengan begitu, kuharap ... ucapanku benar.
“She’s strong. Dia pasti ... bisa melewati ini.”
***
“Kama! Kama! Kama!”
Ulfi dan Laura berteriak heboh. Sementara aku dan Ghea juga tidak mau ketinggalan. Kami bertepuk tangan keras-keras. Jantungku ikutan bertalu, terutama dengan semakin intensnya tarik menarik seulas tambang yang dilakukan kedua tim.
Tapi, pada tim biru, yaitu tim kelas kami, X A, ada Kama. Dan jika ada Kama, pasti kami akan menang. Kama itu kuat hingga anak-anak laki-laki di kelas pun segan padanya. Teori ini belum pernah terbukti keliru, semua orang setuju. Hari ini pun, seharusnya kembali begitu.
“Ayo Kamaaa!!! Dikit lagi!!! Tarik dikit lagiii!!!”
Keringat bercucuran deras di kening Kama, melewati sebagian anak rambut yang bandel keluar dari jalinan ekor kuda di belakang kepala, mengilap di bawah teriknya matahari. Tambang besar yang ditarik meregang kencang sekarang. Ini sudah babak ketiga setelah sebelumnya kedua tim seri, babak penentuan. Semua orang sudah lelah tampaknya, namun masih bersemangat untuk berjuang sampai akhir.
Dan jika masalah semangat, Kama tidak terkalahkan.
Sempat-sempatnya, ia menyunggingkan senyum, lalu berteriak keras-keras di udara, di antara riuh sorak penonton.
“UPI! GHEA! NANA! RARA! INI DEMI KALIAN! TRAKTIR GUE MI AYAAAMMM!!!”
Kama menarik dengan sekuat tenaga, menyentak hingga mengagetkan lawan yang sudah di ujung daya juang. Dan ... strategi itu berhasil. Bendera kecil yang terikat di tengah tambang semakin bergeser dan bergeser melewati garis batas, masuk ke dalam wilayah tim kami. Lalu, kaki-kaki tim lawan ikut mendekati garis pembatas itu, berusaha ditahan sekuat tenaga namun gagal. Mereka semua berjatuhan. Seluruh tim biru sontak melepaskan tambangnya dan bersorak sekuat tenaga, berpelukan. Sorak sorai pun mengisi udara.
Aku menjadi salah satu orang yang dipeluk bergantian, meski hanya penonton. Mereka menggotong Kama beramai-ramai dan semua orang tertawa bahagia. Aku, termasuk.
Aku tidak tahu kenapa, di antara segala memoriku tentang Kama, ingatan itu adalah salah satu yang paling kuat. Mungkin karena hari itu begitu panas, namun keringat tidak lagi terasa karena serunya permainan. Mungkin karena sehabis itu kami pergi ke minimarket dan masing-masing menghabiskan dua batang es krim─aku ingat membeli rasa cokelat dan satu yang berbentuk seperti semanngka. Atau mungkin ... karena hari itu, meski bagi orang lain biasa saja, merupakan salah satu hari paling membahagiakan untukku. Hari dimana aku tertawa lepas. Hari dimana aku merasa ... oh, aku punya orang-orang ini, sahabat-sahabatku. Jadi, meskipun langit mendung dan hari yang buruk menerpa, aku punya mereka...
Dan karena aku punya mereka ... aku akan baik-baik saja.
Sekarang, aku rasanya memegangi salah satu ujung tambang itu. Teman-temanku pergi, tumbang satu persatu. Dimulai dari Ulfi. Lalu ...
Tidak. Tidak boleh lagi. Aku akan memegangi tambang ini erat-erat. Tidak boleh kalah. Tidak peduli terik yang membakar atau tanganku yang terluka. Aku tidak ingin melepaskan. Ghea, Kama, Laura ... kuharap kalian juga.
Aku mulai berjalan di sepanjang lorong, jantung berdegup kencang. Aku berjalan menuju ruang rawat Kama.
Kama, kamu kuat. Kamu harus kuat. Bertahan, di sana. Aku mohon.


 rainaya
rainaya