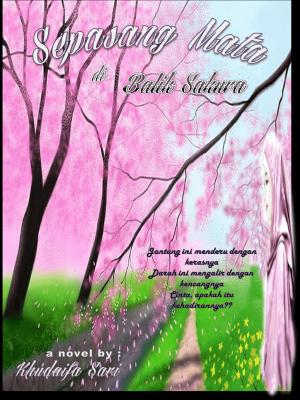Jum’at, 11 Desember. 18. 10 WITA
Resfeber, adalah kata yang kudapatkan baru-baru ini saat iseng berselancar di blog, mencari ide untuk tulisanku. Dia adalah satu kata yang diambil dari bahasa Swedia, tentang perasaan cemas dan antusias saat akan memulai suatu perjalanan. Dan resfeber, aku mengalami sekarang.
Masalahnya di sini adalah, aku bukannya sedang pergi ke mana menaiki pesawat yang seumur hidup belum pernah kulakukan. Aku hanya naik mobil, dalam perjalanan pulang setelah berfoya-foya di salah satu mal terbesar yang aku tahu. Dan aku tidak tahu kenapa aku merasakan sensasi bersalah itu sekarang. Seharusnya tadi, di perjalanan pergi. Karena bagaimana pun, kami telah bolos sekolah. Tapi tidak, perasaan itu lebih tajam sekarang.
Dengan kelelahan, aku menyandarkan kepala dan menatap jendela mobil di sisiku. Hanya deret gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlarian ke belakang. Atau kendaraan lain yang seakan bergerak lambat, lalu tertinggal. Atau semburat jingga yang sesekali mengintip di sela gedung-gedung tinggi. Sore telah hampir berakhir dan senja mengintip, mengawasi. Dan aku ... ingin tidur. Mengantuk. Capek.
Sayangnya, empat ember bocor di sampingku ini tidak bersedia menutup mulut.
“Eh! Kapan sih, gue begitu? Lihat, dong!” Kama, dengan perpaduan antara suara cempreng, nyaring, dan mulut yang bawelnya minta ampun kembali berkoar-koar.
Cewek pemilik kulit sawo matang, rambut keriting yang super hitam dan super tebal dan senyum paling lebar seantero planet itu mengulurkan tangannya, coba menjangkau Ulfi dan Ghea yang sedang cekikikan di bangku belakang. Mereka sedang memeriksa hasil photo booth tadi dan tidak henti-henti membahasnya.
Belum sempat Kama berhasil merebutnya, Ulfi, cewek mungil bermuka bulat, berjilbab yang sering disangka anak SMP itu telah menjauhkan tangannya sambil tertawa keras-keras. “Ya ampun, Ma! Lo lucu banget sumpah merem gini hahaha.”
“Masa sih, gue merem! Liat sini!”
“Beneran! Iya kan, Ghe?” jawab Ulfi di antara derai tawa. Ghea yang paling anggun di antara semuany hanya cekikikan, tidak mampu menyembunyikan tawa.
Hal itu, seperti bisa ditebak, membuat Kama makin bersemangat melihat hasil foto. Ia sampai mengubah posisinya hingga persis menghadap kursi belakang. Kama menarik lengan Ulfi, membuat cewek itu berteriak sembari mempertahankan gelangnya yang nyaris putus.
“KAMAAA!!! Ini gelang berharga, ya! Gelang persahabatan kita! Kalo putus lo tanggung jawab!”
Sementara Ulfi membenarkan gelang kupu-kupu yang tadi kami beli, Kama kembali mengulurkan tangan.“Iya, maaf! Elo sih! Sini! Sini! Mana fotonya gue liaaattt~”
“Enggak!”
Mereka tertawa, lagi. Seisi mobil dipenuhi derai tawa mereka, mengherankanku bagaimana supir taksi daring yang kami tumpangi sekarang tidak juga protes. Kama masih berusaha meraih hasil foto-foto itu, yang terus dioper bergantian antara Ulfi dan Ghea.
Kama menggulung lengan bajunya hingga ke pundak, siap berperang. “Awas kalian, ya!”
Sayangnya, keganasannya membuat lengannya menyikut Laura yang sedang memainkan ponsel sampai ponsel itu juga terjatuh.
“Kamaaa!!! Gue lagi chatting-an sama Rei, ih!”
Tanpa rasa bersalah, Kama memeletkan lidah. “Pacaran mulu, sih lo, Ra. Rasain!”
Aku nyaris tertawa. Getir, tentu saja. Masalah Laura dan Rei masih menjadi sesuatu yang menyentuh sudut hatiku, dengan cara yang tidak mengenakkan. Akan selalu begitu.
“Kayak Nana dong, lo. Kalem!” Alisku sedikit berkerut ketika mendengar namaku disebut.
“Ih, Nana mah emang alergi cowok!” Laura menyahut, lalu menunduk untuk memungut ponselnya. Ketika ia duduk kembali, ia menatapku. “Na, Mama ada nelpon?”
”Chat,” balasku. “Tapi belum gue buka, bingung mau bales apa.”
“Nggak usah. Bentar lagi kita juga nyampe rumah.”
Mengangguk, aku pun membuang pandang kembali. Aku tidak ingin mengobrol dengan Laura. Keberisikan di sekitar berusaha kuredam dengan menyumpalkan earphone ke telinga. Breathe, lagu lama milik Taylor Swift mengalun melewati indera pendengaranku. Nada-nada yang sendu, senja yang berada di ujung jalan, dan gerimis yang menyapa jendela lamat-lamat. Dan aku kembali merasakannya. Resfeber.
Tatapanku sejenak beralih ke depan, entah bagaimana, firasat buruk yang menggerayangiku semakin kuat. Di luar jendela, gerimis menderas menjadi hujan. Sore yang bersemburat jingga menggelap. Dan aku hampir bisa melupakan perasaan bersalah ini. Hampir. Karena tahu-tahu pemandanganku berubah. Deret gedung yang berlarian sekarang kabur seperti kilat. Di sepersekian detik yang sama, semuanya terjadi ...
Aku mendengar suara tabrakan keras pecah di telinga, menggantikan derai tawa yang terdengar detik sebelumnya. Juga duniaku yang berjumpalitan saat itu juga. Semuanya menggelap, bersamaan dengan tubuhku yang terasa melayang dan dilemparkan. Hanya satu kedipan mata sebelum aku akhirnya dapat merasakan benturan yang lebih keras. Lalu sunyi.
Tidak ada tawa Ulfi. Tidak ada Laura yang marah-marah. Tidak ada teriakan Kama dan cekikikan Ghea. Semua hening. Telingaku berdengung. Lalu, setelah berusaha keras, aku membuka mata, coba merasakan tanganku, tubuhku. Gamang. Namun, perlahan tapi pasti, aku dapat mengendalikannya kembali.
Perlu upaya lebih keras dariku untuk memerintahkan otakku yang kebingungan untuk bergerak, untuk bangkit, sementara seluruh tubuhku terasa seperti adonan agar-agar.
Ketika aku berhasil bangkit duduk, aku melihat pecahan kaca di sekitarku, di tubuhku, banyak sekali. Juga darah. Dan, tidak jauh di depan, sebuah mobil telah terbalik, tidak lagi berbentuk.
Itu mobil yang kami tumpangi tadi.
***
Kepalaku berdenyut seketika. Sekelilingku mendadak bising oleh dengung keras yang tak berkesudahan. Dengan sisa-sisa kekuatan, aku merangkak di atas aspal, menggapai mobil itu, menggapai apapun, siapapun yang dapat kujangkau.
Ada tangan yang terkulai dari jendela yang telah pecah, yang bagian atapnya sekarang menyatu dengan aspal. Tangan itu memiliki gelang berwarna biru, dengan manik bintang, lonceng kecil dan bandul kupu-kupu. Ada darah mengalir di sela jari.
Aku merasakan tubuhnya menegang. Aku ingin berteriak. Aku merasakan diriku berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Yang kutahu, orang-orang berdatangan di sekitar. Ribut. Ribut sekali. Seseorang menarik tangan yang tadi kulihat. Yang lain menarik tubuh-tubuh lainnya.
Ghea. Ulfi. Kama. Laura... aku menantikan mereka. Aku ingin mendengar mereka berteriak atau apapun. Tapi tidak ada. Tidak ada ... tidak ada yang sadar selain aku.
“Kamu nggak pa-pa?”
Sepasang lengan kokoh kemudian ikut serta menarikku. Aku meronta, tetapi tubuhku lemah dan aku tidak sanggup berbuat apa-apa. Mereka menyeretku ke pinggiran jalan. Samar, aku mulai mendengar suara-suara.
“Panggil ambulan!”
“Lagi di jalan!”
“Tolong bantu tarik! Anak ini terjepit!”
“Yang ini nggak sadarkan diri!”
“Yang ini lukanya parah! Darahnya terlalu banyak!”
Aku menggigit kuku. Tidak, aku menggigit ujung-ujung jariku, kalut, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pikirannya yang berproses dengan acak kembali mengabsen nama teman-temanku. Ghea. Ulfi. Kama. Laura ... bagaimana keadaan mereka semua? Siapa yang tidak sadarkan diri? Siapa yang terluka parah?
Duniaku berputar. Mobil itu masih dalam posisi terbaliknya, seluruh badannya ringsek, pecahan kaca berhamburan di aspal, bersama tetes-tetes darah. Beberapa orang lewat di dekatku, menggotong tubuh. Jins biru, kaus abu-abu dan jaket abu-abu gelap, aku mengenalinya. Di tangannya yang terkulai, menetes darah, melewati gelang kupu-kupu.
Gelang itu putus, jatuh di dekatku. Aku memungutnya, lantas merangkak karena kakiku tidak sanggup berdiri, menggilas pecahan kaca dengan lutut dan telapak tangan. Mereka meletakkannya sekarang. Di atas sebuah tandu. Di pinggiran jalan. Orang-orang berkumpul mengerubunginya.
“Ambulannya mana?!” Seseorang berteriak panik. “Ini dia nggak ada napasnya! Kepalanya bocor!”
“Saya dokter! Coba saya periksa!”
Seseorang berpakaian kasual datang. Ia menerobos kerumunan yang memberinya tempat dengan mudah. Orang itu memeriksa denyut nadi di leher, lalu mulai memberikan CPR. Berkali-kali. Yang tidak direspon dengan baik.
Aku merangsek maju sekarang, mengambil tempat di sisi lainnya, menggenggam tangan sahabatku yang terkulai.
“Upi ....,” desisku, parau
Ulfi beberapa menit yang lalu tengah tertawa, mengolok-olok Kama tentang hasil fotonya. Ulfi setengah jam yang lalu tampak amat cantik dengan jilbabnya, atau jaket barunya. Ulfi yang sekarang diam, matanya terpejam, darah mengaliri keningnya hingga sepanjang tubuh bagian kiri. Ulfi yang sekarang diam, meski udara coba dialirkan ke mulutnya, meski jantungnya coba dipacu, ia ... tetap diam.
Hingga, orang yang mengaku dokter itu berhenti, memeriksa denyut nadi Ulfi sekali lagi, lalu menatapku. “Namanya siapa?”
“U-Ulfi.” Aku tergagap, kesulitan menemukan suaraku. “Ulfi Khalifa.”
“Ulfi Khalifa. Kematian pukul 18.19.”
***
Kamis, 11 Desember. 18.19 WITA
Kami pertama kali bertemu saat SMP, kelas dua.
Pada saat itu, kukira dia dan Kama orang yang sangat ekstrover sehingga aku bahkan tidak pernah berpikir bisa berteman dengannya. Aku yang amat pendiam, yang selalu berusaha menyatu dengan tembok dan menghindari menjadi terlihat, dengan dia yang selalu menjadi pusat perhatian, selalu menjadi badut yang membuat semua orang tertawa. Dia seperti bunga matahari, sumber segala yang cerah dan menyenangkan.
Dia an aku, berada pada lingkaran pertemanan yang berbeda. Tetapi saat itu hujan, orang-orang mungkin kelaparan sehingga kantin sedang ramai-ramainya.
“Pak, bakso satu,” gumamku pelan pada Pak Nanang yang punya kios bakso dan mi ayam. Kantin sekolah kami hanya ada satu, tetapi cukup luas. Ada beberapa pedagang dengan kios masing-masing, sementara kebutuhan lain disediakan koperasi sekolah. Hari ini, aku kepengin bakso meski tahu antreannya tidak mudah.
Pak Nanang sedang sibuk membuatkan dua porsi mi ayam untuk anak yang datang sebelumku. Beliau hanya mengangguk, masih mengerjakan pesanannya. Aku menunggu. Aku adalah orang yang sabar dalam menunggu. Aku pandai menunggu. Saking pandainya, aku terus menunggu meski seharusnya giliranku berikutnya, tetapi seseorang datang, seorang cewek bersuara nyaring. “Pak! Baksonya satu, yang cepet ya!”
Dan ia mendapatkannya dengan cepat, sementara aku masih menunggu.
Murid-murid lain berdatangan, semakin banyak hingga membentuk kerumunan di sekitarku. Aku yang datang lebih dulu hanya bisa terdiam di tengah-tengah sana. Terlupakan. Tergeser oleh murid-murid yang baru datang, yang berteriak-teriak minta makanan mereka segera diberikan.
Kadang, aku membenci diriku. Diriku yang terlalu pendiam, yang kadang kalau bicara tidak terdengar. Diriku yang kelewat pemalu, selalu menunduk dan menghindar. Diriku yang amat sabar, mau-mau saja mengalah. Bahkan dalam situasi seperti ini. Aku melirik arloji di tangan kananku. Lima belas menit lagi jam istirahat berakhir, antrean masih tersisa banyak dan aku tidak tahu kapan aku akan mendapatkan baksoku. Haruskah aku menyerah dan coba melupakan rasa lapar?
Di tengah perdebatan batinku, cewek itu datang.
“Pak! Ini dia dari tadi pesen bakso belum dikasih!”
Aku menatap ke arahnya. Cewek itu menunjukku. Ulfi Khalifa, aku tahu namanya, mendengarnya setiap absen karena kami sekelas. Aku bahkan hafal suaranya karena dia duduk di depan, sering menjawab pertanyaan guru dan punya banyak teman.
Namaku? Aku yakin dia tidak tahu. Aku bahkan ragu dia tahu kami sekelas dan hanya berjarak beberapa meja.
Apa yang kemudian dia lakukan ... aku tidak menduganya. Kupikir, dia hanya akan membantu mengingatkan Pak Nanang soal pesananku, dan dengan itu pun aku sudah nyaris menangis haru. Aku yang terlupakan, lalu seseorang menyuarakan apa yang tidak bisa kusuarakan, itu semua sudah cukup untuk membuatku amat berterima kasih. Tetapi Ulfi memilih untuk tidak berhenti di sana.
Aku terkejut ketika ia justru menyodorkan bakso di tangannya ke arahku. Lebih terkejut lagi mendengar ucapannya. “Nih, bakso lo,” Ulfi memberikan padaku mangkok bakso yang masih hangat. “Tungguin ya, kita makan bareng!”
Seperti yang kubilang, aku pandai menunggu, tetapi dia kembali dengan cepat, dengan semangkok bakso lain di tangan. Kami memilih salah satu meja yang kosong dan dia mulai memperkenalkan diri.
“Omong-omong, gue Ulfi.”
Aku mengangguk, melihatnya, memilih untuk tidak mengapa-apakan baksoku sebelum dia mengunyah miliknya. “Tahu.”
Ia tersenyum seraya menuang kecap. “Kok diem aja? Makan.” Lalu menambahkan sambal, sebelum kembali melihat ke arahku. “Dan lo Launa, kan?”
Aku tersentak, nyaris tersedak kuah bakso yang baru saja kucoba hirup. Aku kemudian menatapnya dengan pertanyaan yang amat jelas tercetak di dahi, membuatnya tertawa.
“Kenapa kaget banget, sih? Semua orang juga kenal lo kali,” ujarnya. “Nih ya, lo tuh paling pendiam di kelas tapi kan lo selalu ranking satu. Sudahnya lo kembar. Di sini, nggak banyak anak kembar, cuma lo doang, wajar semua orang penasaran.”
Masuk akal. Aku mulai meraih botol saus dan menuang sedikit pada mangkokku.
“Lain kali, pesan lebih keras, daripada nunggu lama-lama kayak tadi.”
Aku mengangguk. Ia tersenyum.
“Atau lain kali, gue aja deh yang pesenin. Sekalian gue kenalin lo sama temen-temen gue, ya.”
Tidak ada kata-kata resmi seperti orang memulai hubungan. Hari berikutnya, Kama masuk, tetapi Ulfi tidak meninggalkanku, dia menungguku untuk ke kantin bersama. Ia memesan untukku (untuk semua teman-temannya, sebenarnya), Kama dan Ghea, juga Laura.
Dan seperti itulah ... permulaan persahabatan kami.
Dan seperti itulah ... awal keterikatanku pada Ulfi Khalifa.
***
...
15. Teddy bear jumbo
16. Keyboard
17. Tiket konser Seventeen
18.
19.
Dua angka terakhir kosong, dan daftar itu berakhir sampai di sana. Aku menatap Ulfi yang baru saja kembali membawakan minuman. Laura dan Kama dengan senang hati segera menyambut jus jeruk serta potongan rujak itu.
Aku masih diam di atas kasur Ulfi usai meneliti buku lamanya, tempat aku menjatuhkan daftar yang terdengar seperti daftar hadiah tersebut.
“Ini apa, Pi?”
“O-oh!” Dengan sedikit panik, Ulfi buru-buru mengambil catatan itu dariku lalu cepat-cepat menyembunyikannya. Wajahnya sedikit merona ketika ia menatapku. “Bukan apa-apa kok. Cuma ... wishlist.”
“Wishlist?” Aku mengerutkan kening.
“Uhmm...” Ulfi berdiri, ia mengembalikan buku itu di antara rak buku-bukunya sebelum duduk di sampingku, lalu merebahkan diri. Di sisi kasur, Laura, Kama dan Ghea kembali membahas PR sambil menyantap camilan. Aku masih menatap Ulfi, menunggu jawabannya.
“Gini. Lo tahu, kan, Na, kalau bokap gue itu udah nggak ada?”
Aku mengangguk. Ayah Ulfi meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik, lima tahun lalu.
“Sebagai anak-anak dan remaja, gue juga punya keinginan. Tapi gue sadar gue nggak punya siapa-siapa untuk dimintain hadiah. Gue nggak mau nambahin beban Ibu. Abang gue juga masih kuliah. Jadi gue nabung, kadang gue kerja di toko Om gue. Uangnya buat beliin hadiah tiap ulang tahun gue sendiri.”
Ketika ia menatapku, ada cengiran kecil di wajah Ulfi. “Aneh, ya, ngerayain ulang tahun sendiri?”
Aku menggeleng. Terpikir olehku untuk memberikan hadiah yang diinginkan Ulfi di ulangtahunnya yang ke-18 nanti. Tapi apa? Daftar itu masih kosong.
“Terus, ini nomor 18 sama 19 kok kosong?”
Jeda. Ulfi memandangi langit-langit kamarnya yang kosong. Ketika dia menatapku kembali, dia mengendikkan bahu.
“Gue nggak tahu apa lagi yang gue inginkan. Rasanya ... sampai 17 aja cukup.”
***
Yang kuingat, aku mati rasa saat itu juga.
Tangan Ulfi yang berada di genggamanku terasa dingin. Darahnya lengket, menempel di telapak tanganku. Aku mengusapnya, sebisa mungkin menyingkirkan noda itu. Lalu, aku memasangkan gelang kupu-kupu itu kembali di tangan Ulfi. Gelangnya sempat putus. Dan ia benci kalau gelangnya putus. Ulfi bilang gelang itu adalah tanda persahabatan kami. Ulfi bilang kami harus selalu memakainya, bersama-sama.
Tanganku gemeteran saat mengaitkannya. Berkali-kali, aku tidak bisa melakukannya dengan benar. Dadaku sesak dan pelupuk mataku buram dipenuhi cairan yang ingin keluar. Ketika aku selesai melakukannya, memasangkan gelang itu hingga terlihat cantik di pergelangan tangan Ulfi, aku mendengar ambulan yang meraung-raung dari kejauhan. Akhirnya ..
“Pi,” kataku, menggoyangkan tangan Ulfi yang tidak bergerak. Seseorang telah mencoba menutup wajahnya, yang kutolak seketika, kuhempaskan.
Ulfi belum mati. Ulfi belum boleh mati.
“Pi ... bangun PI....” Aku menggoyangkan tangannya. Tetapi ia bergeming.
“Pi... UPIIII!!!”
Tidak peduli seberapa keras aku berteriak, tidak ada sahutan. Tidak peduli sekeras apa aku mencoba, Ulfi tidak merespons.
Mataku panas. Penglihatanku mengabur. Hingga rasa-rasanya, aku kembali melihat senyum Ulfi di hadapanku.
Ulfi segera membuka pintu mobil dan naik duluan. Ia menutup pintunya, bahkan sebelum siapapun masuk hanya untuk menurunkan kaca jendela dan melambai kepada kami semua.
“Dah, guys. Gue pulang duluan, ya~”
Jangan pulang. Jangan pulang duluan. Kamu nggak boleh pulang dulu, Ulfi... masih ada kita di sini.
Ulfi memandangi langit-langit kamarnya yang kosong. Ketika dia menatapku kembali, dia mengendikkan bahu.
“Gue nggak tahu apa lagi yang gue inginkan. Rasanya ... sampai 17 aja cukup.”
Tidak. 17 belum cukup. Masih ada 18, 19 dan seterusnya, Upi!
“Ulfi Khalifa. Kematian pukul 18.19.”
Tetapi hitungannya terhenti di 17. Hadiah ke-18 dan 19 tidak pernah ada. Umur ke-18 dan 19 tidak pernah datang.
Yang datang hanyalah waktu kematian.
“Rasanya ... sampai 17 aja cukup.”
Ketika Ulfi mengalihkan pandang, aku mendengar gumaman lirihnya, gumaman yang kuharap salah kudengar.
“Atau mungkin, gue pengin sama-sama Papa lagi. Gue kangen Papa...”
Kesadaran itu merenggut energiku seperti penyedot debu. Menyisakanku dengan kehampaan, dengan rongga besar yang menganga di dada. Aku ingin menangis. Demi Tuhan aku ingin menangis. Tetapi energiku menguap habis dan semua yang bisa kulakukan adalah berusaha keras untuk tetap bernapas.
Orang-orang di sekitar kembali sibuk. Aku melihat mereka menggotong Ghea ke ambulan, dia sama tidak sadarkan dirinya. Dokter yang semula memeriksa Ulfi telah berlari, menghampiri tubuh yang baru saja digotong setelah ditempatkan hati-hati di atas aspal. Dari keterburuan yang kulihat, aku tahu dia sedang berada dalam keadaan gawat. Darah memenuhi wajahnya hingga seragam.
Laura?
Dan gelap menyambutku.


 rainaya
rainaya