Yasmine langsung mengalihkan pandangannya dari novel begitu mendengar derit pintu. Wajah terkejutnya luntur perlahan, berganti semringah begitu menyadari yang datang ke kamarnya adalah sang kakak. Pakaian mahal yang Yasmine lihat selepas magrib tadi sudah berganti baju tidur satin sebatas lutut. Wajah lelah Elea juga tampak lebih segar dibandingkan sebelumnya.
“Beli novel baru?” tanya Elea sembari mendudukkan diri di ujung ranjang Yasmine. Ia mencebik begitu melihat judul buku yang sedang dipegang sang asik. “Cinta-cintaan lagi.”
“Ini seru tahu, Kak. Aku lagi butuh yang manis-manis,” sahut Yasmine, penuh rasa bangga. “Uminya Mas Adam seru juga, ya?”
Dahi Elea lantas berkerut. “Umi Adam?”
“Tadi aku ketemu sama beliau di Gramedia. Terus tiba-tiba beliau minta gabung sama aku, Nurul, Ibnu. Kita bertiga juga ditraktir es krim juga, lho, Kak.”
“Iya, sih, Umi Inaya emang asyik banget orangnya. Beda sama Abi Emran yang sangat pengatur,” gumam Elea tanpa sadar.
Yasmine terdiam sesaat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kakaknya memiliki keluhan akan keluarga sang calon kakak ipar. Selama ini, Elea selalu terlihat nyaman saat bersama orang tua Adam. Ia juga pintar mengambil topik sehingga pembicaraannya dengan Umi Inaya dan Abi Emran tidak membosankan. Namun, rupanya ada momen di mana Elea harus berpura-pura di depan mereka.
“Udah nikah nanti pakai hijab, ya. Jangan pakai baju seksi lagi. Batasi pergaulan kamu sama lawan jenis. Harus bisa lebih terbuka juga sama Adam, jangan ambil keputusan sendiri.”
Wejangan dari Abi Emran masih terngiang dengan jelas di benak Elea. Ekspresi serius lelaki patuh baya berjenggot tebal itu juga masih sering menari-nari di pelupuk mata Elea. Perasaan, dulu orang tua Adam tidak keberatan dengan gaya hidup Elea. Mengapa menjelang hari H ijab kabul mereka tiba-tiba melayangkan banyak sekali peraturan. Belum lagi dengan posesif Adam yang kian buruk. Elea semakin tertekan.
“Kak?”
Lamunan Elea buyar begitu bahunya diguncang perlahan. Dia melirik Yasmine sembari tersenyum tipis. “Hm?”
“Kakak gak apa-apa?”
Bukannya menjawab, Elea justru membaringkan tubuhnya di samping Yasmine. Pandangannya lurus ke langit-langit kamar. Ingatannya berpusat pada kejadian beberapa jam yang lalu. “Adam nyebelin, Yas. Posesifnya, tuh, makin parah aja akhir-akhir ini,” adu Elea seketika.
Lidah Yasmine kembali kelu. Bingung harus bereaksi seperti apa atas ucapan kakaknya barusan.
“Kemarin dia minta kakak ngejauhin salah satu hair stylist. Tadi dia minta kakak jaga jarak sama salah satu model. Curiga besok dia minta kakak berhenti kerja,” lanjut Elea.
“Mungkin Mas Adam begitu karena takut kehilangan Kakak.” Tidak tahu kalimat ini tepat atau tidak, Yasmine hanya menyuarakan apa yang muncul di kepalanya.
“Selama tiga tahun kita pacaran, Kakak gak pernah ada niatan untuk ninggalin Adam. Sekalipun posesifnya itu bikin sesak napas, tapi kakak selalu memilih untuk bertahan. Sebentar lagi kita juga bakalan nikah. Apa lagi yang harus dia takutkan, coba?”
Tanpa sadar, Yasmine menggaruk kepalanya. “Mungkin ini cobaan sebelum nikah?” Ia berkata asal lagi. “Kata orang, kalau mau nikah, tuh, godaannya banyak banget. Bisa dari pasangan, keluarga, ekonomi, bisa juga dari orang luar.”
“Tapi kalau Adam terus-terusan kasih tekanan berlebihan kayak gini, kakak jadi ragu buat lanjutin pernikahan ini.”
Saat itu juga, Yasmine mendaratkan pukulan keras di bahu kakaknya. Tak peduli mata Elea sudah mencuat setengah karena ulahnya barusan, Yasmine tetap melototi sang kakak dengan penuh keberanian.
“Istigfar, Kak! Nyebut! Astagfirullah al-azim ....” Gadis itu geleng-geleng kepala, tak percaya dengan kalimat yang baru saja lolos dari bibir ranum kakaknya. “Jangan asal bicara, Kak. Sebentar lagi Kakak sama Mas Adam nikah. Semua persiapan juga udah matang. Masa Kakak ngomongnya begitu, sih?”
Seraya mengusap bahunya, Elea berkata, “Ya udah, kalau begitu kamu bantuin kakak. Bilang sama Adam, jangan posesif berlebihan.”
“Kan, Kakak tahu aku sama Mas Adam gak begitu dekat. Aneh banget kalau tiba-tiba aku ngomong begitu. Apalagi umur aku sama Mas Adam beda jauh. Entar malah dijawab, ‘anak kecil gak usah ikut campur’. Gimana kalau begitu?”
“Justru karena umur kalian beda jauh. Siapa tahu Adam jadi malu diingetin sama anak kecil. Iya, kan?”
Yasmine terdiam. Bukannya tidak mau membantu, tetapi ia dan calon suami kakaknya itu memang tidak dekat. Jangankan meminta Adam untuk memperbaiki sifatnya yang membebani Elea, saat berterima kasih karena telah dibelikan sepatu saja Yasmine harus mengumpulkan mental lebih dulu kemarin. Saat disuruh mengajak Adam makan malam bersama oleh Mama Asri saja, Yasmine perlu menyusun kalimat berulang kali.
Tentu saja, Yasmine tahu Adam adalah orang yang baik. Dia juga sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Tidak keberatan harus menjemput Elea dari tempat kerja setiap hari sekalipun kesibukannya sebagai dokter bedah pun tiada duanya. Yasmine juga tahu Adam sangat mencintai Elea hanya dari cara sorot matanya. Ia juga sering membelikan makanan untuk Yasmine. Namun, entah mengapa, seperti ada tembok besar yang membatasi keduanya.
Dengan sekali entakan, Elea bangkit dari tidurnya. “Lupain apa yang kakak bilang tadi, ya. Kakak cuma lagi agak capek aja.”
“Kak!” panggil Yasmine sebelum Elea benar-benar pergi dari kamarnya. “Jangan mikirin yang gak penting, ya? Aku yakin, Kakak bakalan bahagia nikah sama Mas Adam. Semuanya pasti baik-baik aja.”
Elea mengangguk sembari tersenyum tipis. “Ya, semoga.”
Pintu pun tertutup. Walaupun Yasmine melihat senyum tipis Elea dengan jelas barusan, tetapi ia tidak bisa tenang begitu saja. Sekalipun ia sendiri yang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi Yasmine pun jadi takut semuanya berjalan tidak sesuai harapan semua orang.
***
“Nanti mau makan di mana, Sayang?” tanya Adam, memecah keheningan yang menyelimuti kebersamaannya dengan Elea.
Tidak ada jawaban dari Elea. Perempuan itu sibuk mengamati kesibukan ruas jalan Jakarta dari balik kaca mobil. Lama kelamaan, fokusnya hilang dan pandangannya berubah kosong. Lalu, isi kepalanya ramai, membandingkan baik dan buruknya kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.
“El,” panggil Adam, disertai sentuhan lembut di punggung tangan Elea.
Perlahan, Elea memalingkan pandangannya dari jendela mobil. Kini, kedua netranya sibuk mengamati cincin perak melingkar di jari manis Adam. Sudah setahun lebih benda itu selalu menemani Adam, menjadi saksi bisu tawa dan segala perdebatan yang terjadi di antara mereka.
“Kamu sakit?” Tangan Adam berpindah ke dahi Elea. Ia berusaha membagi fokus antara jalanan dan Elea. “Badan kamu gak enak, ya? Hari ini banyak minum, gak? Tadi beneran makan siang, kan, gak bohong sama aku?”
Elea meraih tangan besar lelaki itu dan menggenggamnya erat. “Aku gak apa-apa, Dam. Aku baik-baik aja. Kamu gak usah khawatir berlebihan begitu.”
“Beneran gak apa-apa?” tanya Adam lagi, masih berusaha memastikan kekasihnya tidak pura-pura.
“Iya, bener.” Elea mengangguk kecil. “Tadi kamu nanya makan di mana, ya? Gimana kalau makan di apartemen aja? Nanti kita delivery.”
“Apartemennya masih kotor, Sayang. Besok baru mulai di bersihin.”
“Kamu bilang ada balkonnya. Kita makan di sana aja. Udah ada kursinya, kan?”
“Kita makan di restoran deket sini aja, ya? Angin malam gak baik buat—”
“Dam,” potong Elea seketika. “Sekali ini aja, tolong turuti kemauan aku. Aku capek debat karena hal yang sepele sama kamu.”
Lelaki 30 tahun itu membuang napas pelan. Dengan berat hati, ia pun berkata, “Ya udah kalau itu mau kamu. Kita makan di sana.”
“Gitu, dong.”
Tanpa mengatakan apa pun lagi, Elea melepaskan pegangan tangannya dengan Adam. Lelaki itu juga fokus menyetir tanpa berniat membuka pembicaraan baru. Entah mengapa, apa pun yang mereka bicarakan, selalu berakhir dengan perdebatan akhir-akhir ini.
Setelah dua hari tidak bertemu—karena Adam sangat sibuk di rumah sakit—akhirnya ia bisa mengajak Elea melihat calon hunian mereka hari ini. Mobil sport sedan putih Adam tengah meluncur menuju White Apartement, salah satu bangunan apartemen mewah di daerah Pondok Indah. Sayangnya, kesunyian lebih banyak mendominasi kebersamaan calon pengantin itu. Padahal, biasanya, Elea banyak bercerita mengenai kegiatannya seharian penuh dan Adam selalu memberikan respons tak kalah heboh.
Setelah berkendara setengah jam, akhirnya mereka sampai di area White Apartement. Adam menyerahkan sebuah kartu pada Elea ketika mereka dalam lift.
“Kamu harus nunjukin kartu ini ke penjaga di depan kalau mau masuk,” ucap lelaki itu.
Untuk beberapa saat, Elea hanya menatap benda persegi itu dalam diam. Lalu, ia mengambilnya dengan gerakan lunglai. “Oke.”
“Tapi, kalau mereka udah familiar sama wajah dan kendaraan kita, kayaknya bisa keluar masuk lebih dipermudah,” tambah Adam lagi.
Kali ini, Elea hanya mengangguk untuk menanggapi ucapan Adam. Lalu, ia membuka ponsel. “Kamu mau makan apa?”
“Samain aja sama kamu.”
Lagi, kesunyian yang menyelimuti keduanya. Walaupun tak ada sepatah kata yang terucap, tetapi kepala mereka amat ramai di dalam sana. Adam bertanya-tanya kapan situasi semacam ini berakhir, sementara Elea pun tak habis pikir mengapa dirinya bisa begitu sensitif akhir-akhir ini.
Begitu pintu apartemen terbuka, yang membelai indera penciuman Elea untuk pertama kali adalah aroma barang-barang baru. Begitu masuk, Elea langsung disambut dengan satu set sofa putih yang menghadap televisi berukuran 50 inci. Selain beberapa potret kebersamaan Elea dan Adam, deretan buku yang berjejer di tembok juga cukup menarik perhatian siapa saja yang datang.
Berbelok ke kanan, Elea langsung mendapati kitchen and bar. Tidak ada meja makan, seperti yang Elea minta. Ia maju beberapa langkah, lalu memeriksa ketiga pintu yang ada di hadapannya. Sebelah kiri adalah kamar mandi. Ruangannya memang tidak terlalu luas, tetapi Elea puas dengan tata letak cermin, wastafel, toilet, dan bathup di sana.
Di balik pintu sebelah kanan, ada sebuah kasur berukuran besar. Lagi, Adam menuruti kemauan Elea, membelikan lemari transparan untuk pakaiannya. Jadi, nanti Elea tidak perlu mengobrak-abrik seisi lemari untuk memilih pakaian. Di sampingnya ada lemari putih berukuran sedang, pasti di sanalah pakaian Adam akan ditata rapi.
“Ini kamar untuk anak kita,” ucap Adam sembari membuka pintu yang ada di tengah-tengah. “Kan, dulu kamu pernah bilang, selama kita belum punya anak, kamarnya dipakai untuk keluarga kita yang nginep aja. Jadi, aku sengaja beli kasur besar sama lemari. Supaya orang tua kita gak bingung kalau nginep di sini.”
Lidah Elea semakin kelu. Entah mengapa, rongga mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Adam ingat semua yang Elea minta. Bahkan, tanpa banyak bicara, ia mengabulkan semuanya tanpa protes sedikit pun. Namun, entah mengapa, Elea tidak merasakan kebahagiaan sebesar yang ia perkirakan.
“Sayang? Kok, diem aja? Ada yang gak sesuai sama kemauan kamu, ya?” tanya Adam dengan nada cemas.
Perlahan tetapi pasti, Elea menoleh. Ia tersenyum samar sembari menggeleng. “Enggak, kok. Semuanya sesuai sam apa yang aku mau,” jawabnya dengan nada lirih. “Makasih, ya, Dam? Kamu selalu berusaha untuk menuruti kemauan aku selama ini. Maaf, aku belum bisa menjadi calon istri yang baik buat kamu.”
“Hey ... kok, ngomongnya begitu, sih?” Adam mengusap rambut panjang Elea dengan penuh sayang. “Dengerin aku. Dari dulu sampai sekarang, kamu selalu menjadi pasangan yang baik buat aku. Kamu selalu kasih kebahagiaan yang besar buat aku. Kamu selalu bikin aku ngerasa bersyukur punya kamu dalam hidup aku.”
Hati Elea berdesir mendengar kalimat panjang Adam itu. “Makasih, ya? Makasih karena kamu selalu kasih cinta yang begitu besar buat aku.”
“Sama-sama, Sayang,” imbuh Adam sembari tersenyum lembut. “Udah gak marah lagi, kan?”
“Siapa yang marah?” sahut Elea dengan dahi berkerut.
“Kamu, lah.” Adam mencolek hidung mancung Elea. “Dari tadi aku gak lihat senyum cantik kamu. Sepanjang jalan juga kamu cemberuuut terus.”
Elea membalas ulah Adam dengan mencubit perutnya. “Kamunya nyebelin, sih! Perkara tempat makan aja kamu permasalahin. Kayak anak kecil, tahu gak?”
“Aku cuma mikirin kesehatan kamu, El. Aku gak mau kamu masuk angin kalau kita makan di—”
“Masih mau dibahas?”
Saat itu juga, Adam langsung melipat bibirnya dalam-dalam. Tidak, dia tidak mau beradu mulut lagi dengan Elea.
Perempuan itu berdecih pelan melihat tingkah calon suaminya. Kemudian, perhatian Elea teralihkan pada ponselnya yang berbunyi. “Makanan kita udah di depan, Dam. Katanya gak dikasih izin masuk. Abang ojeknya nunggu di depan pos satpam.”
“Ya udah, aku aja yang ke sana.”
“Nih, sambil bawa HP aku. Biar kalian gak sama-sama bingung,” ucap Elea seraya menyerahkan benda pipih kesayangannya tanpa beban sedikit pun.
Tanpa banyak bicara lagi, Adam pun menerima ponsel Elea. Dengan langkah panjang, ia memburu pintu utama apartemen, siap menyambut makan malam apa saja yang dipesan kekasihnya saat di lift tadi. Namun, baru saja tubuh adam melewati daun pintu, langkahnya langsung terhenti ketika ponsel Elea kembali berbunyi. Tanpa bisa menahan diri, Adam pun membuka pesan yang baru saja masuk itu.
Rendi
El, ini form yang lo minta kemarin. Baca baik-baik, ya. Chat gue kalau lo udah pegang keputusan pastinya.
Dengan segudang tanda tanya yang bercokol di kepala, Adam membuka dokumen yang dikirim oleh Rendi. Matanya langsung membulat begitu melihat judul yang tertera di kepala dokumen. Saat itu juga, ia lupa dengan makan malam. Yang Adam ingat hanyalah ... ia harus menemui Elea dan menanyakan tujuannya meminta dokumen itu pada Rendi.
“Kok, cepet banget, Dam?” tanya Elea yang baru saja keluar dari kamar mandi. Alisnya bertaut ketika mendapati sorot mata tajam Adam yang tertuju padanya. “Dam, kenapa?”
Dengan sekali entakan, Adam menunjukkan tampilan layar ponsel ditangannya pada Elea. “Bisa kamu jelasin maksud dari dokumen ini.”
Elea pun mengalihkan pandangan ke benda pipih itu. Wajah terkejutnya berubah lebih santai begitu setelah tahu yang terjadi bukanlah masalah besar. “Oh, itu?” sahut Elea sembari berjalan menuju sofa. “Itu formulir pendaftaran buat jadi model di New York.”
“Aku tahu, El. Aku bisa baca, kok. Tapi kenapa kamu butuh formulir ini?” desak Adam sembari mengekori Elea.
“Kamu inget sama desainer kesukaan aku? Peteryne Lee itu, lho. Dia bakal ngerancang banyak busana untuk musim dingin dan fashion show akan di adakan di New York. Nah, aku mau daftar untuk jadi modelnya,” terang Elea dengan begitu enteng.
“Kamu mau lanjut kerja setelah kita nikah nanti?”
“Of course I will,” balas Elea, tanpa memerlukan waktu untuk berpikir barang sedikit pun.
Adam mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu pandanganya tertuju pada Elea. Tidak ada lagi kehangatan yang terpancar dari kedua netranya. Tatapan Adam begitu tajam dan penuh amarah. “Terus aku gimana?” tanyanya dengan nada yang begitu rendah.
“Kamu gimana apanya?”
“Kan, kamu tahu, aku mau punya istri yang diem di rumah, gak kerja. Aku juga udah minta kamu buat berhenti jadi model, kan? Kita udah pernah bahas ini, lho, El. Kenapa malah jadi begini?” Adam tampak frutrasi mengatakan setiap ungkapan hatinya. Walaupun dadanya sudah bergemuruh sejak tadi, tetapi ia berusaha menekan amarah sekuat tenaga.
Elea bungkam. Sorot matanya juga ikut berubah, menjadi begitu dingin. Sepertinya perdebatan kali ini akan menguras tenaga lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya.


 muizzafarkadain
muizzafarkadain









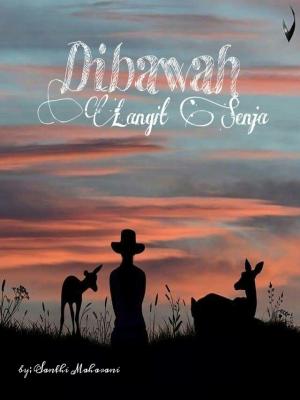
Oh ternyata Yasmin cuman anak sambung toh....dan ibu tirinya memberikan perlakuan yang berbeda
Comment on chapter 1. Kehidupan Yasmine