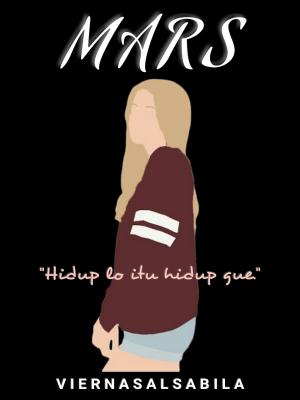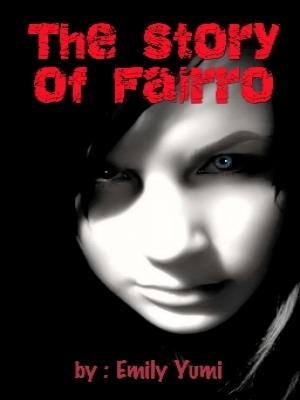[Este's pov]
Sepetmber 7th, 1997
Penyebab utama aku tidak pernah bersemangat setiap berlibur bersama Ayah, Bunda, dan Dorothea, karena tawa dan segala kesenangan yang berlangsung akan segera pudar. Sebagaimana kedua orangtuaku mengiming-imingi anak perempuan kecil berusia dua tahun untuk berpakaian rapih layaknya anak-anak lain yang akan bertamasya sekeluarga ke kota kecil. Menonton parade, mencicipi semua jenis makanan ringan di pinggir kota, meniup gelembung sabun, bersepeda di pagi hari. Semua itu telah terbayang jelas di dalam benakku. Satu hal lagi yang membuat liburan ini berkesan karena bertepatan dengan hari ulang tahunku!
Sampai mobil yang dikendarai pria—yang dulunya kupanggil Bapak—berhenti di depan sebuah gedung putih pucat yang dihalangi gerbang hitam berkarat nan kokoh dengan berbagai tanaman liar yang menjalarinya. Ibu menggandeng tanganku dan menyuruhku untuk berteman baik dengan anak-anak yang sedang bercanda gurau dan bermain di halaman tempat itu. Berbekal Bapak dan Ibu yang membuang brokoli dari nasi jika aku berhenti menangis, maka aku harus mencoba dekat dengan anak-anak itu supaya waktu berlibur lebih cepat dirasakan.
Naluri seorang anak kecil dengan bahagia akan menceritakan rencana besar yang sudah disusun sejak ia bangun tidur pagi-pagi buta tadi pada teman sebayanya. Saking asik bermain dan mengobrol, seorang wanita paruh baya menghampiriku dengan raut wajah resah. Tidak banyak yang kuingat, wanita bernama Bu Ratih itu melempar pandangan ke arah mobil Bapak dan Ibu yang terparkir di depan gerbang. Tanpa menunggu sepatah kata pun keluar dari mulutnya aku berderap sekencang-kencangnya, membuka pintu kursi penumpang tengah, tetapi nihil.
Aku tidak menemukan siapa-siapa. Hal yang paling tidak dimengerti oleh seorang anak yang akan diajak berlibur oleh orangtuanya, adalah ketika wanita asing menggenggam kedua tangan mungilnya dan berujar pelan selepas menghela napas.
“Nanti kita pergi jalan-jalan ya, Este....”
“Este, kamu masih demam?”
Kedua kelopak mataku langsung terbuka lebar mendengar nada suara khawatir di sebelahku. Tampak Dorothea yang sudah lengkap dengan kaus merah muda dan rok tulipnya menatapku dengan kedua bibir mencebik dan dahi berkerut. Kedua mata kakak perempuan angkatku itu sudah tidak lagi repot-repot manahan air matanya. “Kita kan sudah janji akan kembaran saat nonton di bioskop....” isak Dorothea sembari melirik nanar roknya.
“Dorothea! Este perlu istirahat, jangan diganggu adiknya, dong!” Bunda berseru kencang dari lantai bawah, tetapi hal itu sama sekali tidak membuat Dorothea menghilang dari pandanganku. Aku menggumamkan kata maaf lirih, dan anak perempuan yang lahir hanya lebih tua beberapa bulan dariku itu masih menunduk—enggan turun menyusul Ayah dan Bunda yang pasti sudah siap berangkat ke mal.
“Nanti malam aku akan jadi Si Buruk Rupa,” ucapku akhirnya mengalah berperan sebagai tokoh laki-laki sampai Dorothea mengangkat wajah dan tersenyum cerah. Setiap bersandiwara berdua di kamar, aku selalu menang suit hingga terus mendapatkan peran sang tokoh utama putri.
“Kali ini jangan ingkar janji lagi, ya!” Kusambut kelingking Dorothea yang teracung di depan hidungku dan terpaksa mengangguk, meskipun kepalaku masih terasa sedikit pening. Beberapa saat setelah Dorothea pergi meninggalkan kamarku, terdengar suara deru mobil di halaman yang semakin menjauhi pendengaranku.
Kutarik selimut tebal hingga menutupi hidung yang tidak lagi tersumbat parah seperti semalam sebelumnya. Baru saja aku akan menutup kembali kedua mata, suara ketukan di pintu menahan niat untuk tidur lagi siang itu. “A-ayah?!” pekikku langsung terduduk di atas kasur. Pria berusia tiga puluh tahunan yang seluruh helai rambutnya hampir memutih tersenyum kecil dan mendorong pintu kamarku dengan kakinya sambil membawa semangkuk—seperti sup—yang masih mengepul hangat.
“Este sudah tidak pusing lagi?” Pertanyaan Ayah langsung membuatku mengurut pelipis sambil mengaduh kesakitan. Tidak seperti Bunda dan Dorothea yang panik saat mengukur suhu tubuhku, Ayah meletakkan mangkuk di atas meja belajar dengan hati-hati sebelum mendirikan posisi bantal di kepala ranjang supaya aku bisa makan di kasur sambil bersandar dengan nyaman.
“Este tidak apa hanya mendengarkan cerita film dari Dorothea?”
“Tidak apa, Yah,” jawabku setelah menyeput kuah sup tahu buatan Ayah.
“Ya, sudah ... ayah pikir kamu akan merasa kesal karena tidak bisa menyaksikan secara lang--”
“Ayah kenapa tidak jadi pergi ... sama Bunda dan Dori?” Kupotong perkataan pria yang duduk di hadapanku. “Maaf, karena Este sakit ya? Tapi kan sudah ada Bibi yang menjaga.”
“Dori tidak ingin Este bosan, dan Ayah juga tidak terlalu suka menonton di bioskop,” tutur pria itu menimbulkan gurat keheranan yang nyata di wajahku.
“Kenapa?”
“Nanti kan juga ditayangkan di TV!” Aku baru menyadari yang Ayah bilang itu tidak salah. Film dinosaurus yang kutonton dengan Dorothea tahun lalu, kini sudah sering berlalu-lalang di suatu stasiun TV.
“Tapi kalau di bioskop kan tidak ada iklan, Yah,” debatku.
Ayah turut membalas, “Di bioskop tidak bisa menonton sambil bermain monopoli!” Aku tertawa renyah mendengar permainan kesukaanku dan Ayah setiap kami menonton acara TV bersama di ruang keluarga. Bunda dan Dorothea adalah tipe yang harus fokus pada alur cerita, sedangkan aku dan Ayah sudah terlalu percaya diri menebak akhir dari suatu film dan melalukan kegiatan lain, sekalipun perkiraan kami terkadang meleset.
“Saat pergi ke pantai, Este juga lebih banyak tidur siang di bawah parasol.” Ayah mengungkit liburan keluarga kami bulan lalu di kampung halaman tempat Kakek dan Nenek Dorothea tinggal. Segala sesuatu yang aku rasakan sekarang—rumah, keluarga, liburan, sekolah—seharusnya dimiliki Dorothea seorang.
“Aku masih tidak percaya ... aku punya keluarga dan—semua ini, Ayah....” Dengan suara bergetar aku menunjuk kerlap-kerlip bintang yang dapat menyala saat lampu kamar dimatikan. Semua terekam jelas dalam ingatanku, Dorothea dan aku digendong Ayah dan Ibu yang berdiri di atas kasur supaya tangan kami mampu menggapai dan menempelkan bintang-bintang itu di langit-langit kamar.
“Percayalah, Este.” Ayah mengangkat tangan dan mengusap lembut puncak kepalaku. “Ayah, Bunda, dan Dori percaya Este adalah hadiah Tahun Baru terbaik...!” Suara pria dewasa yang selama ini kuhormati terdengar bergetar dengan kedua mata yang mulai memerah menahan tangisan yang akan tumpah membasahi sepasang rahang tegasnya. “Ayah, Bunda, dan Dori tidak minta apa-apa, selain Este selalu percaya sama kami....”
Setelah selesai makan dan Ayah sudah menyingkirkan mangkuk sup beserta meja lipat sebagai tatakannya, aku bangkit dan menghambur ke beliau dengan kedua tangan mendekap erat tubuh besar pria yang memuji hiasan bolu kukus buatanku di panti asuhan tiga tahun lalu. Mendengar isak tangis penuh haruku di balik bahunya membuat Ayah tertegun sejenak sebelum mengusap punggung kecilku dan sesekali menarik napas menghilangkan getaran dalam suaranya yang berulang kali membisikkan kata ‘Este itu anak Ayah, anak Bunda, adik Dori.’
Ya. Aku anak Ayah dan Bunda, adik Dori. Kami selamanya akan menjadi keluarga. Tidak peduli takdir apa yang Tuhan berikan nanti, tidak ada yang bisa menghapus ikatan ini semudah itu.
September 7th, 2008
Cahaya matahari semakin turun, menghilang dari bumi. Untuk kesekian kalinya dalam balutan gaun putih yang menutupi lantai, dan rambut hitam terkepang menjuntai dari belakang telinga lalu tersampir di di bahu kiri, aku setia duduk menunggu. Namun, teruntuk hari ini aku mendapatkan imbalan yang sangat berarti. Semua orang datang untuk memperingati ulang tahunku. Hal ini mungkin terdengar aneh, tetapi sudah menjadi ritual bagiku, Dorothea, dan Ivy untuk maraton film bersama, dan menyantap masakan buatanku.
Sayangnya kali ini, kedua tanganku tidak bisa membantu Jovie dan Ezra menyiapkan bahan-bahan masakan. Aku hanya mampu tertawa kecil akan keteledoran Jovie memecahkan telur, atau mendengus geli melihat sifat pemarah Ezra yang tidak suka konter tempat memasaknya dipenuhi perabotan kotor. Kemudian, selayaknya Gustav di zaman SMA, Ivy akan menghasut Dorothea membantunya mengunci pintu dan membalik papan penandanya mengisyaratkan toko sudah tidak lagi menerima tamu.
Selagi menyingkirkan meja dan kursi, kulihat Ivy berkali-kali melempar tatapan ke Dorothea yang memunggunginya. Aku menjadi merasa bersalah telah membebani sahabatku itu dengan konflik pribadi rumah tanggaku.
“Katakan saja aku yang menyuruhmu, Vy! Katakan! KATAKAN!” Napasku terengah-engah usai berteriak sekencang-kencangnya di samping telinga Ivy. Percuma saja. Kalau aku bisa mengira Louis akan meracuni wineku malam itu, sekarang aku pasti dapat meluruskan segala prasangka dan ketidaknyamanan antara dua orang di hadapanku ini.
“Dorothea,” panggil Ivy. Kulirik kakak angkatku dan meremat jari-jariku cemas. Kami berdua sangat mengenal Augustine Howard, ia tidak akan menyebut nama orang sesuai akta kelahiran jika sedang tidak ingin membicarakan hal yang sangat penting. Seperti dugaanku, Dorothea berhenti menggeser meja, tetapi tidak kunjung membalik tubuhnya. Hanya gumaman kecil sebagai tanggapan berarti dari mulut Dorothea.
“Este,” sebuah suara pria terdengar samar memasuki indra pendengaranku. Kuhiraukan hal mistis yang sudah biasa kurasakan sejak kematianku di toko ini. Hubungan Dorothea dan Ivy tidak boleh berakhir karena diriku.
“Aku ... membunuh Louis, saat kubilang aku tidak singgah di warung Hafiz—aku berbohong, Louis juga ada di sana dan aku memukul kepalanya dengan botol kaca.” Usai pengakuan Ivy, mataku tidak bisa terlepas dari Dorothea yang mulai menoleh dan balas menatap sahabat sekaligus kekasihnya itu sendu.
“Kenapa ... kamu baru mengatakannya sekarang?”
“Aku terlalu takut mengakuinya di saat kamu belum memberi jawaban pasti ... untuk tinggal bersamaku....” Kedua obsidian kelam Ivy sudah basah dan kedua tangannya yang gemetar terkepal erat, menahan diri untuk tidak menghambur ke dalam pelukan Dorothea. Sahabatku itu sepertinya sudah siap dengan segala keputusan baru yang akan kakakku ambil nanti. “Dharma mengetahui segalanya, dan yang kumaksud segalanya ... Dharma bahkan sudah menyelidiki kebenaran perselingkuhan Louis dan Marjorie...,” tambah Ivy tergagap.
Kali ini aku pun turut memandang Ivy yang berjalan meraih tas tangannya di atas meja kasir, lalu mengeluarkan gelas bekas wine yang kuminum, dan kotak tempat rokok milik Louis. “Ini ditemukan di brankas Louis sehari setelah kematiannya,” ucap Ivy sembari menyodorkan kedua barang bukti itu pada Dorothea.
“Jangan terlalu lama mencium dasar gelas itu, Dharma bilang aroma petisida yang kuat dapat merusak pernapasan....”
Aku tertawa hambar mendengar penjelasan teman Ivy yang berprofesi sebagai detektif itu. Malam dimana aku menangis seperti anak kecil, merasakan kembali hadirnya keraguan dari pedihnya api cemburu melihat kedatangan Marjorie membutakan akal sehatku. Kini setelah aku hanya dikenang sebagai nama, baru kuingat jelas aroma pekat nan menyengat yang sebenarnya sudah terhirup saat menyorongkan gelas kaca itu hingga wine di dalamnya lolos masuk ke tenggorokanku.
Dorothea membuka kotak rokok dan menarik secarik lipatan kertas yang cukup tebal. Setelah membuka dan meratakan bagian yang berkerut, kedua manik mata kakakku melebar tidak percaya dengan isi kertas itu. “Louis ingin menyerahkan warisan miliknya untuk Majie, tapi tidak ... dengan rumahnya?”
Ivy jelas sudah membaca surat pribadi itu lebih dulu karena ia menimpali keterkejutan Dorothea, “Dengan jaminan Marjorie tidak lagi mendatangi Ibu Louis, dan ... Este—“ Ivy membekap mulut, kesedihan dan penyesalan mendalam pecah sampai sahabatku itu berlutut di lantai toko. Isak tangis Ivy terdengar sangat memilukan. Setelah memasukkan kembali gelas dan tempat rokok kembali ke tas tangan Ivy, Dorothea merengkuh Ivy erat dan terus mengatakan semuanya akan segera terlupakan. “Kamu melakukannya untukku dan Este...! Sekarang biar aku yang merahasiakan semua ini, Vy, bagi semua bebanmu padaku....” Dorothea menangkup kedua sisi wajah kekasihnya dan langsung menyatukan kedua belah bibir mereka sampai suara tangisan Ivy seketika teredam.
“Este,”
Aku tersentak di tempat sambil menurunkan arah tatapanku ke bawah dimana sebuah tangan menyelipkan jari-jarinya dengan milikku. Pandanganku naik dan langsung melihat wajah orang yang meracuni minumanku—seseorang yang tidak pernah ingin membicarakan masa kanak-kanaknya, seseorang yang lebih memilih memeluk dan menciumku daripada menjelaskan dengan kata-kata, seseorang ... yang mengikat sumpah suci bersama.... Sama sepertiku, ia mengenakan pakaian yang ia kenakan saat kami menikah.
“Kita tidak perlu takut tua, Este!” Louis memaksakan tawa yang menyayat hati karena setitik air mata jatuh dari kedua mata pria itu yang melengkung seperti bulan sabit. Aku masih terdiam menunggu kata-kata yang sekiranya akan terlontar lagi dari mulut suamiku. “Satu-satunya penyakit yang kurasakan sampai botol itu menghantam kepalaku...,” ujar Louis mengangkat tanganku yang ia genggam dan diletakkan di dadanya yang sudah tidak lagi berdetak. “Kamu tidak ada di sisiku, padahal kita sudah janji ... sehidup—semati....” Air mata yang kutahan kini tumpah ruah meluluh lantahkan rasa cemburu, keraguan, dan dendam yang dahulu menumpuk, menghempas rasa cinta yang telah tumbuh sejak kami meninggalkan masa remaja bersama. Kedua belah bibir Louis kembali terbuka dan berkata, “Aku juga tidan bunuh dir--”
“Lou,” panggilku pelan. “Kamu tidak perlu mengulang apa yang sudah kudengar dari Ivy....”
Louis merengkuh pinggang dan bahuku, lalu menuntun istrinya ini menembus pintu toko untuk pertama kalinya. “Banyak hal yang harus kamu ketahui, tentang Kak Majie ... dan Josh--!”
“Tapi kita harus pulang sebelum subuh!” selaku menimbulkan kerutan di dahi Louis. Aku tidak bisa menahan gelak tawa ketika lanjut berkata, “Ada anak laki-laki penggemar nomor satu blueberry sandwich!”
“Hei, itu kan juga kesukaanku!” timpal Louis tidak terima. Aku mengangguk semangat sebagai balasan dan menambahkan sosok anak itu adalah pengalih utama kekesalanku selama menunggu sendirian di toko.
“Kamu tidak perlu kesal lagi,” imbuh Louis sembari mengecup punggung tanganku dan semakin mendekap erat diriku ke dalam pelukannya di bawah lampu-lampu jalan raya dan deru kendaraan yang berlalu lalang melewati kami.
Detik-detik saat pandanganku mengabur, teriakan suamiku yang meminta pertolongan, diselingi wajah cantik tanpa cela Marjorie yang tampak sangat berbeda denganku ... kupikir aku selalu ditakdirkan untuk diberikan harapan palsu. Ditakdirkan untuk sendiri, seperti ketika orangtua kandungku berbohong di hari ulang tahunku.
Ya, Tuhan, biarkan aku menarik semua doa dan sumpah selama aku terjebak dalam kenangan pahit dan tempat ini. Aku tidak ingin kehidupan lain. Biarkan aku membeku dan tenggelam bersama orang yang kucintai di tempat dimana sepasang kekasih mengakui rahasia tergelap mereka, tempat dua orang mulai saling ingin mengerti satu sama lain, tempat seseorang bertemu persinggahan baru bagi hatinya yang telah patah, tempat bagi seseorang bisa menikmati makan siang bersama kedua neneknya tanpa memikirkan masa lalu ... tempat dimana segala bentuk cinta dan luka dirasakan dan disimpan dalam kapsul waktu sebagaimana kenangan berharga terus membayangi perjalanan hidup seseorang.


 urmr9teen
urmr9teen