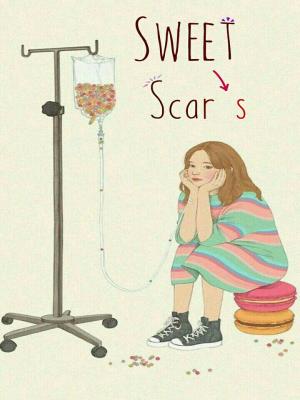[Marjorie’s pov]
January 1st, 2001. 11:00 pm.
“Ma-Majie...?”
Bu Cinthya, pelatih tari sejak aku masih kelas 1 SD sekaligus pemilik sanggar yang kudatangi malam itu, menatap kehadiran cucu sahabat masa kecilnya dengan sangat kebingungan—bercampur iba. Aku hanya membawa satu tas, telepon genggam di tanganku, piyama, dan sepatu yang tadi sore juga kukenakan.
Wanita yang sudah memasuki usia enam puluh tahun itu merangkul kedua bahuku. Kami berdua memasuki rumah utama tanpa membuka suara. Aku yang belum siap membagi cerita hidupku yang menyedihkan, atau Bu Cinthya yang juga tidak tahu harus bagaimana menghiburku. Berdasarkan cerita Oma, Bu Cinthya ini tidak memiliki cucu kandung. Ia hidup sendiri tanpa suami, anak, tetapi setia hadir dan membantu keluarga besar saat mereka membutuhkan.
Lampu-lampu dari setiap ruang dari sanggar Bu Cinthya telah dipadamkan, hanya lampu kuning terasnya yang dibiarkan menyala. Aku yang sejak tadi memandanginya dari balik pintu kaca ruang tamu terhenyak saat Bu Cinthya kembali degan secangkir cokelat panas dan sekaleng kecil kue kering. “Sudah makan malam?” Kepalaku menggeleng kuat, tetapi perutku mengkhianati cara pikirku dan seenaknya berteriak tanpa bisa kutahan. Bu Cinthya terkekeh tampak sangat gemas dengan sikapku, mungkin mengingatkan beliau dengan keponakannya.
Setelah menyesap kehangatan manis dari cangkirku, aku memberanikan diri meminta izin, “Maaf sudah merepotkan, Bu ... saya tidak tahu kapan bisa pulang, karena Ibu dan saya--”
Bu Cinthya menggenggam tanganku erat dan tersenyum teduh membalas ekspresi memelasku. “Ama sudah menelepon saya, tinggallah di sini selama yang kamu mau,” ujarnya menenangkan.
“Oma memang satu-satunya orang yang tulus menyayangiku....”
“Jangan bilang seperti itu,” ucap Bu Cinthya membuatku tersadar dari lamunan. Astaga, kupikir aku mengatakan itu di dalam hati. Tanpa menunggu respon dariku, sahabat karib Oma lanjut berbicara, “Saya pikir, saat mengusir Majie, Ibu kamu sudah memperkirakan tujuanmu berlari adalah tempat saya.” Bu Cinthya mengusap puncak kepalaku selembut tepukan hangat Oma setiap aku tidak bisa tidur saat tengah malam. Ia mengatakan padaku untuk tidak mengkhawatirkan hari esok tentang sekolah ataupun hubunganku dengan Oma. Bu Cinthya bilang aku bisa mengunjungi Oma setiap Sabtu atau Minggu dimana Ibuku biasanya akan pergi menginap di rumah teman.
“Tapi ... aku sudah berkata jahat, aku mempertanyakan—kenapa aku dilahirkan ...di rumah it...!” Aku bahkan tidak mampu melanjutkan apa yang kukatakan dengan berani pada Ibu sejam lalu. Baru kusadari, Oma juga berada di sana ... bagaimana bisa aku tega?
“Apa Ama tidak pernah bercerita tentang rumah itu?” Bu Cinthya kembali menarikku ke alam sadar. Aku hanya mampu memandangnya keheranan. “Rumah itu sepenuhnya masih atas nama Opa Majie, semasa Arnold hidup, Ama selalu merasa terkekang dan tidak bebas. Sampai Ama menjadi janda—satu-satunya alasan ia masih menetap di rumah itu karena Ibumu. Ama ingin melindungi Ibumu, pewaris rumah itu, dari sanak keluargamu yang lain.” Bu Cinthya menyandarkan punggungnya ke kepala sofa sambil memandang ke depan dengan senyum manis dan suara sendu, “Padahal sejak lulus kuliah Ama selalu ingin tinggal dan menari sepanjang hari bersama saya.”
Hatiku sangat terenyuh mendengar perkataan wanita lanjut usia yang duduk bersebelahan denganku itu. Aku juga ingin memiliki persahabatan yang langgeng sampai akhir hayatku. Sahabat seumur hidupku.
January 1st, 2002
“Jadi Kak Majie sudah tahu sejak kita MOS?”
Usai menyelesaikan tugas piketku, Louis datang dan menutup pintu kelas rapat. Gurat wajahnya terlihat marah, tetapi juga seperti ingin menangis. Aku bahkan tidak pernah meneteskan air mata setiap Oma dan Bu Cinthya menceritakan masa kanak-kanak dan perundungan yang dialami Ibuku semasa remaja, apalagi adik tiri yang tidak sedarah.
“Sudah,” sahutku tenang. Kutunggu kata-kata selanjutnya dari mulut teman sekelasku yang sejak tadi enggan menatap lurus ke kedua netraku setelah mengetahui kami berdua terlahir dari satu Ayah. Baguslah, Louis masih tahu diri dibandingkan Ibunya.
Tubuhku sedikit berjengit di tempat saat mendadak Louis melangkah mendekat dan menggenggam satu tanganku dengan kedua telapak tangannya. Ia masih tidak ingin menatapku.
“Aku bukan Ibuku, Kak Majie ... tolong jangan membenciku....”
Kenapa? Kenapa Louis begitu ingin dekat denganku? Padahal ia punya Ibu yang sangat menyayanginya, kekayaan yang berlimpah, dan ... seorang Ayah.
Tanganku yang tidak digenggam Louis mengepal kuat membayangkan masa kecil laki-laki ini yang pasti dipenuhi berbagai kenangan bahagia. Tidak sepertiku. Kuhabiskan masa kecil dengan menjadi anak idaman semua orang. Membanggakan Ibuku yang bekerja sendiri untuk menghidupiku dan Oma, tidak pernah membiarkan murid lain meraih ranking satu di kelas, memenangkan semua perlombaan tari, belajar Bahasa Inggris dan Bahasa asing lainnya supaya aku diterima di institusi bergengsi.
Semua itu agar Ayah pulang. Supaya Ayah sadar, akulah anak yang berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatiannya.
Tapi Louis? Akademiknya di bawah rata-rata, ia punya teman hanya karena status sosial belaka, dan tidak punya kemampuan non-akademik lain yang patut diperhatikan. Kenapa justru hanya ia yang memiliki kesempatan menyambut Ayah di rumah? Ini tidak adil!
Indra pendengaranku menangkap samar tawa riang Hannah. Ia pasti telah berhasil membujuk Augusta dan Dorothea pulang bersama kami. Tetapi, kalau mereka melihat Louis di sini....
Setitik ide brilian melintasi pikiranku. Ya, Louis, kamu memang bukan Ibumu yang hanya pintar membual dan bergosip.
Kulepas ikatan dan mengacak rambutku asal. Kemudian, dengan sekuat tenaga aku meninju rahangku sendiri, sebanyak tiga berturut-turut. Hingga darah segar menetes dari ujung bibir. Kulirik Louis yang tampak syok dengan kondisi genggaman tangannya yang mulai merenggang. Kucengkeram balik tangannya, lalu kutempatkan pada tulang pipiku yang mulai memar. “Aku diusir Ibu dari rumah,” pernyataanku semakin membuat Louis terpaku. “Jangan berkata seolah kamu akan terus di sisiku!” Kudorong salah satu kursi yang telah kususun di atas meja hingga terdengar dentuman keras yang beradu dengan lantai kelas.
Bersamaan dengan pintu kelas yang digebrak, kugerakkan lengan Louis yang lemas untuk menampar sisi wajahku yang tidak memar sampai menimbulkan suara keras yang mengejutkan tiga siswi di ambang pintu. Kepalaku kembali merasakan sakit yang luar biasa karena hantaman bertubi-tubi dari tanganku sendiri dan Louis. Hannah menjerit nyaring meminta pertolongan, Dorothea berseru memanggil Augusta.
Hal terakhir yang kulihat, Louis tersungkur di lantai. Augusta menarik kerah Louis dan membuat wajahnya nyaris serupa dengan kondisiku.
July 14th, 2008
Louis yang bermulut tajam. Louis yang selalu memperhatikan Marjorie dari jauh. Louis yang selalu setia pada sang kakak tiri, bahkan sampai ajal menjemput nyawanya. Citra itu sukses kubangun sejak kami menempuh pendidikan di sekolah menengah atas yang sama. Sejak saat itu Ayah mulai memperhatikanku, ia bahkan memanggilku ‘Nak’ saat kami dipertemukan di ruang Kepala Sekolah.
Jika Ayah bisa menghiraukan kehadiranku di hidupnya, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Tentu saja aku bisa. Aku bukan lagi tokoh dalam drama murahan yang selalu dikasihani.
“Lima menit lagi.” Suara sok memerintah dari kepala sipir di tahanan membuyarkan lamunanku. Sedikit tidaknya aku berterima kasih pada bapak itu. Kutatap pria sekaligus teman SMA yang mengunjungiku sembari menunjukkan kelahiran anak baru dari kakaknya tadi. Namun, tidak bertahan lama saat kudengar kabar yang dibawa Joshua bahwa Ibu Louis sudah mengurus surat tanah atas nama mendiang putra tunggalnya, dan akan mendermakannya ke anak-anak panti asuhan.
“Penyesalan memang selalu datang di akhir,” sahutku, tidak peduli. Sejak awal aku memang tidak tergiur dengan kemewahan semata itu. Saat berkuliah sambil bekerja pun aku menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan usaha Ayah, Ibu tiri, dan Louis.
“Apa yang kamu kejar?” Pertanyaan mendadak Joshua membuatku mendongak menatap sorot matanya yang sangat serius ingin mendengar jawabanku. Lebih tepatnya, alasanku memasuki kehidupan Louis dan Este. Tidak sulit menyimpulkan Joshua memiliki perasaan padaku sejak dulu. Namun, aku tidak percaya pada sebuah hubungan yang membuat dua orang dengan latar belakang dan cara berpikir yang berbeda berada di satu rumah. Hal romantis seperti itu tidak terjadi di rumahku yang dulu, maupun rumah Louis yang diceritakan langsung dari mulutnya ketika ulang tahun ke-17.
“Aku tidak ingin menjadi tokoh utama yang menyedihkan.” Tentu saja Joshua tidak memahami perkataanku. Aku sangat pandai menutupi kehidupan pribadi maupun luka dalam yang tidak akan pernah sembuh. Berkali-kali Joshua menanyakan hal buruk apa yang kualami selama menimba ilmu teater di Akademi Seni, sehingga aku melampiaskannya ke orang lain. Yah, Joshua tidak sepenuhnya salah. Pelampiasan adalah caraku bertahan hidup. Jadilah seseorang yang mereka takutkan.
“Apa Este pernah berbuat salah padamu?” desak Joshua tidak menyerah. Entah apa yang ia inginkan dariku.
“Waktu besuk habis.”
Walaupun tidak memberikan jawaban pasti. Pikiranku dibayangi pertanyaan temanku itu seiring salah satu sipir membawaku menyusuri lorong menuju sel tahanan.
Kenapa aku melakukan itu pada Este?
Karena ia menghalangi rencanaku menghancurkan Louis. Este memiliki Dorothea yang selalu menemani dan memahami dirinya. Augusta yang tidak perlu berpikir untuk menjaga kedua kakak beradik itu. Este memiliki segalanya, kenapa ia harus mempertahankan orang tidak berguna seperti Louis?
Yah ... ia membuat rencanaku sedikit terganggu. Namun, aku juga tidak menyangka Louis akan tega melakukan ‘hal itu’ pada Este. Louis meninggalkan istri yang sangat mencintainya itu di tempat dimana aku meninggalkan adik tiriku untuk menempuh pendidikan di negara lain.
“Ck, membusuklah di neraka, Louis,” gumamku lelah sebelum tidur telentang di atas alas tidur tipis. Memejamkan mata sembari menghitung hari dimana aku bebas dan kembali bertemu dengan Oma dan Bu Cinthya.


 urmr9teen
urmr9teen