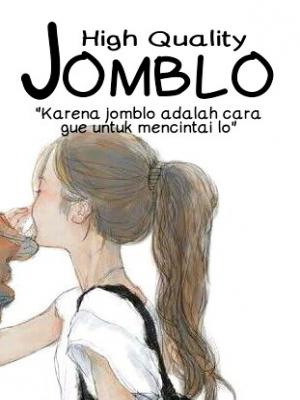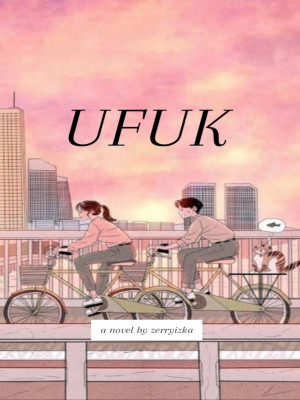Jantungku berdegup kencang, saat nafas mas Arsha menerpa pipi kananku. Sungguh, kami belum pernah sedekat ini. Jika malam ini adalah momennya, maka aku siap. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan satu hal dulu.
Sebelum bibir mas Arsha menyentuh bibirku, ku tahan wajah mas Arsha dengan menggunakan kedua tanganku. Mas Arsha menatapku bingung, seolah bertanya ‘ada apa?’.
Kuberanikan diri untuk menatap matanya lamat-lamat “Mas nggak harus melakukan ini hanya karena ingin bersaing dengan laki-laki lain, apa mas berniat untuk nggak menceraikan Sheila?.”
Mendengar pertanyaanku, kabut hasrat di mata mas Arsha menghilang, mata itu kini terlihat menerawang jauh. Tanpa sepatah katapun, dia pergi begitu saja meninggalkanku dengan harapan yang pupus. Sia-sia aku berharap lebih. Nyatanya, malam ini tak berarti apa-apa. Sekarang, semua terlihat nyata. Sama seperti kata Rifan, meskipun tanpa cinta, tapi cemburu itu tetap ada. Alasan mengapa mas Arsha mengikuti insting laki-lakinya, adalah karena Mas Arsha punya jiwa kompetisi, bukan karena dia mulai mencintaiku.
~
Pagi harinya kami benar-benar dilanda kecanggungan yang haqiqi. Jika biasanya kami semanis pasangan suami istri sungguhan, maka kali ini berbeda, mas Arsha mendiamkanku. Dia terlihat tak ingin terlibat percakapan apapun denganku.
“Mas pulang jam berapa semalam?.” Pada akhirnya aku mencoba meruntuhkan egoku, daripada nasi goreng dihadapanku ini terasa hambar.
“Jam 4 pagi.” Jawabnya singkat, tanpa perlu menatapku.
Aku menghembuskan nafasku perlahan, mencoba menghilangkan rasa sesak yang menyeruak di dada “Mas semalam ngga tidur?.”
“tidur.”
“berapa jam?”
“Sejak saya pergi dari sini.” Saya? Bukankah kami menyebut diri kami sebagai ‘saya’ saat berinteraksi di kampus? Tapi inikan di rumah. Mas Arsha kenapa?
“Loh, mas tidur dimana?.”
“Teras kosannya Dera.”
Jleb!
Hatiku benar-benar sakit saat ini, kejujuran mas Arsha menghancurkan segala pemikiran positif yang aku punya.
“Mas kan punya rumah, kenapa harus menginap dirumah orang lain?.”
“Perlu kamu ingat. Ini hanya rumah, bukan rumah tangga.” Sarkasnya.
‘Kalau yang kita bina ini hanya rumah dan bukan rumah tangga, lalu aku ini apa buatmu mas? Furniture?’ Seandainya saja aku punya hak untuk mengatakan itu.
~
Duduk di bawah pohon yang berada disamping lapangan basket memang membuatku setentram ini. Anginya sejuk, membuatku melupakan laraku walau hanya sekejap. Aku kesepian, entah kapan sahabat karibku akan kembali dari kampung halamannya.
“Hei Shei.”
Aku menoleh ke sumber suara, dan memberikan seulas senyum tipis “Eh kak, ada apa?.”
Rifan mendudukan dirinya disampingku “Boleh duduk sini kan?.”
“Udah duduk baru ijin, ya ngapain kak.?”
Rifan berdiri “Ya kalau ngga boleh, saya bangun lagi nih.”
Aku tertawa “Ya nggak gitu juga kali kak, yaudah duduk lagi sini.”
Rifan kembali duduk, menaruh bola basket yang tadi ia pegang ke sampingnya “Saya punya kenalan, kamu mau kenal?.”
Aku tertawa terbahak-bahak, karena perkataannya yang terdengar aneh di telingaku.
Rifan menatapku bingung “Kenapa kamu ketawa Shei?.”
Entah bagaimana, ucapan Rifan otomatis menghentikan tawaku “Loh, Sheila kira kakak lagi ngelawak.”
Rifan menggelengkan kepalanya “Saya serius Shei, dia baik, Chindo, ganteng juga, kaya lagi. Dia pingin kenal kamu.”
“Siapa?.”
“Edi.”
Aku mengerutkan dahiku, cukup terkejut setelah mendengar namanya “Chindo itu Chinese Indonesia kan kak?.”
Rifan mengangguk, mengiyakan.
“Kok namanya Edi?.”
“Kenapa? Keren loh itu, namanya cinta Indonesia banget.”
“Ehm iya deh iya, keren.”
Rifan tertawa, melihat responku yang seadanya “Bercanda, itu nama buatan saya. Nama aslinya Edward Sean, nama Chinesenya Kim Ryu Jin.”
“Bukannya itu nama Korea yah?”.
“Nggak tahu juga, coba kamu tanya sendiri ke orangnya Shei.” Ucapnya Rifan sambil berdiri, entah apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
“Edi!!! Sini woy.” Rifan berteriak ke arah lapangan basket, sembari menunjuk ke salah satu pemain yang sedang berkumpul deng timnya.
Tak berapa lama, orang yang dipanggil Edi pun hadir. Dia muncul dari belakang tubuh Rifan. Sosoknya yang tinggi dengan tubuh proporsional, serta ditambah dengan ketampanan khas orang Korea, membuatnya terlihat tidak nyata.
“Apa sih? Ada Edi mulu! Nama gue Sean” Gerutu Edi, eh Sean maksudnya.
Aku tertawa, entah kenapa aku mendadak sereceh ini.
Sean menatap kearahku, ekspresinya terlihat sangat terkejut “Eh, Sheila yah?.”
Aku tersenyum “Iya kak.”
Sean menggaruk kepalanya yang kuyakini tidak gatal “Duh, gimana yah. Mau ngobrol banyak tapi aku kondisinya lagi kayak gini.”
“Cih! Biasanya aja ke saya gue elo, giliran ketemu pawang aja, sok imut Lo! Aku aku-an segala, bikin jijik aja. Yaudah saya pergi duluan.” Protes Rifan, sembari melangkah pergi.
“Kamu ada kelas sore Shei?.”
Aku mengangguk, tak berencana mengembangkan percakapan. Lagipula sebentar lagi kelas suamiku akan dimulai.
“Pulang jam berapa?.”
“Jam 7 paling.”
“Punya jam malam.”
“Punya.”
“Jam berapa?.”
“Jam 10.”
“Yaudah.”
Setelah banyaknya pertanyaan yang dilontarkan Sean, akhirnya tanpa sadar aku gantian bertanya padanya “Yaudah apa?.”
Dia tersenyum dengan sepasang lesung pipi yang membuatnya beribu-ribu kali lebih tampan. Bukankah tidak adil? Dia memborong habis semua deskripsi dari ketampanan manusia.
“Gitu dong, jangan cuek-cuek banget gitu loh. Maksudku tadi itu, yaudah sana ke kelas, nanti jam 7 aku tungguin di depan kelas kamu, kita lanjut ngobrol. Nanti jam 10 aku antar pulang.”
Aku meringis, ngeri “Kata Yaudah dari kak Edi panjang banget maknanya. Eh”
Sean mengusap kepalaku, dia memang jauh lebih tinggi dibandingkan aku. Tapi perbedaan tinggi ini sangat pas dan sangat direkomendasikan untuk menjadi sepasang kekasih, eh.
“Panggil Ryu aja. Panggil nama asli aku, karena aku mau kamu jadi yang spesial.”
Inikah yang dinamakan romansa kampus? Indahnya, Seandainya saja aku belum menikah, mungkin akan lebih baik.
“Ehem!! Sheila Anggara, kamu berniat untuk bolos dari kelas saya atau bagaimana?” Suara bariton itu lagi...
>>To be continue<<


 kimchicya20
kimchicya20