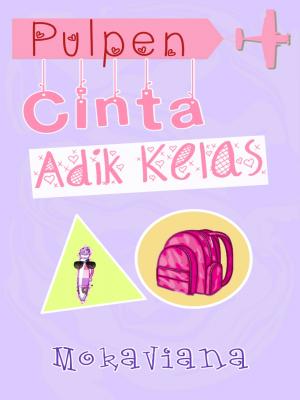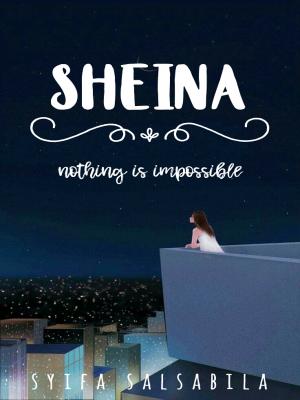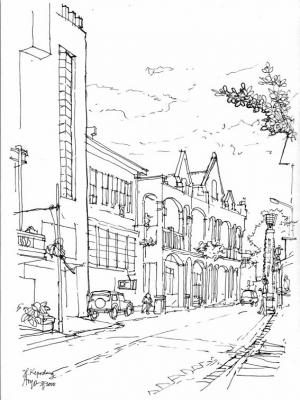Bersamaan setelah dering bel istirahat, Samuel, teman sekelasku yang cabut pelajaran sebelumnya, datang dari luar kelas sambil berteriak, “Ada anak baru di kelas sebelah.”
Sontak saja membuat santer satu kelas. Seisi penghuni kelas, termasuk aku, menoleh. Salah seorang temanku, Riris, bertanya penuh semangat,“Cewek atau cowok?”
“Kalau cewek mah masih disana gue sampai sekarang,” balas Samuel cuek.
Tanpa banyak tanya lagi, Riris buru-buru ke luar kelas. Sebelum punggung Riris tidak terlihat sama sekali, Samuel berseru memberitahu, “Di mading deket tangga.”
Sekembalinya, muka Riris kemerah-merahan. Antek maupun yang sebangsa dengan Riris lekas mengerubungi Riris, meminta hasil pantauan.
“Gimana ris?”
Riris hanya mengangguk seolah terhipnotis sambil menggumam, “Ganteng.”
Wah, sepertinya efek ganteng anak baru itu memang luar biasa nih. Riris saja cuma diam dan mengangguk menjawab pertanyaan, selagi benaknya dipenuhi imajinasi. Kelas jadi riuh. Beberapa kaum hawa di kelasku ikut datang mengerumuni Riris.
“Dari mana Ris asalnya?”
“Udah kaya adipati belom Ris?” tanya Mirna, yang ngefans berat sama Adipati Dolken.
“Kacamataan gak Ris?”
“Dia ngapain Ris di mading? Bagi-bagi ID Line?”
Bertanya pada Riris saat ini tidak ubahnya menanyai tembok. Tetap tidak dijawab, serius.
Beberapa temanku geregetan dan memutuskan melihat sendiri sosok cogan yang telah membuat teman satu kelasnya kelepek kelepek. Aku sendiri? Biasa saja sih. Tetapi saat kulihat jam kelas sudah menunjukkan pukul 9.50 penanda waktu istirahatku tinggal 10 menit, mau tidak mau aku ikut ke luar kelas. Siapa tahu bisa sekalian lihat anak baru selagi lewat.
Rasa-rasanya nih cogan memang oke punya deh. Di koridor lantai dua pun aku mendengar bisikan anak perempuan lain sebelum menuju tempat yang sama, mading. Wow, mungkin ada sekitar dua puluh perempuan berkeliling di situ. Aku memperlambat kecepatan jalanku. Aha! kutemukan celah. Mendadak mataku dan matanya saling menatap. Singkat. Aku melotot ketakutan. Cepat-cepat turun tangga, menyusuri koridor dan masuk ke dalam celah kecil di ujung lorong. Toilet. Lupakan perihal kantin beserta isi isinya dan keroncongan perut. Aku susah payah menstabilkan napasku yang megap-megap.
Sebelum otakku sempat berkontemplasi akan apa yang terjadi, masuk dua cewek lain ke toilet. Masih membicarakan anak itu.
“Denger denger sih dia anak daerah.”
“Oh, bukan asal sini?”
“Bukan, dari Kupang katanya.”
“Udah punya pacar belom ya…”
“Gue sih calonnya.”
“Yeu dasar.”
Keduanya lalu meninggalkan toilet. Dari Kupang? Sialan, jantungku masih belum karuan lajunya, ini lagi mereka mengonfirmasi kalau cowok baru itu dari Kupang. Loncat loncat nih jantung. Berarti benar dong dugaanku?
Aku mengenal anak baru yang lagi viral di sekolahku dalam beberapa jam kedatangannya itu. Dia Davio, teman TK-ku di Kupang. Aku menghela napas berat. Mengenangnya saja sudah sanggup membuat sekujur tubuhku keringat dingin. Dulu Davio selalu membully-ku. Davio berhasil membuat masa TK-ku yang seharusnya riang belum adanya PR matematika, malah jadi lebih mengerikan ketimbang ulangan fisika, kimia, dan biologi dalam satu hari. Davio sering menghasut anak lain menjauhiku, menjatuhkan bekal makanku dengan sengaja, hingga pernah mendorongku ke pantai saat studi tour padahal aku tidak bisa berenang. Ketika akan masuk SD, ayahku pindah tugas dinas. Ke Jakarta meninggalkan Kupang. Bukannya aku membenci Kupang, kota dengan segala keindahan padanan karangnya, tetapi ya sebab ingin menyingkirkan memori tentang Davio. Kepindahan itulah yang membuat aku dapat bertahan sampai hari ini. Tak tahunya tanpa peringatan lebih dulu, sosok horor itu datang jauh jauh ke Jakarta, satu sekolah denganku dan beberapa menit lalu bersitatap denganku.
Aku melirik arloji sekilas. Lima menit lagi bel isirahat telah berakhir akan terdengar. Bagaimana cara kembali ke kelas tanpa menghadapi cowok baru ganteng aka tukang bully-ku semasa TK.
Pilihan pertama, memakai masker. Tunggu dulu, kalau aku harus ke koperasi untuk membeli masker berarti aku harus lari menyusuri koridor selatan dan barat. Butuh waktu lebih dari 3 menit untuk bolak-balik ke koperasi, mengambil masker, mengeluarkan uang, membayar dan menunggu kembalian. Atau bisa juga lewat lapangan dan mengambil jalur Pythagoras. Mungkin bisa menghemat waktu satu menit. Namun bagaimana jika ternyata persediaan maskernya kosong? Sama saja aku sudah menyiakan dua menit.
Pilihan kedua, melepas kacamata. Mungkin Davio tidak mengenaliku tanpa kacamata. Itu sih tidak separah aku yang tak mampu mengenali jalan tanpa memakai kacamata. Alias tidak terlihat apa-apa (yang berkacamataan pasti tahu rasanya).
Pilihan ketiga, berjalan biasa sambil menundukkan kepala. Toh, masih ada belasan cewek sebagai tameng perlindungan untuknya.
Melihat waktuku yang semakin menipis dan sudah tersisa tiga menit lagi, pilihan tiga-lah yang paling lumayan dan rasional. Oke, lets try.
TADA! Ternyata sesampainya aku di mading dekat tangga, kerumunan itu sudah bubar. Sudah tidak nampak lagi makhluk sejenis Riris dan sosok horror bernama Davio. Aku merapatkan sisi kanan tubuh ke dinding. Mengecek koridor kanan kiri. Celingukan. Mencari sosok misterius plus horor itu. Nihil. Artinya aman.
Kelasku, kelas 12 IPA 6, letaknya di ujung lorong. Harus melewati dua kelas –12 IPA 4 dan 5– dari posisi aku berdiri saat ini. Satu kelasnya (12 ipa 5) pasti kelas Davio, berdasarkan laporan Samuel bahwa kelas kami sebelahan. Saatnya berpikir kembali.
Lebih baik aku lari secepat kilat atau berjalan sambil menutup sebelah muka dengan telapak tangan ala selebritas menghindari paparazi atau berjalan biasa saja? Aduh kalau aku mengambil pilihan yang aneh nanti malah dicurigai. Ya sudah deh kembali ke rencana awal sejak dari toilet. Jalan senormal mungkin.
Waktu tinggal semenit 35 detik. Satu kelas sudah lewat. Deg-degan semakin meningkat. Dalam beberapa hitungan aku akan melintasi kelas Davio. Persis di depan pintu kelas Davio yang terbuka lebar, aku mendadak terdiam skakmat di situ. Dalam sepersekian detik, mataku dan matanya kembali saling mengunci. Aku melotot kaget, dia melongo. Masa bodoh urusan mengatur siasat, aku berlari ke kelasku.
Sepanjang sisa pelajaran di sekolah, sepeserpun materi dari guru tidak tersangkut di otak. Benar-benar hanya teringat nostalgia tidak bahagia. Aku bahkan masih ingat jelas apa objek yang menjadikan Davio selalu membullyku. Gara-gara aku ini sudah pendek, gendut, berkacamata meskipun masih tk, rambut keriting kasar kayak gimbal, tidak punya teman (ini efek domino dari Davio juga) dan parahnya lagi cengeng. Setiap davio berulah, pasti berlanjut dengan aku menangis sesenggukan diam-diam tapi ketahuan olehnya.
Rasa-rasanya aku harus berterima kasih sama Davio juga. Dialah yang mengubah hidupku. Ketakutan masa kecil membuatku selalu mengantisipasi apapun semaksimal mungkin. Sampai di Jakarta, aku berubah total. Les berenang sehingga punya badan ideal. Puberty goals kata orang. Aku lebih sering merawat rambut dan nyatanya sekarang rambutku lurus ikal sedikit. Mengenai kacamata, masih aku pakai sampai sekarang karena rabun jauhku memang hereditas.
Masalahnya, aku belum siap harus menyudahi masa kejayaan dan balik menjadi upik abu karena hadirnya sesosok di masa lalu. Tunggu dulu. Lagi-lagi aku harus merencanakan antisipasi jika harus bersemuka dengan Davio kedepannya.
Rencana satu : Minta maaf pada Davio meskipun jelas aku tidak salah apapun.
Rencana dua : Aku ancam duluan saja Davio ini. Lagi pula, posisi dia sekarang itu kan anak baru belum bisa dipercaya sepenuhnya oleh anak-anak sekolahku. Sedangkan aku sudah dikenal oleh mereka. Otomatis teman-teman lebih percaya padaku daripada dia.
Rencana tiga : Pura-pura tidak kenal. Ditambah sedikit perubahan penampilan supaya dia tidak mengenalku. Barangkali aku bisa berdandan sok eksis sekaligus membuatnya ngeri.
Lagi, aku memilih solusi paling aman. Rencana tiga.
Keesokan harinya, aku bangun pagi pagi buta. Mengambil liptint kakakku yang masih tertidur lelap. Menggeledah lemari sendiri untuk menemukan sweater. Setelah semuanya lengkap, aku duduk di depan meja rias. Membuka laci lalu mendapati soft lens yang selama ini mendekam tanpa pernah kupakai. Sesi dandan pun dimulai.
Satu jam kemudian baru lah aku berhasil memasang soft lens. Itu pun sambil bercucur air mata. Memoles bibir dengan liptint. Tidak lupa pula sweater untuk menutup nametag namaku yang terjahit di dada kanan seragam. Terakhir yang akan membuat pangling, rambut. Kemarin, sepulang sekolah, aku mencatok seluruh rambutku dan memberi tambahan poni di kanan dan kiri. Padahal selama tujuh belas tahun hidupku, sungguhpun membayangkan aku berponi saja tidak pernah.
Satu lagi, aku merengek pada kakakku untuk mengantarku naik mobil. Duilah banyak gaya tidak aku ini? Aksi norak bin mendadak aku ini sukses membuat penghuni satu rumah keheranan.
Problem yang baru aku sadari kemudian yakni jalanan dari rumah ke sekolah selalu padat merayap tanpa ampun. Terang saja, sepanjang perjalanan kakakku memarahi tindakan belagaku. Aku sendiri mengutuk diri yang ingin sok naik mobil tanpa pikir panjang. Terbukti, aku tiba di gerbang sekolah pukul 6.47. Dimana gerbang sekolah sudah ditutup 17 menit yang lalu. Anyway, kebijakan di sekolah aku yaitu anak-anak di dalam sana yang datang tepat waktu akan menghabiskan satu jam mereka –dari 6.30 s.d 7.30– dengan membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia raya dan budaya literasi membaca buku. Sementara kami-kami ini yang entah kesiangan, macet atau gengsi (hanya aku sih) harus berdiri dengan sikap sempurna selama sisa waktu kedatangan sampai bel berbunyi. Di luar gerbang sekolah.
Aku mengumpat-umpat Davio sebagai pelaku tidak tepat waktunya aku hari ini. Entah merasa terpangil atau bagaimana, rupa yang aku sebut itu datang. Sempat menghampiri pintu gerbang sebentar. Aku yakin dia berusaha merayu satpam dengan alasan macet. Tidak tahu saja dia macet memang sarapannya orang Jakarta dan basi sekali menyebut macet sebagai alibi. Setelah gagal bernegosiasi dengan sang penjaga gerbang, dia berjalan ke arahku. Aku ulang, ke arahku. Lantas berdiri persis di sampingku.
“Lo telat juga?” tanyanya.
Aku diam, gondok. Yaiyalah, sudah jelas aku berdiri disini lantaran telat. Mana mungkin ada murid dengan sukarelawan berjemur di depan gerbang sekolah sebagai tontonan para pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil atau bahkan sepeda yang melintasi sekolah.
“Btw kenalin, gue anak baru di 12 IPA 5, lu kelas berapa?”dia mencoba menyapaku rupanya.
Maaf ya, sudah tahu please. Aku mendelik. Davio sedang sandiwara mungkin.
“12 IPA 6,”jawabku pendek.
Tiba-tiba dia mengulurkan tangan,” Nama gue..”
Sebelum Davio menyelesaikan omongannya, aku sekonyong-konyong batuk bohongan yang luar biasa hiperbolanya. Tidak sempat terdengar namanya. Lagi pun, aku tetap ingat.
Canggung karena tangannya tak kunjung kubalas, dia kembali bertanya, “Nama lu?”
Hah? Ini bercanda atau betulan lupa atau rencanaku berhasil 100%? Aku yang sejak tadi memandang lurus ke depan, mengalihkan pandangan. Menatap matanya tepat di manik. Mencoba menerka-nerka apakah dia bersenda gurau atau tidak. Ini Davio bukan ya?
Mendapati aku yang terbengong-bengong, ‘Davio gak jelas’ ini menurunkan uluran tangannya. Membuka jaket jeans yang sedari tadi dia kenakan. Sontak mataku menangkap nametag di dada kanan kemejanya. Reno. Eh? Kok?
“Eh sorry tadi lu bilang apa?” otakku mulai berusaha mencerna.
“Nama lu siapa?”
“Bukan. Bukan itu, nama lu siapa tadi gue gak denger”
“Oh. Reno”
“Reno!?? Lu bukan Davio ?!” aku berteriak tertahan.
Detik itu juga, satpam sekolah datang menghampiri,“Neng jangan teriak-teriak ya, yang di dalam lagi pada berdoa.”
Aku meringis, “Iyah maaf pak.”
Selanjutnya, aku berbisik sepelan mungkin agar tak terdengar Bapak Satpam, “Lu beneran bukan Davio?”
“Haha bukan. Gue kembarannya Davio. Loh kok lu bisa kenal Davio?”
Aku mencoba mereka ulang kejadian kemarin. Pantas saja, waktu aku dan Reno saling tatap, dia tidak menunjukkan gelagat aneh sama sekali. Akunya saja yang terlalu parno.
“Jadi kok lu bisa kenal Davio?” Reno mengulang pertanyaanya.
Aku menghembuskan napas lega. Kedua kalinya selain kepindah tugasan ayahku.
“Gue Riena. Teman TK nya Davio. Davio sekolah disini juga?” Aku berharap-harap cemas.
“Engga. Ortu kami cerai dan setelahnya kami ninggalin Kupang. Davio nemenin nyokap gue di bandung dan gue nemenin bokap di Jakarta” katanya sambil tersenyum.
Setelah dilihat-lihat, senyum Reno memang tidak sama dengan Davio. Reno punya lesung pipit. Aku mengembangkan bibir sedikit sambil terus memperhatikan Reno.
Konyol. Aku menyiapkan berbagai antisipasi dan repot-repot mengganti penampilan sampai telat masuk sekolah. Ternyata salah orang. Aku tersenyum semakin lebar. Aih, sosok di hadapanku ini semakin rupawan jika dilihat semakin dekat. Apa aku gebet saja ya? Mendahului Riris dan cewek gibah di toilet. HAHAHA.
Eh, tetapi kalau harus punya calon ipar kaya Davio? Ogah deh.


 mute
mute