BAB 1
Malam itu, wajah pesatren berbeda dari biasanya. Jalan setapak berbatu yang menghubungkan antara gapura dengan aula pertemuan terlihat benderang. Neon kuning menyorot sepanjang jalan --bahkan, rumput liar setinggi mata kaki orang dewasa yang menjadi pagar pembatas, tampak ayu tertimpa sinar.
Anehnya, Mas Darmaji juru kunci pelistrikan tak bersungut sama sekali --bahkan tampak begitu tenang. Padahal dialah yang paling getol melarang lampu jalan menyala semua jika tak ada tamu agung, atau perhelatan penting di pesantren. Katanya, keuangan pesantren tahun ini sedang seret, tak ada jatah untuk membayar listrik bulanan jika tagihan sampai membengkak. Lagi pula, setelah jam delapan malam, jalan itu sepi. Para santri paling anti lewat jalan yang menjadi satu-satunya rute tercepat menuju pesantren tersebut. Mereka lebih memilih memutar lewat jalan belakang meski jaraknya lumayan melelahkan kaki.
"Tumben lampunya boleh nyala semua?" gumam Rahdi, sembari mengeluarkan rebana dari kotak kayu besar --tempat penyimpanannya. Beberapa kali sorot matanya menatap jalan, lalu bergidik ngeri.
"Meski nyala semua, masih terlihat menakutkan," sahut Rasyid.
"Iyo. Opo kalau sudah terang begini, demitnya nggak pergi dari pohon itu?"
"Kayaknya sih, nggak."
Rasyid diam sejenak. Tatapannya tegak lurus dengan pohon sono di samping jembatan yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempatnya berdiri. Dahan pohon itu bergoyang-goyang tertiup angin.
"Tapi, beneran pohon itu ada hantunya?" tanya Rasyid.
Rasdi ikut menghentikan kegiatannya. Menggeser bola matanya, menatap pohon Sono yang sama. "Katanya, sih memang ada. Inget Mutar, adik kelas kita?"
Rasyid mengangguk cepat.
"Beberapa minggu lalu dia kejang-kejang setelah kembali dari rapat warga. Ada yang bilang, Mutar ketempelan penghuni situ saat lewat di depan pohon sono itu."
"Ah, yang benar kamu?!" Keterkejutan Rasyid menggema ke penjuru aula. Kebetulan, saat itu hanya ada dirinya, Rasdi dan Samuel. Kondisi sekitar aula pun sepi karena santri lain sibuk dengan kegiatan rutin masing-masing. Mereka pengurus hadroh pesantren, mendapat mandat dari Ustad Amir untuk bermain malam ini.
Di sisi lain, Samuel yang sejak tadi bertugas menyisihkan debu teras gapura, mendadak melopat dan lari terbirit-birit mendekati dua rekannya yang lain. Melempar sapu ijuknya serampangan. Bersembunyi di belakang Rasdi dan Rasyid, sembari menggigil ketakutan.
"Walah! Iki opo toh iki!" protes Rasyid. Lengan bajunya yang ditarik-tarik Samuel, ia tarik kembali.
"What's up, Sam?" tanya Rasdi.
"Somebody blew me. I think it's an Indonesian ghost. You know? Indonesian ghosts are scary. Their clothes, faces ... are all scary," terang Samuel. Nada suaranya bergetar.
Rasyid yang memang tak paham sama sekali dengan Bahasa Inggris, mengangkat kepalanya ke arah Rasdi, alisnya bertaut meminta Rasdi menjelaskan perkataan si Bule.
"Si Bule, bilang ... ada yang niup telinganya. Dan, sepertinya itu hantu Indonesia. Dia takut dengan hantu Indonesia. Katanya, wajah dan baju hantu Indonesia itu menyeramkan."
Rasyid langsung menoleh pada Samuel dengan tatapan mencibir. "Walah, mentang-mentang hantu di negaramu berkelas ... hantu Indonesia itu ekonomis, mereka nggak perlu biaya mahal untuk nakut-nakutin orang. Nggak boros kayak hantu negaramu."
Rasdi terkekeh. Samuel, yang memang belum mahir sekali Bahasa Indonesia hanya mampu memandang wajah kesal Rasyid dengan dahi terlipat, dan berkali-kali bertanya "What? What?" pada Rasdi.
"There is no. Back to work," ujar Rasdi. Kemudian meminta Samuel memanggil personil hadroh yang lain.
"Sampai kapan, kamu bakal begitu sama dia, Syid?"
Rasyid mengedikkan bahu. Raut wajahnya masih tampak kesal.
"Dia itu sudah berusaha mencoba deket sama kamu. Kamu, kok, ya, terus-terusan ketus sama dia?"
"Aku, ya, nggak ngerti." Rasyid mendesah berat.
"Iri karena Samuel santri baru, tapi bisa menyaingi kita yang sudah santri lama di sini?" tebak Rasdi.
"Ora gitu." Rasyid mencoba menampik itu. "Alah, ngapain toh bahas itu. Ayo kerja lagi, keburu Ustad Amir balik dari kota."
Rasdi menepuk bahu Rasyid dan kembali ke pekerjaannya.
"Oh, ya, Di, memang Siapa, sih yang mau datang? Kok kita di suruh main hadroh malam-malam begini?" tanya Rasyid.
"Tamu penting, kata Ustad Amir."
"Temennya Pak Kyai?"
"Ndak tahu ... tapi, ada yang bilang itu putrinya Pak Kyai."
Rasyid menerima rebana terakhir dari Rasdi, mengelapnya dengan kain dan menatanya di atas meja.
"Mbak Nasya?" Mata Rasyid menyipit.
"Mungkin," jawab Rasdi sembari mengedikkan bahu.
"Ya, pantas seisi pesantren ribut. Orang yang dateng putri kesayangannya Pak Kyai."
"Hust! Nggak baik membicarakan Pak Kyai."
Rasyid memutar badannya. Menarik kursi kayu dari samping meja dan meletakkannya di belakang badan Rasdi.
"Ora, aku hanya kasihan saja sama ustadzah Kamila," kelakar Rasyid, sembari mendudukkan tubuhnya di kursi tadi.
"Kok, kayaknya nggak adil begitu. Ustadzah Kamila dikurung di pesantren, sedang Mbak Nasya, boleh bertidak sesuai keinginanya," imbuhnya.
"Makin ngelantur omonganmu. Tahu apa kamu perihal ini. Kalau sampai ada yang dengar dan ngelaporin kita ke Ustad Amir. Bisa-bisa kita dihukum berdiri satu jam, sambil menghafal surat-surat munjiyat. Mau kamu? Wes kerja aja, jaga bicaramu."
"Dasar kamu penakut," ledek Rasyid.
Rasdi tak peduli.
Di sudut lain, di kediaman Kyai Jamal. Sang istri yang sejak tadi mondar mandir di depan pintu rumah, terlihat cemas karena sang putri tak kunjung datang. Berulang kali mata wanita setengah abad itu, mengamati lekat jam lemari di samping kursi yang diduduki Kyai Jamal. Semakin cepat pergerakan jarum jamnya, semakin keras gemuru jantungnya.
"Bukne duduk saja," pinta Kyai Jamal.
"Bagaimana, Bukne bisa duduk Pakne. Ini sudah jam berapa, harusnya Nasya sudah sampai setengah jam lalu. Nggak biasanya selama ini."
"Sabar, Bapak sudah menelepon Ustad Amir. Dia, Saleh dan Kamila sedang menunggu Nasya di terminal. Nasya belum tiba di terminal. Mungkin sebentar lagi."
Bu nyai berhenti mondar-mandir. Masih setia dengan wajah khawatirnya. Kali ini rasa kesal bercampur di sana. Dihampirinya meja kaca depan sang suami, dan diambilnya ponsel milik suaminya yang tergeletak di atasnya.
"Pakne ini, karena nggak ikut melahirkan, jadi nggak tahu gimana takutnya Bukne sekarang. Bukne nggak sabar. Biar Nasya Bukne hubungi."
Dan sepersekian detik selanjutnya, bu nyai sudah menghubungi Nasya. Namun,
"Pakne, hp Nasya tidak aktif ini. Pie Pakne? Ada apa dengan Nasya?" Mata bu nyai mulai berkaca-kaca.
Kyai Jamal berdiri dari duduknya. Menghampiri sang istri, meminta ponsel yang digenggam istrinya.
"Jangan mikir macem-macem. Sini biar Bapak yang telepon."
Setelah menekan tombol panggil, Kyai Jamal mendesah sekali, mencoba membuang seluruh kekhawatirannya. Berharap kali ini panggilannya akan tersambung, dan suara Nasyalah yang terdengar. Sayangnya, bukanlah suara Nasya yang ia dengar, melainkan suara operator saluler yang menyatakan nomor Nasya sedang tidak dapat dihubungi.
"Bagaimana, Pakne?"
"Tidak aktif. Coba Pakne telepon Ustad Amir."
"Ya Allah, Pakne ... ayo, kita keterminal saja," bujuk bu nyai.
"Sabar Bukne, tunggu dulu," pinta Kyai Jamal, sembari menunggu panggilannya dengan Amir terhubung.
"Assalamualaikum, Pak Kyai?" sapa suara dari balik telepon.
"Waala'ikumussalam, Ustad Amir ... Nasya sudah sampai?"
"Belum, Pak Kyai. Ini Ustadzah Kamila juga mulai cemas karena ponselnya Nasya tidak bisa dihubungi."
"Ya, sudah ... Minta tolong, tunggu di sana dulu, ya. Siapa tahu setelah ini Nasya datang."
"Inggeh, Kyai."
Setelah itu Pak Kyai memutus sambungan. Menatap sang istri yang menunggu jawaban. Tak ada yang bisa ia jelaskan selain menggeleng, dan membiarkan tangis sang istri pecah saat itu juga. Kyai Jamal semakin yakin jika sudah terjadi sesuatu pada Nasya. Putrinya itu sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja.
***
Nasya membuka kelopak matanya susah payah, teramat berat dan enggan. Rasa nyeri yang menghimpit kepala, membuatnya mendesis lalu mengerutkan dahi dalam-dalam. Ia ingin bangun. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia ingin menghubungi Abi dan Ummi yang pastinya sudah sangat khawatir.
"Ya Allah," rintihnya.
Nasya menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Menatap kesekeliling meski dalam bentuk samar. Semua asing. Ruangan besar dengan ranjang-ranjang besi dan tirai biru muda sebagai pembatas. Lalu lalang pria dan wanita berseragam putih. Rintihan, tangisan, dan aroma karbol yang menyengat indera penciuman. Semua tampak baru baginya. Dan ketika Nasya semakin memusatkan perhatian, ia sadar tempat yang ditinggalinya ini bernama rumah sakit. Ia dan penumpang lain, telah menjadi korban kecelakaan bus beberapa saat lalu.
Nasya mendesah. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya meski otot-ototnya terasa kaku. Ia mengatur selang infus yang ukurannya cukup panjang agar tak membelit tubuhnya. Kali ini, kaki yang terjulur di atas ranjang, ia geser dan biarkan menggantung di tepi ranjang. Lagi, Nasya mengembuskan napas berat. Syukurlah, meski sakit, semakin lama tubuhnya mulai bisa dikuasai.
"Permisi, Suster?" panggil Nasya, pada salah seorang perawat yang kebetulan melintas di depan ranjangnya. Suaranya parau. Tenggorokannya teramat kering.
"Ya, Mbak ... ada yang bisa saya bantu?"
"Maaf, Suster ini rumah sakit mana, ya?"
"Oh, ini RSUD Mojokerto, Mbak."
Nasya berpikir sejenak. Ah, berarti ia masih cukup jauh dari rumah.
"Boleh saya meminta air dan meminjam ponsel untuk menghubungi keluarga saya?"
Nasya tak melihat barang-barang miliknya sama sekali. Untunglah, ia hafal betul nomor abi.
"Tentu saja, Mbak." Perawat itu merogo saku setelannya. "Ini." Lalu menyerahkannya pada Nasya.
"Saya nggak akan lama kok, Suster."
"Pakai saja, Mbak. Nggak apa-apa. Saya pergi dulu untuk mengambilkan Mbak air minum."
Nasya menyunggingkan senyum penuh terima kasih, dan perawat itu pun membalasnya dengan ramah.
"Terima kasih, Suster."
"Sama-sama, Mbak."
Sesegera mungkin Nasya mendial nomor Abi, menunggu jawaban.
"Assalamualaikum, siapa ini?"
Nasya melantunkan hamdalah dalam hati.
"Waalaikumussalam. Abi ... Abi ... ini Nasya, Abi."
Abi di seberang telepon terdiam. Tanpa tak kuasa menahan keterkejutannya.
"Abi, Nasya ada di RSUD Mojokerto."
"Astagfirullah, ya Allah, Nasya ... apa yang terjadi. Abi dan semua menunggumu dengan cemas."
"Bus yang Nasya tumpangi mengalami kecelakaan, Abi. Syukurlah Nasya masih dilindungi Allah."
Terdengar tangis di sana. Tangis dari sang ummi. Mungkin abi sudah mengganti mode teleponnya kemode keras.
"Nasya, Nasya baik-baik saja, 'kan, Nak?" suara Ummi menggantikan Abi.
"Alhamdulillah, Nasya baik Ummi."
"Tunggu, Nak ... jangan ke mana-mana, Ummi dan Abi akan menjemputmu."
Nasya mengangguk. Anggukan yang tak akan diketahui oleh abi mau pun umminya. Tanpa ia sadari, air matanya menitik. Nasya begitu lega bisa mendengar suara kedua orang tuanya.
***


 rara_el_hasan
rara_el_hasan






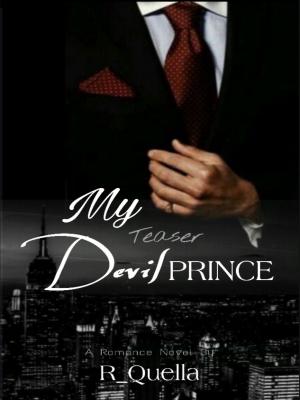



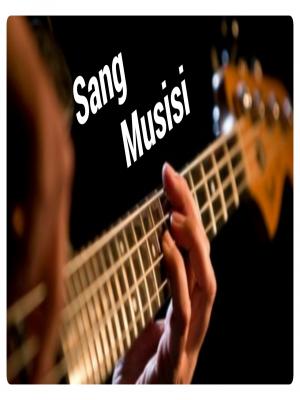
@Ardhio_Prantoko wah makasi banyak ya bang
Comment on chapter ***