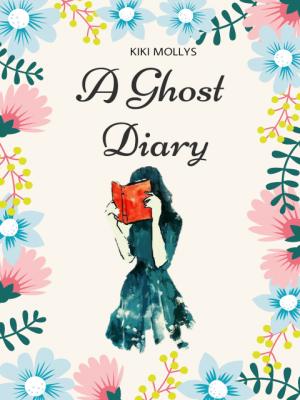“Jauhkan kucing itu dari saya!” Sebuah teriakan terdengar dari suatu lorong rumah sakit membuat kesunyian malam itu pecah. “Suster! Tolong! Buat kucing itu pergi dari sini! Suster!”
Seorang wanita, terduduk panik di atas ranjangnya berteriak-teriak minta tolong seakan melihat sosok yang menakutkan. Di depannya nampak kucing yang duduk tenang di ranjang yang sama dengan wanita itu. Dia menatap pasien wanita itu lama.
“SUSTER!” Sesaat kemudian dua orang suster berhamburan masuk kedalam ruang rawat mengecek wanita itu. Satu diantaranya menenangkannya dan suster yang lain mencoba mengeluarkan kucing tersebut dari ruang rawat.
Setelah beberapa menit penuh drama, akhirnya wanita itu kembali terlelap dengan terbaring mendekap bantal. Tinggallah aku yang terjaga, tidak bisa tidur lagi.
Di ruang yang berukuran empat puluh meter persegi, terdapat 4 pasien termasuk aku, yang dirawat dengan berbagai macam penyakit. Aku sebagai pasien yang baru dua hari di sini, belum tahu siapa ’tetanggaku’ dan sakit apa yang diderita mereka. Aku melihat, satu ibu paruh baya bertubuh agak gempal dengan kaki terlilit kain kasa, kutebak sih patah tulang kering karena jatuh dari motor. Di sampingnya, sepertinya anaknya, kutebak berumur 14 tahun, kepalanya dililit kain kasa juga. Satu pasien lagi adalah wanita itu, wanita yang tadi berteriak-teriak melihat kucing seperti melihat setan.
Aku sendiri mengidap penyakit lupus. Penyakit yang kata mbah Google cukup parah. Iya, aku dengan inisiatif mencari info tentang penyakitku sendiri, soalnya dokter yang menanganiku tidak menjelaskannya padaku, ia hanya mau berbicara dengan ayahku, dan ayahku berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku berani bertaruh, kalau ayah tidak ingin membuatku makin stres dengan apa yang aku derita. Suatu hari aku mencuri dengar pembicaraan mereka, dan yang terdengar penyakit lupus disebut berulang kali. Sejak itu aku yakin bahwa aku menderita penyakit lupus, penyakit yang merenggut nyawa ibuku juga.
Baiklah aku akan jelaskan sedikit apa itu penyakit lupus. Penyakit lupus ini disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh, Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi. Akan tetapi pada penderita lupus seperti aku, sistem imun justru menyerang tubuhnya sendiri. Ya aku dikhianati oleh tubuhku sendiri. Parahnya, penyakit ini belum ada obatnya.
Setengah jam sudah aku membolak balikan tubuhku, mencoba menemukan posisi yang nyaman untuk bisa tidur lagi. Kulihat jam dinding sudah menunjukan pukul 11 malam. Aku salut pada kedua ibu anak itu, mereka bisa langsung terlelap walaupun sama-sama terbangun saat kejadian wanita tadi berteriak-teriak.
Malam itu entah kenapa dingin udara menusuk hingga tulangku, kutarik selimut agar rasa dingin yang aneh ini dapat berkurang. Sayup-sayup di kejauhan ada suara anjing melolong menyedihkan, seakan-akan mengumumkan berita kematian pada gelapnya malam. Dedaunan bergerak-gerak ditiup angin, saling bergesekan dan menimbulkan suara yang membuat hatiku tak nyaman.
Jantungku hampir melompat saat pintu ruang rawat dibuka perlahan. Lampu di ruangan memang sengaja dimatikan karena kami berempat tidak bisa tidur kalau lampu menyala. Siapa itu? Siapa malam-malam datang bertamu? Hatiku berdegup kencang saat kudengar bunyi langkah sepatu berderap di lantai keramik.
Masih dalam posisi tidur, kupicingkan mataku agar pupil mataku membesar dan retinaku bekerja untuk lebih fokus menangkap siluet tubuh yang masuk. Kulihat sosok itu berbaju putih. OH MY GOD. Apakah itu??
Mulutku nyaris menjerit, sebelum akhirnya lampu mendadak menyala dan menampilkan sosok pria berkacamata dengan jas putih dan stetoskop yang terkalung di lehernya. Seorang dokter.
Aku berpura-pura tidur. Dari celah kelopak mataku yang kubuka sesedikit mungkin, aku bisa melihat dokter itu sedang membawa clipboarddan pulpen. Dia melihat ranjang kami satu persatu, otakku baru mencerna kalau dia adalah dokter jaga malam ini. Namun, apakah harus selarut ini dia mengecek pasien? Dan dokter jaga bukannya hanya berjaga di ruang IGD? Ah entahlah aku kuliah di fakultas hukum bukan fakultas kedokteran.
Dia menuliskan sesuatu di clipboard-nya, urutan ranjang kami adalah seperti ini: Ranjang wanita yang tadi menjerit-jerit histeris, ibu paruh baya, anaknya, barulah ranjangku. Hanya perlu satu menit dia mencatat tiap ranjangnya hingga dia berhenti di ranjangku, mataku sepenuhnya terpejam sekarang, kucoba bernafas senormal mungkin layaknya orang tidur, tapi aku merasakan dokter itu memperhatikanku.
Lalu kudengar derap langkahnya berjalan menjauh, mematikan kembali lampu ruangan dan lenyap disertai bunyi pintu yang berdecit. Aku berdebat dalam hati. Kenapa aku berpura-pura tidur? Kenapa tidak bilang saja aku susah tidur, mungkin saja dokter itu akan memberikanku obat tidur atau bisa menemaniku mengobrol hingga mengantuk. Sejumlah pertanyaan memenuhi otaku hingga aku lelah dan akhirnya jatuh tertidur.
###
"Shiren!!”
Esok hari, suara berfrekuensi tinggi itu tertangkap telingaku yang pada saat itu belum bisa bekerja sepenuhnya.
Apa lagi sih ini? Aku mengucek-ngucek mataku, butuh beberapa detik untuk mengumpulkan nyawaku dan mencerna apa yang terjadi di depanku.
Pagi ini kegaduhan kembali terjadi. Namun, kali ini jeritan itu bukan keluar dari wanita semalam, melainkan dari seorang berkerudung yang mendekap dan menggunjang-gunjang tubuh wanita itu yang baru kuketahui namanya Shiren. Aku yakin perempuan itu ibunya.
“Bangun Shiren! Jangan tinggalkan ibu,” Ibu itu menjerit seraya mengguncang-guncang tubuh Shiren. "Tolong bangun Shiren!”
“Bu, Shiren sudah tiada. Ikhlaskan kepergiannya,” Lelaki berkumis berkata pelan, kurasa sang ayah, pada ibu itu. Sesekali ia mengusap pundak istrinya dengan lemah lembut.
Rupanya Shiren telah tiada. Kulihat di ruangan itu hadir pula dokter yang menangani Shiren beserta dua orang suster berdiri di belakangnya, sementara pasien satu ruangan denganku, ibu-anak itu juga sudah bangun, mereka berdua duduk di ranjangnya hanya bisa terpaku melihat kejadian ini. Tak tahu harus apa.
Tangis pilu itu terjadi sekitar setengah jam, hingga pada akhirnya tubuh tanpa nyawa itu dikeluarkan dari ruang rawat dan dipindah ke ruang jenazah sebelum dibawa ambulance untuk diantarkan ke rumah duka. Adegan memilikukan ini sudah tidak asing bagiku, aku pernah mengalaminya sendiri, waktu ibuku meninggal di depan mataku, saat usiaku masih sepuluh tahun.
Saat itu, ibu sekuat tenaga menyampaikan pesan padaku, berbicara sekuat tenaga walaupun untuk bernafas saja sulit, ayah sudah melarang untuk tidak banyak berbicara tapi ibuku sepertinya tahu tidak ada kesempatan lagi untuk berbicara padaku.
“Nak, jadilah perempuan yang kuat.” Setelah itu matanya terpejam untuk selama-lamanya. Saat itu aku merupakan bocah sepuluh tahun yang keras kepala, aku masih belum menerima kenyataan kalau aku sudah tidak memiliki ibu lagi. Setelah dimakamkan, aku tidak mau pergi dari kuburannya sampe aku menginap di samping kuburan ibu. Sampai akhirnya ayah menyeret dan membopongku seperti karung beras dipanggulnya ke rumah.
“Selamat pagi.” Suara itu membuyarkan lamunanku. Seorang suster menyapaku sambil tersenyum simpul. Aku menjawab pelan. Kemudian dia melanjutkan. “di cek dulu tensinya ya, kak.”
Aku membiarkan suster itu memasangkan alat ke lenganku, memompa alat tensi darah dan mencatat hasilnya di clipboard yang sama dengan clipboardyang dibawa dokter semalam.
“Apakah sendi nya masih terasa sakit kak?”
Aku mengangguk perlahan.
“Baik, sebentar lagi saya akan antar sarapan untuk pagi ini, setelah sarapan obatnya harus diminum ya kak.” Kata suster. "Hari ini akan dilakukan analisa ruam kulit oleh dokter pukul satu siang nanti.”
Aku mengangguk lagi. Kemudian suster membereskan peralatan yang menempel di lenganku dan hendak pergi, namun, ketika berbalik badan aku mengurungkan niatnya.
“Suster,” kataku. “Apa yang terjadi pada Shiren?”
Akhirnya pertanyaan ini keluar dari mulutku, rasa penasaranku sebenernya sudah bergejolak, semalam Shiren seperti sehat wal afiat, dia bisa menjerit-jerit melihat ada kucing melompat di atas ranjangnya, paginya tiba-tiba dia sudah tiada. Kan aneh.
Suster tersenyum, kemudian berkata, “Shiren memiliki jantung yang lemah, beberapa bulan lalu, jantungnya dipasang ring agar dapat bekerja dengan baik, ternyata ringitu tidak membantu banyak, semalam ia mengalami serangan jantung.” Setelah itu suster itu pamit. “Saya ambil sarapannya dulu ya kak.”
"Kayaknya gara-gara kucing deh. Kayanya kucing semalem itu kucing jadi-jadian,” Tiba-tiba pasien ibu berkata padaku setelah suster menghilang dari pandangan. Walaupun obrolan tadi terjadi antara aku dengan suster, tapi ibu itu nimbrung sepertinya sudah terlatih ngerumpi.Walaupun demikian aku tak bisa mencegahnya untuk mendengarkan pembicaraan kami, bagaimanapun juga ruangan ini memang bukan kamar VIP.
“Apaan sih mama, mikirnya yang nggak-nggak. Emang udah waktunya aja kali.” Anaknya, yang duduk di ranjangnya protes.
“Ih kamu mah nggak percayaan kalau orang tua ngomong.” Ibunya sewot. “Di kampung mama nih, kucing itu dipakai orang pinter buat ngirim bala. Apalagi kemarin kucingnya matanya melotot serem. Hiiiy..”
Aku hanya tersenyum.
“Pokoknya kalau di antara kita liat kucing itu lagi, kita cepet-cepet harus mengusirnya, kalau perlu gebuk pakai sapu!”
“Apaan sih mama. Kucing segala pake dicurigain. Mama tau nggak, kalau kucing itu hewan kesayangan Nabi Muhammad. Ntar malah kualat loh”
Setelah itu terjadi perdebatan antara keduanya.
Ucapan ibu tadi walaupun tidak berdasar tapi cukup membuatku bertanya-tanya, apa benar kucing semalam adalah kucing jadi-jadian, apakah kucing itu mencari tumbal setiap harinya? Terus kenapa dia memilih Shiren? Kalau begitu kucing itu bisa saja mencari tumbal selanjutnya. OH MY GOD!
Dan malam hari pun tiba, sepanjang hari selain bertemu dokter yang memeriksa ruam-ruam yang bermunculan di kulitku, tak henti-hentinya aku berhalusinasi tentang kucing jadi-jadian itu. Ayah datang membawa makanan, rupanya dia mengerti sekali kalau makanan rumah sakit hambar rasanya, ia datang sejak sore hari sehabis pulang kantor, dan sekarang ia tertidur di sofa yang ada di sudut ruangan. Kasian, pagi-pagi buta ayah harus bangun dan pulang ke rumah untuk berganti pakaian kemudian berangkat kembali ke kantor, gara-gara aku ayah jadi kerepotan, padahal ibu berpesan agar aku menjadi wanita yang kuat, bukan wanita sakit-sakitan begini.
Aku lagi-lagi tak bisa tidur. Malam ini begitu sunyi, yang kudengar hanya bunyi tik tok jam dinding yang menunjukan pukul sebelas malam, aku merasa kesepian, percayalah rasa ini lebih menyakitkan ketimbang penyakit lupus yang kuderita. Di kampus, aku punya banyak teman, semua memanggil ku Laras, aku rindu mereka semua, beberapa bulan lalu mereka telah menyelamatkan aku ketika aku tiba-tiba ambruk di depan kelas saat presentasi sebuah mata kuliah. Mereka membawaku ke rumah sakit dan menjengukku beberapa hari datang silih berganti, membawa catatan kuliah, membawa karangan bunga, membawa makanan, memberikanku semangat untuk tetap berjuang melawan penyakit sialan ini.
Tapi kini mereka tak datang lagi, 3 hari sudah aku dirawat kembali di rumah sakit, karena tiba-tiba terjadi pendarahan yang luar biasa di rongga hidungku dan jatuh pingsan di kelas. Mungkin mereka sudah terbiasa tanpa kehadiranku atau memang dalam hidup ini pada akhirnya kita akan sendirian. Orang-orang yang kita sayangi akan melanjutkan hidup dan lupa apa yang terjadi. Kalau begitu, mungkin aku tidak perlu khawatir pada ayah yang nanti akan kutinggal pergi.
“Miaww.” Aku terlonjak kaget mendengar suara kucing yang begitu tiba-tiba.
“Kucing jadi-jadian!” Otakku sudah terkontaminasi pikiran pasien tetanggaku. Membuat sebuah hipotesa tanpa dasar menyebut kucing tersebut adalah penyebab kematian Shiren. Alih-alih takut, aku beranjak dari ranjangku dan mencari sumber suara kucing itu berasal. Sepertinya suaranya berasal dari luar.
Detik selanjutnya, aku celingak-celinguk sambil berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang lengang, cahaya lampu neon berpendar membantu penglihatanku untuk mencari kucing jadi-jadian itu.
“Miaw.”
Itu dia! Kucing itu berada di ujung koridor, duduk dan tak bergerak, aku memandangnya lekat-lekat apakah kucing itu kucing asli atau bukan, dia memandangku balik. Bulu kudukku meremang, ingin lari rasanya tapi otak dan kakiku rupanya tidak sejalan, kaki ku malah berjalan mendekati kucing itu, berjalan kearahnya perlahan-lahan agar dia tak lari.
“Pus.” Entah keberanian dari mana, aku memanggil kucing itu. Biar kujelaskan dulu bagaimana penampakan kucing yang kini ada di hadapanku. Ras nya domestik alias kucing kampung, kalau dilihat dari badannya yang besar dan gendut sepertinya ia berjenis kelamin jantan, bulunya berwarna orange, warnanya persis seperti karakter animasi Garfield. Matanya besar dan hitam, kucing yang lucu sebenernya, tapi mengingat dia adalah kucing jadian-jadian kesan lucu itu jadi hilang.
“Pus.” Kupanggil untuk kedua kalinya. Jantungku mencelos saat tahu bahwa kucing itu berjalan mendekat. Laras, kamu cari mati. Hatiku membatin
Hatiku lega, saat kucing itu menggesek-gesekan badannya secara manja ke kakiku sesaat dia mengeong pelan, kurasakan ada kehangatan yang menjalar dari tubuhya, bulunya halus dan lembut, apakah dia dirawat seseorang? Rasa-rasanya kucing liar tidak ada yang setampan ini. Lalu dia pergi sebelum aku sempat mengelusnya. Kucing itu hilang dari pandangan, walaupun pertemuan itu singkat, aku yakin bahwa dia hanya kucing biasa, bukan kucing jadian-jadian.
“Namanya Oscar.”
Aku hampir menjerit kaget saat mendengar suara itu tiba-tiba hadir di belakangku. Aku menoleh ke belakang. Kulihat seorang dokter berkacamata berdiri di belakangku. Sejak kapan? Mungkin sejak pertemuanku dengan si kucing. Rasanya aku tidak asing dengan dokter ini. Oh iya, dokter jaga kemarin malam! Aku tidak lupa dengan clipboardyang dia bawa. Berwarna biru tua, kulihat jas putihnya tersemat name tag bertuliskan “dr. Fendy”
“Kok tahu dok namanya Oscar?” Tanyaku
“Soalnya itu kucingku.”
Terkuak sudah misteri kucing jadi-jadian. Ingin rasanya kuberitahu pada pasien tetanggaku langsung, betapa jahatnya sudah meracuni pikiranku untuk berprasangka buruk pada Oscar.
“Kenapa diberi nama Oscar?” Tanyaku padanya.
“Kenapa kamu tidak di ranjangmu malam-malam begini?” Dokter Fendy bertanya balik padaku, yang langsung kujawab dengan kikuk
“Erhmm.. Anu.. “
“Duduklah.” Dia menunjuk bangku panjang yang terletak di pinggir koridor.
Sepertinya dia mengerti kalau aku lelah berdiri sebentar saja, penyakit ini sungguh menyebalkan. Tanpa diperintah dua kali, aku duduk di bangku panjang tersebut, kemudian Dokter Fendy duduk di ujung satu nya.
Sebetulnya saya penasaran dengan Oscar. Ada yang bilang kematian Shiren diakibatkan karena ulah Oscar yang menginginkan tumbal.Ingin rasanya aku berkata itu pada Dokter Fendy, tapi aku yakin dia akan menertawakanku. Berani taruhan, dunia astral pasti tidak ada tempat bagi mereka yang masa hidupnya sebagian besar dihabiskan dengan membaca buku.
“Saya hanya bosan saja di kamar dok.” Malah kalimat itu yang keluar dari mulutku.
“Kamu tak perlu berbohong.” Kata Dokter Fendy. “Kamu curiga kalau Oscar adalah penyebab kematian Shiren dan mencoba menyelidikinya kan?”
Apakah dokter belajar membaca pikiran orang juga pada saat kuliah? Kalau iya berarti aku harus hati-hati dengan pikiranku.
“Banyak kok yang berpikir seperti itu juga.” Dia melanjutkan. “Mengira Oscar membawa malapetaka pada pasien.”
“Lalu apakah itu benar?”
“Tentu saja tidak.” Kata Dokter Fendy. “Malah sebaliknya. Oscar membantu pasien untuk tenang dalam menghadapi ajalnya.”
Aku terdiam, Mencoba mencerna perkataannya.
“Oscar mampu mendeteksi kematian. Pasien yang tak memiliki waktu lama lagi akan mengeluarkan bau kimia atau istilahnya disebut Feromone, yang hanya bisa dicium oleh Oscar. Saat mencium bau tersebut, oscar akan langsung datang ke kamar pasien lalu melompat ke ranjang pasien, disana dia akan meringkuk di sebelah tubuh pasien selama berjam-jam untuk menemani pasien.”
Aku masih terdiam.
“Oscar juga dapat menyerap energi negatif dari pasien.”
“Energi negatif yang seperti apa?”
“Kamu pernah mendengar tentang 5 tahapan kesedihan?”
Aku menggeleng.
“Pada umumnya, manusia akan mengalami lima tahapan dalam merespon sebuah kenyataan pahit tentang kesedihan, entah itu karena putus cinta, kematian, atau gagal dalam usaha.” Dokter Fendy menjelaskan. “Lima tahapan itu adalah, penolakan, kemarahan, penyesalan, depresi, dan penerimaan."
“Maksudnya?” Tanyaku penasaran.
“Pada fase pertama, sesorang akan menolak kenyataan apa yang telah membuatnya bersedih. Pada tahap kedua, yaitu kemarahan, seseorang akan cenderung mencari kambing hitam, mencari sesuatu yang dapat disalahkan, pelampiasan amarah ini tentu saja bukan hanya pada manusia, terkadang seseorang bahkan marah pada tuhan nya sendiri, menganggap semua ini tidak adil.
“Saat rasa putus asa mulai melemahkan pemikiran manusia, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berharap bahwa kejadian pahit tersebut tidak terjadi dan berharap semuanya bisa kembali seperti sedia kala, semua itu ada di tahap penyesalan.
“Depresi adalah tahap ke empat. Tahap ini adalah tahap yang paling menyakitkan, seseorang akan mengurung diri, tidak makan, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tahap ini lah seseorang seharusnya mendapatkan pertolongan, pertolongan tersebut bisa berupa motivasi, atau dukungan dari keluarga, kerabat, teman, sahabat, pacar untuk meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja.
“Tahap kelima. Penerimaan, kalau seseorang sudah mencapai tahap ini. Sudah dipastikan bahwa dia sudah naik kelas. Artinya sudah dapat menerima kenyataan bahwa hidup ini harus terus berjalan, meskipun kehidupan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.
"Dan energi yang coba diserap oleh Oscar adalah energi yang ditimbulkan pada saat manusia berada fase kemarahan, penyesalan, dan depresi.”
“Apakah Oscar dapat menyembuhkan penyakit?” Tanyaku lagi.
“Mungkin saja. Hal itu juga sedang menjadi perhatian saya. Dengan adanya penelitian bahwa kucing dapat menyerap energi negatif, kesembuhan mungkin saja didapatkan oleh pasien selama pikirannya tetap positif dan semangat untuk terus melawan penyakitnya.”
Lalu Dokter Fendy duduk mendekat ke arahku. Kini jarak kami hanya 30 sentimeter saja. Dan tiba-tiba saja tangannya mengusap-usap kepalaku. “Nah mulai sekarang kamu harus yakin bahwa kamu bisa melawan penyakitmu.” Tandasnya sambil tersenyum padaku.
Sepersekian detik aku merasakan desir angin yang entah datang dari mana. Senyuman Dokter Fendy itu manis sekali, matanya yang indah di balik kacamata itu menampilkan sosok yang meneduhkan, wajahku bersemu merah. Aku buru-buru menolehkan wajahku ke arah berlawanan, berharap Dokter Fendy tidak melihat wajahku yang memerah ini.
“Sudah larut. Sebaiknya kamu kembali ke ruang rawat. Di sini juga dingin, tidak bagus buat kamu.”
Kemudian, aku bangkit dan bergegas masuk kembali ke ruang rawat. Tanpa menoleh ke arahnya, masih mencoba menyembunyikan muka ku. Sebelum aku membuka pintu. Aku bertanya padanya,
“Apakah dokter menangani penyakit dalam juga?” Memang tidak sopan, aku berkata padanya dengan membelakanginya. Berharap dia tidak hanya dokter jaga di malam hari saja, tapi bisa menangani penyakit lupus ku ini.
“Saya sedang koas di sini. Masih harus belajar lagi untuk ambil spesialisasi penyakit dalam.”
Aku kecewa dan merasa senang secara bersamaan. Kecewa karena penyakitku tidak bisa ditangani olehnya tetapi di lain sisi, aku punya alasan untuk tidak merasa kesepian selama di rumah sakit sekarang.
###
Esok harinya, mentari bersinar dengan teriknya, mengantarkan energi panas ke bumi yang membuat beberapa manusia di atasnya kegerahan. Salah satu di antara manusia itu adalah aku. Aku mengibaskan telapak tanganku beberapa kali ke wajah, menghalau rasa panas yang menyerang. Aku berada di salah satu ruang tunggu di rumah sakit yang AC nya tidak berfungsi dengan baik. Di ruangan itu aku ditemani ayah dan beberapa pasien yang menunggu giliran untuk memasuki ruangan yang di pintunya bertuliskan instalasi Radiologi.
Hari ini, secara mendadak tim dokter yang menanganiku memintaku untuk melakukan scanningMRI setelah aku tiba-tiba terjatuh tak kuat berdiri saat aku hendak pergi ke toilet, mereka ingin tahu kondisi terakhir seluruh organ bagian dalamku untuk nantinya akan digunakan untuk dievaluasi dan langkah apa yang sebaiknya diambil.
Aku duduk di kursi roda sekarang, infus telah terpasang di tanganku. Sedangkan kakiku, khususnya bagian lutut, rasanya lemas sekali, mereka tak kuat menopang tubuhku. Pagi tadi ayah panik bukan kepalang melihatku tumbang di samping ranjang, pagi ini ia meminta ijin dari kantornya untuk menemaniku melakukan scanMRI.
“Ayah seharusnya tak perlu menemaniku. Aku bisa sendiri kok”
“Jangan khawatir sayang, ayah sudah meminta cuti dari bos ayah.”
Bohong. Aku tahu ayah berbohong. Jatah cuti dalam satu tahunnya sudah habis untuk menemaniku. Sepertinya dia memutuskan untuk membolos.
“Ayah sudah sering ambil cuti, mungkin jatah cuti ayah sudah habis hanya untuk menemaniku.” Aku protes pada ayah. “Jika ayah terus-terusan nggak masuk kerja gini, ayah bisa di PHK loh.”
“Ayah lebih baik kehilangan pekerjaan dibandingkan kehilangan kesempatan bersamamu, nak.”
“Hentikan Yah.” Suaraku bergetar menahan tangis. “Berhentilah mengkhawatirkanku. Yakin saja aku akan baik-baik saja. Dengan ayah berkata seperti itu pun ayah seperti tak yakin bahwa waktu ku tak akan lama lagi.”
“Loh..”
“Tahu aku akan mati,” aku memotong perkataan ayah. "Jadi ayah nggak mau kehilangan kesempatan saat-saat terakhirku kan."
“Ayah sudah kehilangan ibumu, saat itu ayah tidak banyak waktu untuk menemaninya, sekarang ayah tidak mau mengulang kesalahan yang sama lagi.”
“Tuh kan.” Nadaku mulai meninggi. “Artinya ayah sudah tahu aku sebentar lagi mati!”
"Bukan begitu maksud ayah nak.”
Aku merasakan beberapa pasang mata sudah tertuju pada kami. Mungkin mereka sedikit kecewa saat adegan itu harus terhenti karena namaku dipanggil petugas, giliranku untuk di scanpun tiba. Proses scanningtidak terlalu lama, aku hanya disuruh berbaring pada alat yang nantinya bergerak masuk kedalam lingkaran besar. Setelah itu aku disuruh kembali ke ruang rawat inap.
Ayah mendorong kursi rodaku kembali menuju ruang rawat. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya sejak kami berdebat di ruang tunggu. Kami berdua hanya diam. Saat melewati salah satu koridor di rumah sakit, aku melihat Oscar. Dia sedang meringkuk di ranjang seseorang yang dirawat di ruang VIP yang tak sengaja gorden jendelanya tersibak, sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. Entah sejak kapan dan bagaimana dia berada di sana. Tapi yang jelas akan ada isak tangis lagi tak lama lagi di rumah sakit ini. Aku benci rumah sakit.
Malamnya aku menunggu Dokter Fendy di ranjangku, tak sabar menantikan kunjungannya yang memeriksa keadaan beberapa pasien di ruang rawat inap.
Dokter Fendy memiliki wajahnya oriental, kacamata bundar yang bertengger di hidungnya yang mancung membuatnya terlihat sangat manis. Perawakannya tinggi kurus, aku tidak tahu pasti berapa usianya, tapi sepertinya dia masih sangat muda, mungkin 23 tahun. Dokter Fendy bilang masih koas, buat yang belum tahu koas biar ku jelaskan apa itu koas (dibaca ko-as). Koas adalah tahap dimana seorang mahasiswa harus lakukan dalam memenuhi kompetensi sebelum dinyatakan sebagai seorang dokter. Kalau kata kasarnya, Koas merupakan strata terendah di dalam rumah sakit, dimana dokter muda yang selalu mengikuti dokter senior kemanapun pergi, dari mulai visit pasien sampai menulis rekam medis, dan tentu saja disuruh-suruh jaga malam.
Kira-kira setelah koas selesai, dia minat mengambil spesialisasi apa ya? Sudah berapa lama dia menjalani koas? Apakah dia sudah memiliki pacar? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam benakku. Namun, sampai detik ini Dokter Fendy belum menampakan batang hidungnya, padahal jam dinding di ruang rawat sudah menunjukan pukul 11.15.
Ingin rasanya aku keluar ruangan, mencari udara segar, berjalan-jalan keliling rumah sakit mungkin saja aku akan bertemu dengan Dokter Fendy di ruang jaganya. Tapi sendi-sendiku ini rasanya sakit sekali, untuk digerakan saja rasanya susah, aku tak berdaya sampai akhirnya aku jatuh tertidur.
Besoknya, seperti dugaanku, ada pasien yang meninggal, dia adalah pasien yang kemarin kulihat bersama Oscar yang kudengar beritanya pasien tersebut kanker darah stadium 4. Positifnya dari meninggalnya seseorang yang memiliki sakit keras adalah setidaknya dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Ruang rawat inapku pun sudah genap penghuninya. Ranjang Shiren kini terisi oleh pasien berumur 3 tahun, dia mencret-mencret setelah minum pemutih pakaian akibat keteledoran orang tuanya, beruntung masih selamat. Hanya saja terkadang seisi ruangan mendadak bau kotoran.
Aku gagal bertemu dengan Dokter Fendy tadi malam, sepertinya dia tidak datang atau mungkin tidak sedang jaga malam. Tapi sama sekali tidak ada dokter jaga pengganti yang mengecek pasien. Walaupun aku tidur tapi pasti aku terbangun dengan suara pintu ruang rawat kalau dibuka, kupingku sangat sensitif jadi tak mungkin aku melewatkannya.
“Ibu tidak mendengar ada dokter jaga yang datang tadi malam?” Aku bertanya pada pasien tetanggaku dan pada anaknya juga. Yang ku ketahui baru-baru ini bernama Bu Ratih dan Rahma
“Tidak nak, bahkan selama seminggu ibu di sini tidak pernah tahu ada dokter jaga yang berkunjung tiap malam.”
Kemudian aku memencet tombol panggilan untuk memanggil suster. Beberapa menit kemudian seorang suster menghampiriku,
“Ada yang bisa dibantu kak?” Tanya suster itu. Aku mengenalnya. Dia suster Mila.
“Dokter Fendy kemarin tidak ada jadwal jaga ya suster?” Tanyaku.
“Dokter Fendy?” dahi Mira mengerut
“Iya, dokter Fendy yang masih Koas itu loh suster? Masa gak tau.”
Mila diam sejenak. Aku menunggu jawabannya, ku perhatikan Bu Ratih dan Rahma turut menanti sebuah jawaban juga nampaknya.
“Dokter fendy sudah nggak ada sejak sekitar sebulan yang lalu.”
“Nggak ada gimana, baru 2 hari yang lalu saya ketemu dia.”
“Nggak mungkin kak. Dokter Fendy sudah meninggal.”
Hatiku mencelos, aku masih ingat sentuhan Dokter Fendy yang menyentuh kepala ku.
“Saat menuju ke rumah sakit, beliau kecelakaan.” Tandas Mila.
Aku masih belum percaya akan hal itu, pertemuanku dengannya nampak seperti nyata. Lalu Oscar?
“Lalu apa benar Oscar kucing milikinya?”
“Betul. Beliau membawa Oscar kesini sedang melakukan researchtentang kemampuan kucing dalam mendeteksi kematian pasien. Pihak rumah sakit pun tidak keberatan dengan hal tersebut selama tidak ada protes dari pasien. Walaupun majikannya sudah tiada, kucing itu tetap setia di rumah sakit ini,"
Otakku bertanya-tanya. Jadi yang kutemui tempo lalu itu siapa?
“Suster tahu tanggal berapa tepatnya Dokter Fendy meninggal?” Tanyaku.
“Tanggal 28 Juni, dua hari lalu diadakan peringatan 40 hari meninggalnya Beliau di rumah orang tuanya di daerah Jakarta Barat, beberapa staf dan dokter rumah sakit turut hadir.”
Aku tak bisa berkata kata lagi.
“Seseorang yang meninggal, arwahnya masih berada di bumi selama 40 hari, mungkin yang dilihat dan bersama nak Laras waktu itu adalah arwahnya Dokter Fendy.” Kata Bu Ratih. “Nah saat 40 hari lewat. Arwahnya sudah pergi ke langit.”
Mataku mengeluarkan air mata, pertemuan singkat dengan arwah Dokter Fendy tidak membuatku takut, hanya saja, mengapa Tuhan mempertemukan dengan seseorang yang aku suka kemudian menghilangkannya begitu saja, Tuhan benar-benar tidak adil.
Malam itu langit memuntahkan air. Seakan mengerti isi hatiku yang menangis ini. Bunyi tetesan yang menimpa atap rumah sakit begitu menenangkan. Aku menggigil, tubuhku demam sejak kabar bahwa Dokter Fendy sudah meninggal masuk ke otakku. Aku seperti lumpuh. Untuk duduk saja aku dibantu dua orang suster. Kini keadaanku makin parah.
"Miaw."
Sayup-sayup suara kucing tertangkap indera pendengaranku. Dan betapa terkejutnya aku bahwa tiba-tiba sosok Oscar melompat di ranjangku. Ia menatapku lama kemudian dia menggesekan tubuhnya yang halus ketanganku sebelum akhirnya dia meringkuk di samping tubuhku. Pikiranku lelah untuk memikirkan bagaimana Oscar bisa masuk ke ruangan padahal aku yakin pintu sedang tertutup rapat. Tanganku yang tertanam selang infus masih kuat untuk mengelus kepala Oscar. Dia nampak tenang.
Aku menoleh ke arah sofa. Dimana ayahku sedang tertidur pulas. Badannya yang kurus dan renta terbungkus kaus tipis. Raut wajahnya tenang meneduhkan. Kini ayah tidak perlu mencemaskan aku lagi. Berbahagialah ayah. Kau berhak akan hal itu.
END


 dimdim02
dimdim02