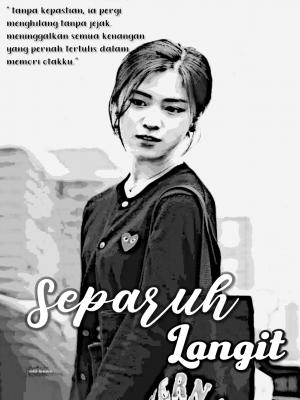THE DAY BEFORE
11:40 PM
Pada tengah malam yang cerah, Ella berjalan di setapak pemakaman umum.
Kalau para hantu serta konco-konconya terhitung sebagai makhluk, Ella sudah pasti menjadi pusat perhatian karena sudah mengganggu pesta malam keakraban mereka. Apalagi dengan gaun merah yang dikenakannya, mungkin Ella akan dinobatkan sebagai Prom Queen.
Sambil bersenandung pelan, Ella membetulkan cangkul yang sedang dipikulnya. Tangan kanannya menyapu satu batu nisan ke nisan yang lain. Membaca setiap nama yang tak sengaja terbaca olehnya lalu berdoa dalam hati. Ella bukan seorang religius, tapi seperti mandatori baginya bahwa setiap datang ke pemakaman, berdoa adalah hal yang wajib selain menyebar bunga.
Sayangnya, Ella tidak membawa bunga.
Ella mendadak memelankan langkah lalu berhenti bersenandung. Gadis itu menurunkan cangkul, memperhatikan sekelilingnya yang hening. Saat ini, Ella sudah tiba di tengah pemakamanan. Makam yang menjadi tujuannya malam ini seharusnya berada tak jauh dari posisinya sekarang.
“Kanan apa kiri, ya?” gumamnya.
Setelah menimbang beberapa saat, Ella mengikuti instingnya untuk ke kanan. Sambil melanjutkan langkah, kali ini Ella tidak bersenandung. Ia masih sesekali berdoa tapi lebih sering menghembuskan napas panjang. Berjalan di setapak pemakaman pada tengah malam mestinya tidak terasa semembosankan ini, kan?
Ella hampir menghembuskan napas panjang yang kesekian kalinya saat sudut mata nya menangkap sesuatu. Sudut bibirnya perlahan turun, menyadari sesuatu itu ternyata merupakan tujuannya.
“Seharusnya aku nggak perlu repot-repot,” katanya, dengan nada yang terlalu keras hantu yang sedang tidur pun akan terbangun olehnya. Ella melanjutkan langkah, mendekati makam destinasinya. “Bawa cangkul dari parkiran mobil ke sini hanya untuk, apa, olahraga ringan?”
Ujung heels hitam Ella menyentuh gundukan tanah yang mengelilingi makam. Ella menghentakkan cangkul, kesal melihat objek makamnya sudah terbuka lebar. Batu nisan yang kini tampak miring bertuliskan ‘Nino Herdian’. Di salah satu sisi makam, seorang pria tampak duduk dengan santai. Disampingnya, sebuah cangkul lain tergeletak dipenuhi tanah, sama seperti kedua ujung jari dan pakaian lusuh yang dikenakan pria itu.
Pria itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Ella dari balik poni yang basah oleh keringat. “Kamu terlalu lama. Aku tidak bisa lebih lama lagi bernapas dari tumpukan tanah sialan itu.”
Kalau Ella tidak mengenal pria di depannya dengan baik, ia sudah pasti histeris ketakutan saat melihat wajahnya yang pucat serta bibir yang terlalu kering. Atau mungkin, Ella sedang berhadapan dengan hantu emo, gentayangan karena galau yang tidak berkesudahan.
“Begitu, ya?” ucap Ella, bersekedap tak peduli. Ia memperhatikan kedua tangan pria di depannya yang bergetar dan napasnya yang pendek-pendek. “Bangkit dari kubur sepertinya berat sekali, ya--” berikutnya, Ella menekankan setiap kata yang keluar dari mulutnya, “--Nino Herdian.”
Nino mendengus lalu mengulurkan tangannya yang kotor oleh tanah. Ella secara spontan menatapnya jijik.
“Bajuku, mana? Aku butuh baju bersih,” jawab Nino, melihat kesekeliling Ella. Sadar gadis itu tak membawa apapun selain cangkul, ia menurunkan tangannya. “Kamu bahkan tidak membawa bunga.”
Ella memutar bolanya lantas mendekati Nino. “Bawa cangkul saja sudah memakan banyak tenaga. Mana sempat aku membawakanmu baju,” Ella berhenti di samping Nino, membuat pria itu mendongak untuk melihatnya. “Lagipula, yang kamu butuhkan saat ini bukan baju bersih. Melainkan…”
Ella merogoh saku gaun merahnya lalu menyodorkan ponsel pada Nino. “Seseorang menunggu untuk kamu telepon,”
Dari tempat Nino duduk saat ini, Ella tampak menyeramkan dengan cahaya bulan yang remang di belakangnya. Gaun semerah darah dan sepasang mata kucing itu sama sekali tidak membantu. Nino melihatnya tidak suka, merasa terintimidasi dengan situasinya saat ini. Seakan Ella punya kuasa yang lebih daripada Nino yang, omong-omong, baru saja bangkit dari kubur.
Pada akhirnya, Nino menerima ponsel yang diberikan Ella.
“Selamat datang kembali di dunia fana, Nino Herdian,” ucap Ella, tersenyum manis.
*
00:00 PM
Telepon itu berdering di waktu yang salah.
Deringnya yang terdengar hingga sudut terjauh apartemen itu membuktikan bahwa sunyi sejatinya sedang mengambil alih. Di salah satu koridor, sebuah pintu terbuka setengah. Dering yang masih menggema di antara kesunyian itu menyusup keluar dari sana.
Tak ada yang berbeda dari kamar sederhana itu. Tempat tidur yang masih rapi tanda belum disentuh, lemari kayu di salah satu sisi tembok, dan meja belajar yang lebih ramai daripada isi kamar. Sebuah laptop terbuka di atasnya, menunjukan halaman Microsoft Word yang setengah terisi oleh rangkaian induk dan anak kalimat. Di sebelahnya, ponsel keluaran terbaru tergeletak, bergetar-getar oleh panggilan masuk.
Layarnya yang kerap menyala menampilkan nama pemilik nomor panggilan masuk. Terpampang jelas bagai maklumat yang tak bisa diabaikan.
Nino.
Dua tahun yang lalu, nama itu sudah menjadi sejarah di dalam kehidupannya. Tapi nasib seperti sedang mempermainkannya, membawa nama itu kembali sebagai pengingat bahwa apa yang sudah berlalu tak berarti hilang.
Gadis itu meringkuk di sudut kamar. Sambil memeluk kedua lututnya yang bergetar, ia berusaha mengatur napasnya yang menjadi tak karuan sejak telepon itu berdering.
“Mustahil…” gumamnya, menahan air mata. “Ini tidak mungkin...”
Ketika pada akhirnya telepon itu berhenti berdering, gadis itu dengan kalap beranjak dari posisinya. Ia mengambil ponsel lalu mencari kontak nama yang harus dihubunginya saat ini juga sebelum dirinya kehilangan akal sehat.
Beruntungnya, gadis itu hanya harus menunggu tiga nada sambung sebelum orang lain di ujung yang berbeda mengangkat telepon tersebut.
“Jes?”
Sebuah suara berat menjawabnya.
“Dia baru saja meneleponku!” seru gadis itu, panik.
Lawan bicaranya terdiam sesaat. Lalu, “Siapa?”
“Nin--Nino…” jawab gadis itu, berbisik pelan hingga nyaris tak terdengar. “Gimana bisa ini terjadi, Bi?”
“Jes--”
“Bagaimana mungkin…” gadis itu berbisik lirih lalu terisak pelan. Ia bersandar pada sisi meja belajar lalu merosot turun. “Aku membunuhnya hari itu. Aku membunuhnya, Bi…”
*
THE MORNING
Billy selalu membusungkan dada setiap kali kakinya melangkah masuk ke kantor.
Ada sesuatu yang membuatnya tak pernah kehilangan rasa bangga. Sulitnya berjuang menjadi bagian dari Intel Kepolisian ternyata tak pernah lekang dari ingatannya. Menjelma bagai amunisi rasa bangga yang meletup-letup dalam dirinya.
Tapi bahkan setelah melewati itu semua, pagi ini, Billy tidak merasa bangga. Tidak ada aksi membusungkan dada, tidak ada derap langkah tegas seperti yang sudah-sudah. Semua energi yang semestinya penuh, pagi ini hilang tak tersisa. Billy tak punya tenaga untuk sedikit saja merasa bangga.
Billy melewati pintu masuk kantor dengan lesu. Tangan kirinya membawa setumpuk berkas lama yang kertasnya sudah menguning sementara kunci mobil berdencing di tangan satunya. Seorang penjaga menyapanya ketika melewati meja resepsionis tapi Billy sama sekali tidak menyadarinya.
Kantor Intel Kepolisian padat seperti biasanya. Para penjaga keamanan kota itu hilir-mudik mengerjakan tugasnya, bergumam membicarakan satu kasus ke kasus lain yang tak ada habisnya.
Ketika Billy muncul, keributan ruangan perlahan berkurang. Semua pasang mata seketika menaruh atensi pada dirinya. Billy yang tak peduli, terus berjalan menghampiri mejanya di salah satu sudut ruangan. Sampai akhirnya ia duduk dan membanting berkas menguning itu ke meja, baru keramaian kantor kembali seperti semula.
Billy menghembuskan napas panjang lalu mengusap wajahnya yang kusut.
“Detektif Billy,” sapa seorang kolega. Billy mendongak, mendapati seorang wanita tinggi dengan sepasang mata kucing. Wanita itu membawa dua cangkir kopi lalu meletakan satu di antaranya ke meja. “Malam yang buruk?”
“Thanks,” sahut Billy, menyesap kopi yang masih mengepulkan uap. “Malam yang sangat buruk.”
“Oh? Ceritakan padaku, Bi!” seru koleganya, menarik kursi dari meja sebelah untuk mendekati Billy.
“Ella…” Billy menatap koleganya ini ragu. Seakan apa yang ingin diutarakannya ini bisa membuatnya gila. Pada akhirnya, Billy menggelengkan kepala lalu kembali pada berkas yang dibawanya.
Ella melirik berkas lalu mendengus. Gadis itu kemudian bersandar pada kursi.
“Sesuatu terjadi pada Jessi?” tanyanya.
Billy mengangguk pelan. “Dia bilang seseorang meneleponnya tadi malam.”
“Lalu? Semua orang bisa menelepon Jessi,”
“Tapi yang menelepon ini bukan orang biasa, El,” jawab Billy, masih sambil membolak-balik berkas. Fokusnya terpecah, sama sekali tidak bisa berpikir jernih. “Aku harus menemukan sesuatu--”
Ella menahan pergerakan tangan Billy. Melihat itu, Billy menoleh pada koleganya yang kali ini menatapnya serius.
“Apa yang terjadi?”
Billy menghela napas, lalu menjawab, “Nino. Nino Herdian menelepon Jessi tadi malam.”
Satu alis Ella terangkat kemudian terkekeh kecil. “Kamu bercanda,”
Tapi Billy jelas tidak bercanda. Pria itu kembali pada berkasnya yang sudah memenuhi meja kerja.
“Kamu tidak bercanda,” sahut Ella lagi, menghentikan tawanya. Gadis itu lalu bersedekap dengan kening mengernyit. “Itu tidak mungkin, Bi. Nino mati dua tahun yang lalu! Mungkin Jessi--”
“Jessi tidak berbohong, El,” putus Billy. Ia berhenti pada selembar kertas yang dicarinya. Matanya membaca dengan cepat lalu melipatnya ke saku. Setelah itu, Billy beranjak dari kursinya.
“Darimana kamu tahu Jessi tidak berbohong, Bi?”
Billy meraih kunci mobilnya lalu berjalan memutari meja. “Karena Nino juga meneleponku semalam.”
Ella menatap punggung Billy yang menjauh lalu menghilang di koridor. Gadis itu menghembuskan napas, berpindah tempat duduk ke kursi Billy yang masih hangat karena ditinggal pemiliknya. Ella mengangkat salah satu kertas lantas membacanya dalam hati;
Pembunuhan Nino Herdian
Sambil menyesap kopinya yang hangat, Ella tersenyum dalam diam.
*
THE DAY BEFORE
11:55 PM
Berapa kali pun Billy mencoba mengacuhkannya, telepon itu tetap berdering.
Ia mengernyit, tak habis pikir bagaimana nama itu muncul pada layar ponselnya. Sejauh yang Billy ingat, seumur hidupnya tak pernah menyimpan satu nomor telepon dengan nama Nino pada daftar kontak ponselnya. Billy akan lebih percaya kalau orang yang meneleponnya tengah malam adalah kantor kepolisian atau Jessi.
Tapi, Nino? Dia sudah mati dua tahun yang lalu, demi Tuhan.
Billy tak akan pernah lupa bagaimana pria muda itu tersenyum kala terakhir kali sebelum peluru menghunus keningnya. Suara tawanya yang renyah bagai manusia paling bahagia meski kematian menyambutnya dengan kedua tangan yang terbuka lebar. Billy mengingatnya, di setiap malam, di setiap mimpi buruk yang menghantuinya.
Terdorong insting detektifnya, Billy memutuskan untuk mengangkat teleponnya. Ia mengecilkan volume TV lantas dengan tangan bergetar menekan tombol hijau.
Sesaat, tidak ada suara yang muncul. Lalu,
“Opsir Billy?”
Dua tahun berlalu, dan suara itu tetap diingat oleh Billy.
“Opsir Billy? Oh, haruskah aku menyebutmu… Detektif Billy?”
“Siapa ini?” tanya Billy, mengencangkan genggamannya pada ponsel. “Telepon iseng di tengah malam melanggar undang-un--”
“Demi Tuhan, Billy. Mesti aku memperkenalkan diri, huh? Ini aku. Nino! Nino Herdian,” kemudian Nino bergumam kecil, “Astaga, mati dua tahun dan semua orang langsung tidak mengingatmu…”
Billy mendengus. Ia bangkit dari sofa lalu mendekati jendela ruang tengah. Sebut saja Billy paranoid, tapi ia tak mau ambil risiko. Pria itu mengintip dari balik jendela, berharap seseorang ada di sana. Namun, yang didapatinya hanya jalan komplek yang sepi dan sunyi, tak ada tanda-tanda seseorang sejak menguntitnya.
“Nino Herdian sudah mati dua tahun yang lalu. Jadi, katakan padaku, siapa ini dan apa keperluanmu menelepon tengah malam, huh?”
“Oh iya, iya. Benar sekali. Nino Herdian mati dua tahun yang lalu. Penyeledikan untuk kasusku itu ternyata membuat pangkatmu di kepolisian naik, bukan? Seharusnya kau berterima kasih padaku, Detektif Billy. Kematianku membawamu keberuntungan,”
“Kematianmu membawa semua orang kebaikan, Nino.” Billy tercekat, sungguh asing menyebut nama itu setelah sekian tahun berusaha untuk tidak lagi-lagi menyebutnya.
“Begitu ya…” sahut Nino. “Tapi aku baru saja hidup kembali, Detektif. Ternyata aku masih memiliki satu tugas yang belum selesai di dunia ini.”
Billy mematung. Mendadak merasakan setiap sendinya berubah kaku.
“Apa Jessi sudah tahu rahasiamu, Billy?”
“Kamu tidak akan berani--”
“Tentu saja aku berani, Billy,” kali ini Nino terdengar lebih serius. Hilang sudah jejak nada bercanda sebelumnya. “Aku akan mengatakan semuanya pada Jessi. Kau mencuri kekasihku, anyway.”
“Tunggu--”
“Besok malam, Detektif Billy. Dan, sejak kau suka sekali menjadi pusat perhatian, keramaian akan menjadi temanmu besok malam.”
“Apa? Aku tidak--”
“Sampai nanti, Detektif Billy!”
Sambungan telepon terputus. Billy menatapnya tak percaya lalu membantingnya ke atas meja. Masih dengan napas yang memburu, Billy bersandar dengan kedua tangannya pada bingkai jendela. Ia tak bisa membiarkan Nino, atau siapapun yang meneleponnya barusan itu, membocorkan rahasianya pada Jessi. Rahasia itu seharusnya hanya menjadi miliknya seorang.
Jessi tidak perlu mengetahuinya.
Tiba-tiba, ponselnya kembali berdering. Billy nyaris mengangkatnya kembali tapi tertahan ketika melihat siapa orang yang meneleponnya.
Jessi.
Nino bilang ia akan memberitahu Jessi rahasianya besok malam. Itu artinya, Billy punya waktu 24 jam sebelum hal itu benar-benar terjadi. Setelah mengatur napasnya menjadi lebih tenang, Billy mengangkat telepon dari kekasihnya itu.
“Jes?”
*
THE AFTERNOON
Suasana ibukota memadat menuju sore hari. Di hari Jumat yang cerah, Jessi seharusnya berada di antara padatnya ibukota di luar sana. Menikmati dunia yang tak pernah berhenti memberikan kejutan, mencari inspirasi untuk buku yang sedang Jessi tulis. Tapi Jessi harus puas mengendap di apartemennya sendiri. Bukan keinginannya, tentu saja. Namun, rasa takut yang merayapinya mampu menahan diri untuk tidak keluar.
Jessi memandang jalan raya ibukota dari balik jendela apartemennya di lantai lima belas. Deretan mobil mewah dan angkutan umum itu menjadi fokus perhatiannya. Nino mungkin berada di antara kerumunan itu. Atau mungkin--Jessi memandang apartemen yang berada di seberangnya--Nino berada di salah satu kamar gedung apartemen itu.
Menyadari pikirannya ngalor-ngidul, Jessi menghembuskan napas panjang. Ia memejamkan mata lalu merasakan seseorang mendekatinya di belakang. Gadis itu dapat mencium aroma musk, bercambur baur dengan aroma masakan dari arah dapur.
“Daripada melamun, mending kita makan siang,” ucap Billy. Jessi menyandarkan punggungnya pada Billy yang segera merangkul pingkulnya. “Emangnya ada yang seru buat dilamunin?”
Jessi memutar bola matanya. “Mana kutahu. Mungkin… Nino?”
“Sudah kubilang berkali-kali, Jes. Siapapun yang menelepon semalam itu, sudah pasti bukan Nino. Kita tahu penjahat itu sudah mati dua tahun yang lalu,”
Tentu saja. Nino Herdian sempat menjadi artis warta berita pada saat kematiannya. Penjahat wanita yang pernah menjadi kekasih Jessi itu kerap muncul di halaman utama koran dan portal berita selama sehari penuh karena kriminalitas yang dilakukannya. Bersama Billy dan Jessi, ketiganya sontak menjadi nama yang banyak diketik pada mesin pencari Google selama seharian.
“Aku membunuhnya,” gumam Jessi. Sekilas memori malam itu di kamar rumahnya yang lama muncul; Nino yang tertawa dan Jessi yang menarik pelatuk pistol digenggaman nya. “Aku benar-benar membunuhnya, Bi…”
Billy menghela napas lalu menarik Jessi agar berhadapan dengannya. Ditatapnya gadis cantik yang sudah mengisi hidupnya ini lamat-lamat. Ia membelai rambut Jessi lalu turun hingga ke pipi. Sepanjang Billy melakukan itu, ia tak habis pikir bagaimana Nino bisa menyakiti wanita secantik Jessi dan menyia-yiakannya begitu saja.
Sampai di satu titik, Billy melirik luka yang membekas pada leher Jessi. Bekas luka Nino yang tak pernah hilang.
“Mungkin yang meneleponmu semalam memang Nino,” kata Billy. “Tapi kamu tahu aku tidak akan membiarkan dia melukai kamu lagi sampai kapanpun, kan?”
Jessi menunduk lalu mengangguk pelan. Ia kemudian meletakkan keningnya pada pundak Billy yang kokoh.
“Kenapa orang itu masih menghantui kita meski ia sudah mati, Bi?” tanya Jessi.
Karena rahasia itu.
Melihat Jessi yang putus asa, Billy tak ingin hal lain selain mengatakan rahasia yang sudah memberatkan hidupnya selama dua tahun ini. Tapi Billy tak siap dengan reaksi yang akan diberikan Jessi. Billy selamanya tak siap untuk ditinggal pergi Jessi setelah gadis itu tahu apa yang sebetulnya terjadi pada malam pembunuhan Nino.
Billy memeluk Jessi dengan erat. “Aku tak akan membiarkan seorang hantu menyakitimu, Jes,” katanya, menatap pantulan dirinya pada kaca jendela apartemen. “Tidak akan pernah.”
*
TWO YEARS BEFORE
February 12th
Pertama kali Jessi dan Nino pergi kencan, keduanya sama-sama mengenakan gaun rumah sakit yang membosankan. Namun, dengan latar belakang atap rumah sakit yang asri dan langit malam yang cantik, suasana kencan kala itu jauh dari kata membosankan.
Sementara beberapa lantai di bawah sana para suster kebingungan mencari dua pasiennya yang absen, Jessi dan Nino tertawa pelan, berbagi rahasia yang hanya mereka dan Tuhan yang paham. Keduanya duduk bersila di salah satu tembok, merasakan hilir angin yang sesekali memainkan rambut dan menerbangkan bungkusan cokelat yang menjadi menu kencan malam itu.
“Ouch!” Jessi mendadak meringis saat sedang tertawa. Tangannya refleks menyentuh bekas operasinya pada bagian perut.
“Jes, kamu baik-baik saja?” tanya Nino, yang sigap mencengkeram kedua bahu Jessi.
Jessi mendengus geli. “Aku baik-baik saja. Ini semua gara-gara kamu, aku jadi kebanyakan tertawa sampai melukai bekas jahitanku,”
Nino memutar bola matanya, kembali rileks. “Makanya jangan jadi manusia receh,”
Jessi mendorong pelan Nino yang ikut tertawa. Beberapa saat kemudian, mereka sama-sama terdiam. Namun hening yang menyelimuti keduanya sama sekali bukan keheningan yang janggal. Jessi menghembuskan napas lalu menatap sudut kota yang malam ini tampak hidup dengan bisingnya suara klakson serta derum mesin kendaraan di kejauhan. Nino menatap Jessi dengan tatapan hangat.
“Aku sudah menceritakan padamu kenapa aku harus operasi karena menelan biji salak sialan itu,” kata Nino, kembali membuat Jessi tersenyum kecil. “Sekarang, giliran kamu yang cerita. Apa yang terjadi padamu, Jes?”
Awalnya, Nino pikir Jessi tidak akan bersuara. Namun, perempuan itu menunduk lalu membalas tatapan Nino. “Adikku bermain-main dengan pistol milik mendiang papaku. Karena panik, saat aku memergokinya di kamar, dia tak sengaja menekan pelatuk dan menembakku.”
“Wow…”
Jessi mengangkat bahu. “Adikku itu memang luar biasa liarnya. Sudah menginjak SMA tapi belum juga bisa mengurus hidupnya. Sehari-hari hanya bermain sama geng motor anehnya itu, huh.”
“Aku yakin adikmu tidak bermaksud menyakitimu, Jes.”
“Well…” Jessi menatap langit lalu menarik napas panjang. “Siapa yang tahu. Aku tidak punya keluarga yang harmonis, No. Setiap hari, rasanya seperti kami mencoba saling membunuh satu sama lain. Aku tak pernah merasa rumah seperti ‘rumah’, kamu mengerti maksudku, kan?”
Nino menatap Jessi selama beberapa saat dengan raut wajah yang serius. Lantas, ia ikut menoleh pada langit malam.
“Aku mengerti,”
*
THE EVENING
Jessi baru saja selesai membereskan piring kotor saat telepon itu kembali berdering.
Billy sudah pamit sejak sejam yang lalu, mengatakan ia baru saja mendapatkan pesan penting dari kantor. Selama Billy berada di sisinya, telepon itu sama sekali tidak berdering. Namun, saat ini, suara deringnya kembali memenuhi seisi apartemen.
Jessi tak tahu harus bereaksi apa. Tubuhnya mendadak kaku dan terdiam di dapur. Teleponnya yang berdering bergetar-getar di atas meja makan yang baru selesai ia bereskan. Sambil harap-harap cemas, Jessi mendekati meja. Berharap setengah mati siapapun yang meneleponnya bukan orang dari alam yang berbeda.
Ketika nama yang muncul di layar ponselnya ‘Ella’, Jessi nyaris pingsan. Keualahan dengan rasa lega yang membanjirinya. Jessi tanpa ragu mengangkat teleponnya.
“Halo?”
“Jessi! Oh, thank God!”
Mungkin Jessi merasa lega terlalu dini. Mendengar nada suara Ella yang cemas, Jessi tiba-tiba saja kembali merasa tegang.
“Ella?”
“Billy! Sesuatu yang buruk baru saja terjadi,” katanya, membuat Jessi segera menjatuhkan diri pada kursi makan. “Please, Jes, kamu harus menolongnya.”
“Apa maksudmu, El? Jelaskan dengan benar!”
“Ini tentang Nino, Jes,” saat Ella menyebut namanya, Jessi seperti merasa setiap sendinya putus dan mati. “Nino menculik Billy dan ingin kamu datang menemuinya.”
“Di-dimana?”
Ella terdengar mendengus putus asa. “Mana kutahu, Jes! Mungkin Nino menghubungimu?”
Setelah itu, Jessi segera memutuskan sambungan telepon. Ia membuka kotak masuk dan melihat pesan singkat dari Nino yang belum dibukanya. Dengan tangan bergetar, Jessi membuka pesan tersebut, melihat sederet kalimat yang membuatnya cepat-cepat bangkit lalu keluar dari apartemen.
*
TWO YEARS BEFORE
May 4th
Hari saat Jessi membunuh Nino, ia baru saja pulang dari kampus. Masih dengan pakaian lusuh oleh keringat dan setumpuk proposal, Jessi melangkah masuk ke rumahnya yang tidak terkunci. Tapi bukan karena itu yang membuat Jessi seketika merasa sesuatu yang salah sedang terjadi di rumahnya.
Namun, bercak darah yang mengotori lantai rumahnya.
“Ma?” panggil Jessi ragu. Mestinya Jessi berlari keluar dan mencari pertolongan, tapi rasa cemasnya yang memuncaknya membuatnya urung. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada ibu dan adiknya di rumah.
Jessi melangkah pelan. Berusaha agar langkah kakinya tidak terdengar sambil mengikuti jejak darah. Napasnya memburu tak karuan tapi ia tetap melangkah maju, menuju ruang tengah yang sudah berpenghuni.
“Jes?” panggil Nino. Di saat yang bersamaan, Jessi berteriak histeris, membiarkan proposal yang sejak tadi dibawanya jatuh berserakan.
Nino sedang duduk di sofa. Memainkan pistol milik mendiang ayah Jessi yang entah kenapa sudah ada digenggamannya. Tepat didepannya, tubuh ibu dan adik Jessi tergeletak tak bernyawa. Ibu dengan luka tembak pada kening dan adik laki-laki Jessi dengan luka tembak pada perut dan kening.
“Apa yang kamu lakukan?” tanya Jessi, menatap Nino nanar.
Nino mengernyit bingung lalu berdiri, masih dengan pistol di tangannya. “Jes? Kamu yang bilang kalau rumah ini tidak terasa seperti rumah. Ingat, tidak? Kamu juga bilang kalau keluargamu rasanya saling membunuh satu sama lain? Aku hanya mencoba membantu,”
“Membantu?” beo Jessi, berjalan mundur. “Kamu baru saja membunuh keluargaku!”
“Jes!” seru Nino, mencengkeram tangan Jessi erat. “Aku tahu rasanya tinggal bersama keluarga yang tidak harmonis. Kamu bukan satu-satunya yang pernah disakiti oleh adikmu sendiri…”
Jessi menggeleng dengan panik. “Kamu… kamu pembunuh, No…”
Mendengar itu, Nino merasakan sesuatu terbuka di dalam kepalanya. Wajahnya segera berubah serius dan cengkeraman tangannya menguat, tak peduli pada Jessi yang merintih kesakitan.
“Aku. Bukan. Pembunuh!” pekik Nino, mendorong Jessi hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Gadis itu merasakan sakit luar biasa pada kepalanya, tapi ia berusaha tetap sadar lalu merangkak menjauhi Nino.
“Apa gunanya punya keluarga yang tidak harmonis, Jes,” ucap Nino, sambil tertawa kecil. “Mereka tidak berguna!”
Jessi merangkak hingga sampai mendekati meja depan televisi. Ia melihat pistol milik ayahnya tergeletak di sana.
“Jes! Kita memiliki satu sama lain saat ini. Kita bebas!”
Tapi Jessi sama sekali tidak merasa bebas. Ia meraih pistol yang pernah melukainya itu lalu tanpa ragu menembakan sisa pelurunya tepat di kening Nino.
*
THE EVENING
“Sudah kuduga,” gumam Billy, membaca pesan singkat yang baru saja dikirimkan oleh salah satu koleganya.
Tadi pagi, Billy sudah sibuk kesana-kemari, menghubungi kolega-koleganya yang bisa diajak kerja sama dalam diam. Billy menyuruhnya untuk melakukan pengecekan pada makam Nino Herdian, mencari keganjalan yang terjadi.
Makamnya terbuka lebar, Bi. Kalau itu belum terdengar aneh, ada sesuatu yang lebih aneh lagi--
Billy memberhentikan mobil yang sedang dikendarainya di lampu merah. Ia bersandar, membaca kembali pesan dari Jimmy, koleganya.
--mayatnya terbakar sampai habis! Bisa kamu bayangkan itu?!
“Yang mati sudah pasti tidak akan bisa kembali,” kata Billy lagi.
Ketika ia sedang membaca pesan dari Jimmy, sebuah pesan lain masuk. Membaca nama yang muncul pada layar ponselnya, Billy seketika duduk dengan tegak. Ia baru saja menerima satu pesan email dari Nino.
Setengah mati panik, Billy membukanya. Mendapati foto Jessi yang terburu-buru keluar dari apartemen dan sederet pesan singkat, menyebutkan lokasi kemana Jessi pergi.
Come save your princess, Bi. I’ll wait.
*
THE (JUDGEMENT) NIGHT
Jakarta Fair terlihat penuh sesak malam ini.
Jessi menatap kerumunan di depannya lalu berbalik badan. Ia hampir saja berteriak saat sebuah kembang api meledak di belakangnya. Semua orang disekelilingnya bertepuk tangan riuh, tak menyadari seorang gadis yang sudah seperti akan pingsan dalam hitungan detik.
Sambil berusaha menghubungi Ella, Jessi menyelinap di antara kerumunan. Kolega Billy itu tak mengangkat telepon sejak terakhir kali ia menghubungi Jessi. Gadis itu tahu, seharusnya ia memberanikan diri menelepon Nino. Tapi, sungguh, ia sama sekali tak ingin berbicara dengan psikopat yang semestinya sudah menjadi hantu itu.
“Sial!” pekiknya, kesal.
Jessi sudah hampir akan menelepon Billy waktu ponselnya berdering lebih dulu. Bukan Ella atau Billy, tapi Nino--Nino Herdian.
“Halo?”
“Akhirnya! Sulit sekali menghubungi kamu ya, Jes.”
Jessi mendengus. Lantas, “Apa yang kamu lakukan pada Billy?”
“Billy? Ah, kenapa kamu tidak melihatnya saja sendiri, sayang. Daripada kamu sendirian di situ, lebih baik kamu ikut denganku, benar?”
Fakta bahwa Nino bisa melihatnya tapi ia tidak bisa melihat Nino membuat Jessi segera frustasi. Gadis itu menoleh ke kiri dan kanan, ke atas gedung, dan memutari badannya. Tapi yang ia lihat hanya kerumunan pengunjung yang tertawa bebas.
“Berhenti berputar, sayang. Lihat aku di sini,”
Jessi mengikuti arahannya dan berhenti berputar. Ia melihat ke arah suatu kerumunan dan perlahan, ia melihat sesosok yang kerap muncul di mimpi buruknya di sana. Berdiri diam di antara pengunjung yang berlalu-lalang.
Nino tersenyum lalu berbicara pada ponselnya, “Ikut denganku, Jes.”
*
Selama lima belas menit, Jessi mengikuti Nino mengelilingi Jakarta Fair yang semakin sesak. Pria itu sesekali meliriknya dari atas bahu, melempar senyum kecil, lalu melanjutkan perjalanan menuju salah satu pintu gedung.
Setelah melewati beberapa stan dan pameran, Nino berbelok, menaikki tangga yang semestinya terlarang untuk didatangi pengunjung. Namun sepertinya Nino sudah mengurus segala sesuatunya karena ia tetap melangkah pasti tanpa mengkhawatirkan satpam atau penjaga lainnya.
Sesaat kemudian, Nino masuk ke salah satu ruangan kosong. Pria itu berhenti tepat di depan jendela floor-to-ceiling yang menghadap langsung ke arah panggung. Di salah satu sisinya, terdapat satu jendela kecil yang terbuka, membuat suara keramaian di bawah sana terdengar samar-samar.
“Dimana Billy?” tanya Jessi.
Nino menghembuskan napas lalu berbalik badan. “Mana kutahu. Dia kan kekasihmu. Seharusnya kamu lebih ta--”
Jessi merogoh celana jeansnya, mengeluarkan pistol yang sama seperti yang digunakannya dua tahun lalu. Nino menatapnya dengan satu alis terangkat.
“Kutanya sekali lagi. Dimana Billy, huh?!”
“Atau, apa, kamu akan membunuhku?”
“Aku sudah pernah membunuhmu sebelumnya, Nino. Akan kulakukan lagi jika aku harus,” sahut Jessi, mendekati Nino dengan pistol terangkat.
Melihat itu, Nino mendadak tertawa. Suara tawanya yang terdengar lepas dan membahana, membuat Jessi seketika mengernyitkan kening.
Suara tawa itu…
“Kamu…” Jessi menggenggam pistolnya erat-erat. “Kamu siapa?”
“Nino! Nino Herdian!” seru Nino, mengangkat kedua tangannya dengan heboh. “Apa semuanya belum jelas, Jes?”
Jessi menggelengkan kepalanya pelan. “Bukan… itu, bukan suara tawa Nino…”
Tidak peduli betapa Jessi membenci seorang Nino Herdian, Jessi tak pernah melupakan bagaimana pria itu tertawa untuknya. Dan, pria di depannya ini tidak tertawa seperti Nino yang dikenalnya.
“Oh,” sahut Nino, menghentikan tawanya. “Ternyata kamu mengingat Nino Herdian, Jessi.”
“Siapa kamu, huh?! Dimana Bil--”
“Jes!”
Pintu ruangan menjeblak terbuka. Jessi dengan spontan tersentak lalu mengarahkan pistol pada siapapun yang baru saja masuk. Ketika dilihatnya Billy sedang menodongkan pistol ke arahnya, Jessi menghembuskan napas lega.
“Billy!” seru Jessi, menurunkan pistol secara spontan. Namun, didepannya, Billy tidak mengikuti gerakannya. Alih-alih menurunkan pistol, Billy mengalihkan moncong pistol ke arah Nino.
“Hentikan omong kosong ini. Atau aku akan--”
“Apa?” tantang Nino. “Membunuhku? Lagi?”
Mendengar itu, Jessi mengernyitkan kening. “Lagi?” beonya. Gadis itu kemudian menatap Nino dan Billy bergantian. “Bi? Apa maksudnya?”
“Jessi, kamu sudah dibohongi kekasihmu selama ini,” ucap Nino, berjalan mendekati jendela kecil yang terbuka. “Kamu tidak pernah membunuh Nino--”
“Diam di tempat!” pekik Billy.
“--tapi kekasihmu yang melakukannya.”
Setelah itu, Nino bergerak cepat. Ia melempar ponselnya, mendarat dengan keras pada kening Billy yang segera menarik pelatuk. Sayangnya, peluru yang keluar hanya menyentuh tembok. Memanfaatkan Billy yang oleng, Nino segera melompat dari jendela yang terbuka.
“No!” pekik Jessi, lebih karena spontan. Ia berlari mendekati jendela, melihat siluet Nino yang ternyata jatuh ke atas jaring-jaring tempat bermain mandi bola anak-anak yang berada tepat di bawah jendela.
Nino secepat mungkin turun dari jaring-jaring tersebut. Ia mendongak pada Jessi, tersenyum, lalu menghilang di antara kerumunan.
*
LAST PART OF JUDGEMENT NIGHT
Billy mengerang kesakitan, menyentuh keningnya yang membengkak. Detektif muda itu melihat tangannya lalu bersumpah pelan saat menyadari darah segar mengalir dari luka pada keningnya.
“Bi,” panggil Jessi. Suaranya yang lemah mendadak memberikan sensasi resah pada Billy. Beberapa saat yang lalu, Nino baru saja membuka rahasia yang susah payah Billy sembunyikan.
“Jes,” sahut Billy, menatap Jessi yang masih menatap kerumunan melalui jendela. “Aku bisa jelaskan semuanya,”
Jessi berbalik badan lalu bersedekap. “Oke.”
Billy menarik napas lalu berjalan mendekati Jessi. “Hari ketika Nino terbunuh, aku datang ke rumahmu, Jes. Bukan karena seseorang menelepon kepolisian, tapi karena Nico,” Billy terdiam sesaat. Lantas, “Nico Herdian.”
“Ni...co?”
“Ada alasan kenapa Nino seperti Nino yang kamu temui, Jes. Keluarganya penuh masalah. Ayahnya seorang pemabuk sementara ibunya sakit-sakitan. Nico, adik yang hanya terpaut setahun dengan Nino, memiliki jiwa liar yang sulit ditenangkan. Berkali-kali Nino berusaha melindungi Nico, berkali-kali pula ia gagal,”
Saat ini, Billy sudah berdiri tepat dihadapan Jessi. Jarak pendek diantaranya sangat membuat Billy sakit kepala.
“Suatu hari, sang ibu meninggal karena penyakit yang dideritanya. Fakta itu membuat sesuatu dalam diri Nino rusak, Jes. Hal yang terjadi berikutnya, Nino berusaha membakar rumah dan keluarganya yang masih ada di dalam. Ayahnya tidak selamat, dan seharusnya Nico juga tidak selamat dari kebakaran itu. Tapi…”
Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Nico Herdian berhasil selamat dari kebakaran itu entah bagaimana caranya. Seseorang sudah pasti membantunya. Dari apa yang dilihat Jessi malam ini, Nico bersih tanpa luka bakar. Siapapun yang menyelamatkan Nico adalah orang yang sama yang meminta Nico untuk melakukan perubahan pada wajahnya. Membuat sang adik menjadi replika kakaknya.
“Nico meneleponku di hari Nino tewas, Jes. Sama seperti yang ia lakukan padamu dua hari yang lalu. Memperingatiku bahwa Nino akan membunuh seseorang. Oleh karena itu, aku datang ke rumahmu dan membunuh Nino,”
“Tapi, Bi, aku yang menarik pelatuk itu!”
Billy menggeleng. “Itu hanya ingatanmu yang salah. Ketika aku datang, kamu sudah terkapar di lantai setengah sadar. Lalu Nino mulai tertawa seperti orang gila sebelum aku menembaknya,”
Jessi berusaha memutar ingatannya. Menyusun timeline yang sudah tidak beraturan sejak dua tahun lalu. Hingga pada satu titik, Jessi akhirnya berhasil menemukan sebuah memori yang sempat terlepas.
Ketika Nino mendorongnya ke lantai, Jessi tidak merangkak untuk mengambil pistol. Adalah Billy yang pada saat itu datang dan menarik pelatuk.
“Kamu membiarkan aku berpikir bahwa aku membunuhnya, Bi,” ucap Jessi pelan. “Aku yang sama sekali tidak bisa tidur sejak hari itu.”
Billy menunduk. “Aku hanya tidak ingin kamu membenciku.”
“Karena sudah menyelamatkanku?”
“Karena aku seorang pembunuh,” sahut Billy, kembali menatap Jessi. “Aku membunuh Nino, Jes. Aku tahu, itu adalah hal yang benar. Tapi perasaan membunuh itu tidak hilang, Jes. Aku… aku membunuh…”
“Billy,” Jessi menghilangkan jarak lalu memeluk Billy. “Aku tidak akan membencimu karena sudah menyelamatkanku,”
Billy menghembuskan napas lalu membalas pelukan Jessi. “Maafkan aku, Jes.”
Keduanya bertahan dalam posisi yang sama selama beberapa saat. Ketika di luar sana suara kembang api kembali terdengar, Jessi memutuskan untuk melepas pelukan.
“Bi, bagaimana dengan Nico?”
“Aku masih harus mencarinya,” jawab Billy mantap. “Nico sama berbahayanya dengan Nino. Ia tidak bisa dibiarkan bebas. Tapi sebelum itu--”
Jessi menatap keseriusan pada wajah Billy. “--aku harus mencari tahu siapa yang bekerja sama dengannya.”
*
“Aku tidak menyelamatkanmu untuk sebuah kegagalan, Nico,”
Nico berdecak kesal, melirik Ella yang berderap mendekatinya. Ia sedang berdiri di depan makam Nino yang masih terbuka lebar. Namun, berbeda dengan malam sebelumnya, saat ini garis polisi sudah melingkarinya.
“Aku tidak gagal,” jawabnya. “Tugasku hanya membuat Billy mengakui rahasianya pada Jessi. Sudah, kan?”
Ella yang kini sudah di sampingnya, bersedekap. “Tapi kamu gagal menghancurkan hubungan keduanya.”
“Bukan salahku,” Nico mengangkat bahu. “Ella, ada banyak laki-laki di luar sana. Untuk apa sih semua ini kamu lakukan pada Billy? Dia tidak menaruh hati padamu.”
“Aku yang ada untuknya selama ini, Nic. Bukan wanita sialan itu,” amuk Ella.
“You are damn crazy woman,” ucap Nico, menggelengkan kepala. Ia kemudian berdiri tegak. “Well, berhubung tugasku sudah selesai, sekarang waktunya aku pergi.”
Nico berjalan melewati Ella yang segera mendengus. “Dasar keluarga tidak berguna,”
Mendengar itu, Nico menghentikan langkahnya. Ia berbalik badan, menatap punggung Ella. “Apa katamu barusan?”
“Oh?” sahut Ella, berbalik badan. “Aku bilang, dasar keluarga tidak bergun--ah!”
Nico mendorong Ella tanpa ragu. Wanita keras kepala yang telah menyelamatkannya itu kini terbaring tak berdaya pada lubang makam Nino. Darah segar perlahan mulai mengalir dari kepalanya yang terbentur batu. Kalau Ella belum tewas saat ini, ia pasti akan tewas karena kehabisan darah.
“Sayang sekali,” ucap Nico, berbalik badan meninggalkan Ella. “Kamu berurusan dengan keluarga yang salah.”
END


 andnsa
andnsa