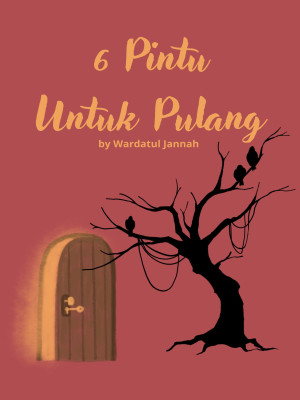25 September
Dengan penuh semangat aku masih bertahan menunggu Fatir yang telah berjanji akan menjemputku. Mengenakan baju tunik abu dan celana jeans hitam lengkap dengan bando berbahan kain melingkar di kepala, aku siap menyambut pacarku. Sebetulnya, pria yang akrab dipanggil Acil itu sudah telat sepuluh menit dari jam yang telah disepakati, tapi itu tidak lantas membuatku kesal. Binar bahagia masih tersisa selepas hari anniversary kami yang pertama dua hari lalu. Hubunganku dengannya adalah hubungan terlama yang pernah kujalani selama ini. Rasa bosan yang menyergap di awal menjalin hubungan seringkali menjadi alasan kandasnya hubunganku di masa lalu yang baru seumur jagung. Namun Acil mengajarkan diriku akan pentingnya sebuah komitmen dalam sebuah hubungan. Ia pernah menuturkan, jika kedua pihak memegang teguh komitmen serta sepenuh hati menjaganya, maka rasa bosan, kesal, dan lelah yang kerap hadir hanya akan menjadi bumbu dalam satu hubungan, menjelma menjadi sebentuk perasaan untuk mempererat kedekatan, bukan malah menjadi penyebab perpisahan.
Mobil hitam berplat D itu berhenti persis di depan pagar rumahku. Dapat kulihat dari teras rumah, Acil keluar dari mobil dan melangkah masuk ke halaman. Senyum itu. Kembali ia tampilkan di hadapan mataku untuk kesekian juta kalinya. Ku balas dengan senyuman hangat pula. Tentu senang rasanya ketika orang yang ditunggu telah datang memenuhi janji. Ahh, kadang bahagia bisa sesederhana ini. Iya benar, hanya dengan menyaksikan orang yang kita sayangi tersenyum bahagia.
“Maaf ya aku telat,” katanya setelah jarak tubuhnya lumayan dekat denganku.
“Gapapa, cuma telat dikit kok.” Sahutku.
“Ibu sama Ayah ada?” Acil mengedarkan pandangan ke arah jendela demi melihat ke dalam rumah.
“Kebetulan Ibu lagi pergi sama Ayah, katanya sih ada urusan sama temennya.” Jelasku sesuai yang dikatakan Ibu sebelum pergi. Berhubung ini hari Minggu, ayahku ada di rumah menikmati akhir pekan. Jika di hari kerja, ayah biasanya pergi bekerja dari pagi hingga petang dan terkadang baru pulang ketika malam menyelimuti langit.
“Ohh gitu.. jadi, mau langsung pergi aja nih?” tanya Acil dan langsung kusetujui.
Acil mulai menancap gas. Mobil melaju menyusuri jalanan kota Bandung yang agak lengang. Sesekali mataku menikmati pemandangan di kanan-kiri jalan. Sementara Acil fokus menyetir, diriku yang duduk tepat di sampingnya memburu tombol-tombol dekat dashboard mobil untuk memutar lagu favorit kami. Lagu berjudul You Are The One ini seakan mampu mewakili perasaan kami berdua yang hanya ingin menjadi satu-satunya, bukan salah satunya. Tak jarang ketika lagu itu mengalun kami pun ikut bernyanyi, lalu saling melempar pandangan dan tersipu malu setelahnya. Namun kali ini kami hanya menikmatinya dalam diam dan beberapa anggukan kecil.
“Oh iya Ra, kayaknya, sekarang kita gak bisa ke resto Jepang itu deh. Temenku bilang sih, hari ini tempat itu lagi tutup.” Kata Acil tiba-tiba.
“Lho, kenapa tutup ya?” mataku sedikit mendelik karena heran.
“Emm.. Katanya sih, lagi libur gitu restonya. Gimana dong?” tertangkap gelagat aneh ditunjukkan olehnya. Tidak biasa.
“Ya udah gapapa, kita cari tempat makan lain aja,” jawabku akhirnya setelah beberapa saat mengira-ngira apa yang mungkin disembunyikan lawan bicaraku.
“Gimanaa.. kalau kita makan di mal deket tempat kerjaku aja? Kamu mau gak?”
“Boleh. Dimana aja aku mau kok. Di pinggir jalan pun gak masalah. Sesekali kita coba beli nasgor atau soto ayam gitu, di trotoar depan sana,” aku menyarankan demikian karena hampir dapat dipastikan dirinya berbohong perihal tutupnya resto itu dan sepertinya ia tengah mengalami masalah keuangan. Mengingat harga makanan di resto pasti jauh lebih mahal dibanding sebagian besar makanan yang disajikan di mal. Mungkin saja ia kehabisan uang sebab dibelikan hadiah-hadiah ketika anniversary kemarin. Jika dihitung-hitung, pasti tidak sedikit uang yang harus ia keluarkan demi merayakan hari istimewa itu. Padahal diriku tak pernah meminta apapun padanya. Harga jam tangan yang kini telah melingkar manis di pergelangan tanganku saja, pasti harganya di atas lima juta. Belum lagi boneka jumbo berbentuk tokoh kartun keroppi, kartun favoritku. Itu semua belum termasuk balon-balon, bunga mawar, dan hal-hal lain yang ia persembahkan untukku pada hari itu.
“Lain kali aja kayaknya Ra, sekarang kita ke mal aja ya?” ia tetap teguh pada pendiriannya. Akhirnya aku menurut saja.
Jujur, saat ini aku benar-benar merasa ada yang janggal dengan pria yang sudah kukenal sejak lebih kurang sepuluh tahun lalu itu. Entah mengapa ada seberkas rasa curiga yang menyelimuti hati ini. Dirinya tak pernah bersikap semencurigakan ini sebelumnya. Sejak awal aku dan dia memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih, rasanya tak pernah ada yang disembunyikan diantara kami. Apapun kenyataannya bagaimana pun itu, pahit maupun manis selalu kami utarakan agar tak ada rasa curiga seperti yang tengah kusembunyikan saat ini. Saking tak ingin ada rahasia, bahkan Acil mengaku siap mendengarkan segala curhatanku. Sekalipun hal yang ku ceritakan seringkali hanya hal sepele dan mungkin saja bukan hal penting baginya. Namun ia tak pernah mengeluh akan celotehanku, yang ada Acil akan sangat heran jika aku tidak bercerita apa-apa padanya ketika bertemu. Sungguh beruntungnya diriku memiliki orang yang mampu mengerti perasaan pasangannya.
Terlepas dari itu semua, sesungguhnya Acil adalah tipe orang yang sangat friendly. Dulu, saat pertama kali mengenalnya ia merupakan kakak kelasku di SMP. Ia sudah duduk di kelas 9, namun itu tak membuatnya gengsi untuk sekedar ngobrol atau menyapa adik kelasnya. Yaa.. contohnya padaku yang ketika itu baru masuk SMP dan duduk di kelas 7. Dengan statusku sebagai adik kelasnya terpaut dua tingkat, aku tak pernah memanggilnya dengan panggilan Aa, Kakak, atau sebagainya, aku lebih nyaman memanggil nama panggilannya saja, Acil. Dan ia tak pernah keberatan akan hal itu. Setelah ia lulus SMP, aku dan dirinya tak pernah berkesempatan untuk bertemu dengan waktu yang lama. Kami hanya saling mengenal dan menyapa sewajarnya bila sewaktu-waktu berpapasan. Lagipula waktu itu diriku belum memiliki ketertarikan padanya. Justru kami mulai dekat setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Jika diingat lagi, peristiwa yang membuat aku dan Acil dekat itu bisa dibilang kebetulan.
Waktu itu hari Sabtu. Meta, sahabatku, meminta untuk mengantarnya ke salah satu sanggar mural yang berlokasi tak jauh dari kampus tempatku kuliah. Tentu diriku dengan mudah menyetujui. Katanya ia hendak mendaftarkan diri menjadi anggota sanggar tersebut. Pengarahan pada para pendaftar akan segera dimulai. Aku memilih duduk di salah satu sudut di sanggar itu, tak begitu jauh dari ruangan yang ada Meta di dalamnya. Demi mengisi waktu supaya tidak jenuh, akhirnya ponsel yang menjadi pelarian. Berselancar di sosial media menjadi pilihan. Terlalu larut bermain di dunia maya membuatku tak sadar ada seseorang di dunia nyata sedang berjalan mendekat padaku.
“Kok malah diem disini? Gak ikut kumpul?” sebuah suara pria membuatku sedikit kaget. Spontan kujawab,
“Nggak. Orang kesini cuma mau anter tem…” kalimatku tertahan sebab terkejut dan terpana melihat orang yang kini ada di sampingku. Kedua matanya menatap wajahku lekat-lekat. Aku sangat yakin, aku pasti mengenalnya. Sayangnya ingatanku malah melupakan namanya. Sambil mengingat-ingat, kulemparkan senyum padanya. Sebuah nama sudah terpikir di kepala, namun entah mengapa lidah ini terasa amat kelu untuk sekedar menyebutkannya. Akhirnya mulutku terbuka beberapa kali tapi tidak sampai berhasil mengeluarkan sepatah kata pun.
“Kyara ya?” ia menyebut nama depanku.
“Iyaa bener, aku juga inget nama kamu kok. Cuma dari tadi susah nyebutinnya.” Pria itu tampak tersenyum geli.
“A.. euhh.. dil! eh, apa ya.. aduh kok bisa lupa ya,” aku berusaha keras mengingat namanya, namun gagal.
“Karena kamu manusia.” Ujarnya datar.
“Hm? Maksudnya?” dahiku mengernyit.
“Tadi kan kamu nanya, kenapa kok bisa lupa. Yaa karena kamu manusia. Manusia itu kan gak lepas dari salah dan lupa,” mendengar itu membuatku tertawa cukup keras.
“Apaan sih, garing tau gak” seruku dengan suara yang masih menyisakan tawa.
“Tapi kok bisa ketawa, ya?” tawa kembali pecah diantara kami.
Pertemuan kembali yang menakjubkan. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, akhirnya aku yang sudah kuliah semester 5 bertemu dengannya yang kini sudah berkarir setelah sebelumnya meraih gelar S1 di bidang Ilmu Komunikasi. Dan mural adalah hobinya. Itulah sebabnya ia ada disini sebagai salah satu senior. Setelah pertemuan di sanggar itu, aku dan dia mulai intens berkomunikasi. Baik dengan saling mengirim pesan, ataupun bertemu langsung. Setelah sangat akrab, kami makin erat layaknya sepasang sahabat. Banyak hal yang sering kami diskusikan. Berbagi tawa juga duka adalah hal biasa. Saling mengingatkan dan meringankan beban satu sama lain seakan menjadi kewajiban. Kurang lebih enam bulan lamanya kami bersahabat, hingga Acil mengungkapkan perasaannya yang ternyata lebih dari sekedar sahabat dan berniat menjadikanku sebagai pacarnya. Diriku sempat bimbang. Mana mungkin sahabat akan menjadi cinta? Apakah itu akan berjalan dengan baik? Mungkin rasa bosan tidak sempat hinggap ketika kami bersahabat, tapi apakah akan sama ketika kami berpacaran? Aku sangat ingat, di Alun-Alun Bandung ia mengutarakan keinginannya itu. Kala itu kami duduk di atas rumput sintetis yang menghijau.
“Kamu yakin Cil, kita kan udah lumayan lama sahabatan. Masa iya, tiba-tiba kita pacaran?” kalimat itu cukup mencerminkan betapa ragunya diriku. Acil mengubah posisi duduknya menjadi lebih dekat denganku. Matanya tajam menatap bola mataku. Kulihat pupil matanya yang membesar dan menghitam.
“Ra, justru aku pilih kamu karena kita pernah sahabatan. Dan kamu, satu-satunya cewek yang bisa jadi sahabat aku sekaligus buat aku nyaman. Rasanya bakalan seru aja kalau sisa umurku dihabisin bareng sahabat, yaitu kamu, Ra.” Kembali Acil mencoba meyakinkan raguku.
“Lagian aku gak akan main-main kok sama kamu. Aku ada niatan untuk nikahin kamu, walaupun bukan dalam waktu dekat. Karena untuk saat ini aku masih berjuang buat capai mimpi-mimpi aku sebelum jemput kamu buat jadi istriku nanti. Apa kamu mau nemenin aku berjuang?” lanjutnya dengan suara yang lembut. Mendengar itu membuat hatiku terhentak.
Sungguh diluar perkiraan, orang yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya mengatakan kalimat semacam itu. Ketika itu dia sedang merintis karirnya, sedangkan aku masih berstatus sebagai mahasiswi di salah satu Universitas swasta dan sudah memasuki semester 6.
“Boleh ga aku pikirin dulu? Nanti, kalau udah dapet jawabannya, aku langsung kasih tau kamu deh.” Akhirnya itulah yang mampu meluncur melewati bibirku dengan harap Acil bisa mengerti betapa campur aduknya perasaan yang kini memenuhi hatiku. Kemudian Acil mengangguk pelan.
Tiga hari berikutnya setelah melalui pertimbangan yang matang serta konsultasi pada Ibu dan Ayah, akhirnya aku berhasil meyakinkan hati dan menentukan jawaban atas pertanyaan Acil tempo hari. Mulanya inginku ialah menyampaikan hal ini secara langsung. Tapi saat itu ia sedang pergi ke luar kota untuk keperluan pekerjaan. Seminggu lagi ia baru akan kembali ke kota Kembang ini. Sementara ada rasa tidak enak ketika membiarkannya menunggu terlalu lama. Sehingga diriku memilih memberitahukannya melalui pesan singkat. Yah, setidaknya aku dapat memberinya sebentuk kepastian. Tak disangka, hubungan itu kini telah berjalan selama satu tahun lamanya. Dan karena latar belakang kami yang awalnya sahabat, membuat suasana hubungan kami masih kental dengan nuansa persahabatan. Salah satu bentuknya ialah dari nama panggilan yang belum berubah, masih saling memanggil nama masing-masing. Beberapa tujuan hidup dan mimpi kami satu persatu sukses dicapai. Sekarang Acil sudah memiliki mobil pribadi dan sedang mencicil rumah. Lalu diriku baru saja menyelesaikan sidang skripsi, beberapa bulan lagi aku segera diwisuda. Tentu tidak sedikit perjuangan yang kami lewati untuk sampai di titik ini. Namun semua kepedihan dan air mata itu berhasil kami taklukkan dan kami masih berpegang erat dalam satu prinsip. Tidak akan meninggalkan satu sama lain. Jauh di palung hati, aku pun mengharapkan dirinya lah yang menjadi pelabuhan cinta terkahirku. Tapi masih ada ketentuan Tuhan yang belum kuketahui dan bisa saja mengubah segalanya. Alhasil, sekarang ini aku hanya mencoba melakukan yang terbaik apapun yang nanti menjadi takdirku.
“Heyyy!!” sebuah suara membuyarkan lamunanku tentang masa lalu.
“Kok ngelamun sih? Hati-hati lho nanti kesurupan, aku juga nanti yang repot,” lanjut Acil histeris.
“Ihh naudzubillah.. ” Sahutku sambil tertawa.
“Saha manehh??” Acil menirukan kalimat yang sering ditanyakan pada orang yang sedang kesurupan. Kalimat berbahasa Sunda itu memiliki arti, ‘kamu siapa?’. Tak lupa salah satu tangannya diangkat ke atas kepalaku. Ia merenggangkan jari-jarinya sambil memutar-mutar tangannya persis seperti seorang paranormal yang tengah mengobati pasiennya. Lantas kami pun tertawa karena kelakuannya. Mobil masih melaju dengan kecepatan yang tidak begitu tinggi, hingga akhirnya kami merasa mobil yang membawa kami ini menggilas sesuatu.
Dreb!
“Apa itu tadi?” teriakku spontan.
“Aduh, Ra, kayaknya aku nabrak sesuatu deh. Bentar ya, aku cek dulu,” jelas sekali Acil tampak panik. Lelaki yang mengenakan kaos hijau army itu keluar mengecek bagian bawah mobil. Ia melangkah ke arah ban kanan belakang setelah sebelumnya mengecek depannya. Mataku terus mengikuti tubuhnya sambil masih terduduk dengan sedikit rasa cemas. Semoga saja tadi itu bukan apa-apa.
Duk! Duk! Duk! Duk!
Suara kaca mobil tepat di sebelah kiriku diketuk dengan sangat keras. Tiba-tiba saja ada anak kecil yang mengenakan pakaian kurang bersih berdiri tegap memasang raut wajah yang seakan sedang marah. Matanya melotot, tangannya mengepal habis menggedor kaca. Dia terlihat sangat marah. Tapi entah apa yang sebenarnya ia inginkan. Rasa takut membuatku enggan membuka kaca mobil. Khawatir anak itu bertindak nekad dan malah mencelakaiku. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati apa yang ia gendong. Tampak seperti seekor kucing warna hitam. Meski tak terlihat dengan jelas, namun aku dapat melihat bagian ekornya menjuntai melewati lengan anak lelaki yang masih menunjukkan ekspresi tidak senang itu. Mulutnya membungkam sedari tadi, hingga ia pergi begitu saja dengan berlari menjauhi mobil. Mataku mengikuti tubuh mungilnya yang mulai hilang tenggelam oleh banyaknya orang-orang yang berlalu lalang disana. Entah mengapa, firasatku mengatakan kucing itulah yang tergilas tadi. Jika benar…
Drek!
Pintu di sebelah kanan terbuka. Tubuh ini hampir melonjak dan refleks aku berteriak.
“Kamu kenapa sih?” Acil terlihat kaget dengan teriakanku.
“Kamu gak nabrak kucing kan?” kontan pertanyaan itu kutujukan disertai rasa panik.
“Ga tau. Ga ada kucing di bawah. Tapi tadi aku liat ada bercak darah di ban depan sebelah kiri.” Jelasnya. Aku tak bergeming. Kuhempaskan tubuhku ke kursi yang kududuki sedari tadi. Tubuhku lemas. Tapi jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Setelah mengatur nafas dan berusaha tenang, aku baru menceritakan padanya tentang anak kecil yang menggendong kucing hitam tadi. Berbeda denganku, Acil terkesan cuek dan santai. Bahkan berulang kali ia meyakinkanku bahwa itu hanya sebuah kecelakaan dan memintaku untuk tenang.
“Gak usah jadi beban pikiran dong Ra, Insya Allah kita bakal baik-baik aja kok. Please, jangan percaya tahayul.” Ia mengakhiri kalimatnya. Tetap saja ada rasa tak enak dan kepikiran.
Kami telah sampai di mal yang Acil maksud. Kami parkir di basement. Sejak kecil aku tak menyukai kegelapan. Dan kini aku berada di tempat yang identik dengan cahaya yang minim. Terlebih kejadian di perjalanan tadi yang sedikitnya cukup membuatku parno dan agak ketakutan saat ini. Kupegang erat lengan pacarku. Selanjutnya kami melangkah masuk ke dalam mal. Kurasa ada panggilan masuk ke ponselku, spontan kulepas peganganku pada Acil guna meraih ponsel yang tersimpan di dalam tas selempang yang kubawa. Langkahku menjadi lambat karena hendak menjawab telpon yang ternyata berasal dari Derina, salah satu sahabatku. Baru beberapa detik panggilan itu kujawab, Acil malah pamit pergi ke toilet. Kuputuskan untuk menunggunya di tempat yang agak sepi tak begitu jauh dari toilet. Selepas berbincang lewat telpon beberapa menit, pandanganku kembali tunduk pada layar ponsel sebab Acil belum kunjung memunculkan diri. Detik berikutnya, ada yang menepuk pundakku dari arah belakang, pelan sekali, tapi masih dapat kurasa ada sentuhan. Pemandangan menohok yang kini tersaji di hadapanku. Seorang nenek berpakaian tak rapi dengan rambut yang acak-acakan sampai menutupi sebagian wajahnya. Di tangan kirinya tergenggam tongkat dari kayu. Ingin aku langsung berlari menjauh darinya, namun kaki ini terasa berat bahkan hanya untuk melangkah.
“Neng, jangan takut gitu sama nenek,” katanya dengan suara parau. Rasanya aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun tenggorokanku seolah tercekat.
“Nenek hanya mau memberitahu, mulai sekarang Neng harus hati-hati. Mungkin saja, akan terjadi hal-hal yang diluar dugaan,” sambungnya diikuti tawa. Mengerikan. Matanya menyorot tajam padaku.
“Ma..maa..aff Nek, maksud Nenek apa ya?” Jawabku sambil tergagap. Alih-alih mendapat penjelasan lebih lanjut, sosok Nenek itu malah pergi berlalu meninggalkanku. Arah langkahnya yang gontai dan terseok-seok sepertinya mengarah ke basement tempat tadi Acil memarkirkan mobilnya. Sementara aku langsung mengambil langkah seribu menuju depan toilet yang tadi Acil tuju. Sungguh lega ketika mataku menangkap diri Acil.
“Ciiil..!” aku masih berlari dan terpaksa berteriak agar suara cemprengku terdengar olehnya.
“Kenapa Ra?” suaranya pelan.
“Eh, kamu kok pucet gitu?” melihat Acil yang terlihat lain membuatku mengabaikan pertanyaannya, kini pacarku tampak seperti orang sakit. Wajahnya pucat, suaranya pun tidak seenergik biasanya.
“Masa sih? Perasaan kamu aja kali,” tanggapannya santai.
“Oiya tadi kamu kenapa, teriak-teriak gitu?” sambungnya kemudian. Diriku masih heran dengan perubahan pacarku. Ia mulai melangkah dan aku pun mengikutinya. Sambil berjalan, aku menceritakan apa yang baru saja kualami. Reaksi Acil hanya sekedarnya saja. Ia lebih banyak diam. Sesekali bergumam, kemudian tersenyum.
“Udah ya ceritanya, kita kesini kan mau makan.” Baru kali ini kudengar pacarku menyuruhku berhenti bercerita. Di ujung rasa takutku terhadap sosok nenek misterius tadi, kini hadir rasa bingung yang memenuhi benakku. Rentetan pertanyaan pun bergantian terlintas di pikiranku mengenai pacarku. Sikapnya yang dingin serta tubuhnya yang terlihat lesu menghasilkan ketakutan dan kekhawatiran tersendiri. Jika benar ia sakit, mengapa begitu mendadak dan terkesan tiba-tiba. Padahal sedari tadi kami bertemu dirinya terlihat bugar dan ceria seperti biasanya. Kini sangat bertolak belakang. Sikapnya berubah seratus delapan puluh derajat.
Setelah beberapa saat berjalan dan naik lift hingga sampai di lantai empat, langkah kami akhirnya terhenti di salah satu tempat makan yang menawarkan berbagai macam steak. Tempat itu tidak begitu padat akan pengunjung. Hanya beberapa orang saja yang dapat kami lihat disana. Ada yang masih menikmati makananannya, ada pula yang terlihat masih menunggu pesanannya datang. Suasananya sendiri sangat santai. Lampu-lampu berukuran tak terlalu besar menggantung di langit-langit dan menebarkan cahaya kekuningan yang temaram. Perkakas dan ornamen yang dominan disana terbuat dari bahan kayu dan cenderung berwarna coklat, putih, hitam, dan warna lain sebagai penyempurna. Aku dan Acil duduk di salah satu sudut di tempat itu. Lalu kami memesan makanan yang kami inginkan. Ketika menunggu pesanan kami datang, perhatianku tertuju pada sebidang lahan yang cukup luas tepat di tengah-tengah lantai empat ini. Yang dapat kulihat hanya tali-tali merah yang dikaitkan pada tiang besi kurang lebih berukuran satu meter mengelilingi lahan tak bertuan itu. Sebetulnya rasa ingin tahuku yang tiba-tiba menyembul ini belum terpuaskan, namun kuhentikan usaha untuk mengetahui lebih jauh. Aku baru sadar, sedari duduk disini aku mengabaikan pacarku.
“Eh sorry, aku jadi nyuekin kamu.” Ada rasa bersalah tersirat dalam kalimatku.
“Gapapa. Santai aja, Ra.” Sahutnya datar dengan seutas senyum tipis sekali, sampai hampir tidak terlihat. Kurasa dia sedang menyembunyikan kekesalannya padaku. Jika benar, usahanya kali ini benar-benar gagal. Sikap dinginnya yang makin menjadi tentu dapat kumengerti dengan cepat. Aku pun tak mengerti kenapa tadi aku hingga larut memperhatikan tempat itu.
“Beneran kamu gak sakit? Kamu keliatan lemes banget loh,” kataku prihatin.
“Itu cuma keliatannya aja, padahal mah aku sehat walafiat.” Jawabnya mencoba menenangkan, tapi masih dengan sikap dingin, suara datar dan matanya yang hanya sekilas saja menatapku.
“Kamu marah ya?” kucoba menatap wajahnya yang masih terlihat pucat. Sekilas matanya menatap ke arahku yang duduk di hadapannya dan terhalang meja, tapi seketika kedua matanya kembali terpaku pada layar ponsel yang ia genggam.
“Gak ko.” Katanya sambil tertunduk, suaranya pelan tapi tetap terdengar tegas.
“Yakin, mau marah aja nih?” kuulang kalimat yang sering ia katakan jika aku kedapatan tengah merajuk atau kesal padanya. Biasanya aku akan menjawab dengan gerakan kepala. Anggukan berarti benar aku sedang marah. Dan gelengan ketika aku tidak benar-benar marah, atau sedang pura-pura marah. Acil akan langsung meminta maaf dan menghiburku jika aku mengangguk. Tapi ia akan ikut-ikutan berpura-pura marah jika aku sedang bermain-main dengan kekesalanku.
“Aku gak marah kok. Kamu gak usah khawatir.” Tuturnya tanpa menggerakkan kepalanya sedikitpun. Tapi ia mengakhiri kalimatnya dengan senyum yang lebih lebar.
“Tapi kamu kok diem terus? Gak biasanya.” Kutunggu jawabannya beberapa saat.
“Emangnya, kamu pengen aku gimana, Ra?” ia malah balik bertanya tapi dengan nada tak serius. Ia pun sedikit tertawa ketika mengucapkan kalimatnya.
“Gak pengen gimana-gimana sih. Cuma aneh aja gitu, tiba-tiba kamu jadi pendiem. Biasanya kan kayak cacing kepanasan.” Aku tertawa karena kupikir Acil sedang ingin bercanda. Tapi ia hanya tersenyum. Akhirnya aku tertawa sendiri.
“Aku lagi pengen diem aja.” cetusnya.
“Ooh gitu.” Timpalku singkat. Akhirnya kami membeku di bawah atmosfer keheningan yang perlahan mulai tercipta. Tak ada tawa yang kerap meledak jika kami bertemu seperti sebelumnya. Siapa yang tidak diserang rasa curiga ketika pacarnya berubah sikap. Lagi-lagi pikiranku berkelana mengira-ngira apa yang mungkin sedang ia sembunyikan. Setelah satu tahun lebih dilewati bersama tanpa ada rahasia, kini terasa banyak hal yang sengaja disembunyikan agar aku tak tahu. Getar ponsel yang tergeletak di depanku membuatku sedikit kaget dan terperanjat diantara lamunan yang kian larut. Kembali nama Derina yang muncul. Dahiku mengernyit. Memastikan apakah aku membaca dengan benar, atau salah lihat. Tapi tulisannya tidak berubah, itu artinya benar Derina yang menelpon. Padahal ku rasa penjelasnku saat menelpon tadi sudah sangat jelas ketika ia menanyakan perihal beberapa produk kosmetik yang hendak ia beli dariku. Beberapa bulan terakhir ini aku aktif berjualan online. Mulai dari pakaian, kosmetik, hingga makanan. Derina adalah salah satu langgananku. Mungkin ia akan menambah pesanannya padaku. Segera kuangkat panggilan itu dengan sumringah.
“Ra, lu lagi dimana?” logat betawi dan suara khas wanita yang kerap dipanggil Rina itu memenuhi pendengaranku.
“Ehm? Gue? Lagi di mal sama Acil.” Meski agak bingung, kucoba jawab apa adanya.
“Iya, gue juga tau. Tapi maksudnya lu dimana nya gitu? Mal itu kan luas.”
“Maksud lu apa sih?” tanyaku penuh kebingungan sambil menyiapkan telinga untuk menyimak penjelelasan sahabatku di ujung telpon sana.
“Sekarang gue lagi di mal juga Ra. Ini gue lagi sama Acil. Katanya lagi nyariin lu. Hp dia ketinggalan di mobil. Jadi dia gak bisa nelpon.” Dahiku kembali mengernyit. Tapi kali ini karena aku kurang dapat mengurai dan mengartikan kalimat sahabatku itu.
“Lu lagi sama Acil? Maksudnya?” tanyaku memburu jawaban.
“Iyaa, ini gue lagi sama Acil, pacar lu. Katanya abis dia dari toilet, lu ilang Ra. Lu kemana sih? Gak kesian lu dia bolak-balik nyariin lu.”
“Lu yakin, yang lagi sama lu itu beneran Acil? Salah orang kali lu.”
“Yakin, nih dia lagi duduk di samping gue,”
“Bentar Rin, kalau Acil lagi sama lu, terus yang lagi sama gue ini siapa dong?” diriku mulai ketakutan.
“Gak mungkin Ra, orang Acil lagi sama gue. Jangan-jangan itu makhluk yang mirip sama Acil. Hati-hati, Ra.” Suara Rina terdengar samar.
“Pantesan dari tadi Acil tuh aneh banget sikapnya. Gue pengen ngomong sama Acil dong Rin” Pintaku tergesa.
“Apa Ra? Kok suara lu gak jelas sih? Apa Ra? Ra? Ra?” kemudian suara itu lenyap seiring panggilan itu diakhiri oleh sang penelpon sendiri. Kucoba telpon lagi, tapi nihil, tidak tersambung. Nomor yang dituju malah tidak aktif. Rasa takut dan bingung menyeruak memenuhi diriku. Rasanya tubuhku ditimpa beban yang sangat berat, hingga kurasa kaku pada sekujur tubuhku. Kalimat-kalimat Rina kini terus berulang dalam ingatan. Kembali kuperhatikan sosok yang ada di hadapanku. Pantas saja ia nampak pucat setelah keluar dari toilet tadi, belum lagi sikapnya yang janggal, membuat ia sangat berbeda dengan Acil yang selama ini kukenal. Ternyata ia bukanlah Acil. Aku pun berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkan diri dari sosok misterius ini. Baru ku gerakkan kaki kananku untuk melangkah perlahan demi kabur menjauh, sosok di hadapanku sigap menangkap gerak-gerikku. Tatapan tajam kini ia arahkan padaku. Tentu aku tidak sudi membalas tatapannya.
“Mau kemana?” ia bertanya namun terdengar seperti intimidasi di telingaku. Dadaku seakan terenyak dan tak kuasa menimpali pertanyaan itu. Dengan cepat tangan sosok itu memegang erat tangan kiriku yang masih menempel di meja.
“Aku mohon, jangan sakitin aku. Kita udah beda alam, aku minta kamu jangan ganggu manusia. Aku cuma ngira kalau kamu itu pacar aku.” Ucapku dengan suara gemetar seraya menunduk.
“Aku gak bakal nyakitin kamu. Asal jangan sekali-kali kamu teriak. Janji?”
“Iya, janji. Tolong lepasin tangan aku,”
“Nanti aku lepasin, tapi sekarang ikut aku!” tangaku ditarik agak keras. Tubuhnya menuntunku di belakangnya. Beberapa kali kucoba melepaskan genggamannya tapi yang ada sosok ini menambah kekuatannya. Tangaku makin terperangkap diantara jari jemarinya. Beberapa pengunjung mulai memandangiku. Tanpa disadari makhluk itu menuntunku ke lahan kosong tadi. Sambil tak henti berusaha melepaskan tangan, kakiku kini sudah berada tepat di tengah-tengah tempat yang dilingkari tali-tali tadi. Itu artinya kini aku ada di pusat lantai empat ini. Semua pengunjung mal itu seksama memperhatikanku yang sedang meronta meminta dilepaskan. Tanganku belum bebas juga. Kemudian makhluk itu mengangkat tangan kirinya dan menjentikannya. Bak sebuah perintah, tiba-tiba serentak muncul orang-orang berpakaian warna hijau namun terlihat layaknya zombie yang kerap divisualisasikan di film. Mereka muncul dari segala arah dan semua menuju ke arahku. Tubuh mereka tertahan di sekitar tali merah dan tampak meraung-raung siap menyerang. Takut, bingung, dan perasaan lain yang bercampur menghasilkan air mata yang mulai mengalir deras. Aku benar-benar sendirian saat ini. Tak ada satupun yang bergerak mencoba menyelamatkanku. Pengunjung lain hanya melihatku sebagai tontonan. Kemudian makhluk di hadapanku melepaskan pegangannya perlahan. Langkahnya mundur menjauhiku. Badanku terasa kaku. Aku tak tahu apa yang harus kuperbuat. Atau kemana aku harus melarikan diri. Sementara kini di sekelilingku makhluk-makhluk meyeramkan dengan luka dan darah yang tampak dari tubuh mereka membuatku akhirnya berteriak minta tolong. Serentak mereka maju perlahan dengan gaya berjalan masing-masing. Semuanya seperti akan menyerangku saat itu juga. Aku yang berdiri sendirian hanya mampu menutupi wajahku dengan kedua tanganku sambil menangis ketakutan, dengan harap ada orang yang murah hati berani menyelamatkanku. Aku memang penakut sejak kecil. Itu sebabnya diriku tak pernah tertarik dengan segala hal yang berbau horor. Berbeda dengan pacarku yang sangat gemar dengan dunia horor. Dan sekarang diriku terjebak dalam situasi yang tak pernah terbayangkan. Dan Acil entah dimana keberadaannya. Makhluk-makhluk menyeramkan itu semakin dekat dengan tubuhku. Tak tahu lagi apa yang akan terjadi berikutnya pada diriku. Diantara tangisku yang makin menjadi, terdengar suara alunan gitar yang cukup keras. Diiringi sorak dan tepuk tangan banyak orang. Ada apa ini? Batinku penasaran. Pelan-pelan kuberanikan diri membuka tanganku demi melihat apa yang terjadi. Kudapati mahkluk-makhluk aneh tadi sudah menjauh tapi masih memandangiku. Dan tepat di seberangku ada seorang pria bergitar tersenyum manis ke arahku. Acil, ya, aku sangat yakin, benar itu dia. Beberapa kali punggung tangaku menyeka air mata yang cukup menghalangi penglihatanku. Semakin jelas wajah Acil yang kini sedang menyanyikan lagu How Would You Feel milik penyanyi Ed Sheeran. Setelah dia menyelesaikan bait pertama, ia melanjutkan pada bagian reff yang ia nyanyikan sambil berjalan ke arahku. Seiring makin banyak pengunjung yang ‘menonton’, makin banyak pula pertanyaan yang belum menemukan jawabannya di benakku. Termasuk apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Acil tiba-tiba muncul dan menyanyikan lagu? Tentu ini bukan hari ulang tahunku. Bukan pula dengannya. Hari ini hanya 25 September yang biasa saja. Akhirnya aku hanya terpaku dan mematung di tempatku berdiri.
“How would you feel, if I told you I loved you,
It’s just something that I want to do,
I’ll be taking my time,
Spending my life,
Falling deeper in love with you,
So tell me that you love me too.” Suara Acil yang lumayan merdu menggelegar terdengar ke segala penjuru dengan bantuan mikrofon kecil yang diselipkan diantara kerah bajunya. Matanya menatap ke arahku sambil sesekali melirik gitar yang tengah ia mainkan. Langkah demi langkahnya makin mendekatkannya padaku yang masih ada dalam kebingungan dan sisa tangis ketakutan. Riuh orang bertepuk tangan kembali terdengar ketika Acil selesai bernyayi. Diberikannya gitar pada salah seorang dari makhluk-makhluk mengerikan tadi. Di hadapanku ada Acil yang terlihat gugup.
“Kamu Acil yang asli kan?” diriku memastikan.
“Asli lah. Lagian tadi tuh cuma ngerjain kamu aja,” katanya sambil memamerkan deretan gigi depannya.
“Maksudnya?” aku terperangah.
“Ya, semua hal aneh yang terjadi sama kamu hari ini cuma settingan. Anak kecil yang kamu liat di mobil, nenek-nenek aneh, mereka temen-temen sanggarku. Termasuk zombie-zombie disini.” Ia tertawa kecil ketika bicara. Kumemandang berkeliling, dapat kulihat anak kecil dan nenek tadi yang sempat membuatku takut kini malah melambaikan tangannya seraya tersenyum padaku. Lalu anak kecil itu memamerkan boneka kucing hitamnya padaku dari kejauhan. Ternyata selama ini aku tidak benar-benar mengalami peristiwa horor.
“Kucingnya juga?” tanyaku pada Acil penasaran.
“Ya, itu juga cuma boneka.” Acil tertawa kemudian sorak dan tawa dari ‘penonton’ terdengar begitu ramai. Suara Acil dan aku yang tentu terdengar oleh banyak orang karena kini bukan hanya Acil yang menggunakan mikrofon, tapi di tanganku juga sudah ada mikrofon wireless.
“Aku minta maaf , kalau kamu sampe ketakutan banget tadi. Karena aku pengen kamu tuh gak usah takut-takut banget sama yang namanya hantu, atau sejeninsnya. Aku pengen Kyara-ku lebih berani lagi.” Aku tertawa mendengarnya.
“Oke, aku maafin. Tapi, kok sampai seniat ini?” mengingat semua ini pasti membutuhkan persiapan yang tidak sederhana.
“Yaa.. sebenernya, hari ini ada hal penting yang mau aku sampaikan ke kamu, Ra.” Wajahku mengekspresikan keingintahuan yang tinggi tanpa berkata.
“Would you be my wife?” Acil berlutut di hadapanku, tangannya mengulurkan sebuah kotak merah marun berisikan cincin yang indah. Seketika tanganku menutup mulut yang ternganga karena terkejut. Sorakan ‘penonton’ kompak meramaikan suasana.
“Kamu lamar aku?” masih tak percaya dengan apa yang kudengar. Acil mengangguk yakin.
“Maaf, aku gak bisa. Gak bisa jawab sekarang,”
“Kenapa?”
“Kamu kan tau sendiri, aku pengen dilamar di depan Ibu sama Ayah.”
“Ah ya lupa, Ibu sama Ayahnya Kyara silakan masuk.” Kalimat itu diiringi kemunculan ibu dan ayah yang kemudian berhenti di belakangku. Kuraih tangan mereka berdua untuk mencium tangannya.
“Acil yang ngundang kami kesini.” Tutur Ibu sambil tersenyum setelah sebelumnya tangannya kukecup. Kulihat mata mereka yang berkaca-kaca. Mungkin ada haru yang menyeruak sebab anak tunggalnya akan segera dipinang seorang pria.
“Tapi, masa iya orang tuaku aja?” protesku sesaat setelah tubuhku berbalik dari ibu dan ayah.
“Tenang..” Acil menepuk tangannya sebanyak dua kali. Berselang beberapa saat, kedua orang tuanya muncul dari balik kerumunan orang yang mulai mengitari kami. Mereka berdua tersenyum padaku juga pada orang tuaku. Rasa tidak percaya masih menguasai diriku. Aku dilamar? Benarkah? Atau ini hanya mimpi di siang bolong? Jika benar ini mimpi, mengapa semua yang kurasa begitu nyata? Akhirnya aku malah bengong seperti orang linglung.
“Kalau masih kurang, aku panggil juga sahabat-sahabat kamu sekaligus relawan udah yang bantuin aku buat menyukseskan acara hari ini.” Tangan Acil menunjuk ke salah satu arah, disana kulihat Meta dan Derina tertawa saat melihatku.
“Awas ya kalian berdua,” ancamanku kemudian sambil ikut tertawa. Riuh keramaian pengunjung mal bersatu dengan sorak dan tepuk tangan orang-orang yang tengah menyaksikan acara lamaran terbuka ini.
“Oke, semua orang-orang yang kita sayang udah kumpul disini. Apa aku bisa dapet jawaban kamu sekarang?” orang yang masih bersimpuh di hadapanku menunggu jawaban. Lalu aku menghela napas panjang. Menyiapkan mental dan menentukan jawaban yang akan menentukan bagaimana masa depanku. Setelah dirasa cukup yakin. Dengan bismillah, kuberanikan diri menjawab,
“Ya, aku mau.” Jawabanku itu disambut bahagia oleh semua orang yang menyaksikan. Kemudian sebuah cincin dipasangkan oleh mama Acil di jari manis sebelah kiriku. Dan hari ini, tidak lagi menjadi 25 September yang biasa. Hari ini akan kukenang sebagai tanggal pertunanganku dengan Acil.


 Winwina
Winwina