“Lho, mau kemana?”
Fara membawa nampan berisi dua porsi makanan pesanannya. Keningnya berkerut, heran sebab Moira mengajaknya untuk ke luar dari restoran itu.
“Kita makan di tempat lain aja,” ajak Moira sambil menarik siku Fara.
“Ini ‘kan makanannya udah ada,” protes Fara tetapi mengikuti juga tarikan dari tangan Moira.
“Bungkus aja.”
Fara tak bisa menolak. Penasaran, kepalanya menoleh ke belakang sekadar mencari tahu apa yang membuat sahabatnya bertingkah demikian. Padahal tadi sangat semangat untuk makan siang. Pasti ada sesuatu pikir Fara.
“Kenapa sih harus makan di sini?” tanya Fara setelah mereka tiba di food court yang berada di mal yang sama.
“Gak ada kursi,” terang Moira singkat sembari membuka kotak yang membungkus makanannya.
“Perasaan tadi ada deh.” Fara menautkan kedua alisnya seraya beripikir. Sepenglihatannya pada saat masuk ke restoran dirinya melihat tempat yang kosong.
“Iya ada, cuman udah diduluin. Orangnya gak mau ngalah.” Moira menghembuskan napasnya pelan, mengingat kejadian tadi bersama Anindira. Terbayang tatapan wanita itu, pun dengan suaranya yang terus terngiang-ngiang.
Tidak puas kamu merebut semua hakku?
“Jahat banget sih tuh orang, padahal mau enak wifi-an di sana,” gerutu Fara.
“Orang jahat adalah orang baik yang dikecewakan.” Moira bergumam pelan setengah melamun. Matanya menatap kosong pada nasi yang berada di depannya.
“Hah?! Ngomong apa sih lo?”
Fara terheran, matanya menyelisik pada Moira yang kini dilihatnya sedang memikirkan sesuatu. Fara ingin bertanya namun tak ia lakukan dan memilih menyantap makanannya.
***
Moira mengendap-endap berjalan ke dapur. Dilihatnya Ibram sedang memasak. Kalau didengar dari suaranya, agaknya pria itu sedang memasak telur. Moira jadi menyesal tak mengecek lagi pesannya yang ternyata belum dikirim.
Pasti Ibram sangat lelah setelah lembur pulang jam 8 malam tadi dan mengetahui fakta tidak ada makanan apapun. Lalu, Moira dengan cueknya mengabaikan Ibram yang mengadu kelaparan, sebab dipikirnya pria itu sudah membaca pesannya yang menyuruh untuk makan di luar.
Pikirannya hari ini sungguh kacau, perkataan Anindira terus menghantuinya membuat mood-nya hancur. Bahkan semangat belajarnya pun hilang. Tak ada perisapan apapun untuk UTS esok hari, mungkin subuh nanti ia akan coba untuk belajar.
“Jangan cuma ngintip, sini bantuin,” ujar Ibram yang mengetahui keberadaan Moira.
Moira nyengir lalu melangkahkan kakinya mendekat pada Ibram yang sibuk di depan kompor. Memberanikan diri, Moira memeluk Ibram dari belakang dan sedikit merasakan tubuh Ibram yang menegang sesaat. Moira menempelkan wajahnya pada punggung Ibram dan menghirup aroma tubuh pria itu yang maskulin.
“Maaf,” ucap Moira pelan. Ia sungguh menyesal.
Terdengar Ibram menghembuskan napasnya pelan. “Jangan ulangi,” peringatnya.
Moira mengangguk pelan. Kemudian ia mengigit bibir dan menimang apakah ia ceritakan apa yang ada dipikirannya? Sebab jika tidak rasa-rasanya ia tak nyaman, dan tak sanggup sembunyikan perasaan gelisahnya. Toh masalah ini pun ada sangkut pautnya dengan Ibram. Ralat, pria itulah sumber masalahnya pikir Moira.
“Ada yang menganggu pikiran Moira,” jujurnya. Kemudian ia mengurai pelukannya dan mundur selangkah sebab merasakan Ibram yang hendak membalikan badan.
Sepiring nasi dan telur orak-arik berada di tangannya. Ibram menatap Moira selama beberapa detik sebelum buka suara, “Apa?”
“Um, Mas Ibram makan dulu deh,” putusnya.
Ibram mengangguk samar kemudian menarik kursi dan menaruh santapannya di meja makan yang langsung dilahapnya dengan semangat. Moira memperhatikan Ibram yang sedang terfokus pada makannya. Jika ia bercerita lebih dahulu takut akan menghilangkan selera makan suaminya itu.
Tak menunggu lama, 5 menit Ibram sudah menyelesaikan makan malamnya. Pria itu meneguk air putih yang barusan Moira ambilkan dari kulkas.
“Jadi?” tanya Ibram sambil menaruh gelas yang sudah kosong. Alisnya bertaut tanda ia penasaran dan tak sabar.
Moira meremas-remas tangannya yang mulai berkeringat. Kalau boleh jujur, Moira tak ingin terus-terusan membahas perihal ini. Inginnya semua ini berakhir begitu saja. Tetapi tidak mungkin, ‘kan? Diam tak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, justru malah membuatnya kian larut.
“Moira,” panggil Ibram lembut yang membuat kepala Moira yang semula tertunduk kini terangkat. “Apa yang mengganggu pikiranmu?”
“Anindira.” Moira langsung menjawab dengan suara pelan nyaris berbisik, tetapi masih dapat didengar oleh Ibram.
“Kenapa dia?” Kini rasa penasaran Ibram dua kali lipat dari sebelumnya. Pria itu menelan ludah, sesungguhnya ia sendiri bosan dengan topik ini.
“Apa keputusan Mas Ibram?”
“Tentang?”
Moira berdecak. “Masa harus diperjelas, sih?!”
“Apanya?” Kembali Ibram bertanya. Walau sebetulnya pria itu tak benar-benar tak mengerti apa yang dimaksud Moira.
“So-soal… kita.” Moira menggaruk tengkuknya yang tak gatal. “Aku… atau… um… Mas Ibram….”
Ibram masih menunggu Moira yang sepertinya ragu untuk mengungkapkannya.
Kini tangan Moira berpindah menggaruk pundaknya. Rasanya sudah diujung lidah tetapi tak sanggup ia ungkapkan. Bukan. Bukan tidak sanggup tetapi ia merasa belum siap atas apa yang bakal didengarnya. Penolakan, tentu menjadi hal yang paling tidak siap ia dengar sekarang.
Ibram berdehem membuat Moira kembali mendongakan wajahnya yang semula tertunduk.
Moira menghela napas lalu menghembuskannya pelan, begitu ia ulang beberapa kali hingga membuat Ibram gemas dibuatnya.
“Aku tidak suka menunggu. Katakan sekarang atau tidak sama sekali!” ancam Ibram.
“Eh, i-iya, Moira ngomong sekarang,” kata Moira mulai diserang panik.
Ibram tersenyum dalam hati, ancamannya itu berhasil walau sesungguhnya tidak betul-betul begitu.
“Begini, Mas.” Moira berdehem membersihkan tenggorokannya yang terasa ada yang menghalangi. “Menyambung pertanyaan Moira yang kemarin belum Mas Ibram jawab.”
Terlihat mata Ibram tengah menatap ke samping mencoba mengingat. Detik berikutnya ia mengangguk-anggukan kepala, merasa sudah ingat pertanyaan yang Moira ajukan tetapi dialihkan olehnya dengan sesuatu.
“Moira−” Gadis itu menelan ludah. “−butuh kepastian,” sambungnya seraya tertunduk.
“Kepastian apa?” jawab Ibram langsung. Kini tangannya ia lipat di atas meja makan.
“Soal kita,” jawab Moira dengan nada suara lebih tinggi dari sebelumnya, sedang alisnya tengah bertaut.
“Apanya yang harus dipastikan? Menurutmu pernikahan belum cukup menjelaskannya?” tanya Ibram tiba-tiba jengkel sehabis mendengar ucapan Moira barusan.
“Hah?” Moira sungguh tidak mengerti.
“Ck, kamu butuh kepastian apa lagi?” Kini Ibram bertanya dengan suara lembut.
“Ya soal kita.” Giliran Moira yang merasa jengkel. “Soal perasaan Mas Ibram, soal wanita itu gimana!”
“Kenapa repot-repot mikirin orang lain?!” Mata Ibram menyipit.
“Ih, Mas Ibram!” kesal Moira. Ibram terlalu berputar-putar, mungkin pria itu coba mengalihkan pembahasan seperti kemarin. Moira tak akan biarkan pembicaraan ini usai tanpa penjelasan, tekadnya. “Jadi gimana Mas Ibram pilih Moira atau Anindira?!” Nada kesal tak bisa Moira sembunyikan lagi. Dadanya kini kembang kempis.
Bukannya menjawab pria di depan sana malah tertawa seolah-olah pertanyaan Moira adalah hal lucu. Moira mengernyitkan hidungnya, hatinya bertanya-tanya apakah pria di depannya itu salah makan?
“Apanya yang lucu?!” semprot Moira lagi.
Tawa Ibram makin memelan, lalu pria itu berujar, “Pertanyaanmu konyol. Kamu menanyakan sesuatu yang sudah jelas jawabannya.”
Moira membuka mulutnya lebar, otaknya kian pusing dibuat pria itu. Lalu matanya menangkap Ibram yang mulai beranjak dari kursinya. Tawanya sudah hilang, lalu wajah dinginnya yang kembali terlihat.
“Mas Ibram kita belum selesai!” teriak Moira yang mulai melihat Ibram kian menjauh dari tempatnya.
Ibram terus bergerak tanpa pedulikan teriakan Moira. Gadis itu kini geram bukan main atas tingkah Ibram yang selalu tak mau selesaikan masalah. Pria itu selalu begitu!
Moira melipat kedua tangannya di depan dada dengan dada yang kembang kempis.
***
Mungkin dulu rumah adalah tempat ia pulang, paling ia nanti setelah lelah beraktivitas. Berbeda dengan sekarang yang rasanya kalau bisa ia tak ingin kembali ke sana. Kembali ke sana sama dengan kembali membuka luka-lukanya. Akan tetapi, jika tidak ke sana ke mana lagi? Tak ada tempat yang bisa ia tuju selain ke rumah itu. Walau menyakitkan, ia harus terima ke sanalah satu-satunya tempatnya pulang.
Anindira menghela napas, coba siapkan hati kalau-kalau dia akan kembali menangis dan mengingat semuanya. Tetapi sejurus kemudian ada yang menggelitik perasaannya. Sebuah mobil yang familier terparkir di depan rumahnya.
Wanita itu buru-buru ingin sampai ke rumahnya lalu turun dari taksi yang ia tumpangi. Sejurus kemudian jantungnya terasa copot saat ia turun dari taksi. Kakinya berjalan dengan cepat untuk menghampiri orang yang tengah duduk di kursi yang ada di teras.
“Ngapain kamu ke sini?” hardik Anindira.
“Aku ingin bicara denganmu,” jawabnya tenang.
“Aku tidak mau. Lebih baik kamu segera pergi dari sini.”
Anindira masih terbayang kejadian yang merenggut nyawa mamanya. Ibram tentu tak termaafkan.
“Aku tidak akan pergi sebelum kita selesaikan semuanya.” Ibram bersikeras. Sudah beberapa hari ke belakang ia biarkan masalah ini berlarut, tapi tidak dengan sekarang terlebih karena pertanyaan Moira semalam.
“Selesaikan semuanya?” Mata Anindira kini berkilat merah. “Apa maksud kamu?”
“Duduklah dulu,” pinta Ibram. “Kita bicarakan baik-baik.”
Tampak Anindira tengah berpikir sejenak. Tetapi detik berikutnya wanita itu mengikuti permintaan Ibram. Ia duduk di seberang Ibram dengan hati yang masih dikuasai emosi.
“Soal Tante−”
“Aku tidak ingin bicarakan soal itu,” ucap Anindira. Ia tak mau bersedih lagi. Membicarakan Mama sama dengan membuka lukanya kembali.
Ibram menghela napas lalu membuangnya pelan. “Soal kita.”
Kini Anindira tak protes, hanya matanya tengah menatap Ibram dengan tatapan tak terdefinisikan.
“Sebelumnya aku meminta maaf telah membuatmu berada di posisi ini.” Ibram menjeda ucapannya 5 detik, memilih kata-kata yang pas tanpa menyakiti Anindira. “Kamu tahu, aku sangat menyayangimu. Tetapi−”
“Apa?” Pandangan Anindira mulai kabur. Rasa-rasanya ia tahu apa yang akan diucapkan Ibram.
“Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini.” Ibram menatap Anindira, memastikan reaksi apa yang akan diberikan wanita itu.
Reaksi Anindira diluar dugaan Ibram. Wanita itu kini tengah tertawa sumbang. Sebelah tangannya tengah memegangi perut, sedang tangan yang lain menyeka air mata yang keluar dari sudut matanya.
Ibram tidak tahu apakah itu tawa bahagia atau tangis yang disembunyikan dengan tawa?
“Anindira,” panggil Ibram hati-hati.
“Kamu malah memperjelas semuanya.” Anindira mencoba menghentikan tawanya, air matanya ia seka kembali. “Aku sudah tahu itu,” imbuhnya yang sekarang nada suaranya melemah.
“Maafkan aku,” sesal Ibram.
“Terima kasih Ibram, kamu sudah membuktikan padaku bahwa laki-laki pada dasarnya memang sama saja.”
“An, aku−”
“Sudahlah, kamu tak usah pura-pura menyesal begitu,” ucapnya. “Aku tidak tahu karma itu ada atau tidak. Tapi yang kutahu Tuhan itu Maha Adil.”
Jantung Ibram rasanya terjatuh ke dalam perut. Entah itu sebuah ancaman atau doa, tetapi yang pasti Ibram menangkap sinyal yang tak baik.
***
Moira tengah mengetuk-ngetukan kepalanya ke meja belajar dengan pelan. Ia tak bisa berkonsentrasi sama sekali. Sedari tadi apa yang dipelajarinya sangat sulit untuk masuk ke dalam otaknya. Saat hendak mengangkat kepalanya kembali tiba-tiba sesuatu menahannya hingga keningnya terasa nyeri karena tertekan.
“Stress gara-gara mogok bicara sama suami sendiri?”
Tiba-tiba Moira menyentakan kepalanya untuk melihat pelaku yang menekan kepalanya, pun yang berucap barusan.
“Ih, sok tahu!” serunya. “Orang Moira lagi ngafalin materi.”
Ibram mendengus tak percaya. Kemudian kakinya mundur dan duduk di tepi petiduran. Menatap Moira yang membelakanginya.
“Aku ganggu?” tanya Ibram kemudian.
“Jelas. Moira lagi belajar,” kilah Moira yang sejujurnya tak demikian.
Dari tadi memang dia belajar tetapi tak satupun materi yang menyangkut dalam otaknya. Tetapi itulah alasan yang bisa ia gunakan agar menjauhkan Ibram darinya. Perkataan Ibram tadi sebetulnya benar, Moira putuskan mogok bicara karena percakapannya yang semalam dibuat menggantung oleh Ibram tanpa penjelasan.
“Baiklah aku keluar,” pamit Ibram.
Terdengar Moira mendengus kasar. Yang Moira inginkan setidaknya pria itu sedikit memaksanya atau merayunya membuka suara dan hentikan aksinya. Tetapi apa? Pria itu malah pamit.
Moira menghentakan kakinya berdiri bermaksud pindah dari meja belajar kemudian tubuhnya tersentak karena Ibram masih ada di situ. Kini malah berada di hadapannya. Wajah Moira mendongak untuk menatap wajah Ibram yang beberapa centi berada di atasnya.
“Kaget?” tanya Ibram masih dengan suara datarnya.
“Enggak biasa aja,” jawab Moira sebisa mungkin untuk terdengar biasa saja walau dalam hati tidak demikian.
“Kalau ini kaget?” tanya Ibram kemudian dengan gerakan tiba-tiba melandaskan bibirnya pada Moira.
Moira sontak menegang untuk beberapa saat, kemudian tangannya menutup bibirnya.
“Ih, Mas Ibram!” kesalnya seraya mendorong tubuh Ibram agar menjauh.
Ibram terkekeh, ternyata begitu menyenangkan menggodanya. Seharusnya Moira sudah mulai terbiasa, tetapi masih saja bereaksi seperti baru pertama kali mendapatkannya. Hati Ibram jadi tergelitik untuk bertanya.
“First kiss kamu siapa?” Ada nada tak suka saat menanyakannya. Tiba-tiba hatinya diliputi kekesalan memikirkan orang yang mendapatkan ciuman pertama Moira.
Moira mendengus, ia merasa direndahkan atas pertanyaan Ibram. “Pikir aja sendiri!” jawabnya ketus seraya menyingkirkan Ibram.
Tangan Ibram melingkari perut Moira, kemudian menarik kembali tubuh kecil itu. “Jawab dulu, aku mana bisa berpikir. Mantan-mantan kamu saja aku tidak tahu!”
Moira kian tersinggung dengar pertanyaan Ibram. Memangnya pria itu tidak bisa menebak apa? Hatinya jadi geram sendiri.
“Moira balik tanya, kalau Mas Ibram siapa?” tanya Moira dengan nada tinggi.
“Anindira,” jawab Ibram enteng tanpa dosa.
Hati Moira berdenyut kala mendengarnya. Seharusnya ia sudah tahu tanpa harus bertanya. Sama saja ia dengan suka rela hatinya dirobek. Moira menyikirkan tangan Ibram yang melingkar di perutnya dengan paksa. Mencoba menyikir dari Ibram takut-takut pria itu menangkap air matanya yang akan mulai turun.
“Tapi kamu bakal jadi yang terakhir,” sambung Ibram menghentikan aksi Moira yang bersikeras ingin melepaskan jeratannya.
“Ma-maksudnya?”
“Aku memilihmu, Moira Azkadina.”
Tiba-tiba perut Moira jadi mulas. Moira paham betul maksud dari perkataan Ibram. Itu adalah jawaban dari pertanyaannya kemarin. Tunggu dulu, Moira harus kembali memastikan.
“Anindira atau Moira?”
Ibram mengernyitkan keningnya tak mengerti. Kemudian Moira kembali bertanya seperti itu, memaksanya untuk menjawab. “Moira.”
“Moira Azkadina?” Moira belum yakin.
“Iya,” jawab Ibram.
“Moira Azkadina binti Abu Bakar?” Lagi, Moira belum yakin.
“Iya, sayang.”
Pipi Moira tak tertolong, tanpa permisi semburat merah muncul begitu saja. Inilah jawaban yang Moira inginkan dan nanti-nanti. Rasanya kebahagiaan tengah meronta dalam hatinya. Ingin sekali Moira berteriak sekarang juga, namun tak mungkin ia lakukan. Titik kata yang Ibram utarakan barusan tak pernah disangkanya. Mata Moira mulai berkaca-kaca. Benarkah ini jawaban dari kesabarannya?
Lalu Moira berjinjit untuk menyamakan tingginya dengan Ibram. Detik berikutnya bibirnya ia tempelkan pada pipi Ibram yang memiliki brewok tipis yang menggelitik bibir.
Ibram tersenyum mendapatkan keberanian seperti itu dari Moira. Keputusan ini tentu bukan hal mudah baginya. Kalau saja wajah Moira tak selalu tampil dari setiap istikharahnya, kalau saja nasihat Ayah tak pernah termimpikan olehnya, dan kalau saja perasaannya tak condong kepadanya maka ia tak akan seyakin ini untuk memilih Moira.
Mulanya memang sulit terimakan Moira yang ternyata sudah berhasil tempati hatinya. Tetapi ternyata perasaan itu kian lama kian menjadi. Moira yang belum lama ini singgah dihidupnya telah berhasil singkirkan cintanya selama 10 tahun pada Anindira.
Ibram setuju sekarang pada pepatah yang mengatakan bahwa cinta datang karena terbiasa.


 itsarney
itsarney





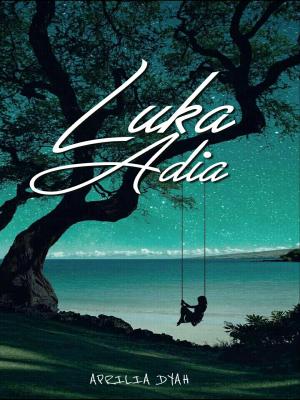




@itsarney akunku yurriansan. klo kmu mau mampir dluan boleh, aku bksln lmbat feedbacknya. krena klo wattpad bsanya buka pke lptop, aku gk dnload aplikasinya. dan lptopku lg d service
Comment on chapter BAB 1: Keputusasaan