Cerahnya mentari yang bersinar hari ini bak mengkhianati Anindira yang hatinya tengah diselimuti awan hitam. Air matanya terus turun hingga jari-jarinya bosan untuk menyeka. Terlihat lingkaran hitam pada kedua matanya, mendandakan waktu tidurnya tidak baik.
Anindira tak pernah menyangka, ternyata gaun hitamlah yang ia kenakan lebih dulu bukan gaun putih seperti keinginan Mama. Ada rasa sakit yang tak terdefinisikan dalam hatinya.
Mengapa? Mengapa? Mengapa?
Itu yang selalu ia teriakan. Tak bisakah hapuskan kata ‘perpisahan’ dalam kamus hidupnya. Berapa kali orang-orang terdekatnya direnggut?
Dulu saat Ayah direnggut, masih ada Mama dan Ibram yang menjadi tempatnya bersandar. Lalu, saat Ibram juga direnggut, masih ada Mama yang menjadi tumpuannya. Namun sekarang ketika Mama yang direnggut siapa yang akan menjadi penguatnya?
Anindira terisak semakin kencang. Tangannya meremas dadanya sendiri seolah takut robekan hatinya kian melebar.
Moira!
Nama itu yang terus dimakinya dalam hati.
***
Ibram tersentak kaget saat membuka pintu depan rumahnya, kakinya yang hendak masuk kembali mundur. Tampak Moira tengah berjongkok dengan sebuah baskom berisi air di tangannya.
“Biar Moira yang buka,” pintanya kala melihat Ibram berusaha membuka sepatu.
Ibram mengangkat sedikit kakinya agar memudahkan Moira melepaskan sepatunya. Lalu setelah kedua sepatu dan kaos kaki Ibram tanggal, Moira langsung mencelupkan kaki Ibram silih berganti yang kemudian mengelapnya dengan handuk kecil yang ia sampirkan di pundak.
Hati kecil Ibram berdesir. Ia sangat merindukan aktivitas ini setelah beberapa hari ke belakang tak melakukannya. Ralat. Moira tak melakukannya.
Sejak kejadian di rumah sakit tempo hari, Moira memang mendiamkannya. Ah, tidak. Bahkan dirinya juga mengabaikan Moira. Pikirannya terlalu kalut memikirkan fakta bahwa Mama Anindira meninggal karenanya. Mungkin tidak sepenuhnya benar begitu, tetapi yang pasti ucapan Ibram yang memicunya.
Soal kejadian kemarin saat Bunda memintanya menceraikan Moira, Ibram tak ambil pusing sebab bukan dari bibir Moira sendiri permintaan itu mengudara. Ibram masih dengan janjinya, tak akan ceraikan gadis itu sebelum ia sendiri yang memintanya. Soal Bunda, Ibram anggap sudah beres walau sebetulnya tidak demikian. Kemarin, Ibram meminta Bundanya tak usah ikut campur mengenai rumah tangganya, dan mengantarkannya pulang dengan paksa.
Moira sudah selesai dengan aktivitasnya. Gadis itu bergegas ke tempat cuci yang berada di samping dapur. Ia meletakan handuk bekas mengelap kaki Ibram ke dalam mesin cuci. Saat hendak berbalik tubuh Moira tersentak kaget mengetahui Ibram berada di hadapannya. Ia kira pria itu akan langsung bergegas ke atas untuk bersih-bersih badan.
“Assalamu’alaikum, aku lupa mengucapkannya,” kata Ibram sembari merengkuh wajah Moira dan mendaratkan kecupan di kening Moira.
Moira mengerjapkan matanya beberapa kali, merasa tidak percaya atas apa yang barusan ia alami. Sejurus kemudian pipinya bersemu merah. Ini pertama kalinya Ibram berbuat manis sepulang kerja. Biasanya juga pria itu tak berbuat demikian, malah beberapa hari terakhir seperti tak menganggapnya ada.
“Wa-wa’alaikumsalam.” Akhirnya Moira mendapat kesadarannya.
Sebelah sudut bibir Ibram berkedut melihat pipi Moira yang memerah, belum lagi mendengar suara gadis itu yang tertahan. Rasanya ia menyesal beberapa hari ke belakang telah mengabaikannya, ia punya utang penjelasan pada Moira. Dalam hati Ibram memuji kesabaran Moira yang tak langsung menghakiminya. Mungkin kalau ia adalah Anindira maka sudah habis dicecar berbagai pertanyaan. Ah, mengapa jadi membandingkan!
“Aku ke atas dulu,” ucap Ibram sambil menepuk pelan puncak kepala Moira yang tak berbalut kain tudung.
Moira menghembuskan napasnya yang sedari tadi ia tahan. Tangannya kemudian memegang jantungnya yang berdebar sekuat tenaga kuda. Walau ini termasuk hal biasa yang pernah mereka lakukan, tetapi tetap saja masih begitu asing bagi Moira.
Kemudian Moira berkacak pinggang dengan bibir mengerucut. Harusnya ‘kan ia membrondongi Ibram banyak pertanyaan, bukannya tersipu malu seperti tadi!
Ah, Ibram selalu saja demikian, menganggap semuanya sudah baik-baik saja!
***
Moira yang sedang fokus menonton kembali terkaget ketika kepala seseorang mendarat di pangkuannya. Ibram terkekeh mengetahui Moira kaget akan kehadirannya.
Moira ikut tersenyum, ini pertama kalinya ia lihat Ibram tersenyum seperti itu. Biasanya pria itu hanya menunjukan wajah datar atau dingin.
“Mau mendengar sesuatu?” kata Ibram membuka percakapan.
Moira menundukan kepalanya agar pandangan mereka bertemu, jarinya menyusup rambut Ibram yang terasa lembut. “Pastikan sesuatu itu gak akan buat telinga Moira sakit,” peringatnya.
Ibram menghembuskan napasnya berat, tangan kirinya terangkat mengarah ke tengkuk Moira dan mengelusnya samar. “Mama Anindira meninggal.”
“Inna lillahi!” seru Moira terkaget bukan main. Jantungnya kembali berpacu dengan cepat. “Mas Ibram enggak becanda, ‘kan?!”
“Itu bukan hal yang pantas dibuat lelucon, Moira,” desah Ibram.
“Ja-jadi….”
Moira membekap mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca, memorinya melayang ke malam itu. Betapa egois dirinya, menganggap paling tersakiti tetapi faktanya ada yang lebih tersakiti dari dirinya.
“Maafin Moira,” ucapnya bersamaan dengan air yang meleleh dari matanya.
“Kenapa minta maaf?” Tangan Ibram yang tadi berada di tengkuk Moira kini bergerak menghapus air mata Moira. “Kenapa menangis?”
“Mo-Moira udah egosi malam itu,” sesalnya. “Moira tahu gimana rasanya kehilangan, Moira tahu gimana posisi wanita itu.”
“Sebagai seorang istri itu sudah wajar.” Ibram kembali menyeka air mata Moira. “Sudah jangan menangis.”
“Kalau tahu itu hari terakhir mamanya, Moira bakal ridho tinggalkan Mas Ibram di sana.”
Ibram mengangkat satu alisnya. “Jadi kamu gak ridho waktu itu?”
Mendadak tangis Moira terhenti. Kemudian terlihat matanya menyipit pada Ibram dan berkata, “Memangnya istri mana yang ridho meninggalkan suaminya bersama wanita lain, lalu berpelukan di depan matanya?!”
Ibram malah terkekeh melihatnya. Ini adalah Moira yang cemburu dengan terang-terangan. Biasanya gadis itu tak berani utarakan kecuali dengan tangisannya.
“Sekarang aku setuju dengan Sayyidina Ali, wanita bisa menyembunyikan cinta selama 40 tahun namun tak sanggup menyembunyikan cemburu mesti sesaat.” Ibram mencubit hidung Moira dengan gemas setelahnya.
“Si-siapa yang cemburu?!” kilah Moira sambil menyingkirkan tangan Ibram dari hidungnya.
“Mau dengar yang lainnya tidak?” Ibram mengalihkan pembicaraan.
“Apa?”
“Tapi, ini bakal membuatmu makin cemburu.” Ibram mengingatkan dengan nada datar.
Moira tak langsung menjawab. Pandangannya tengah menatap telaga madu dalam mata Ibram. Kalau ia memilih untuk tidak mendengarnya, maka itu akan mengamini ucapan Ibram yang menganggapnya cemburu. Tetapi jika memilih mendengarnya, maka ia harus siapkan hati dan telinga untuk siap-siap mendengar berita yang mungkin saja tidak baik atau tidak seharusnya ia dengar.
“Ap-apa itu?” Moira memberanikan diri. Bukannya ia pernah mendengar yang lebih pahit sebelumnya? Kehadirannya tidak diinginkan. Itu yang terus terngiang-ngiang di telinganya.
“Rahimahallah Mama Anindira inginkan aku menikahi Anindira malam itu.”
Ada kesakitan yang menjalar hatinya. Namun, sebisa mungkin Moira sembunyikan itu. Saat ini ia hanya perlu memasang telinga, mendengar kelanjutan cerita dari Ibram. Hati kecil Moira meyakinkan bahwa malam itu tidak terjadi akad. Ibram sudah berjanji padanya tak akan melakukan itu sebelum ia jadi ibu dari anaknya. Ah, mengingat itu rasa sakit hati Moira kian bertambah. Akankah waktu itu tiba?
“Tetapi, aku tidak bisa melakukannya. Kamu−” Ibram menunjuk hidung Moira dengan telunjuknya. “−melayang terus-terusan dipikiranku malam itu.”
Moira sedikit melebarkan matanya. Ia majukan sedikit kepalanya, merasa tak percaya atas apa yang barusan ia dengar.
“Aku mengatakan yang sesungguhnya malam itu pada Rahimahallah Mama Anindira kalau… aku sudah menikah.” Suara Ibram melemah saat mengucapkan kalimat terakhir. Bayangan Mama Anindira yang sekarat tiba-tiba berputar bagai roll film dalam kepalanya.
Moira membelai pelan rambut Ibram. Gadis itu menangkap kesedihan dari suara suaminya. Sudah sepantasnya pria itu berlaku demikian, sebab ia sudah lebih lama mengenal sosok itu dibandingkan dengan mengenal dirinya. Rasa kehilangan adalah wajar baginya, Moira maklumi itu.
“Mamanya sudah tiada sekarang. Ap-apa perjanjian Mas Ibram dan wanita itu masih berlaku?” tanya Moira hati-hati.
Ibram mengangkat sebelah alisnya minta penjelasan lebih rinci dari ucapan Moira barusan.
“Mas Ibram yang akan nikahi Anindira,” terang Moira walau sejujurnya enggan menyebut nama itu.
Ibram menelan ludahnya, matanya menatap langit-langit di atas. Janji itu, ia hampir sudah melupakannya. Moira kembali mengingatkannya. Tetapi bukankah secara otomatis perjanjian itu batal mengingat Mama Anindira sudah tiada. Ah, Ibram berpikir seolah-olah dirinya memang enggan menikahi Anindira. Sejurus kemudian dia bertanya-tanya dalam hatinya, masihkah Anindira di hatinya? Mengapa perasaannya menjadi rambang?!
Pandangan Ibram teralih kembali pada mata milik Moira. Benarkah secepat ini dia berpaling?
“Mas Ib−”
Ucapan Moira kemudian terbungkam oleh ulah Ibram yang tiba-tiba.
***
Moira dan Fara memutuskan untuk berkunjung ke mal setelah menyelesaikan UTS hari ini. Mumpung masih agak siang pikir mereka berdua.
Niatnya ke mal tidak untuk berbelanja sebab memang mereka berdua bukan tipe seperti itu. Moira dan Fara tipe orang yang senang menghabiskan uang dengan makan atau menonton film. Dan saat ini yang akan mereka lakukan adalah makan mengingat masuk jam makan siang.
Kaki mereka berdua melangkah ke restoran cepat saji dengan menu andalan ayam goreng dengan saus super pedas. Makanan pedas memang menjadi menu favorit orang-orang yang berada di usia Moira dan Fara.
Restoran tampak ramai. Moira celingak-celinguk mencari kursi kosong sementara Fara mengantri di depan kasir untuk memesan.
Tak lama, mata Moira menangkap ada meja kosong di dekat toilet. Buru-buru gadis itu berjalan takut ada yang mendahului mengetahui fakta itulah satu-satunya kursi yang kosong saat ini.
Baru saja hatinya hendak bersorak gembira kala mencapai kursi tiba-tiba tubuhnya menegang. Pandangannya kini bertemu dengan mata yang sama tengah menatapnya dengan terkejut.
“Kamu!” serunya tak suka.
Moira ingin hendak kabur saat ini juga. Tetapi tidak mungkin ia lakukan, sebab ia merasa tidak perlu repot-repot demikian. Seharusnya wanita di depannya yang harus kabur kala melihatnya. Moira mengerucutkan bibirnya tak suka.
“Aku yang duluan di sini!” ucap Moira seraya mengangkat dagunya.
Mata wanita dihadapannya melotot sempurna melihat tingkah gadis kecil itu yang sok congkak.
“Lebih baik kamu mengalah kepada orang dewasa, Dek!”
“Ih, apa itu enggak kebalik?!” tanya Moira sambil mengernyitkan hidungnya.
Wanita dihadapan Moira tampak menghembuskan napasnya kasar. Kemudian, ia memajukan badannya agar lebih dekat kepada Moira. “Dengar, aku sedang tidak ingin berdebat. Pergilah!”
“Memangnya kamu yang punya restoran ini?” Moira tak suka diusir demikian. Keberaniannya ini datang mungkin karena perasaan tidak suka pada wanita itu.
Wanita itu mendengus. “Tidak puas kamu merebut semua hakku?”
Keberanian Moira mulai sirna. Moira menatap mata yang sepekat malam itu di depannya dengan ngilu. Dapat Moira rasakan kepedihan dibalik tatapannya. Detik berikutnya perasaan bersalah menyelimuti Moira. Entah mengapa, datang begitu saja.
“Ibram,” ucapnya dengan mengatupkan gigi. “Lalu, Mamaku! Kamu tidak puas?!”
Terdengar jelas kepedihan dalam suara Anindira. Tiba-tiba napas Moira memburu, penglihatannya kabur. Moira tahu betul bagaimana rasanya kehilangan. Namun, ia tak bisa bayangkan di posisi Anindira. Wanita itu terlihat rapuh walau mati-matian ia menutupinya.
Semua orang yang disayangi wanita itu pergi karena dirinya?
Hati Moira langsung diselimuti penyeselan. Tetapi apa yang sesungguhnya ia sesalkan? Sedang semua ini bukanlah skenarionya.
Moira beranikan diri untuk mengangkat tangannya yang semula terkepal di pahanya kini mengarah pada tangan Anindira yang terkepal di atas meja. “Ikhlas,” ucap Moira pelan nyaris berbisik.
Anindira langsung menarik tangannya seolah baru saja ia terkena tegangan listrik dari Moira. “Haram tanganku disentuh olehmu,” ucapnya tajam. “Jangan sok mengajariku. Harusnya kamu ajari dirimu untuk tidak merebut apa yang bukan hakmu!”
Hati Moira kian berdenyut ketika Anindira kembali mengulang-ulang ucapannya. Tetapi sebisa mungkin Moira tak melihatkan kelemahan dihadapan wanita itu.
“Sakit badan bisa sembuh dengan obat. Sakit batin bisa sembuh dengan taubat.” Moira mengucapkan itu sambil beranjak dari kursinya. Meninggalkan Anindira yang tengah terbelalak mendengar ucapannya.
Kalau hati Moira menguasai pikirannya maka itu tak akan jadi ucapannya. Untung saja logikanya terus ia gunakan. Moira berpegang teguh pada prinsipnya, bahwa segala sesuatu sudah digariskan oleh Allah. Menerima semua takdir baik dan buruk sama dengan mengimani rukun iman yang ke-6. Jikalau ia terus-terusan terbawa perasaan atas ucapan Anindira, maka Moira harus pertanyakan keimanannya sendiri.
Kita ini ibaratnya hanya wayang yang menjalankan scenario dalang tanpa bisa mengubahnya.
***
Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza 😊
Jangan sungkan untuk beri kritik dan saran, supaya aku bisa belajar lebih baik lagi^^
PS. Cerita ini juga dipublikasikan di Wattpad.


 itsarney
itsarney









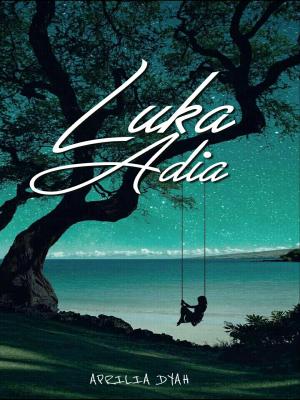
@itsarney akunku yurriansan. klo kmu mau mampir dluan boleh, aku bksln lmbat feedbacknya. krena klo wattpad bsanya buka pke lptop, aku gk dnload aplikasinya. dan lptopku lg d service
Comment on chapter BAB 1: Keputusasaan