BAB 4
Selamat membaca 😊
۞۞۞
Moira berlari mengikuti sebuah cahaya. Bahunya naik turun, peluh menghiasi wajahnya. Beberapa kali ia terjatuh hingga membuat lututnya terluka. Air matanya jatuh ketika melihat gamisnya robek dan menampilkan lututnya yang terluka. Tubuhnya kian bergetar, rasa takut menyelimutinya sekarang. Lalu sebuah tangan terulur membuat Moira mendongakan wajahnya. Terlihat seulas senyum menghiasi wajah orang yang mengulurkan tangan kepadanya.
“Ayah,” bisik Moira sambil terisak.
Ayah mengangguk, lalu Moira menerima uluran tangannya dan sekarang mereka berdiri saling berhadapan. Ayah terlihat berbeda, begitu tampan dengan jubah putih dan sorban yang terlilit di kepalanya.
“Moira, jangan berlari. Jangan kejar cahaya itu, belum saatnya,” nasihat Ayah seraya mengelus puncak kepala Moira yang berbalut kerudung.
“Tapi di sini gelap, Yah,” protes Moira seraya terisak. “Moira takut, enggak ada siapa-siapa.”
“Itu,” tunjuk Ayah. Moira mengikuti ke mana arah telunjuk sang ayah dan mendapati seorang pria yang entah siapa. Moira tak dapat melihatnya dengan jelas. “Dia yang akan jadi cahaya Moira.”
“Siapa dia?” tanya Moira penasaran, air matanya ia hapus dengan kasar menggunakan punggung tangannya.
“Moira akan tahu nanti,” ucap Ayah membuat teka-teki. “Apabila Moira taat kepadanya, cahaya itu yang akan Moira dapat. Sebaliknya, apabila Moira tidak taat kepadanya, ke sana Moira akan berjalan.” Ayah menunjuk ke arah sebelah cahaya berasal. Di sana begitu gelap dan mengerikan.
“Moira takut,” rengek Moira seraya memeluk lengan Ayah erat.
“Jangan takut ketika ada iman di hati Moira.” Ayah kembali menasehati. “Ayah pamit dulu, ya?! Assalamualaikum,” pamit Ayah kemudian. Detik berikutnya Ayah tak lagi berada di hadapan Moira, Ayah berjalan seperti ditarik angin begitu cepat hingga Moira tak dapat mengejarnya.
Moira berlari seraya meneriaki ayahnya, tapi usahanya itu nihil. Ayah tak mengindahkannya sama sekali.
“Ayah!” tiba-tiba semuanya terang. Moira mengerjapkan matanya beberapa kali, dadanya kembang kempis, napasnya memburu.
“Moira!” teriak seseorang yang langsung membuat Moira mendapatkan kesadarannya. “Kamu sudah bangun, sayang?”
“Bunda!” Moira memeluk erat ibu mertuanya. Tangisnya tumpah mengingat tadi hanya sebuah mimpi, dan mengingat Ayah telah tiada adalah kenyataan. “Ayah, Bunda. Ayah!” isaknya.
Bunda mengelus punggung Moira bermaksud menenangkan sang menantu. “Sabar, sayang. Ini yang terbaik buat Ayah. Allah sayang Ayah Moira, sekarang beliau enggak sakit lagi,” ucap Bunda seraya menangis.
“Bunda.” Suara itu berasal dari balik pintu kamar Moira, Adam−ayah mertua Moira−. “Semuanya sudah siap,” terangnya kemudian.
Bunda mengangguk. Sementara Moira tangisnya kian pecah. Ia tahu betul maksud dari ucapan ayah mertuanya itu. Berapa lama dirinya tidak sadarkan diri?
“Ayo, sayang. Tabahkan hatimu, beri bakti yang terbaik untuk Ayah hari ini.” Bunda menuntun Moira untuk ke luar kamar.
Pandangan Moira sedikit kabur karena air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Namun yang pasti, ia dapat melihat di luar kamar begitu padat orang yang melayat. Sampai-sampai jenazah Ayah tak terlihat di tengah sana. Begitu pun dengan karung berisi beras yang berjejer di ruang tengah, amat banyak.
“Jangan risau soal rezeki. Yang meninggal saja masih Allah jamin rezekinya, apalagi yang hidup.” Teringat ucapan Ayah dulu ketika dirinya risau soal rezeki. Kala itu Moira ragu untuk melanjutkan studinya karena memikirkan rezeki, ia takut kalau Ayah tak bisa membiayai karena hanya mengandalkan uang pensiunan. Tapi nyatanya sesuai ucapan Ayah, bahkan sekarang ia sudah kuliah sampai semester 5. Lalu, ucapannya begitu nyata tatkala melihat begitu banyak rezeki Ayah saat ini walau beliau sudah pupus.
Waktu berjalan begitu cepat. Dengan kaki bergetar lemas Moira mencoba untuk tetap tegak berdiri di depan peristirahatan terakhir Ayah. Lambat laun, tanah merah itu semakin menggunduk hingga membuat Ayah tak terlihat lagi. Kini ia betul-betul kehilangan Ayahnya. Sosoknya, raganya, jasadnya. Yang tertinggal hanya nasihat-nasihatnya.
Moira menaburkan bunga, menyiramkan air hingga air matanya ikut menyirami tanah merah itu. Dilihatnya Akmal dan Fara yang ikut menabur bunga di sana. Tapi saat ini Moira tak dapat menyapa mereka, tenggorokannya bagai terganjal batu. Tak mampu berbicara.
Tak lama suara adzan Maghrib berkumandang. Warna oranye yang tadi sempat menyinari pemakaman Ayah kini hilang ditelan malam. Bunda dan Abi mengajak Moira untuk segera beranjak. Dituntunnya ia berjalan oleh sang ibu mertua.
Merasa ada yang hilang, Moira menengokan kepalanya ke sana kemari. “Mas Ibram mana?” tanyanya kemudian dengan suara serak.
“Ibram gak bisa ambil cuti dadakan, sayang. Tapi sebentar lagi dia pasti pulang,” jawab Bunda.
Jelas ibu mertuanya itu berbohong. Sewaktu Moira menghubunginya perihal kondisi Almarhum, Bunda langsung menghubungi Ibram tetapi ponsel anaknya itu tidak aktif. Lalu berinisiatif menghubungi kawan sejawatnya dan mendapati jawaban bahwa Ibram sedang cuti. Kemana anak itu saat kondisi berduka seperti ini, batinnya risau.
***
“Terima kasih ya, Ibram,” ucap mama Anindira setelah sampai ke depan pintu rumahnya. “Senang bisa menghabiskan waktu seharian dengan kalian,” imbuhnya sambil menatap Anindira dan Ibram silih berganti.
“Ibram juga senang kalau Tante senang. Apalagi tadi pas di kebun teh Tante kelihatan gembira sekali di sana,” jawab Ibram sambil tersenyum tulus.
Tadi siang, Ibram pergi bersama Anindira dan mamanya. Atas permintaan Mama Anindira mereka pergi ke Puncak Bogor. Walau sebetulnya ini adalah liburan yang dipaksa, tetapi dari lubuk hati Ibram yang paling dalam sama sekali tidak ada rasa terpaksa.
“Kalau begitu, Ibram pamit Tante.” Ibram bersalaman pada Mama Aninidira, lalu detik berikutnya Anindira memeluknya erat. Mulanya Ibram ragu untuk membalas pelukan itu, tapi ia tak mau menjadi munafik. Ibram balas memeluk Moira, dan sebelum melangkahkan kakinya untuk pergi ia mencium puncak kepala Anindira sekilas.
Ibram menghembuskan nafasnya berat setelah duduk dibalik kemudinya. Sejenak ia menunduk, menempelkan keningnya pada roda kemudi. Apa yang terjadi hari ini begitu tak terprediksi. Niat awal menjelaskan semuanya apa yang terjadi, tetapi dirinya malah terjebak atas tindakannya sendiri. Walau ia juga tak menampik kalau dihatinya hanya ada Anindira di sana. Tetapi, bukan seperti ini keinginannya. Ditambah Anindira berbohong kepada mamanya soal lamaran itu.
Tak terasa umpatan lolos dari mulut Ibram.
“Terserahlah, aku akan hidup bagaimana nanti!”
Ibram menjalankan mobilnya. Sebelumnya ia sempat berpikir kemana malam ini dia akan pulang, ke rumahnya atau ke rumah mertuanya?
Tetapi lebih baik ke rumahnya terlebih dahulu sekalian membawa baju-bajunya ke rumah Moira. Mengingat Moira hati Ibram jadi gusar tak menentu. Mengapa wajah bulat, lesung pipit, tubuh mungil Moira terus-terusan terbayang sepanjang perjalanan.
Dan di sinilah sekrang Ibram, memasuki jalanan komplek rumah Moira tak jadi pulang ke rumahnya dulu. Ia pelankan kendaraannya tatkala tiba di pekarangan rumah Moira. Matanya menyipit, keningnya berkerut terheran melihat rumah mertuanya yang amat ramai. Kerumunan orang-orang di sana berjalan meninggalkan rumah mertuanya seraya membawa sebuah kresek hitam yang terlihat seperti sebuah bingkisan.
Dengan perasaan heran penuh pertanyaan, Ibram turun dari mobilnya. Hendak bertanya pada salah satu orang yang melintasinya tetapi urung ia lakukan. Langkah kakinya ia percepat, hingga sampai di ambang pintu. Dilihatnya Bunda dan juga Abi di dalam rumah yang sekarang tampak berbeda. Sofa yang biasanya menghiasi ruang tamu kini terganti dengan gelaran tikar.
“Ibram!” teriak Bunda ketika melihat sosok putranya. Tangis Bunda pecah di dada Ibram. Lutut Ibram mulai terasa lemas. Apakah…
“Di mana Moira?” tanya Ibram tak sabaran sambil memegang kedua lengan Bunda.
“Dia di kamarnya,” jawab Bunda seraya menghapus air matanya dengan ujung pashmina.
Tanpa menunggu lama, Ibram langsung melangkahkan kakinya. Dadanya berdebar. Banyaknya langkah kaki yang diambil Ibram, sebanyak itulah ia merutuki dirinya sendiri.
Pintu kamar Moira sedikit terbuka. Ragu untuk masuk ke dalam, Ibram menghentikan langkah kakinya di sana. Bagaimana ia harus menjelaskan? Bagaimana ia harus memulai?
Terdengar suara tangisan Moira di dalam sana. Ibram tak kuasa mendengarnya, lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dilihatnya Moira tengah menangis seraya memeluk guling di tepi ranjang. Ibram menelan ludahnya susah-susah, bak menelan sebongkah batu.
Ibram duduk di samping Moira dengan gerakan pelan. Menyadari kehadirannya, Moira mengangkat kepalanya yang sedari tadi tertunduk.
Wajahnya begitu kusut. Matanya sembab. Teriris hati Ibram melihatnya. Moira terlihat rapuh, penopangnya telah pupus.
Ibram telah siap dengan segala caci maki Moira. Sangat. Sangat siap. Dirinya memang pantas untuk mendapatkannya. Bahkan dikutukpun rasanya lebih pantas.
Namun, nyatanya tak sesuai pikiran Ibram. Moira malah menarik tangannya, lalu gadis itu mencium punggung tangannya lama. Ibram dapat merasakan air mata di sana, punggung tangannya basah. Berdosalah lagi Ibram yang telah berburuk sangka.
“Terima kasih,” ucap Moira serak dengan tetap pada posisinya yang masih mencium tangan Ibram. “Terima kasih sudah membantu Moira memenuhi permintaan terakhir Ayah,” imbuhnya sambil tergugu menangis.
Terkutulah kau Ibram! lagi-lagi Ibram merutuk dirinya sendiri.
Ibram meletakan tangannya pada puncak kepala Moira, diusapnya pelan. Tak terasa air mata jatuh mengenai kerudung Moira. Kalau ditanya siapa yang paling berdosa di muka bumi ini, maka dengan lantang Ibram akan menjawab dirinya sendiri.
Moira tentu melewati hari ini dengan berat, tapi tak ada dirinya untuk menemani. Andai tadi ia tak menuruti permintaan mama Anindira. Dan andaikan saja ia tak lupa untuk mengisi baterai ponselnya tadi pagi. Mungkin semua tak akan seperti ini.
“Mas Ibram, Moira udah gak punya siapa-siapa lagi,” ujar Moira seraya mengangkat kepalanya dan menatap Ibram.
“Ada aku di sini,” jawab Ibram seraya menghapus air mata sang istri dengan ibu jari tangannya. “Kamu gak akan sendirian.”
“Jangan tinggalkan Moira,” pinta Moira dengan air mata yang terus deras keluar.
Ibram tak langsung membalas, lama sekali ia menatap Moira. Gadis kecil di hadapannya ini sudah jadi tanggung jawabnya kemarin, lalu mengapa harus ragu untuk menjawab ‘iya’?
“Iya.”
Berjanji untuk selalu menemani sang istri tentulah bukan sebuah kesalahan. Tetapi, jika berjanji kepada dua wanita sekaligus untuk selalu bersama, tentu hal yang tak termaafkan. Untuk yang kedua kalinya Ibram terjerumus oleh lidahnya sendiri.
***
Terima kasih sudah mampir dan meninggalkan jejak, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza 😊
Jangan sungkan untuk memberi kritik dan saran ^^
17 Juni 2019,
Arney


 itsarney
itsarney





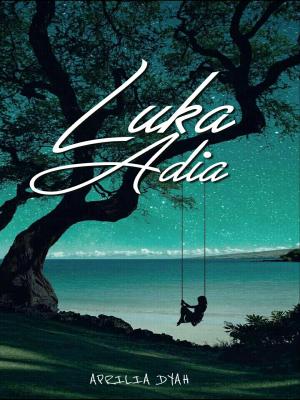


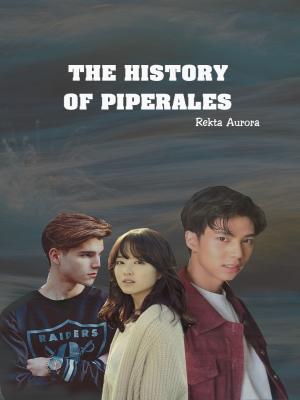

@itsarney akunku yurriansan. klo kmu mau mampir dluan boleh, aku bksln lmbat feedbacknya. krena klo wattpad bsanya buka pke lptop, aku gk dnload aplikasinya. dan lptopku lg d service
Comment on chapter BAB 1: Keputusasaan