Ketergesaan adalah satu kata yang cukup untuk menggambarkan suasana gedung Asosiasi Sihir pagi ini ketika mereka mendengar rumor bahwa kapal Fortuner kembali ke Pelabuhan Akre kemarin senja. Tidak perlu repot-repot memeriksa rumor itu benar atau tidak, semua orang pasti tahu rupa kapal itu dan tak mungkin main-main dalam menyebarkan rumor tentangnya. Semua Petinggi berkumpul, termasuk Sofia dan satu anggota baru yang menggantikan posisi Lothius. Beberapa orang tak mengenalnya karena wanita yang satu ini amat misterius, tapi Sofia yang pintar membaca gerak-gerik lawan bicara tahu bahwa dia adalah wanita yang ambisius, seolah-olah ia memang mengincar jabatan Petinggi Asosiasi.
Sifatnya yang ambisius itu juga dibuktikan dengan penelusuran latar belakang yang cukup buram bagi penyihir seperti dirinya. Yang Sofia dapat hanyalah fakta bahwa ia adalah pemimpin pasukan elit bernama Neo-Camlot, sebuah kelompok kecil berisi ksatria dan penyihir elit. Bagaimana cara ia mendapatkan status kepemimpinan? Ia cukup menunggu saudara tirinya mati dan otomatis ia menggantikan kedudukannya. Aneh menurut Sofia, seolah-olah kematian saudara tirinya memang telah direncanakan.
Namanya Morgana, orang-orang sering memanggilnya Lady Morgana atau Fata Morgana. Beberapa sumber mengatakan bahwa Morgana adalah saudara ipar Lothius, tapi kabar ini juga tak jelas apa sumbernya, membuat Sofia tambah tak keruhan. Yang terburuk, Lady Morgana termasuk dalam daftar Penyihir Abadi di catatan Sofia karena identitasnya yang lenyap. Iason sudah mendapat peringatan Sofia, “kita tak tahu siapa dia, Iason. Satu langkah salah dan kita hancur, pikirkan itu.”
Iason mempertimbangkan beragam hal hingga ia sampai ke satu titik, Lady Morgana beserta kelompok elitnya akan tetap diawasi secara rahasia oleh Sofia.
Mereka duduk bersebelahan, Sofia duduk sendiri sementara Lady Morgana dikawal oleh dua ajudan kepercayaannya. Satu penyihir yang berdarah separuh iblis bernama Marlin dan seorang ksatria bertubuh tegap, namun tampak cacat lidah bernama Merdraut. Keduanya digadang-gadang sebagai duo penyihir-ksatria terkuat seantero Unomi. Dikabarkan mereka mampu mengalahkan Tyran Behemoth. Dan rasa-rasanya ini bukan sebuah kisah fantasi belaka bila melihat tongkat Marlin yang terbuat dari tulang lurus, masih berwarna keputihan, dan penuh ukiran rune sihir.
“Kapiten Eias akan datang tiga menit lagi,” begitulah kata seorang serdadu yang bertugas mengantarkan pesan. Semua petinggi saling pandang, berpikir bagaimana sosok Kapiten Eias yang bahkan bisa melintasi Perairan Iblis dan kembali dengan utuh bersama semua awak kapalnya. Wajah-wajah Petinggi Asosiasi terlihat beragam, ada yang cemas, ada yang semangat, ada yang acuh tak acuh menyambut anggota baru mereka.
Begitu pintu ruang rapat terbuka, terlihatlah seorang pemuda berjubah merah. Ia berjalan dengan seorang gadis tigra bertunik coklat. Wajah mereka tampak benar-benar asing bagi semua orang di sana. “Kapiten Eias! Selamat datang di Asosiasi Sihir, mohon duduklah di tempat yang tersedia,” dengan langkah anggun untuk ukuran seorang pria, ia duduk di bangku di antara Reynald sang Druid dan Morgana sang Enchantress. Setelah Kapiten Eias duduk nyaman, Iason langsung bertanya, “kami tak akan berbasa-basi, bagaimana misi Anda di Tír na nÓg?”
“Bisa dikatakan berhasil, bisa tidak,” jawabnya santai, “kami berhasil tahu senjata ampuh macam apa yang digunakan untuk membunuh Penyihir Abadi, tapi kami tak bisa membujuk Kaisar untuk bekerja sama.”
“Apa senjata itu?” tanya Iason dan Reynald bebarengan.
“Darah para peri, begitulah yang mereka katakan.”
Semua orang tampak tak percaya dan hampir-hampir menganggap pemuda itu gila, tapi dilihat dari raut wajah seriusnya, pemuda itu tidak berbohong. “Kalian mungkin menganggapku gila atau semacamnya, tapi ketahuilah bahwa apa yang kuucapkan itu fakta yang kudapat dari Tír na nÓg.”
Semua orang bungkam, hingga Lady Morgana mengangkat tangannya, “rupanya ada orang yang juga berpikiran sama denganku di sini,” paparnya dengan nada congkak, “darah peri memang mampu menetralkan sihir apapun, tapi jarang digunakan karena kutukan yang menyertainya,” ia menatap setiap pasang mata secara bergilir, lalu berhenti di Kapiten Eias, “cukup bernyali juga untuk mengatakannya di depan sang Druid.”
Kapiten Eias tersinggung, tapi ia hanya menyeringai membalas, “Anda benar juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Menunggu Penyihir Abadi menghabisi kita?”
Keadaan menjadi hening. Semua anggota lama Petinggi Asosiasi diam melihati dua anggota baru mereka bertengkat; entah karena mudah akrab atau memang bermusuhan. Morgana duduk menyilangkan tangan, “apa kau punya solusi lain?”
“Tentu saja tidak, tapi,” Eias menyikut bawahannya, menyuruh tigra itu melempar dua kantong darah segar yang bersinar redup, “tapi perjalanan kami tak pernah sia-sia.” Eias bangkit dari kursinya, mengangkat dua kantong darah itu tinggi-tinggi, “kita punya sampel darah peri murni, yang sekarang kita perlukan hanyalah seseorang untuk mengimitasinya.” Dengan angkuh, Eias pergi dari tempat duduknya bersama sang ajudan, “seperti yang Kapiten Hartein ucapkan, tugas kami hanyalah membawa senjata yang dimaksud: darah peri murni. Sisanya kuserahkan pada kalian.”
“Mau kemana kau, Eias?” bentak Sofia yang merasa pemuda yang satu ini sudah di luar batas, “rapat belum selesai dan kau pergi sebelum urusan selesai?! Pria macam apa kau?”
Eias berhenti, lantas menoleh, “terserah Anda bilang apa, Lady Sofia. Tapi kami adalah pelaut yang kelelahan dan langsung dipanggil dalam waktu yang singkat? Ayolah, beri kami waktu setidaknya tiga hari untuk melepaskan penat.”
Sofia ingin saja menghantam wajah sombong Eias. Ia merasa sudah banyak membuang-buang waktu hanya demi mendapatkan dua kantung darah. “Tidak kompeten!” begitulah batinnya melihat gelagat Eias yang benar-benar tidak mencerminkan seorang Petinggi Asosiasi, melainkan seorang pelaut murahan yang hidupnya serba mudah dan santai. “Kau! Berani sekali kau—”
“Hentikan Sofia!” seru Iason, “dia benar. Sebuah pencapaian tersendiri mereka bisa selamat dari Perairan Iblis dua kali dan berhasil membawa informasi yang cukup penting ini.”
Eias tak menggubris kalimat peringatan itu dan tetap saja berjalan ke pintu. Seorang serdadu berhelm yang tadi bertugas menjadi pengantar pesan membukakan pintu, lantas ikut keluar bersama Eias dan ajudannya. “Satu hal lagi, Lady Sofia. Aku menggantikan Hartein sebagai kapten armada, bukan Petinggi Asosiasi. Mohon ingat hal ini, Lady Sofia.” Ketiga sosok itu menggeluyur pergi, meninggalkan rapat yang hanya berjalan tiga menit. Dengan langkah cepat, ketiganya bersegera keluar menggunakan kereta kuda yang kini mengarah ke rumah dinas baru Eias yang diwariskan dari Hartein. Begitu turun, mereka disambut dengan pemandangan mansion bercorak kuno, dengan jendela-jendela berwarna palet cerah, juga ukiran-ukiran di daun pintu yang tampak berat hingga di dorong oleh dua pelayan, juga dengan patung Gargoyle yang bertengger di pilar-pilar tinggi yang seolah menatap rendah tiap orang yang melintas, angkuh meski berwujud batu.
“Tuan Eias?” tanya kepala pelayan tua. Eias mengangguk, “terima kasih telah menuntaskan misi yang bahkan terlihat mustahil.”
“Dan kau...” gumam Eias.
“Ah, mohon maaf,” pria itu menunduk, “namaku Pacey, kepala pelayan di Mansion ini. Silakan Anda masuk.”
Pacey melirik serdadu yang mengawal, lalu bertanya-tanya apakah serdadu itu juga termasuk kawanannya, “iya, dia dan gadis tigra ini adalah orang kepercayanku. Oh, sebenarnya satu lagi, tapi dia masih akan datang sore nanti.” Ketiganya berjalan melewati barisan pelayan berseragam hitam-putih yang secara kompak membungkukan badan. Eias hanya mengangguk lemah, melihati begitu banyaknya orang yang menghormati dan memujanya. Cukup menyenangkan, begitulah senyum di wajah yang ia pamerkan.
“Di mana ruangan Hartein? Aku ada beberapa berkas yang harus kutangani,” tanyanya dengan nada suara sok berkuasa.
“Ah, mari kuantarkan,” tawar Pacey yang berjalan mendahului. Dengan jentikan tangan, semua pelayan kembali menghablur ke posnya masing-masing. Hanya delapan orang pelayan, itu sudah termasuk Pacey yang kini sudah merogoh kunci, memasukkannya ke selot dan membuka sebuah ruang kerja.
Ruang tamu mansion saja sudah tampak megah. Biasanya, di tiap ruang tamu akan terlihat gantungan lilin yang diam dan terang bersinar memamerkan temaram cahaya hangat dari lilin atau batu lumos, tapi di sini tidak. Tepat di atas langit-langit, terlihat rangkat mati Behemoth yang tersusun utuh melintang di langit-langit. Dengan tulang-belulang putih yang indah juga mengintimidasi, Behemoth diam bertengger dengan anggun, merasa nyaman meski tulang-belulangnya dikaitkan oleh sehelai benang tipis yang kuat untuk menopang tubuhnya tetap melayang. Sungguh, Hartein tak tanggung-tanggung berburu hanya untuk melengkapi koleksi demi memenuhi kepuasan pribadi.
Begitu juga dengan ruang kerjanya yang dipenuhi oleh aksesoris serupa. Eias menyuruh gadis Tigra dan sang serdadu untuk berjaga di luar atau berputar-putar, sementara ia ingin berbicara dengan Pacey. Lagipula, mau tidak mau, Eias harus mengenal bawahannya sendiri.
Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar, membuat keduanya diam dan memilih untuk menghentikan perbincangan. “Ah, masuklah!” serunya. Pacey segera berdiri, lalu minggir ke pojokan, bersiap sedia atas perintah yang akan nantinya. Tapi bukan perintah untuk menunggu yang ia terima, melainkan perintah untuk pergi, “maaf, Pacey, kami punya perbincangan di antara kami. Aku rasa kau tak perlu ikut.”
Pacey mengerti. Tanpa perlu disuruh dua kali, ia pergi dari ruangan itu setelah memberi Eias kunci ruangan. Sesuai waktunya untuk acara minum teh sore hari, Pacey juga tak lupa telah menghidangkan kue-kue dan empat cangkir teh untuk Eias, sang serdadu, gadis tigra, dan seorang tamu bertudung putih. Begitu pintu di tutup, gadis Tigra segera mengunci rapat pintu dan merapalinya mantra. Setelah yakin mantra itu selesai dan tak segesek suara pun akan keluar, ia mengangguk. “Aman,” ucapnya.
Empat orang saling pandang, diam, lalu di antara mereka mulai bicara, “aktingmu cukup bagus, Petra,” tukas sang serdadu yang kini membuka helm yang sedari tadi menutup wajahnya, “dengan ini, tahap satu berjalan sesuai rencana.” Sang serdadu menaruh helm besinya, memamerkan wajah dingin seorang pemikir keras.
“Kau melebih-lebihkan, Gawain,” jawab Eias yang kini sudah berubah wujud menjadi Petra. Mantra ilusi Petra benar-benar tak terdeteksi bahkan oleh endusan anjing Asosiasi Penyihir! Mantra orisinal yang cukup menakutkan, bahkan di kalangan para peri. “Kita sudah memasang umpan, bukan?”
“Benar,” kali ini yang menjawab adalah Abi yang baru saja datang. Ia duduk di sebelah Gawain, membuka peta Benua Unomi yang sudah ditandai di beberapa titik. Tempat-tempat itu dinamai Hutan Magis. “Dari pergerakan sebelumnya, musuh kita, Necromancer, menggunakan taktik klasik di mana ia ingin membuat semua orang berpikir bahwasannya ia menghancurkan kawasan Hutan Magis demi kendali Tyran yang absolut... tapi kita salah, itu jebakannya.”
Gawain mengambil pena, “dua Petinggi Asosiasi meninggal dan satunya menghilang. Semuanya dalam waktu yang hampir bebarengan. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan: beberapa Penyihir Abadi sedang berkumpul di Hyulida,” Gawain memelankan suaranya, lantas berbisik pelan, “termasuk kami, ada empat. Satu pengendali mayat dan satunya peramal masa depan. Mereka hilang, tapi bukan berarti kita tak bisa mencarinya.”
“Dengan cara umpan...” balas Petra, “itu berarti kita hanya perlu menunggu, bukan?”
“Tidak hanya menunggu,” Abi memotong cepat, “tapi juga mengumpulkan informasi sekecil apapun dan mulai merangkainya seperti permainan puzzle. Tiap potongan kecil akan dirangkai jadi gambar yang besar.” Abi makin memelankan intonasi suaranya, “bagaimana pertemuan kalian dengan semua Petinggi Asosiasi, apa ada yang mencurigakan?”
“Menurutku,” Petra membahas, “wanita tadi cukup mencurigakan...” Tigra Lily mengangguk setuju dengaan Petra, “dia bukan peri, tapi dia tahu betul kemampuan darah peri. Dia pasti memiliki persekongkolan dengan Penyihir Abadi sehingga mengetaui informasi semacam ini,” Petra memandang Gawain, “bagaimana menurutmu, Gawain?”
Gawain menyilangkan tangan, berpikir dan bergumam sendiri. Dengan mata terpejam lama, ia akhirnya bicara, “untuk hal itu, kita hanya perlu diam; terlalu dini mengambil kesimpulan semacam itu,” tukasnya dengan berdiri lalu menoleh ke arah jendela, “rupanya satu orang telah mengambil umpan.” Cukup dengan intuisi, Gawain sudah bisa menebak bahwa ada beberapa orang yang mengawasi mereka melalui jendela. Mereka tersembunyi di salah satu dahan, mencoba bersembunyi dan mengintip dengan seksama gerak-gerik Gawain dan komplotannya.
“Perlu kukejar?” tanya Lily yang segera bangun berdiri beranjak menuju pintu.
Gawain menyeringai, “biarkan saja. Kau tak perlu repot-repot mengejarnya, Lily. Lagipula, segelmu pasti membuat ilusi lain, bukan?” menurut pengamat di luar, Eias akan tampak duduk menulis atau membaca, sementara tiga pengawalnya hanya akan berdiri di pojok ruangan, mengawal Eias dari dekat.
Begitulah yang Panther dan Felice lihat. Mereka berjongkok di ranting, mencoba sebisa mungkin menyatu dengan alam. Merasa aneh dengan pergerakan monoton dari Eias dan anggotanya, Panther bertanya, “kau yakin mereka tak merapal mantra penyegel?” tanyanya ragu.
“Tidak,” jawab Felice yang ikut ragu, “tidak ada berkas sihir. Jika ada, mereka menggunakan mantra segel tingkat tinggi hingga Aperception tidak mampu menembusnya.” Dengan meningkatkan fokus, Felice mulai mengendusi udara dan merasakan bahwa setidaknya ada berkas sihir unik yang telah dirapal meski amat tipis. “Mereka cukup ahli, apa yang harus kita lakukan? Ada kemungkinan mereka sudah tahu...”
“... mereka mempermainkan kita,” simpul Panther. Ia berdiri lalu melompat turun, “tidak banyak yang bisa kita laporkan. Yang terpenting, mereka punya seorang penyihir dan jelas juga mereka menyembunyikan suatu hal. Kita akan mengorek informasi dari para pelayan dengan uang, seperti biasanya.” Panther sudah menunduk dan siap berlari meninggalkan Felice yang masih menatap mansion, lantas memalingkan pandangan untuk segera melapor kepada Sofia.
Kawasan mansion baru Eias terletak di bagian Selatan Hyulida. Terdapat kebun-kebun pribadi milik Hartein dan orang-orang para pekerjanya, menggarap tanah seluas dua hektar demi menghasilkan buah coklat yang akan diolah dan dijual ke pasar. Cukup mudah bagi keduanya menyelinap keluar-masuk tanpa diketahui siapapun. Saat keluar, mereka sampai di pinggiran Kota Hyulida, lalu menghablur tanpa jejak di keramaian. Dengan langkah yang cepat, mereka segera kembali ke gedung Guild di tengah-tengah kota. Tidak seperti biasanya, Sofia sudah menunggu mereka di ruang tunggu dan berbincang dengan beberapa petualang veteran tentang keadaan lapangan, fluktuasi pasar, atau persebaran personil, dan rumor hangat.
Mereka menunggu duduk memunggungi Sofia, begitulah cara mereka untuk bertemu di tempat umum. Felice memanggil seorang pelayan, memesan dua roti lapis seperti pelanggan pada umumnya sambil menunggu Sofia dan para petualang veteran selesai bicara. Saat pesanan datang yang ketepatan dengan para veteran selesai bicara, perbincangan di antara ketiganya dimulai.
“Seperti yang Anda duga, mereka menyembunyikan sesuatu,” papar Panther dengan suara berat, namun tetap menjaga volume suaranya agar hanya ketiganya yang mendengar.
Sofia menyeruput cangkir kopinya, ia sudah lama tidak bersantai seperti ini. Sering kali ia menenggelamkan diri di tumpukan kertas, kini ia bisa bebas setidaknya satu-dua hari, karena selanjutnya, Asosiasi Sihir akan mulai bergerak serius. Dengan berbekal darah dan pengetahuan Lady Morgana untuk memanipulasi serta mengimitasi darah peri, Asosiasi Sihir sudah memiliki senjata ampuh untuk memburu Penyihir Abadi. “Kalian gagal mengintai?”
Keduanya membisu, itu jawaban yang cukup jelas bagi Sofia. Kini ia berpikir orang macam apa Eias. Ia bukan sekedar pelaut biasa; ia pasti lebih dari itu. Mungkin congkak, tapi kesombongannya bukan berarti hanya omong kosong. Tidak hanya itu, ia punya beberapa abdi yang terlihat cukup kuat. Jika saja orang bernama Eias dan tigra ajudannya itu punya rekam jejak yang jelas, Sofia mungkin bisa bernapas lega. Tapi kini ia menggigit bibir, teringat pesan ketiga Master Septim: jangan mudah percayakan punggungmu, bahkan pada orang yang selama ini kau anggap kawan sendiri. Hanya mengingatnya, Sofia kehilangan langkah kepercayaan. Apakah ada di antara Petinggi Asosiasi yang benar-benar berkhianat?
Sofia mendengus. Ia hampir tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Alangkah baiknya bila ia bisa bertemu dengan seorang lain yang bisa dipercaya. Sofia termenung, tangannya tiba-tiba merayap menuju saku, lalu mengambil jurnal tua lengkap dengan pena dan tinta. Sebuah harapan akan rasa percaya muncul, tapi ia tak bisa bertindak gegabah. Dengan tangan yang cukup bergetar, ia mulai menulis, “hei kawan! Bagaimana kabarmu?”
Malam itu, Gawain sedang keluar bersama Abi untuk menikmati waktu berduaan. Perbincangan di antara keduanya menjadi canggung. Awal mereka bertemu di awal tahun ini, mereka tak bicara sedikitpun kecuali gumaman atau dengkuran. Bila saja Gawain tak belajar bahasa rune kuno dari Enire, pernikahan mereka tak mungkin terjadi. Dan kini mereka kembali ke titik awal, di mana keduanya hanya diam tak bicara sedikitpun.
Untuk urusan gadis, Gawain tak punya rencana apapun. Ia kosong dan hanya bisa melirik bagaimana cara sepasang kekasih berkencan di jalanan atau taman, lantas menirunya. “Ada tempat yang ingin kau kunjungi? Kutraktir,” tanyanya dengan membeo seorang pemuda yang sedang bergandengan tangan dengan kekasihnya.
Abi manggut-manggut, bukan jawaban yang tepat. Sama seperti Gawain, ia tak memiliki ketertarikan terhadap emas dan perhiasan lainnya. Tidak feminim, tapi cantik secara natural. Lekuk tubuhnya yang ramping, rambut pendek putih keperakan, iris mata yang senada warna, wajah tanpa ekspresi yang sulit ditebak, juga kulit yang cenderung puith meski sering terpapar sinar mentari adalah daya tarik utamanya, membuat pria tunduk dan bertekuk lutut hanya demi menemui hatinya yang dingin dan penuh misteri logika. Ada beberapa orang yang mengatainya sebagai pria; wajar saja bila kita tengok kuncup dadanya yang relatif kecil bagi seorang gadis yang bertubuh fisik delapan belas tahun, juga dengan otot lengan yang berisi namun tetap menjaga proporsi tubuh wanitanya agar tetap anggun.
Tapi bukan berarti es di kutub dunia tidak bisa mencair, begitulah gambaran yang dapat kita padani dari Abi. Sedikit demi sedikit, ia belajar bagaimana cara menjadi seorang wanita, mulai dari menjaga cincin yang diberikan Gawain, mulai memikirkan baju apa yang cocok untuk ia kenakan, dan mencari resep makanan yang digemari Gawain secara rahasia dan sembunyi-sembunyi agar memberi kejutan yang tak Gawain duga-duga.
Sebagai seorang pria, Gawain lah seharusnya yang memandu, bukan bertanya. Sesuai dengan saran Lily, ia mengajak Abi ke sebuah kedai di pinggir trotoar jalan. Semua anak muda menyebutnya Caffè yang diambil dari kata “kopi” namun dalam bahasa asing. Produk unggulan yang dijual tentu saja beragam macam kopi dan olahannya. Gawain tentu belum pernah ke sana—ia hanya meniru kelakuan pasangan lain yang keluar masuk, dan tentu saja Abi juga belum pernah ke sana.
Begitu masuk, aroma kuat kopi yang disangrai menggelitik hidung, menaikkan minat untuk mencicipi kopi barang satu-dua teguk saja. Mengetahui ada sebuah kursi kosong, mereka menyegerakan diri duduk, memanggil pelayan yang langsung memberikan sebuah kertas dan daftar menu. Ilustrasi semua hidangan yang tergores kasar dengan pensil arang terpapang, menampilkan gambaran tentang apa yang nanti mereka pesan. Keduanya bingung, hingga mulai menunjuk acak salah satu dari gambar. Entah dorongan batin atau memang murni kebetulan, keduanya memesan secangkir kopi yang sama.
Lima menit setelah memesan, kedua cangkir datang dengan uap yang masih mengepul hangat. Hitam separuh coklat, dengan buih yang masih berputar di tengah-tengah, juga bau karamel yang tenggelam di dasar, begitulah yang mereka pesan. Sesuai adat lama yang mengatakan bahwa “wanita terlebih dahulu”, Gawain mempersilakan Abi untuk minum. “Pria lah yang seharusnya mengambil inisiatif, Gawain,” ucapnya dengan menyeruput kopi yang masih panas. Ia tidak kehilangan kontur wajahnya—kecuali rona merah yang sedari tadi masih menyala dari pipi hingga ke telinga.
“Terserah katamu, Abi,” balas Gawain dengan nada berkuasa, tak ingin kalah dengan Abi, meski keduanya tahu bahwa di balik wajah datarnya, mereka menahan malu.
Seorang penyaji kopi berupa wanita elf gemuk menaikkan alis begitu melihat tingkah laku dua insan yang berlagak. Ia teringat kontes drama yang ia ikuti, yang tak ia sangka-sangka bertemu dengan calon suaminya. Berawal dari panggung pementasan hingga ke panggung pernikahan. “Ah, sungguh masa muda yang menyenangkan,” gumamnya. Tidak hanya dia, beberapa gadis yang lain tampak iri-iri dengan pesona yang terpancar dari keduanya, sementara si pria pasangan mereka acuh tak acuh, tak menyadari bahwa gadisnya sedang membandingkan diri mereka sendiri dengan Gawain dan Abi. Serasa ada bumbu tersendiri yang tiba-tiba tercampur ke udara yang bahkan baunya saja sudah membuat air ludah sendiri terasa manis, apalagi saduran aroma kuat dari olahan kopi yang bahkan bisa membuat bulu kuduk petualang kuat menegak.
“Maaf mengganggu waktu Anda, Master,” bisik Florence tiba-tiba, “tapi seorang kawan sedang mengirimkan pesan.”
Begitu mendengar, kopi yang Gawain teguk langsung saja terasa pahit. Mata abu-abunya terpejam, meninggalkan bayangan Abi sebagai istri, lalu membukanya kembali demi menggantikan —lebih tepatnya menurunkan— citra sang istri menjadi sebatas rekan. Itu menyakitkan bagi hati Gawain, tapi entah kenapa ia mulai terbiasa melakukan hal ini. Lagi dan lagi. Apakah ia akan menjadi sosok yang tidak hanya mati semangatnya; tapi juga ikut mati hatinya? Lalu apa? Orang yang mati akal pikiran dan logikanya? Kapan ia akan benar-benar mati? Apakah akhirat mengampuninya?
Mata Abi yang menangkap pandangan menyedihkan Gawain, mengerti bahwa tiada hal lain yang biasa mengganggu pikiran Gawain. Ia menghirup napas, menaruh cangkir ke tempatnya, lalu menghembuskannya perlahan. Ia harus profesional; mengesampingkan perasaan demi sistematika logika sebagai jalan guna mengambil keputusan. Dengan sentuhan hangat ke tangan Gawain, ia bertanya, “kenapa?”
Sungguh tidak sopan bagi seorang pria untuk membahas pekerjaan di tengah kencan; itu sama saja menyuruh sang gadis untuk merencanakan bagaimana cara untuk memutus hubungan. Tapi tidak dengan keduanya yang memang berbeda dengan yang lain. Itu risiko dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Tidak ada waktu cukup untuk istirahat atau bersantai. “Hanya permasalahan kecil, aku teringat seorang kawan.”
Sebenarnya, bila pesan itu tidak ia terima sekarang, ia mungkin saja tenang. Tapi mengapa kawannya itu mengirim pesan saat ini? Kebetulan? Tidak. Pengalaman hidupnya membuktikan bahwa kebetulan hanyalah omong kosong bagi mereka yang ingin menutupi usahanya. Dari sana, Gawain menarik kesimpulan bahwa ada motif dan niatan tersendiri mengapa kawannya itu mengirim pesan di saat-saat seperti ini.
“Gawain, bicaralah,” tukas Abi dengan nada datar dan dingin seperti biasanya. Gawain hanya bisa tersenyum, rupa-rupanya Abi paham dengan kondisi.
Gawain melirik kanan-kiri, memastikan tidak ada seseorang yang mendengar. “Seorang kawan lama mengirimkan pesan. Jujur saja aku tak pernah bertemu orang ini, tapi dia adalah penyedia informasi dan pemberi arahan yang tepat. Tidak aneh rasanya bila ia tiba-tiba mengirim pesan—karena memang kami sering melakukan hal semacam itu—tapi yang membuatku bingung, waktu yang ia pilih kali ini—”
“Cukup aneh bila dikatakan kebetulan,” potong Abi.
Gawain mengangguk, “itu berarti, dia tinggal tidak jauh dari sini.” Rumor memang tersebar cepat, terutama di kota besar atau kota pelabuhan. Jika kepulangan Gawain kemarin sore dan baru terdengar di Hyulida pada tengah malam, maka wajar saja bila kota di sekitar Hyulida mendapat berita semacam ini tadi sore. Gawain tak tahu rerata kecepatan rumor itu tersebar, tapi ia tak merasa perkiraannya juga salah. “Mari kita abaikan saja motif yang tersembunyi, dia hanyalah seorang teman, tidak lebih.” Gawain mencoba mengembalikan suasana yang susah-susah ia kondisikan. Lagipula, ini kencan pertama mereka, jadi ia harus memberikan kesan baik bagi istrinya.
“Tidak apa. Kau pernah bilang kau berhutang banyak pada dia bukan? Jawab saja dan tambahkan salamku padanya,” Abi juga sudah kembali ke sisi periangnya. Ia kembali malu-malu mencuri tatap wajah serius Gawain yang entah sejak kapan ia kagumi. Ah, kekuatan cinta memang tak terduga, membawa kemanisan di tengah pahitnya kekurangan juga kelemahan.
Gawain merogoh tas kecilnya, hanya berbeda beberapa saat dengan Sofia menarik pena dan buku jurnal. Dengan tulisan yang luwes seperti biasanya; tulisan khas seorang wanita, di sana tertulis, “hei kawan! Bagaimana kabarmu?”
“Baik dan selalu baik-baik saja! Kuharap kau juga sama sepertiku, siapapun kau di sana.”
Ah, Sofia merasa ia seolah berbicara pada seorang pendeta yang tak ia kenal di balik tirai di bilik sempit tempat pengakuan dosa. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa datang ke kuil, lalu berjalan ke pojokkan, tempat di mana kelompok paduan suara menyanyikan lagu rohani, lalu di sekitar sana, kalian akan menemui sebuah bilik kecil dari kayu yang melekat di dinding kuil. Bilik itulah yang dinamakan sebagai bilik pengakuan dosa. Bedanya, hal yang membatasi mereka bukanlah sebuah tirai atau dinding kayu tipis, melainkan tempat dan mungkin juga waktu, juga cara berinteraksi mereka bukan berbicara, melainkan menulis surat secara spontan.
“Fisikku sehat, kawan. Tapi tidak dengan fikiran yang terbebani padaku,” tulis Sofia.
“Ah. Aku tak pantas mengatakn ini, tapi anggur adalah obat mujarab untuk melupakan permasalahan duniawi yang kita hadapi. Tidak selesai, memang, tapi bukankah setiap orang membutuhkan tempat mengadu dan tempat pelarian? Selaiknya pastur dengan kepercayaan yang ia anut, juga dengan pemabuk dengan segenggam anggur,” balas Gawain berusaha menghibur kawannya. Untuk kebaikan bersama, ia tak menunjukkan tulisan itu pada Abi; ia sudah bisa membayangkan wajah cemburu Abi. “Bagaimana bila kutraktir? Aku juga ingin menyampaikan rasa terima kasih pada dirimu!”
“Sungguh bila pekerjaan ini bisa lenyap,” tulis Sofia. Ia merasa iri dengan teman penyihir seakademi yang bisa menikmati masa mudanya, sementara ia dituntut harus menggantikan Laura sebagai Petinggi Asosiasi. “Kau benar, kawan. Rupa-rupanya aku membutuhkan waktu untuk beristirahat.” Sofia memandangi keramaian di dalam gedung Guild, melihati pecahnya tawa tiap petualang yang berkumpul bersama. Ia bangga, tapi entah mengapa ada ceruk hampa di hatinya.
Rasa bencinya pada kaum pria membuat ceruk itu makin menganga. Kebenciannya itu berasal dari Enire yang sudah ia cap menjadi pria yang melarikan diri tanggung jawabnya. Akibatnya, Sofia mencap sebagian besar kaum adam dengan stempel yang sama. Tapi ia segera mengenyahkan pikirannya, lantas bertanya, “kau sekarang sedang berada di mana?”
“Di tanah. Aku pergi dengan beberapa orang setelah muntab terpapar matahari dan melihati laut. Aku ingin tidur di ladang, tepatnya di bawah teduhnya pohon apel desaku. Sungguh, aku ingin kembali ke sana, tapi beberapa urusan sedang mengekangku.”
“O, rupanya kau punya kesibukkan tersendiri ya? Maafkan aku yang egois,” tulis Sofia. “Omong-omong, bisakah kau bercerita lebih banyak tentangmu?”
“Sulit, kawan. Lebih baik kita bercerita dengan temu langsung daripada bercerita melalui tinta. Jadi bagaimana? Kau mau kutraktir?”
“Tentu saja!” balas Sofia dengan tersenyum. “Aku juga muak dengan kapten kapalmu yang sombong itu. Haha, aku tak tahu bahwa Kapten Eias ternyata orang yang semacam itu.”
Sofia lengah, ia mengira bahwa ia sedang berbicara dengan seorang kelasi bodoh hasil citra Gawain. Jika kita sekilas melihat tulisannya, tak ada yang aneh. Tapi Gawain teliti dan pemikir keras. Langsung saja, ia tersedak. Abi langsung menghampirinya, membantu Gawain dengan mengurut leher dan menepuk-nepuknya. Gawain mengangkat tangannya, menyuruh Abi untuk berhenti. Pias wajahnya kali ini benar-benar serius. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri, meninggalkan cangkir kopi yang belum saja habis. Abi ikut beranjak, meninggalkan bayaran di meja dan langsung ikut pergi. Udara berat terasa pekat di tiap bulu roma semua orang di sana ketika menyaksikan tingkah laku Gawain, namun segera lenyap ketika pemuda itu pergi.
Dengan langkah cepat dan melirik kanan-kiri, mawas akan pengawasan, ia berbisik, “Abi, segeralah bersembunyi. Terserah di mana, tapi bersembunyilah di kota ini.”
“Ada apa?”
“Kubilang sembunyi!” hardik Gawain dengan nada tinggi. Abi tercekat tegang, juga beberapa orang di sekitar yang sempat mendengarnya. Baru kali ini ia mendapati ekspresi Gawain yang benar-benar panik ketakutan, tanpa kepura-puraan sedikitpun. Melihat Abi yang masih membeku, Gawain segera memeluknya, “maafkan Aku, Abi. Aku membentak—”
“Aku mengerti...” balas Abi sembari melepas tangan Gawain, mendorongnya, lalu berpaling. Kencan pertama mereka gagal total, begitulah keduanya menyimpulkan. Abi tahu ada permasalahan lain yang sedang menghantui Gawain, dan itu memang telah menjadi risiko mereka. Dalam satu kedipan mata, sosok Abi menghilang di antara kerumunan, menghablur secara sempurna di tengah lautan manusia. Yakin bahwa Abi dapat menjaga dirinya sendiri, Gawain pergi mengikuti arus, lalu memilih duduk di taman kota Hyulida yang terbuka.
Saat ini musim gugur, itu berarti sudah sekitar empat hingga lima bulan Florence sekarat. Bagaimana kabarnya? Apakah mereka sudah sampai? Perjalanan menuju Amarta bisa memakan waktu satu tahun lebih. Apakah Enire tua bisa melintasinya? Pikiran ini juga mengganggu Gawain. Ia senang bahwa Florence tidak akan ikut campur dalam perburuan, tapi khawatir karena risiko mengarungi lautan pasir lebih mengerikan daripada samudra. Kekhawatiran kembali muncul menggerogoti Gawain, tapi ia tetap mengatur napas tenang, membuat skala prioritas masalah yang harus cepat-cepat ia tangani.
Prioritas utama adalah identitas dari kawan jurnalnya. Dilihat dari kalimatnya, sang kawan sudah pernah bertemu bahkan berbicara langsung dengan sosok Kapiten Eias, itu berarti dia bisa saja tinggal di Kota Akre atau puluhan kota singgah sebelumnya. Tapi, jika dilihat dari waktu ia mengirim pesan, ia seolah baru saja menerima kabar Eias baru-baru ini.
“Bagaimana menurutmu, Florence?” gumam Gawain sembari berpikir. Hanya ada segelintir orang yang menemui sosok Eias, dan salah satunya adalah Petinggi Asosiasi. “Asumsikan dia seorang Penyihir Abadi, maka semua ini bisa masuk akal.”
“Bagaimana masuk akal?”
“Pertama: itu bisa menjawab mengapa jurnal ini tidak sampai di tangan ibuku. Aku paham prosedur di mana semua barang ayahku disita. Tapi ini hanya jurnal biasa! Tidak lebih! Itu berarti, ada orang yang sengaja merapalinya agar jurnal ini bisa terhubung satu sama lain. Kedua: karena gagal menangkapmu, ia mulai mengincar keluargaku. Ia berhasil membunuh Erno dan Morgausse, lalu mengambil alih hak perlindungan Florence, alhasil ia bisa mengawasi Florence dari dekat!”
“Tunggu dulu!” sergah Florence, “itu tak menjelaskan bagaimana mereka tahu insiden Grende. Saat itu...”
“Ingat, musuh kita di sini ada dua; Clairvoyant dan Necromancer. Ada kemungkinan mereka bersengkongkol, seperti Abi dan diriku.” Gawain meremas tangannya, berang, “satu di antara keduanya adalah orang yang memegang jurnal ini. Dia... benar-benar bisa menggiringku...”
“Apa maksud Anda?”
“Dia adalah orang pertama yang menyarankanku untuk ikut ekspedisi Tír na nÓg, karena mereka belum sepenuhnya tahu-menahu tentang senjata ampuh yang dimaksud.”
“Bukankah Clairvoyant sudah tahu senjata ampuh yang dimaksud, juga dengan hasil ekspedisi hanya melalui penglihatan masa depannya? Jika bisa, mengapa ia repot-repot menyuruh Anda ikut ekspedisi? Semua ini masih tidak masuk akal bagiku, Master.”
“Tentu saja, Florence, dia pasti tahu akan hal itu; alasan utama ia menghimbauku ikut hanyalah satu: untuk menyingkirkanku. Dia pasti punya batasan tertentu untuk bisa melihat masa depan, dan mungkin, mantra penangkal milik Oberon adalah salah satunya. Akibatnya, ia tak bisa dengan jelas memprediksi kematianku.”
“Lalu apa maksud pesan kali ini?”
“Tentu saja untuk menjebakku! Dia mengira aku orang yang bodoh; untung saja aku pernah menulis seperti itu.” Gawain mendongakkan kepala, “selama ini... selama ini kita dikendalikan oleh bajingan!” umpatnya, “akan kubalas.. iya, akan kubalas!” dengan seringai licik dan mata keji, Gawain terkikik seperti orang gila. Florence diam sejenak, lalu ia memberanikan diri untuk bicara.
“Bagaimana bila kawan yang kita maksudkan ini bukan Penyihir Abadi?” tanyanya sebelum Gawain lepas kendali.
Gawain diam, berpikir. Jika saja ia salah membunuh, maka dua Penyihir Abadi akan lenyap bersembunyi lagi, membuat pencarian kembali ke titik awal. “Ada kemungkinan semacam itu, cukup besar.” Suara langkah kaki orang-orang yang berseliweran tidak mengganggu konsentrasi Gawain sedikitpun, malahan memacu jantungnya untuk berdetak cepat. “Rupanya kita perlu bertemu seorang kawan lama,” gumamnya sembari menulis.
“Kawan! Kau ada di mana? Aku sedang berada di suatu kawasan desa dekat Kota Suci Hyulida. Sungguh menakjubkan! Baru kali pertama aku melihat Pohon Yggdrasil yang mencakari surga!”
“Benarkah? Aku senang mendengar pujian Anda kepada Kota Suci Hyulida. Ini mungkin takdir, tapi aku juga sedang berada di Hyulida!”
Gawain manggut-manggut, perkiraannya benar. “Oh! Kalau begitu, di mana tempat yang cocok untuk minum?”
“Twilight’s Tavern, sedikit ke utara dari distrik rempah-rempah merah. Kau tahu tempatnya?”
Tentu saja Gawain tahu; baru saja ia melintasi tempat yang dimaksud. Twilight’s Tavern adalah kedai minum yang cukup mewah untuk kantong sebagian besar petualang. Rasa bir dan anggurnya cukup kuat dan sering juga diadakan kontes adu minum dengan taruhan yang cukup menggiurkan. “Ah, nanti akan kutanyakan pada orang-orang sekitar. Kota Suci Hyulida adalah kota terbesar dan termegah yang pernah kusaksikan. Kalau begitu, pukul sepuluh malam besok, bagaimana?”
“Sepakat!” Sofia tersenyum. Dengan ini, ia akan mendengarkan kisah heroik petualangan ke Neverland, namun dengan versi yang lebih bersahabat. Karena ia mungkin bertemu dengan orang berumur, jadi ia sudah memikirkan gaun apa yang harus ia kenakan, aksesoris apa, juga topik yang akan ia bicarakan. Lagipula, ia senang ketika berbicara dengan seorang petualang ulung.
Sayang rencana yang ia rangkai tak pernah terwujud. Julia yang mendengar rencana ini melarang keras Sofia untuk melakukan pertemuan langsung. “Anda adalah seorang Petinggi Asosiasi! Anda tak boleh ceroboh dan gegabah. Suruh Sabre, Felice, atau Panther untuk mengawal!” Sofia tak bisa memanggil paksa ketiganya yang sibuk dalam misi mengintai malam itu. “Lebih baik saya, Julia, yang menemuinya. Tenang saja, Anda boleh saja ikut dan mengamati dari bangku yang lain sambil curi-curi dengar, bagaimana?”
Implikasinya, malam ini Sofia tak bisa berbincang langsung dengan kawannya ini. Ia duduk di bangku dekat jendela dengan tunik dan tudung coklat tua yang usang, sementara Julia mengenakan gaun ringan berwarna kuning keemasan. Sofia mendengus, mengapa ia harus menurut pada Julia?
Tepat pada pukul sepuluh lebih sepuluh menit, seorang pemuda masuk. Pemuda elf yang tampak segar bugar, matanya menunjukkan bahwa ia seorang yang cerdas. Pemuda itu melihat sekitar, lalu menangkap sosok Julia. Dengan langkah santai namun rapat, ia datang menghampiri Julia, duduk lalu keduanya berjabat tangan.
“Urs, salam kenal.”
“Julia, salam kenal juga, kawan,” begitulah perbincangan yang Sofia dengar. Keduanya mulai saling bercerita. Julia yang telah mengarang, mulai bercerita tentang pekerjaannya sebagai seorang akuntan. Pemuda bernama Urs hanya mendengarnya saja, manggut-manggut sambil meminum anggur.
Di saat Sofia lengah mengawasi mereka, sebuah belati sudah mendorong punggungya. Dingin dan tajam, kulitnya sudah mulai tergores. Ia tidak menyadari keberadaan seseorang, tahu-tahu nyawanya sudah terancam. “Bicara atau mati?”
Sofia tak berani menoleh, ia tahu betul bahwa jika ia bergerak sedikit saja, maka nyawanya melayang. Ketenangan adalah kunci kemenangan nyawanya, begitulah pikir Sofia yang hanya berbisik, “bicara.”
“Siapa namamu?”
“Niele, Sofia.” Sesungguhnya, ia punya pilihan untuk berbohong, tapi ia kehilangan opsi tersebut karena intuisi yang mengatakan bahwa belati akan tertembus ke dadanya bila ia menipu.
Sosok di belakangnya diam, lantas makin menodong belatinya, “apa kau termasuk mereka?!” tanyanya dengan nada rendah, namun berintonasi memaksa.
“Siapa yang kau maksud?”
“Jangan berpura-pura bodoh!” tanya sosok itu dengan makin mengancam.
Sofia merenung sejenak. Sesuai dengan seni persuasi, ia mencoba mengulur waktu hingga sosok itu lengah. Tapi tidak sedikitpun ia merasakan kelengahan di belakangnya, jadi ia hanya diam lantas bertanya lagi, “kau pasti tahu diriku, bukan? Mari kita bicara, pelaut.”
Sosok itu—Gawain—mengerutkan kening. Bisa jadi semua ini sesuai dengan prediksi Clairvoyant, dan ia hanya tergiring ke arah jalan yang ditentukan. Ia melirik Urs yang dengan mudahnya mengatasi wanita palsu bergaun kuning dan tetap membuatnya sibuk hingga tak menyadari keadaan Sofia. Apakah Sofia Clairvoyant yang dimaksud? Tidak, masih belum cukup bukti untuk menilainya. Tapi dengan metode yang sama—yaitu mengancam— ia tak akan mendapat jawaban. Maka dari itu, ia menyarungkan lagi belatinya, duduk di sebelah Sofia dan memberi dua botol yang sudah ia pegang di tangan kirinya.
Dengan membuka tudung, keduanya mulai bicara. “Aku akan terus terang, Sofia,” tukas Gawain, “apa kau salah satu Penyihir Abadi?”
Melihat rupa Gawain, Sofia langsung teringat wajah gurunya, Lothius. Mirip, bahkan hingga ke sinar mata dan nada suara. Tapi keduanya beda orang, itulah yang diyakini Sofia. “Tidak,” jawabnya.
Gawain langsung saja menghembuskan napas lega. Ia tahu dengan jelas bawa Sofia jujur hanya dengan melihat gerak-geriknya. Itu berarti ada satu orang lain yang dapat ia percaya selain Hartein di jajaran Petinggi Asosiasi, meski secara pribadi ia tak senang dengan Sofia. Ia mulai meneguk anggur, juga Sofia ikut setelah ia tahu bahwa botol itu tak diracun.
Urs yang tahu bagian Gawain sudah selesai dengan bagiannya, segera menyibukkan Julia dengan bualan. Ah, ia pemuda dimabuk cinta dan Julia adalah gadis yang juga cukup usia. Mungkin alasan mengapa ia menggantikan peran Sofia hanyalah untuk mencari teman bicara, bukan untuk menyamar. Semakin ia ikut arus bicara Urs, ia makin lupa dengan tujuan awal yang ia gaungkan di depan Sofia kemarin. Tapi tak apa, baik Sofia dan dirinya mendapatkan apa yang mereka cari di Twilight’s Tavern.
Sofia melirik Gawain dari iring-iringan. Penasaran betul bagaimana seorang semirip gurunya datang. Gawain mendengus, sudah waktunya ia bicara terang-terangan. “Mari kita bekerja sama, Lady So—”
“Sebelum mengajak, perkenalkan dirimu terlebih dahulu,” potong Sofia.
“Seperti dalam jurnal, aku bukan siapa-siapa; hanya seorang pelaut yang bodoh.”
Sofia terkikik mendengarnya, lalu meneguk anggur dan berkata, “seorang idiot tak pernah memperkirakan hal semacam ini, kawan.” Ia menggantung kalimatnya, menoleh, “siapapun itu, aku perlu nama, kawan. Bagaimana aku memanggilmu hanya dengan sebutan ‘hei kau!’ atau ‘kawan’ atau sebagainya.” Tangannya bersandar di jendela, “siapa dirimu, kawan?”
“Gawain, panggil saja seperti itu.” Jawaban singkat itu tidak meyakinkan Sofia tentang identitas sang pemuda, tapi cukup untuk membungkamnya untuk tak bertanya lagi; pun toh, ia masih bica mencari melalui luasnya relasi di Guild. “Seperti yang kutawarkan, bagaimana bila kami bekerja sama, Anda dengan Kapiten Eias?”
“Berikan alasan mengapa aku bisa membeli kalimatmu, Gawain.”
“Setidaknya satu,” balas Gawain lirih, “satu di antara Petinggi Asosisasi bekerja sama dengan Penyihir Abadi, begitulah kesimpulan Kapiten tentang keadaan ini.” Apa yang dikatakan Gawain mirip dengan Enire, membuat Sofia tercekat bahwa ada anggapan yang sama dari orang lain. “Terserah Anda mau percaya atau tidak; juga terserah Anda mau menerima tawaran kami atau tidak.”
“Berikan alasan mengapa kau percaya padaku,” tukas Sofia meyakinkan.
“Cukup sederhana, Anda bukan Penyihir Abadi dan pemegang sah jurnal.”
“Kau percaya hanya dengan alasan yang sederhana semacam itu?”
Gawain berhenti minum, ia sudah merasa isi perutnya sudah meluap hingga ke kerongkongan. Meski masih belum larut juga ia belum sepenuhnya mabuk, ia sudah tak nafsu untuk menghabiskan sisa malamnya dengan minum; ia mulai membatasi kebiasaan buruknya. Dengan beranjak berdiri meninggalkan uang bayaran di meja, ia bertanya, “terkadang, kesederhanaan fikiran adalah jawaban tiap permasalahan.”
Tepat akan pergi, tangannya ditahan. Sofia kembali menanyakan hal yang sama, namun dengan intonasi yang lebih dalam. “Apa tujuan kalian?”
“Anda tak usah repot-repot mengangkat hidung Anda untuk mengendus urusan macam ini, itu pekerjaan kami: para anjing.”
“Para anjing?”
Gawain hanya membalas, “seorang pemburu membutuhkan anjing untuk menangkap serigala.” Gawain mengebaskan tangannya, merasa bahwa tujuan pembicaraan di antara keduanya sudah tercapai. Begitu ia keluar dari kedai minum, ia mengenakan kembali tudung dan tunik abu-abunya, hilang di jalan malam yang sepi.
Sofia tahu bahwa cara menghubungi Gawain cukup dengan jurnal, lebih baik ia menghindari kontak langsung dengan Gawain. Istilah “para anjing” sudah cukup membuat Sofia paham, dan apa yang ia sepakati di tempat ini tak boleh terdengar ke telinga siapapun, bahkan Julia. “Para anjing ya... mereka peranakan dari serigala yang dijinakkan... ganas namun taat dan penurut... para gembala mengendalikan domba-nya dengan anjing, guna mengusir nenek moyang mereka, serigala...” Sofia memandangi jalanan, mencoba menangkap sosok Gawain yang kini bermandikan gerimis juga bayangan lompongan busuk di ujung jalan, seolah menunggu orang lain di sana, “aku si gembala dan juga sudah menjadi tugas utamaku, menjaga kehidupan rakyat—kehidupan domba.”
Dia berdiri, mengirim sinyal pada Julia untuk menikmati sisa perbincangan, lantas keluar dari kedai. Ia berjalan sembari mendongakkan kepala, mendapati bahwa mendung menutupi sinar bintang, apalagi malam ini bulan baru. Hanya berbekal tempias batu lumos jalanan dan lampu minyak yang bertengger di sudut-sudut bangunan, ia berjalan dengan beban banyak pikiran.
Karena tak fokus pada langkahnya, ia menumbuk seorang bocah berbaju lusuh. Begitu mendongakkan kepala, ia menunjukkan wajah takut-takut pada Sofia, juga dengan telinga anjingnya yang mengerut. Begitulah nasib demi-human atau Halfbeast. Mereka hina bina, mereka hanya dianggap sampah. Tapi tidak pada pikiran Sofia, ia menganggap semuanya sama, begitulah ketika ia melihat Sabre, Panther, dan Felice.
Sofia menegelus kepala si bocah, memberinya sekeping uang lantas pergi. Dengan garis wajah keras, ia hendak melindungi semua hal yang ia bisa; senyum dan tawa semua petualang, lengkap dengan kesedihan dan kepahitan seorang pengemis. Ia bukan siapa-siapa, ia tak bisa mengubah segalanya, ia tahu akan hal itu. Dibanding Gawain, Sofia adalah sosok yang lebih realistis. Matanya terpejam, mendongak membiarkan wajahnya basah oleh gerimis yang kini mulai bercampur kabut, mengharap bahwa pikiran dan ketakutan akan sirna, seperti gerimis yang membasuh debu di wajahnya.
Perburuan Penyihir Abadi, dimulai.


 KurniaRamdan39
KurniaRamdan39



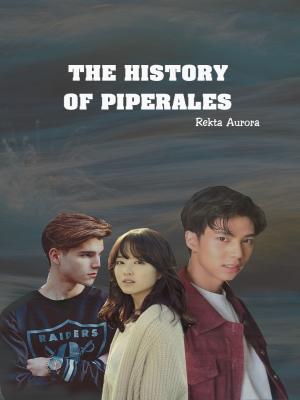







ntap
Comment on chapter Fiveteen: Persona