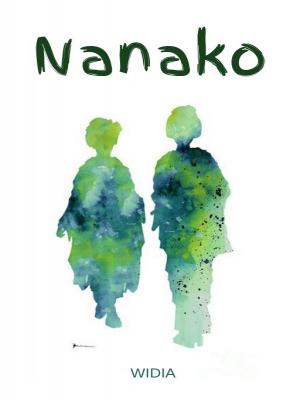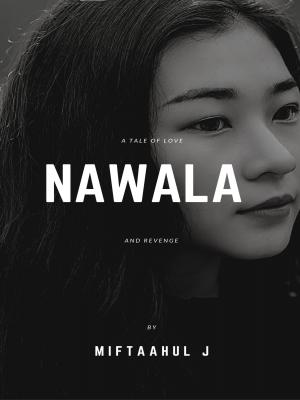Mendung gelap menyelimuti area kampus sore ini. Para mahasiswa telah menyelesaikan jadwal kuliah siangnya. Arry berjalan santai keluar dari kelas dan melewati toilet.
Ketika rintik air tercurah dari langit, Arry terhenti melihat seorang perempuan berambut panjang—bersandar di dinding samping toilet sambil memegangi dada kirinya.
“Tolong,” rintih mahasiswi itu lalu ambruk.
Arry segera menangkap tubuhnya.
***
Sejak menolong Raina yang pingsan, Arry semakin akrab dengan gadis itu. Mahasiswa berambut jabrik pun tidak tahu, mengapa secara kebetulan bertemu lagi. Arry yang mengendarai motor sering mengantarkan pulang gadis berambut panjang ke rumah indekosnya.
“Raina! Ayo, barengan,” ajak Arry seusai kuliah di halaman kampus. “Mendung, nih. Keburu hujan.”
Raina tidak menolak. Perkenalan dengan Arry seperti suratan takdir yang memang harus dijalani. Walau mereka berbeda jurusan, tapi bersama di bawah atap universitas ini.
Di perjalanan, titik-titik air mulai berjatuhan. Tak disangka, Raina berteriak panik.
“Arry, ngebut dong! Udah hujan, nih. Buruan!” Suara Raina di boncengan menembus helm—mengagetkan Arry.
“Iya, iya. Duh, hujan air doang. Takut amat, sih!” gerutu Arry.
Tidak sampai lima menit, mereka sudah tiba di rumah indekos Raina. Segera gadis itu masuk kamar dan meminum obat. Ia duduk sambil mengatur napasnya yang memburu. Arry memandang heran dari teras.
Hujan semakin deras. Petir menggelegar. Raina menjerit sembari menutup kedua telinga dengan tangannya. Arry semakin bingung saat melepas helm. Ia pun terkena cipratan air hujan, membuat celana dan jaketnya basah.
“Arry!” panggil Raina. Ia menangis sesenggukan.
“Kenapa, Raina? Ada apa?” Spontan Arry masuk ke kamar.
“Tutup pintunya, please!”
“Hah, oke!”
“Aku takut!” Raina menghambur ke tubuh Arry yang berdiri di depan pintu.
“Takut apa?” Arry membiarkan teman perempuan memeluk tubuhnya.
“Hujan. Aku takut hujan.”
“Hujan? Astaga, kenapa takut hujan? Udah, jangan nangis ya. Nggak apa-apa, kok. Ada aku di sini.” Arry mengangkat wajah Raina dan menghapus air mata dengan jemarinya.
Raina mulai tenang. “Maaf ya, memang inilah penyakitku. Ombrophobia.”
Arry mengajak Raina duduk. “Ombrophobia itu fobia hujan?”
Raina mengangguk. “Udah cukup lama aku sakit begini. Sejak SMA. Tapi, entah kenapa akhir-akhir ini semakin parah.”
“Cara penyembuhannya gimana?”
“Terapi ke dokter. Selama ini, aku juga minum obat anticemas.”
“Hmm, gitu ya. Ada trauma tentang hujankah?”
Wajah Raina semakin tegang. “A-aku belum bisa cerita sekarang.”
“Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah baikan, kamu boleh cerita kapan aja.”
“Sebenarnya, namaku berasal dari kata rain karena lahir saat hujan. Aku kesal sama diriku sendiri. Kenapa aku malah takut hujan? Huh ...!” Raina menjambak rambutnya.
“Hei, hei. Jangan gitu dong! Raina, tenang ya. Kamu pasti sembuh, kok.” Arry menggenggam tangan gadis itu agar berhenti menjambak rambutnya sampai rontok beberapa helai. Lalu, pemuda itu membelai rambut panjang Raina.
“Makasih, ya. Kamu selalu menolongku.” Raina tersenyum.
“Siap. Eh, hujannya udah reda. Aku pulang, ya.” Arry berpamitan.
***
Seminggu kemudian, entah mengapa Arry merasa ingin berkunjung ke rumah indekos Raina. Sepulang kuliah, tiba-tiba saja ia mengarahkan motornya ke tempat indekos gadis cantik itu.
“Apa mungkin, kamu kangen sama aku?” canda Raina saat Arry sudah duduk di teras depan kamarnya.
Tawa Arry meledak. “Maybe.”
Arry dan Raina semakin dekat seolah dua insan yang sedang kasmaran. Malam yang sendu karena hujan, membuat Arry termenung sambil memeluk gitar di kamar indekos. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang Raina. Ia selalu mengingat segala tentang gadis itu. Seolah alam bawah sadarnya lumpuh terkena hipnotis yang entah dari mana asalnya.
Benak Arry sedang kalut. Ia tidak bisa mendefinisikan perasaan. SMA dulu ia pernah merasa jatuh cinta, tapi tidak begini.
“Arry.” Suara perempuan lirih memanggil. Arry keluar dari kamar. Ia menuju tangga yang menghubungkan bangunan indekos tiga lantai ini. Setiap lantai berisi tiga kamar.
“Siapa di sana?” Arry mengamati lorong yang sepi. Para penghuni indekos berkumpul di lantai dua. Sedangkan ia sendirian di lantai tiga—lantai paling atas.
Arry hendak masuk lagi ke kamar, tapi sekelebat bayangan tampak di dekat tangga. Ia menoleh. Perempuan berambut panjang berjalan di lorong. Arry mengejarnya.
“Hai! Raina?” Arry mengikutinya sampai ke kamar paling ujung.
Namun, bayangan gadis itu lenyap. Mana mungkin ada perempuan di tempat indekos khusus laki-laki? Pikiran Arry kacau. Hampir setiap malam, kejadian aneh terus terulang.
Tok, tok, tok. Arry mendengar pintu kamarnya diketuk. Ia berdiri dan membukakan pintu. Tidak ada siapa-siapa.
***
Kejadian aneh makin sering terjadi semenjak Arry dekat dengan Raina. Ia berusaha keras menghapus bayangan Raina yang menari-nari di pelupuk mata. Juga menahan detak jantung yang sangat kencang. Arry bertekad menghindari Raina agar bisa melupakannya.
***
Raina duduk termenung di bangku ruang kuliah. Telah lama ia tidak bertemu Arry. Beberapa kali ia pernah berpapasan tapi hendak menyapa, mahasiswa itu sudah berlalu. Hari-hari Raina semakin terasa melelahkan. Selain karena tugas-tugas kuliah, musim hujan ini saatnya melawan ketakutan. Ia harus mengatasi penyakitnya, Ombrophobia—fobia hujan.
Raina terkenang masa lalu. Saat itu juga, ia menepis bayangan yang hadir di benaknya. Ia menggeleng. Mencoba melupakan semua. Tapi, tidak bisa. Sore ini, rasa takut menyerbu seiring hujan yang mulai berjatuhan.
Tidak menunggu lama, Raina meminum obatnya. Jantung berdebar tanpa bisa dikendalikan. Ia meraih ponsel dengan tangan gemetar. Dicarinya nomor kontak bernama Arry.
***
Arry menatap mata Raina yang sayu. Ia menyesal telah menghindari gadis malang itu. Raina membutuhkannya. Rasa simpati tumbuh semakin kuat dalam hati.
Hari masih sore tapi angkasa terlihat kelam. Mendung menyelimuti dan mengguyurkan rintik-rintik air. Raina duduk meringkuk di lantai, memeluk lututnya.
“Ombrophobia ini sungguh menyiksa!” keluh Raina.
Arry menghampiri. “Aku pikir, kamu udah baikan.”
“Nggak mungkin. Selamanya aku akan sakit seperti ini.”
“Kamu harus optimis. Pasti sembuh!” Tanpa sadar, Arry memeluk Raina. Tidak lama. Tiba-tiba listrik padam. Gelap dan sunyi.
“Pergi, Arry.” Raina berontak melepas tubuhnya.
“Apa?”
“Aku mau sendirian. Pulanglah!” bentak Raina.
“Kenapa? Kamu nggak takut?”
“Nggak! Cepat pergi!”
“Oke, oke.” Arry keluar dari kamar indekos itu. “Cewek ini benar-benar aneh!” gerutunya sambil mengendarai sepeda motor.
“Pergi kamu! Jangan ganggu aku!” teriak Raina. Suaranya menggema dalam kamar. Matanya membulat lebar. Sosok yang menakutkan itu muncul di sudut kamar.
“Pergi atau mati?” Suara lirih terdengar dari balik bayangan berambut hitam.
“TIDAK!” Raina melempar sosok bayangan dengan botol parfum.
Cermin di kamar itu pecah berkeping-keping.
***
Arry melamun di dalam kamar indekos. Ia bingung memikirkan sikap Raina. Sebenarnya, ada apa dengan gadis itu? Pasti terjadi sesuatu di masa lalunya. Arry sangat penasaran. Ombrophobia yang diidap Raina pasti ada penyebabnya.
Gerimis menghiasi malam hari. Namun, seperti malam sebelumnya. Arry mendengar ketukan suara pintu kamarnya, berkali-kali.
Tok, tok, tok.
Arry membuka mata. Ia belum tidur sepenuhnya tadi. Kini, terpaksa ia menahan kantuk sambil membukakan pintu.
“Siapa?” tanya Arry sembari mengucek matanya.
Tidak ada siapa pun di depan pintu. Arry menengok ke koridor lantai tiga itu. Di lorong depan kamar yang kosong, tampak seorang perempuan berambut panjang. Ia menoleh perlahan. Arry mengenal wajah itu—sosok yang berdiri dekat pagar pembatas lantai tiga.
“Raina?”
“Arry.”
“Ngapain kamu di situ?”
“Kamu pilih pergi atau mati?”
“Apa maksudmu?”
“Selamat tinggal.” Perempuan itu melompati pembatas lantai tiga. Tubuhnya terjun bebas ke bawah.
“RAINA!”
Arry terbangun. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Suasana sunyi, hanya sisa-sisa tetesan air hujan dari genting. Ternyata cuma mimpi, batin Arry memegang dada, menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia menengok jam dinding. Pukul 02.25 dini hari.
Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu bagaikan deja vu.
“Tunggu! Aku nggak mimpi kan?” bisik Arry lalu menampar pipinya sendiri. “Aww! Sakit!”
Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar makin kencang.
Arry bangkit. Dengan ragu-ragu ia mengulurkan tangan di pegangan pintu. Satu, dua, tiga. Ia membuka pintu. Hanya ada semilir angin yang berembus dingin. Arry beranikan diri menengok ke koridor lantai tiga itu. Di lorong depan kamar yang kosong, tampak seorang perempuan berambut panjang.
“Nggak! Nggak mungkin Raina di sini,” bisik Arry. Matanya membelalak.
Sosok perempuan itu menoleh. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajah.
“Aaa ...!” jerit Arry lalu mengunci pintu rapat-rapat.
***
Pagi hari di kampus, Arry tampak berantakan. Ia kurang tidur karena sering bermimpi buruk. Ditambah lagi, kedatangan sosok perempuan yang menakutkan ke rumah indekosnya. Tapi, mengapa wajahnya begitu? Ini tidak masuk akal! Pikiran Arry seperti benang kusut.
Arry berencana menemui Raina untuk membicarakan permasalahan supranatural ini. Namun tak disangka, gadis berambut panjang itu menghindar ketika Arry menyapa di halaman kampus. Apalagi, dosennya sudah datang ke kelas. Terpaksa Arry mengikuti kuliah lebih dulu.
***
Sore hampir gelap, Arry masih betah di perpustakaan. Sampai senja menjelang, tugasnya baru tuntas. Beruntung, dosennya sedang mampir ke perpustakaan. Mahasiswa bandel itu bisa mengumpulkan tugas hari ini.
Ketika langit mulai gelap, lampu-lampu gedung belum sepenuhnya menyala, segelintir dosen dan mahasiswa yang tersisa pun hendak pulang. Arry berjalan santai keluar dari perpustakaan yang akan ditutup oleh petugasnya. Ruangan itu berada di lantai tiga. Ia dikejutkan oleh sosok Raina di depan teras perpustakaan.
“Raina? Lagi ngapain?” sapa Arry.
Perempuan berambut panjang menoleh perlahan. Persis seperti kejadian di rumah indekosnya—juga di lantai tiga. Wajah serupa Raina itu tampak menangis.
“Pergi atau mati?” Kata-kata yang sama, kembali terdengar.
“Raina! Apa maksudmu?” Arry hampir frustrasi mendengar ucapan itu lagi.
“Selamat tinggal, Arry!” Sosok mirip Raina itu menjatuhkan tubuhnya. Seolah dinding pembatas setinggi dada di lantai tiga itu tak berguna.
“TIDAK! RAINA!” Arry melongok ke bawah. Lalu dengan panik, ia berlari turun melewati anak tangga. “Raina!” panggilnya kencang, mengejutkan para mahasiswa di sekitarnya.
Sampai di halaman kampus, tidak ada tubuh yang terjatuh dari lantai tiga. Semua terjadi seperti bangun dari mimpi buruk. Tanpa bekas. Secara kebetulan, Raina lewat di belakang Arry. Raina yang nyata. Ia hendak kabur, tapi berhasil dihentikan oleh Arry.
“Raina, tunggu! Aku khawatir banget!” Seketika itu, Arry memeluk sang gadis. Pemandangan itu cukup membuat beberapa mahasiswa tercengang. Hanya saja, ini sudah petang dan sepi. Bila terjadi pada pagi atau siang hari—ketika ramai—tentu akan lebih heboh lagi.
“Lepas! Apa-apaan kamu, Arry?” Raina berontak.
“Raina, dengarkan! Aku mimpi buruk tentangmu. Bahkan, aku didatangi hantu yang persis denganmu. Barusan juga, hantu itu menjatuhkan diri dari lantai tiga. Aku takut! Lebih takut lagi, memikirkan keselamatan kamu,” ujar Arry panjang lebar. Dua tangannya menangkup pipi Raina.
“Nggak. Jangan pikirkan aku!” Raina menepis tangan Arry. “Pergilah! Menjauh dariku. Jangan dekati aku lagi!” Suaranya bergetar.
“Apa? Kenapa, Raina? Aku benar-benar bingung. Tolong, jelaskan padaku.”
“Kita nggak bisa lebih dekat lagi. Aku nggak bisa.” Raina mulai menitikkan air mata.
“Kenapa nggak bisa? Apa salahku? Maaf, kalau aku pernah menghindari kamu. Tapi sekarang, aku mau bersamamu.”
“Pergi. Atau, kamu akan mati!” tegas Raina terakhir kali, sebelum ia berlari menembus gerimis yang baru turun.
Arry terpaku di tempatnya berdiri. Ia hanya menatap kepergian Raina. Pertanyaan besar bergelayut dalam benaknya. Kalimat itu lagi. Pergi atau mati. Raina, gadis yang sangat misterius. Pasti ada sesuatu dalam dirinya. Arry berniat mencari tahu.
***
Takut. Tak dapat dimungkiri, rasa itu pasti ada dalam hati Arry. Tapi demi memuaskan rasa penasaran, ia ingin bertemu lagi dengan penampakan itu. Setahu Arry, hantu adalah arwah orang yang sudah meninggal. Lalu, bagaimana bisa wajah hantu mirip dengan orang yang masih hidup?
Hingga hampir tengah malam, Arry menunggu. Hantu perempuan berambut panjang itu belum tampak juga. Arry belum mengantuk dan tidak bisa terpejam sama sekali. Suasana malam semakin sunyi. Daripada galau memikirkan hal gaib, mahasiswa itu memutuskan untuk mengerjakan tugas. Biasanya, ia sering lupa melakukan kewajiban seorang mahasiswa.
Hampir satu jam Arry berkonsentrasi penuh dengan pena dan kertas-kertas tugasnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar.
Tok, tok, tok.
Arry menatap tajam pada pintu kamarnya.
“Siapa?” teriaknya. Di hati kecilnya berharap ada sahutan seseorang. Tapi, tidak ada jawaban. Jantung Arry berdetak kian cepat.
Perlahan Arry berdiri mendekati pintu. Lengannya terulur. Belum sampai menyentuh pegangan pintu, lampu di kamarnya padam. Ia terkejut setengah mati. Tangan meraba-raba mencari ponselnya yang memiliki fitur senter. Beberapa detik kemudian, ia berhasil menggenggam ponsel dan menyalakan senternya.
Saat itu di hadapan Arry—dengan penerangan minim dari senter ponsel—muncul sosok perempuan berambut panjang. Hantu mirip Raina yang ditunggu-tunggu. Hantu itu berdiri menunduk. Wajah dan seluruh kepalanya tertutup rambut kusut sepinggang. Mata Arry mengerjap-ngerjap, meyakinkan diri bahwa pandangannya benar.
“Si-siapa kamu?” tanya Arry gemetaran.
“Arry.” Suara dari balik helai rambut.
“Aku ingin tahu. Tolong, jawablah. Sebenarnya kamu siapa?” tanya Arry setengah memohon.
Sosok itu perlahan-lahan mendekat. Entah ia berjalan atau melayang. Arry berusaha memberanikan diri. Tapi, tetap saja tidak berani memperhatikan keseluruhan tubuh makhluk gaib di hadapannya. Seolah bayangan samar. Terus merapat sampai tepat di depan wajah Arry.
“Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu menjauhi Raina!” jawabnya dengan suara serak yang hampir menyayat telinga.
Bulu kuduk Arry meremang. Ia susah payah menelan air ludah. Mengumpulkan tekad dengan mengingat Raina yang ia kenal, sampai berani bicara lagi, “Kenapa? Lalu, bagaimana kalau aku ingin terus bersamanya?”
Hantu itu merintih. Kepalanya terangkat. Rambut panjang sedikit tersingkap hingga tampak raut wajahnya. Sangat mirip Raina dan terlihat begitu sedih.
“Boleh. Tapi, aku juga boleh kan meminta tolong?” Ia bertanya.
“Apa?”
“Balaskan dendamku padanya!”
“Dendam pada Raina?”
“Ya, pilih saja. Bunuh dia atau pergi? Atau, kamu mati!”
“A-aku nggak ngerti. Apa salah Raina padamu?”
Hantu itu mengikik. Arry semakin ciut nyali. Hantu di hadapannya seperti bayangan Raina. Tapi, tatapan mata itu berganti penuh kebencian.
“Raina sudah menyakitiku. Dia pantas mati, begitu pun kamu!” Mata hantu itu memelotot seolah ingin lepas. Bau anyir merebak dari mulutnya yang berdarah dan terbahak. Ia terus tertawa sambil menjulurkan jemari tangannya. Kuku-kuku tajam hendak mencekik leher orang di depannya.
“Ja-jangan ....” Napas Arry berkejaran dengan pacuan jantung. Ia tak sanggup lagi. Ponsel di genggamannya terlepas. Tubuhnya lemas dan ambruk. Terakhir kali, ia merapal doa-doa sebisanya, sampai tak sadarkan diri. Hantu perempuan itu tidak pergi. Justru, ia leluasa menguasai tubuh pemuda yang terkulai di lantai.
***
Perlahan, tubuh Arry bangun. Gerakannya kaku dan wajah pucat bak mayat hidup. Tatapan kosong dengan kantung mata teramat hitam, seolah kurang tidur selama beberapa hari. Ia memakai jaket bertudung kepala. Kemudian, ia keluar dari kamar tanpa suara. Sepi. Semua penghuni rumah indekos telah terlelap.
Arry menuju dapur. Ia mengambil pisau besar lalu menyembunyikan dalam jaketnya. Menembus malam, ia berjalan kaki menyusuri pinggir kota. Selama setengah jam menerobos kabut dan gerimis, rupanya Arry sampai di tujuan. Rumah indekos Raina.
Tok, tok, tok. Arry mengetuk pintu berkali-kali.
Raina tersentak. Ia bangun dengan gemetar. Bimbang, harus membuka pintu atau tidak. Raina mengintip dari lubang pintu. Mengetahui sosok pemuda di depan pintu kamar, akhirnya ia memutar kunci.
“Arry? Ngapain tengah malam ke sini?” Raina tercengang saat membuka pintu. Tepat saat itu, hujan turun semakin deras bersama kilatan guntur.
Tanpa menjawab, Arry langsung memasuki kamar dan mengunci pintunya. Adegan itu bergerak lambat tapi Raina sama sekali tidak mampu menghentikan. Ia kebingungan. Walau begitu, rasa takutnya pada hujan berkurang sebab Arry ada di sini. Tetap saja, Raina tak mengerti tujuan kedatangan temannya.
“Ada apa, Arry? Jawablah,” ucap Raina tidak sabar.
Arry masih membisu—hanya tersenyum ganjil pada Raina. Ia menatap penuh nafsu, seakan ingin melumatnya habis-habisan.
Beberapa saat kemudian, baru terdengar suara dari bibir Arry, “Apa kabar, Raina?”
Namun, itu bukan suara berat milik Arry. Raina mengenal suara perempuan itu. Walau lebih serak, ia tidak mungkin bisa lupa.
“Ka-kamu?” Raina mundur beberapa langkah. Ia ingin tak percaya tapi ini nyata.
“Iya. Kamu pasti ingat aku.” Arry—yang sedang kerasukan—tertawa nyaring.
“Tidak! Pergi kamu dari tubuhnya! Aku tidak terima,” bentak Raina.
“Munafik! Apakah aku tidak boleh membalasmu? Ingat, dulu kamu yang menyakiti aku!”
“Bukan begini caranya. Jangan libatkan Arry dalam urusan kita! Dia tidak bersalah.”
“Jahat! Kamu pernah menyakitiku dengan melibatkan seorang lelaki. Sekarang giliranku.”
“Cukup! Keluar dari tubuhnya!”
“Tidak akan!” Tangan Arry mengeluarkan pisau dapur dari balik jaketnya.
Raina berlutut lemah dan menitikkan air mata. Benarkah ia harus mati di tangan Arry?
“Kumohon, jangan! Aku menyayangi Arry.”
“Bohong!” Arry semakin tinggi mengacungkan pisaunya. Mata memerah penuh amarah.
“Sadarlah, Arry! Jangan biarkan makhluk itu menguasaimu. Ini aku. Raina!”
“Tidak ...!” Pisau terjatuh ke lantai, begitu juga tubuh Arry. Ia tak sadarkan diri.
“Arry, bangun!” Raina menghampiri tubuh pemuda itu.
Arwah perempuan telah keluar.
Ketika Arry membuka mata, tampak olehnya hantu di samping Raina. Mereka memang bagaikan pinang dibelah dua.
“Raina, i-itu—“
“Ya. Dia kembaranku.”
Raina dan Arry menatap ke arah yang sama. Sosok hantu perempuan berambut panjang. Ia berdiam di sudut kamar.
“A-apa tujuannya datang ke sini? Dia juga selalu menggangguku!” Arry panik.
“Kamu ingin tahu? Ya, kamu harus tahu sebelum mati!” Arwah itu melayang—mendekat.
“Jangan! Pergi kamu! Jangan ganggu kami!” teriak Raina. Tapi, itu tidak berguna. Sang arwah kembali memasuki raga Arry—lelaki yang mulai ia sayangi.
***
Dua gadis belia berseragam—atasan putih dan rok biru—Raina dan Rainy. Anak kembar yang populer. Selain karena cantik, juga berprestasi. Para murid laki-laki selalu menggoda. Namun, hanya satu lelaki yang menarik perhatian keduanya. Tedy, teman sekelas mereka.
Setiap hari, Raina dan Rainy bergantian mengobrol dengan Tedy. Murid lelaki itu atlet basket keren, juga terkenal. Sejak kelas 7, mereka mulai akrab. Pada kelas 8, mereka bertiga semakin bersahabat karib. Dua saudara kembar saling bertukar cerita, betapa senang bisa dekat dengan Tedy. Namun, mereka belum menyadari api yang tersimpan dalam dada. Suatu saat, mereka bisa habis terbakar. Tanpa sisa.
Suatu hari seusai Ujian Nasional, para siswa kelas 9 SMP berangkat rekreasi ke sebuah hotel di kawasan dataran tinggi. Raina dan Rainy mengikuti dengan semangat. Seperti biasa, mereka bersenda gurau dengan Tedy. Saat menaiki bus pariwisata, mereka berbagi makanan dan minuman secara adil. Bulan lalu, ketika ulang tahun kelima belas si anak kembar itu—begitu juga tahun-tahun lalu—Tedy pun memberikan kado yang sama nilainya. Karena itulah, si kembar menjadi bingung.
Namun, dua bersaudara telah menyusun rencana. Tanpa saling mengetahui, mereka masing-masing berniat menyatakan perasaan pada Tedy. Walau sebenarnya Raina takut akan ditolak, ia nekat saja. Rainy juga sebetulnya malu tapi berusaha demi seseorang spesial di hati.
Sore hari, rombongan siswa SMP sampai di hotel. Guru membagi kamar-kamar untuk ratusan siswa. Mereka dapat beristirahat, setelah mendapat jatah kamar. Raina dan Rainy menempati sebuah kamar. Mereka meletakkan isi tas ransel ke dalam lemari, yaitu pakaian dan peralatan mandi.
“Kak Raina, mau mandi dulu?” tawaran Rainy.
“Nggak. Kamu duluan aja.”
“Oke.” Rainy pun masuk ke kamar mandi.
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Raina. Walau hari beranjak gelap dan belum mandi, ia bertekad mendahului sang adik. Raina ingin mempunyai pacar sebelum adiknya. Ia harus merebut Tedy. Jangan sampai Rainy yang mendapatkan cowok itu.
Tok, tok, tok. Raina mengetuk pintu kamar hotel yang ditempati oleh Tedy.
“Ada apa Raina?” tanya Tedy saat melihat wajah di hadapannya.
Tidak hanya teman-teman akrab, semua orang yang cukup lama mengenal saudara kembar itu pasti bisa membedakannya. Walau sama persis, bukan berarti si kembar identik tidak memiliki perbedaan. Raina bertubuh lebih pendek dan suaranya lembut. Sedangkan Rainy bertubuh lebih tinggi serta bersuara agak serak.
“Aku mau ngomong. Ikut, yuk.”
Raina mengajak Tedy turun dari lantai tiga. Mereka menuju ke taman samping hotel. Di sebelah kiri taman, ada ruangan aula untuk acara pentas seni nanti malam. Sedangkan di sebelah kanan taman, terdapat kolam renang yang kosong tanpa air. Kolam itu selesai dibersihkan. Besok, barulah kolam diisi air untuk kegiatan berenang para siswa.
“Di sini aja, Raina. Mau ngomong apa?” Tedy, lelaki jangkung dan berkulit cerah itu penasaran. Taman itu cukup sepi. Mungkin karena para siswa masih banyak yang mandi dan sebagian sibuk mempersiapkan panggung di aula.
“Kita kan mau perpisahan. Kamu bisa aja beda SMA denganku. Sebelum kita berpisah, bolehkah aku tanya sesuatu?”
“Boleh, Raina. Tanya apa?”
“Sebenarnya, siapa yang kamu sukai? Aku atau Rainy?”
Tedy gugup. Ia terdiam beberapa saat.
“Aku suka sama kalian berdua, sebagai teman. Kalian berdua asyik.”
Raina menggeleng. “Bukan teman. Sebagai pacar, siapa yang kamu pilih?”
“A-aku nggak bisa jawab sekarang. Aku nggak tahu.”
“Walaupun kamu belum mau pacaran, tapi aku ingin tahu. Siapa sebenarnya yang ada di hatimu? Aku atau Rainy? Karena aku suka sama kamu, Tedy.”
Raina memandangi mata teman lelakinya. Ia sangat berharap, nama Raina yang ada di hatinya. Bukan Rainy.
Tedy menelan ludah. Ia tetap pada pendirian. “Aku belum bisa jawab.”
“Waktu kita tinggal sedikit lagi. Setelah wisuda dan terima ijazah nanti, kita akan sibuk mendaftar ke SMA. Kumohon, jawablah sekarang.”
“Maafkan aku. Ehm, gini aja. Mungkin nanti malam, kamu akan tahu jawabanku. Tapi, tolong. Apa pun jawabanku, jangan marah ya?” Tedy menggenggam tangan Raina.
“Hmmm. Oke. Aku nggak akan marah.”
“Janji?”
“Iya, janji.” Raina ikut menggengam tangan Tedy. Mereka pun tersenyum berpandangan. Tedy berharap Raina bisa menerima pilihannya.
Pemandangan—dua orang berpegangan tangan di taman—itu tertangkap oleh mata Rainy. Seusai mandi dan tidak menemukan Raina, ia pun mencari-cari sang kakak. Ternyata, sepasang matanya melihat kejadian luar biasa. Dengan menyimpulkan sendiri, ia tahu bahwa Raina sedang menyatakan perasaan pada Tedy. Cowok itu pun menanggapi dengan mesra.
Entah benar atau tidak, tapi itulah yang tampak di mata. Bara api di dada Rainy berkobar-kobar. Ia bersembunyi sambil terus mengawasi Raina dan Tedy. Mereka naik ke lantai tiga, hendak kembali ke kamar masing-masing.
Rainy memanggil dari belakang, “Kak Raina! Tedy!”
Raina terkejut. Tedy langsung melepas genggaman tangannya. Sejak tadi, mereka berjalan sembari bergandengan tangan. Walau hal itu cukup sering Tedy lakukan dengan Raina-Rainy, mereka baik-baik saja. Mereka beranggapan sekadar sahabat. Namun, sekarang kondisinya berbeda.
“Apa yang kalian lakukan?” tanya Rainy dingin.
“Ehm, kami cuma ngobrol sebentar,” jawab Tedy gugup.
“Ngobrol apa, Kak Raina? Tentang perasaan kamu?”
Raina menenangkan diri dan menjawab, “Iya. Aku ingin Tedy mengerti tentang perasaanku.”
“Kalau gitu, aku juga ingin Tedy mengerti perasaanku. Nggak cuma Kak Raina. Aku juga suka sama kamu, Tedy.”
Rainy begitu lancar mengucapkannya. Tak ada lagi rasa malu. Ia pun memiliki kepekaan tajam seperti ikatan batin dengan saudara kembarnya. Meskipun tidak mendengar langsung, ia yakin Raina sudah berkata hal yang sama.
Kini, Tedy yang paling kebingungan. Ia menggaruk-garuk kepala.
“Oke. Jawaban ada di kamu, Tedy. Kamu harus menentukan pilihan!” ucap Raina.
Dua saudara kembar itu tidak lagi bekerja sama. Mereka justru saling melawan demi mendapatkan hati lelaki yang sama, Tedy.
“Raina, Rainy, dengarkan aku. Nanti, aku akan ngomong saat pensi. Aku akan baca puisi sekaligus nembak salah satu dari kalian.” Akhirnya, Tedy membocorkan rencana besarnya.
“Terlalu lama. Mendingan, kamu bilang sekarang aja.” Raina tidak sabar.
“Ya. Lagipula, malu kan dilihat banyak orang. Teman-teman dan guru, semuanya ngelihat. Pasti malu dong kalau ditolak.”
“Astaga.” Tedy menghela napas.
“Ayo, katakan. Raina atau Rainy?” tanya Raina.
“Raina atau Rainy?” Rainy mengulangi pertanyaan yang sama.
“Aku nggak bisa jawab.” Tedy menyerah.
“Aku akan membantu. Kulihat, kalian mesra banget tadi. Pasti kamu pilih Kak Raina kan, Tedy?”
Tedy membisu.
“Udah jelas. Selamat tinggal. Semoga kalian bahagia.”
Itulah kalimat terakhir Rainy sebelum terjun. Ia menjatuhkan diri dari lantai tiga. Tubuhnya meluncur tepat ke kolam renang tanpa air. Kepala berambut panjang terbentur keras ke dinding keramik. Darah mengalir.
“RAINY!” pekik Raina.
“RAINY, TIDAK!” Tedy melongok ke bawah dinding pembatas.
***
Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik. Entah mengapa Rainy berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ia terlalu gegabah menyimpulkan perasaan Tedy.
“Rainy ...!” Mata Raina memerah dengan kucuran air begitu deras. Ia berlutut, menyesal. Tubuhnya lemah dan gemetar.
Bersamaan dengan meluncurnya tubuh Rainy, hujan mengguyur deras. Darah semakin menggenang tersapu hujan di dasar kolam renang. Para penghuni hotel berhamburan ke teras. Guru-guru dibantu petugas hotel mengevakuasi jasad Rainy yang tewas seketika. Para siswa histeris menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Suara jeritan mereka beradu dengan guntur menggelegar.
Mayat Rainy digotong ke dalam lobi. Pihak hotel menelepon mobil jenazah dari rumah sakit terdekat. Raina tidak kuat menahan shock. Ia pingsan lalu direbahkan di kamar dengan bantuan teman-teman dan guru. Sedangkan Tedy menangis tersedu-sedu. Ia berlari turun ke lantai bawah—lobi tempat Rainy dimasukkan ke kantong jenazah.
“Rainy, kamu yang kupilih. Kamu yang kuinginkan,” ujar Tedy tertahan. Air mata tumpah bersama tubuhnya yang ambruk ke lantai.
Rainy dimasukkan ke mobil jenazah, meninggalkan Tedy. Pergi untuk selama-lamanya.
***
Raina mengurung diri di kamar hingga seminggu lamanya. Ijazah SMP diantarkan oleh sang kepala sekolah ke rumahnya. Beliau berpesan agar Raina semangat untuk sekolah lagi. Ia harus melanjutkan pendidikan ke SMA. Raina pun menjadi murid SMA dengan kesedihan yang terus melingkupi. Sifatnya berubah jadi pendiam, pemurung, dan penyendiri. Tiada lagi keceriaan.
Peristiwa menyedihkan bertubi-tubi terjadi. Pada pertengahan masa SMA, Raina mendengar kabar dari teman SMP-nya yang satu sekolah dengan Tedy. Lelaki itu pindah ke luar kota. Ia menjadi siswa SMA yang nakal. Hobinya mengikuti balap liar.
Awalnya, Tedy juga sangat terpukul atas kematian Rainy, perempuan yang ia sukai. Namun, ia mengambil jalan yang salah untuk menghapus kesedihan. Rokok, mabuk, geng motor, kemudian balapan liar pun ia ikuti. Tedy sengaja tidak pernah pacaran. Sampai seorang teman perempuan di SMA berhasil menggodanya. Tedy bersedia memulai hubungan dengan orang baru.
Suatu malam, Tedy mengantarkan pacarnya pulang. Di tengah hujan deras, ia memacu sepeda motornya dengan kecepatan penuh. Gadis di boncengannya memeluk erat. Tiba-tiba saat jalan sepi, Tedy melihat sekelebat bayangan menyeberang. Rambut panjang dan wajahnya tidak asing lagi.
“Rainy!” bisik Tedy kehilangan konsentrasi. Ia tidak waspada. Truk besar melaju dari arah berlawanan. Tabrakan tidak dapat dihindarkan.
“Tedy meninggal karena kecelakaan,” ucap seorang teman Raina melalui sambungan telepon.
Itulah masa SMA yang amat menyedihkan bagi Raina. Lengkap sudah penderitaan. Ia semakin depresi. Terlarut dalam penyakit Ombrophobia.
***
Selama SMA, Raina memang tidak pernah berpacaran. Ia terkurung oleh fobia hujan hingga hubungan sosialnya terganggu. Sampai Arry hadir dalam hidupnya. Mahasiswa di universitas yang sama. Lelaki itu sudah melihat semua, kejadian lima tahun lalu sampai saat ini.
Ruh Arry diajak secara gaib oleh ruh Rainy. Menjelajah waktu ketika Raina dan Rainy masih bahagia, hingga tragedi menghancurkan dua saudara kembar itu. Hidup Raina bergantung pada obat anticemas karena fobia hujan. Sedangkan Rainy telah mati akibat cemburu buta membuatnya bunuh diri.
Kini, Raina mulai menaruh hati pada Arry. Namun, ruh Rainy yang belum tenang selalu menghantui. Terutama Arry, yang harus menanggung masalah ini.
***
Mata Arry terbuka. Ia melihat Raina dan Rainy di kamar indekos itu. Mereka berdua sama-sama menangis. Benar-benar kejadian yang sangat ganjil. Saudara kembar menangis bersama, seorang manusia dan satunya lagi berwujud hantu.
Apa salah Arry hingga harus mengalami peristiwa ini? Ia pun memutar otak. Apa tindakan yang harus ia ambil? Ia berdoa beberapa saat, hingga menemukan ide yang tepat.
“Rainy, Raina, aku memutuskan untuk pergi. Aku nggak mau semakin memperburuk keadaan kalian berdua. Aku janji, nggak akan bertemu Raina lagi. Aku akan pergi dari hidup kalian,” ucap Arry berpamitan.
Raina menggeleng tapi tak mampu bicara. Ia berusaha keras meyakinkan hatinya sendiri. Terpaksa ia harus merelakan Arry pergi. Ia tidak mau Arry terluka karena Rainy. Apalagi, kalau nasibnya sampai seperti Tedy. Mungkin nanti Raina pun akan bunuh diri.
“Kamu janji?” tanya Rainy.
“Janji.” Arry mengangguk mantap.
“Pergilah. Aku pun akan pergi,” bisik arwah itu.
“Baik. Selamat tinggal.” Arry berlari keluar dari kamar indekos Raina. Sepanjang jalan, ia mengusap air mata. Betapa perih hatinya, terpaksa pergi menjauhi gadis yang ia sayangi.
***
Raina dan Arry melakukan hal yang sama—berhenti kuliah di universitas kota itu. Mereka pulang ke kampung halaman hingga memperoleh pekerjaan di kota lain. Lulus kuliah, Arry bekerja di sebuah kantor finance. Siapa yang menyangka, takdir membawanya berjumpa masa lalu. Satu tahun lamanya bekerja, ia bertemu seseorang.
Suatu malam, hujan deras mengguyur kompleks perkantoran tempatnya bekerja lembur. Arry hendak pulang, tepat saat listrik padam. Di teras kantor notaris—sebelah kantornya, terlihat sosok perempuan berambut panjang. Ia mengira ada karyawan yang lembur juga sepertinya.
Arry menghampiri perempuan berambut panjang itu. Rambutnya menutupi punggung yang memakai kemeja putih. Roknya berwarna hitam seolah tak tampak di kegelapan. Posisinya yang membelakangi membuat penasaran. Arry mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu perempuan itu. Ia menoleh.
“Raina?”
“Arry? Kamu karyawan di sini?” tanya perempuan yang ternyata telah dikenal oleh Arry.
“Ya, di kantor sebelah itu. Udah setahun. Kalau kamu, kerja di sini?”
Raina mengangguk. “Ini hari pertamaku. Tapi, baru sehari magang udah disuruh lembur. Gila.”
Arry tercenung. Tidak menyangka bertemu dengan perempuan ini. Seseorang yang menjadi bagian masa lalunya. Ia berharap tidak pernah berjumpa lagi. Bahkan, Raina pun menyepakati hal yang sama.
Suara guntur memecah kesunyian antara dua orang—Arry dan Raina. Hujan masih mengguyur bumi. Kenangan berkelebat, membuat Arry teringat pertemuan pertamanya dengan Raina. Kejadian ini seolah deja vu yang terulang. Tapi, ada perbedaan yang ganjil. Raina tidak seperti dulu. Ia terlihat tenang saat hujan.
“Kamu nggak apa-apa, Raina?”
“Kenapa?”
“Maaf, maksudku tentang fobia itu.”
Raina menggeleng sambil tersenyum. “Tenang aja, Arry. Aku udah sembuh.”
Arry menatap mata Raina yang berkilat memantulkan cahaya halilintar di angkasa. Raina sudah sembuh. Tapi, masih tersimpan sesuatu.
Seperti terhipnotis, Arry terus memperhatikan rambut lurus Raina. Rambut hitam sepinggang yang tertiup angin. Dari balik helai-helai rambut yang berkibar, di antara kegelapan dan hujan, sosok itu muncul lagi.
Di belakang Raina, bayangan perempuan itu masih ada. Rainy!
“Di-dia!” Arry terbelalak.
“Nggak apa-apa, Arry. Dia akan selalu bersamaku. Semoga nanti kamu terbiasa.” Raina tersenyum manis.
END


 RiskiDiannita
RiskiDiannita