Ada semacam peraturan tak tertulis di kalangan siswa Wadit bahwa mereka yang datang ke sekolah diantar-jemput itu kurang oke. Padahal, dulunya Wadit terkenal karena keborjuannya. Entah sejak kapan semua itu berubah—mungkin sejak sepuluh tahun yang lalu, sebagaimana hal-hal penting lain dalam sejarah Wadit.
Oleh sebab itu, Senin pagi Dio tiba di sekolah dengan tampang kusut yang lebih masai daripada bahan parasut.
Ken sampai menoleh dua kali ketika melihat sosok tiang listrik itu turun dari boncengan.
Hah, Dio dianter naik motor? Sama cewek pula? Ken sampai mematung di gerbang, tidak sanggup mencerna pemandangan di depannya.
Tiba-tiba, si pengendara motor melambai kepada Ken.
“Hei! Ken!”
Helmnya diangkat, menampilkan wajah super cantik dengan rambut merah panjang yang melambai lembut tertiup angin sepoi. Ken seketika mengenalinya.
“Kak Artemis!!” seru Ken, menyongsong mereka. “Kakak kapan pulang?”
“Sabtu pagi. Mami-Papi juga lagi di sini.”
Ken mendelik kepada Dio. “Katanya cuman Tante Dita yang pulang?”
Artemis tertawa lepas. “Iya, aku sengaja nggak ngasih tau dia. Kalo dia tau, pasti dia nggak sudi ngejemput di bandara!”
Ken ikut tertawa, membayangkan betapa syoknya Dio ketika melihat kakaknya muncul. Padahal, serius deh, apa sih yang menyebalkan dari Artemis? Cantik, keren, pintar, jago silat pula. Ken sih pasti bangga punya kakak seperti dia.
“Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kamu masih aja satu sekolah sama Dio. Nggak bosen?”
“Bosen, Kak. Tapi mau gimana lagi?”
“Kamu mestinya protes ama sekolah. Kalo anak-anak bosen sama Dio, ntar mereka nggak konsen belajar.”
“Gue wabah?!” gerutu Dio bete.
“Emang udah jodoh kali ya? Haha...” lanjut Artemis, kelihatan menikmati membuli-buli Dio. Ken tidak bisa menyembunyikan cengiran puasnya. Memang asik banget melihat orang yang selalu menyayat-nyayat hati orang lain kena batunya, dibuli-buli tanpa bisa melawan.
“Gaia di sini juga?” tanya Ken.
Artemis mengangguk. “Yep. Di sono musim liburan tanggal segini. Dan mumpung pada kemari, aku ikutan cuti. Oiya, katanya kemaren anak ini dihajar preman ya?” Artemis menuding ke arah Dio dengan satu jempol.
Ken menegang. Apakah Artemis akan memarahinya karena tidak berhasil melindungi Dio?
Tangan Artemis tiba-tiba meraih sisi wajah Ken, meneliti guratan yang sudah menipis di pelipisnya. “Kamu juga kena ya? Pasti gara-gara ngelindungin dia? Padahal dia mah biarin aja, salah sendiri payah.”
“Lo tega kalo gue habis dipukulin?” kata Dio dengan nada jengkel.
“Mana yang lebih baik: habis dipukulin karena melindungi, atau dilindungi cewek?” tantang Artemis.
“Mending nggak dipukulin sama sekali,” tandas Dio. “Lagian gue nggak keberatan diselamatin cewek, gue nggak sexist kayak lo.”
Artemis mendecakkan lidah keras. “Ck… adikku kok letoy gini, bikin malu aja...”
“Bisa kenyang pake harga diri? Udah ah, ngapain sih lo nongkrongin gerbang sekolah? Kayak tante seneng aja.”
BLETAKKK!!!
Ken meringis, ikut merasakan sakit yang diderita Dio. Suara jitakannya kenceng banget!
“Ken,” Artemis melanjutkan dengan santai, seolah-olah tidak baru saja melakukan kekerasan domestik, “kapan-kapan lunch bareng yuk? Nanti bilang-bilang ajalah sama anak ini, gimana teknisnya,” kata Artemis, menepuk punggung Dio.
“Kenapa gue?” protes Dio.
“Trus siapa dong?”
“Kenapa kalian nggak tukeran nomer aja?”
“Hapeku belom bisa jalan di sini, tau kan?”
“Punya hape kok nggak guna.”
“Iya, kayak kamu.”
Dio spontan terdiam, mangkel. Ken tertawa keras.
“Nah, aku pulang dulu. Kalian masuk sana. Ciao.”
Ken melambai sampai Artemis dan motornya menghilang di tikungan. Dio melipat lengan.
“Lo beneran mau makan bareng dia?” selidiknya, penuh tanya.
“Nggak tau juga sih,” Ken mengangkat bahu. “Kamu ikut, kan?”
“Nggak lah!”
“Kenapa?”
“Kan kalian berdua yang mau ngobrol?”
Mata Ken melebar. “Yaaaah, jangan gitu dong, Di. Aku segen kalo cuma berdua sama Kak Artemis.”
“Ya itu masalah lo!”
Nadia dan Rena tiba-tiba muncul.
“Siapa yang tadi itu?” tanya Rena sambil menjulurkan leher.
“Kakak gue,” gerutu Dio. “Kenapa?”
“Cantik,” Rena berkomentar, terdengar lega.
“Siapa dulu adiknya.”
Ken menyodok pinggang Dio. Karena ini masalah prinsip.
~ ~ ~
Persiapan pameran Wadit memasuki tahap “Sosialisasi Perencanaan Mandiri”, alias masing-masing kelas dan ekskul mulai menggodok rencana yang sesuai dengan blueprint dari OSIS, kemudian diharapkan melaporkan hasil diskusi mereka paling lambat tanggal 31 Agustus.
Rasanya atmosfer sekolah jadi berbeda. Jam pelajaran dipotong dari 45 menit menjadi 40 menit, sehingga dari sembilan jam pelajaran perhari, mereka punya waktu 45 menit untuk mengerjakan pameran setelah semua pelajaran selesai.
Bagi anak-anak yang kurang suka belajar, waktu 45 menit ini sangat menyenangkan, karena terasa seperti jam kosong. Sementara itu, bagi yang kurang suka belajar dan kurang suka bersosialisasi seperti penghuni bangku pojok di kelas 2H, waktu 45 menit di penghujung hari terasa jadi bagaikan neraka.
Yang paling asik adalah jadi anak OSIS. Ken tidak tinggal di kelas dan ikut butek membicarakan apa yang akan dilakukan kelas mereka, melainkan keliling-keliling sekolah membawa-bawa clipboard, denah kampus, dan tablet inventaris OSIS, menampung pertanyaan dan pemintaan serta mengonfirmasi informasi.
Ketika melewati kelas 2H, Ken menyempatkan diri melambai kepada Dio sambil nyengir lebar, mendapat suatu kebahagiaan tersendiri melihat cowok itu menderita di pojokan, sementara dia bisa bebas berkeliaran.
Dio bangkit berdiri, menimbulkan bunyi derit ketika kursinya bergeser.
Aditya, yang sedang mencatat di papan tulis, menoleh kepadanya sambil mengangkat sebelah alis.
“Toilet,” gerutu Dio. Tanpa menunggu izin, dia langsung keluar mengejar Ken.
“Kamu ngapain keluar segala? Emang beneran mau ke toilet?” labrak Ken langsung.
“Gue mau ikut lo.”
“Ken,” kata Kartika, yang berpatroli bersamanya dan Nindya, anggota tim sarpras. “Kita duluan ya.”
“Ehhh—“ Ken ingin menahan mereka, tapi dua anak itu buru-buru ngacir.
“Mereka takut gue ya?”
Ken jadi mendelik pada Dio, yang mengangkat tangan. “Ngapain ikut-ikut?” hardiknya.
“Bosen di kelas.”
“Kamu mestinya bantuin temen-temen mikir, tau!”
“Biarin lah. Masih banyak orang lagi di sana, apa bedanya cuma ilang satu kepala?”
“Kalo kamu kenapa?” Ken bicara ke balik punggung Dio.
Dio berbalik dengan kaget. Di belakangnya, Nadia melirik ke kiri dan ke kanan, kelihatan seperti maling ketangkap.
“S-soalnya… um… D-dio juga keluar...”
“Lo mau ikut gue ke WC?” selidik Dio, setengah bercanda. Tapi wajah Nadia langsung memerah, bibirnya membuka lalu menutup tanpa mengeluarkan suara.
“Jangan ngobrolin WC sama cewek, nggak sopan tau!”
“Lah elo juga nyebut-nyebut WC!”
“Sst, jangan ribut! Entar ngeganggu yang pada lagi rapat!”
Kelas-kelas di sekitar mereka sedang berisik bukan kepalang membicarakan hal-hal seru apa yang ingin mereka lakukan di pameran. Keributan paling parah datang dari arah kelas 2E, yang sepertinya sedang mengadakan pertunjukan konser. Kalau sebentar lagi tidak ada guru yang datang untuk menegur mereka, berarti standar sekolah ini sudah super ngedrop.
“Kuping lo di pantat ya—aduh!” Karena Ken menyodokkan gulungan kertas tebal kepadanya.
“Acara pameran ini penting banget tau. Reputasi dan gengsi sekolah kita dipertaruhkan. Selain itu, nama baik ketua OSIS kita juga. Jadi kalian balik lagi ke kelas sana, coba berkontribusi gitu.”
Nadia sudah akan mengangguk dan menurut, tapi Dio dengan keras kepala tidak mau menyingkir.
“Nggak ah, bosen di sana. Mending ngintilin lo. Gue pegel kebanyakan duduk,” katanya.
“Shuttle run aja kalo gitu.”
“Ih, diam-diam lo ternyata pengikut Bos juga!” seru Dio.
“Enak aja, ora sudi!”
Dio berbisik kepada Nadia, “Kenapa tiba-tiba bahasa Jawa?”
Ken mengeluh, mulai berjalan lagi. Dalam hati kesal juga Kartika dan Nindya meninggalkannya. Kalau ada yang nanya aneh-aneh, kan kacau kalau dia nggak bisa jawab. “Yaudah terserah, tapi jangan ngerecokin aku!”
Dio tidak kelihatan mendengarnya sementara dia menyejajarkan langkah, tangannya digenggam dengan santai di belakang punggungnya. Lehernya terjulur sementara kepalanya melongok kepo ke dalam kelas-kelas yang mereka lewati. Nadia berjalan di sebelah Ken, kelihatan sama penasarannya.
Mendekati tangga, tiba-tiba Do berhenti.
“Eh, eh, liat tuh. Ngapain sepupu lo ngomong di depan?”
Ken mengikuti arah yang ditunjuk Dio.
Mereka berdiri di depan pintu kelas 2B: di dalamnya situasi benar-benar bertolak belakang dengan kelas 2E. Anak-anak sedang duduk diam mendengarkan penjelasan dari ketua kelas mereka: seorang cewek dengan rambut bob pendek dan kacamata oval. Ken tidak ingat namanya. Di sebelah si kacamata, ada Rena.
“Dan dia berdiri di depan aja, padahal murid baru,” komentar Ken dengan suara rendah.
“Rena rame sih orangnya,” kata Nando.
“Anjong!” umpat Dio keras, membuat orang-orang di dalam kelas menoleh kepadanya. Ken langsung menyikutnya.
“Sori, nggak maksud ngagetin kalian,” kata Nando, nyengir lebar. “Ken, tadi kok Tika sama Nindya lari buru-buru gitu?”
“Dimana-mana juga orang lari karena buru-buru,” gerutu Dio.
Nando menatap Dio dengan pandangan aneh. Tatapan itu bertahan selama dua detik.
“Nando!” si kacamata oval memanggil.
“Hei, Res,” sapa Nando sambil melangkah masuk ke dalam ruang kelas. “Kenapa?”
“Kelas kita kan mau bikin workshop tanah liat. Menurut kamu sebaiknya kita bikin tungku juga, atau hasil bikinan pengunjung nanti kita kirim ke pengrajin keramik aja?”
“Ngebakar keramik itu bukannya bisa berhari-hari ya?” kata Nando.
Si ketua kelas mengerutkan kening. “Iya juga ya. Tapi berarti kita harus masukin perhitungan ongkos kirim...”
“Papaku punya koneksi ke pengrajin keramik,” timbrung Rena. “Mungkin nanti aku bisa tanya-tanya soal harga dan macem-macemnya.”
“Hei, kayaknya kita belum kenalan,” Nando tiba-tiba mengganti topik.
Kenalan tuh segampang itu ya? pikir Ken takjub. Satu hal yang didapatnya dari meninggalkan dunia perpremanan adalah jadi orang baik itu tidak serta-merta jadi punya banyak teman. Dia masih sering heran bagaimana orang yang judes, membosankan, dan bermuka ngantuk seperti Dio bisa populer.
“Kalo gitu gimana kalo kita main ke tempat pengrajinnya terus belajar dulu di sana?” seseorang mengusulkan.
“Kayaknya asik tuh!”
“Boleh, boleh!”
“Kayak studi tur ya?” Komentar yang ini disambut sorakan meriah. Karena, pihak sekolah bersedia memberi dana dan izin jor-joran untuk pameran, tapi mereka tidak mau mengadakan studi tur. Dalihnya, pameran berdampak ke masyarakat, sementara studi tur hanya bermanfaat untuk para warga sekolah saja. Kalau kata Dio sih, sekolah cuma butuh pencitraan.
“Tapi ongkos kalian tanggung sendiri ya,” kata Nando.
“Looh, kok nggak ditanggung anggaran?”
“Budget kita terbatas tau!”
“Ah, OSIS pelit nih!”
“Iya, pelit nih!”
“Kalian coba ngedanus sendiri sana!” hardik Nando, tapi terdengar setengah bercanda.
“Tapi kita boleh buat proposal pengajuan studi tur kan?” kata Rena sambil tersenyum lebar.
Nando balas tersenyum. “Tapi belom tentu di-acc ya.”
“Tenang aja, kita bisa bikin proposal yang bagus ok.”
“OSIS juga kompeten menilai proposal kok.”
Baru kenalan, sekarang sudah negosiasi bisnis? Ken semakin takjub.
Begitu sudah keluar dari kelas 2B, Nando tiba-tiba berkata antusias, “Rena cantik banget ya...”
“Genit orangnya,” timpal Dio.
Nando memandang Dio lagi. Dengan sorot seperti tadi. Kali ini ditambah kernyitan tipis. Dio balas memandangnya, posenya pongah, seperti ngajak berantem. Dengan badan yang jauh lebih tinggi, Dio jadi kelihatan sangat menekan.
“Kalian!” suara Rena membuat Nando memutus kontak mata dengan penuh kelegaan. “Aku ikut dong!”
“Gue nggak nyangka ternyata lo demen deketan sama Ken,” sahut Dio, setengah berharap Rena langsung menyanggah dan mengurungkan niatnya tanpa banyak ribut.
“Hah,” Rena melepeh, “ora sudi!”
Nando berbisik kepada Ken, “Kenapa tiba-tiba Jawa?”
“Terus kenapa mau ngikut-ngikut?” tuntut Dio.
“Aku nggak mau kalian punya kesempatan ngomongin aku kalau aku bisa cegah.”
“Kalian suka ngomongin orang di belakang ya?” bisik Nando lagi.
“Enak aja!”
Terdengar langkah berat dari arah tangga, mendekati mereka. Sosok besar berbatik Cirebon muncul dengan gulungan kertas berukuran besar yang dipukul-pukulkan ke telapak tangannya, seolah-olah itu bat bisbol.
“Ken Ratu! Dionysus! Sedang apa kalian?!!” suara keras membuat mereka semua terlonjak. Bahkan di tengah keributan, suara Bos menggema di seluruh koridor, terdengar lebih seram daripada polisi yang mau menangkap teroris.
Bos berjalan ke arah mereka dengan langkah gagah, seperti mau menghajar orang. Di tangannya ada gulungan kertas yang mirip dengan yang dipegang Ken.
“Kenapa kalian tidak di kelas?”
“Mau ke toilet Pak,” jawab Dio spontan.
“Masa kalian ke toilet berempat?! Dionysus, awas ya kalau kamu berbuat tidak senonoh!”
“Kagak ada, Pak! Buset, nggak elit banget!”
“Kamu berani bilang cucunya Brahmadibrata nggak elit?!”
“Ah, terserah Bapak deh,” kata Dio gusar.
“Memang terserah saya!” sambar Bos dengan nada pongah. “Kamu, ngapain senyam-senyum?” Bos ganti menegur Ken, yang tidak bisa menahan cengiran gelinya.
“Nggak apa-apa, Pak.” Ken menggigit bagian dalam pipinya dalam usaha menampilkan poker face. Namun, efek yang timbul malah boker face. Bos terlihat tidak terkesan.
Setelah memberi mereka masing-masing pelototan galak penuh ancaman shuttle run, beliau berjalan menuju kelas 2E. Begitu sampai di sana, dia memukul pintu dengan gulungan kertasnya dan berteriak, secara efektif membuat tidak hanya kelas 2E, tapi juga anak-anak di kelas lain terdiam.
“Napa sih tu orang? Kurang makan yodium ya?” kata Dio.
“Kalsium kali?” usul Rena.
“Nando kemana?” Ken celingukan.
“Kabur kayaknya, begitu tau Bos dateng,” kata Dio. “Udahlah buruan, sebelum si Bos beres ngomel di sana dan balik ngomelin kita.”


 drei
drei





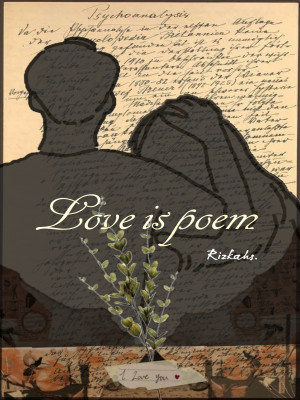




95 banding lima, auto sakit perut ketawa cekikikan. Tenyata kalau di perhatiin tokoh Ken, karakternya hampir mirip dengan, tokoh Tio di ceritaku.
Comment on chapter Satu