Dio bersumpah tidak akan mendatangi rumah Nadia lagi kalau harus dengan angkutan umum.
Dari rumahnya, mereka harus naik bus sekali disambung angkot satu kali. Nggak taunya, si angkot yang mereka tumpangi cuma lewat depan Perumwas. Dari situ mereka harus jalan nembus komplek sejauh dua kilometer sampai akhirnya nemu tembok luar ‘istana’ yang dituju. Sebenarnya bisa sih naik angkot lagi dua kali supaya bisa sampai pas di tujuan, memutari bagian luar komplek, tapi gara-gara supir angkot yang mereka tumpangi bilang, “Jalan aja dikit lagi Neng, lewat dalem komplek aja biar cepet!” akhirnya Ken memutuskan jalan kaki. Nggak taunya jauh kan.
Baru sampai pintu depan, Dio dan Ken sudah membelalakkan mata. Pagar besi menjulang amat lebar memberi jalan ke halaman luas yang keliatan seperti tempat parkir. Ada juga tiang bendera di sana. Mungkin keluarga ini suka melakukan upacara Senin pagi. Ada semak-semak yang dibentuk bulat-bulat memagari jalan menuju halaman yang lebih dalam lagi. Kemudian setelah itu ada sebuah paviliun kecil tempat Dio dan Ken diperiksa identitas dan bawaannya.
Paviliun itu dilengkapi dengan komputer berkoneksi internet super cepat untuk mengakses database Dinas Kependudukan. Pemeriksaan terdiri atas pengecekan riwayat kriminal, penggeledahan isi tas dan saku, perekaman sidik jari, dan med check singkat. Dio nyaris teriak frustrasi saat diminta memberikan sampel darah, urin, dan ludah. Mau berkunjung ke rumah teman aja ribet banget.
Berkat kecanggihan lab med check tersebut, hanya dalam lima menit saja mereka sudah dinyatakan bukan hospes penyakit berbahaya. Saat mereka pikir pengumuman dari (salah satu) dokter keluarga itu adalah rintangan terakhir, rupanya masih ada lagi. Sang pemilik rumah belum memberikan izin.
Ah elah…
Setelah diperbolehkan masuk, mereka pun mengikuti seorang pelayan berjalan satu banjar dengan Ken di tengah, menuju paviliun tamu. Rumah ini seperti komplek paviliun yang dihubungkan oleh lorong-lorong, sebagian terbuka dengan taman di kanan-kiri, sebagian lagi tertutup dan gelap, seperti lorong yang pertama mereka lewati. Suasana di dalam lorong itu temaram, rasanya kayak rumah tradisional zaman medieval yang belum berlistrik. Bau keantikan dan kekunoan menguar dari berbagai perabot di dalamnya.
Begitu sudah tiba di ruang tamu, dua pelayan lain datang membawakan teh dan cemilan. Di sana mereka menunggu si nona rumah datang.
Kegiatan hari ini bisa dibilang sukses, walaupun ending-nya masih ngegantung. Tapi soal Nadia balik lagi ke sekolah atau enggak bukan poin pentingnya, jadi setidaknya ada satu masalah yang terselesaikan.
Dio tidak terlalu peduli apakah Nadia bakal kembali bersekolah atau malah keluar, hanya saja… setelah usaha yang mereka kerahkan pada hari yang terik ini, Dio jadi agak berharap hasilnya sesuai dengan keinginan mereka. Kalau ternyata Nadia tetap meninggalkan sekolah, rasanya Dio tidak akan merasa lega kalau Bos tidak memberi mereka kompensasi yang sepadan.
Memangnya ongkos dari Angsa Emas ke Perumwas itu murah? Mana supir angkot zaman sekarang suka semena-mena ngasih harga, berlindung di balik kedok “rakyat kecil”. Kalau saja semua orang sadar, bahwa yang namanya rakyat kecil itu bukan masalah penghasilan atau gaya hidup, tapi mentalitas.
Bukannya Dio punya hak ngomong begitu sih.
Ken tidak menceritakan apa yang dikatakan Nadia setelah Dio keluar ruangan, tetapi Dio tidak keberatan. Dia tidak tertarik pada curhat-curhatan cewek. Selain itu, ada hal-hal yang lebih peting untuk dia pikirkan. Atau, lebih tepatnya, untuk tidak dipikirkan.
Karena otak adalah organ paling pembangkang: semakin kita tidak ingin memikirkan sesuatu, kita malah semakin memikirkannya.
“Dek, jalannya muter sedikit nggak apa-apa ya?” supir tiba-tiba berkata, mengerem mobil. “Ini kayaknya ada razia, jalannya ditutup. Tuh.” Dia menunjuk beberapa bangku PKL yang dijajarkan menutup akses jalan.
“Waduh,” komentar Ken, kedua matanya memerhatikan beberapa polisi yang sedang menghukum dua orang remaja yang tertangkap. Satu di antara mereka mengenakan slayer hijau, satu lagi jaket hijau yang nampak cukup familiar.
Mereka putar balik, mengambil jalur alternatif.
“Ngapain anak-anak Penyu Hijau rusuh di sini?” gumam Ken, masih memerhatikan anak-anak yang disuruh jongkok dengan tangan diangkat ke atas, di depan mereka polisi-polisi bertampang sangar sedang mengomel.
“Adek tau?” tanya sopir, tercengang.
“Jaketnya itu lho,” jelas Ken.
“Iya, belakangan ini banyak bentrokan di sini, Dek. Anak-anak itu banyak berkeliaran di jalan. Sepertinya gara-gara kerusuhan di dekat sekolah Adek kemarin. Sekarang orang-orang daerah sini nggak bisa pake jaket hitam, takut tau-tau digebuk.”
Ken menggaruk dagu. “Ini kan wilayah Penyu Hijau. Anak Kobra Hitam kayaknya nggak bakal sembarang maen ke sini pake jaket item deh.”
“Adek kayaknya ngerti banget.”
“Ya gitu deh Pak… ada… temen yang ikutan,” kilah Ken, agak salah tingkah.
“Wah iya Dek? Anak sekolah Adek?”
“Temen SMP,” jawab Ken hati-hati.
Semasa SMP, Ken mengetuai sebuah geng keamanan sekolah yang dinamai Kutu Kelabu. Dio tidak tahu bagaimana persisnya ceritanya, yang jelas di akhir kelas tiga, geng tersebut semakin banyak diincar sehingga Ken membubarkannya. Atau mungkin, Ken justru membubarkan gengnya sehingga para mantan anggotanya jadi diincar geng lain?
Dio tak akan heran kalau para mantan anak buah Ken menggabungkan diri ke Kobra Hitam atau Penyu Hijau, dua geng yang disebut-sebut sebagai biang keroknya kerusuhan di kota ini. Bisa jadi, mereka mencar-mencar ke berbagai geng, untuk mendapatkan perlindungan.
“Kalau temen sekolah Adek sekarang ada nggak sih yang kayak gitu?”
“Nggak ada Pak. Kayaknya. Kalopun ada, saya nggak tau.”
“Kenapa ya mereka itu suka tawuran? Kan capek. Sama aja capeknya dengan sekolah. Kalau nggak mau sekolah, mestinya nggak mau berkelahi juga.”
Andai semua anak berandalan punya logika kayak gitu, Pak, kata Dio dalam hati.
“Nggak semua anak-anak itu nggak sekolah lho, Pak,” sanggah Ken. “Malah ada juga yang di sekolahnya pinter.”
“Oh ya, Dek? Tapi ngapain dong kalau begitu?”
“Mungkin mereka didorong sense of justice versi mereka sendiri,” kata Dio nimbrung—
BRAKKK!
Dio nyaris menggigit lidahnya saat mengumpat.
Tiba-tiba atap mobil dipukul. Di kiri dan kanan mobil masing-masing dua sepeda motor menyejajarkan diri. Para pengendaranya tidak memakai atribut apa-apa. Yang diboncengi memegang batang kayu, memukul-mukul mobil. Mereka memberi isyarat supaya mobil minggir. Dio dan Ken merapat ke tengah, kuatir kaca yang dipukul akan pecah berhamburan ke dalam.
“Ada apaan nih?!” seru Dio. Dia benci mendengar suaranya sendiri melengking panik.
“Kebut Pak!” teriak Ken.
“I-iya Dek!”
Supir tancap gas. Motor-motor mengikuti. Ken perhatikan daerah ini lumayan sepi walau hari masih terang.
“Mereka nyariin lo apa, Ken?” kata Dio.
“Masaaa?!!” seru Ken. “Tau darimana aku yang ada di mobil ini, kan kacanya gelap!”
“Ya nggak tau, mungkin preman punya sensor sesamanya, jadi langsung tau yang naik mobil ini elo.”
“Pegangan Deeeek!!!” supir berteriak, memotong sumpah serapah yang siap terlontar dari mulut Ken. Dia membanting setir ke kiri, menyerempet motor yang depan. Motor itu oleng, lalu penumpangnya berjatuhan ke trotoar. Motor di belakangnya mengerem pada waktu yang tepat, sehingga tidak mengalami nasib yang sama dengan yang depan. Sementara itu, motor-motor di sebelah kanan masih dengan agresifnya memukuli mobil. Kaca mobil mulai retak-retak. Untung nih mobil kacanya nggak biasa, nggak mudah pecah.
Mobilnya konglomerat memang beda.
Siuuut—mobil berbelok tajam ke kanan lagi.
Supirnya juga beda. Jangan-jangan si bapak ini waktu mudanya hobinya trek-trekan. Dua motor mengerem karena tidak mau bertabrakan. Sebagai akibat pengereman, mereka jadi ketinggalan beberapa meter.
Siuuut—supir berbelok ke kanan, lalu ke kanan lagi, sehingga mereka menuju ke jalan tempat motor pertama jatuh. Ken melihat dua anak geng malang itu masih ada di sana, yang seorang kelihatannya kejeduk cukup keras karena dia berbaring di trotoar sambil memegangi kepalanya. Supir memilih berbelok ke kiri, menyusuri arah mereka datang. Tanpa berlama-lama lagi, mereka sampai ke tempat yang dihadang bangku PKL tadi.
Jalan yang tadinya akan mereka ambil masih ditutup, sehingga supir mengambil jalur alternatif lain. Tiga motor yang masih mengejar mereka berhenti, tidak ingin kelihatan polisi.
“Mudah-mudahan mereka nggak berkeliaran di sebelah sini juga,” kata supir tegang.
Ken meraba retakan di kaca.
“Gila bener. Pak, ini mobilnya rusak gimana, Pak?” Ken memegang kepalanya dengan kalut. Mampus kalo mesti ganti…
“Waduh saya juga nggak tahu Dek, tapi yang penting kita selamat.”
“Bapak nanti nggak bakal dimarahin kan?”
Supir melirik Ken melalui spion. “Kalau soal dimarahi Nyonya sih kayaknya enggak, Dek, mobil ini punya Nona Nadia soalnya.”
Untung deh kalo gitu.
“Anu… Adek-adek tau siapa mereka?”
Ken menggeleng. “Nggak tau. Tapi harusnya mereka nggak tau di dalem sini aku. Lagian, aku kan nggak pernah terlibat apa-apa sejak Kubu bubar. Sebelum bubar aja aku nggak ngapa-ngapain. Mungkin nggak sih yang tadi itu random? Kita cuma lagi sial aja.”
Dio menggaruk dagu. Memang sih, yang namanya jadi korban penyerangan geng motor itu bisa jadi random. Mungkin anak-anak itu lagi diospek, disuruh ‘meminjam’ SIM supir mobil dengan merek tertentu, atau hal bego sejenis.
Tapi kalau ada Ken Ratu dalam penyerangan random itu, rasanya kebetulannya pas banget.
Terlalu pas.
“Aturan kalo ada razia mereka sembunyi, ini malah sengaja ngejar kita,” kata Dio lambat-lambat.
“Mungkin pada lagi kejar setoran?” usul Ken.
“Tetep aja. Coba aja tanya diri lo sendiri. Kalo ada polisi lo pasti bernaluri untuk menghindar jauh-jauh kan?”
Ken memberi Dio tatapan keji. “Kamu bisa nggak sih nggak ngungkit-ngungkit masalah itu tiap lima detik? Emangnya kamu pikir aku nggak bakal bete?”
Dio nyengir. “Abis lo kalo lagi bete lucu sih, Ken.”
Perlu dua detik bagi Dio untuk menyadari kalau kata-katanya punya makna ambigu.
Sial. Dia jadi malu sendiri.
“Yah,” kata Dio sambil meneliti retakan kaca, “kita berharap aja ini emang random dan nggak bakal ada kedua kalinya.”
~ ~ ~
Mestinya Dio berkaca dari pengalaman. Dari lahir sampai sekarang, Ken selalu terlibat masalah aneh-aneh. Dan itu bukan 100% disebabkan kedodolan Ken sendiri. Seringkali, malah masalah yang sepertinya melekatkan diri sama anak satu itu.
Misalnya, waktu SD Ken pernah berantem dengan anak kelas sebelah yang lumayan ditakuti. Penyebabnya adalah Ken menginjak perangkap yang Dio siapkan untuk membalas anak-anak kelas sebelah itu karena mereka pernah mencoba membuli Dio (waktu SD, anak-anak cenderung mengolok-olok posturnya yang bongsor alih-alih kagum). Begitu Ken menginjak tali yang akan memicu jatuhnya sebuah ember penuh air, refleks hasil latihan silat membuat Ken menghindar tepat waktu. Begonya, ketika dia melompat menghindar, dia menyenggol tiga anak target Dio sampai ketiga anak itu tercebur ke selokan. Disusul dengan terbentur ember yang memantul ke arah mereka.
Kemudian, waktu SMP Ken tanpa sengaja jadi ketua preman-preman sekolah, yang akhirnya menjadi geng bernama Kutu Kelabu. Selama rezim Kutu Kelabu, tak terhitung berapa kali guru BK memanggil Ken lewat loudspeaker. Padahal Ken sendiri tidak benar-benar melakukan apapun yang berkaitan dengan geng bego itu.
Meskipun Ken sudah memproklamirkan diri berhenti dari perpremanan, tidak berarti masalah akan berhenti membuntutinya. Dan karena Dio satu kelompok dengannya, mungkin sekali masalah ikut membuntutinya juga. Jadi, Dio merasa wajib tahu apa yang terjadi ketika dilihatnya Ken dan ketua OSIS-nya berlari menyeberangi lapangan menuju gedung depan, sementara bel masuk kelas berdering lebih cepat dari seharusnya, disusul dengan suara Bos yang menggelegar lewat sound system menyuruh semua orang segera masuk kelas.
Maka, dengan cueknya dia pun mengikuti Aditya, ketua kelasnya, keluar dari ruangan.
“Loh, mau kemana?” seorang cowok yang sedang berlari ke arah berlawanan tiba-tiba mencekal lengan Dio, membuatnya mengerem dan berbalik. Dia mengenali wajah orang ini sebagai teman sekelasnya, tapi dia masih belum tahu namanya.
“Ke belakang,” jawab Dio asal.
“Kata Bos, kita harus cepet-cepet masuk kelas!”
“Gue udah kebelet!”
“Gue ikut deh!”
“Ih, ngapain lo ngikut gue ke belakang?” kata Dio ngeri.
“Gue juga kebelet, tapi kepaksa buru-buru ke kelas soalnya takut disuruh Bos shuttle run.”
Dengan reputasi begitu, mestinya Bos itu dijuluki The Shuttle Runner.
“Gue bohong,” kata Dio tanpa banyak basa-basi. “Gue nggak mau ke belakang. Lo pergi sendiri aja.” Dengan sebuah sentakan keras, Dio melepaskan diri dari pegangan si teman sekelas, lalu buru-buru berlari sebelum anak itu sempat mengejarnya.
“Loh, Dio, tungguu!!”
Namun, Dio cukup gesit untuk berlari melewati arus anak-anak yang sedang kembali ke kelas. Tanpa berlama-lama, dia pun berhasil mencapai gedung depan.
Dia celingak-celinguk di atrium, mencari-cari sosok berambut panjang. Namun, yang dicarinya tak kelihatan. Antara anak itu sudah masuk ke salah satu ruangan yang berjejer di sebelah kanan dan kiri pintu masuk, atau naik ke lantai dua. Dio menajamkan telinga. Terdengar hiruk-pikuk dari arah ruang guru. Seorang guru pria sedang memberikan arahan kepada guru-guru yang lain, yang mendengarkan sambil berbisik-bisik, menimbulkan bunyi gemuruh teredam.
“...sesudah itu baru kita bubarkan secara berkelompok dengan didampingi dua atau tiga guru. Bagaimana, Bapak-bapak dan Ibu-ibu?”
“Saya setuju!” sahut salah satu guru wanita.
“Tapi bagaimana dengan rombongan terakhir, Pak Agus?” tanya seorang guru pria.
“Akan dikawal oleh polisi.”
“Saya kuatir murid-murid tidak mau masuk sekolah lagi besok-besok.”
“Saya lebih kuatir sama orang tua murid. Mereka pasti banyak ngomong lagi seperti kemarin!”
“Iya, betul...”
Gumaman semakin keras sementara semua orang membuat forum masing-masing.
“Dionysus!”
Dio nyaris mengeluarkan segala makian yang dia tahu. Dengan tubuh setengah terlonjak, dia berbalik dan menghadapi wajah Bos yang mengerikan. Ditambah dengan cahaya redup atrium depan ini, brewoknya Bos membuat dia semakin seperti eselon mafia.
“Sedang apa kamu di sini?!” tanya Bos. Atau, lebih tepatnya, menghardik. “Kenapa kamu tidak di kelas?!”
“Maaf, Pak,” kata Dio, tidak tahu harus ngomong apa lagi. Bos termasuk guru yang tidak bisa dielaki dengan ngeles.
“Maaf, maaf,” gerutu Bos. “Kembali ke kelas sana!”
“Iya, Pak.” Dio memberi Bos anggukan sebelum berbalik, batinnya ngedumel habis-habisan.
“Loh, ada Dio?” suara Ken mengalir dari arah lantai dua. Dio mendongak. Anak itu turun bersama si ketua OSIS. Dio berhenti melangkah, menunggu Bos menyemprot mereka berdua. Sialnya, hal itu tidak terjadi, karena rupanya Ken dan Nando datang ke gedung depan ini atas perintah Bos.
“Ken Ratu,” kata Bos. “Bagaimana keadaan di depan?”
Wajah Ken berubah serius. “Banyak, Pak. Sepertinya mereka memang mau menyerang sekolah.”
Menyerang? otak Dio berputar cepat. Masih ada hubungannya dengan tawuran dua mingguan yang lalu? Atau dengan penyerangan ke mobil Nadia yang ditumpangi Ken kemarin?
“Gawat ini,” kata Bos. “Kalian kembali saja ke ruang OSIS, sana. Dan kamu, Dionysus, kenapa masih ada di sini?!”
“Iya, maaf Pak!” sahut Dio sambil buru-buru menyingkir dari tempat itu. Namun, alih-alih bersegera, Dio melambatkan langkah agar tersusul Ken dan Nando, berharap Bos akan mengurusi entah apa dulu bersama guru-guru dan bukannya langsung berpatroli di koridor-koridor kelas.
Harapannya terkabul—Ken dan si Ketua OSIS hanya keluar berdua.
“Buruan ke kelas, napa?” kata Ken galak, begitu melihat sosok Dio.
“Ada apaan sih, Ken?” tanya Dio langsung, mengabaikan teguran barusan. “Sekolah kita mau diserang preman?”
“Kalo udah tau, ngapain nanya?!” Ken menghardik.
“Tapi lo bakal ngelAWW!!! Sakit, monyet!”
Karena Ken sudah menyikut rusuk Dio lagi sebelum cowok itu menyelesaikan kalimatnya yang bisa bikin Nando kebocoran fakta penting yang Ken tidak ingin dia ketahui.
“Ke kelas sana, buruan!”
Dio mendecakkan lidah, tapi tidak berani berkata apapun lagi karena Ken melotot tajam-tajam padanya. Kalaupun anak itu tidak akan menghajarnya di muka umum, ada kemungkinan dia akan melabrak masuk rumahnya dan menghajarnya di sana. Jadi Dio memilih untuk menyerah dulu sementara ini.
~ ~ ~
Proses pembubaran anak-anak berlangsung lambat dan senyap. Jam terakhir dibatalkan. Para guru dan staf pria dibagi ke dalam dua kelompok besar, satu ikut patroli bersama polisi, satunya lagi mengantar anak-anak dan guru dan staf wanita dalam kelompok-kelompok sampai lokasi aman. Kelompok berikutnya baru dipulangkan kalau guru-guru yang mengantar sudah kembali, makanya jadinya lama.
Sekarang sekolah sudah sepi. Tinggal empat guru laki-laki termasuk Bos, pengurus inti OSIS, dan Dio.
“Loh kok kamu masih di sini?” tanya Ken heran begitu Dio menghampirinya. Ken sedang mengecek daftar pulang, membandingkannya dengan daftar hadir yang diisi tadi pagi untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
“Sengaja nungguin lo,” gerutu Dio pelan, tidak ingin terdengar oleh dua anak OSIS lainnya. Yang seorang adalah Nando, seorang lagi anak cewek yang Dio tidak tahu namanya.
“Nungguin aku?” ulang Ken dengan suara keras.
Nando dan si pengurus cewek spontan menoleh, pandangan mereka tertarik. Dio ingin mencekik Ken saat itu juga.
“Iya, nungguin lo,” tukas Dio kesal. Dia mendelik ke arah Nando dan si pengurus cewek, yang geragapan kasak-kusuk sok sibuk. Ken mengikuti arah pandangannya.
“Kalian bakal pulang bareng Pak Abimanyu kan? Aku duluan ya?”
“Loh Ken, nggak nunggu Pak Jehan dulu?” tanya si cewek. Dio lelah merujuk kepadanya dengan sebutan “si cewek” atau “si pengurus cewek”, tapi dia tidak ingin kelihatan mesum memelototi dada anak itu untuk membaca nametag-nya. ...kenapa sih nametag itu harus dipasang di dada?!
Ken nampak menimbang-nimbang. Entah bagaimana, Dio tahu apa yang dipikirkannya. Dengan risiko preman-preman itu masih berkeliaran di luar, Ken pasti tidak ingin pulang dikawal guru karena khawatir reputasi lamanya terkuak. Apalagi kalau dia harus berkelahi; lebih repot berkelahi sambil melindungi daripada hanya berkelahi saja.
“Enggak deh. Lagian polisi mestinya masih muter-muter di daerah sini. Keliatannya udah sepi juga kok,” kata Ken.
Nando nampak ragu, tapi setelah beberapa detik dia mengangguk juga. “Oke deh,” katanya. “Hati-hati ya. Jangan main dulu, langsung pulang!”
“Iya, Mamah,” cibir Ken. “Yuk, duluan.”
Setelah agak jauh dari sekolah, Dio akhirnya membuka pembicaraan.
“Menurut gue, lo lagi diincar, Ken,” katanya tanpa preambule.
“Kenapa tiba-tiba ngomong gitu?”
“Menurut gue, kedatangan preman-preman itu kemari ada hubungannya dengan anak-anak yang ngejar-ngejar kita pas pulang dari tempat Nadia kemaren.”
Ken melipat lengan, mencerna spekulasi Dio baik-baik.
“Apa yang bikin kamu berpikir dua kejadian ini berkaitan?”
“Firasat.”
Ken hampir tersedak tertawa, tapi untung ditahannya. Kalau dia ketawa saat itu juga, Dio bakal benar-benar mencekiknya. Tentu saja, kemungkinannya sangat besar Dio sendiri yang berakhir dicekik.
“Kamu kayak cewek aja, bawa-bawa firasat segala.”
“Yang namanya sixth sense itu nggak memandang gender,” gerutu Dio, sambil merasakan hidungnya kembang kempis karena canggung.
“Masih ada kemungkinan ini kelanjutan tawuran yang kemaren-kemaren itu kan? Lagian, yang nyerang mobil kita waktu itu nggak tau yang di dalam mobil itu aku. Jadi belum tentu mereka ngincer aku.”
“Mungkin aja kalau lo dikuntit, Ken. Kita kan nggak tau. Anak-anak macem gitu bisa pinter buat yang beginian. Walaupun nyerang mobilnya Brahmadibrata itu agak goblok sih kalo kata gue.”
Ken menggaruk kepala. “Yang kamu bilangin itu masuk akal… tapi inget kita lagi ngomongin siapa, Di. Mereka bukan tipe yang bisa bikin rencana belibet kayak gitu. Mereka tuh tipe gempur-hantam-kabur!”
Dio diam. Kata-kata Ken masuk akal. Apalagi, diucapkan oleh mantan preman sekaliber Ken, kata-kata itu jadi punya kredibilitas tinggi. Tapi, Dio tetap punya perasaan tak enak. Dio tak mencemaskan keselamatan Ken, tentu saja. Cewek itu pasti membabat habis siapa saja yang berani menyerangnya tanpa segan-segan. Hanya saja, firasatnya mengatakan semua ini bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Tawuran di dekat Wadit? Penyerangan ke mobil Brahmadibrata? Cakupannya terlalu luas kalau yang diincar hanya Ken saja.
“Gue merasa anak-anak itu sedang bergerak besar-besaran. Dan elo, entah mau mereka rekrut untuk ikutan, atau merea singkirkan,” kata Dio. “Lo adalah titik tumpu dari segala kejadian yang udah, sedang, dan akan terjadi di kota kita ini.”
Ken menatap Dio dengan sorot terguncang. “Kamu jangan ngomong yang serem-serem gitu dong! Lagian, kenapa kamu tiba-tiba jadi peduli gini sih? Kamu nggak dapet untung apa-apa dari sengaja nungguin aku pulang, dan sengaja ngomong panjang lebar soal ini. Kamu kayak ngarep aku bener-bener lagi ditarget.”
Rahang Dio spontan menceklik terbuka, membuatnya mangap tak percaya.
Ni anak… udah orang bela-belain mikirin dan nungguin… dijawab secara nggak sopan kayak gitu?
“Yaudah kalo lo nggak mau dengerin omongan gue,” bentak Dio. Dia mempercepat langkahnya, kesal. Sia-sia nunggu sampe dua jam untuk menyebutkan hal-hal tadi. Begini nih kalau ngomong tanpa diminta, bukannya diberi terima kasih, malah dianggap usil. Kalau tahu Ken bakal menolak kekhawatirannya mentah-mentah, mending tidak usah ngomong apa-apa sama sekali. Dasar cewek nggak tahu diuntung. Cih!
“Dio! Hei!” panggil Ken, cepat-cepat mengejar.
Dio tidak ingin berbalik, meskipun sesuatu menggelitik kesadarannya. Dia merasa seperti jadi cewek yang lagi merajuk karena cowoknya tidak mengabulkan keinginannya. Ihh, gatel, gatel...
“Woi, jangan cepet-cepet dong jalannya, kakiku lebih pendek tau!” seru Ken. “Sori, sori, aku ngomongnya kelewatan!”
Akhirnya Dio berhenti dan berbalik. Dia tidak ingin seperti cewek yang sedang merajuk.
Tiba-tiba, dilihatnya gerakan tanpa suara di belakang Ken. Suaranya tercekat di kerongkongan. Terdorong oleh sebuah refleks yang Dio tidak tahu dimilikinya, Dio melompat dan mendorong Ken ke samping.
Swish—sesuatu membelah udara, sebelum sesuatu yang keras menghantam sisi kepalanya.
BUK!!!
Rasa sakit muncul secara tertunda dan perlahan, membuat Dio sendiri tidak yakin apa yang baru saja terjadi.
“DIOOO!!!” Ken berteriak—suara nyaringnya terdengar seperti tiupan terompet, membuat kepalanya terasa berdenyut. Untuk sejenak saja, sekitar Dio terlihat gelap dan berputar.
Dio mengerjap, mencoba mengembalikan fokus pandangan. Dia merasa sesuatu yang basah mengalir melalui sisi wajahnya. Cairan itu menetes ke atas aspal, berwarna gelap dan kental.
Dio tidak ingin memikirkan cairan apa itu.
Bruk! Sesosok tubuh ambruk.
“Bangsaaaattttt!!!” seseorang berteriak, melompat, menerjang. Dio merasakan pertarungan terjadi di atas tubuhnya yang meringkuk. Terdengar derap langkah orang-orang mendekat. Suara tinju menghantam rahang dan batangan kayu mematahkan lengan. Tubuh-tubuh berjatuhan.
Dio bertumpu pada kedua tangannya, mencoba bangun.
“Dio, ayo!” kerah di tengkuknya ditarik, memaksanya bangun sambil setengah tercekik. Begitu dia sudah—memaksakan diri—bangkit, tangan Ken berpindah dari kerah bajunya ke tangannya, menariknya agar melangkah.
Ken membawanya lari menyusuri jalanan sepi yang masih dekat dengan komplek sekolah ini. Sekeliling Dio melebur ke dalam pusaran warna-warna kabur. Dia merasakan kakinya berayun bergantian, tetapi tidak merasa menapak.
“Kenapa mereka tiba-tiba muncul?” kata Ken. “Mereka beneran ngincer aku? Tapi kenapa? Aku udah setahun pensiun dari begituan!”
Dio tidak bisa berpikir, maka dia diam saja. Dia memusatkan energinya untuk menjaga tubuhnya tetap vertikal. Sekarang dia merasa pusing dan belakang kepalanya berdenyut. Kalau bukan karena Ken menggenggam tangannya erat-erat, Dio pasti sudah kehilangan nalar.
Grusak—
Ken tiba-tiba berhenti. Dio tidak siap, sehingga dia pun menabrak anak itu dengan spektakuler. Kalau tidak sedang pusing karena gejala gegar otak, Dio pasti sudah mengomentari sikap tubuh Ken yang berdiri mantap, sehingga tidak goyah walau baru ditubruk sesosok laki-laki dengan tinggi 186cm dan berat 65kg.
Dio sudah akan memaki, ketika disadarinya segerombolan orang berdiri di hadapan mereka, berbaris membarikade jalan. Penampilan mereka sejenis dengan preman-preman yang tadi menimpuk Dio dan dihajar Ken tanpa ampun.
Terdengar gemuruh dari belakang mereka, disusul dengan kemunculan preman-preman pejalan kaki dan pengendara motor. Jumlah mereka ada dua puluhan. Ditambah yang mengepung dari depan, totalnya tiga puluhan. Dio terlalu pusing untuk menghitung dengan akurat.
“Ken Ratu!” salah seorang dari preman-preman itu berteriak. “Gua kemari mau buat perhitungan sama lu!”
“Sori,” kata Ken dengan nada santai, walaupun tangannya meremas tangan Dio semakin kuat. “Aku nggak bawa kalkulator hari ini!”
Dio memang sedang puyeng karena kepalanya baru dipukul, tetapi setidaknya dia masih bisa membedakan candaan mana yang lucu dan garing.
Sesuai dugaannya, si ketua preman semakin berang.
“Nggak usah sok pinter lu!” bentaknya. “Lu udah terlalu banyak bikin masalah sama anak-anak gua. Sekarang lu harus rasain gimana akibatnya kalau berurusan dengan gua! Lu akan habis hari ini! Boys, hajarrrrr!!!”
“UOOOYYYAAAAAA!!!”
Bagaikan tentara pejuang kemerdekaan melawan pemerintah kolonial, preman-preman itu menyerbu maju, senjata mereka terangkat tinggi-tinggi ke udara. Ada balok kayu, ada bat bisbol, ada linggis, palu, obeng, dan handuk putih. Dio tidak tahu apa yang akan dilakukan preman dengan sehelai handuk putih, tapi mungkin Dio salah lihat saking pusingnya. Knalpot motor yang sudah dimodif habis-habisan digerung-gerungkan seolah-olah mereka itu instrumen musik dalam konser masif.
Begitu pegangan Ken terlepas, Dio sudah tidak kuat lagi berdiri, dan langsung limbung.
“Dio!” seru Ken. Tapi, Ken tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Dio, karena gelombang pertama sudah dalam jarak pukul.
Dio berhasil kembali menyeimbangkan diri. Dia melihat sesuatu bergerak dari sudut matanya dan secara refleks mengangkat tangan. Sebuah obeng menyabet lengannya, menimbulkan luka yang memanjang dari sikut sampai pergelangan. Dio menahan diri tidak meringis.
Anehnya, sabetan itu seperti mengangkat kabut yang menutupi pandangan dan pendengarannya. Tiba-tiba Dio bisa melihat sekitarnya dengan jelas. Melihat Ken menghindari dua, menangkis satu, dan menangkap satu senjata tumpul yang diayunkan penuh nafsu ke arahnya. Tiga orang bergerak tergesa-gesa untuk memukul Ken dari belakang. Dio membiarkan otot-otot kaki dan tangannya bergerak tanpa perintah sadar; dia melompat tinggi dengan kaki teracung. Kalau Ken belum menyadari ada orang yang hendak menyerangnya dari belakang, maka dia jelas-jelas melihat Dio melakukan sapuan ke arah kepalanya, dan merunduk pada saat yang tepat. Dio bermaksud menarget ketiga preman itu, tetapi spin kick-nya hanya mengenai pelipis salah satu dari mereka. Setidaknya korbannya sampai berputar di tempat karena terbawa momentum dan roboh menimpa teman di sebelahnya. Ken menggunakan bat bisbol yang direbutnya untuk menghajar preman yang satu lagi.
Namun, gugur satu tumbuh seribu.
Masih banyak preman yang menyerbu dalam kelompok-kelompok, bergantian menyerang dengan teman mereka yang berjatuhan satu persatu. Ketika selama sesaat serangan berhenti datang, Dio dan Ken berdiri berpunggungan dengan kuda-kuda siap bertahan, Dio berteriak,
“Ken, lo punya masalah apa sih sama mereka?”
“Nggak tau,” sahut Ken, “aku nggak pernah ketemu mereka.”
Preman-preman menyerbu. Dio tidak sempat benar-benar menghitung mereka, tapi rasanya jumlah mereka sudah berkurang setengahnya.
“Mampus luuu!!” si pemimpin gerombolan berteriak, menerjang paling depan. Sebuah linggis teracung tinggi-tinggi.
Ken dan Dio saling menjauh.
“Tadi katanya lo udah bikin banyak masalah sama mereka.”
“Nggak tau, Di!” Ken terdengar agak frustrasi.
Brak! Bug! Dzig! Bunyi-bunyian mengerikan memenuhi udara di sela-sela teriakan murka dan kesakitan. Dio banyak berkelit dari pukulan, tidak leluasa untuk bertahan apalagi melakukan serangan balasan. Lucunya, memang banyak pukulan yang meleset jauh. Dio jadi curiga, mungkin orang-orang ini masih teler dari minum-minum. Dio tidak mencium bau alkohol di tengah-tengah bau keringat, darah, dan badan, tapi dia tidak terlalu keberatan.
Dio baru menyadari kesalahan besar yang telah dibuatnya ketika orang yang hendak memukulnya kehilangan keseimbangan, kemudian senjatanya terlempar dari tangannya ke arah—
“Ken!!”
Dio hendak menendang senjata itu dari arah geraknya, tetapi dia menangkap sesuatu didongsokkan ke arahnya. Sesuatu yang terlihat tumpul dan berkarat—bukan, melainkan berlumuran darah—
Dio merunduk, tapi tidak cukup cepat—
Sesuatu menindih punggungnya, memaksanya tersungkur.
“AARRGHHH!!!” raungan kesakitan terlepas dari penyerangnya. Benda berkarat yang nyaris melubangi lehernya terjatuh, disusul dengan sesosok tubuh dengan lengan yang tertekuk ke arah yang tidak wajar.
Saat itulah, terdengar tiupan peluit dan tembakan.
“Berhenti! Polisi!!!” teriak satu suara mantap.
“Anjing! Polisi!!” satu preman memaki.
“Kabuuur!”
Para preman yang masih cukup sehat belingsatan ke segala arah. Beberapa segera melompat ke boncengan, beberapa berlari melompati semak yang memagari lahan terbuka hijau.
“Berhenti!!” seorang polisi kembali berteriak.
Sementara preman-preman itu sibuk menyelamatkan diri, Dio menatap sekeliling. Pemandangan di ruas jalan yang cukup sepi itu lumayan mengerikan. Tubuh-tubuh berserakan, sebagian masih sadar dan mencoba merangkak pergi—tetapi tidak berhasil, pastinya—dan sebagian lainnya benar-benar membeku dengan lebam-lebam dan luka-luka berdarah memenuhi seluruh bagian tubuh yang terlihat.
Diam-diam Dio berdoa semoga tidak ada yang mati. Dio tidak peduli kehidupan macam apa yang menanti preman-preman itu pascapenyerangan ini, atau apakah mereka akan hidup atau mampus. Namun, adanya korban jiwa akan membebani psikis Ken lebih berat. Setidaknya, Dio tidak akan tahan melihat orang di dekatnya menanggung sesuatu segawat itu.
“Ken Ratu! Dionysus!” suara menggelegar memanggil mereka.
Bos, bersama tiga guru lelaki dan dua pengurus OSIS yang tadi mereka tinggalkan di sekolah, berlari tergopoh-gopoh di sebelah mobil patroli yang membunyikan sirine secara tidak penting.
Ken duduk dengan kaki terjulur di sebelah Dio, mengelap dahinya. Dia mengernyit ketika punggung tangannya mengusap pelipisnya. Darah dan keringat mengaliri sisi wajahnya dari sana.
“Ken, pisau yang tadi…?” tanya Dio.
Ken menatap noda darah di tangannya. Mengangguk.
“Bangke!” kutuk Dio.
Ken berjengit. Dio mendengus getir. Mantan ketua preman yang baru saja menghabisi dua puluhan orang tidak suka mendengar kata-kata makian? Ada yang salah di situ.
“Harusnya gue melawan,” gerutu Dio, lebih kepada dirinya sendiri, menatap jari-jarinya. Sekujur tubuhnya terasa berdenyut. Jantungnya berdegup sangat kencang, membuatnya pusing.
Dia merasakan pandangan menyelidik Ken, tetapi tidak dihiraukannya.
“Kalau gue lebih banyak melawan daripada menghindar, pisau sialan itu nggak bakalan ngenain lo,” kata Dio, sebelum dia bisa menahan diri. “Sial!”
“Ken Ratu! Dionysus!” seru Bos lagi, akhirnya mencapai mereka. “Kalian tidak apa-apa?”
Suara Bos yang super toa membuat kepala Dio semakin nyut-nyutan. Pandangannya mulai mengabur.
“Nggak apa-apa pantat lo?!” bentak Dio sebal. Terdengar suara-suara tersentak, tetapi Dio sudah tidak begitu awas ada siapa saja di sekitarnya. “Ken—bawa Ken ke rumah sakit…”
“DIO!!!”
Pekikan terakhir itu mengantar Dio ke dalam kegelapan.


 drei
drei


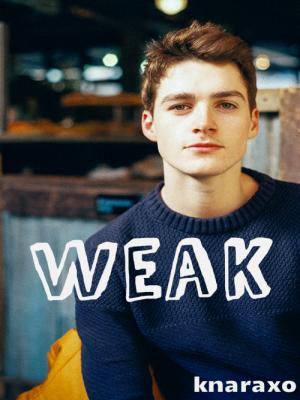







95 banding lima, auto sakit perut ketawa cekikikan. Tenyata kalau di perhatiin tokoh Ken, karakternya hampir mirip dengan, tokoh Tio di ceritaku.
Comment on chapter Satu