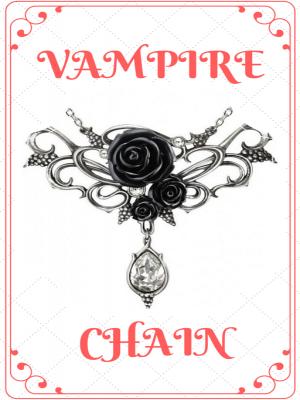PESTA ini membosankan.
Walau untuk kasusnya, semua pesta akan dia sebut membosankan.
Vino menenggak habis dalam satu tegukan gelas berisi mocktail di tangannya sambil tetap melirik ke arah meja di salah satu sudut secara obsesif. Tingkah menyedihkannya selama setengah jam terakhir ini tidak lain demi mengemis secuil perhatian dari seorang perempuan yang bahkan tidak menoleh sedikitpun ke arahnya sejak dia menginjakkan kaki di tempat ini.
Namanya Alice, mantan kekasih yang membuatnya rela membeli tiket penerbangan ke Singapura dan berujung terdampar di rooftop party di Dunlop Street berisi orang-orang yang tidak ada satupun dia kenal. Oh, ada satu, si plontos Ruben yang mengundangnya ke pesta mahasiswa ini dengan iming-iming, “Alice juga bakal dateng, Vin, lo masih pengen ngajak dia balikan, kan?”
Sialnya, ya, ya, dia memang masih mengharapkan Alice kembali.
Karena perasaan adalah hal yang sungguh absurd, kamu masih bisa menginginkan seseorang yang sudah menginjak-nginjakmu sampai babak belur. Hampir seakan Vino dengan kesadaran penuh menyodorkan hatinya untuk dihancurkan berulang kali layaknya masokis sejati.
Jatuh cinta dan sakit jiwa mungkin memang tidak ada bedanya.
Seperti dia masih mengingat dengan teramat jelas seakan itu baru kemarin bahwa gaun biru yang dikenakan Alice saat ini berwarna sama kala mereka pertama kali bertemu tiga tahun lalu. Dia hampir berpikir Alice sengaja mengenakannya saat ini.
Gila, memang.
Kalau saja ibunya tahu di mana Vino berada, dia akan habis dimarahi. Tak peduli dia adalah lelaki dewasa dua puluh empat tahun yang harusnya punya kebebasan untuk travelling ke mana pun tanpa wali, ibunya masih dan akan selalu menganggapnya seperti bocah yang perlu diawasi. Lain lagi dengan Windra, kakak laki-lakinya lebih pengertian dan berjanji akan mendukung alibi Vino yang ngakunya pada ibu mereka sekarang sedang berada di Bogor untuk mencari inspirasi.
Mencari inspirasi, my ass, keluh Vino sambil berdecak ketika memandangi Alice yang tengah tertawa pada apa pun yang dikatakan lelaki bule yang sedang bicara dengannya, ini, sih, namanya mencari seutas benang di tumpukan jarum, berdarah-darah.
Vino tengah membuat perhitungan di kepala; apa dia harus menghampiri Alice saat ini juga dan mengusir pergi lelaki yang sedang bersamanya, atau perlu menunggu sampai waktu yang tepat, sampai mungkin Alice yang lebih dulu mengirim sinyal padanya untuk mendekat.
Dia tidak pernah bagus dalam membaca situasi, atau menerka bahasa tubuh dan isi hati. Sebutan lainnya, Vino Giffari Bharata ini bukan manusia paling peka. Keluhan yang paling sering Alice layangkan padanya kala mereka masih bersama bahkan adalah Vino tidak perhatian sama sekali.
Dia memberikan ratusan puisi berupa curahan isi hatinya untuk Alice, dan perempuan itu masih berani berkata dengan begitu putus asa, “Kamu sebenarnya cinta, nggak, sih, sama aku?”
Alice ini antara punya kecenderungan sadistik dan senang menyiksanya, atau dia benar-benar buta.
Namun, kadang, Vino pun bertanya-tanya apa dia memang sungguhan cinta, atau ini hanya obsesi semata.
Batasnya begitu kabur hingga dia sendiri tidak yakin.
Vino mengambil lagi gelas di meja dan meneguknya sampai habis, merasa geram ketika matanya menyaksikan Alice terkikik geli saat Chris Hemsworth KW yang bersamanya mengelus pipinya dengan buku-buku jari. Dia panas untuk alasan yang tidak jelas, Alice bahkan sudah bukan lagi miliknya untuk dicemburui seperti ini.
Seakan belum lengkap, suara Charlie Puth terdengar dalam lagu Attention yang seperti tengah menyindir Vino telak untuk menambah kesengsaraannya. DJ-nya yang kurang ajar atau dia yang kelewat menyedihkan? Apa pun itu, Vino merasa seperti orang paling bodoh se-Singapura saat ini.
Semua orang di sekelilingnya masih sibuk berdansa atau minum bergelas-gelas alkohol hingga mabuk, sementara yang dia inginkan hanyalah Alice meliriknya barang sedetik saja sudah cukup.
Ini pesta, untuk bersenang-senang, bukan untuk mengemis perhatian. Vino berdecak sambil mencari distraksi lain agar berhenti memandangi mantan kekasih yang bahkan tidak menganggapnya ada.
Pandangannya kemudian tak sengaja menangkap sosok perempuan molek di tengah lantai dansa dengan gaun merah muda berenda dan rambut berombak kecokelatan tergerai melewati bahunya yang polos. Dia berdansa dengan begitu lepas mengikuti irama musik yang terputar tanpa memedulikan beberapa lelaki di dekatnya yang menunjukkan gelagat ingin berdansa bersama.
Vino seperti terbius, pandangan matanya tidak bisa lepas dari perempuan itu seakan tengah memandangi mahakarya.
Just look, don’t touch—aura tidak tersentuh itu memancar kuat dari si perempuan bergaun merah muda, dan Vino hampir berpikir apa dia sekarang berteleportasi ke National Gallery Singapore dan sedang memandangi salah satu lukisannya Claude Monet, atau masih di tengah pesta.
Dia senang menjadi pusat perhatian, Vino langsung mengambil kesimpulan dengan pandangan masih terkunci pada perempuan itu. Ada sekitar tiga lelaki di sekitarnya yang terang-terangan tengah menggodanya, tetapi tidak ada yang digubris, pun dia juga tidak menghindar dengan pergi berdansa ke tempat lain. Vino menyipitkan mata, dia cukup pintar untuk membuat laki-laki berpikir mereka punya kesempatan dengannya, tapi dia tidak akan menerima satu pun ajakan mereka.
Garis wajahnya memberi Vino kesan kuat kalau dia orang Indonesia, tetapi sulit untuk memastikannya dari jarak jauh di tengah keberagaman yang ada di pesta ini. Mulai dari etnis Tiongkok, India, Melayu, sampai Kaukasia, semuanya tumpah ruah di atap salah satu bangunan tiga lantai berdinding bata ekspos di daerah Little India yang sering disebut sebagai ghetto area-nya Singapura.
Apa dia salah satu mahasiswa seperti yang lain? Atau hanya turis yang tidak sengaja terseret ke pesta ini?
Perempuan itu tidak kelihatan dia datang bersama seseorang, outfit yang dia kenakan menunjukkan dia datang untuk bersenang-senang dan tidak akan pulang sebelum pergantian malam.
Dia suka perasaan diinginkan.
Dia ingin kebebasan.
Bahkan sejak masih kanak-kanak, Vino dikenal sebagai anak yang intens dan senang melakukan kontak mata—yang dia sebut sebagai observasi. Psikolog yang dia datangi bersama ibunya di usia tujuh tahun bilang bahwa itu adalah caranya membangun koneksi dengan individu lain, karena kepekaan emosionalnya begitu rendah dan dia buruk dalam melakukan interaksi, sehingga menatap mata seseorang adalah cara yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.
Jika ada kontes saling tatap, bungsu dari dua bersaudara ini akan menyabet gelar juara dengan mudah. Orang-orang banyak yang tidak nyaman padanya karena ini, karena dia bisa terus menatap seseorang dalam jangka waktu lama hingga membuat mereka merasa terganggu.
Waktu kecil, Windra bahkan sering menyenggolnya jika dia terlalu lama memandangi orang di jalan dan mengeluarkan nasihat, “Jangan terlalu lama menatap orang asing, Dek, mereka nggak nyaman.”
Yang biasanya dengan enteng dia balas, “Bukan kemauanku, Mas, kata psikolog itu salah satu gejala karena aku disleksia.”
Kakak lelakinya pun tidak bisa protes lebih jauh jika kartu itu sudah Vino keluarkan, topik itu sampai kapan pun akan menjadi hal sensitif untuk keluarga mereka.
Aib, bisa dibilang. Mengakui itu toh sudah tidak semenyakitkan saat dia masih SD dulu.
Dan mungkin karena caranya yang terus memandang tanpa malu-malu membuat objek yang dari tadi dia amati akhirnya menyadari keberadaannya. Perempuan itu menoleh ke arah Vino yang tengah berdiri seorang diri di dekat meja bar. Kebanyakan orang akan mengalihkan pandangan jika ketahuan, tetapi Vino tidak pernah punya masalah dengan kontak mata. Dia justru akan membuat ini menjadi kontes ‘ayo kita lihat siapa yang lebih dulu akan melepaskan pandangan’.
Dia tidak pernah kalah.
Ketika matanya dan si perempuan bergaun merah muda saling beradu, Vino pun tidak langsung mundur. Dia memiringkan kepala, menyangga dagunya dengan sebelah tangan yang bersandar di atas meja, mencari posisi terbaik untuk mengamati perempuan itu. Perempuan paling atraktif di rooftop party ini, jika mau jujur.
Alice who?
Di kepalanya, mantan kekasihnya sudah sepenuhnya tersingkirkan oleh si perempuan molek di tengah lantai dansa.
Perpaduan antara sinar bulan di langit malam Singapura dan cahaya violet dari lampu yang menyorot di pesta ini menimpa wajah si perempuan bergaun merah muda. Vino bersumpah ini seperti adegan film ketika perempuan itu melangkahkan kaki jenjangnya meninggalkan lantai dansa dan berjalan ke arahnya, dengan alunan suara Charlie Puth yang masih terdengar sebagai latar suasana.
Dia penuh rasa percaya diri, pikir Vino selagi mengamati cara perempuan itu berjalan dengan stiletto putih entah berapa senti di kakinya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Vino mengangkat alis ketika menyadari air muka perempuan itu yang tidak secerah ketika di lantai dansa beberapa saat lalu, dia kelihatan seperti campuran penasaran dan terganggu.
Tidak, dia sedang mencari apa yang sebenarnya dia inginkan.
Apa yang kamu inginkan?
“Hello.”
Satu sapaan barusan membuyarkan monolog di kepala Vino, lelaki berpostur jangkung itu secara otomatis menegakkan tubuhnya untuk membenarkan caranya berdiri ketika perempuan bergaun merah muda itu akhirnya sampai di hadapannya.
Malam ini, Vino merapikan diri cukup baik dengan mengenakan kemeja putih dan blazer hitam, bahkan menyempatkan diri untuk cukuran dan menyemprotkan parfum beraroma white musk.
Agenda memenangkan kembali mantan kekasih sudah berganti menjadi membuat seorang perempuan cantik lain terkesan hanya dalam hitungan menit.
Dilihat dari dekat pun perempuan itu semakin menawan. Kulitnya seputih susu, sepasang mata cokelatnya begitu jernih, pulasan makeup di wajahnya terlihat natural, dan aroma manis campuran jasmine dan vanila yang memabukkan langsung tertangkap indra penciuman Vino.
Dia seperti baru saja berhadapan langsung dengan malaikat yang terlihat.
Vino berdehem, agar dia tidak dikira sebagai orang bodoh selain penguntit. “Hey.”
Perempuan itu menarik kurva bibirnya yang dilapisi lipstik merah menyala membentuk senyuman menantang. “So, you like what you see?”
Busted.
Vino balas tersenyum kalem. Dia tidak begitu khawatir karena perempuan itu toh tidak kelihatan marah atau tidak nyaman seperti orang kebanyakan saat dia pandangi terus-terusan.
Dia ingin validasi.
Dia ingin tahu kenapa aku memandanginya.
Tidak, dia tahu kenapa aku memandanginya, dia hanya ingin mendengarnya.
“Sorry...” That’s my dyslexia thing, yep, mana mungkin bilang begitu pada pertemuan pertama. Vino meloloskan tawa pelan, sekaligus mencoba mengetes tebakannya dengan mengatakan, “Kamu perempuan paling cantik yang aku lihat di pesta ini.”
Tidak buruk, dia tidak sepenuhnya berdusta ketika mengatakannya.
Perempuan itu terlihat terkejut dengan jawaban straightforward Vino yang dikatakan dengan begitu tenang. Sepasang alisnya terangkat, tetapi ekspresi tidak percaya itu secara cepat berganti dengan raut terhibur. “Kamu sudah melihat semua perempuan yang ada di pesta ini sampai bisa membuat pernyataan itu?”
Oke, perempuan ini seratus persen orang Indonesia.
Senyuman Vino mengembang lebih lebar. “Kebalikannya, mataku dari tadi hanya tertuju pada satu perempuan. Tapi lalu aku melihatmu, dan aku langsung lupa dengan perempuan sebelumnya.”
“Aku nggak tahu apa aku harus tersanjung karena pujian itu, atau aku harus takut karena kemungkinan kamu adalah pembunuh berantai yang sedang mengincarku.”
Vino kali ini tertawa dengan lebih lepas. Perempuan ini cerdas dan punya selera humor. “Kamu benar, karena kamu sangat cantik, kamu harus berhati-hati jika ada seseorang yang memandangimu terus atau mengikutimu. Lapor ke polisi kalau ada yang mencurigakan.”
Vino menyadari bibir perempuan itu berkedut tiap kali dia menyebutnya cantik. Dia menyukai pujian, Vino menyimpulkan, dia butuh pengakuan.
“Apa itu artinya aku juga harus berhati-hati sama kamu?”
“Mungkin.” Untuk alasan yang lain. Daripada membunuhmu, aku lebih ingin mengabadikanmu dalam tinta di atas lembaran jurnalku, memujamu dalam tiap cara yang aku tahu. Vino buru-buru menambahkan, “FYI, aku bukan pembunuh berantai. Aku cuma penulis.”
Perempuan itu terlihat tertarik mendengarnya. “Oh, ya? Apa yang kamu tulis?”
“Macam-macam. Dongeng, prosa, cerita pendek.” Vino mengerling ke arahnya, “Atau puisi tentang matamu.”
Dia rasa dia baru saja melelehkan gunung es jika melihat ekspresi wajah perempuan bergaun merah muda itu ketika mendengar balasannya. Perempuan itu tampak kehilangan kata seakan tidak mengantisipasi jawaban itu sebelumnya, dia menggigir bibir bawahnya dan memberi Vino tatapan terpana.
Mereka hanya saling bertatapan untuk beberapa saat tanpa ada kalimat lanjutan, dan Vino memutuskan bahwa sekarang waktunya dia mengenalkan diri pada perempuan yang sudah merebut hatinya pada pandangan pertama.
“Vino.” Dia mengulurkan tangan dengan penuh percaya diri.
Uluran itu bersambut, Vino menjabat jemari kurus perempuan itu untuk sekelebat.
“Freya.”
Freya. Freya. Freya.
Nama itu bergema di telinganya berulang-ulang, dan Vino suka bagaimana nama itu terdengar. Nama itu begitu cocok, begitu tepat. Nama yang sama dengan dewi cinta dan kecantikan dari mitologi Nordik. Sungguh, tidak ada nama lain di muka bumi yang lebih tepat untuk perempuan ini selain Freya.
Dia bahkan berpikir dia ingin melenyapkan seluruh pemilik nama Freya yang ada di dunia—termasuk sang dewi Nordik yang menurut mitologi ada di Fólkvangr (jangan minta Vino untuk mengeja itu, memikirkan kata itu saja membuatnya pening)—hanya untuk menyisakan Freya di hadapannya sebagai pemilik nama itu satu-satunya.
Lelaki dua puluh empat tahun ini biasanya buruk dengan nama. Dia bisa mengingat detail terkecil seperti warna sepatu, wangi parfum, atau letak persis tahi lalat seseorang; tetapi mengingat nama selalu menjadi satu dari kelemahannya.
Namun, yang satu ini adalah pengecualian. Persetan dengan otaknya yang bekerja dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang, dia akan memenuhi isi kepalanya dengan nama Freya sampai hanya itu satu-satunya yang bisa dia pikirkan.
“Mau ngobrol di tempat lain?”
Karena kebisingan pesta tidak pernah menjadi tempat favorit seorang Vino Giffari Bharata, dentuman kencang musik dan suara-suara tumpang tindih yang ada sering memberinya rasa gelisah. Jika sebelumnya dia menyiksa dirinya sendiri dengan mendatangi pesta ini demi mantan kekasih, itu hal yang tepat jika sekarang dia hendak membebaskan diri dengan meninggalkan keramaian ini bersama perempuan lain.
Vino kembali mengulurkan tangan, karena untuk satu dan lain hal, dia punya keyakinan bahwa perempuan itu tidak akan menolak ajakannya.
Dia sedang mencari apa yang dia inginkan.
Dia menyukai tantangan.
Freya mengulum senyum seakan dirinya sendiri pun tahu dia tidak mungkin menolak. Tangannya meraih tangan Vino, kali ini untuk waktu yang lebih lama dari sebelumnya. “Lead the way.”
Caranya mengatakan itu terdengar seperti ‘kejutkan aku, bawa aku pergi ke tempat yang seru’. Pikir Vino dengan begitu egoisnya: ini pertama kali kita berjumpa, dan hal pertama yang ingin kulakukan adalah membawamu pergi sejauh-jauhnya.
Mereka meninggalkan pesta itu tanpa berpikir lama, berlari-lari kecil menuruni tiap anak tangga seperti sepasang bocah yang baru saja ketahuan memecahkan kaca jendela, tertawa seperti orang gila ketika melewati tamu-tamu pesta yang menatap mereka penuh tanda tanya.
Ketika mereka sudah sampai di anak tangga terakhir, kaki Freya tersandung dan membuat keseimbangannya oleng. Dia terjatuh tepat di pelukan Vino yang seperti sudah berdiri dengan siaga untuk menangkapnya.
Vino memejamkan mata, menikmati sensasi kehangatan malaikat tak bersayap yang berada dalam dekapannya. Semerbak harum mawar tercium dari rambut bergelombang kecokelatan Freya. Satu tangan Vino masih menggenggam jemari sang dewi, sementara tangan yang lain menahan pinggang ramping itu dengan taraf sopan.
“Aku rasa aku jatuh cinta.” Gumamnya begitu saja, setelah melepaskan pegangannya.
Freya memandangnya tak percaya, perempuan dengan tinggi badan sekitar seratus enam puluh enam senti itu pun tertawa. “Apa ini nggak terlalu cepat?”
“Cinta bukan masalah waktu.”
Para pencinta di dunia tidak butuh waktu lama untuk mendeklarasikan cinta mereka, cukup dengan satu pandangan untuk menciptakan ratusan puisi tentang senyumnya.
Mereka cepat mati juga, Windra yang selalu pesimis pernah mengatakan itu suatu waktu sambil geleng-geleng kepala, mereka semua sangat konyol karena begitu mengagungkan cinta. Vino biasanya menurut pada kakak lelakinya, tetapi untuk hal satu ini dia enggan mendengarkan.
Dia lebih suka jadi budak cinta daripada budak korporat seperti Windra Gazali Bharata.
“Kamu bahkan hanya tahu namaku.” Perempuan di sisinya itu terdengar merajuk.
“Freya.” Vino mengetes nama itu di lidahnya, dan dia menyukainya. “Cukup dengan namamu saja aku aku sudah jatuh cinta.”
Mereka berjalan bergandengan tangan meninggalkan bangunan yang menjadi venue pesta para mahasiswa di Singapura, dentuman musik dan hingar-bingar yang terjadi di atap bagai angin lalu yang mengiringi kepergian keduanya. Ini sangat aneh karena mereka baru saja bertemu, tetapi sudah begitu intim layaknya sepasang kekasih. Orang-orang di sepanjang Dunlop Street yang melihat kebersaman mereka malam ini akan berpikir keduanya sudah menjalin hubungan bertahun-tahun.
“Apa aku harus tersanjung atau takut?” Freya kembali buka suara, dengan nada tanya yang kurang lebih sama seperti beberapa saat lalu ketika Vino menyebutnya perempuan paling cantik di pesta itu. “Karena kata-katamu sejujurnya sangat mengerikan untuk dikatakan pada pertemuan pertama.”
“Kamu benar, jangan semudah itu percaya pada seseorang yang baru kamu temui dan sudah menyatakan cinta. Kemungkinan besar dia orang gila.”
“Jadi, kamu orang gila?”
“Ya, gila karena kamu.”
“Kamu mengatakannya seperti itu salahku.”
“Siapa yang menyalahkanmu? Aku jatuh cinta padamu itu urusanku, bukan urusanmu.”
Vino menghentikan langkahnya, membuat Freya otomatis ikut berhenti melangkah dan memberinya tatapan bertanya.
“Mau bermain?” Lelaki dengan tinggi badan seratus tujuh delapan senti itu memberi penawaran dengan cengiran kekanakan, Freya yang mengenakan stilleto hanya mencapai telinganya dari posisi mereka berdiri saat ini. “Caranya mudah, aku akan memberikan kencan paling fantastis dalam hidupmu untuk malam ini, yang perlu kamu lakukan cuma satu.”
Mata jernih Freya berkilat-kilat, mata paling indah se-Singapura, ada sorot penasaran di sana. “Apa?”
“Jatuh cinta padaku.”
Perempuan itu tertawa, lebih karena terhibur alih-alih mengejek. Dia memandang Vino seakan menunggu lanjutannya, dan dia akhirnya sadar kalau lelaki ini tidak sedang bercanda.
“Bagaimana jika sampai kencan berakhir aku belum juga jatuh cinta padamu?” tanya Freya dengan nada jenaka.
“Berarti kamu menang, lalu aku akan berbesar hati untuk mundur dan mengakui kekalahanku.”
Seorang pencinta sejati tidak pernah memaksakan kehendak, mereka akan mencintai sampai mati tanpa mengharapkan balasan.
Atau, setidaknya itu yang selama ini Vino coba lakukan. Walau untuk kasus-kasus tertentu, sifat obsesifnya lebih sering mengambil alih dan membuat perempuan-perempuan yang pernah mengisi hatinya pergi tanpa pernah kembali.
Namun, itu cerita untuk lain kali.
Freya adalah lembaran kertas putih bersih yang menunggu untuk dia tulis dengan tintanya.
“Deal.”
Dan kisah mereka resmi dimulai.


 firaisred
firaisred