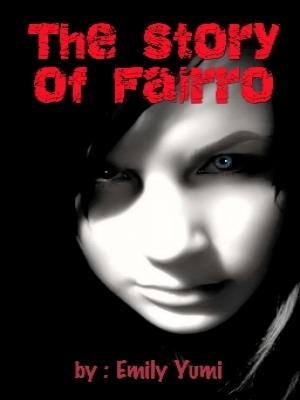“Aku jatuh cinta padamu, tapi kini kau telah berlalu, tinggalkan rasa rindu, jadi belenggu didalam hatiku”. Lirik senandung lawas yang dilantunkan oleh Poppy Mercury tiba-tiba saja membuka jendela khayalku, membawaku pada nostalgia. Namanya Hasanah, gadis keturunan totok Batak, yang kecantikan dan ke ayuannya sering kudengar terlontar dari mulut para lelaki pemuja kecantikan. Berasal dari desa Sabahotang, sebuah perkampungan yang jauh dari kebisingan, seperti lainnya, desa itu menawarkan ketenangan dan keindahan pemandangan sawah, ladang, dan juga pegunungan.
Semasa kecil, ia dan kedua orang tuanya tinggal di luar Sibuhuan. Padang Bolak adalah desa kelahirannya. Lalu imigrasi ke Sibuhuan dan berdomisili di Sabahotang, kec. Barumun, Padang Lawas hingga sekarang.
Setelah merampungkan Sekolah Dasar (SD) di tanah kelahirannya, gadis tangguh yang sampai sekarang belum mampu kutaklukan itu melanjutkan pendidikan jenjang Tsanawiyahnya di Al-Mukhlishin, sebuah pondok pesantren yang terletak di Sibuhuan, didirikan oleh Syekh Mukhtar Muda Nasution, ulama besar jebolan Makkah ini kemudian meng-amanahkan Ponpes ini kepada Ust Fauzan Nasution, sang punggawa Quran lulusan PTIQ, Jakarta.
Dan jauh di seberang sana, kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan itu, terdapat seorang remaja yang arah dan tujuan hidupnya ntah kemana. selain ke sehariannya dihabiskan hanya bermain catur, merokok, dan nongkrong di warung kopi dengan remaja-remaja berandalan lainnya, juga adalah seorang anak durhaka yang sama sekali tidak memilki rasa hormat kepada orang tua, yang bisanya hanya meronta dan membentak jika keinginannya tak terpenuhi. Ibarat debu yang terhembus angin melanglang buana, tidak berpijak di bumi juga tak di langit. Bertolak belakang sekali, bukan? Jika gadis itu adalah jelmaan Malaikat, maka remaja itu jelmaan Iblis. Namanya Zainuddin, iya, remaja itu adalah aku.
Tahun 2012, aku yang telah berusia 18 tahun mengikuti ujian Paket B, ijazahnya setara dengan SMP. Setelah itu, aku memberanikan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang MA/SMA yang lebih formal dari sebelumnya. “aku masih ingat, sore, sehari sebelum hari pertama ikut berkecimpung dalam dunia pendidikan formal, aku menangis di atas bangku itu, sebab untuk menjemput celana sekolah ke tukang jahit untuk di pendekkan, aku tak punya uang”, kisahku dengan hati nelengsa dalam buku harianku.
Secara kebetulan atau tidak, di Ponpes ini, dua yang tidak sejoli itu bertemu, di satukan oleh niat dan tujuan yang sama, meski akhirnya terpisah oleh cita dan tujuan yang tidak sama.
Rasanya tiga tahun cepat sekali berlalu, aku yang belum mengenalnya merasa menyesal. Hanya yang kutahu ketika itu, dia seorang gadis yang bersifat ke ibuan, dan meski bukan seorang hafizhoh tapi aku melihat Quran dalam diri dan kesehariannya.
Ah tapi barangkali, aku yang terlalu jauh dan berlebihan.
Terlalu jauh mengaguminya, dan terlalu berlebihan menyanjungnya.
Di bawah naungan Pesantren itu, aku dan dia sama-sama mengukir cita diri masing-masing.
Di bawah naungan Pesantren itu, aku jatuh cinta pada gadis itu.
Di bawah naungan Pesantren itu pula, remaja jelmaan Iblis itu telah berubah, seolah sekarang ia adalah jelmaan Malaikat. Nilai-nilai Pesantren yang di tanamkan telah tumbuh dalam dirinya, dan bahkan telah beranting. Kini, ia orang nomor satu di Pesantren itu, sekarang, siapa yang tidak mengenalnya di lingkungan itu? sebab bukan hanya santri dan santriwati, dan bahkan semua tenaga edukasi tergeragap dengan prestasinya menjadi juara 1 (umum) diantara ribuan siswa-siswi, mengalahkan mereka yang telah belajar 6 tahun, mengalahkan mereka yang sejak Tsanawiyah harus bangun pagi-pagi lalu duduk manis di depan papan tulis, mengalahkan para penghafal-hafal yang Qiyamullailnya tidak pernah tinggal.
Akan tetapi, Sebagai santri yang kesehariannya adalah belajar, belajar dan belajar, nasihat dan siraman rohani sebagai makanan pokok setiap hari. Mengharuskan hal-hal yang bersifat seperti itu tidak menjadi prioritas hidup sehingga tidak menggubrisnya, dan lebih memilih memendam rasa hingga datang waktu yang tepat.
Tgk. Zubair Hasibuan, ulama zuhud lulusan Aceh, tokoh sufi yang dikenal tegas menegakan Syariat, berdakwah, dan beramar makruf nahi munkar ini adalah guru robbani (spiritual) ku, dimalam hari aku mengikuti tawajuh (praktek sufisme) dan di siangnya belajar/mengaji kitab tashawwuf karya Goust Al-A’zhom, imam Al-Ghozali, Ihya Ulumiddin kepada ulama karismatik ini.
“Memandang wanita, bisa menghalangi hati menerima ilmu agama. Memandang wanita, bisa menghilangkan ilmu yang telah di pelajari”. Titah beliau kepadaku dalam bahasa batak Mandailing.
Beranjak dari sini, aku terpaksa mengubur, melupakan, dan menghapus yang namanya cinta untuk sekarang. Berbagai usaha dicari dan dicoba, hingga akhirnya berhasil, meski belum sepenuhnya, tapi setidaknya ia tidak terlalu mengusik hati lagi.
Mei 2015 adalah tahun akhir dari jenjang MA/SMA kami, yang menandakan semuanya, tak terkecuali aku dan gadis itu, harus berpisah. Setiap diri memilih jalan hidup masing-masing. Simbol santri/wati seketika itu terlepas begitu saja dari diri, dan rasanya setengah harga diri hilang begitu saja.
Jauh sebelum perpisahan, aku sering memandangi wajahnya sambil mengandai-andai, “ jikalau dirimulah, jikalau dirimulah…”, tapi gadis itu tak pernah terpanah dengan lirikanku. Dan bahkan, aku tunggang-langgang mencuri perhatiannya. “kebetulan, ketika mengikuti ujian nasional (UN), kami diwajibkan untuk tinggal di Ponpes, santri di pondok dan santriwati di asrama. Malam terakhir, aku dapat giliran untuk mengimami sholat Shubuh, dan seperti malam-malam sebelumnya, para akhowat pun ikut jamaah di belakang. Sengaja ku pilih surat Ar-Rahman ayat setelah Al-Fatihah demi mencari perhatiannya, tapi sayang, malam itu satupun dari mereka tidak ada yang ke mesjid, mereka telat bangun sehingga sholat di asrama. Yah, usahaku gagal , nonsens, hahh”. Kenangku sambil menyungging senyum.
Setelah itu, hanya sesekali atau sama sekali tidak pernah ada lagi pertemuan, masing-masing terseret kesibukan, aku sibuk menyiapkan segala keperluan berupa administrasi beasiswaku, karna alhamdulilah, aku sedikit lebih beruntung di banding kawan seangkatan, aku memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi S1 ke negeri Ibnu Batutoh, Maroko. Begitupun dengan yang lainnya, sibuk dengan kepentingan masing-masing.
20 september 2015, untuk pertama kalinya aku menginjakan kaki ke bumi seribu wali ini, maroko, lingkungan dan budaya yang tentu berbeda sekali. Negeri ini menawarkan gaya hidup baru, bahasa baru, kultur baru, dan satu lagi, negeri ini menawarkan dara-dara jelita yang kecantikannya tak kutemukan di negeriku sendiri. Dengan cepat, aku mampu beradaptasi, gaya hidup dan bahasa lingkungan baru itu telah menyatu dalam diriku. Hanya, satu yang belum terkikis, dara-dara jelita itu belum mampu memudarkan pesona gadis itu, lirikan tajam para dara jelita itu belum mampu memanahku. “Ah masih saja gadis itu bersemayam di pelupuk mata, laksana daun jatuh ke kedua kelopak mataku, menutup pandanganku dari para dara ini, sehingga pesona mereka tak mampu kunikmati. Dan sebenarnya, aku berharap merekalah yang menjadi ganti dirinya, sayang, semuanya nonsens”. Gumamku sendiri.
Setahun berlalu tinggal di negeri seribu benteng ini, rasa itu belum jua berubah. Dan sebab usia dan jiwa yang telah merasa butuh akan kawan hidup, memberanikanku untuk mencoba mengutarakan “bahwa aku jatuh cinta padanya sejak dibangku MA, dan jika bersedia, aku ingin meminangnya…”.
Lewat Messenger, aku dekati ia, sempat berungkali aku kirim pesan-pesan dengan gaya bahasa terakrab layaknya kawan lama yang sudah lama tidak saling menyapa, tapi nonsens, ia tak menggubrisku. Aku putus asa, dan usaha ku cukupkan sampai disini saja. ini cukup merugikanku, dua minggu setelahnya, nilaiku anjlok di ujian semester tiga dan bahkan setelah mengikuti remedial pun aku terancam tidak lulus.
Tak lama kemudian, aku mengenal kawan karibnya di Facebook melalui seorang temanku. Kepadanya, kuceritakan tentang diriku, bagaimana aku, dan siapa aku, “oh!! jadi kamu orangnya ?” jawabnya spontan. “Iya, saya” balasku.
Laksana kisah uda Zainuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wick, setengah mati dan terbaring berbulan di kamar setelah membaca surat balasan dari Hayati bahwa “pernikahan itu adalah pilihannya”. Laksana ujung panah tertusuk tepat di jantungku setelah mendengar jawaban bahwa ia tak pernah menyukaiku.
Semua usahaku nonsens.
Ku doakan agar jangan ada orang yang melakukan hal seperti ini kepadamu, dan semoga kau bahagia.


 zain
zain