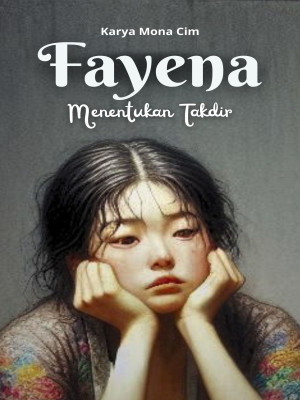Jariku mengetuk-ngetuk meja sambil berpikir. Apa yang sekarang terjadi pada gadis itu? Hidupnya dulu merana, tak tega melihatnya. Gadis itu menghadapi orang-orang yang tak bersahabat. Jika aku menjadinya, lebih baik mati saja. Manusia di dunia ini begitu jahat.
Namaku Rio, seorang siswa SMA 2 yang biasa saja. Wajahku standar, tinggiku cukup, otakku lumayan pintar untuk mendapat nilai di atas 80. Sebuah kacamata bertengger di hidungku. Banyak temanku menyebutku seorang kutu buku atau nerd.
Yah, keluargaku juga biasa saja. Tidak terlalu sepi ataupun ramai. Yang penting kedua orangtuaku tidak pernah bertengkar. Aku memiliki seorang kakak perempuan yang cantik. Dia sudah pergi meninggalkan kota ini untuk melanjutkan studi.
Sayangnya, dalam hidupku ini terjadi sesuatu yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya aku tertarik pada seorang gadis di kelas sebelah. Seorang gadis yang bahkan tidak ingin dipandang orang yang berlalu lalang.
Diva namanya. Seorang gadis bertubuh kurus dengan pakaian yang cukup lusuh. Bisa ditebak kalau dia memakai seragam bekas orang lain. Tidak ada yang menarik darinya. Satu-satunya hal yang kuketahui adalah dia sering ditindas.
***
“Hei, kutu buku,” panggil temanku padaku. Jam kosong merupakan waktu favorit para murid. Namun tidak untukku. Lebih baik belajar daripada bersosialisasi, begitu kataku. Entah bagaimana, seseorang bernama Doni tahan menghadapi kelakuanku. Sering aku bersikap cukup kasar padanya, namun dia tidak menjauh.
“Kenapa, Don?” Di depanku ada sebuah buku cetak fisika. Walau guru fisika kami tidak datang, aku akan tetap mempelajari mata pelajaran ini.
Doni menghela napas. “Nikmatilah hidupmu, Rio. Jika kamu terus menjadi seperti ini, kamu akan stress sendiri. Having a little fun is okay. Don’t push yourself too hard.”
Aku berdiri. “Ayo, ke kantin.”
Doni merangkul pundakku dan berjalan bersama ke kantin. Inilah pertama kalinya aku pergi meninggalkan kelas sebelum jam istirahat tiba. Dan tak kusangka kalau hal berbeda yang kulakukan dari biasanya akan berdampak pada kehidupanku selanjutnya.
“Kamu nonton bola semalam?” tanya Doni, “aku melewatkannya demi membantu ibu.”
“Wah, anak yang sungguh berbakti,” sarkasku. Doni nyengir. Selama ini yang kutahu, Doni bukan orang yang rajin. Memang dia rajin untuk dirinya sendiri, contohnya belajar sebelum ujian. Tapi jika hal itu berurusan dengan orang lain, rasa egoisnya keluar. Pasti alasan membantu ibu adalah sebuah kebohongan.
“Tahu aja aku bohong. Memang kamu teman terbaikku,” seru Doni.
“Ah, ini pasti kebohongan juga. Iya, kan?” tanyaku.
Tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu menghantam tembok. Aku dan Doni mengintip ke sumber suara itu. Ruang peralatan yang bisa disebut gudang adalah tempatnya. Seorang gadis yang berpakaian lusuh ditendang oleh beberapa orang.
“Itu geng terbesar di sekolah kita. Apa yang harus kita lakukan? Anak itu bisa mati,” bisik Doni padaku. Aku mengangkat bahu tidak tahu.
“Masa bodoh,” kataku dan beranjak pergi. Walau di dalam ini, hati nuraniku berteriak untuk membantu gadis itu. Aku menguatkan tekad dan berjalan pergi. Toh, alasan aku keluar dari kelas adalah makan di kantin.
Doni menoleh beberapa kali ke ruang itu sebelum mengikuti aku menuju kantin. Bisa ditebak kalau dia merasakan hal yang sama. Rasanya ini tidak benar. Apakah aku harus membantunya? Sayangnya, rasa sosialku tidak setinggi itu sampai aku memiliki niat untuk membantu orang. Biar saja. Toh, bukan urusanku.
***
Hujan turun. Terpaksa, aku harus menunggu hujan reda di halte bus. Mayoritas murid di sekolah ini dijemput dengan mobil. Berbeda denganku yang berekonomi secara pas-pasan, membuatku harus menaiki bus, bahkan berjalan kaki pulang.
“Hah,” desahku lelah. Rasa tidak mengenakkan apa ini? Kenapa rasanya ada sesuatu yang salah? Apa ada sesuatu yang seharusnya kulakukan? Langsung teringat olehku akan gadis yang ditindas itu setelah melihat orang yang bersangkutan muncul di sebelahnya.
Wajahnya lebam, banyak plester di tangan dan kakinya. Untuk sesaat, aku merasa sangat bersalah. Mungkin jika aku membantunya tadi, dia tidak akan terluka seperti ini. Aku terus menatapnya yang duduk di halte yang sama.
Dia menatapku. “Jangan kasihani aku. Aku bukan orang yang menyedihkan hingga perlu dikasihani. Aku hanyalah orang yang kurang beruntung,” katanya tiba-tiba. Suaranya enak didengar, seperti kicauan burung nightingale.
“Aku tidak mengasihanimu,” sanggahku.
Dia menatapku lekat. “Wajahmu mengatakannya.”
“Wah, anak yang sungguh aneh. Bagaimana dia bisa menafsirkan perkataan dari wajah seseorang,” pikirku.
Gadis itu menatap hujan yang masih turun. “Kau tahu apa yang kupikirkan saat melihat hujan?” Aku menggeleng. Dia tersenyum kecil saat melihat responku dari ujung matanya. “Hujan adalah sesuatu yang kuat. Walau dia terjatuh ke tanah dan tak bisa bergerak lagi, dia mencari cara untuk kembali ke atas.”
“Saat berada di tanah pun dia memberikan manfaat bagi makhluk lain seperti tumbuhan. Lalu dia akan mengalir hingga menemukan suatu tempat bernama laut. Matahari menolongnya kembali menjadi sebuah uap. Itulah saatnya di mana segala perih di kehidupan menghilang,” ceritanya. Aku mengerutkan dahi. Bagaimana bisa hujan diartikan seperti itu? Menurutku, hujan hanyalah sebuah beban dan pembangkit memori masa lalu. Aku tidak tahu kalau ada makna seperti ini di balik kata hujan.
“Walau begitu, sang hujan yang kini menjadi uap tidak lupa akan penderitaannya saat dalam proses kembali ke awan. Bahkan dia melewati berkali-kali fase itu. Memang, dia sangat kuat.” Gadis itu tersenyum. Kali ini, bisa dilihat senyumnya sangat manis. Di balik luka memar di wajahnya, ada lengkungan kecil yang muncul.
“Apa ini cerita tentangmu?” tebakku.
Dia mengangguk. “Ya. Aku selalu ingin kuat seperti hujan. Penderitaan memang sering terjadi, namun ada kalanya rasa tenang berada dalam hati. Penderitaan itu bisa hilang, tapi tidak bisa dilupakan. Penderitaan yang terlihat buruk, bisa juga menjadi sesuatu yang positif.”
“Positif bagaimana? Penindasan yang dilakukan atasmu tidak memiliki nilai positif di dalamnya.” Aku menggaruk tengkuk karena bingung. Gadis di sebelahnya memiliki cara pandang yang berbeda.
“Kau tahu, setiap kali aku ditindas, aku belajar untuk bersabar. Sabar itu memang sulit didapatkan seseorang. Tapi sabar bukan berarti pasrah. Di sela-sela waktu aku ditindas, aku mengumpulkan keberanian untuk menasihati mereka.” Gadis itu tersenyum. “Jika kamu melakukannya, rasa sakit ini akan hilang. Rasa bangga muncul karena sudah melakukan hal yang benar walau diperlakukan secara salah.”
“Kamu benar-benar kuat.”
***
Kali kedua aku melihatnya ditindas adalah saat pelajaran olahraga. Olahraga dilakukan secara serempak oleh beberapa kelas. Karena itu, guru olahraga tidak akan tahu siapa yang tidak hadir. Di saat itulah, Diva kembali tertindas.
Bertempat di belakang sekolah yang sangat sepi, tempat pribadi para murid untuk melakukan transaksi ilegal hingga menyiksa orang. Aku mengetahuinya di pagi itu. Bola bergulir melewati lapangan. Tendangan Doni memang selalu yang terbaik. Sayangnya, orang kesulitan untuk mengambil bolanya.
Sampailah bola itu di dekat tempat itu. Terdengar suara yang membuat bulu kudukku berdiri. Apa aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja kudengar itu suara bata yang dihantamkan?
“Hei, dia pingsan,” seru seorang anggota geng. Mereka terdengar panik. Aku hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Banyak luka kudapat dari rantingnya yang tajam, namun kutahan. Aku tidak ingin ketahuan oleh mereka. Bola yang kukejar ditinggalkan.
Beberapa waktu kemudian, langkah mereka tak terdengar lagi. Aku menghembuskan napas lega dan keluar dari tempat persembunyianku. Kini saatnya mengetahui yang terjadi. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat kepala Diva berdarah. Aku panik. Aku berlari menghampiri guru olahraga kami.
“Pak, tolong saya!” seruku panik.
“Saya sedang sibuk. Saya tidak bisa menolong kamu. Urus hal itu sendiri. Memangnya saya siapa?” gerutu guru olahraga itu. Aku benar-benar kesal. Tak bisakah dia membantuku sejenak?
Aku kembali ke tempat itu. Kugendong Diva dan kubawa ke UKS. Perawat yang ada di sana sangat terkejut. Untungnya dia handal. Beberapa menit kemudian, kepala Diva sudah dibalut.
“Sekarang kita hanya perlu membawanya ke rumah sakit. Kamu mau ikut?” tanya perawat itu padaku. Tentu saja aku mengangguk.
***
“Kondisinya sangat kritis. Kecil sekali kemungkinan untuknya selamat. Tapi kami akan tetap mengusahakan yang terbaik,” kata seorang dokter. Perawat sekolah dan aku menarik napas dan berpikiran positif.
“Apakah Diva selalu ditindas, nak?” tanyanya.
Aku mengangguk. “Walau begitu, dia benar-benar kuat. Aku tak pernah melihat orang yang sekuat dirinya. Bahkan dia mencoba untuk terus bersabar walaupun dirinya diperlakukan seperti ini.”
Perawat itu termenung. “Kalau saja semua orang seperti dirinya. Yang berpikiran jauh ke depan. Yang berpikiran terbuka. Yang tidak mendendam. Pasti dunia ini akan berjalan dengan baik.”
Aku mengiyakan. Seseorang seperti Diva itu langka.
***
Matanya mengerjap, membiasakan diri dengan cahaya. Diva telah siuman. Walau kemungkinan hidupnya sangat kecil, dia mampu melewati semua itu. “Aku selamat?”
Aku mengangguk. Dia menangis terharu. “Kenapa menangis?” tanyaku.
“Kesakitan selalu ingin aku hindari. Tapi aku tidak bisa memikirkan jika semua ini sungguh berakhir,” katanya. Aku tidak mengerti. “Aku kira aku akan mati,” jelasnya.
Aku mengelus kepala Diva lembut. “Apa yang akan kamu lakukan pada mereka. Tampaknya kepalamu tidak akan sembuh dengan cepat.”
“Apa lagi? Tentu saja memaafkan mereka,” jawab Diva tanpa ragu.
“Kamu benar-benar aneh,” cibirku, “bagaimana bisa kamu sebaik ini pada orang-orang yang jahat padamu?”
“Caranya hanya satu. Jangan biarkan kebencian masuk ke dalam hati. Jika kamu bisa melakukan itu, rasa tenang dan damai dalam hati selalu ada dalam dirimu.” Diva tersenyum lagi.
***
Beberapa bulan kemudian, Diva masuk sekolah. Luka di kepalanya sudah sembuh. Dia berjalan ke ruang kepala sekolah. Satu hal yang kuketahui tentang guru olahraga yang tidak bertanggung jawab itu adalah dipecat. Bahkan nama baiknya telah tercoreng di setiap tempat.
“Hei,” sapaku saat berpapasan dengannya. Dia membalas dengan melambaikan tangannya. “Ke kelas?”
“Tidak,” gelengnya, “hari ini aku datang untuk memberitahu kepala sekolah aku akan pindah sekolah.”
“Hei, jangan bercanda.” Aku mulai kesal. “Katamu kamu akan memaafkan mereka? Kenapa malah pergi? Bukankah kamu akan terus menasihati mereka agar menyadari kesalahan mereka?”
Dia menggeleng. “Aku sudah sampai di ujung batas. Aku harus pindah sebelum rasa benci memasuki hatiku. Aku harus pergi agar memulai hidup yang baru. Dari kejadian saat itu, aku menyadari kalau diri orang sulit untuk dirubah.”
Aku menghela napas pasrah.
“Terima kasih sudah mau menjadi temanku. Aku pamit pergi.” Dia pergi dari sekolah.
***
Lama berlalu tanpa kehadirannya. Kini, aku adalah seorang laki-laki berusia 21 tahun. Hidupku kembali seperti biasa, seperti sebelum bertemu dengan gadis itu. Aku mengubah siaran TV. Tak ada yang menarik.
“Dulu saya sering ditindas—”
Aku langsung mengenali siapa orang di balik layar itu. Diva, dia kembali dengan keadaan yang berbeda.
“Lalu saya memiliki seorang teman. Dia sangat berjasa dalam hidupku. Kalau saja saat itu dia tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah tak bernyawa,” ceritanya. Senyumnya masih manis seperti dulu.
“Ketahuilah, Diva. Sebenarnya kamulah orang yang berjasa hidupku. Kamu membuka mataku ke sesuatu yang kecil namun berarti. Siapa yang akan mengira hujan memiliki makna seperti itu? Siapa yang sangka seorang remaja berumur 16 tahun bisa berpikiran sangat dewasa. Aku mendapatkan semuanya darimu,” senyumku sambil menatap Diva yang sedang diwawancarai.
“Apakah kamu punya pesan, Diva?” tanya pembawa acara itu.
“Ya. Hai, Rio. Terima kasih sudah mau mendengar pemikiranku di bawah derasnya air hujan saat SMA. Terima kasih juga sudah membawaku ke rumah sakit saat aku hampir terbunuh. Terima kasih sudah menjadi matahari untukku. Sekarang aku sudah berada di awan, dan bersiap untuk kembali menjadi hujan. Pastikan kamu ada di sana saat aku di tanah. Kita akan berjuang bersama.”
Wajah Diva menghilang dari layar. Acara itu sudah berakhir. “Kamu benar-benar orang terkuat yang pernah kutemui. Jangan khawatir. Aku akan bersamamu di kejamnya dunia.”
***


 luv2rit
luv2rit