KISAH INI FIKSI SEMATA, BERSUMBER DARI IMAJINAJIS.
DIHARAPKAN KEBIJAKAN PEMBACA.
NAMUN, TYDACK MENUTUP KEMUNGKINAN TERDAPAT BEBERAPA KESAMAAN DALAM KISAH NYATA KARENA MEMANG DISENGAJA.
***
Diana menyukai aroma karbol. Lebih alami dan membuatnya tenang. Khas sekali dengan rumah sakit. Para asisten rumah tangga di Istana Negara tidak pernah menggunakan pembersih lantai beraroma tersebut. Mungkin ada benarnya juga, mereka ingin membedakan antara rumah sakit dan tempat bernaung presiden.
Selang infus tertancap di tangannya. Ia risih sekali tapi tidak berani mencabutnya. Terakhir kali ia dirawat di rumah sakit adalah ketika sekolah dasar karena penyakit DBD. Sejak saat itu, Diana tidak pernah merasakan kasur putih rumah sakit. Dan ini merupakan kali kedua ia tertidur di kasur ini.
Pintu ruangan kelas satunya dibuka perlahan, menampakan Erik yang membawa beberapa kresek berisi cemilan. "Baikan?" tanya Erik sambil meletakan kresek itu di nakas.
"Lumayan," balas Diana singkat.
Erik menggeret kursi pendek yang berada di sudut ruangan dan meletakannya di samping kasur. Mereka tidak saling bicara selama beberapa menit. Tidak pula memakan atau meminum cemilan. Tidak juga menyentuh handphone. Keduanya terdiam lama, berkutat pada bayangan masing-masing.
"Yang tadi itu... jangan diulangi lagi," ucap Erik lemah, ada sorot khawatir di matanya. "Harusnya lo berlindung di tempat yang aman, bukan—"
"Gue nggak bisa diem aja ngelihat lo dikeroyok," potong Diana sembari bangkit duduk menghadap Erik dari posisi tidurnya yang nyaman. "Semua orang bakal ngelakuin hal yang sama kalau mereka di posisi gue."
Alis tebal Erik terangkat satu. Senyuman miring menghiasi wajahnya. "Semua orang?"
"Semua temen-temen lo," tegas Diana.
"Temen-temen gue? Yakin?" Erik geleng-geleng kepala. "Kadang ada beberapa orang yang memanfaatkan status pertemanan untuk kepentingan lain."
Diana berdecak sebal. "Oh, please. Kita masih di bawah dua puluh tahun, bukan diatas 45 tahun. Kita bukan orang dewasa yang selalu punya cara lihai buat dapetin uang. Satu-satunya hal yang gue manfaatkan dari lo selama kita berteman cuma nama lo yang selalu gue jadiin alasan tiap pulang malem."
Bagaimana pun, Diana remaja biasa yang pernah saja melakukan kebohongan kepada kedua orang tuanya. Tentunya, bukan karena pergi ke club malam atau berkeliling di mall, waktu malam akhir pekan Diana habiskan untuk menonton konser band rock indie, meskipun frekuensinya hanya dalam dua bulan sekali. Diana selalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa Erik ada bersamanya kendati itu tidak selalu benar.
"Diana!" David membuka kasar pintu kamar rawat inap yang ditempati putrinya. Erik dan Diana terkejut bukan main. Julia pun datang setelah David memasuki ruangan sebanyak tiga langkah."Separah apa?" tanyanya yang kemudian merangkul kedua pundak Diana.
"Aku masih mampu meluk Ayah sampai sesak," ucap Diana santai. Kedua tangannya mendekap kuat David tanpa ampun, membuktikan bahwa ia baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan kedua orang tuanya.
"Astaga...." Kini bergantian Julia memeluk anak semata wayangnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahannya karena kekuatan yang Diana isyaratkan lewat pelukan.
"Ibu Julia, Pak David," panggil Erik selembut mungkin. Pemuda delapan belas tahun itu tidak ingin merusak suasana keluarga yang terjadi di depannya. "Saya minta maaf, saya nggak bisa menjaga Diana sebaik yang Ibu dan Bapak harapkan."
Pelukan Julia mengendur untuk Diana. Wanita itu teralihkan oleh ekspresi Erik yang memprihatinkan, bahkan ia merasa Diana jauh lebih baik ketimbang Erik yang tidak sedang memakai tempat tidur rumah sakit. Meskipun sekujur tubuh Erik dipenuhi luka. Matanya bengkak, ujung mulutnya sedikit sobek, ada goresan panjang di pipinya, belum lagi luka lebam yang tertutup oleh jaket berbahan kain yang ia kenakan.
Erik menundukan kepalanya. Satu persatu, lututnya menyentuh lantai. "Saya benar-benar menyesal."
Sebelum Erik bersujud di hadapan suaminya, Julia segera memberhentikan tindakannya tersebut. "Duh, kamu ngapain, Rik? Ayo, berdiri!"
David pun ikut membantu Erik bangkit dari posisi yang menurutnya, tak seharusnya dilakukan. "Saya nggak marah sama kamu. Saya seharusnya yang berterima kasih karena kamu mau menjaga Diana semaksimal mungkin." Tepukan mantap di pundak kirinya memberi kekuatan bagi Erik. "Diana orangnya keras kepala dan nggak mau diatur, saya nggak habis pikir, apa yang membuat kamu betah berteman sama anak saya."
"Nggak apa-apa. Kamu nggak harus merasa bersalah," tambah Julia meyakinkan Erik untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri.
Diana tidak bisa berkata-kata di tempatnya. Di satu sisi ia senang menyaksikan Erik dengan raut melankolis seperti itu karena seumur hidupnya, ia tidak pernah melihat Erik sesedih ini. Tangannya gatal ingin meraih handphone di atas nakas dan mengambil potret ekspresi Erik dari dekat lantas menjadikannya lock screen selama seminggu. Namun, di sisi lain, ia tidak menyangka Erik begitu merasa bersalah hanya karena satu peluru menembus pahanya. Lecet di bagian dagu tak Diana hitung.
"Selamat malam." Tamu ketiga datang di kamar Diana tanpa mengetuk pintu. "Setelah keadaan kamu pulih, bisa Om minta waktu kamu sebagai saksi?"
Permintaan Kapolri Wijaya, Diana sanggupi. "Bisa, Om."
"Rik." Dagu Wijaya bergerak menunjukan arah keluar kamar.
"Waktunya pulang," Erik mengembuskan napas berat dan lekas mengangkat pantatnya dari kursi setelah menerima kode dari ayahnya.
"Selamat istirahat, Dia. Semoga cepat sembuh," ujar Wijaya di ambang pintu kamar sambil mengangkat topi dinasnya.
"Makasih, Om Yaya. Semoga Erik juga lekas sembuh," balas Diana ramah.
Wijaya tidak protes, Diana sudah memanggilnya Yaya semenjak Diana belum mempunyai gigi yang lengkap. Erik pun berpamitan pada Julia dan David. Diana penasaran dengan apa yang dibisikan ibunya kepada Erik yang membuat pemuda itu tertawa.
"Panglima izin pulang dulu, belum ngasih makan Sandy di rumah," kata Erik sambil mengelus pelan puncak kepalanya.
"Tidak diizinkan. Kembali ke tempat!" tolak Diana menunjuk kursi yang tadi Erik duduki.
"Siap." Cepat-cepat Erik duduk dan memasang wajah seserius mungkin seolah sedang mematuhui perintah seorang jendral berpangkat.
Gadis bermata oriental itu memutar bola matanya jengah. "Pulang sana, kalau Sandy mati, gue nggak mau nyari gantinya."
"Lo aja yang jadi gantinya," celetukan Erik diiringi colekan di dagu Diana sebelum ia berlari mendahului ayahnya meninggalkan kamar.
Diana mengerang kesal. Vas bunga yang masih kosong di atas nakas ingin sekali ia fungsikan sebagai alat penghilang ingatan untuk Erik. Tapi ia tidak berkutik. Tangannya diinfus dan kakinya kaku. Ia hanya bisa menyaksikan kedua orang tuanya tertawa akan sikap jail Erik.
"Asem!" umpatnya diam-diam.
***
Diana belum sembuh total, namun ia tidak bisa terus menikmati aroma karbol di rumah sakit. Tugas sekolahnya sudah mulai menumpuk dan yang terpenting, ia tidak ingin semakin banyak perawat serta dokter yang mengetahui dirinya berakhir di rumah sakit akibat ikut terlibat dalam insiden penculikan Eva yang sudah viral. Seluruh paspampres beserta tim Wijaya telah mewanti-wanti pihak rumah sakit agar tidak membeberkan perihal rawat inapnya selama tiga hari ke belakang. Diana sangat bersyukur akan hal itu.
Begitu keluar dari rumah sakit, bukan rumah tujuan utamanya. Melainkan kantor tempat dimana Wijaya bekerja. Mobil kepresidenan sempat mengantri untuk dapat masuk ke dalam kantor polisi. Di saat menunggu itulah mata Diana mulai bosan dan mulai menoleh kesana kemari mencari pemandangan yang bisa menghiburnya.
Ia membuka sedikit kaca mobil dan mengedarkan pandangan menelusuri jalanan beraspal di sekitarnya. Diana tidak menemukan hiburan tapi ia tidak sengaja melihat dua orang pria tengah berbicara serius di luar area kantor. Satu orang berkepala plontos dan satu lagi mengenakan pakaian serba hitam.
Diana mengernyit, memastikan si pria berpakaian serba hitam itu menyelipkan amplop coklat ke dalam jaket yang dikenakan si kepala plontos. Sewaktu mereka berdua bersalaman, Diana menatap ngeri bekas luka seperti tapak kuda yang terdapat di tangan si kepala plontos. Luka itu seperti luka bekas terkena benda panas. Membuat kulit menonjol dan seolah tidak akan hilang selamanya.
Tiba-tiba saja si kepala plontos menoleh ke arah mobil kepresidenan di saat rekannya telah berjalan pergi masuk ke dalam kantor. Diana sempat beradu pandang dengannya sebelum memutuskan untuk cepat-cepat menutup kaca mobil.
Dibantu sang ibu, Diana melangkah perlahan menyeret satu kakinya masuk ke dalam kantor. Luka bekas tembakan peluru di kakinya membutuhkan waktu dua bulan ke depan jika Diana rutin meminum obat yang dokter anjurkan.
Ibu dan anak itu menyusuri tiap bilik ruangan dipandu polisi wanita sampai tiba di sebuah ruangan berpintu besi. Diana mengira ia akan diwawancarai di ruangan dengan kaca dua sisi, tapi perkiraannya meleset.
Polisi wanita itu membuka pintu besi tersebut dan mengisyaratkan Diana masuk. Julia mrmberikan ucapan terima kasih yang dibalas anggukan sopan polisi wanita itu.
"Silahkan masuk," ujar seseorang dari dalam ruangan.
Diana memandang kosong kepergian polisi wanita itu. Satu persatu hipotesa muncul di dalam pikirannya.
"Ayo, Sayang. Mama tunggu di depan ya," ucap Julia mendorong lembut anaknya masuk.
"Duduk," telunjuk orang yang menyuruhnya tadi masuk, mengarahkannya ke sebuah kursi kecil. Diana sedikit kaget sewaktu ibunya menutup pintu dari luar.
Diana ingin menunjukan reaksi kagetnya karena yang mengintrogasinya adalah orang berpakaian serba hitam yang tadi ia lihat di depan kantor. Pakaiannya persis seperti terakhir kali ia lihat. Diana memutuskan untuk menahan ekspresi kagetnya itu dan bereaksi biasa saja seakan ia baru pertama kali bertemu.
Di dalam, sudah ada Wijaya yang tengah melipat dada. Badan atletisnya disandarkan di tembok ruangan yang catnya mulai luntur.
"Nama?" tanya orang berpakaian serba hitam itu sedetik sehabis Diana mengambil posisi duduk di kursi yang berbunyi sewaktu ia mendudukinya.
"Harus saya sebutkan?" tanya Diana balik seraya mendengus.
Orang itu mengibas-ngibaskan tangannya. "Formalitas sajalah."
"Oke. Diana Davidson."
Sugeng. Diana berhasil mendapatkan nama orang yang sedang mengintrograsinya. Kartu tanda pengenal yang Sugeng kalungi berayun ketika ia menyisihkan beberapa map dan mulai mengetik di laptop.
"Usia?"
"Tujuh belas."
"Langsung saja," Sugeng menyandarkan punggungnya di kursi. "Saya sudah mendengar kronologi dari saksi Erik. Dan sekarang, coba ceritakan mengenai kejadian penculikan saudari Eva dari sudut pandang Anda."
Diana melirik Wijaya sekilas. "Singkatnya, saya pulang sekolah, dijemput Erik terus lihat Eva di pinggir jalan. Mungkin nunggu jemputannya."
"Pukul berapa?"
"Sekitar jam lima sore." Jawaban Diana mengalir lancar, selancar gerakan tangan Sugeng yang mengetik di laptop tanpa henti.
"Lanjutkan."
Lampu ruangan tiba-tiba meredup, Diana tidak tahu apa ini hanya perasaannya saja atau hal ini memang disengaja. "Tiba-tiba, ada mobil van menepi ke arah Eva, dua orang keluar dari mobil dan maksa Eva masuk ke dalem mobil." Diana mengambil jeda dengan tarikan disertai hembusan napas. "Saya dan Erik berusaha mengikuti van itu. Kami memang berhasil menyelamatkan Eva tapi... ada korban jiwa."
"Bisa ceritakan mengenai cara Anda dan Erik menyelamatkan Eva?" Sugeng berhenti mengetik. Seluruh pandangannya mengarah pada Diana.
"Semuanya terlalu cepat dan berantakan buat saya. Jadi saya nggak bisa ingat dengan jelas," kata Diana apa adanya.
"Seingatnya saja," paksa Sugeng yang kembali memasang ancang-ancang mengetik.
Keberadaan Wijaya membuat Diana sedikit gugup. Apa Wijaya di sini bertugas menegurnya jika ia ketahuan berbohong?
"Mungkin karena saya panik, saya langsung saja memanah mobil mereka dari belakang."
"Dari mana kamu mendapatkan panah?"
"Saya punya kegiatan memanah di sekolah. Kebetulan waktu itu saya habis latihan memanah."
Sugeng menekan tombol enter beberapa kali di laptopnya. "Lanjutkan lagi."
"Erik bilang harusnya kami mengikuti mereka diam-diam. Mereka langsung berbelok ke pasar dan kami buat banyak keributan di sana. Untungnya, kondisi pasar tidak terlalu ramai mungkin karena sore hari. Begitu keluar dari pasar, van itu menabrak pembatas jalan karena saya menyebarkan banyak kantong minyak ke ban mobil mereka. Saya kira, saya cukup beruntung. Bukannya sedikit nggak masuk akal?" Diana memicingkan matanya.
"Faktor ban gundul, kondisi jalanan aspal sekitar pasar yang habis diguyur hujan, supir mengerem mendadak, minyak yang kamu kasih, semuanya masih bisa diterima. Tapi tentunya bakal kami selidiki lagi," jelas Sugeng. "Anda bilang tadi ada korban jiwa, bisa ceritakan bagaimana korban meninggal?"
Seketika kepala Diana berat. Ia tidak mau mengingat kejadian ini tapi ia harus mulai mengais lembaran memori yang ia tutup rapat.
"Diana?" panggil Sugeng menyadarkan lamunannya.
"Ditembak mati oleh temannya sendiri," ucapnya lemah.
"Kenapa bisa?"
Semuanya berputar di otaknya. Mulai dari pesan terakhir korban yang tidak ia ketahui namanya sampai pembicaraan revolusi yang tidak pernah tuntas. Sugeng menatapnya tajam. Sorotnya penuh intimidasi namun, Diana tidak takut.
"Bilang saja yang sejujurnya, Diana. Percayakan semuanya sama kami." Wijaya turun tangan. Ia menumpu satu tangannya di meja yang membatasi Diana dan Sugeng. "Jangan berbohong."
Melihat Wijaya dan Sugeng menatapnya dengan pandangan menguasai, Diana semakin ragu. Terlebih kecurigaan Diana telah muncul pada Sugeng sebelum ia menginjak ruangan ini. Tepatnya saat Sugeng menyelipkan amplop coklat ke dalam saku jaket pria yang memiliki bekas luka berbentuk seperti tapak kuda.
Om Yaya yang ia kenal tidak pernah semencurigakan ini. Seolah tidak mempercayai semua ucapannya dan memaksanya mengetahui apa yang tidak ia ketahui.
"Temannya coba menyampaikan sesuatu sama saya tapi sebelum tuntas, dia sudah mati," kata Diana sambil menahan napas.
"Apa yang dia bilang?" tanya Sugeng yang ikut mencondongkan tubuhnya.
"Tidak jelas."
"Lebih detailnya?" paksa Sugeng lebih tegas.
Entah dari mana keberanian itu berasal, Diana mencoba menenangkan detak jantungnya dan berkata, "Saya nggak bisa denger dia ngomong apa karena dari jarak lima meter di depan saya, Erik sedang baku tembak sama dua orang preman lain."
"Setelah itu?"
"Pasukan BIN dateng terus saya sama Erik di bawa ke rumah sakit."
Wijaya dan Sugeng berdiskusi lewat pandangan sebelum akhirnya memutuskan.
"Terima kasih, Diana. Kamu bisa keluar dari sini," ucap Wijaya tersenyum tipis.
Diana mengangguk dan setengah berlari keluar ruangan. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Ia menutup kedua wajahnya seraya bergumam, "what are you doing, Diana?"
***
See u next chapter!
Think genius and keep punk


 brainwasher_
brainwasher_












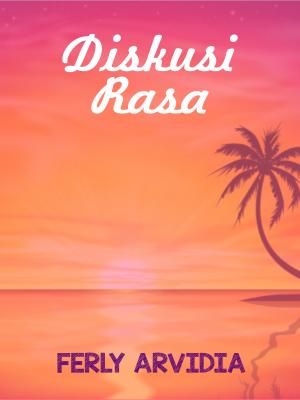
🤩🤩🤩🤩
Comment on chapter Don't be a Good Person: