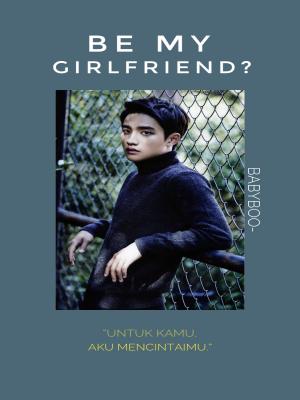Now and Past
I feel that life has become
Too complicated to understand
I question the reason for my being
Meandering through life’s maze
Thinking about you, I ask my self
Is this permanent, or is it just a phase
B r i a n
Malam Minggu mungkin adalah malam yang paling ditunggu-tunggu oleh penghuni maison de rêve –atau mungkin hanya oleh gue. Padahal, gue sendiri gak tahu mau melakukan apa di malam Minggu, karena bagi gue mau malam Minggu kek, mau malam Jumat kliwon, mau malam Senin, semuanya sama aja.
Gak deh, bagi gue yang menakutkan adalah malam Senin, karena besoknya gue harus was was dengan kesiapan otak gue menghadapi cobaan dunia yang datang dan hanya berakhir di akhir semester. Malam Minggu untuk Sena pasti ia isi dengan tidur. Ya iyalah, toh kemarin-kemarinnya gak pernah tidur, wajar sih memanjakan diri sendiri di satu hari.
Malam Minggu gue, biasanya gue isi dengan gabut berat di depan televisi bersama Bang Yoga dan Bang Ijul. Tapi saat ini, Bang Ijul gak ada di sebelah gue, entah kemana dia pergi. Walaupun kegiatan gue dan Bang Yoga memang unfaedah –karena kita hanya menyetel televisi hingga tengah malam tanpa mengerti konten acara yang semakin bobrok itu— setidaknya gue gak tidur melulu seperti si Jhordan yang suara ngoroknya aja bisa terdengar sampai sini.
Dan yang paling gue gak ngerti adalah Dennis dan Cakka akan tetap mengurung diri di kamar. Gue kadang curiga, jangan-jangan mereka bukan belajar tapi nonton film… ah, sudahlah. Jadi pengen ikutan.
“Bang,” panggil gue pada Bang Yoga yang sedang memainkan ponselnya, membuka online shop dan memilih-milih lip balm. “Anjir, Bang, lip balm mah di warung Pak Dudung juga ada, ngapain deh mesti beli online? Ribet.”
Bang Yoga menoyor gue. “Yeuu, suka-suka gue lah.”
“Lagian, Bang, bukannya pacar lo pasti ngasih lip balm tiap bulan?” Tanya gue penasaran. Ya iya penasaran, gue yang jarang bersih-bersih ini sampai ingin membuang semua isi kamar Bang Yoga karena isinya adalah kardus-kardus bekas pemberian pacarnya yang sudah ia tumpuk hingga hampir menyentuh langit-langit kamar.
“Pacar gue?” Tanyanya sok bego. Yeuu, bego beneran kayaknya, sih.
Gue mengangguk. “Iyeee, pacar lo, Bang, masa pacar gue yang ngasih lo lip balm. Itu kardus yang setumpuk itu kan dari pacar lo?”
“Emang lo punya pacar?”
“HAH, CAPEK GUE!” Gue tidak berniat bertanya kembali pada Bang Yoga yang hanya cengengesan. Gue gak mengerti kenapa setiap gue menyinggung sesuatu tentang pacarnya, Bang Yoga pasti mengalihkan topik dan gak menjawab pertanyaan gue.
Ya, kan gue jadi penasaran.
Awas aja kalau gue mati penasaran.
Setahu gue, kotak warna pink atau biru akan mampir ke kosan setiap bulan dengan tujuan Bang Yoga dan diberikan oleh Cakka. Terlalu banyak kenapa yang ingin gue tanyakan pada Bang Yoga. Kenapa si cewek –yang bahkan gue lupa namanya karena gak pernah Bang Yoga kenalin ke kita-kita—gak ngasih langsung. Harusnya, kalau mereka pacaran, si cewek pasti bisa ngasih langsung tuh hadiahnya. Terus, kenapa harus lewat Cakka? Kenapa Bang Yoga kok kayaknya selalu gabut di malam Minggu padahal dia punya pacar?
Ah, udah lah pusing gue. Ngapain juga jomblo kayak gue memenuhi memori dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu.
“Itu mah bukan dari Ditas, Yan. Itu akal-akalan Cakka doang,” jawabnya setelah keheningan panjang. Matanya masih menatap televisi dengan serius –padahal yang ditampilkan hanya iklan-iklan gak penting.
“Ha? Gimana-gimana?” Tanya gue bingung.
Oh iya, gue jadi ingat ceweknya Bang Yoga namanya Ditas. Seinget gue, namanya bagus, tapi apa, ya? Ditas Atlanta? Ditas Atlantis? Yeu, emang Ancol. Ditas Anugrah? Bukan ah, kayak sinetron. Ditas…. Ditas apa, ya?
“Iya, Ditas gak mungkin lah ngasih gue gituan, tiap bulan lagi,” Bang Yoga menghela napas. Kali ini, dari helaan napasnya gue tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan dan sepertinya sangat sakit. Tapi kenapa? “Cakka pasti pura-pura kalau itu dari Ditas, biar gue gak putus sama dia, biar gue tetep kejar dia, biar gue gak menyerah, biar gue merasa kalau Ditas peduli sama gue.”
“Bang,” gue menepuk-nepuk bahu Bang Yoga prihatin. “Bang sebenernya gue sedih, tapi pengen ketawa.”
“Sialan!”
“Iya, habis semenjak lo menyebut nama Ditas, gue jadi ingin mengingat nama panjangnya,” ujar gue. “Ditas apa sih? Atlantis? Seinget gue bagus gitu namanya?”
“Ya gak Atlantis juga, Yan,” entah sudah berapa kali Bang Yoga menoyor kepala gue. “Ditas Alaska. Ditas Alaska Harris,” jawabnya dengan ekspresi yang sulit gue terjemahkan.
Haduh, ini orang sama pacarnya kenapa, sih? Punya pacar ternyata gak sebahagia yang gue pikirkan. Mending jomblo aja kayak gue, no more worry. “Tapi emang Cakka seniat itu beliin lo lip balm tiap bulan? Gue suruh ke warung beli cengek aja dia gak mau.”
“Ya beda itu mah!” Jawab Bang Yoga pelan. “Cengek dan lip balm adalah dua hal yang berbeda. Lo dan gue adalah dua orang yang berbeda bagi Cakka.”
Iya juga, sih. Terkadang gue sangat iri dengan Yoga dan Cakka –kakak adik yang bisa tinggal di satu tempat. Keluarga gue jauh, tinggal di ujung Indonesia. Kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke, keluarga gue benar-benar tinggal di sana, di Sabang. Gue sudah gak pulang selama dua tahun, and it makes me feel so sad.
Mungkin kalau teknologi tidak berkembang seperti sekarang, melihat adik-adik gue tumbuh dan berkembang pun gue gak akan mampu. Rasanya bakal sangat-sangat sedih jika gue pergi lama dan ketika gue kembali, semuanya berubah. Mungkin sofa di rumah yang tadinya menghadap ke barat akan menghadap ke selatan, lantai kamar mandi yang berwarna biru sudah berganti dengan warna cokelat, dan mungkin adik-adik gue yang tingginya dulu sepinggang gue, kini sudah melebihi kakaknya.
“Enak, ya, bisa selalu lihat adek tiap hari,” gumam gue.
Tapi ternyata Bang Yoga mendengarnya dan melirik gue dengan ekor matanya. “Suatu saat lo pasti pulang, Yan,” jawabnya. “Iya, gue tahu, tiket pesawatnya mahal banget, gue juga tahu uang lo bakal habis di jalanan, dan saat lo sampai, lo mungkin gak bawa apa-apa buat keluarga lo atau bahkan sulit untuk kembali ke sini.”
Gue menghela napas panjang. Apa yang dikatakan Bang Yoga memang benar adanya, memang itu yang selalu gue pertimbangkan, memang itu yang selalu gue rasakan, dan gue gak pernah tahu solusinya sampai sekarang –kecuali kalau gue pulang ketika sudah selesai wisuda nanti. Yang gue sendiri tahu, mungkin di wisuda gue nanti, gak akan ada keluarga gue yang datang.
“Tapi, Yan. Lo pasti pulang, lo pasti kembali. Gue tahu lo bukan orang yang sepasrah itu buat gak pulang bertahun-tahun,” lanjut Bang Yoga. “Lo pasti mau berusaha, kan, Yan? Kumpulin uang buat keluarga lo.”
Seakan menampar gue, perkataan Bang Yoga itu membuat gue menatap matanya yang tersenyum –sama dengan bibirnya yang mulai melengkung. Apa yang sudah gue lakukan selama ini? Gue ingin pulang, tapi gue gak berusaha apa-apa. Gue ingin bertemu keluarga gue di sana, tetapi yang gue lakukan hanya berleha-leha. Harusnya, ya, seharusnya kalau gue menginginkan sesuatu, gue harus mengusahakannya.
“Dan selama lo berusaha itu, lo harus tahu sesuatu,” ujar Bang Yoga lagi. “Kita semua keluarga lo. Lo mau anggap gue kakak lo, it’s ok, karena gue emang kakak lo. Ada si Panjul juga, ada temen-temen lo yang setidaknya bisa membuat lo semangat tanpa terus kepikiran masalah yang sama, dan ada Cakka yang bisa lo anggap adik.”
“Bang….”
“Your life must go on,” Bang Yoga menepuk pundak gue. “Lo gak akan tahu jalan keluar kalau lo gak mencoba nyari.” Bang Yoga bangkit dari sofa. “Gue ke atas, ya. Mau tidur.”
Bang Yoga sudah beranjak menuju kamarnya tanpa sempat gue mengucapkan terima kasih. Entah sudah berapa ratus kalimat Bang Yoga yang membuat hati gue tergerak, tetapi sulit untuk membuat seluruh tubuh gue bergerak untuk melakukannya. Bang Yoga benar, kenapa gue hanya diam kalau gue mengharapkan suatu hasil? Emang lo bisa ngerjain soal matematika kalau cuma diliatin doang?
Diam-diam dalam hati gue bertekad, setidaknya gue harus mencari pekerjaan paruh waktu. Jadi pelayan kafe? Jadi penjaga perpustakaan? Atau jadi apa, ya? Gue merasa gak pernah berbakat menjadi apa-apa sehingga pada akhirnya gue menyerah pada diri gue sendiri.
Apa gue ngamen aja di lampu merah bareng Sena dan Bang Ijul? Ya kali, sampai tahun dua ribu lima puluh juga gak akan bisa gue pulang ke sana.
Bersamaan dengan gue yang kepikiran untuk mengamen bareng Bang Julian, sosok Bang Julian masuk dari luar dengan muka yang kusut dan sulit gue tafsirkan. Dan saat matanya bertemu dengan gue, dia tiba-tiba nyengir. Hih, kan serem?
“Lah, Bang, kenapa dah nyengir-nyengir sendiri?”
“Gak,” jawabnya. “Aing lagi sedih. Ke kamar yak.”
Terus kalau lagi sedih kenapa dia nyengir-nyengir gitu? Bang Ijul datang tepat tengah malam dari luar, tiba-tiba nyengir, dan bilang kalau dia sedang sedih. Dia di luar habis ketemu apaan, ya? Dengan berlari kecil, gue menutup dan mengunci semua pintu serta jendela, takut-takut ada sesuatu aneh yang mengenai gue juga.
Handphone gue bergetar dan menampilkan sebuah pesan yang masuk.
[Chilaaa]
Bri, besok anterin gue, dong ke supermarket
Kebiasaan nih bocah belum tidur jam segini, pasti lagi nonton drama Korea kesukaan dia yang udah dia tonton dari semenjak pulang kuliah –mungkin sekarang udah habis enam episode dari sejak saat itu.
[Brian]
Ngapain?
[Chilaaa]
Beli raket nyamuk heheheh.
Demi apa pun beli raket nyamuk buat apaan? Kosannya sangat menjanjikan untuk tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. “Ada-ada aja ni bocah.”
[Brian]
Ya ampun chilaaa buat apaan?
[Chilaaa]
Ya buat matiin nyamuk lah, masa buat nyetrum lo
Ya iya, memang benar. Tapi gimana, ya? Ya begitu, lah. Mau bagaimana pun juga, Chila adalah seseorang yang selalu ada di hidup gue. Ini tuh, beneran ada, gitu. Bukan arti konotasi-konotasi semacam dia-selalu-ada-di-setiap-suka-dan-duka. Dia benar-benar ada karena gue dan Chila belum pernah terpisahkan semenjak bayi. Bahkan bisa dibilang kalau dia selalu ada di saat suka dan tidak ada di saat duka.
Memang benar-benar ni bocah. Setiap gue ada masalah, dia pasti mendengarkan sebentar dan berujung tertawa. Emang dia kira gue lagi ngelawak apa? Setiap saat dia selalu ngintilin gue kemana-mana –kecuali kalau ada jam kuliah yang berbeda. Gue menganggap itu hal wajar sih, toh kita sama-sama teman dari kecil dari Sabang sana, dan jauh dari orang tua. Bagi gue, Chila sudah seperti adik sendiri yang mesti gue jaga. Apalagi di Sabang sana, dia hanya tinggal dengan neneknya yang sudah tua dan sakit.
Chila is calling…
“Oy,” jawab gue.
“Bri, lo belum tidur?”
“Udah,” jawab gue. “Ya belum lah ciloook.”
Chila adalah satu-satunya orang yang akan memanggil gue dengan kata ‘Bri’ ketika yang lain memanggil gue ‘Yan’. Emang terdengar biasa aja dan sama aja, sih. Tapi dia selalu marah-marah sendiri ketika ada orang yang memanggil gue dengan kata ‘Bri’, dih emang lo siapa, Chil.
“Anterin gue ya, besok,” ujarnya dengan nada riang. “Beli raket nyamuk.” Kemudian disusul tawa terkekehnya yang menyebalkan.
“Iyee,” jawab gue. “Imbalannya?”
“Soda gembira?”
“DEAL!”
“Kayaknya lo lebih sayang soda dari pada gue,” jawab dia.
“Emang,” gue mencibir. “Lo lagi ngapain sih anjir jam segini belum tidur? Nonton oppa-oppa Korea? Gantengan juga gue elah, tidur lo. Besok kan lo bisa liat gue.”
“Halah lo sendiri belum tidur,” jawab Chila. Pasti dia sedang ngemil karena samar-samar gue mendengar suara plastik chiki yang dibuka dengan susah payah. “Yah, susah amat, sih.”
“Idih dari TK lo gak bisa buka chiki? Terus nanti kalau lo nikah, lo minta bukain chiki sama siapa kalau gak ada gue?”
Chila mencibir di ujung sana. “Pake gunting lah! Gak mikir lo.”
“Ya udah, kenapa dari tadi gak pake gunting?”
“Mager gue jalannya.”
“Pantesan gendut, mageran sih.”
“BRI, KETEMU-KETEMU GUE TAMPOL, YA!” Jawabnya dengan nada tinggi, membuat gue ingin terbahak-bahak. Cewek emang sesensitif itu ya kalau di bilang gendut? Padahal gendut kan sehat wal afiat.
Tidak bisa dipastikan kapan percakapan gue dan Chila akan berakhir. Gak pernah ada hal penting yang gue dan dia bicarakan, tetapi selalu saja berakhir sampai salah satu dari kita tertidur.
Gue sungkan mengakui, tapi Chila adalah satu-satunya orang yang akan menemani gue ketika gue harus begadang semaleman –padahal alasan tugas gue gak kelar-kelar adalah karena gue mengobrol dengan dia. Gue mungkin seperti supir bagi Chila, yang akan mengantar dia kemana-mana setiap dia butuh sesuatu. Sejujurnya dari hati gue yang paling dalam, gue gak pernah merasa keberatan untuk mengantar dia. Gue lebih khawatir kalau dia harus jalan sendirian di mall dan jadi anak ilang di sana. Ya, walaupun hampir bisa dipastikan bahwa Chila akan selalu menraktir gue setelahnya.
“Chil?” Tanya gue. “Kok diem? Biasanya bacot?”
“Ada yang nangis ya di kosan lo?”
“Ha?”
“Serem ih, merinding gue. Nyanyi apa nangis?” Tanyanya.
Gue mencoba menajamkan pendengaran gue untuk mendengar apa yang Chila dengar. Hanya gue yang tahu kalau pendengaran Chila memang setajam itu. Gue bahkan gak mendengar apa-apa sebelum akhirnya gue mendengar suara dari ujung lantai bawah, lantai yang gue pijaki saat ini.
Tiba-tiba bulu kuduk gue merinding dan rasa-rasanya suhu tubuh gue jadi menurun. “Hantu ya, Bri? Mampus lo,” Chila di ujung sana malah tertawa menyebalkan.
“Diem lo!” Dengan sok berani, gue berjalan mengikuti sumber suara tersebut. Gue gak percaya hantu, tapi telinga gue benar-benar menangkap suara itu. Semua penghuni kosan pasti sudah tidur, jadi ini apa?
“Chil gue tutup ya?”
“Iya, gue juga mau tidur,” jawab Chila. “Tiati lo, nanti tertarik ke alam mereka, daa!” Yeuu, dasar si cilok korban film. “Iya dah sana.” Jawab gue, tapi terlambat, teleponnya sudah ditutup dari tadi.
Suara tersebut semakin jelas ketika gue menambah satu langkah lebih dekat.
“ANJIR KAGET GUE!” Kaki gue menginjak sesuatu cukup keras yang berada di depan gue.
“Ngapain sih anjir mengendap-endap kayak mau nyuri?” Tanya Sena sambil mengusap kakinya yang sudah gue injak tadi.
“Lo turun karena lo denger sesuatu aneh, kan?”
“Ha? Enggak, gue mau ngambil minum. Galon di atas airnya habis,” jawab Sena sambil menggaruk tengkuknya. “Ada apa emang?”
“Ada suara nangis,” jawab gue. “Atau mungkin nyanyi? Dari sana.” Gue menunjuk ujung kosan takut-takut. Sena mengerutkan keningnya dan mencoba menajamkan pendengarannya.
Kemudian tanpa aba-aba, Sena berjalan mendahului gue dan akhirnya berhenti di depan kamar Bang Ijul. “Lo lebay deh, ah. Asalnya dari sini. Mungkin Bang Ijul lagi nyanyi,” jawab Sena.
Iya, benar. Asal suaranya dari kamar Bang Ijul. Ini suara Bang Ijul juga, dia sedang bernyanyi. Ya ampun, bikin gue takut dan jantungan aja, gue kira ada makhluk aneh di sini. Tapi suara nyanyiannya terdengar aneh?
Gak, bukan aneh. Tapi lebih tepatnya…
“Lagunya kok sendu banget, ya kalau dinyanyiin Bang Ijul?” Ujar Sena memecah keheningan, tangan kanannya memegang Tupperware yang selalu ia bawa dan mencak-mencak kalau hilang –takut dimarahi mamanya. Kemudian, ia duduk dan bersandar di dinding depan kamar Bang Ijul.
“Iya, Sen,” jawab gue. “Bang Ijul kenapa, ya? Tadi dia pas masuk bilang, ‘aing lagi sedih’, tapi gue gak tahu kenapa. Harusnya gue nanya kan, ya?” Jawab gue merasa bersalah. Tadi yang seharusnya gue lakukan adalah bertanya dan bukannya berpikiran aneh tentang Bang Ijul yang tiba-tiba nyengir.
Sena menggeleng. “Kadang kalau lagi sedih kita gak butuh pertanyaan orang yang cuma bertanya, ‘Lo kenapa?’ karena rasa penasaran aja. Kadang yang kita butuhkan itu cuma sendirian, tenangin diri,” jawab Sena, lalu berdiri. “Tidur, Yan. Kita tunggu Bang Ijul cerita sendiri. Atau tunggu sampai lo yakin kalau pertanyaan lo untuk Bang Ijul bukan hanya rasa penasaran.”
Sena berlalu dari hadapan gue, sementara itu gue masih terdiam di depan kamar Bang Ijul sambil mendengarkan nyanyiannya yang terasa sangat menyentuh hati gue. Bang Ijul kenapa?
***
J u l i a n
Lo pernah gak sih ketika melihat hujan, lo merasa setiap tetesnya membawa kenangan lo kembali? Mungkin ini agak terdengar lebay, tapi belakangan ini gue sering merasakannya. Entah bagaimana, Bandung yang tidak dianugerahi sebagai kota hujan, akhir-akhir ini malah sering sekali hujan.
Gue sebenarnya gak benci hujan. Walaupun hujan membawa kenangan, setidaknya tidak semua kenangan membawa gue ke sebuah kesedihan tanpa ujung. Sayangnya, kenangan yang kini memenuhi isi kepala gue hanyalah kenangan yang membawa gue kepada kesedihan.
Tadi sore, gue sedang nongkrong-nongkrong gaul di sebuah kafe tengah kota dengan jendela besar yang langsung menghadap ke jalan raya bersama teman-teman himpunan gue. Membicarakan teater yang akan kita laksanakan setengah tahun ke depan adalah agenda pertemuan kali itu. Rapat kita tidak pernah terlalu serius, kadang-kadang diisi oleh candaan –atau mungkin hampir tiga perempatnya diisi oleh candaan. Gue berhasil tertawa lebar, seakan gak pernah ada beban di hati gue.
Malam ini, gue pulang dengan suasana hati yang sudah berubah seratus delapan puluh derajat. Mata gue sore itu menangkap sesosok orang yang tidak pernah gue temui lagi, yang berusaha gue hapus mati-matian dari hati dan pikiran gue.
“Julian?” Tanyanya dengan nada kaget menyaksikan gue yang jarang nongkrong di kafe.
Gue yang dipanggil, tapi seluruh orang di hadapan gue menoleh dengan dramatis saat itu. “Buset, lo kenal Oryza, Jul?” Berniat gak menjawab nada-nada kaget itu, gue malah membuka mulut dengan ragu-ragu. “Temen SMA.”
Orang-orang di hadapan gue yang notabene adalah teman-teman himpunan gue mengangguk-angguk takjub. Mungkin terdengar aneh kali, ya? Seorang Julian yang gak ada apa-apanya bisa mengenal musisi sekaligus aktris yang sudah sering berperan dalam teater ternama? Luar biasa.
Siapa yang gak kenal Oryza Atjana, anak sastra Jepang angkatan dua ribu enam belas yang sering dibilang body goals oleh cewek dan bidadari jatuh dari surga oleh para cowok? Mereka semua gak berlebihan, karena kenyataannya memang begitu.
Mau tahu apa yang lebih luar biasa dari itu semua?
Oryza Atjana adalah mantan gue saat SMA.
See? It’s really amazing.
“Lagi… ngapain, Jul?” Tanyanya sambil tersenyum, rambutnya kini berwarna kecoklatan, pasti sering ditata untuk pentas-pentas yang mungkin sudah ratusan kali ia ikuti. Pentas teater yang terkadang gue impikan juga.
“Rapat,” jawab gue singkat. Membuat Iza –ini dulu panggilan akrab gue pada Oryza—hanya mengangguk-angguk dan mencoba mencari topik. Tapi sebelum ia membuka mulutnya lagi, gue dengan cepat berkata, “Gue rapat dulu, ya.”
Oryza saat itu tidak menjawab, ia hanya menatap gue yang kembali fokus pada rapat. Padahal sama sekali enggak. Boro-boro fokus, yang ada justru gue sangat ingin rapat ini segera kelar. Ya, tapi, dasar manusia-manusia zaman now yang sering bergosip tiada henti, topik rapat sedikit menyimpang dan akhirnya seratus persen menyimpang ketika Oryza benar-benar pergi dari hadapan kita semua.
“Julian? Lo serius dia satu SMA sama lo?” Tanya Kevin dengan mata yang berbinar-binar. “Buset, cantik banget, ya, kalau dilihat dari deket, biasanya kan gue lihat dia dari jauh doang pas ada pementasan teater.”
“Wah gila, Jul, gue kaget banget dia temen lo!” Annisa menggeleng-gelengkan kepalanya. “Gue akan lebih kaget lagi kalau dia itu mantan lo saat SMA, gak mungkin kan? Hahaha.”
Disusul oleh tawa teman-teman gue yang berderai.
Iya, gak mungkin, kan?
Memang, segalanya terasa sangat-sangat tidak mungkin. Mau dipikirkan sejauh apa pun, semuanya terasa aneh. Gue bahkan berusaha keras melupakan bagaimana seorang Julian jatuh cinta pada Oryza saat itu, dan bagaimana seorang Oryza menerima permintaan pacaran dari seorang bocah kelas dua SMA.
Gue tahu semuanya akan berakhir dengan cepat, karena gue dan Oryza hanyalah sebuah ketidakmungkinan.
Tidak mungkin.
Bahkan teman-teman gue baru saja mengatakan hal itu beberapa menit yang lalu. Membuat gue yang tadinya sangat aktif di rapat kali ini –dengan tujuan agar cepat selesai, hanya terdiam di sudut meja, memandang kopi yang mulai mendingin di hadapan gue. Kenapa, sih? Kenapa lo harus datang dan mengingatkan gue akan kita?
Rapat berakhir tepat di pukul delapan malam. Saat itu, hujan masih belum terlalu deras, dan satu persatu teman gue pulang, meninggalkan gue yang masih berdiam dengan alasan ‘gue mau pake wifi-nya dulu’. Ya iya, memang benar. Tapi alasan gue yang lebih besar adalah karena seorang Oryza Atjana masih berada di sana, di bangku yang dekat dengan pintu keluar.
Pulang lebih dulu dibandingkan dia akan meningkatkan resiko untuk dipanggil dan ditanya kembali, karena tempat duduknya berada dalam posisi strategis. Maka dari itu, gue tetap berdiam di tempat, sok sokan memainkan handphone gue yang baterainya tinggal satu persen –dan sialnya gue lupa bawa powerbank atau charger.
Hati gue terus-terusan berteriak, “WOY KAPAN SIH LO PULANG? LO PENJAGA KAFE ATAU APAAN SIH?” Tapi mulut gue masih terdiam, tidak mengeluarkan satu kata pun dengan ekor mata yang terus melirik ke ujung sana.
Tidak ada tanda-tanda pergerakan, bahkan hingga menjelang tengah malam, membuat gue akhirnya menyerah dan ingin pulang saat itu juga. Lagian, apa yang perlu gue lakukan di sini? Meminta Yoga untuk nongkrong bersama gue? Palingan dia lagi bergalau ria di depan televisi bersama Brian. Sena? Tidur. Jhordan? Jangan ditanya. Dennis dan Cakka? Pasti sedang bersemedi dengan bukunya di dalam kamar. Gue memang harus pulang.
Melihat dia yang belum bergerak sedikit pun di sana, ada rasa geer timbul di dalam hati gue. Apa mungkin dia nunggu gue? Apa mungkin dia ingin berbicara gue? Pun rasa geer itu kemudian gue buang jauh-jauh agar tidak semakin merajalela. Memang kalau iya kenapa?
They said, don’t re-read the book, because you will repeat the same chapter.
I agree.
No choice but to agree.
Gue sudah mempersiapkan diri gue untuk tidak menyahut jika dia memanggil gue. Tapi gue salah. Bahkan ketika gue hanya mendengar, “Julian,” dari mulutnya, kaki gue berhenti dan berbalik ke arah Oryza yang tersenyum.
“Kayaknya lo lupa bayar,” dia menunjuk kasir dan membuat gue terlonjak.
Anjir, bisa sampai lupa.
Kayaknya imej gue memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga gue buru-buru membayar dan keluar dari kafe ini ketika akhirnya gue mendapati dia menunggu gue di depan pintu.
“Lo belum pulang?” Tanya gue pelan. Melihat cewek berkeliaran sendirian di tengah malam membuat gue merasa aneh dan sudah seharusnya gue bertanya.
“Gue nunggu lo,” jawabnya. “Tapi lo gak ngajak gue bicara, dan lo gak samperin gue.”
Dia benar-benar menunggu gue.
“Ada apa?” Jantung gue sesungguhnya sedang berdetak sangat cepat, gue berusaha mengalihkan pandangan agar tidak terlalu sering melihat muka dia.
“Maaf,” ujarnya pelan. “Maaf karena gue pernah…”
Gue tersenyum kecil dan memotong ucapannya. “Gak perlu, Za. Gue udah maafin lo.” Karena gue gak mau kalau dia kembali menceritakan kesalahan dia –atau mungkin kesalahan gue juga di masa lalu. “Lo pulang sama siapa? Gue mau pulang.” Sebenci-bencinya gue pada Oryza, gue gak tega melihat seorang perempuan berada di luar, sendirian, di tengah malam.
Tapi gue memutuskan untuk meninggalkan dia dan berjalan beberapa langkah lebih dahulu.
“Gue jadi pemeran utama,” ujarnya, lalu menarik nafas panjang. “Gue jadi pemeran utama untuk teater yang akan menjadi perwakilan kampus kita di lomba nasional nanti. The Mask.”
Mendengarnya, gue menghentikan langkah. Ada sesuatu yang membuat dada gue serasa bergemuruh mendengarnya. Gue berbalik dan menatap matanya yang sedang menatap gue juga, “Maksudnya, lo ikut casting?” Tanya gue.
“Gak,” jawabnya cepat. “Gue udah pasti jadi pemeran utama wanita, karena produsernya yang tunjuk langsung.”
Gue ingin menertawakan diri sendiri. Ya, kenapa gue harus lupa kalau akting dia sudah diakui di mana-mana hingga kampus gue gak perlu lagi mengadakan casting untuk pemeran utama wanita?
Gue berusaha menahan emosi yang tiba-tiba muncul di dalam diri gue.
“Lo mau ikut casting jadi pemeran utama laki-laki?” Tanyanya lagi.
Setelah lo menghancurkan masa lalu gue, kenapa lo harus menghancurkan mimpi gue juga, Oryza? Oryza yang sesungguhnya masih mengukir nama di dalam hati gue, Oryza yang sesungguhnya namanya masih diam-diam gue sebut. Kali ini… lo mau menghancurkan mimpi gue?
“Za, lo memang harus jadi pemeran utama wanita-nya?”
“Why not?”
Gue menangguk-angguk, ya, kenapa enggak? Bahkan pementasan teater yang cukup besar seperti itu rasanya adalah hal mudah bagi Oryza.
“Oke,” jawab gue. “Itu artinya gue harus rela gak ikut casting lagi.” Jawab gue pelan. Kaki gue melangkah meninggalkan dia dan sudut mata gue menangkap sesosok laki-laki yang memaksa dia untuk pulang. Gue gak peduli, mungkin itu pacar barunya?
“Julian!”
Gue gak mendengar panggilan itu karena rasa-rasanya, kepala gue udah dipenuhi dengan memori yang buruk. Tetes hujan mulai membesar, membuat gue segera mengambil motor gue dan mengendarainya kencang menuju kosan. Selama perjalanan itu pula, gue merasa kepala gue rasanya akan pecah.
Gak tahu. Gak tahu kenapa rasanya sakit ketika ia dengan mudahnya mengatakan, “Why not?” di saat The Mask adalah mimpi gue yang sudah gue idam-idamkan sejak dulu.
Yang naskahnya sudah gue hapal di luar kepala.
Yang bahkan not baloknya sudah bisa gue mainkan berkali-kali tanpa melihat lagi.
The Mask sudah tidak boleh lagi masuk ke dalam daftar impian gue.
Masuk ke dalam kosan, gue kira semuanya sudah tidur karena lampu-lampu sudah dimatikan. Tapi ternyata, gue melihat Brian sedang memainkan handphone-nya di tengah sofa, dia belum tidur. Gue gak bisa menunjukkan muka sedih gue sebagai abang tertua. Maka gue nyengir.
“Lah, Bang, kenapa dah nyengir-nyengir sendiri?”
“Gak,” jawab gue. “Aing lagi sedih. Ke kamar yak.”
Gue meninggalkan Brian yang masih mengamati gue kaget sampai pintu kamar gue benar-benar menutup. Gue gak seharusnya sefrustasi ini tapi bagaimana lagi? Ini mimpi gue, dari dulu gue ingin sekali ikut The Mask, bahkan sejak gue masih tahun satu di kampus.
Kenapa pemeran utama wanitanya harus Oryza?
Bukan, bukan karena gue gak bisa bermain dengan Oryza, atau bukan juga karena gue terlalu membenci Oryza.
Tapi jika ada Oryza, memang seharusnya tidak ada gue. Dari dulu pun begitu.
Apa gue harus bilang sekeras-kerasnya di hadapan muka dia, bahwa gue begini karena ada sesuatu yang pernah terjadi dahulu?
Dulu sekali.
Ketika gue dan dia sangat senang ikut teater dan bermain peran.
Gue membuka naskah yang sudah lama gue simpan dan baca hingga lecek, lalu kemudian gue membuka bagian lagu yang akan dimainkan oleh sang pemeran utama laki-laki. Entah kenapa lagu itu terdengar begitu menyedihkan bagi gue saat ini.
Listen
To the sound from deep within
It's only beginning to find release
Oh, the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own, all 'cause you won't listen
Menyedihkan karena gue harus merelakan lagi mimpi gue yang bisa gue gunakan untuk membuktikan kepada ayah gue bahwa gue berhasil.
***


 adillazulfana
adillazulfana