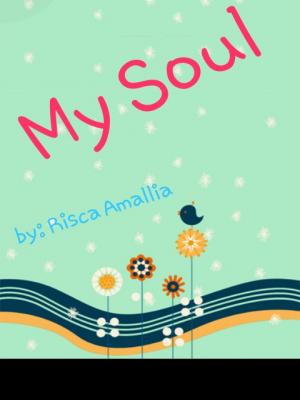Pak Danish sudah menelpon Alya berkali-kali. Beberapa panggilan tak terjawab, Alya mengacuhkannya begitu saja. Padahal, Langit di sebelah barat sudah memerah. Pak Danish tentu akan marah besar saat Alya pulang nanti. Amina tak menyadari hal itu. Sepeda motor mereka terus melaju pulang, seperti tidak akan terjadi apa-apa.
Amina, ia mulai prihatin dengan keadaan Alya. Kondisinya bahkan sangat buruk. Dengan baju sekotor itu, ujung bawah rok-nya pun tersobek saat memanjat pintu kebun Ajar tadi sore. Belum lagi, ia menangis sepanjang perjalanan. Matanya sembab. Ia tentu sedang memikul sesuatu yang berat.
“Kau ingin ku antar ke mana?”
“Antarkan saja aku ke kampus kak.”
“Kenapa?”
“Aku shalat di sana saja.”
Amina tidak berpikir panjang. Ia terus memacu sepeda motornya. Suara azan mulai berkumandang di mana-mana. Sementara ponsel Alya terus berdering meminta di angkat. Amina tak banyak mengomentari. Mereka tiba di jalan simpang kampus. Sepi.
“Terimakasih kau telah banyak membantuku kak.”
“Tak apa, Cuma ini yang bisa ku buat untuk kau.”
“Kau sangat baik.”
“Aku bahkan sangat mengerti keadaan kau sekarang. Semoga di lain waktu, kita dapat berjumpa lagi.”
Mereka berpelukan untuk kali terakhir. Amina tidak bisa lama di sana dan langsung pamit. Ia pun beranjak dan meninggalkan Alya di sana, sendiri. Suasana kampus menjadi sangat berbeda saat malam hari. Biasanya ramai dan terang. Dan sekarang gelap dan sendiri. “Ini seperti akhir ceritaku di sini.”
Setelah shalat magrib, Alya menghubungi ayahnya. Tentu ia di marahi besar. Tapi anak itu sudah terlanjur tenang. Beberapa saat kemudian ayahnya pun tiba. Kemarahan Pak Danish ketika berpapasan memang jauh lebih menakutkan dari pada di telpon tadi. Alya bahkan tidak menanggapinya. Ia hanya masuk ke mobil dan duduk. Dari balik jendela belakang mobil. Ia melihat bangunan itu semakin jauh. “Memang banyak kenangan yang tak mungkin di lupakan di sini.”


 Sayuti
Sayuti