8
Suara ketukan di pintu terus terdengar sejak setengah menit lalu, membuat Cendi terpaksa bangkit dari duduk santainya sembari membaca buku. Dengan malas, ia membuka pintu. Sudah dapat menduga siapa yang ada di baliknya. “Apa?”
“Makan malam.”
“Nggak lapar.”
“Aku nggak peduli kamu lapar atau nggak. Pokoknya kamu harus ikut makan malam.”
Cendi mengesah. Mulai deh, gaya otoriternya keluar. “Aku capek. Aku mau langsung tidur.” Walau tahu bantahannya tak akan berguna, tetap saja Cendi mencoba.
“Makan dulu.” Seperti yang sudah diduga, Nicho tetap memaksa bahkan meraih pergelangan tangan Cendi keluar dari kamar. Tegas tapi tidak kasar. Meski pemaksa, Nicho tak akan pernah menyakiti Cendi.
“Nicho apaan, sih? Lepasin dong! Aku bukan anak kecil!” Cendi berseru kurang suka.
“Oh ya?”
Cendi mendengus, malas berdebat dengan diktator super menyebalkan macam Nicho. Toh ia tak akan menang “Iya, iya, aku ikut makan. Lepasin tanganku!”
Nicho menurut dan Cendi segera mengunci pintu, lalu berjalan—dengan terpaksa—mengikuti Nicho menuju restoran yang terletak di halaman samping resort yang sudah penuh oleh manusia.
“Dibawa paksa sama Nicho?” Tiara tersenyum melihat raut muka Cendi yang tampak kesal.
Cendi tak menjawab dan langsung duduk di samping tunangan Nicho itu, mengabaikan Nicho yang telah menarik sebuah kursi lain untuknya. Wajahnya tetap terlipat. Bibirnya dimajukan sampai lima mili. Ia jelas-jelas ingin menunjukkan kekesalannya.
Nicho sudah sangat terbiasa melihat Cendi merajuk. Maka, ia hanya diam seraya memasukkan kembali kursi yang ditariknya lalu duduk di ujung meja berbentuk persegi itu.
“Tadi kan aku sudah menawarkan jemput kamu di telepon. Tapi kamu nolak,” ucap Tiara. “Mending aku yang jemput kan, daripada dijemput Nicho.”
“Kalian berdua sama saja.”
“Itu karena kami sayang kamu,” balas Tiara lembut.
Selalu itu alasan mereka. Cendi sampai bosan mendengarnya.
“Sudah bisa pesankah kita?” Mona mencoba menengahi.
“Tentu.” Nicho langsung memanggil pelayan yang segera datang membawakan daftar menu. Tiara dan yang lainnya memilih makanan dengan penuh semangat, tapi Cendi hanya diam tak tertarik. Paling-paling juga nanti Tiara atau Nicho yang akan memesankan untuknya.
“Aku pesankan cumi bakar pedas kesukaanmu, ya?” Nicho menawarkan.
Tuh, kan.
“Terserah,” sahut Cendi cuek.
Tahu Cendi masih dalam suasana hati yang buruk, Nicho tak lagi berbicara dan langsung memesankan makanan untuknya, tak lupa minuman kesukaan Cendi. Setelah semua memesan, pelayan pun berlalu. Hanya perlu menunggu beberapa menit hingga makanan mereka diantar.
Sementara yang lain menikmati makanan mereka dengan antusias dan berkali-kali berdecak memuji kelezatannya, Cendi hanya membolak-balik makanannya dengan malas. Padahal cumi bakar pedas yang terhidang di atas piringnya merupakan menu favoritnya dan tampak sangat lezat. Tapi entah kenapa ia sama sekali tak bernafsu melahapnya. Entah apa yang mengganjal di dalam perasaannya, ia sendiri kurang tahu.
Nyanyian ombak yang berdebur di pantai terdengar jelas di telinga Cendi. Sangat merdu. Menenangkan. Seolah berbisik kepadanya agar datang menghampiri.
Jalan-jalan malam hari di sekitar pantai sepertinya menyenangkan. “Setelah ini aku mau jalan-jalan ke pantai,” ucap Cendi tanpa mengangkat kepalanya dari piring makanan. Lebih seperti pengumuman daripada permintaan izin.
“Katanya capek, mau langsung tidur.” Nicho bereaksi.
“Tadinya. Sekarang sudah nggak ngantuk,” sahut Cendi. “Aku ingin jalan-jalan di pantai.” Ia menegaskan.
Nicho tampak tak rela, tapi tak mau berdebat saat ini. “Habiskan dulu makananmu.”
Cendi tak membalas. Tetap dengan malas, ia mengunyah makanannya sepotong demi sepotong. Baginya, kalau Nicho tidak membantah berarti tak keberatan. Keberatan pun Cendi tak peduli. Ia tetap akan pergi baik Nicho suka atau tidak.
Beberapa menit setelah—akhirnya—menghabiskan makanannya, Cendi sudah berdiri di tepi pantai. Deburan ombak menari indah di hadapannya. Angin yang bertiup tak terlalu kencang terasa sangat nyaman menyentuh wajahnya.
Cendi memejamkan matanya agar bisa merasakan embusan angin dengan lebih syahdu. Dan bayangan Rocky pun kembali merasuk ruang pikirnya. Tapi kali ini bergantian dengan bayangan Hans.
Cendi buru-buru membuka mata. Kenapa bayangan wajah Hans muncul lagi? Apa itu artinya ia belum bisa melupakan laki-laki itu? Atau… ia hanya belum benar-benar bisa menyembuhkan luka hatinya?
Ah… entahlah! Baik Hans ataupun Rocky, rasanya saat ini Cendi benar-benar tak ingin mengingat keduanya.
***
“Kamu nggak cerita ke Nicho kan, kalau aku tenggelam?” Cendi bertanya pada Tiara saat sarapan bersama, di hari kedua mereka di Lombok.
“Belum sih.” Tiara menatap jail. “Apa aku perlu cerita?”
Cendi memelotot. Membuat Tiara sontak tergelak. “Iya, iya, aku nggak akan cerita. Aku nggak selalu cerita segalanya sama Nicho, kok.” Ia bahkan harus sangat berhati-hati dalam menjaga lidah saat Nicho bertanya apa yang terjadi di Bali. Ia tahu pasti Cendi tak akan suka jika Nicho mendengar peristiwa itu.
“Bagus deh,” balas Cendi. “Kalau Nicho sampai tahu, bisa-bisa aku dikurung dalam resort dan nggak boleh ke pantai tanpa pengawal.”
Tawa Tiara kembali meledak. “Memang parah protektifnya.”
“Tau tuh, suamimu. Kok bisa sih, dia kayak gitu?” gerutu Cendi. “Ke mana dia, nggak kelihatan dari tadi?”
“Ada urusan di Mataram,” jawab Tiara. “Dan dia belum jadi suamiku.” Ia mengingatkan.
“Tapi kan hampir,” sahut Cendi tak acuh. “Atau mungkin kamu berencana meninggalkannya?”
Tiara refleks menjitak kepala Cendi. “Ngaco aja! Mana mungkin aku meninggalkannya.”
Cendi memberengut sambil mengusap kepalanya. “Nggak perlu pakai kekerasan juga, kali.”
“Maaf.” Sedikit menyesal karena sepertinya memukul terlalu keras, Tiara mengusap kepala Cendi. “Kamu, sih aneh-aneh pertanyaannya. Jangan laporin Nicho, ya! Bisa ngomel dia kalau tahu aku jitak kamu.”
“Apa, sih? Memangnya aku pengadu? Nggak penting banget.” Cendi menyingkirkan tangan Tiara dari kepalanya. “Kira-kira, lama nggak dia ke Mataram?”
“Mungkin.”
“Great!” Cendi tersenyum senang. “Aku bisa bebas dari dia.” Mengabaikan makanannya yang masih tersisa sedikit, Cendi beranjak dan segera meninggalkan resto. Mengabaikan seruan Tiara yang memintanya kembali untuk menghabiskan sarapan.
Sesampainya di pantai, Cendi langsung melepas alas kaki dan berjalan di pasir yang lembut. Hari masih lumayan pagi. Matahari masih condong di arah timur. Ia paling suka bermain air di tepi pantai, berkejar-kejaran dengan ombak yang bergulung. Terasa menyenangkan saat lidah ombak menjilati kakinya yang telanjang.
“Cuma bermain ombak? Kenapa nggak berenang?” Suara seseorang terdengar mengusik kesendirian Cendi.
Cendi menoleh dan sedikit terkejut mendapati Reno-lah yang berbicara. “Aku nggak bisa berenang.”
“Oh.” Reno melangkah lebih mendekat, lalu mengulurkan tangan. “Kenalkan, aku Reno.”
“Cendi,” balas Cendi sembari membalas tangan Reno. “Dan kita sudah pernah kenal sebelumnya.”
Reno mengernyit. “Kapan?”
“Sudah agak lama sih,” sahut Cendi. “Mungkin kamu sudah lupa. Aku pernah mewawancarai kamu di radio tempatku bekerja. Waktu kamu jadi juara Asian GP.”
Reno diam. Mencoba mengingat sejenak, sebelum kemudian berseru, “Ah, ya, aku ingat! Jadi, kamu penyiar yang waktu itu? Yang di Surabaya itu, kan?”
Cendi tersenyum dan mengangguk. “By the way, kok, kamu ada di sini?”
Kembali Reno mengernyit. “Ada yang aneh?”
“Nggak.” Cendi menggeleng. “Agak kaget saja melihat kamu di sini. Kupikir kamu masih di Bali.”
“Tahu dari mana aku di Bali?”
“Kita menginap di hotel yang sama,” jawab Cendi. “Kita juga datang di hari yang sama.”
“Oh ya? Kok, aku nggak tahu?”
Cendi hanya mengedikkan bahu. “Kamu ke sini sendiri?”
Reno menggeleng. “Sama saudara-saudaraku.”
Cendi mengernyitkan kening. “Yang juga di Bali sama kamu?”
“Ya, kami berempat,” jawab Reno. “Aku, adikku, dan dua sepupu.”
Untuk sesaat Cendi membatu. Jadi Rocky juga di sini?
“Tapi aku masih penasaran deh, kok kamu bisa tahu kita menginap di hotel yang sama di Bali?”
“Kalian nggak mungkin nggak sadar, kan, kalau kedatangan kalian bikin lobi ramai?”
“Oh… ahahahaha…” Reno tertawa. “Iya ya, waktu itu banyak yang mengerubungi kami. Tapi itu bukan salahku, lho. Sebagian besar dari mereka penggemar adikku. By the way, kamu tahu adikku?”
Cendi mengangguk. “Rocky Herlangga. Mungkin hanya sebagian kecil yang nggak kenal dia.”
“Ya,” sahut Reno. “Nggak nyangka adikku bisa seterkenal itu. Bangga jadi kakakknya, haha.”
Cendi hanya membalas dengan senyum kecil dan beberapa saat keduanya taka da yang bersuara, hingga Cendi melontarkan pertanyaan, “Kapan kalian meluncur kemari?”
“Hari pertama di tahun yang baru.”
Dan sekali lagi Cendi membatu. Jika mereka meninggalkan Bali di hari pertama, berarti wanita pirang yang ia lihat saat itu tak ada hubungannya dengan Rocky?
“Kamu sendiri, kapan meninggalkan Bali?” Reno balas bertanya.
“Baru kemarin.”
“Menginap di mana?”
Cendi tahu tak seharusnya ia menyebutkan tempat menginap pada orang yang baru dikenal. Namun, entah mengapa, tangannya refleks menunjuk resort yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Mungkin karena ia menganggap Reno bukan orang yang berbahaya.
Reno mengikuti arah yang ditunjuk Cendi dan wajahnya menampilkan raut terkejut. “Wah, kebetulan aku juga menginap di sana!”
Sekali lagi kejutan untuk Cendi. Ternyata sejak kemarin ia kembali tinggal di bawah atap yang sama dengan Rocky. Lalu, di mana anak itu sekarang? Kenapa Cendi sama sekali belum melihatnya?


 kucingpipus
kucingpipus

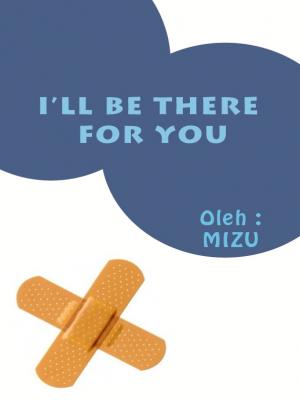








Like.
Comment on chapter Prolog