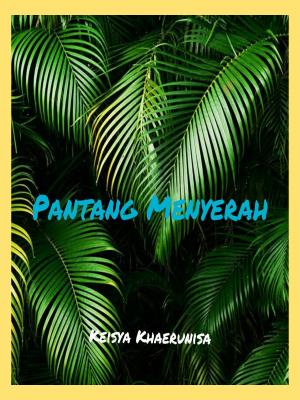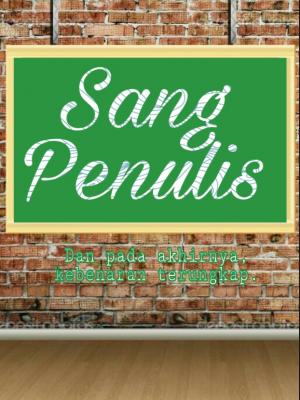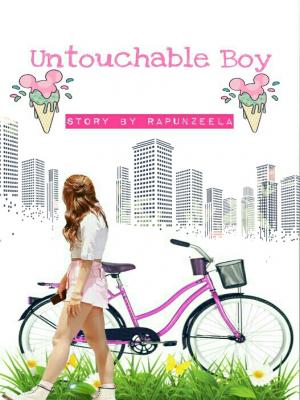“Seorang anak merupakan bagian dari kepingan-kepingan mimpi orangtuanya.”
“A’an! Bangun!!! Kamu itu sudah dibilangi, selesai salat Subuh jangan tidur lagi, susah banget,” teriak Bu Asri—ibunya A’an—dari ambang pintu. Melihat nggak ada pergerakan dari anak laki-lakinya, Bu Asri pun mendekat. “Bangun, An! Sana loh ke pasar!” Tangan Bu Asri menggoyang-goyangkan tubuh di balik selimut.
Sedikit tersadar, A’an langsung mengerjapkan mata. Lalu merenggangkan otot-ototnya. “Iya, Ibu, ini sudah bangun.” Ia bergumam dengan mata terpejam. Di kamar 3 x 2,5 meter itu A’an berusaha keras mengumpulkan nyawa.
“Kalau Ibu ke sini lagi, kamu belum juga bangun. Jangan salahkan Ibu kalau sapu melayang, ya!” ancam Bu Asri lalu pergi meninggalkan A’an.
Mendengar ucapan ibunya, A’an yang hanya mengenakan kolor itu langsung melemparkan selimut, bangun. Pernah terakhir dia diancam dilempar panci, dan alhasil perkakas untuk masak air itu pun harus mendarat di kepalannya meninggalkan jejak hitam di jidat karena pantat paci yang gosong.
A’an Budiono, anak semata wayang. Namanya memang seperti itu, ada tanda petik satu yang memisahkan huruf ‘A’ pada kata pertama dari namanya. Anak yang hidup dari usaha orangtua yang memiliki warung makan, mengharuskannya pergi ke pasar di pagi buta.
Meskipun kegiatan belanja itu telah dilakukannya sejak duduk di sekolah dasar, namun rasa malas lebih sering menghampiri dirinya, apalagi saat musim hujan yang udara di pagi hari dinginnya berlipat ganda membuat tubuh sampai menggigil.
Dengan cepat dia memakai celana panjang dan kaus yang tergantung di balik pintu, lalu mengeluarkan motor. “Hari pertama masuk, masa juga harus ke pasar.” A’an mencoba melakukan negosiasi.
Ibu menoleh mendengarnya. “Oh, kalau gitu, nggak perlu uang jajan, ya?” ucapnya sambil tangan kanannya nggak berhenti menggoyang-goyangkan sutil, sedangkan lainnya memegang telinga wajan.
A’an hanya bisa nyengir, “Ya, ya Ibuku yang cantik. Ini berangkat, kok.” Tangannya terulur, untuk menerima catatan yang harus dibeli beserta uangnya.
***
Urusan memilih sayuran, dan berbaur dengan aroma khas pasar tradisional sudah sangat melekat di hidup cowok yang kini sedang memarkirkan motor. Hampir semua pembeli mengenalnya. Tak jarang pujian untuk A’an pun terlontar. “Wis bagus, rajin meneh.[1]” Bahkan sampai berharap A’an menjadi menantunya. “Sesok nek wis gede, rabi karo anakku wae yo.[2]”
A’an yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum malu-malu. Satu hal yang nggak disukai cowok itu ketika di pasar adalah bertemu dengan Mbak Kotim—perempuan berdaster yang selalu menyisir rambut dan nggak pernah rapi—sejak A’an SD sampai sekarang, selalu mengganggu cowok yang memiliki senyuman yang aduhai ini.
Hal yang ditakutkan pun terjadi lagi. Mbak Kotim mengetahui kedatangan A’an, langsung mengendap-endap memelankan langkah kakinya. Beberapa ibu-ibu sudah hafal dengan perangai perempuan satu ini, dan dari arah belakang motor. “Eh, Mas ganteng!” teriaknya sambil memukul jok motor matic itu. Membuat A’an setengah melompat saking kagetnya.
A’an bergidik begitu dilihatnya ada perempuan yang nyengir lebar ke arahnya, ia pun memutari motor untuk menghindari godaan perempuan dengan kadar kewarasan yang minim. “Mas ganteng, sombong ih,” ucapnya yang masih terdengar oleh A’an. Cowok itu menoleh, memastikan kalau Mbak Kotim nggak mengikutinya.
Dulu waktu A’an SMP, pernah Mbak Kotim memeluk A’an dari belakang, hingga A’an teriak sekencang-kencangnya. Sampai beberapa penjual pun berlari menuju sumber suara. Melihat yang sebenarnya terjadi, mereka justru terbahak mengetahui A’an dipeluk oleh Mbak Kotim.
***
“Kenapa? Ketemu pacarnya lagi di pasar?” goda Bu Asri disusul tawa meledek begitu tahu A’an masuk rumah dengan muka yang terlihat tegang.
“Ibu mau punya menantu seperti Mbak Kotim?” Serangan balik untuk ibunya. A’an segera menurunkan belanjaan dari motornya, kemudian membawanya ke arah ibu.
Pak Ito—ayah A’an—yang mendengar percakapan nggak jelas itu pun terbahak. “A’an,” panggil Pak Ito, begitu sudah membuka warung makannya.
“Iya, Pak?” ucap A’an menoleh ke arah ayahnya yang kini berjalan mendengkat sambil menepiskan debu di kedua telapak tangannya.
“Nanti kalau ada ekstra kulikuler ….”
“Jangan lupa ambil badminton,” potong A’an.
Pak Ito pun langsung terbahak mendengarnya. A’an masih teringat ketika dia baru masuk SMP, ayahnya pun mengucapkan hal yang sama. “Memang anaknya Ayah,” ucap Pak Ito sambil menepuk bahu A’an kemudian berlalu ke belakang.
“Besar harapan ayahmu melihat kamu menjadi atlet bulu tangkis profesional,” ucap Bu Asih di sela-sela mengeluarkan belanjaan. “Dulu, sewaktu ayahmu masih muda, sehari sebelum dia turnamen tingkat nasional ayahmu kecelakaan, itu kenapa tangan kanan ayahmu lemah sampai sekarang.”
Ada keharuan dirasakan oleh A’an. Itulah kenapa Pak Ito begitu besar mendukungnya untuk menjadi atlet badminton, bahkan sejak SD sudah diikutkan club badminton, segala keperluan raket, sepatu olah raganya dibelikannya kualitas yang baik. Pak Ito rela merogoh uangnya lebih dalam untuk itu.
A’an menghela napas. “Doakan A’an ya, Bu,” ucapnya lalu berdiri. Meninggalkan Bu Asih untuk mengambil handuk, terus menuju kamar mandi.
Bu Asih hanya tersenyum. Pasti Le, semoga gusti Allah memberikan kemudahan jalanmu, batin wanita itu.
A’an masuk kamar mandi, langsung menggantungkan handuk dan melepaskan bajunya. Ketika tangan mau melepaskan celana pendeknya, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat A’an berteriak, “AAARGH!”
[1] Sudah cakep, rajin juga.
[2] Besok kalau sudah besar, nikah sama anakku saja, ya.


 NurwahiddaturRohman
NurwahiddaturRohman