Perasaan Adit mendadak terasa tidak enak. Meskipun ia kini berada di tengah keramaian.
Nightclub itu lebih meriah karena sedang mengadakan acara yang disponsori perusahaan rokok ternama. Adit tampak duduk di meja bar, berpikir, sementara musik EDM diputar keras-keras mengikuti permaian DJ. Di hadapannya tersaji minuman berwarna keemasan, pahit dan pahang, yang segera mengantarkan penikmatnya pengar. Ia tidak menyentuh minuman itu, ia masih membutuhkan fokus dirinya. Jay yang memesankan minuman itu untuknya, karena menurutnya Adit yang tampak galau dan resah itu sedang membutuhkan sedikit sentuhan suka cita. Jay jelas salah besar, pikir Adit, yang ia butuhkan saat ini hanyalah kepastian dari gadis itu. Bukan alkohol.
Sambil mengepulkan asap rokok, Adit memutar duduknya agar menghadap ke arah panggung, tempat tujuh orang penari terbalut pakaian kulit ketat sedang bergoyang luwes dan enerjik, meletupkan semangat para pengunjung di lantai dansa. Namun di tengah kemeriahan itu, ia tetap merasa kesepian dan sendirian.
Adit menatap layar ponselnya, sudah enam kali ia mengirimkan gadis itu pesan di kolom chat-nya, tapi tidak juga gadis itu membalasnya. Tak ada kabar dari gadis itu sejak tadi.
Dengan hati tak menentu, Adit kembali membuat sambungan telepon. Tapi sambungan itu kini dihubungkan ke voicemail. Ponsel itu mati. Adit tiba-tiba merasakan firasat tidak enak, perasaan tak menentu yang mendesak dan menggulungnya. Ia kembali teringat pesan gadis itu di gedung tadi, saat ia mengantarnya ke taksi: Baik-baik ya, kamu, Dit...
Harusnya ia mengikuti perasaannya. Itu adalah pesan perpisahan—betul, kan? Ia merasa harus menemui dan mencari gadis itu. Sekarang juga. Tapi ke mana? Di mana tempat tinggal gadis itu? Gadis itu tidak berkuliah atau kerja. Ia baru akan kuliah tahun depan. Temannya? Adit sama sekali tidak pernah ingat gadis itu pernah menyebut nama temannya. Kebanyakan mereka membicarakan diri mereka sendiri dan hal-hal spontan yang terlintas di pikiran mereka saat itu. Adit tiba-tiba sangsi benar-benar mengenal gadis itu...
Satu-satunya informasi yang ia ingat adalah Kompleks Bahagia Asri. Tapi perumahan itu cukup luas. Ia tidak mungkin mengetuk satu per satu rumah dan menandainya seperti yang dilakukan para penyamun dalam cerita Alibaba.
Sesudah berpamitan kepada teman-temannya, ia pun segera meninggalkan gedung mewah tersebut. Mengebut dengan mobilnya, membelah malam yang larut dan sepi. Ia memelankan laju mobilnya ketika memasuki kawasan perumahan yang sudah amat sering ia kunjungi itu.
Karena tidak punya tujuan, Adit memarkirkan mobilnya di depan trotoar rumah Abriel, berharap sahabatnya itu bisa menolongnya. Barangkali, jika Adit menjelaskan kepada Abriel ciri-ciri fisik gadis itu, Abriel bisa membantunya menemukan gadis itu—mungkin Abriel pernah mendengar namanya, atau lebih baik malah mengenalnya jika mereka memang tinggal satu kompleks, pikirnya.
Namun, Adit segera termenung begitu menyadari kalau di sana ia tidak melihat penampakan Vios perak yang dikenalnya. Adit hapal betul, karena garasi dalam rumah Abriel hanya bisa menampung dua mobil orangtuanya: sebuah van besar papanya dan sedan kecil baru ibunya—plus motor Abriel disudut, yang amat jarang digunakan kecuali jika papanya mendadak ingin naik motor. Maka dari itu jika mobil Abriel tidak ditempatnya, itu artinya kemungkinan besar Abriel sedang tidak ada di rumah. Adit pun segera menelepon ponsel Abriel. Enam kali nada sambung yang ia dengar setelahnya.
Telinga Adit mulai berdenging. Jengah dan frustasi. Diteleponnya lagi nomor itu. Tak ada yang menjawab. Ia mengecek jam tangannya, pukul dua belas malam lewat beberapa angka panjang. Apa mungkin Abriel sudah tidur? Jangan-jangan sahabatnya itu menginap di rumah temannya—tapi, siapa? Ataukah Abriel memang sedang bersama Irena? Tapi... hingga selarut ini? Dan pada malam sekolah? Adit memutar pertanyaan-pertanyaan itu di kepalanya dengan cepat.
Percobaan terakhirnya. Ia kembali menelepon Abriel. Jika Abriel tidak mengangkatnya, ia akan berkeliling kompleks ini satu kali. Kemudian pulang. Barangkali, besok di sekolah ia bisa menceritakan masalahnya pada Abriel. Abriel pasti mau membantunya, mencarikan jalan keluar untuknya. Anak itu selalu bisa diandalkan.
Nada sambung akhirnya berhenti. Adit mendengar suara gemerisik.
"Apaan, Dit?" jawab Abriel dengan suara setengah hati. Adit menebak mood Abriel sedang tidak begitu baik. Atau Abriel sudah tidur dan ia mungkin barusan membangunkannya.
"Eh, sori gue nelepon malam-malam gini. Lo lagi di mana?"
Jeda beberapa detik. "Di rumah. Emang kenapa?"
Adit sedikit bernapas lega. "Keluar dong, bentaran aja. Gue di depan rumah lo. Gue stres banget. Perlu bantuan lo."
Jeda lama. "Gue lagi nggak bisa keluar..."
Adit mulai curiga. "El, lo nggak di rumah, ya? Mobil lo juga nggak ada. Serius, gue di depan rumah lo."
Hening lagi. "Sori gue bohong, Dit. Gue nggak lagi di rumah."
"Ah, gue tahu! Lo lagi sama si Idung, ya? Kalian ngapain hayooo malam-malam gini? Di mana lo, Njiiiis?"
"Gue di Lembang."
"Lembang?" decak Adit, terperangah. "Sama Irena, beneran?"
"Mmh... iya."
Adit bersorak. "Kalian ngapain malam-malam gini hayooo, di Lembang pula!"
"Ngadem aja."
Adit langsung paham. "Lo nginap? Besok lo bolos apa balik pagi?"
"Besok gue bolos. Barusan gue udah telepon Tomi, minta diizinin."
"Kok lo nggak neleponnya ke gue, sih?" Adit langsung protes. "Besok gue sendirian, dong."
Lawan bicaranya terkekeh kering. "Sori ya, Dit."
Hambar. Nada suara Abriel terasa amat garing. Adit bisa merasakan jarak itu. Mungkin Abriel hanya terganggu karena ia sedang bersama Irena sekarang, Adit berusaha meraba situasi.
"Oke, deh kalau gitu. Lo have fun sama si Idung. Inget, jangan kebablasan lo. Suasananya, udara dinginnya, kan mendukung banget, tuh," pesan Adit sebelum Abriel mengiyakan dengan nada muram dan menutup teleponnya duluan.
Belum pernah sahabatnya itu berbicara sedatar dan sedingin itu padanya. Bahkan saat Adit menghilangkan CD kompilasi musik milik Abriel yang sangat berharga, hadiah dari Almarhum Om-nya. Meski nyaris melempar Adit dengan botol plastik, nada dan caranya berbicara tidak se... aneh itu. Apa yang sudah ia perbuat padanya? Apakah tanpa ia sadari ia telah membuat Abriel tersinggung atau marah?
Tetapi barangkali itu hanya perasaannya saja, Adit membatin. Barangkali karena perasaannya sedang tidak menentu, hatinya jadi terlalu peka. Abriel adalah sahabatnya, sahabat terbaiknya di dunia ini. Jika ia memiliki salah, Abriel akan menegurnya langsung, tidak mungkin anak itu serta-merta memusuhinya tanpa alasan yang kuat. Abriel bukan orang seperti itu, ia amat mengenalnya. Meski dari luar tampaknya cuek, anak itu sebetulnya sangat sensitif dan lembut. Dan untuk saat-saat tertentu terkadang anak itu malah terlalu peka.
Mata Adit tiba-tiba terasa perih, mengantuk. Hari ini sudah diputuskan. Ia akan pulang ke rumah. Besok, sepulang sekolah, ia akan meneruskan pencariannya.
Di bawah lampu jalanan yang menerangi malam, diputarnya mobilnya kembali ke jalan pulang. Kali ini, ia merasa sedikit pasrah.
* * *
Masih menggenggam ponselnya, Abriel masih termangu di beranda penginapan yang beberapa waktu lalu di sewa ia dan Isabel. Penginapan sederhana berdinding kayu di mana satu ruangan terdiri dari dua kamar, satu ruang tengah dengan perapian, dan satu kamar mandi.
Derit kayu di bawah kakinya terdengar saat kaki Abriel menginjaknya. Di saat bersamaan, tusukan rasa bersalah itu masih menekan batinnya. Ia sadar, barusan ia memperlakukan sahabatnya dengan sangat buruk. Sangat tidak adil. Seharusnya, ia tidak perlu seketus itu pada Adit...
Tapi, ada beberapa alasan yang kembali menegaskan diri Abriel mengenai sikap dinginnya tadi dipicu oleh ucapan dan pengakuan Adit dulu. Pertama, ia ingat betul bagaimana dulu Adit mengungkap padanya bahwa ia tidak ingin melepas baik Andine ataupun Audrey—Isabel. Kalau saja bisa, Adit ingin memiliki keduanya. Abriel juga masih ingat betul, mimik tamak Adit saat itu. Mimik soknya, karena mendadak saja ia seolah terjebak di antara dua gadis cantik beserta kelebihan masing-masing yang menarik minatnya: jika Andine bisa untuk siang hari, maka Isabel bisa ia gunakan untuk menemani malam harinya—sekarang kata-kata itu sangat amat mengganggu Abriel!
Selanjutnya, saat Adit memberitahunya bahwa Isabel telah membuka kesempatan untuknya, lalu dengan mudahnya Adit menepikan Andine. Menyingkirkannya seperti velg mobilnya yang ketinggalan zaman.
Terakhir. Ia benci jika mengingat-ingat saat Adit memberitahunya bahwa ia sudah mencium bibir Isabel. Dan, menurutnya ciuman kali itu berbeda...
Sekarang, bagaimana bisa ia meneruskan persahabatannya dengan Adit, duduk di sebelahnya sepanjang waktu, jika yang akan Adit bicarakan nantinya hanya Audrey, Audrey, dan Audrey.
Isabel. Angsanya.
Abriel menggaruk rambutnya yang basah. Ia sudah mandi air panas tadi. Tubuhnya sudah wangi dan segar. Kini, giliran Isabel yang menggunakan kamar mandinya. Abriel bisa mendengar bunyi bathtub sedang digunakan Isabel. Terdengar siul-siulan nyaring bernada tak selaras menggema dari kamar mandi itu. Orkestra baru favoritnya.
Kedinginan, Abriel masuk dan menutup kembali pintu menuju beranda. Kemudian duduk bersila di depan perapian yang menyala kecil. Memejamkan matanya, menikmati hangat menjalari tubuhnya. Masalah Adit akan dipikirkannya besok. Sekarang. Di sini. Ia hanya akan menikmati waktunya, setiap detik yang berjalan bersama Isabel.
Pintu kamar mandi terbuka. Isabel yang sudah mengganti pakaiannya dengan piyama lengan panjang dan celana semata kaki muncul. Rambut basahnya sudah tergulung handuk hingga membuat menara putih di atas kepala mungilnya.
Cepat, ia mengambil tempat di sebelah Abriel, memburu kehangatan dari api yang menyala dan berderak-derak pelan. Isabel menjulurkan kedua tangannya ke arah perapian, menggeliat-liatkan bahunya ketika menerima gelombang panas dari bara api. Ia baru berhenti setelah sekujur tubuhnya terasa hangat.
"Nyaman," gumam Isabel, kedua tangannya sudah dalam posisi memeluk lutut.
Abriel kontan menoleh padanya. Dengan lampu yang temaram, ia bisa melihat wajah Isabel yang murni tanpa riasan tampak berpijar menyambar cahaya dari bara api.
"Sebenarnya, kita ngapain harus ke Subang?" tanya Abriel, setelah merasa, ini mungkin saat yang tepat untuk mendapatkan jawabannya,
Isabel memeluk kedua lututnya di atas karpet, erat. Ia terdiam cukup lama, mengamati api melalap kayu di depannya.
"El, kalau saya ceritain ini... kamu harus nikahin saya—atau saya terpaksa harus bunuh kamu. Apa kamu bersedia?" desah Isabel ketika ia menjawab.
Abriel langsung tertawa mendengar ucapan Isabel yang kadang sering ngasal dan tidak terduga itu. "Oke. Untuk opsi pertama," katanya kemudian, ia lalu berdeham dan menghadapkan dirinya seutuhnya pada Isabel, tampak sangat berminat mengikuti permainan gadis itu.
"Meskipun nanti kamu pacaran sama orang, lari ke ujung dunia—bahkan jika NASA ngirim kamu ke Pluto, saya akan cari dan nagih janji kamu. Karena rahasia ini, harus kamu bawa sampai mati. Dan satu-satunya cara buat yakin kamu nggak akan bilang-bilang ke orang adalah dengan mengawasi kamu seumur hidup."
"Deal."
"Yakin, kamu setuju dengan syarat itu? Kalau kamu nggak mau nikahin saya, paling nggak kita tetanggaan sampai tua, sampai kita sama-sama pikun... bisa?"
"Oke, setuju," potong Abriel. Ada binar kecil di mata Abriel yang tidak dapat diabaikan Isabel. Ia percaya.
Isabel tampak menarik napas dalam-dalam sebelum mengatakan hal yang ia rahasiakan rapat-rapat itu. Dipandanginya kedua bola mata Abriel yang berkilauan sekali lagi.
"Sebenarnya, Pak Ma'el yang suka jadi wasit—penjual jus—itu ayah saya."
Otak Abriel memproses dengan cepat pengakuan Isabel itu. "Hah?" Ia langsung merespons, rahangnya terasa jatuh karena ia membuka mulutnya terlalu lebar.
"Makanya," tambah Isabel segera. "Saya mau jalan sama Adit."
"Maksud kamu..."
Isabel mengangguk seolah mampu membaca pikiran Abriel. "Supaya saya punya alasan untuk datang ke gedung futsal itu, dan duduk dekat dengan Papap saya. Kalau nggak gitu, saya nggak mungkin bisa punya kesempatan untuk dekat, mandangin selama berjam-jam. Setelah sekian lama saya nyari, akhirnya saya ketemu juga—ajaib banget ya, campur tangan takdir di sini. Papap nggak ngenalin saya sama sekali, nggak pa-pa, sayalah sebagai anak yang harus mengingatkan. Kemarin, saya sengaja persiapin diri saya untuk ngomong jujur dan ngaku sama beliau, tapi nyatanya Papap saya nggak ada di sana. Ada yang ngasih tahu saya kalau istrinya—'yang baru—lagi sakit. Saya udah dapat alamatnya, di Subang, makanya saya mau datangin dan bilang semuanya. Seenggaknya saya bisa mengobati rindu saya untuk manggil 'Papap'. Setidaknya sekali aja dalam hidup saya sebagai gadis dewasa, saya bisa ngerasain pengalaman punya ayah."
Abriel mencerna kalimat per kalimat yang diungkapkan Isabel padanya. Menggantikan keterkejutan, mendadak ada gelenyar rasa lega dan haru yang tak terbendung di dalam dadanya. Membayangkan perjuangan gadis itu mendapatkan kembali pengakuan dari ayahnya. Abriel tidak bisa berkata-kata. Tapi ia bisa merasakan matanya terasa panas.
Saat itu juga, ia maju untuk mendekap tubuh Isabel dengan erat. Bukan pelukan iba, melainkan pelukan perayaan, selebrasi—suka cita. "Bentar lagi kamu ketemu Papap kamu ya, Angsa. Sebentar lagi aja..."
Pasrah, Isabel menerima pelukan itu. Hatinya berdebar namun juga terasa lega dan hangat. Di dalam dada Abriel, ia tersenyum seraya memejamkan matanya. Isabel tidak ingat kapan terakhir kalinya ia merasakan perasaan senyaman itu.
Malam itu akhirnya pun berlalu dengan perlahan, lembut, dan damai. Pukul jam tiga pagi mereka memutuskan untuk mengentikan obrolan mereka karena jam lima nanti mereka sudah harus berangkat dari penginapan menuju Subang.
Dengan besi panjang yang sudah tersedia, Abriel menepikan beberapa kayu ke sudut perapian agar api menyala lebih kecil. Ia kemudian mengangkut bagian atas tempat tidur, bantal dan selimut tebal dari kamarnya, menggelarnya di depan perapian. Semua dilakukan atas permintaan Isabel.
Isabel merebahkan diri di dalam kamar dengan pintu sengaja dibuka lebar, agar ia tetap bisa melihat Abriel dari ambang pintu yang membuka, agar mereka tak terpisahkan ruang—karena waktu tak akan sanggup dihentikan. Dalam keheningan, mata mereka terpaut; dua pasang mata itu saling memandang. Tanpa ada kata dan suara yang terucap, hati mereka berbicara jauh lebih banyak.


 Andrafedya
Andrafedya








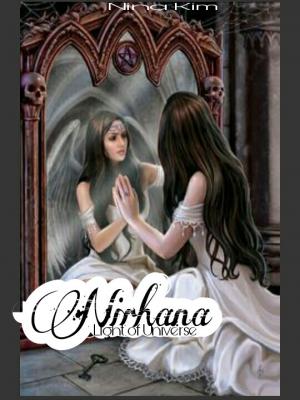





@shalsabillaa semoga ga mengecewakan ya, terima kasih banyak buat apresiasinya
Comment on chapter 1. Makhluk Malang