Setelah melewati jalan Pahlawan yang teduh, kemudian melesak ke jalanan kecil menanjak berkilo-kilo meter di daerah Awiligar, bangunan abu-abu itu akhirnya menjulang di antara hamparan pepohonan tinggi. Kentara sekali hotel tujuh tingkat berdesain minimalis itu baru saja dibangun. Dengan perasaan yang masih diliputi semangat, Abriel mengikuti rute yang mengarahkannya ke lahan parkir di sebelah selatan, tempat mobil-mobil berjajar dengan teratur.
Sebelum turun, tak lupa ia menyemprotkan parfum dan mengenakan kemeja flanelnya, yang sejak beberapa hari lalu tergeletak di jok belakang mobilnya.
Pintu itu berwarna cokelat, berpelitur. Dengan plat dari besi menempel di sisinya. Abriel menghela napas sebelum mengetuk pintunya. Kemudian, seseorang membukakan pintu itu.
Isabel mengenakan jubah mandi tebal berwarna putih. Rambutnya kering tetapi berantakan. Wajahnya bersih tanpa riasan, kaki telanjangnya berjinjit di atas karpet empuk di bawahnya.
"Bapak Abriel," sambut Isabel, cengiran terkuak di wajahnya. Seolah tidak pernah ada kecanggungan sebelumnya, gadis itu dengan riang mempersilakan masuk. Dan dengan ragu, Abriel melangkah masuk ke dalam ruangan luas dan terang benderang itu. "Saya baru aja mau berendam. Saya nyangkanya kamu bakal ngaret," tambah gadis itu seraya mendorong tirai yang menutupi kaca, sekat yang memisahkan antara kamar tidur dan jacuzzi besar yang menghadap langsung ke jendela raksasa di depannya, yang menyuguhkan panorama hijau nan fantastis.
Abriel menelan ludahnya. Pemandangan ini, Isabel, dan suasana yang mengabut di ruangan itu membuatnya tak kuasa untuk tidak merasa kikuk. Namun, ia segera kembali merasakan sensasi seperti menelan pil pahit ketika teringat kembali percakapan terakhir mereka. Mimpi buruknya: membayangkan tubuh Isabel dijamah tangan-tangan kotor, teramat sangat mengusik batin Abriel. Ia benci pada dirinya sendiri karena sebagian dirinya, memaksa menerima kenyataan itu hanya agar ia bisa bertemu kembali dengan gadis itu.
"Kamu ke mana aja?" Abriel akhirnya berkata.
"Saya liburan, di 'Jogja'," jawab Isabel ringan sambil membuat tanda petik dengan jarinya ketika mengatakan "Jogja".
"Kamu bohong sama Mama kamu," ujar Abriel, sambil melesakkan diri ke atas sofa. Meskipun berusaha kasual, duduknya tetap tegak.
"Eh, kamu mau minum apa? Ada soda di minibar."
Dengan cepat Abriel menggeleng. "Ntar aja. Kamu yang naruh kertas di mobil aku tadi?"
Isabel nyengir. "Saya minta tolong Mang Okim. It's a long story."
"Aku nyariin kamu. Selama seminggu. Kayak orang gila, setiap hari datang ke rumah kamu."
Isabel bersedekap memunggungi cermin. "Saya tahu, makanya saya nyuruh kamu ke sini. Supaya kamu berhenti datang ke rumah saya. Kayak orang gila."
"Aku mau minta maaf sama kamu," ujar Abriel menatap langsung ke mata Isabel. Ia berharap Isabel melihat kesungguhannya. "Apapun yang kamu lakuin, itu adalah... hak kamu. Dan ini mungkin terdengar sok pahlawan banget, ngatur.... ah, terserah. Tapi aku cuma pengin tahu, apa ada cara buat bikin kamu berhenti ngelakuin semua ini? Kalau ada yang bisa aku lakuin untuk itu, aku bersedia.".
"Maksud kamu?"
"Apa kamu nggak merasa berada dalam bahaya?"
"Bahaya gimana?" Isabel malah nyengir.
Abriel mengertakan giginya mendapati Isabel menganggap kekhawatirannya sebagai lelucon membuatnya frustasi. "Kamu... nggak terikat sama agensi... maksudku, kamu menjalankan semuanya sendiri, kan? Nggak ada orang yang tahu dengan siapa hari ini kamu ketemuan..."
Isabel memutar bola matanya. "Saya nggak gila. Saya punya kok orang yang saya hubungi sebelum ada apa-apa. Namanya Mei. Sepupu saya, sepupu jauh sih. Dia tinggal di Jakarta. Setiap hari saya kirim e-mail dan chatting-an sama dia. Data klien saya, saya kasih ke dia semua. Hampir sembilan puluh persen klien juga dapat dari dia, dia atur semua yang masuk ke website. Setelah saya beres jalanin kerjaan saya, saya kabarin dia lagi. Kalau dalam delapan belas jam sejak date saya, saya nggak hubungin dia. Dia bakalan lapor polisi. Pokoknya, Mei ini canggih anaknya. Saya udah biasa percayakan banyak hal sama dia."
Abriel terpana sesaat mendengar penjelasan gadis itu. "Meskipun gitu, berarti kamu sendiri sadar, ada titik di mana mungkin kamu berada dalam bahaya, kan?"
"Yep."
"Terus... kamu masih mau ngelanjutin semua ini?" tuntut Abriel. "Apa nggak ada jalan lain untuk mengobati apapun itu pada diri kamu selain dengan melakukan semua ini? Apa nggak ada cara supaya aku bisa ikut di dalam semua ini?"
Isabel tampak berpikir sejenak. "Kamu mau jadi klien saya?"
"Semacam klien...?"
"Permanen," Isabel meluruskan. "Kalau kamu nggak pengin saya jalan sama orang lain, itu artinya kamu harus booking saya satu kali dua puluh empat jam selama tiga ratus enam puluh lima hari—biayanya pasti mahal banget. Dan setahu saya uang jajan kamu nggak mencukupi banget untuk itu."
Otak Abriel mulai menghitung dengan perkiraan. "Kalau semuanya harus dibayar pake duit, jujur aku nggak punya uang sebanyak itu."
Isabel tampak puas. "Jadi, kamu nggak bisa melarang saya buat tetap kerja."
"Gimana kalau saya temanin kamu setiap kali kamu dapat... panggilan," cetusnya tanpa berpikir panjang.
"Maksud kamu, kamu ngintilin saya ke mana pun saya pergi, gitu?"
Abriel mengangguk. "Tapi waktunya diatur setelah aku pulang sekolah."
Isabel mengerjap sekali. Dipandanginya Abriel seolah-olah ia adalah barang paling antik yang pernah dijumpainya.
"Saya pengin bilang sejak awal kamu datang tadi, tapi ini semua terlalu lucu, serius, deh!" Tak butuh waktu lama untuk mendengar ledakan tawa dari Isabel.
Namun Abriel tidak balas tertawa. Dengan penuh antisipasi, ia menatap gadis itu dengan tajam. Ia tidak siap untuk kenyataan yang lebih pahit dari ini.
"Apa yang lucu?" Abriel bertanya pelan dan waspada.
Isabel masih tertawa sambil menutupi mulutnya. Sekarang ia sudah menjauhi Abriel, menggeser sekat kaca agar ia bisa duduk di pinggiran jacuzzi putih itu.
"El, saya ini bukan... pelacur!" cetusnya. "Saya cewek bayaran, iya. Karena saya memang dipanggil dan dibayar untuk jasa saya. Tapi saya nggak kayak yang kamu sangka. Klien-klien saya nggak ada yang pernah tidur sama saya. Menyentuh saya aja mereka nggak. Okelah, paling banter saya pernah pegangan tangan. Hanya sebatas itu dan dengan profesional."
"Hah?"
"Yang hired saya pun nggak cowok semua. Anak kecil juga pernah sewa saya supaya saya datang ke pertunjukan bakatnya, karena orangtuanya nggak bisa datang. Ingat waktu saya pakai baju balet, kita pulang bareng pakai taksi? Pekerjaan yang saya lakoni ini wajar lho di banyak negara. Misalnya Jepang, Taiwan, Korea. Jasa kayak gini bukan hal tabu. Selama kita tahu batas. Nggak ada yang namanya kontak fisik. Hampir semua klien saya juga sadar akan kontraknya, makanya mereka nggak macam-macam."
Semua informasi itu menyerang Abriel seperti serbuan peluru. Tajam, dan mengenai organ-organ pentingnya. Membuatnya mati rasa.
"Kalau di kepala kamu mikir, kenapa orang-orang itu nggak hired PSK aja, saya rasa karena mereka juga sebetulnya bukan nyari untuk hubungan fisik. Kebanyakan dari mereka hanya butun teman, pengakuan, teman kongkalikong—banyak alasannya, dan nggak semuanya masuk logika sebetulnya," tambah Isabel seraya menyalakan memainkan air di dalam jacuzzi dengan jemarinya.
"Jadi... kamu tuh nggak melakukan hal-hal yang nggak-nggak?" desah Abriel setelah sesaat berpikir keras.
"Nggaklah.What's wrong with you!" kekeh gadis itu. "Niat saya sejak awal membantu orang-orang yang butuh teman. Di banyak negara yang barusan saya sebutin, kamu bisa cek kalau banyak orang yang punya pekerjaan seperti saya. Lagian, saya punya beberapa kenalan yang menjalani profesi ini. Mereka semua baik-baik aja selama punya prinsip dan pintar milih klien. Kalau kamu kenal sama Mei, kamu pasti salut sama dia. Dia sangat picky mencarikan saya klien. Suatu saat nanti kalau udah saatnya, saya bakal bahas soal ini lebih detail. Tapi untuk sekarang, saya gantung dulu, ya!"
Cepat, diburu hormon endorfin, tak sadar Abriel langsung menghampiri Isabel, kemudian memeluknya dengan erat. Puncak kepala gadis itu kini berada di dagunya. Abriel bisa menghirup aroma mint lembut yang menguar dari rambut Isabel. Meskipun Isabel mendorong tubuhnya, Abriel tetap memeluk gadis itu.
"Sorry." Abriel akhirnya melepaskan pelukannya. Wajahnya terasa panas meskipun dadanya sekarang diliputi perasaan sejuk yang luar biasa.
Isabel menatap Abriel tajam. "Clear semua? Kamu bisa pulang sekarang kalau kamu mau."
"Oh, oke, kalau gitu." Abriel sudah mundur. "Kapan kamu balik ke rumah kamu?"
Masih dengan bibir cemberut, Isabel melirik ke arah jendela. "Kayaknya kita nggak bisa jalan lagi, deh, El," ujarnya usai ragu sejenak.
"Kok bisa gitu?" protes Abriel langsung.
"Soalnya, um, sekarang saya lagi deket sama seseorang."
Perasaan sejuk yang baru saja menghinggapi hati Abriel, terasa memudar. "Dekat gimana maksud kamu?"
"Tinggal nunggu dia nembak, kita jadian," ujar Isabel tanpa intonasi. "Kayak kata kamu, saya sebagai perempuan harus menunggu."
Ada gumpalan menyumbat tenggorokan Abriel. "Jadi, maksud kamu kita... selesai, gitu?"
Isabel mendengus. "Kita kan memang nggak pernah jadi apa-apa. Kalau dibilang selesai, ya nggak selesai. Nyatanya, ada orang di luar sana yang nggak seribet kamu."
Abriel melongo. "Kalau kamu lagi dekat sama orang, ngapain kamu mesti repot-repot kasih pesan supaya aku datang ke sini? Kenapa nggak bilang aja di kertas itu?"
"Saya mau semua jelas aja. Saya nggak perlu dicari. Saya nggak butuh dilindungi dari apapun. Setelah kamu tahu apa yang saya kerjakan selama ini fine-fine aja, kamu bisa mundur, kan?"
Abriel pun menghela napas panjang. Belum pernah seumur hidupnya ia diperlakukan seperti orang tolol dan tidak berharga. Dipermalukan hingga ke tulang-tulangnya.
"Kamu emang hebat," bisiknya, bibirnya hanya bergerak sedikit, kaku.
Isabel masih bergeming. Suara air mengucur di bawahnya terdengar sayup-sayup. Abriel bisa mendengar nadi-nadinya berdesir dan napasnya memburu.
"Harusnya, aku emang nggak usah nyariin atau nguatirin kamu," decak Abriel, menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tak percaya mendapati reaksi sekejam itu.
Beku dan dingin, Isabel masih mematung, tampak tak berperasaan. Untuk terakhir kalinya, sebelum beranjak, Abriel membungkuk dalam memberi penghormatan dari lubuk hatinya pada gadis itu sebelum benar-benar meninggalkannya.
* * *
Dalam perjalanan menuju rumah, Abriel nyaris tidak memikirkan apapun. Apa yang baru saja terjadi, tidak terasa benar-benar telah terjadi. Abriel merasakan sensasi baru terbangun dari mimpi, sehingga ia enggan untuk mencerna lebih lanjut. Yang ia inginkan saat ini hanyalah tempat tidurnya. Mungkinkah ia akan terbangun dan kelak mendapati hari ini hanyalah mimpi buruk?
Entahlah. Tapi satu yang pasti, saat ini ponselnya tengah bergetar di dalam sakunya. Getaran yang lemah, teredam, yang seharusnya ia sadari jika kondisi hatinya lebih baik.
* * *
Di seberang sambungan itu, ada seseorang yang begitu menanti untuk dijawab. Gadis itu menunggu nada sambung dengan begitu harap-harap cemas. Tak ada yang lebih ia inginkan selain berbicara dengan Abriel.
Irena hanya tidak pernah tahu bahwa, selain dirinya yang menghadapi hari terburuk. Ada Abriel yang merasa tak lagi memiliki sepenggal harga diri di dalam tubuhnya.


 Andrafedya
Andrafedya











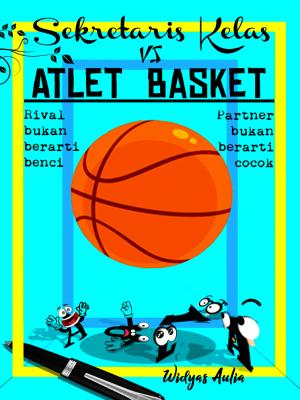


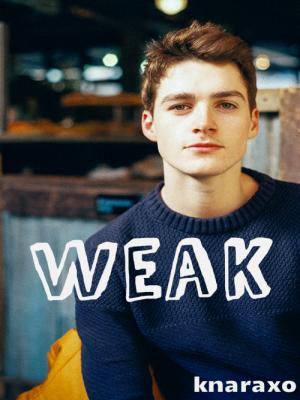

Teenlit namun lbh matang. Metropop namun tidak ngepop amat. Kadarnya pas, bakal lanjut membaca cerita cantik ini. Trims Author untuk cerita ini
Comment on chapter 1. Makhluk MalangKalau suda beres saya akan kasih review.