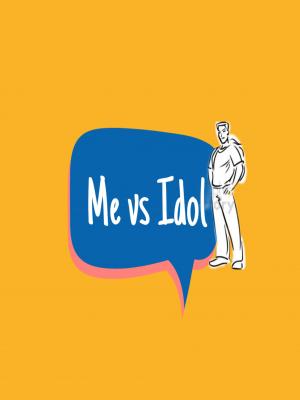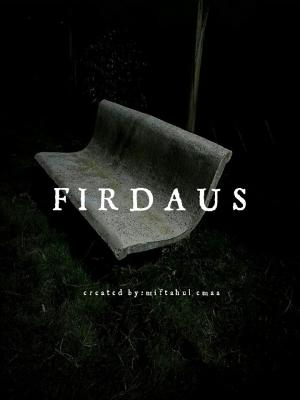Sekitar pukul sebelas, The Lincolns sepakat untuk menyudahi diskusi dan melanjutkannya nanti usai kelas. Sejauh ini, mereka sudah membuat grup belajar di Blackboard dan telah mengunduh beberapa referensi untuk mendukung masalah yang mereka angkat. Sebagian besar adalah masalah lingkungan. Dev dan Vin memilih sampah laut di beberapa negara Asia Tenggara sebagai masalah utama. Sementara Mai dan Bara mendapat inspirasi setelah tanpa sengaja menonton siaran di televisi layar lebar yang tak jauh dari tempat mereka. Kanal berita CNN kembali menayangkan berita tentang badai di Florida, Puerto Riko, dan sekitarnya. Hampir setiap jam, selalu ada breaking news yang membawa informasi terbaru dari kawasan bencana tersebut.
“Kelas masih jam satu. Kalian mau ke mana, guys?” tanya Dev.
“Aku akan kembali ke kamar,” jawab Vin.
“Aku ingin pergi ke perpustakaan,” kata Mai.
“Tirta?”
“Aku mau ikut Mai.”
“Really?” Mai terkejut ‘Tirta’ bilang begitu.
“Apakah kau keberatan, Mai?”
“Tentu tidak! Aku akan sangat senang kau menemaniku.”
“Great!”
“Kau sendiri mau ke mana, Dev?” tanya Vin.
“Aku mau ke Franklin.”
“Apa?? Makan lagi???”
Ketiga temannya heran.
“Oh, ayolah. Sudah beberapa jam berlalu sejak kita sarapan. Lagi pula kita baru saja selesai diskusi. Berpikir memecah banyak glukosa tahu!”
“Ah, terserah kaulah, Dev.”
“Sampai jumpa di kelas, guys.”
Keempat Lincolns pun berpisah. Vin naik ke lantai tujuh. Dev keluar lewat pintu timur menuju Franklin. Mai dan Bara keluar lewat pintu utama dan langsung melangkah ke perpustakaan yang hanya berjarak sekitar tiga ratus meter dari hotel ke arah selatan.
W. E. B. Du Bois Library terletak di tengah-tengah kampus UMass. Gedungnya, yang berbentuk balok dengan dinding bata berwarna merah yang khas, menjulang tinggi ke atas. Ketika para fellow datang ke Amherst, gedung inilah yang pertama kali mereka lihat dari kejauhan. Dengan tinggi sekitar 88 meter, perpustakaan utama UMass ini menjadi perpustakaan tertinggi kedua di dunia, dan perpustakaan kampus tertinggi di dunia[1]. Bahkan, bisa dibilang kalau gedung ini merupakan bangunan tertinggi di Amherst dan kota sekitarnya.
“Kau mau mencari buku apa, Mai?” tanya Bara sambil berjalan di sebelah Mai.
“Aku tidak ingin mencari buku,” jawab Mai.
“Lalu?”
“Aku ingin naik ke lantai 23. Kata Hannah, pemandangan Amherst dari atas sana adalah yang terbaik.”
Hannah adalah mentor Afro-Amerika berambut cornrows yang menjemput Mai di bandara.
“Sepertinya menarik.”
“Let see...”
Begitu masuk perpustakaan, Bara dan Mai langsung mencari lift untuk naik ke lantai tujuan mereka. Beberapa mahasiswa terlihat berlalu lalang. Mereka keluar-masuk lift bergantian. Namun, ternyata hanya Bara dan Mai yang naik sampai lantai 23. Mungkin karena para mahasiswa UMass sudah terlalu sering ke sana dan menganggapnya bukan hal yang istimewa.
Sebenarnya, perpustakaan UMass memiliki 28 lantai. Namun, lantai 23 adalah lantai tertinggi yang memiliki jendela di keempat sisi. Lantai tersebut berisi rak-rak buku untuk beberapa subject, salah satunya nursing. Bara sempat melirik beberapa judulnya saat masuk ke salah satu ruangan yang menghadap ke selatan. Mereka berdua langsung merapat ke jendela yang lebarnya tak sampai satu meter tapi berderet dalam jumlah banyak.
“Waw!” lirih Mai mengagumi apa yang ditangkap oleh matanya.
“Benar-benar luar biasa,” kata Bara.
Tepat di depan mereka, terdapat Old Chapel yang merupakan salah satu bangunan tertua di UMass Amherst. Di depan Old Chapel, ada patung Sam The Minuteman. Agak lebih ke depan sedikit, mereka bisa melihat Haigis Mall yang luas. Lebih jauh lagi, hanya ada hamparan pohon dengan daun yang mulai menguning karena musim gugur. Paling jauh, di horizon, terlihat siluet Lembah Pioneer yang mengelilingi wilayah di sekitar Sungai Connecticut. Pemandangan itu membuat hati keduanya tentram.
“Kita sedang menghadap selatan, bukan?” tanya Mai.
“Betul,” jawab Tirta setelah mengingat-ingat gambaran peta UMass dan wilayah sekitarnya dari Haroon.
Mai lalu menunjuk ke salah satu sudut di sebelah kiri, lalu berkata, “Salah satu alasanku berangkat ke Amerika ada di sana.”
“Apakah ini tentang Emily Dickinson?”
“Ya, kau masih ingat rupanya. Amherst adalah kampung halaman Emily. Dan, rumahnya ada di sekitar wilayah Downtown.”
“Kau beruntung sekali bisa datang ke kampung halaman idolamu.”
“Emily bukan sekedar idolaku, Tirta. Dia adalah inspirasiku,” kata Mai sambil tersenyum. Matanya tetap lurus menatap arah selatan. “Akhir pekan ini aku berencana pergi ke sana.”
“Bolehkah aku ikut?”
“Tentu. Aku akan sangat senang kau pergi bersamaku.”
“Terima kasih, Mai.”
“Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu.”
Mereka berdua lalu tertawa.
“Apakah aku boleh tahu alasanmu mengagumi Emily?” tanya Bara.
Mai tersenyum. “Tentu.”
Ia kemudian mulai bercerita tentang keluarganya yang hidup serba pas-pasan. Ia anak tunggal. Ayahnya adalah seorang penjual pho di sebuah pasar tradisional di salah satu sudut Ho Chi Minh City, sementara ibunya sudah meninggal saat ia masih kecil. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ia selalu membantu ayahnya untuk menyiapkan dagangan mereka. Mulai dari memotong bawang dan jahe, memilih daun salam dan kayu manis, hingga merebus buntut atau iga sapi untuk mendapatkan kaldu yang lezat. Sepulang sekolah, ia langsung pergi ke pasar dan membantu ayahnya berjualan sampai larut malam.
“Pada masa itu, aku merasa kehidupan kami hanya untuk bertahan hidup,” lirih Mai. “Setiap hari bekerja dari pagi sampai malam. Melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun. Sampai pada satu titik, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah selamanya aku akan begini? Terjebak rutinitas di sebuah tempat kecil yang di dalamnya aku tak bisa melihat masa depan. Aku akan terpenjara di sana seumur hidup. Lalu mati tanpa menjadi siapapun dan tidak meninggalkan apapun.”
Bara tak menyangka gadis ceria di sebelahnya memiliki jalan hidup yang begitu berat.
Mai pun melanjutkan kisahnya. Ia bercerita kalau di sela-sela berjualan di pasar, ia sering menyempatkan diri belajar, mengerjakan pekerjaan rumah, dan melakukan hal-hal lain untuk membunuh rasa bosannya. Hingga pada suatu hari, seorang backpacker muda dari Amerika datang ke kedai mereka dan memesan semangkuk pho. Mai yang melayani turis itu.
Setelah mengantarkan pesanannya, Mai kembali ke tempatnya dan lanjut membaca buku pelajaran. Ternyata kegigihan Mai menarik perhatian turis tersebut. Usai mendandaskan pho-nya, turis itu memanggil Mai.
“Hey, girl. Come here!”
Mai pun mendatanginya.
Turis itu kemudian mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah buku kumpulan puisi Emily Dickinson. Ia berkata, “My bag is full and I still want to buy some souvenirs. If you want, I’ll give it to you.”
Mata Mai berbinar-binar menatap buku berwarna hitam dengan siluet seorang gadis berwarna coklat tersebut. Judulnya The Complete Poems of Emily Dickinson—Edited by Thomas H. Johnson. Tanpa sepatah kata, Mai langsung menerimanya. Dari tatapan gadis kecil itu, si turis tahu kalau dirinya tertarik pada buku yang ia beri.
“Just keep it. I hope you enjoy that book.”
Setelah bilang begitu, si turis pergi dengan tas punggung besarnya.
Mai yang masih belum begitu mahir berbahasa Inggris hanya bisa berteriak, “Thank you, Sir!”, dengan logat Saigon yang kental.
Sejak saat itu, Mai seperti menemukan pelita dalam hidupnya. Ia memang belum mengerti isi bukunya, tapi itu jadi motivasi tersendiri baginya untuk belajar bahasa Inggris dan kuliah di jurusan sastra Inggris. Apalagi setelah ia mengetahui kisah hidup Emily Dickinson, gadis rumahan dari Amherst yang puisinya begitu fenomenal.
“Tahukah kau Tirta, selama hidup, Emily lebih dikenal sebagai seorang tukang kebun daripada penyair? Oleh lingkungannya, dia dianggap gadis yang nyentrik dan aneh. Sering mengenakan baju berwarna putih, enggan menjamu tamu, dan lebih suka tinggal di kamarnya.”
“Sungguh?”
“Iya. Dan, hanya sebelas puisinya yang diterbitkan saat dia masih hidup. Padahal Emily menulis sekitar 1.800 puisi dalam kurun waktu empat puluh tahun hidupnya. Dia dikenal dunia setelah orang-orang terdekatnya menerbitkan kumpulan puisinya. Buku yang kudapatkan dari turis asing yang datang ke kedai ayahku saat aku masih sekolah adalah versi paling lengkap. Terbit pertama tahun 1955, hampir tujuh puluh tahun setelah Emily meninggal.”
“Wow! Pengetahuanmu tentang Emily Dickinson sangat luar biasa, Mai,” puji Bara.
“Sudah kukatakan, dia bukan sekedar idolaku, Tirta. Dia adalah inspirasiku. Tentu aku tahu kisah hidupnya.”
Tiba-tiba Bara teringat sesuatu.
“Kisah hidup Emily membuatku teringat Anne Frank.”
“Oh, ya! Kau benar.”
“Kau tahu tentangnya?”
“Tentu. Aku juga membaca diary-nya.”
“Menarik, bukan? Sayangnya, dunia mengenal mereka setelah mereka meninggal dunia.”
“Menurutku, justru itu yang membuat mereka luar biasa. Mereka berhasil menciptakan karya yang membuat dunia mengenal—bahkan mengagumi—mereka. Sekalipun mereka telah tiada.”
“Benar juga.”
“Aku ingin seperti mereka, Tirta. Hidup untuk dikenang. Bukan sekedar hidup untuk hari ini dan besok saja. Tapi untuk selamanya.”
“Hei, kenapa pemikiran kita sama?”
“Benarkah?”
“Ya!” Bara antusias. “Sejak membaca The Diary of A Young Girl, aku mulai menulis diary-ku sendiri. Sampai sekarang.”
“Keren! Bolehkah aku melihatnya?”
Bara menggeleng. “Maaf, Mai. Kau takkan bisa membacanya karena kutulis dalam bahasa Indonesia.”
“Ah, sayang sekali. Pasti menarik jika aku membaca kisah hidupmu yang penuh inspirasi.”
Bara tersenyum. Alasan sebenarnya adalah karena di diary itu tertulis nama Bara, bukan Tirta.
“Kalau begitu, terjemahkan untukku, please.... Aku sangat penasaran. Pasti kisahnya seru!”
Bara tertawa.
Tidak, Mai. Kisahnya sangat membosankan, kata Bara dalam hati. []
[1] Menurut buku Library World Records karya Godfrey Oswald (2009, McFarland & Company, Inc.)


 gadingaurizki
gadingaurizki