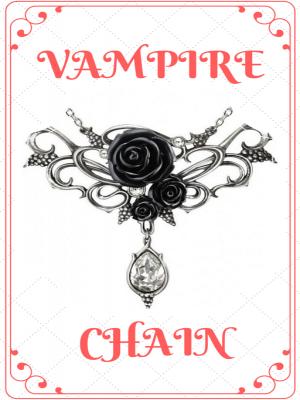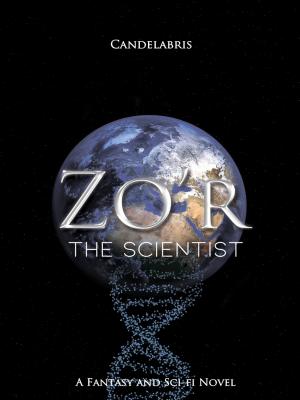Baru beberapa langkah kakiku memasuki Kejora, Ava -rekan sesama pelayan- menyongsong kehadiranku dengan tergopoh. Alisku terangkat melihat dirinya yang tampak cemas. Tidak hanya aku, Andre yang berjalan di belakangku pun ikut menatapnya bingung.
"Aduh, Keira, untung lo udah di sini. Dari tadi ada pelanggan yang nyariin lo. Dia maksa banget pengen dilayani lo." Ava memijit pelipisnya. "Gue sampe pusing, nih. Tiap menit dia manggil gue cuma buat nanyain lo. Mending kalau habis dijawab langsung diem, eh dia malah ngomel-ngomel. Dia curiga kalau lo cuma lagi sembunyi."
Aku dan Andre saling berpandangan. Siapa sebenarnya pelanggan itu?
Tiba-tiba Ava menyodorkan sebuah note dan pulpen. "Nih, lo layanin tuh orang!"
Aku menatap note dan pulpen itu, lalu beralih ke wajah Ava, "Gue ganti baju dulu, ya."
Perempuan itu langsung menggeleng, "Udah nggak usah. Buruan ke sana, tadi dia udah lihat lo dan dia bilang ke gue kalau lo harus segera ke sana."
Kali ini Andre ikut menimpali, "Siapa sih emang tuh orang? Seenaknya aja nyuruh-nyuruh. Sini gue aja yang dateng."
"Nggak usah, Ndre," aku menyentuh lengannya untuk mencegahnya. "Lo pulang aja. Gue mau kerja. Makasih ya es krimnya."
"Tapi--"
Sebelum Andre menuntaskan kalimatnya, aku segera menyela, "Udah sana buruan!"
Andre mengangkat bahu. "Okelah. Bye!"
Sepeninggal Andre, Ava menunjukkan padaku letak meja pelanggan yang ia maksud. Dengan sedikit berdebar, aku mendekati lelaki yang sedang duduk membelakangiku itu.
"Maaf, Anda mau pesan apa, ya?" tanyaku.
Mendengar suaraku, lelaki itu segera menurunkan ponsel yang dibawanya dan membalas tatapanku.
Ya ampun! Bukankah dia orang yang kemarin? Siapa namanya? Kevin? Gavin? Seharusnya aku sudah bisa menebak kalau pelanggan menyebalkan itu adalah dia.
"Kamu?" tanpa sadar telunjukku menunjuk dirinya.
Gavin tertawa. "Nggak usah sok formal gitu, deh. Ngomongnya pake lo gue aja. Kecuali kalau kita udah jadian."
"Jadian?"
Gavin mengangguk. "Gue ralat perkataan gue kemarin. Kalau ternyata lo eligible ya lo masih punya kesempatan buat jadi pacar gue."
Hah? Orang ini nggak waras! Percuma ganteng kalau otaknya bermasalah.
"Oke, terserahlah lo mau ngomong apa." Aku mengeluarkan pulpen dan note yang sejak tadi kumasukkan dalam saku. "Mau pesan apa?"
Bukannya segera menjawab, ia malah menopangkan dagunya di atas tangan. Sebelah tangannya kembali memainkan ponselnya.
Helaan napas berat terdengar dari mulutku. Sabar, batinku menyemangati diri. Untuk kedua kalinya aku bertanya, "Lo mau pesan apa?"
Gavin masih membisu. Ia hanya mengubah posisinya. Punggungnya ia sandarkan ke kursi, sedangkan yang membuatku tak habis pikir adalah kedua kakinya ia letakkan ke atas kursi lain.
Ia pikir ia ada di rumahnya sendiri? Seenaknya saja bertingkah seperti itu.
"Ah, ya sudahlah." Aku bersiap melangkahkan kakiku menjauhinya sebelum ia memanggilku lagi.
"Keira, lo tuh pelayan di sini dan gue pelanggan. Ingat, pelanggan itu raja. Sini layanin gue."
Aku berbalik dan berkata lagi sambil memalingkan wajah, "Oke, mau pesan apa?"
"Gue nggak mau pesen kalau lo buang muka kayak gitu."
Dengan terpaksa, aku menatap wajahnya dan mengulas senyum pahit. "Sekarang bilang ya apa pesanan lo. Gue masih ada kerjaan lain."
"Gue nggak mau pesen kalau senyum lo nggak ikhlas!"
Secara refleks, aku mengepalkan tanganku. Rasanya aku ingin sekali melayangkan tinju padanya.
"Udah, Ra, nggak usah diladenin," perintah sebuah suara.
Aku menoleh ke asal suara. Sudah kuduga suara itu adalah milik Andre. Kedua alisku saling bertaut. Bukannya tadi dia sudah pulang?
Andre mendekatiku dan menatapku sekilas. Lalu ia memandang sebal ke arah Gavin. "Kalau lo berani gangguin pegawai di sini, gue panggil satpam ya biar lo diusir."
Gavin berdiri dan tersenyum miring. "Lo siapa?"
Sebelum suasana memanas dan kami menjadi tontonan gratis bagi orang-orang di sana, aku segera menyentuh lengan Andre. "Udah, Ndre, nggak usah diurusin."
Tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Gavin, Andre bertanya padaku, "Lo mau dia kurang ajar ke pelayan lain juga?"
"Pelayan ini yang kurang ajar duluan ke gue," ujar Gavin.
"Maksud lo karena kejadian kemarin?" tanyaku.
Lagi-lagi Gavin hanya tertawa. "Gue pergi, deh."
Andre dan aku menatap punggung lelaki itu. Baru beberapa langkah, ia membalikkan badannya.
"Tadi gue cuma nguji kesabaran lo aja. You're so patient with me. Bisalah lo masuk kriteria gue," ujarnya padaku sebelum kembali melangkah pergi.
Kepergiannya sekali lagi meninggalkan tanda tanya di kepalaku. Mungkin tidak hanya di kepalaku, tapi juga di kepala Andre.
***
Melirik jam tangan yang melingkar di pergelanganku sebentar, aku lantas mendongakkan kepala, menatap Andre yang sibuk mencoret-coret bukunya. Lelaki ini bersikeras menemaniku sampai waktu pulang tiba. Berkali-kali aku meyakinkannya bahwa Gavin tidak akan datang lagi dan aku akan baik-baik saja. Namun, Andre tetap memaksa. Aku tak punya pilihan lain selain membiarkannya tetap di sini bersamaku.
Tadi setelah Gavin pergi, aku menceritakan kejadian kemarin pada Andre. Aku mengatakan semuanya, tentang Gavin yang menyuruhku berpura-pura menjadi pacarnya di depan mantannya, serta tentang ancamannya padaku. Walaupun aku bercerita dengan nada biasa yang tidak mendramatisasi sama sekali, ceritaku cukup membuat Andre cemas.
"Cowok kayak gitu harus lo hindari, Ra. Gue takut lo kemakan omongan manisnya," ujarnya saat itu.
Aku tersenyum mendengar kecemasannya itu. Sejujurnya, ia tak perlu takut karena satu-satunya cowok yang kupercaya ada di hadapanku. Ya, Andrelah orangnya.
Sejak kejadian kurang lebih satu tahun lalu, aku berhenti memercayai sosok yang disebut laki-laki. Kalau laki-laki yang kuwarisi darahnya saja bisa berkhianat, bagaimana dengan yang lainnya? Namun, aku salah. Masih ada satu laki-laki yang bisa kupercaya. Teman masa kecil yang setia menemaniku bahkan ketika aku berada di titik terendahku.
Lamunanku buyar ketika ponselku berbunyi. Andre juga menghentikan aktivitas belajarnya. Ia memandangku yang hanya menatap layar ponsel dengan diam.
"Kok nggak diangkat?" tanyanya.
Aku mengerutkan kening, "Nomornya nggak dikenal."
"Udah angkat aja. Siapa tahu penting."
Aku mengikuti sarannya. "Halo?" sapaku. Suara di ujung sana terdengar gelisah sampai aku tak bisa mendengarnya dengan jelas. "Halo?" sapaku lagi.
"Keira, ibumu... Cepat kamu pulang, ya!"
"Ibu? Ibu kenapa?" tanyaku panik. Namun, sambungan telepon sudah keburu dimatikan. Firasatku tak enak, jantungku berdetak lebih cepat. Aku bangkit dari kursi dan bergegas meminta izin untuk pulang cepat.
"Kenapa, Ra?" Andre yang kelihatannya sudah tahu jika ada yang tidak beres segera merapikan bukunya.
Dalam keadaan panik, aku tak mengindahkan pertanyaannya itu. "Anterin gue balik, Ndre," pintaku.
***
Sesampainya di depan rumah, sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul. Perasaanku semakin campur aduk seiring dengan napasku yang memburu. Kenapa mereka sampai berkumpul di sini?
Andre menolehkan kepala ke arahku. "Ra, tenangin pikiran lo. Gue ada di sini kok."
Aku mengangguk. Setelah menguatkan hati, dengan perlahan kuturunkan badanku dari motor Andre. Sesuai perkataan lelaki itu, tak lama setelah aku turun, ia pun melakukan hal yang sama. Berdua, kami berjalan masuk ke dalam, sementara beberapa pasang mata tampak tertuju pada kami.
"Ibu!" teriakku ketika kulihat wanita itu sedang duduk memeluk lutut. Wajahnya menyorotkan sinar ketakutan. Pelukan erat segera kuhadiahkan untuknya. "Ibu, jangan takut. Aku udah pulang." Kubelai rambutnya dan kucium kepalanya, mencoba mengusir ketakutannya.
Seorang tetangga bernama Bu Sari menepuk pundakku. "Keira, tadi nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba saja ibumu keluar. Dia seperti orang kebingungan. Saat saya dan tetangga lain mencoba mendekatinya, ia malah ngamuk. Untung sekarang sudah bisa tenang."
Tanpa melepaskan pelukanku dari Ibu, aku tersenyum pada Bu Sari. "Makasih, Bu. Aku nggak tahu apa jadinya kalau Bu Sari dan tetangga lain nggak di sini."
Bu Sari membalas senyumanku sambil mengelus punggungku. "Besok lagi, mungkin lebih baik kalau pintu rumahmu dikunci saja. Bukan apa-apa, tapi kalau ibumu keluar tanpa sepengetahuan tetangga lain, bagaimana? Lagipula, kamu sudah menyingkirkan benda-benda tajam dan mengunci dapur kan?"
Aku merenungkan kalimat itu. Tebersit rasa tak tega membayangkan wanita yang sudah mengandungku itu harus dikurung dalam rumah. Namun, barangkali itu memang cara yang tepat. Apalagi mengingat fakta bahwa aku belum sanggup membayar perawat untuk menjaganya.
"Kamu juga jangan kebanyakan main!"
Kali ini aku melepaskan pelukanku dan menoleh ke sumber suara. Bukan hanya aku yang menoleh, tapi juga Bu Sari, Andre, dan tetangga lain yang ada di situ.
"Jam segini baru pulang, sama pacarmu lagi. Nggak inget apa sama ibumu?"
Tanganku mengepal, tapi sebisa mungkin kuatur amarahku agar tidak meledak. Sebenarnya ingin sekali aku membantah kalimat yang dilontarkan Bu Wati, tapi aku memilih diam.
Bu Sari menyentuh lenganku seolah memintaku sabar. Kemudian wanita itu berkata, "Keira ini kan sudah kelas dua belas, Bu. Wajar kalau jam segini baru pulang. Bu Wati kayak nggak tahu aja kalau anak kelas dua belas itu biasanya les sepulang sekolah."
"Justru karena anak saya satu sekolah sama dia makanya saya tahu kalau Keira ini sering bolos les, nggak ngerjain tugas, dan...."
"Cukup!!"
Suara Andre yang tegas serta merta membuatku dan para tetangga menoleh ke arahnya.
Andre berdiri berhadapan dengan Bu Wati. "Kalau Ibu tetangga yang baik, seharusnya Ibu tahu kalau Keira ini sedang kesusahan. Dia baru pulang jam segini bukan karena main, tapi karena ia harus bekerja."
"Kerja?" Bu Sari memandangku heran. "Kamu kerja? Bukannya ayahmu selalu mengirim uang untukmu dan ibumu?"
Aku tak menjawab pertanyaannya. Aku justru menatap Andre dan mengisyaratkan padanya untuk memberiku bantuan.
Untung saja Andre menangkap isyaratku. Ia berdeham sejenak sebelum berkata, "Maaf, Ibu-Ibu, tapi Keira dan ibunya butuh istirahat. Lebih baik Ibu-Ibu pulang dulu, ya."
"Kamu itu yang harusnya pulang," sahut Bu Wati. "Anak laki-laki kok jam segini main ke rumah anak perempuan. Nggak elok."
"Huss!" Bu Sari menempelkan telunjuknya di depan mulut Bu Wati. Ia lantas menatapku, Andre, dan Ibu secara bergantian. "Kami pamit dulu, ya. Jaga ibumu baik-baik."
***
Setelah Ibu tertidur, aku menghampiri Andre yang sibuk belajar di ruang tengah. "Ndre, lo pulang aja, udah malem."
"Lo nggak papa?"
"Gue udah biasa kok."
Andre tampak menimbang sebentar sebelum akhirnya membereskan buku-bukunya. Ia berdiri sambil memakai jaket dan tasnya. "Bener ya yang dibilang Gavin. Lo tuh sabar banget. Bahkan orang yang baru kenal sama lo aja bisa bilang begitu."
"Ah, lo bisa aja," elakku.
"Keira," panggil Andre lirih. "Coba kalau lo belum pindah rumah, mungkin tetangga lo itu nggak bakal nyinyirin lo."
Aku tertawa mendengarnya. "Tapi kalau nggak ada dia dan tetangga yang lain, gue nggak tahu apa yang bakal terjadi sama Ibu."
Tawaku menular pada Andre. "Ya, udah gue pamit, ya."
Aku mengantarnya sampai ke depan. Sebelum lelaki itu memacu motornya, ia menaikkan kaca helmnya. "Gue kangen waktu kita masih tetanggaan."
Kalimat itu menggantung di kepalaku. Yah, seandainya saja kita masih bertetangga.... Seandainya saja satu kesalahan tak berbuntut pada kesalahan lain....
***


 hannfridd
hannfridd