Pukul lima sore, mereka sudah bersiap di Stasiun Gambir. Sebentar lagi kereta mereka akan datang. Kereta yang akan membawa mereka, menuju ke kota Malang, dalam sebuah petualangan.
Dengan sebatang rokok di antara jemari tengah dan telunjuk, Boy melambungkan angan ke segala penjuru. Ia membayangkan, apakah ia berhasil membawa para sahabatnya sampai puncak? Atau hanya bertahan sampai beberapa pos saja?
Entahlah.
Yang jelas, Boy mempunyai target. Tak apa tak sampai puncak, tapi paling tidak, para sahabatnya harus melihat keindahan Ranu Kumbolo.
“Jangan kebanyakan rokok, Boy. Nggak baik.”
Boy melirik ke kursi sebelahnya. “Caca? Sejak kapan disitu?”
“Beberapa menit lalu, kayaknya. Lo lagi asyik ngelamun, sih, jadi nggak peka sama kedatangan gue.”
Boy segera membuang rokoknya, ke tempat sampah yang tepat ada di dekatnya, kemudian ia kembali ke kursi tunggunya lagi.
“Kok dibuang rokoknya? Kan belum habis?” Tanya Caca.
“Kasihan kalau lo sampai kena asap rokok.”
“Tapi lo nggak kasihan sama diri lo sendiri? Ngerokok tiap hari… eh, bahkan mungkin, beberapa jam sekali. Ya, kan?”
Boy menghela nafas. “Nggak sesering itu, kok, Ca. Jauh lebih parah mantan lo.”
“Mantan gue?”
“Alah. Lo kebanyakan mantan, sih! Juang, maksud gue. Dia kan ahli banget rokoknya.”
Caca tertawa. “Ah, ya. Gue aja sampai capek bilanginnya.”
"Untung lo putus ya sama dia."
"Ya gitu.. Tapi, dia baik, loh."
Mereka berbincang. Kali ini membahas tentang rokok dan Juang. Entah, segala hal yang menyangkut tentang Juang, pasti mengundang tawa. Begitupun Caca dan Boy, kini tertawa karena membicarakan Juang yang lebih mencintai rokok daripada uang di ATM-nya.
Tiba-tiba, pembicaraan mereka terinterupsi.
“Boy, gue mau tukar tempat duduk!”
Itu suara Maya. Tiba-tiba, Maya hadir di hadapan mereka.
“Tukar? Kenapa?”
“Gue baru sadar, kursi kereta gue tuh sebelahan sama dia. Gue gak mau!”
‘Dia’, yang dimaksud Maya adalah Caca.
Caca mengerutkan keningnya. “Emang kenapa, May? Segitu nggak sukanya? Ini cuma duduk, May. Kita diem-dieman, pun, nggak masalah.”
“Gak. Gue nggak sudi!”
"Kenapa, sih?" Caca sebal sendiri.
"Ya lo bayangin aja, berjam-jam perjalanan, gue harus duduk di sebelah lo! Gue males! Emosi melulu bawaannya tau nggak!
Deg.
Caca diam. Sangat terkejut begitu tau bahwa Maya bisa mengeluarkan nada tinggi di hadapannya hanya karena masalah sepele, yaitu kursi kereta api yang akan membawa mereka menuju petualangan. "Nggak usah pakai nada tinggi kali, May."
"Nggak terima?"
"May, coba deh, lo ngomong ke gue.. Kenapa lo begitu sentimen dan penuh sarkasme kalau ke gue?"
Maya tersenyum kecut. "Lo punya otak, kan? Coba deh, pikir sendiri."
"Gue punya otak. Tapi sampai sekarang gue nggak tau, salah gue dimana. Gue bukan peramal, May."
"Berarti lo nggak peka!"
Deg.
Keadaan makin memanas. Bahkan beberapa pasang mata mulai menatap dan melirik kearah dua srikandi manis yang tengah berperang.
Boy mengangkat tangan. “Oke, oke. Kita tukar tempat. Caca sebelahan sama Juang, dan Maya sebelahan sama gue. Gimana? Clear, kan?”
Maya mengangguk. Terlihat raut kelegaan dari wajahnya. “Thanks!”
Setidaknya, mengalah lebih baik daripada membuat dua wanita yang berada dalam satu lingkaran, bertengkar hebat di dalam kereta.
Itu jauh lebih mengerikan.
*
*
Kereta belum datang juga. Kali ini, Caca yang kelaparan, memutuskan tuk melangkah ke kafetaria di dalam stasiun tersebut, bersama Sherin.
Nasi goreng dan es the milik Caca, serta roti bakar cokelat dan susu milik Sherin, sudah tersaji di depan mereka berdua.
Kali ini, mereka bicara tentang hal yang sedikit serius. Mengenai Sherin.
“Lo jujur sama gue, Sher, please,” ucap Caca. “Gue sahabatan sama lo dari SMA. Gue duduk sebangku sama lo terus-terusan. Dan gue tau semua cerita lo. Kata lo, Marcell dah berhenti pukulin lo, kan?”
Sherin mengangguk ragu. “I…iya.”
“Bohong.” Caca menunjuk pipi kanan Sherin. “Tuh, biru.”
“Ini kebentur biasa, Ca…”
Caca menggeleng. “Gue nggak bodoh, Sher. Gini-gini, gue mantan anak PMR. Dan gue tau, itu ulah Marcell. Kata lo, dia udah berhenti. Kenapa tiba-tiba dia pukul lo lagi?”
Sherin menggigit bibirnya. “Kayaknya, lo selalu bisa nebak gue. Jadi percuma gue tutupin semua dari lo.”
“Emang.”
“Marcell sekarang mulai pukulin gue lagi, Ca. Kayaknya, dia banyak masalah, jadi kumat.”
“Dan lo masih bertahan?”
Sherin mengangguk. “Kan lo tau, Marcell udah ba—“
“Sumpah, itu nggak penting, Sher. Jangan karena hal itu, lo biarin diri lo disiksa habis-habisan. Lo berharga. Semua perempuan itu berharga. Nggak ada yang bisa sepelein seorang perempuan.
--Apalagi lo perempuan baik, pintar, bijak… Ah, nyaris sempurna,” kata Caca.
Benar. Perempuan seharusnya dijaga, bukan disiksa, apalagi karena mencari pelampiasan. Semua perempuan berhak mendapat pria yang bisa menjaga serta menuntun kearah yang lebih baik.
Jika lelaki terdekat malah merusak dan menyiksa, untuk apa ada sebuah cinta diantara keduanya? Karena sebenarnya, cinta tidak pernah menyakiti, apalagi sampai hati bermain fisik.
“Angga baik, loh,” kata Caca tiba-tiba.
“Terus?”
Caca menyuap nasi goreng kedalam mulutnya. “Semua orang tau, kalau Angga suka sama lo sejak lama. Bahkan, Angga rela jadi orang terdekat lo, meskipun bukan sebagai pacar. Dia selalu ada buat lo, bahkan lebih sering dari keberadaan Marcell untuk lo. Dia selalu hibur lo, dan yang terpenting, dia nggak pernah sekalipun kasar ke lo. Gue tau, lo pasti sadar akan itu.”
Deg.
Memang benar. Sherin sadar.
Bahkan tak dipungkiri, Sherin sangat nyaman.
“Pikirkan baik-baik tentang posisi Angga. Dia pantas jaga lo, Sher,” kata Caca, menutup topik, sebelum mereka melanjutkan suapan makanan selanjutnya.
*
*
Sementara di sudut lain, Juang dan Boy sedang menikmati kegiatan ‘merokok’ mereka. Ini rokok Boy yang kedua di stasiun, karena yang pertama, baru setengah batang sudah dibuang karena kehadiran Caca tadi. Setelah Caca pergi makan, Boy akhirnya memutuskan tuk sedikit minggir dan bersatu dengan Juang di sebuah arena tuk merokok. Ah, nikmat yang indah.
“Lo oncom banget, sih, sengaja amat bikin Caca sama Maya duduk bareng,” kata Juang, usai Boy menceritakan rengekan Maya yang meminta untuk tukar kursi.
“Niat gue, biar mereka bisa ngobrol bareng,terus damai,” jawab Boy enteng.
“Nggak segampang itu, lah! Lo kan paham, mereka berantem udah dari kelas tiga SMA! Eh, bukan mereka sih, tepatnya Maya doang yang sewot, Cacanya mah masih santai.”
Benar. Selama ini, Caca masih berusaha bersikap baik pada Maya, tapi Maya tetap saja menjaga jarak, bahkan hingga menghindar terang-terangan dengan kata-kata pedas.
“Kenapa ya, Maya bisa sebenci itu sama Caca?” Boy bergumam pelan.
“Jangankan kita. Caca aja nggak tau salah dia apa.”
"Waktu Caca pacaran sama lo, mereka belum berantem, kan?"
Juang menggeleng. "Belum. Masih lengket."
Keduanya diam lagi. Memang, itu masalah pribadi. Tapi tetap saja, itu mempengaruhi lingkar persahabatan mereka.
“Caca cantik, ya. Nanti lo duduk bareng dia. Nggak mau balikan?”
Juang menoyor kepala Boy pelan. “Gue udah punya Vina, ah!”
“Bercanda, bercanda. Tapi serius, lo sama Caca dulu lumayan lama, pacarannya. Satu tahun ada kali, ya?”
Juang mengangguk. “Soalnya Caca baik banget, gila. Gue aja yang kurang ajar.”
“Emang lo kenapa? Kalian tiba-tiba putus, dan nggak mau cerita ke kita-kita. Kan sialan.”
“Privasi, Boy. Kapan-kapan, deh, gue ceritain.”
Boy mengangguk, lalu menghisap rokoknya lagi.
“Lo aja yang sama Caca. Cocok. Caca kan pernah suka sama lo.”
Deg.
“Kapan?” Boy terkejut, sedikit.
“Pas SMA, lah. Caca aja sampai kirim puisi ke lo. Tapi lo malah jadian sama Nadiva, dan lo kira, puisi itu dari Nadiva.”
Deg.
Boy membuang rokoknya lagi. Sebuah rahasia terungkap. “Sialan! Pas itu, gue emang deket sama Caca dan Nadiva. Terus tiba-tiba, Nadiva kasih gue puisi, dan dia bilang, itu buatan dia, ungkapan perasaan dia buat gue.”
“Yeee, oncom! Itu Caca yang buat. Terus Nadiva menawarkan diri untuk kasih puisi itu ke lo. Eh, Nadiva malah kurang ajar, bilang kalau itu puisi dia. Ya udah, deh, lo jadian sama Nadiva. Dan Caca yang lagi patah hati gara-gara lo, gue hibur terus, akhirnya malah gue yang sama Caca,” ungkap Juang panjang lebar.
“Serius itu puisi dari Caca?”
Juang mengangguk. “Orang Caca bikinnya di perpustakaan, sama gue dan Sherin. Jelas kita tau, lah!”
“Dan kalian nggak cerita?”
“Nggak boleh sama Caca. Caca nggak mau ribet. Dan Caca nggak mau ngerusak hubungan lo sama Nadiva.”
Boy menggeleng. “Untung gue udah putus dari Nadiva.”
“Deketin gih, Caca. Kali aja, dia masih ada rasa ke lo,” usul Juang. “Percaya, deh. Laki-laki yang bisa dapat Caca, dia adalah laki-laki beruntung. Caca baik, cantik, dan totalitas. Kalau gue bisa putar waktu, gue nggak akan ngelakuin kesalahan yang bikin gue sama Caca putus. Kadang gue masih nyesel, putus dari Caca,” kata Juang, lagi.
Boy menggumam dalam hati. Kalau gue bisa putar waktu, gue bakal balik ke masa SMA, dan ungkapin perasaan ke Caca lebih awal. Sayangnya, mesin waktu cuma fiksi, aslinya nggak ada.
Lamunan dan perbincangan mereka terhenti, ketika pemberitahuan menyuarakan, bahwa kereta Gajayana yang akan mengangkut mereka, sudah datang.
Boy segera mengetik pesan di grup, untuk para sahabatnya yang masih berpencar.
Drrrt…
Boy: Guys, kereta sudah datang. Ayo, naik.
*
*


 Ervinadyp
Ervinadyp









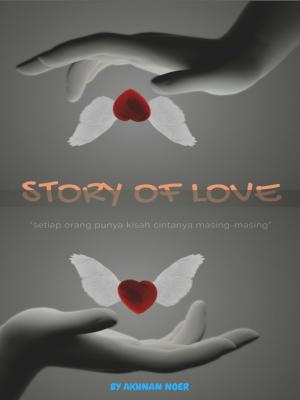







Penasaran sama lanjutannya
Comment on chapter Chit Chat