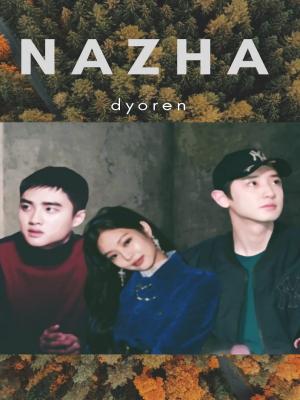Koln, November 2017
“Bagaimana mungkin aku akan ikut kuis Selasa depan? Ini sudah hari Sabtu.” Aku menutup wajahku frustasi dengan buku Hukum Internasional milik Nadira. Nadira mengambil bukunya menjauh dari wajahku.
“Kau tidak akan mungkin bisa mengikuti kuis jika kau hanya mengeluh, Nona.” Ucap Nadira kesal. “Kau baru membacanya 15 menit dan bertingkah seolah kau sudah membolak-balik halamannya sepanjang hidupmu.”
“Itu berlebihan.” aku menginterupsi. “Baiklah. Kembalikan bukunya. Aku berjanji kali ini akan membacanya selama satu jam penuh tanpa mengeluh.” Aku tersenyum lebar. Sedang Nadira mengangkat alisnya sebelah dengan tampang tidak yakin.
“Akan aku buktikan!” kataku percaya diri.
“Let us see.”
Sementara aku sibuk membaca paragrap demi paragrap, di sisi tempat tidurku Nadira duduk sambil menyilangkan tangannya. Dia terus mengamatiku seperti seorang sipir yang mengawasi tahanan.
“Jangan mengamatiku. Kau tidak akan tahan dengan pesonaku nanti,” ujarku tanpa mengalihkan pandangan dari buku.
Nadira melengos dan langsung berdiri dari tempat duduknya berpindah ke sofa di dekat jendela dan mengambil novel karya Haruki Murakami milikku. Aku melanjutkan bacaanku. Kami tenggelam dalam bacaan masing-masing.
“Ada yang mau Pizza?”
Saat aku baru saja menikmati membaca buku dengan tebal 400 halaman ini, Leon datang ke bangsalku dengan membawa 2 kotak pizza ukuran super large.
“Kau datang hari ini, Leon?” tanya Nadira dan menutup buku Murakami-ku.
“Ya mampir sebentar. Ini ada pizza. Kalian pasti suka kan?”
“Tentu saja.”
“Kau akan kena masalah jika pihak rumah sakit mengetahuinya, Tuan Conor.” Kataku masih sambil membaca.
“Tenang saja, Nona Atmaja. Tidak akan ada yang terkena masalah.”
“Ada,” jawab Nadira
“Siapa?” tanya Leon.
“Arrum.”
Merasa namaku disebut, aku protes. Kali ini tidak lagi sambil membaca. Konsentrasiku sudah lenyap.
“Kenapa aku?”
“Leon, kau tahu? Arrum akan kena masalah karena dia tidak juga menyelesaikan bahan kuis untuk Selasa depan.”
Errrr… dasar Nadira!
“Aku sedang berusaha menyelesaikannya saat tiba-tiba saja 2 kotak pizza super large terdampar ke bangsalku. Jadi, aku rasa sekarang prioritasku adalah menyelesaikan Pizza itu terlebih dahulu. Aku lapar. ”
“See! Kau bahkan tidak bertahan selama 15 menit.”
“Whatever!”
“Hohoho… aku terjebak di antara pertengkaran ini.” Kata Leon dengan wajah menggemaskan. Apa? Mengggemaskan? Sejak kapan Leon menjadi menggemaskan?
“Maafkan Arrum ya, Leon. Dia memang seperti itu.”
“Hahaha tidak masalah. Ini bukan pertama kalinya. Sekarang, ayo makan Pizzanya.”
Karena sudah merasa jauh lebih baik aku memutuskan untuk bergabung duduk di sofa bersama Nadira dan Leon. Sambil mendorong penyangga kantung infusku, aku berjalan perlahan. Leon berniat ingin membantu namun aku memberitahunya kalau aku sudah tidak apa-apa.
“Apa kau membaca Murakami, Nadira?” tanya Leon saat tidak sengaja melihat novel dengan sampul putih itu tergolek di sisi meja.
“Tidak. Itu milik Arrum. Aku baru saja ingin membacanya tadi.”
“Itu milikku. Apa kau mau meminjamnya, Leon?”
“Ah tidak. Selain Murakami, buku apalagi yang suka?”
“Hemm banyak. Ernest Hemingway, Jane Austin, Tere Liye. Tere Liye itu penulis asal Indonesia jika kau pernah mendengarnya. Kemudian Agatha Christie, Sherlock Holmes. Aku juga suka komik Detective Conan dan…”
“Kau juga menyukai Detective Conan?”
Detective Conan? Ah! Iya. Gilang juga menyukai Detective Conan dan Sherlock Holmes. Gilang? Bagaimana kabarnya? Dan buku waktu itu aku tidak ingat apa aku membawanya pindah ke Jerman?
“Dan?” tanya Leon.
“Eh? Dan komik Jepang lainnya. Hehe.”
“Di rumahnya, ada satu rak buku kaca besar untuk semua koleksi bukunya.” Kata Nadira dengan mulut belepotan. “Tapi tidak ada satupun buku mengenai politik dan hukum. Padahal dia ini mahasiswi jurusan hukum.”
“Hahaha lucu sekali. Tapi ternyata kita memiliki kesamaan. Aku juga suka Sherlock Holmes dan Detective Conan.”
“Oh ya?” kataku.
“Ya. Aku punya koleksi semua bukunya lengkap. Komik juga. Animenya, live action. Semuanya.”
“Wah, aku baru tahu.” Kataku. Aku menambahkan mayonnaise ke atas pizza kejuku.
“Itu karena selama ini kau tidak mencoba ingin tahu.” Nadira menyamber percakapan lagi. Aku melengos sedang Leon tersenyum seadanya namun tetap manis. Apa? Manis? Sejak kapan Leon menjadi manis?
“Ah ya. Jika kau sudah keluar rumah sakit nanti bagaimana jika kita bertiga menonton movie conan yang ke 21 di bioskop?” ajak Leon.
“Bertiga? Apa kau maksud aku salah satu diantara tiga itu?” tanya Nadira.
“Tentu saja.” Kata Leon polos. Dia tidak tahu kalau Nadira sangat anti dengan anime dan apalah yang berhubungan dengan itu.
“Tidak akan, Leon. Nadira tidak akan pernah bersedia untuk satu hal itu. Dia bahkan tidak akan memasuki kamarku jika aku tidak mau memindahkan komik-komikku ke rak buku di ruang tamu.” Kataku dengan sedikit dramatis. Aku memberikan isyarat pada Leon untuk mendekat agar aku membisikkan sesuatu padanya. Leonpun mendekatkan telinganya denganku. “Mantannya yang paling dia cintai adalah penggila Anime. Dia telah diduakan oleh Waifu mantannya itu,” aku berbisik dengan sura yang sebenarnya masih bisa didengar jelas oleh Nadira.
Nadira memutar bola matanya. “Silakan muat itu di kolom utama koran besok pagi, Arrum. Beritahu hal itu pada seluruh dunia.”
Aku dan Leon tertawa terbahak. Sedang Nadira mencibir kami.
“Baiklah. Aku sudah selesai dengan Pizza ini. Aku mau pergi,” Nadira bangkit dari tempat duduknya dan pergi meski aku memanggil namanya berulang kali.
“Hahaha dia selalu begitu. Tenang saja.”
“Aku percaya,” kata Leon. “Jadi?” lanjutnya.
“Jadi?” kataku bertanya balik dengan bodoh.
“Jadi apa kau mau pergi menonton movie Detective Conan ke 21 bersamaku?”
Apa Leon baru saja mengajakku berkencan atau semacamnya? Tapi tidak. Sepertinya tidak mungkin. Lagipula ini hanya karena kami menyukai sesuatu yang sama. Lagipula, menemukan orang yang sama- sama suka Detective Conan itu jarang kutemui. Tapi apa iya?
“Baiklah.”
Leon tersenyum lagi.
“Ngomong-ngomong, kau seperti seseorang yang kukenal. Dia juga suka DC dan Sherlock Holmes,” kataku. Aku tidak tahu mengapa aku merasa perlu untuk memberitahu hal ini pada Leon. Membicarakan masa laluku dengan orang lain selain Nadira tidak pernah kulakukan.
“Siapa? Apa dia temanmu?”
“Hem. Semacam itu.” Jawabku menggantung. Aku tahu Leon menatapku penuh tanda tanya. Namun dia tidak bertanya lebih jauh. Sungguh pengertian.
“Apa kau rindu teman-temanmu?”
Leon mengulang pertanyaannya tempo hari. Ternyata dia ingat bahwa pertanyaannya belum kujawab.
“Terkadang iya.” Aku menerawang. “Lalu bagaimana denganmu? Siapa yang waktu itu sedang kau rindukan? Apakah keluarga dari Ibumu di Filipina?”
Leon menatapku lurus. Seolah dengan matanya ia dapat mengetahui rahasia terdalam yang aku simpan.
“Kau. Aku merindukanmu.”
Aku terenyak. Selama 5 detik mataku beradu tanpa kedip dengan manik indah milik Leon.
“Aku merindukanmu karena tidak ada lagi yang merepotkanku di kampus.” Leon tertawa setelahnya. Dia tertawa cukup lama seolah itu lelucon paling lucu dan memang seharusnya ditertawakan. “Harusnya kau melihat wajahmu tadi, Arrum.”
Aku mencibir. Ternyata Leon bisa konyol juga. Dia selalu tampak dewasa selama ini. Ternyata banyak hal-hal yang tidak aku ketahui tentang Leon.
“Ah sudahlah! Aku mau membaca lagi.”
Leon masih tertawa. Yaampun anak itu. Tapi, kenapa aku senang melihat Leon tertawa seperti itu? Dia mengingatkanku pada Gilang. Mereka memiliki kesamaan. Tapi, apa benar mereka memiliki kesamaan? Atau aku merasa mereka memiliki kesamaan hanya karena aku sedang merindukan Gilang?
Tunggu! Rindu? Apa aku Rindu Gilang? 5 tahun berlalu apa aku belum bisa melupakan pria itu? Aku sudah pindah negara. Aku kini di Jerman. Di Koln. Banyak pria tampan yang lebih dari Gilang. Harusnya aku bisa menemukan satu dari mereka. Ya, harusnya.
Tapi nyatanya, seberapa rapihpun kita memilah kenangan mana yang ingin dibawa dan mana yang ingin ditinggalkan, kenangan pahit lah yang sering terbawa kemana-mana. Bukan hanya di dalam langkah, tapi juga dalam mimpi panjang di tengah malam.


 BluePaper
BluePaper