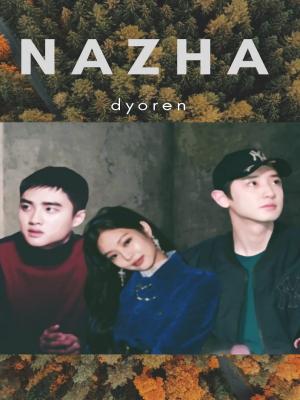Koln, November 2017
“Kau sudah sadar?”
Silau. Mataku mencoba beradaptasi dengan cahaya yang masuk ke retina. Perlahan aku mencoba membuka mata. Sudah berapa lama mataku tertutup? Dan siapa tadi yang bertanya padaku? Apa aku sedang di dalam kubur? Apa tadi itu malaikat? Ah kepalaku pusing sekali.
“Arrum, kau baik-baik saja?”
“Hem? Ini dimana?”
Aroma khas bangsal rumah sakit menancap di hidungku. Membuat kepalaku bertambah pusing.
“Kau pingsan. Ini rumah sakit. Kau ingat?”
Pingsan? Rumah sakit?
“Orang tuamu akan segera datang. Aku sudah mengabari mereka.”
Aku mencoba mengingat siapa pria di sampingku ini. Siapa? Ah iya!
“Leon?”
“Ya Arrum. Ini aku. Beristirahatlah. Orang tuamu akan segera datang.” Leon menatapku dengan matanya yang dalam. Aku tidak pernah tahu sebelumnya jika matanya memiliki pesona seperti ini. Tiba-tiba saja rasa pusing di kepalaku sudah tidak ada. Apa matanya memiliki kekuatan magis?
“Kau…apa kau yang membawaku ke sini?” Aku melirik tanganku yang telah dimasuki jarum infus. Aku pasti benar-benar pingsan. Jika tidak pasti jarum itu tidak akan menusuk kulitku saat ini. Melihat jarum membuatku mual.
“Iya. Kau pingsan saat aku menawarimu tumpangan. Lalu aku membawamu ke sini.” Leon menghembuskan nafas dalam. “Kau terlalu memaksakan diri, kau tahu? Apa kau sudah membaik sekarang?”
Aku mengangguk lemah. Rasanya sudah lebih baik sekarang.
“Kau mau sesuatu? Minum?”
“Ya, boleh. Rasanya aku seperti baru selesai dari berjalan di Sahara.”
Leon menolongku untuk duduk. Dan memberiku segelas air segar.
“Maaf telah merepotkanmu,” kataku tidak enak. Leon tersenyum lagi.
“Sekarang tidurlah. Kau harus istirahat.”
“Aku baru saja bangun dari tidurku yang entah sudah berapa lama. Berapa lama aku pingsan?”
“Sekitar tiga jam,” Leon mengingat-ingat.
“Itu merupakan istirahat yang cukup.”
Leon tertawa.
“Kau tidak berubah, yah.” Kata Leon. Apa maksudnya? “Kau tidak berubah dari saat pertama kali kita bertemu. Kau ingat?”
Apa maksudnya saat aku salah menggunakan lokernya dua tahun lalu?
“Saat itu kau juga keras kepala.”
“Hahaha kau ini.”
Leon tersenyum padaku dan menatapku tanpa berkedip. Aku salah tingkah dipandangi seperti itu.
“Apa ada sesuatu di wajahku?” Aku berusaha agar Leon tidak menatapku lebih lama lagi. Leon menundukkan kepalanya dan tertawa lirih. Ia bangkit dari tempat duduknya. Berjalan perlahan menuju jendela berbingkai kayu bergaya klasik. Dimasukkannya satu tangannya ke saku celana. Ia menatap ke luar jendela. Salju turun dengan syahdu. Jeda terbentuk begitu lama diantara kami. Aku tidak tahu mengapa atmosfernya menjadi begini.
Melihat Leon tengah memandang kosong seperti ini, membuatku merasa nyaman. Apa yang tengah ia pikirkan saat ini?
“Terimakasih,” ucapku kemudian memecahkan keheningan. “Sepertinya aku sering sekali merepotkanmu.”
“Sepertinya kau ditakdirkan bertemu denganku untuk itu,” kata Leon bercanda. Kami tertawa. Suasananya tidak pernah senyaman ini sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya Leon membantuku. Entah bagaimana Leon sering sekali ada di saat aku mengalami kesulitan secara kebetulan. Ah tidak ada yang kebetulan. Ini takdir.
“Emm…bagaimana kuliahmu?” tanyaku mencari topik pembicaraan.
“Tahun depan mungkin aku akan lulus. Kau sendiri?”
“Pasti akan banyak materi yang aku lewatkan selama di rumah sakit,” aku kecewa mengingat kalau besok akan ada kuis. Dan awal Desember ini kami akan mengadakan ujian sebelum akhirnya libur musim dingin tiba. Kali ini Leon benar. Aku tidak boleh memaksakan diri lagi jika tidak ingin ketinggalan banyak materi sebelum ujian. “Apa kau akan lulus tahun depan?”
“Hem… ya begitu. Aku akan mendaftarkan wisudaku bulan Februari nanti. Dan mengikuti wisuda sebelum libur musim panas.”
Aku manggut-manggut.
“Apa yang kau pikirkan?” tanya Leon.
“Aku sedang berpikir bagaimana aku bisa bertahan di kampus kalau kau sudah lulus nanti. Siapa lagi yang nanti akan aku repotkan?”
Kami tertawa lagi.. Leon tertawa sangat lepas. Seolah ia adalah pria 21 tahun paling bahagia di dunia. Saat tertawa gigi rapihnya terlihat jelas. Matanya menyipit. Dan garis-garis di bawah matanya terbentuk. Aku tidak pernah memperhatikan Leon sebelumnya. Tidak pernah seperti ini.
“Arrum,” Leon memanggilku lembut.
“Ya?”
“Apa kau pernah merindukan seseorang?” Tatapan Leon kembali pada jendela.
Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Rindu? Tentu saja pernah. Siapa yang tidak pernah merindukan seseorang.
“Tentu saja. Aku rasa tidak ada satupun orang yang tidak pernah merindukan seseorang. Kenapa? Apa kau merindukan seseorang? Kekasihmu?”
Leon tertawa mendengar petanyaanku.
“Kau sendiri, siapa yang kau rindukan?”
“Curang. Kenapa malah balik bertanya. Tapi baiklah akan aku jawab karena kau telah menolongku. Aku rindu Bibi Fatimah. Aku rindu Pak Rahmat…”
“Siapa itu Bibi Fatimah dan Pak Rahmat?” Tanya Leon memotong ucapanku.
“Mereka adalah orang yang dulu pernah bekerja di rumahku sebelum aku pindah ke Jerman. Mereka merawatku sejak usiaku 8 tahun,” aku menerawang. Bagaimana kabar mereka sekarang?
“Teman-temanmu? Apa kau rindu mereka?”
Ah iya! Teman-temanku. Apa aku rindu mereka? Tania? Apa aku rindu dia? Apa Tania merindukanku? Kenapa mengingat-ingat menjadi menyakitkan. Rasanya sesak.
“Arrum!”
Tiba-tiba piintu ruangan terbuka begitu saja. Memotong memoriku yang sedang memutar kenangan-kenangan lama. Kepalaku dengan cepat melihat ke asal suara datang. Menyebabkan ototku salah bergerak.
“Arrum! Kamu kenapa, Nak?”
Aku cukup kaget saat Mama langsung berhambur ke arahku dengan wajah yang merah. Tangannya berulang kali mengelus-elus rambutku yang berantakan.
“Arrum gapapa, Ma.”
Wanita paruh baya itu menempelkan wajahnya ke keningku. Seolah dengan itu ia dapat mentransfer seluruh kekuatan yang ia miliki kepadaku. Dan itu memang berhasil. Di samping Mama semua terasa akan selalu baik-baik saja.
Masih di dekat jendela, Leon memperhatikan reuni antara orang tua dan anak ini.
“Apa kamu yang menelepon kami tadi?” Papa bertanya pada Leon. Mama berhenti menempelkan wajahnya di keningku dan mulai menyadari bahwa bukan hanya ada aku saja di ruangan ini.
“Yes, Sir.”
“Namanya Leon, Pa. Dia teman Arrum,” kataku.
“Terimakasih Leon. Terimakasih sudah menolong Arrum.” Papa menepuk-nepuk pundak Leon.
“Saya hanya melakukan hal yang seharusnya saya lakukan.” Papa mengangguk-angguk mendengar jawaban Leon. Dan Mama berbisik padaku, “Apa dia pacar kamu?”
Aku mengerutkan kening dan mengerucutan bibir saat Mama bertanya hal aneh itu. “Tentu saja bukan, Ma.”
“Ah ya! Saya harus kembali,” kata Leon seperti baru teringat akan sesuatu.
“Oh ya tentu…tentu. Sekali lagi terimakasih Leon,” ucap Papa.
“Saya permisi Tuan, Nyonya, Arrum.”
Mataku mengantarkan kepergian Leon dari ruangan ini sampai ia benar-benar tidak terlihat lagi. Pertanyaannya tentang rindu belum sempat kujawab tuntas. Begitu juga pertanyaan yang kutanyakan padanya. Jika ingat, nanti akan aku tanya lagi.
“Apa kamu yakin dia hanya seorang teman?” Mama kembali menggodaku.
“Ih mama. Apasih?” Aku membuang mukaku. Mama terkikik pelan di sampingku. Diam-diam aku tersenyum juga.
“Sepertinya Leon menyukaimu.”
Kini kata-kata Nadira terngiang di kepalaku. Apa seperti itu? Apa mungkin Leon menyukaiku?
“Teman-temanmu? Apa kau merindukan mereka?”
Pertanyaan Leon yang belum kujawab datang memotong ucapan Nadira yang muncul di kepala. Teman-temanku? Apa kabar mereka? Sudah 5 tahun berlalu, apa kami saling merindu? Tapi mengapa sesak ini masih saja datang saat mengingat Tania. Sudah 5 tahun. Banyak yang terjadi selama itu. Harusnya aku sudah baik-baik saja. Harusnya aku bisa mengingat hal di masa lalu sebagai kisah masa SMA. Harusnya hanya itu.


 BluePaper
BluePaper