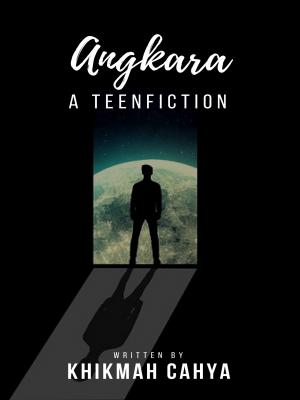Medan, 28 juli 2013
Berkas cahaya mentari pagi menembus jendela kamarku yang tertutup gorden berwarna pink pastel. Meski mataku masih tertutup, aku tahu kalau hari sudah tidak gelap lagi.
“Non Arrum, ayo bangun. Bibi udah buatin sarapan. Nyonya Dan Tuan juga sudah ada di bawah.”
Suara Bibi Fatimah terdengar samar di luar pintu kamarku.
”Non Arrum, ayo bangun. Hari ini kan hari MOS nya Non Arrum,” aksen jawa Bibi Fatimah terdengar lebih nyaring disertai suara ketukan pintu. Aku coba membuka mata. Ah silaunya!
“Hem iya Bi. Arrum udah bangun,” jawabku dengan suara lemah. Suara bibi Fatimah sudah tidak terdengar lagi.
Aku mencoba bangkit dari tempat tidur dan berniat untuk segera ke kamar mandi. Tapi, akibat bergadang yang kelewat batas membuat pandanganku samar sehingga menabrak salah satu sisi tembok kamar.
“Aww!” aku meringis kesakitan.
Insiden itu menyebabkan arwahku yang tadi masih melayang, langsung kembali sepenuhnya ke tubuhku.
***
“Pa, Arrum berangkat bareng Papa kan?” tanyaku di sela-sela sarapan pagi kami.
“Iya Arrum. Makanya kamu cepetan makannya. Nanti Papa telat.” Papa menggigit bagian terkahir rotinya dan meminum sgelas susu putih.”Papa udah selesai.”
“Arrum juga udah selesai.” Aku menghabiskan susuku dangan sekali tegukan. Takut ditinggal papa. Papa adalah orang paling tidak bisa kompromi soal waktu. Tidak ada satu detikpun yang boleh dilewatkan dengan hal yang tidak berguna. Waktu bukan lagi uang. Tapi berubah menjadi pedang.
“Eh rotinya dihabisin dong, Sayang.”
Seperti biasa, Mama selalu protes karena aku menyisakan sarapanku. Lain Papa, lain pula Mama. Mama adalah orang yang tidak bisa kompromi soal makanan. Tidak ada makanan yang boleh tersisa di piring. Selain itu, makanan yang kami makan juga harus sehat dan higienis. Mama melarangku jajan di kantin sekolah. Dengan setenagh hati aku menaati peraturan mama yang satu itu.
“Nanti Arrum ditinggal papa,” kataku beralasan.
“Yaudah kamu bawa aja. Makannya nanti di sana,” Mama meminta kotak makananku kepada Bibi Fatimah dan sigap memasukkan roti ke dalamya.”Nih! harus dimakan ya, Sayang. Kamu butuh tenaga lebih untuk hari ini.” Mama menyerahkan kotak makan berbentuk kubus berwarna biru kepadaku.
“Makasih,Ma.” Aku menuruti saja apa kata Mama. Padahal aku tidak yakin apa aku bisa sarapan di hari MOS pertamaku.
Pak Rahmat sudah menyalakn mesin mobil. Bersiap mengantarku dan Papa ke masing masing tujuan kami. Dengan langkah sangat cepat papa masuk ke dalam mobil. Aku mencoba menyamai langkahnya.
Mesin mobil menderu dan roda mulai berputar. Mama melambaikan tangannya padaku yang kubalas dengan senyuman.
“Bagaimana, apa kamu merasa gugup?” tanya Papa saat di perjalanan kami. Papa selalu menyempatkan diri untuk menjaga komunikasi denganku. Meskipun aku tahu daritadi papa menahan diri untuk tidak membuka ponselnya yang mungkin sudah banyak informasi yang masuk.
“Yah sedikit. Tapi aku bersemangat karena ini MOS pertamaku,” jawabku mantap.
“Gitu dong. Itu baru namanya anak papa,” Papa mengelus rambut hitam legamku.
Papa adalah kepala keluarga yang baik. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, dia berusaha untuk tetap membagi waktu dengan kami. Papa sangat menyayangiku. Apalagi aku adalah anak satu satunya.
“Kalau ada yang macem-macem sama kamu, bilang aja sama papa,” kata papa sambil bercanda. Aku tertawa pelan. Geli dengan tingkahnya.
“Kita sudah sampai,” Pak Rahmat bersuara.
“Cepat sekali sampainya. Pak Rahmat kayak pembalap aja,” godaku. Pak Rahmat adalah supir keluargaku yang sudah bekerja selama 12 tahun dengan Papa dan dia juga suaminya Bibi Fatimah.
“Loh! Bapak memang pembalap dulu,” Pak Rahmat menghentikn ucapanya sebentar. ”Di Kampung bapak,” lanjutnya. Sontak aku dan papa tertawa karena candaan Pak Rahmat.
“Aduuh Pak Rahmat ada ada aja sih,” kata papa sambil memegangi perutnya.”Sudah. Kamu nggak mau turun?” kata Papa padaku.
“Oh iya. Jadi lupa gara-gara Pak Rahmat nih,” candaku.
“Loh? Kok bapak?” Pak Rahmat nampak tak rela disalahkan.
“Kamu baik baik ya, Arrum. Ingat,bilang sama Papa kalau ada yang berani ganggu kamu,” kata Papa sekali lagi. Aku tersemyum dan mengangguk. Aku membuka pintu mobil dan turun. Melambaikan tangan pada Papa.
“Daah”,ucapku.
Mobil Sedan hitam itu kembali melaju di jalanan. Saat diperhatikan, Pak Rahmat memang menyetir seperti pembalap. Aku tersenyum mengingat ucapan Pak Rahmat tadi.
***
Koln, November 2017
“Hei, Arrum. Kenapa kamu senyum sendiri gitu? Mr.Linc sedang menjelaskan hal yang membosankan di depan sana. Apa kamu tersenyum karena itu?” Nadira teman sekelasku yang juga kebetulan memiliki kewarganegaraan yang sama denganku, menegurku dan membuyarkan lamunanku tentang kejadian di masa lalu. Akhir-akhir ini entah mengapa aku sering sekali mengingat-ingat sesuatu
Apa ini karena aku rindu kampung halamanku?
Ini sudah tahun ke 5 aku berada di Koln, salah satu kota besar di jerman. Aku terpaksa ikut pindah dengan orang tuaku karena perusahaan tempat Papa bekerja memintanya bekerja di kantor pusat. Ah sebenarnya tidak terlalu terpaksa, karena sebenarnya Papa dipindahkan pada waktu yang sangat tepat.
“Ahh bukan apa apa. Apa aku tersenyum sendiri tadi?” tanyaku polos. Nadira memutar bola matanya.
“Yaampun Arrum. Tingkah kamu aja udah menjawab pertanyaan kamu.”
“Arrum, Nadira. Apa yang kalian bicarakan di belakang sana ?” Astaga! Mr.Linc menangkap basah kami sedang mengobrol ria.
“E…eh..Tidak ada, Sir. Saya hanya menanyakan hal yang kurang jelas,” aku cepat mencari alasan.
“Apakah itu benar Nadira?” pria dengan kepala plontos itu seakan tidak percaya padaku.
“Ah,,iya Sir. Itu benar.” Nadira kompak denganku.
“Baiklah. Maaf jika suara saya tidak terdengar jelas. Saya sedang kurang sehat.”
“Semoga Anda cepat sembuh,” kata Nadira mencoba bersimpati.
Nadira tersenyum padaku. Aku membalas senyumnya. Kami terkikik pelan.
Dan lagi, kejadian itu melemparku ke masa lalu. Ke masa yang aku sudah coba lupakan, tapi ternyata masih tersimpan. Benarlah kata orang, tak peduli seberapaa rapih kita memilah mana kenangan yang ingin disimpan dan mana yang ingin ditinggalkan saat pindah, selalu kenangan pahitlah yang terputar berulang-ulang.
Kurasa bukan kampung halamanku yang aku rindukan. Tapi seseorang yang ada di sana.
Ah, hatiku nyeri mengingatnya.


 BluePaper
BluePaper