Kesibukan mulai terlihat pada kafe tempat Dhisty bekerja. Kursi-kursi yang ada di atas meja diturunkan satu persatu, dan disandingkan satu sama lain. Kaca-kaca yang berdiri tegak, mulai dibasuh dan dilap perlahan. Kesunyian yang mulanya mendominasi tempat itu, perlahan mulai tersingkirakn dengan percakapan kecil yang keluar dari bibir-bibir karyawan.
“Anjrit, gue lihat foto lo. Enggak cocok lo sama cewek cantik kayak dia. Sok iye, banget.”
“Banyak omong. Bilang aja iri! Gini-gini gue laku dikalangan cewek.”
“Alah cewek jadi-jadian.”
Gelak tawa mulai terdengar karena percakapan itu. Godaan demi godaan terlontar. Sayangnya semua itu tidak terpengaruh pada Dhisty yang kini masih sibuk membersihkan meja dan kursi. Dia hanya menaikkan pandangannya sekilas, menatap tanpa minat lalu menunduk lagi. Tidak ada niat untuk dia bekerja hari ini, yang dia inginkan sekarang adalah diam di kamarnya, sambil mendengarkan musik.
Alasan kenapa Dhsity merasa kehilangan semangat hidup: mengetahui bahwa Gala sudah mempunyai pacar yang membuat dia malasa melakukan apa pun kecuali menangis.
“Dhis, tumben amat lo lesu. Kenapa?”
Kenapa? Gue patah hati. Masalah buat lo?!
Dhisty membersihkan kerongkongannya. “Enggak kenapa-napa.” Dia sudah berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya yang sekarang dia rasakan: frustasi, kecewa, marah, dan putus asa.
“Yakin? Soalnya lo aneh banget. Semangat lo kurang, kayak ngambang.”
“Lo kira yang kuning-kuning hanyut dikali. Parah nih orang.”
“Bego, lo yang salah nangkep!”
“Lah lo yang ambigu banget ngomongnya.”
Dua orang itu terus berdebat, sambil membawa nama Dhisty, seolah-olah ingin mengajak gadis itu berbincang. Tak ada yang tahu bahwa apa yang mereka lakukan hari ini sia-sia. Dhisty tidak tertarik untuk ikut berbicara. Tanpa memberikan pertanda ia beralih ke meja lain, dan mulai mengerjakan seperti tadi.
Apa yang harus dia lakukan agar perasaannya ini tidak kacau? Ia mengelap satu meja, kursi dan terus begitu. Dia bahkan sudah mengacuhkan panggilan dan chat Gala, berharap hatinya membaik, nyatanya dugaannya salah. Dhisty meletakannya lap cukup kasar di meja, sebelum merapikan anak rambutnya yang keluar. Perasaannya tidak baik, sama sekali tidak baik.
“Hayo mikirin apa?”
Seperti tersengat listrik tubuh Dhisty tersentak, netranya langsung membeliak begitu lebar, dan kepalanya otomatis menoleh. Ia mengerjap berulang kali, sebelum berhasil menyesuaikan diriya. Ia bingung ketika sadar bahwa Lingga ada di sampingnya, dengan senyuman ramah –yang Dhisty pikir hanya sebagai formalitas- mengarah padanya.
“Jangan suka kagetin orang, kalau orang jantungan mau tanggung jawab?” kata Dhisty sebelum berpaling dengan ketus. Dan ketika kepalanya hendak menunduk dia menemukan Seva juga sudah datang, dan kini sedang dikelilingi oleh orang-orang. Bukan itu masalahnya, yang membuat Dhisty langsung menunjukan wajah datar, laki-laki itu menatapnya lurus.
“Lagian, lonya disapa enggak denger-denger.”
“Selamat Pagi, Pak Lingga.” Dhisty membungkuk, dengan kedua tangan yang menyentuh bagian perutnya. Begitu formal. Merasa cukup dia langsung menegakkan tubuhnya lalu kembali bekerja.
“Kamu enggak pernah diajarin sopan santun apa gimana? Kamu di rumah bisa seenaknya, di sini enggak bisa, dasar manja.”
Bukan Lingga yang berbicara, melainkan Seva yang membuat semua orang langsung menghentikan pekerjaan mereka, tertarik melihat apa yang akan terjadi. Lingga di samping Dhisty menggaruk belakang rambutnya, sedangkan orang yang diajak bicara, masih acuh.
Gadis itu bahkan hanya meremas lap yang ada ditangannya, tanpa mau langsung membuka mulutnya. Kalau biasanya dia akan melayangkan balasan, tidak untuk kali ini. Sepertinya Seva tidak peduli atau bahkan tidak bisa membaca perubahan Dhisty.
Tatapan Dhisty naik ke arah Seva, datar, tanpa emosi. “Maaf, Pak.” Dia akan mengakhiri semua ini, secepatnya. Ia bisa melihat kekagetan dari wajah Seva. Laki-laki itu diam, membuat Dhisty kembali melakukan pekerjaannya.
Tentu ketika ada tontonan, ada yang berkomentar. Entah secara keras atau pun secara bisik-bisik, seperti sudah menjadi hukum alamnya. Dhisty mengabaikannya ketika telinganya menangkap pembicaraan mengenainya; tidak sopan, dan lainnya.
Dan tanpa sadar Seva masih menatapnya dengan kening yang mengernyit.
****
Sebelah tangan terjulur ke atas, kedua kaki saling berjinjit, bertumpu menggunakan jari-jari kecil yang mulai gemetar, mencoba mengambil piring yang berada di bagian cukup dalam. Tingginya yang lebih rendah dibandingkan dengan rak itu, membuatnya harus berusaha keras. Terlebih dengan tangan yang tidak panjang, membuatnya sangat kesulitan.
“Menyebalkan.” Dhisty berdecak kesal. Ia berdiri tegak, menopangkan kakinya seutuhnya pada kaki. Tujuannya adalah rak bagian kedua dari atas. Perlahan dia berjalan mundur, dengan kepala dan mata yang mengarah pada piring berwarna-warni, mencari tahu keberadaan piring itu.
Dhisty merapikan rambutnya masih dengan kekesalan yang merajelela. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari kursi yang biasanya ada di sana. Nyatanya nihil, beberapa kali dia memperhatikannya, kayu yang sudah dibentuk dengan kaki empat tidak ada di sana. Rasanya dia ingin marah-marah sekarang juga. “Sabar, Dhis. Sabar.” Diusapnya dadanya yang mulai bergerumuh.
Ini berawal dari dia yang sedang sibuk dengan membawa pesanan, mendengarkan protesan pelanggan, dan hampir saja kehilangan kesabaran.
“Mbak, ini kenapa kaya gini. Gelap amat! Saya mau ganti.”
“Apanya yang gelap, Mbak?” Dhisty menurunkan pandangannya menatap kue yang tersaji di piring kecil. “Mbak, kan pilih yang rasa cokelat, dan setahu saya emang warnya seperti itu.”
“Saya tidak mau tahu, saya minta ganti.”
“Ganti? Kenapa? Rasanya tidak enak?”
“Warnanya! Saya kan udah bilang warnanya! Budek ya?!”
“Enggak bisa Mbak.”
“Kok enggak bisa?! Saya kan pembeli, dan pembeli itu adalah raja!”
Pembeli itu teriak kencang, tak hasil menarik perhatian. Dhisty kalang kabut, ia menoleh ke kanan dan kiri, menganggukan kepalanya meminta maaf. Dalam dunia ini memang mempunyai manusia yang beragam, dan yang paling menyebalkan adalah pembeli seperti ini; memperlakukan pelayan sebagai seseorang yang mempunyai drajat bawah, menganggap bahwa dia harus dijunjung tinggi. Ditambah, ketika pembeli marah, yang selalu menjadi orang bersalah: pelayan. Entah apa alasannya.
Dalam tubuh Dhisty, ego yang tengah terikat dengan rantai, mulai memberontak. Meminta untuk keluar.
“Mbak,” Dhisty masih mencoba untuk bersabar. “Kalau rasanya tidak ada masalah, tidak bisa ganti.”
“Ini kafe macam apa, pelayanannya kayak gini.”
Gigi Dhisty bergemulutuk. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Pembeli ini salah mencari hari untuk mencari gara-gara. Apa dia tidak tahu, kalau orang yang sedang patah hati, bisa berubah menjadi macan secara tiba-tiba.
“Mbak, di sini kafe—”
Tarikan dilengannya menghentikan ucapannya. Ia terdorong pelan, aroma apel langsung menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Seva berdiri di depannya menggantikannya.
Ada perdebatan sengit di sana, dan tentunya, Dhisty disalahan oleh pembeli itu. Gadis itu tidak tinggal diam, ia maju, hendak melawan. Sayangnya Lingga sudah menariknya jauh.
Dan di sinilah dia berada, berdiri di dekat rak cokelat, dan berusaha meraih piring dengan berbagai ukuran untuk membawanya ke dapur. Kalau dia inget masalah tadi, rasanya dia ingin pergi dan membalas perkataan orang itu. Ia menghela napas, tanpa ragu dia mengeluarkan ponselnya. Hal yang seharusnya tidak diperbolehkan kecuali keadaan mendesak. Dia membacanya sebentar, ketika dia melihat nama Gala yang masih mendominasi layar ponselnya.
Kemarahannya mereda, digantikan rasa sakit. Dhisty tahu, bahwa dia begitu pengecut, menghindar dari Gala, tanpa laki-laki itu tahu apa masalahnya. Dia hanya tidak mengerti bagaimana cara menghadapi Gala dengan perasaannya yang seperti ini. Helaan napas keluar kembali dari bibir Dhisty. Sejenak ia memperhatikan, ada gedoran-gedoran keras di dalam dirinya; keinginan yang makin lama makin meronta di antara kekangan yang ada. Dia ingin membuka pesan itu, tapi, dia tidak siap dengan konsekuensinya.
Ia menutup pemberitahuan dan langsung mengecek chatnya ke Asri, belum dibalas. Dia sudah tidak tahan menahan ini semua, dia sudah bercerita panjang pada Asri –melewati chat- tapi belum ada balasan sampai saat ini. Dia berharap secepatnya ada balasan. Mungkin sekitar lima menit ia hanya diam di sana, menatap ponselnya sebelum memasukannya kembali. Dan berusaha kembali mengambil piring yang sejak tadi menjadi bahan incarannya.
Bisa saja dia meminta orang lain untuk mengambilkannya. Sayangnya, dia tidak mau membuat orang lain untuk meremehkannya. Ia mencoba dengan cara yang sama, semakin menjijitkan kakinya, dan dia berhasil menarik bagian luar piring, menarinya perlahan. Dia terus melakukannya hingga pada akhirnya dia bisa mengambilnya.
Senyum puas muncul dalam wajahnya. Ia berbalik dan piring itu jatuh berserakan, ketika tubuhnya menabrak seseorang.
“Lo bisa kerja enggak sih?!”
Dhisty mendongak, dan menemukan tatapan kebencian yang terarah padanya. Rita, gadis dengan bibir merah, pakaian kerja ketat, hingga menonjolkan bentuk badannya. Kadang Dhisty berpikir, gadis itu bekerja atau mencari pacar? Lupakan hal itu, sekarang dia harus fokus dengan pecahan piring itu.
“Lo denger enggak omongan gue. Masa cuman bawa piring aja lo enggak becus!”
Kabel kesabaran Dhisty terputus, sorot matanya perlahan berubah; tajam dengan emosi yang menyelimutinya. Gadis itu sejak awal sudah tidak menyukainya. Jadi tidak heran kalau gadis itu bersikap kasar. Sayangnya Dhisty terlalu marah dengan ucapannya.
“Enggak becus lo bilang?” Dhisty tersenyum sinis. “Lo bilang gue enggak becus?”
“Emang iya kan? Tuh lihat piring-piring aja sampai jatuh. Emang apalagi kalau bukan enggak becus?” Rita menekan dua kata terakhir, yang diiringi dengan senyum mengejek.
“Lo yang enggak becus. Lo sengaja kan dorong gue biar piring-piring itu pecah!”
Tadi, sebelum dia berbalik, dia sudah pastikan tidak ada orang di sana, hanya dia sendiri. Dan sayup-sayup dia mendengar suara derapan langkah sebelum ia berbalik, diiringi dengan dorongan kecil. Meski samar, dia bisa merasakannya. Ada yang menyentuh badannya. Dan juga, gadis itu tidak terlihat kaget ketika dia menatapnya.
“Gue? Lo yang salah! Gini nih kalau anak mami kerja, apa-apa salahin orang!” Rita bersidekap, dengan dagu yang terangkat, angkuh. “Lo mending pulang, enggak usah kerja, nyusahin! Bikin rugi!”
Perlahan, jemari Dhisty menutup, menjadi kepalan kuat. Gadis itu sudah melewati garis yang Dhisty berikan. Namun, Dhisty masih menahan diri. Ia membungkuk mengambil pecahan-pecahan yang tercecer di lantai.
“Inget lo ganti tuh piring, kan anak mama, bisalah minta apa-apa. Gue curiga apa ada yang mau sama cewek kayak lo? Manja, suka nyalahin. Kalau lo ditolak wajar sih.”
Dhisty bangkit, dia mencekram tangan Rita erat. “Tutup mulut lo! Lo enggak tahu apa-apa tentang gue! Kalau gue anak mami kenapa? Masalah buat lo ha?!”
Disentaknya dengan keras tangan Dhisty, lalu mendorongnya dengan kuat.
“Enggak masalah, cuman gue mua dengan orang macam lo! Terlalu rendahan.”
“Ini kenapa ribut-ribut!”
Orang-orang datang dengan cepat, mereka langsung mengurumuni kedua orang itu.
“Lo yang rendahan!”
“Dhisty, Rita!”
Dhisty membuang muka, dia masih sakit hati dan tidak puas sebelum menampar gadis itu.
“Ini ada apa? kenapa piring sampai pecah? Jelasin.”
“Dia dorong saya.” Dhsity dengan perasaan menggebu-gebu, menunjuk Rita. Dia menoleh masih dengan tatapan marah. “Dia sengaja.”
“Jangan ngomong aneh-aneh lo! Mana buktinya? Lo yang salah, lo nyalahin orang. Tipekal anak egois.”
“Coba lo ulangin lagi!”
“Berhenti! Dhisty, jangan suka menuduh orang.”
“Bapak salahin saya? Dia yang salah!”
Dhisty menatap tajam Seva. Kali ini dia sungguh kecewa dengan sikap laki-laki itu. Semua orang tidak ada yang bicara, mereka masih mengamati dengan baik. Dari pandangannya Seva menarik napas dalam sebelum menghembuskannya dengan pelan.
“Kamu itu seharusnya sadar dengan apa yang kamu lakuin. Saya lihat kamu hari ini semakin enggak ke kontrol, kalau ada masalah dengan pacar atau siapa pun jangan bawa ke sini.”
“Kenapa enggak ada yang percaya kalau dia yang salah?! Apa karena saya anak semata wayang? Apa enggak bisa anak semata wayang kerja ha?!” Dhisty meninggikan suaranya, membuat semuanya kaget. Matanya terasa panas, dan siap untuk mengeluarkan semuanya. “Dan kenapa kalau saya patah hati?! Apa saya enggak boleh merasa jatuh cinta, karena saya anak semata wayang?! Ha!”
Entah karena patah hati atau karena dia sudah tidak sanggup lagi. Air matanya jatuh.


 D
D

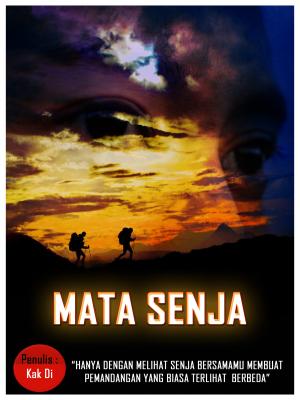





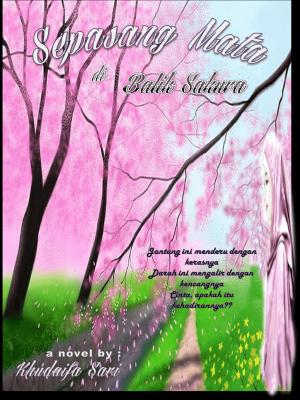


Saya anak semata wayang. Tapi saya jauh dari kata manja.
Comment on chapter Prolog