“Ih gemesin banget sih, pingin uyel-uyel.” Dhisty menekan rahangnya sampai memperlihatkan giginya. Dia terlihat begitu gemas dengan apa yang dilihatnya sekarang.
Sejak setengah jam yang lalu setelah mengerjakan tugasnya, gadis itu sudah merebahkan diri di atas ranjang sembari menatap ponselnya, seperti itu. Ia tidak henti-hentinya tersenyum kecil, atau mengeluarkan gestur. Video kucing, itulah yang ditontonnya sekarang. Dia menyukai kucing, tapi sangat jarang bisa mendekatinya, karena Dhisty begitu takut jika dicakar oleh hewan berbulu itu.
Senyum kembali terulas, dan kakinya kembali dihentakkan kecil ke atas ranjang, saking gemasnya. Lihat bagaimana kucing itu bergeletakan dilantai, sambil merentangkan tangannya. Menggeliat ketika bagian perutnya digelitik. Pasti empuk sekali, melihat bagaimana besar kucing itu.
Dhisty menggeser video demi video, sebelum akhirnya menutup aplikasi itu. Wallpaper hitam ponsel langsung menyapa pandangannya. Ia mengerucutkan bibirnya ketika tidak ada yang menarik di sana. Pandangannya menurun pada icon telpon, beberapa menit dia menatap icon itu sebelum akhirnya memindahkan pandangannya ke icon pesan.
Ia menghela napas.
“Kok belum ada kabar ya,” kata Dhisty, kecewa. Ini sudah terhitung hampir seminggu semenjak dia melamar kerja, tidak ada satu pun yang menelponnya, memberitahukan bahwa dia lolos. “Apa gue gagal?” katanya lagi pada ruang sunyi. Ada ketidakpercayaan, dan kekecewaan yang terselip dalam diri Dhisty ketika mengatakan hal itu. Ia tersenyum miris, sebelum mengubah posisi tubuhnya, menjadi miring.
Ditariknya guling mendekat, dan menaruh kakinya di atas benda panjang itu. “Hem, kemana lagi ya, gue harus ngelamar? Kalau lama kayak gini gimana cara gue nunjuin ke mereka kalau gue bukan anak manja?” Pelukannya semakin mengerat pada guling. Otaknya mulai berpikir dengan cepat, mengenai cara lain untuk menunjukan dirinya manja. Haruskah dia membuat sesuatu dan menjualnya?
Tidak. Tingkat kreativitasnya rendah. Bukannya dibeli, dia yakin barang yang dibuatnya akan dibuang kalau pun itu laku.
“Berbicara pada Papa lagi?” Dhisty menggelengkan kepalanya cepat. “Hal yang tidak memungkinkan. Bukannya diterima, malah kena marah seperti kemarin.”
Bahunya turun, wajahnya ia tempelkan pada guling. Membiarkan hidungnya menghilang di sana. Pilihan terakhir itu sukses membuatnya sakit kepala. Mendadak omelan Papanya langsung terngiang begitu saja di telinganya dan kepalanya. Seolah saat ini Papanya berada di sana, bersamanya.
Dia tidak menampik bahwa dirinya begitu percaya diri. Pasti ada salah satu toko yang mau meloloskannya. Bukan tanpa alasan dia berkeyakinan seperti itu. Pertanyaan yang dierikan padanya, sudah ia pelajari dengan baik. Bahkan dia merelakan, wajahnya dihampiri lingkaran hitam seperti hewan menggemaskan, panda.
Dhisty berharap, sangat berharap bahwa salah satu dari sekian banyak tempat yang ia melamar akan mengabarinya. Kecuali satu tempat, little bear.
“Sebentar lagi, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin mereka kehabisan pulsa.” Dhisty mengangguk-anggukan kepalanya.
Setelah itu tidak ada lagi yang dilakukan oleh Dhisty. Kamarnya begitu hening, hanya terdengar pergerakan kakinya yang beberapa kali menggosok guling, dan jam berdenting, selebihnya tidak ada. Dhisty tengah memulai sesuatu dalam kepalanya, sebuah cerita yang dia buat sendiri dan kini mulai berjalan di dalam kepalanya.
Kedua matanya terpejam, adegan demi adegan receh yang dia imajinasikan satu per satu mulai muncul. Menarik bibirnya untuk tertawa. Ekspresinya berubah-berubah sesuai dengan apa yang dibayangkan. Bagi Dhsity, tempat yang paling tenang di antara tempat yang ada adalah kamar dan dalam dunia pikirannya sendiri, tidak ada yang akan mengganggu dan menginstrupsi.
“Non,”
Dhisty mengeliat, masih mengabaikan panggilan yang tiba-tiba merusak kesenangannya.
“Non.” Kali ini panggilan itu diiringi dengan ketukan berulang kali.
Dhsity berbalik dengan sorot mata kesal. Semua kesenangannya sirna, padahal imajinasinya hampir mendekati konflik. Sangat disayangkan.
“Iya, kenapa, Bi?” Dhisty mengubah posisi tidurnya. Meski kesal, dia tidak punya pilihan lain selain menyahuti.
“Dipanggil Bapak sama Ibu.”
Dhisty mendesah, rasanya begitu malas untuk turun dari ranjang. Ia menyugar rambutnya. “Iya, nanti, Dhisty ke bawah.” Ditundukan tubuhnya hingga dadanya menyentuh pahanya sendiri. “Mager banget buat turun. Kenapa juga harus turun? Kenapa nggak –” perkataannya berhenti, kepalanya menggeleng. Ada satu hal yang menamparnya, hingga membuat gadis itu bangkit dari ranjangnya.
“Gue nggak boleh manja. Gue kan mau mandiri,” Dhisty menyambar ikat rambut lalu mengikat rambutnya sembari meninggalkan kamar nyamannya.
****
“Ya mau gimana lagi, Papa kan harus kerja. Tanggung jawab Papa di perusahaan besar, Mama paham hal itu kan? Ini aja Papa belain buat pulang.”
Dhisty hanya memandang orang tuanya tanpa minat. Ia lebih memilih memakan makannya dibandingkan harus ikut campur dengan percakapan kedua orang tuanya.
Kesibukkan Papanya yang semakin menjadi-jadi, membuat Mamanya mulai melontarkan protesan –hal yang tidak aneh untuk dilakukan. Mengingat waktu kebersamaan mereka –keluarga- semakin sedikit. Papanya bahkan kerap kali tidak pulang, dan hanya mengirimkan pesan pada Mamanya, yang langsung menarik perdebatan di antara mereka berdua.
Sebenarnya, bukan hanya Mamanya yang merasa marah, melainkan dirinya juga. Menjadi anak satu-satunya harus siap untuk menerima kesepian yang kerap kali menyambutnya. Apalagi jika tidak ada satu pun yang bisa dihubungi, rasa itu siap untuk menyapa. Berapa lama pun dia menjadi anak semata wayang, dia belum mampu terbiasa dengan perasaan itu. Jadi yang dia bisa lakukan adalah, keluar dari rumah, bertemu dengan teman-temannya. Yang sayangnya dia sulit untuk melakukannya karena peraturan yang ada.
“Dhis, kasih tahu Papamu dong.”
Kunyahan Dhisty berhenti, ia menatap Mamanya dengan bingung. Bulu matanya turun,mengikuti mata yang beberapa kali tertutup. “Memangnya Dhisty harus ngomong apa?” Dia benar-benar bingung, masalahnya ketika dia salah berbicara yang ada malah menyulut pertengkaran yang ada.
“Kasih tahu Papa kamu, biar nggak usah sibuk terus di kantor. Memangnya cuman kantor aja yang perlu diurusin.”
Dhisty meletakan sendok yang sejak tadi dia genggam. Ia menggaruk sisi belakang telinganya. “Pa, apa nggak bisa kalau Papa nyempatin waktu buat Mama dan Dhisty?”
“Papa maunya juga begitu, tapi kalau Papa nggak ada siapa yang ngawasin perusahaan?” Nath menghela napas. Dadanya membusung sebentar sebelum kembali turun. Tatapannya ke arah Dhsity. “Kamu mendingan fokus kuliah, belum ngerti kamu hal yang kayak gini.”
Rasanya seperti ada garpu yang menusuk jantung Dhisty, hingga menghantarkan rasa nyeri disekujur tubuhnya. Beginilah Papanya, yang emosinya tidak bisa diprediksi sama sekali, dan ketika berbicara selalu menyakitkan, meremehkan, membuat emosi Dhisty hampir meledak.
Kedua tangannya mengepal, lalu terbuka ketika Dhisty berhasil menekan emosinya sekuat tenaga.
“Ya, bagaimana Dhisty mengerti kalau Papa nggak mau kepercayaan,” gumam Dhisty pelan sebelum menyendokkan mulutnya. Ia mengunyah cepat. Dia tidak yakin kalau dia bisa menahan emosinya sampai beberapa tahun ke depan. Rasanya begitu menjengkelkan ketika dirinya yang sudah dewasa malah dianggap belum bisa apa-apa.
Selera makan Dhisty langsung terkuras habis, dia mengunyah dengan tenaga tersisa. Ia ingin pergi sekarang juga dari sini, kembali menyelami imajinasi yang bisa membenarkan mood-nya. Sayangnya, jika kalau dia melakukan itu semua, Papanya akan emosi lagi.
Ingin Dhisty nyanyikan lagu Raisha, serba salah kalau seperti ini.
Lagi, percakapan orang tuanya lebih mendominasi, sedangkan Dhisty diam dengan hati dongkol.
“Dhis?”
“Ya, Ma?” Dhisty menempelkan sendok dalam mulutnya dengan tatapan yang mengarah pada Mama. “Kenapa?”
“Kamu nggak ada kerjaan kan hari ini? Tugas kamu udah selesai?”
Dhisty mengangguk.
“Temenin Mama ya?”
Dilepaskan sendok dalam mulutnya. “Kemana?” kebahagiaan Dhisty perlahan tumbuh, di ajak keluar oleh Mamanya berarti mereka akan bersenang-senang.
****
“Jadi gimana?”
“Apanya?”
“Lancar nggak?” lengan Dhisty ditarik mendekat arah gadis di sampingnya. “Misi lo buat ngelamar kerja, sukses nggak?”
Kedua bahunya melorot, Dhisty menggeleng pelan. Dia melihat ke arah dua Mama yang kini tengah mengobrol dengan ria sebelum akhirnya menoleh ke arah Asri. Gadis yang tidak sengaja yang dia temui di mall. “Nggak. Sama sekali nggak lancar.” Dhisty berkata dengan pelan, tak mau kalau Mama mereka mendengar percakapan ini.
“Gue udah nungguin kabar, tapi belum ada sama sekali yang nyangkut di ponsel gue.” Dhisty mengaduk ramen di depannya, menunduk sedikit sebelum memasukan ramen itu ke dalam mulutnya. “Malahan,” ia mengunyah, “yang sering masuk sms operator atau nggak OA yang nggak jelas. Kesel gue tahu nggak.”
Asri menahan senyumannya, ia menepuk pundak Dhisty, perihatin.
“Ya, sabar. Cari kerja itu memang sulit.” Asri mengucapkan kata kerja sangat pelan, takut kalau di dengar oleh kedua Mamanya yang kini asik menggosip. “Lagian, baru beberapa hari ini, masa lo nyerah.”
Dhisty berhenti menggulung ramennya, ia mendelik sebal. “Siapa bilang gue nyerah?” Ada sisi dalam diri Dhsity yang tersentil oleh perkataan itu. Dia tahu bahwa maksud Asri baik, hanya saja dia tidak bisa menghentikan ketidaksukaan ketika mendengar perkataan itu, seolah meremehkannya.
Setiap orang mempunyai sifat jelek dalam dirinya, mau sebaik apa pun yang terlihat, pasti ada. Begitu juga dengan sebaliknya sejahat apa pun yang terlihat, ada kebaikan yang tertanam. Dan Dhisty mengakui, ada sebagian sifat dirinya yang sangat jelek karena dari dulu dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan.
“Kalian berdua ngomongin apa sih? kok serius amat.” Mama Asri bersuara, terlihat jelas bahwa wanita itu penasaran.
“Rahasia anak muda, Ma.” Asri menjawabnya dan Dhisty tersenyum, pura-pura tidak mempunyai rahasia.
“Mama ‘kan muda juga.”
“Iya, dulu,” timpal Asri.
Mama Asri terkekeh. “Yang penting sama-sama muda, dulu atau sekarang.”
Dhisty tidak bersuara dia sibuk dengan ramen dan gyoza. Mumpung gratis dia akan memanfaatkan sebaik-baiknya.
“Oh ya, Dhisty.”
Dhisty berhenti. Ia menatap Mama Asri, bingung.
“Kamu udah punya pacar?”
“Belum, Tante.” Dhisty tersenyum tipir. Tidak enak sekali mendengar pertanyaan semacam itu.
“Kenapa? Kamu cantik kok.”
“Dia lagi suka sama orang, Ma. Jadi belum bisa pacaran sama orang lain, ya kan Dhis?”
“Asri!” Dhisty kelabakan karena Asri mendadak berbicara seperti itu. Ada hawa panas yang menyapanya, menjalar sampai ke wajah. “Lo jangan aneh-aneh deh,” pintanya sambil melotot, memberikan petunjuk agar Asri tutup mulut.
Selama ini dia tidak ada yang tahu bahwa dia menyukai Gala. Selama ini, dia berusha untuk menutupinya sebaik mungkin dan bersikap sewajar mungkin. Dan sekarang, Asri mencoba untuk memberitahukannya?
Keterlaluan.
Asri menyeringai dibalik gelas yang kini menempel mulutnya. Dia berlagak sok polos, dan Dhisty semakin geram karenanya.
“Kamu suka sama siapa?” Mama Dhisty menimpali. “Kok Mama nggak tahu.”
“Anu.” Dhisty memainkan matanya ke kanan dan ke kiri. Gue harus jawab apa? Nggak mugkin kan, kalau gue jawab gue suka sama Gala. Nggak.
“Dia suka sama Donghae, Tante.”
Dhisty langsung menjentikan jemarinya. “Ya, benar Donghae.” Kepalanya mengangguk-angguk semangat. Sekuat tenaga dia menunjukan bahwa apa yang dikatakan oleh Asri benar adanya.
“Donghae? Itu siapa?”
“Super Junior, Tante.” Dhisty semangat menjawabnya. Sejenak dia melupakan ketakutannya.
“Super Junior?” Kepala Mama Asri miring, tampak bingung. “Korea?”
“Iya.”
“Oh, emang dia nganggep kamu ada?”
Dhisty mengerucut bibirnya. “Tante jahat.”
“Kadang kehidupan itu memang jahat, Sayang.” Mama Dhisty berkata begitu lembut. Berbeda dengan dampak yang begitu menyakitkan untuk Dhisty. “Tapi, nggak apa-apa kamu suka sama mereka, kalau bisa berdampak positif,” tambahnya ketika melihat Dhisty sudah menunjukan kemuraman.
Telat, benar-benar telat.
Dhisty tidak menimpali perkataan yang mengarah padanya. Dia mengambil ponselnya yang sejak tadi diacuhkan. Berniat untuk mendengarkan lagu. “Eh, ini nomer siapa?” Keningnya mulai mengernyit ketika melihat ada nomer yang tidak dikenal.
Tidak ada pikiran atau harapan ketika tangannya mengarah untuk membaca pesan itu.
“Ha?!” tubuhnya menegang. “Gue—” Dhisty berhenti. Ia menyadari satu hal. Lolos, batinnya. “Laper lagi,” dia meringis.


 D
D






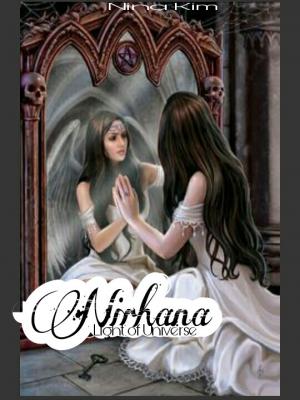



Saya anak semata wayang. Tapi saya jauh dari kata manja.
Comment on chapter Prolog