“Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.”
Ucapan perpisahan itu membuat orang-orang yang bermuram durja, mulai menyunggingkan senyum lebar. Semangat dan keributan langsung menggema di ruang kelas yang semula sepi. Seolah mematahkan kehingan yang sempat menyelimuti ruangan itu. Hampir semua yang ada di sana langsung merencanakan apa yang akan mereka lakukan dengan semangat, kecuali satu orang. Orang yang masih duduk di bangkunya, dengan ketukan jari yang masih menemaninya.
“Muka lo kenapa masih cemberut gitu? Segitu nggak sukanya sama mata kuliahnya?”
Dhisti menggeleng. Ia menoleh ke arah Asri dengan mata yang lelah. “Gue nggak diizinin pergi ke konser. Argh! Padahal gue udah nabung! Bokap gue kadang buat gue kesel setengah mampus.”
Tawa keluar dari bibir mungil Asri.
“Malah ketawa.”
“Lagian, gue mah nggak heran kalau lo nggak diizinin. Kalau lo diizinin, baru gue heran.” Asti masih tertawa tanpa peduli Adhisti yang tengah cemberut.
Ya, dia memang sangat sulit untuk mendapatkan izin. Dari dulu, setiap dia kali ingin pergi selalu dilarang. Kalau dihitung-hitung izin yang dia dapatkan hanya sedikit, sisanya adalah larangan, omelan yang membuat telinganya berdengung, dan kepalanya akan sakit.
“Tega ya lo.” Dhisti bangkit dan meletakan tasnya di pundak sebelah kanannya. “Udah belum lo?”
“Udah. Lo mau ke mana?”
“Nggak tahu, pusing gue. Males juga di rumah.”
“Yakin lo males? Nanti ponsel lo diteror lagi.”
Dhisti menepuk pundak Asri, bentuk kekesalannya. “Emang sahabat kejam ya lo.” Sesuai dengan perkataan Asri dia langsung megecek ponselnya, adakah panggilan dari orang rumah. Kadang dia ingin menonaktifkan ponselnya, agar dia bisa bebas dari semua peraturan yang ada. Dia mendesah lega karena belum ada nomer Mamanya atau Papanya yang tertera di dalam ponsel. Akhrinya dia bisa bernapas lega.
“Dhisti, awas!”
Kepala Dhisti mendongak, dan dia mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu, ia gugup. Mulutnya terbuka sedikit, membantu oksigen agar lebih menjalar tubuhnya. Untung saja dia bisa mengerem cepat, kalau tidak bisa dipastikan hidungnya yang eksotis sudah menabrak pemilik dada yang ada di depannya.
“Serius banget, lihatin apa sih di hpnya?”
Dhisti bergerak mundur, ia menutup wajahnya dengan ponsel. Dia tahu itu adalah hal bodoh, dan sekarang dia melakukan hal bodoh itu. Dia sangat mengenal suara di depannya terlebih dengan aroma parfum yang sudah melekat di hidungnya. “Bukan apa-apa.” Ia memberanikan melihat langsung dan menunjukan senyum tipis. “Sorry ya, gue hampar nabrak.”
“Santai.” Kepala Dhisti diusap pelan oleh orang yang kini memicu jantungnya berdegub kencang. Dalam hati Adhisti menenangkan dirinya, dia tidak boleh terlihat bodoh di depan laki-laki itu. Gala Davendra. Laki-laki yang ia sudah kenal sejak kecil. “Lo mau balik?”
“Nggak, mau jalan bentar sama Asri.”
“Udah minta izin?”
Mendengar kata izin, rasa malu dan berdebar Dhisti menghilang entah kemana. Seolah ada yang mengambil paksa dan menggantikannya dengan perasaan kesal, dan suntuk.
“Jangan bawa-bawa izin deh, Gal. Muak dengernya.” Dhisti cemberut, ia bahkan bersidekap.
Hal yang dilakukan Gala adalah tertawa, membuat Dhisti semakin kesal.
“Lo kok ketawa?! Lo sama Asri sama aja. Bikin gue kesel.”
“Lha kok gue dibawa-bawa?”
Gala berdehem, lalu menepuk kepala Dhisti, hal yang selalu dia lakukan ketika bertemu dengan Dhisti. “Iya deh iya. Maaf ya,” kata Gala sambil menundukan kepalanya, mensejajarkannya di depan wajah Dhisti.
Hawa panas langsung menyambut Dhisti, lagi debaran itu datang. Sial kalau gini, gimana caranya gue marah sama lo sih!
“Maafin, ya?”
Dhisti menepis tangan Gala pelan, lalu menjaga jarak. Semakin lama dia mempertahankan kedekatan mereka tadi, itu semakin memparah kegugupan Dhisti, dan menjauh adalah cara terbaik untuk menenangkan diri. “Iya, bawel amat sih.” Ia melirik ke arah Gala, membuang muka, lalu menghela napas. “Lo mau ke mana? Balik?”
“Gue mau kumpul sama anak-anak.”
“Ke?”
“Kenapa? Mau ikut?”
Dhisti menggeleng cepat. “Gue cuman mau tahu doang.”
“Takut gue kesambet sama cewek lain?”
“Dih, PD bener.” Dhisti menyugar rambutnya. “Kalau lo nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Gue nggak maksa.”
“Ngambek.”
“Nggak!”
“Ngambek.”
Dhisti menghentakan kakinya. “Nggak ya!”
“Iya deh.” Gala terkekeh. “Biasa mau ke tempat Arman, bahas bisnis. Lo langsung balik, nggak usah terlalu lama di luar. Om sama Tante khawatir.”
“Kalau ujung-ujungnya kayak gini lo mending cepet pergi deh, mendadak pusing gue lihat lo.” Dhisti mengibaskan tangannya, memberikan tanda untuk Gala angkat kaki di depannya. Dia sempat lupa, Gala tidak beda dengan kedua orang tuanya, dia selalu saja mengingatkan untuk cepat pulang.
“Iya-iya.” Gala mengacak rambut Dhisti. “Chat gue kalau ada apa-apa.”
“Nggak usah pake ngacak rambut kali, Gal. Ah, lo mah bikin tambah kesel. Pergi sana pergi!”
“Lo jelek kalau ngambek. Sini biar gue rapiin.” Belum sempat protes, Dhisti sudah terlebih dulu menarik Dhisti dan menaruh kedua tangannya di atas rambut gadis yang kini menahan napas. “Lo mau kemana sih perlu rapi banget, biasanya juga lo acak-acakan di rumah.”
“Gue nggak ngerti lo ngomong apa.” Dhisti membuang muka. Meski dia terlihat sebal dengan perkataan Gala, dia membiarkan Gala merapikan rambutnya. Dalam hatinya dia sudah berteriak kegirangan. Jarang-jarang dia mendapatkan kesempatan untuk berdekatan seperti ini dengan Gala. Ya, dia menyukai Gala beberapa tahun belakangan ini, tapi seperti novel-novel yang dia baca, dia tidak berani untuk mengungkapkan. Dhisti tidak mengerti, kenapa dia bisa berada pada posisi yang menyulitkan seperti ini.
“Lihat ‘kan apa yang gue bilang? Dia itu manja, rambut aja perlu dirapiin sama orang.”
Seolah sumbu yang tersulut api, emosi Dhisti meledak. Tatapan yang mulanya ada percikan bahagia, kinni teredam dengan emosi yang luar biasa besar. Ditepisnya tangan Gala dengan kesal, lalu menatap lurus ke arah wanita yang kini tersenyum meremehkan.
“Udah jangan diurusin, Dhis.” Gala menyentuh lengan Dhisti, mencegah keributan yang ada.
Dhisti bergerak mendekati gadis itu dan mengacuhkan perkataan Gala. “Lo kayaknya cari ribut sama gue mulu. Kenapa sih? Lo iri sama gue?”
“Gue?” Rita menunjuk dirinya sendiri. “Iri sama lo?” Dia bergantian menunjuk Dhisti. “Saking manjanya lo halu ya?” Rita tertawa begitu juga dengan teman-teman gadisnya. Tawa yang begitu Dhisti benci.
Kedua tangan Dhisti terkepal rapat, buku-buku tangannya perlahan memutih.
“Gue bakal buat mulut lo tertutup. Dan sampai itu tiba, lo persiapin aja kekalahan lo ini!” Dhisti mengacungkan tangannya di depan Rita sebelum menghentakan kakinya dan pergi dari sana. Ia mengacuhkan panggilan Gala dan Asri. Dia akan membuat Rita menarik semua ucapannya. Harus.
*****
“Nggak!”
Dhisti melebarkan kedua matanya. Ia mencoba untuk tenang. “Pa, apa sih salah Dhisti mau kerja? Dhisti mau mandiri.”
“Mandiri apa? Nggak usah pake mandiri-mandiri. Kamu tuh masih anak kecil.” Nath memalingkan wajahnya dari koran dan menatap anak satu-satunya itu dari balik kacamata bacanya. “Kamu mendingan belajar, nggak usahlah pakai acara mau cari kerja atau buka bisnis. Kamu kira gampang apa buka bisnis dan kerja sama orang?”
Dhsiti sangat sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Papanya benar adanya. Tapi, apa salahnya kalau dia mau berusaha? Tenang, Dhis, tenang. Jangan emosi. Kalau lo emosi yang ada, bokap lo juga ikut emosi.
“Tapi, kan Dhisti mau berusaha. Ayolah Pa, izinin Dhisti.”
“Lihat, kamu bahkan masih ngerengek sama Papa. Itu kamu bilang mau mandiri?” Dhisti menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Menahan segala perasaannya yang saat ini dia rasakan. “Kamu tuh masih manja, kalau kamu bangkrut paling kamu nangis. Udahlah nggak usah bahas lagi. Kamu tuh belum bisa pegang tanggung jawab.”
“Gimana bisa Dhisti pegang tanggung jawab kalau Papa nggak kasih Dhisti kesempatan!” Emosi Dhisti meledak, semua rantai yang menahannya tercerai berai.
“Dhisti!”
“Pa, Papa selalu ngelarang Dhisti. Kemarin Dhisti kuliah ke luar, Papa nggak izinin, pergi sama temen jarang dikasih. Pergi ke konser nggak dikasih. Sekarang Dhisti cari kerja nggak dikasih. Bagaimana cara Dhisti pegang tanggung jawab kalau Papa nggak pernah percaya sama Dhisti?! Dan Dhisti udah umur 22 tahun, bukan anak kecil lagi.”
Dada gadis itu naik turun, seolah menunjukan betapa emosinya sekarang. Pandangannya mulai mengabur. Ya, sebentar lagi dia akan menangis, hal yang selalu terjadi ketika dia terlalu emosi. Jelas dia takut, tapi rasa frustasinya lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya. Seolah kalau tidak dikeluarkan, gadis itu bisa gila.
“Kamu ngelawan Papa sekarang?” Nath menatap tajam Dhisti, emosi juga terlihat jelas di wajahnya. “Kamu itu belum bisa apa-apa. Apa kamu bisa jamin kalau kamu nggak keluyuran di sana? Lagian, kalau kamu di sini masih bisa diawasi, dan kampus di sini nggak jauh beda dibandingkan di luar. Masalah konser dan pergi sama temen, apa sih gunanya pergi ke sana? Nggak ada.”
Kertas yang berisi semua rencananya, Dhisti remas dengan kencang. Dia kehilangan kata-katanya, emosi sudah menghamburkan kata-kata yang begitu banyak di kepalanya. Tanpa mengatakan apa-apa, Dhisti keluar dari ruang kerja Papanya. Ia menutup pintu dengan keras, hingga menarik nada tinggi dari Papanya.
“Dhisti.”
Dhisti berhenti, ia memalingkan muka, enggan untuk menatap Mamanya yang ternyata tak jauh dari ruang kerja Papanya.
“Sayang, dengerin Mama. Papa ngelarang kamu karena Papa sayang kamu.” Afri mengelus rambut putrinya. Ia tahu betapa kesalnya Dhisti.
“Sayang? Sayang apa? Papa selalu ngelarang yang Dhisti mau. Dhisti muak dipanggil anak manja mulu. Memangnya salah apa kalau jadi anak sematawang? Memangnya anak sematawayang nggak bisa mandiri? Udahlah Ma, kalau Mama cuman mau belain Papa percuma. Dhisti capek mau tidur.” Dhisti langsung melangkah pergi. Dia membutuhkan waktu untuk menenangkan dirinya. Ia membuka pintu kamarnya tak sabaran dan menutupnya keras sebelum berlari ke arah ranjangnya.
Apa yang harus dia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mandiri, dan menutup mulut si Rita nenek lampir yang ingin ia tampar bolak balik itu?
Bermenit-menit berlalu, Dhisti tidak bisa mendapatkan jawaban. Ia memutar tubuhnya menjadi terlentang.
Tak tak.
Dhisti menoleh ke arah jendela dengan kernyitan dahinya. Sepertinya dia mendengar sesuatu? Ia menunggu lama, dan ketika suara itu kembali terdengar, dia buru-buru turun dari ranjang dan menyibakan jendela kamarnya. Bibirnya tidak bisa dihentikan untuk tersenyum ketika melihat Gala yang tengah melipat kedua tangannya di balkon. Ia bisa melihat ada batu terselip digenggaman laki-laki itu.
“Ngapain?”
“Jadi pengantar makanan.” Gala menunjuk ke arah keranjang yang ada di depan Dhisti.
Rumah yang berdekatan dan nyaris menempel, membuat keduanya dengan mudah berinteraksi. Ada tali yang menghubungkan balkon mereka. Awalnya tidak tali, itu semua dilakukan oleh keduanya lebih tepatnya Gala. Karena saat Dhisti kecil, gadis itu dikurung oleh Papanya agar tidak pergi kemana-mana. Gala yang kasihan karena melihat Adhisti mulai berencana untuk membuat sebuah alat transportasi untuk keduanya berkomunikasi.
“Eh, buat gue.”
“Siapa lagi?”
Dhisti senyum sumringah. Ia menarik ranjang itu untuk mendekat. “Bukannya lo bilang mau ada perkumpulan?” Dhisti mengeluarkan roti dan beberapa minuman di sana.
“Gue ada ketinggalan sesuatu.”
Dhisti mengangguk-angguk. Ia mengangkat kedua tangannya yang kini dipenuhi oleh barang yang dibelikan oleh Gala. “Thanks yo. Sering-sering Gal.”
“Kenapa muka lo suntuk gitu?”
“Biasa, bokap nggak ngasih gue kerja.”
“Lo mau kerja?” Ada keterkejutan di suara Gala yang menarik Dhisti untuk memincingkan matanya.
“Kenapa? Lo anggap gue nggak bisa?”
“Nggak gitu.” Gala tersenyum. “Lo mau kerja apaan?”
“Apa aja.”
“Diizinin.”
“Lo tahu jawabannya.”
“Dhis, lo kenapa sih perlu maksain diri? Fokus aja belajar dulu.”
“Lo juga ngeraguin gue?” Ada kesinisan yang terdengar ketika Dhisti mengatakannya. Satu orang yang dia harapakan kini juga meremehkannya. Sepertinya, hidupnya begitu menyedihkan.
“Bukan gitu, Dhis. Gue kayaknya salah mulu. Maksud gue, nikmatin aja dulu. Ngapain lo dengerin kata Rita.”
“Lo nggak ngerti perasaan gue kayak gimana Gal!” seru Dhisti. “Udah deh, gue kira ketemu sama lo bisa buat mood gue baik. Nyatanya nggak.” Dhisti berbalik dan masuk kembali ke dalam kamar. Menutup kembali korden dalam kamarnya. Bibirnya sudah maju beberapa centi. “Kenapa sih nggak ada yang percaya kalau gue bisa?!” keluhnya kesal
“Gue percaya Dhis! Kalau ada apa-apa lo bisa tanya sama gue!”
Dhisti menoleh tapi tidak membuka jendela. Ia tidak tahu harus mempercayai perkataan Gala atau bagaimana. Dia masih yakin kalau laki-laki itu tidak mempercayainya. Dhisti berjalan ke arah laptopnya setelah menaruh barang pemberian Gala di atas ranjang. Ia mulai bergelut dengan internet.
“Pokoknya gue nggak boleh nyerah. Gue harus buktiin kalau gue bisa!”


 D
D

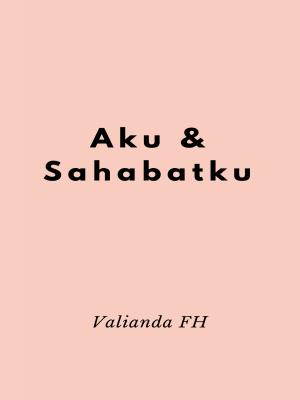








Saya anak semata wayang. Tapi saya jauh dari kata manja.
Comment on chapter Prolog