Baru satu langkah melewati ambang pintu, mata Devon langsung terjatuh pada Mama yang mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya yang dipenuhi aura kekhawatiran semakin memacu langkah Devon mendekati Mama.Mama tersentak melihat Devon. Tingkat kekhawatirannya semakin meningkat seiring dengan jarak Devon yang semakin pendek.Devon mengernyit, senyuman mengembang khas Mama setiap melihatnya pulang tidak tercetak di wajah resah itu. Senyuman itu digantikan dengan gigitan di bibir bawahnya seolah Mama sedang menahan ketakutan luar biasa.Sesampainya Devon, Mama langsung menggenggam tangan Devon kuat-kuat lalu menariknya menaiki tangga.
“Papa mau bicara, Dev.” Ucap Mama lembut.
Di undakan tangga ke tiga langkah Devon otomatis terhenti.
“Tolong temui dulu, ada yang mau Papa bicarakan.” Mama semakin menguatkan pegangannya ketika Devon hendak berbalik menuruni tangga.
“Papa bakal ceramah apa lagi. Aku—“
“Tolong Dev. Kamu lakukan ini demi Mama. “Mama menepuk-nepuk dadanya.“Temui Papa kamu demi Mama.”
Mendapatkan sorot kekhawatiran yang tak biasa itu menyelipkan keanehan di benak Devon. Manik mata Mama yang selalu menatapnya intens dengan sorot keibuan, kini seolah enggan menghadirkan sorotan itu. Mama berulang kali membuang pandangannya setiap Devon berusaha menangkap sorot itu. “Tolong ya Dev.” Imbuh Mama dengan tatapan kabur entah ke mana. Devon bisa melihat bibir Mama bergetar.
Devon mengangguk tanpa perlawanan.Selain untuk menenangkan Mama, dia sangat penasaran dengan arti gurat kesedihan Mamanya itu. Satu kaki yang sudah mendarat di undakan tangga kedua terpaksa dinaikkan menuju ruang kerja Papa.
Papa duduk tegak di kursi kerjanya.Bukan sosok Papa yang dilihatnya, tapi sosok Putranto, bos perusahan sepatu terbesar di Bandung. Tanpa menyambut Devon yang sudah duduk di hadapannya, Putra menyodorkan map biru yang sudah tergeletak di atas meja. Devon mengernyit melihat isyarat Papa yang menggerakan dagu menunjuk ke map itu. Dibukanya map itu lalu dalam sepersekian detik map kembali tertutup ketika kata pertama dalam kertas di balik map itu menyentaknya telak.
Warisan.
Devon menelan ludah.Otaknya berdenyut nyeri dan nyaris meledak mengingat satu kata itu.
“Itu bukan sekedar warisan buat kamu, tapi itu juga amanah kakekmu.”Papa berdeham lalu berdiri.“Kamu bilang mampu hidup tanpa keluarga ini, buktikanlah pada Papa.Harta satu-satunya yang kamu punya cuman warisan ini.”
Devon semakin tenggelam dalam kebeciannya pada Papa.Selama tiga tahun, sosok itu yang selalu mengusir segala hal tentang Nanzo. Tindakan Papa menghancurkan belasan gitar kenangan itu tidak akan berhasil menggeser Nanzo dari benaknya. Tapi sekarang Papa berhasil.Papa menempatkanya tepat di titik terlemah. Titik yang tidak mungkin baginya mengingat setiap detail tentang Nanzo. Titik yang paling menghancurkannya.Titik yang selalu merenggut paksa nyawanya.Titik yang selalu menyeretnya pada realita.
Dirinya mampu berdiri tegak setiap melihat barang-barang peninggalan Nanzo terutama berbagai mendali yang kini berpindah ke kamarnya.Jejak sentuhan di setiap barang itu seolah menghadirkan Nanzo dalam setiap helaan napas Devon.Bahkan, chat dengan Nanzo yang rajin dibuka nyaris setiap hari masih tersimpan di ponselnya. Tapi tidak dengan tempat itu.
Amore Karaoke.
Sepanjang jalan menuju tempat itu, setiap jengkalnya bahkan inchinya menimbulkan kenangan menyakitkan. Percikan air hujan yang jatuh di sepanjang jalan Handimuka bagai garam yang ditaburkan pada luka yang masih basah dan bersinggungan dengan tempat itu membawanya dalam realita yang selalu ingin diingkari. Tempat terakhir bergerutu pada Nanzo, tempat terakhir dia menyikut pinggang Nanzo, tempat terakhir melihat Nanzo berlari dan tempat bertemu dengan gadis pembawa maut itu. Jalanan dan tempat karaoke itu adalah saksi bisu kematian Nanzo.
“ Tunjukkan pada Papa kalau jalan hidup yang kamu pilih itu benar.” Papa membungkukkan badannya melewati meja kerja yang besar. Ditatapnya intens Devon yang seluruh perhatiannya tercurah ke map di depannya. “Kalau kamu berhasil mendirikan kembali tempat karaoke itu. Papa tidak akan memaksa kamu untuk melanjutkan kuliah bisnis kamu, Papa tidak akan memaksa kamu meneruskan perusahaan sepatu keluarga ini, Papa tidak akan memaksakan semua kehendak Papa. Jika itu tercapai, maka kamu memang terbukti mampu hidup tanpa keluarga ini.Tapi jika kamu tidak berhasil, kamu harus mengakui bahwa kamu memang akan selalu bergantung pada keluarga ini.”
Devon menggeram. Darahnya mengalir deras hingga wajahnya memerah.Tak terasa lagi rasa sakit di telapak tangan ketika kuku–kuku jemarinya nyaris merobek kulit. Genderang perang telah dinyalakan, bergejolak hebat di dada, memancing deru napasnya semakin cepat.
Devon mengangkat wajah. Dibalasnya tatapan Papa yang mengintimidasinya, dengan tatapan penuh tantangan. “Devon tidak akan pernah bergantung pada keluarga ini lagi.” Devon mendorong kursinya ke belakang sambil menyambar map itu lalu berbalik meninggalkan ruangan itu.
***
Dengan ransel berat berisi pakaian yang menempel di punggungnya dan dua plastik putih besar tergenggam di tangan yang memuat roti, susu, cemilan bahkan telur dan sayuran, Devon melangkah lebar menuju kafe. Kalau bukan karena persyaratan Revi yang konyol itu, dia ogah datang ke pertemuan anggota baru untuk band yang telah lama tertidur itu. Setelah diusir secara tidak langsung oleh Papa yang berakhir dengan tangis Mama yang tiada henti—hingga Mama diam-diam membekalinya dua plastik makanan untuk hidupnya di dunia ini—Devon terpaksa mengungsi ke kamar kos Revi. Dan cowok itu terpaksa menerima syarat Revi untuk menyusulnya ke kafe ini bila ingin numpang hidup. Kalau saja Taki termasuk ke dalam mahasiswa yang hidup di kamar kos, Devon langsung mengajukan permintaan itu ke Taki yang pasti tanpa embel-embel persyaratan.
Karena motor, kartu kredit, ATM dan berbagai fasilitas lainnya telah diblokir oleh Papa dan hanya mempunyai beberapa lembar uang seratus ribu di dompetnya, Devon harus berhimpitan duduk di angkot dan turun di perempatan jalan karena angkot yang ditumpanginya tidak melewati tujuannya.
“Diusir?”Revi tak kuasa menahan tawa melihat wajah penuh lelah itu sudah duduk di sampingnya.
Devon melemparkan ransel super berat itu namun aksinya tak sanggup menghentikan tawa Revi.
Taki yang duduk berhadapan di depan mereka berdua, hanya menggelengkan kepala dan menghela napas. Drama keluarga ini semakin mengerikan saja hingga terjadi pengusiran segala.Tapi ada yang janggal, lihat itu…wajah sobatnya yang anak Mama itu tidak terlihat menderita sama sekali seperti orang yang telah diusir, justru ketegaran mendominasi rautnya sehingga Taki tak bisa menyembunyikan senyum kelegaan.
“Lo bawa apa tuh?” Revi langsung menyambar salah satu plastik besar yang baru saja diletakkan di bawah kursi.
“Woy hati-hati pecah, ada telurnya.” Sentak Devon.
Revi mengangkat bahu sambil sibuk menjulurkan kepalanya ke dalam timbunan makanan di plastik itu. “Nah, lo bisa bayar pake ini aja.” Revi tersenyum puas. “Eh, tapi Lo nggak mungkin selamanya ngungsi di kamar gue kan? Bu Melati bisa ngamuk kalau tahu.”
“Tenang, gue bakal nyewa kamar di tempat kos lo kalau gue udah punya duit.”
Taki mengernyit.“Jadi lo bener-bener miskin sekarang?Semua fasilitas lo juga diambil?” Goda Taki
Devon mendelikkan mata.Tak ada satu pun temannya yang berbicara layaknya manusia normal.“Lo bisa lihat muka gue keringetan gini.” Sembur Devon.
Taki dan Revi hanya tergelak. Tak tahan ditertawakan kesekian kalinya, Devon mengetuk-ngetuk meja, membangunkan mereka yang begitu bahagia di atas penderitaan orang lain. “Kenapa tiba-tiba ada anggota baru segala?” Tanya Devon mengalihkan pembicaraan ke topik pertemuan.“Gue kira band itu udah bubar.”Imbuhnya.
“Dasar ngomong sembarangan.“ Revi menendang kaki Devon. Hasratnya sudah sangat tinggi menyemburkan kopi yang hendak diminumnya.
“Impian itu nggak cuman jadi daftar panjang di otak, yang akhirnya malah jadi mitos. ” Ucap Taki yang mencegah Revi nyaris memuluskan hasratnya. “Tujuan diciptakannya impian itu untuk direalisasikan.”
Devon menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu mengibas-ngibaskan tanganya tak peduli. “Siapa sih anggota barunya?” Tanyanya yang sebenarnya tak peduli juga. Dia hanya sedang malas mendengar nasehat Taki.
“Dia cewek. Anak seni musik di kampus sebelah.”
“Wah kita bakal punya personil cewek. Sayang banget gue belum sempat putusin Kely.” Keluh Revi yang dibalas dengan toyoran Taki di kepalanya.
“Sepupu gue merekomendasikan cewek itu ke gue. Setelah gue lihat permainan pianonya di youtube channelnya…” Taki mendecakan lidah sambil mengangkat heboh kedua jempolnya.“Keren banget. Dia mahasiswa genius di angkatannya. Ada hal lainjuga yang bikin gue ngebet banget ngajak dia.”
Revi yang tampak paling bersemangat, tiba-tiba bahunya merosot lemas.“Tipikal cewek yang patuh aturan hidup untuk selalu rajin belajar. Nggak bakal cocok sama gue.”
“Dia bisa bikin lagu!”Ucap Taki bangga yang sedetik kemudian membangkitkan semangat playboy-nya Revi.
“Aahh..keren. Gue pengen banget punya cewek jago bikin lagu.”Cowok itu menegakkan badannya lalu menunjuk Devon—yang langsung menyesap kopi pesanannya yang sudah mendingin—dengan lirikan ekor matanya.“Setidaknya bisa menggantikan orang yang udah menyia-nyiakan keahliannya bikin lagu karena terlalu terpuruk dengan kematian.”
Devon menyimpan cangkir kopi di tangannya dengan kasar. Kepalan tangan kananya sudah siap menyumpal mulut Devon, tapi sedetik kemudian jemarinya terbuka dan kembali menyambar gagang cangkir.
Revi mendesah kesal karena pancingannya tidak terwujud. Pertarungan satu arah sore tadi sangat tidak adil, dia juga ingin merasakan kekuatan tonjokan anak Mami itu. Lebih tepatnya, dia ingin Devon mengeluarkan seluruh emosinya agar jiwa dan raga cowok itu tidak selalu mengarah pada kematian, bahwa kehidupannya di bumi ini masih berlanjut dan realita paling menyakitkan itu sedang menantinya untuk dihadapi.
“Lewat sepupu gue akhirnya dia mau ketemu sama kita. “Taki membawa kembali obrolan di meja paling pojok ini ke topik semula.“Tapi mukanya nggak asing, rasanya gue pernah lihat.”
“Mungkin kita juga bisa ngenalin karena kapan sih lo nggak deket-deket sama kita.” Celetuk Revi.
“Dia udah di sini dari tadi, tapi dia nggak mau datang dulu sebelum kita lengkap.” Taki melirik jam tangannya lalu setelah mendengar denting dari ponselnya, pandangannya beralih ke ponsel di samping cangkir kopinya. “Nih dia bales chat gue, katanya pake baju warna biru.” Taki berdiri diikuti oleh Revi mencari anggota baru itu di tengah keramaian kafe yang luas ini.
“Banyak yang pake baju warna biru di sini.” Ucap Devon yang tanpa sadar ikut berdiri pula, mencari sosok itu.
Denting pesan terdengar kembali.
“Dia berdiri di meja nomor 7. Dia minta kita lambaikan tangan.”
“Kenapa nggak ke sini aja sih, sebutin aja meja nomor kita-- ” Gerutuan Devon terinterupsi oleh matanya yang menangkap sosok yang baru muncul dari balik pintu masuk kafe. Devon mengerjapkan mata lalu mencurahkan fokusnya pada sosok berambut keriting yang kini sedang berjalan melewati lalu lalang orang.
Realita yang paling dibencinya itu mengalir deras di sekujur tubuh membuat tekanan darahnya langsung meninggi hingga nyaris memecahkan pembuluh darah. Kepalan tangannya yang sekeras batu meninju meja, menyebabkan tiga cangkir di atasnya melayang dan mendarat kencang di lantai dengan kekuatan yang mampu membungkam keramaian kafe. Devon menendang kasar kursinya ke belakang. Kakinya yang bergemetar hebat melangkah menuju sosok yang kini sedang terpaku menatapnya penuh ketakutan.
Revi meniup napas kencang-kencang. “Pantesan lo merasa tahu cewek itu. Kita emang pernah bersinggungan dengannya tiga tahun lalu.”


 mlounita
mlounita







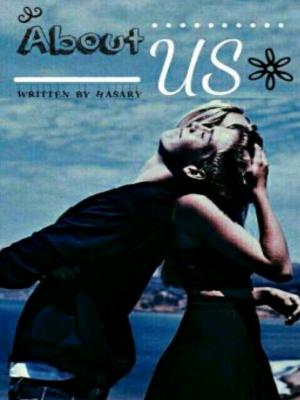


fresh banget ceritanya hehe. ditunggu kelanjutannya ya :)
Comment on chapter Chapter 1